Chapter 28 [Berlian Melody]
Selamat datang di chapter 28
Tinggalkan jejak dengan vote, komen atau benerin typo-typo meresahkaeun
Thanks
Happy reading everybody
Hopefully you will love this story like I do love Jayden and Melody
❤️❤️❤️
____________________________________________________
“Seperti diikat rantai begitu kencang dan tidak diizinkan melarikan diri dari rasa sesak menyakitkan ini.”
—Berlian Melody
____________________________________________________
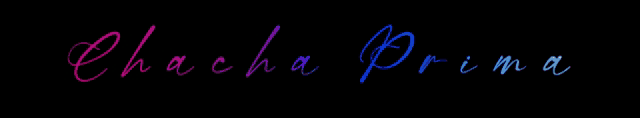
Musim gugur
Clifton Hampden, 22 Oktober
Pukul 00.20
Tidak mungkin Jayden seorang mafia. Tidak mungkin Jayden membunuh orang lain yang disebut-sebut sebagai mafia juga. Jadi, tidak mungkin Jayden ditangkap polisi dan sekarang sedang ditahan di penjara. Aku tidak ingin mempercayai hal tersebut. Sedikit pun tidak.
Setelah ini suamiku akan datang untuk menjemputmu pulang. Lalu ia akan memelukku dan kami akan tidur hingga pagi. Keesokan harinya kami akan bangun dan melakukan rutinitas seperti sedia kala.
Apakah aku terlalu naif bila berpikir demikian? Namun, apabila tidak ada satu hal pun yang kupercayai dari berita itu, kenapa hingga tengah malam ini Jayden tak menjengukku? Apakah karena kekecewaannya terhadapku yang baru saja keguguran?
Tidak. Jayden bukan orang seperti itu. Ia tidak akan marah karena aku keguguran. Namun, kenapa ia tidak datang? Ke mana sebenarnya Jayden? Apakah masih di luar kota karena pekerjanya? Namun, bukankah seharusnya pihak rumah sakit sudah memberitahunya tentang keadaanku? Atau jangan-jangan Jayden amat bersedih sampai-sampai belum bisa kemari? Bila benar demikian, bukankah seharusnya aku pergi ke tempatnya untuk memeluknya?
Aku tak ingin suamiku minum-minum lagi sampai mabuk. Namun, aku yakin ia tidak akan melakukannya atau aku akan marah besar padanya. Belakangan ini kami sudah melalui banyak hal menyedihkan dengan kehilangan orang dan piaraan kesayangan kami. Dan sekarang ini.
Aku refleks menyentuh perutku. Satu isakan pun berhasil membebaskan diri dari tenggorokanku yang kering. Detik-detik selanjutnya isakan demi isakan lain menyusul dengan intensitas sering.
Aku tahu aku hanya berpikir naif. Aku tahu semua berita itu benar. Aku telah melihat seluruh stasiun TV menampilkannya. Hingga pada kunjungan terakhir Dokter Sofia bersama seorang perawat tiga jam lalu, TV di hadapanku masih menampilkan berita-berita tentang penangkapan Jayden di Danau Buldish. Yang kemudian dimatikan Dokter Sofia dan melarangku menonton lagi. Aku hanya tidak ingin mempercayai bahwa selama ini Jayden telah membohongiku tentang dirinya yang sebenarnya.
Aku membekap mulut menggunakan tangan agar tangisku yang pecah bisa teredam. Akan tetapi, gigiku tidak mau bekerja sama melepaskan kukuku. Tekanan yang kuberikan pada gigiku malah semakin besar. Sampai aku tidak sengaja menggigit kutikula hingga membuatnya berdarah. Bau anyir serta rasa asin kontan menyapa dan aku mengabaikannya.
Entah mana yang lebih sakit saat ini: kutikulaku yang sobek, kehilangan bayiku yang harus dibersihkan dari rahimku, atau kebenaran penangkapan Jayden? Aku tidak bisa memilah serta memilihnya. Semua komponen tersebut begitu kompak menyerang mental dan fisikku.
“He’s not worth it. He’s not worth it. Dia nggak patut ditangisin. Seorang pembohong nggak patut ditangisin.”
Kusuntikkan kata-kata itu agar berhenti menangis serta berperilaku logis. Namun, bukannya berhenti. Air mataku malah mengucur kian deras bagai bendungan bobol. Membuat kepalaku berat seperti menyangga berton-ton beban. Linier dengan kinerja paru-paruku di balik rongga dadaku. Seperti diikat rantai begitu kencang dan tidak diizinkan melarikan diri dari rasa sesak menyakitkan ini. Setiap kali menarik napas, aku seperti orang sekarat. Keadaan yang tidak kalah buruk dengan kedua mataku yang perih, panas, dan bengkak akibat terlalu sering menangis.
Demi Neptunus! Aku membutuhkan seseorang di sampingku sekarang. Namun, aku sanksi ada yang mau menemaniku.
Hei, memangnya siapa yang ingin berteman dengan istri seorang bos kriminal? Yang benar saja!
Sejak kemarin, pandangan orang-orang yang bekerja di rumah sakit ini berubah 180 derajat terhadapku. Kendati semua orang bekerja dengan baik di bidangnya masing-masing—termasuk kuretase yang dilakukan Dokter Sofia kepadaku, tetapi aku merasa telunjuk-telunjuk mereka seperti ditudingkan ke arahku sambil bisik-bisik. Sebagian kecil memandangku penuh simpati seperti mengatakan betapa tololnya diriku karena mau-maunya dipersunting pria seperti Jayden Wilder.
Singkat kata, berita penangkapan Jayden Wilder akibat menembak seseorang dari keluarga mafia lain serta keterlibatannya membuat kebakaran di Hotel Four Season London sangat berpengaruh terhadapku dan orang-orang di sekelilingku. Dampaknya luar biasa dasyat sampai-sampai aku ragu bisa melewatinya dengan raga dan mental utuh.
Keluargaku memang tidak henti-hentinya menelepon dan mengirimkan pesan. Namun, aku terlalu takut menerima respons yang mereka berikan padaku. Apakah mereka akan melindungiku, merangkulku, memberiku semangat, atau justru sebaliknya? Memakiku? Menyebutku tolol? Sedangkan aku sendiri hancur.
Bodoh bila aku berpikir keluargaku akan memakiku. Namun, tidak ada yang bisa menebak hati seseorang, bukan? Banyak kasus keretakan keluarga karena anggota keluarga lain salah memilih teman hidup.
Meggy dan Diana belum menampakkan batang hidungnya sejak kemarin. Tidak peduli seberapa erat persahabatan kami, mungkin mereka saat ini takut kepadaku. Tanganku pun begitu gatal ingin mengambil ponsel dan menelepon sahabat sejatiku, Karina. Lagi-lagi dikarenakan rasa takut akan respons darinya yang tidak sesuai keinginanku—seperti respons Meggy dan Diana, aku mengurungkan niat menghubunginya dan mematikan ponsel.
Di kala menyadari tidak ada seorang pun di sekelilingku yang peduli, kecuali Dokter Sofia yang tetap menjalankan tugasnya mengobati tanpa ingin tahu urusan pribadiju, aku kembali menangis kencang. Sampai lambat laun aku mulai mengubah pendapat itu dengan menyelinapkan kenyataan bahwa tidak ada gunanya aku menangis. Menangis hanya mengeluarkan kepedihan dan membebaskan emosi. Namun, tidak menyelesaikan masalah, bukan?
Rupanya, doktrin itu sedikit ampuh. Isakan-isakanku pun memelan sampai akhirnya berhenti total. Hatiku masih sakit, tetapi darahku seolah-olah menguap dari tubuhku dan membuat ragaku kebas. Sebelas-dua belas dengan tenagaku yang seakan-akan terserap habis oleh keadaan, yang menempatkanku di titik paling rendah di hidupku saat ini.
Aku membiarkan air mataku mengering di pipiku sambil memandang kosong susana di luar jendela yang tertutup vertical blind. Tidak terasa kegelapan yang menguasai langit sudah berganti menjadi jingga di kala fajar. Cahayanya mengintip dari celah-celah penutup jendela tersebut. Cahaya yang makin lama makin terang, tetapi tidak sepenuhnya mengangkat keremangan kamar ini. Tidak juga membuang atau mengurangi rasa sakit di hatiku barang sedikit pun.
Tiba-tiba pintu ruang rawat inapku diketuk-ketuk. Mungkin itu Dokter Sofia dan seorang perawat yang akan memeriksa keadaanku seperti rutinitas mereka kala pagi, siang, senja, dan malam. Tanpa diberi respons, mereka pasti masuk dengan sendirinya. Dan kini aku mendengar derit pintu dibuka.
“Mel, aku masuk, ya?”
Mendengar suara familier itu lengkap dengan jenis bahasa yang digunakan, jantungku berpacu cepat bagai mengembalikan seluruh darah ke tubuhku. Memberiku kekuatan membalik tubuh untuk menoleh. Dan betapa kagetnya aku saat melihat siapa yang masuk.
“Umar?” bisikku ragu. Siapa tahu aku sedang mengalami halusinasi akibat depresi berat yang kualami. Mengingat kata Meggy, Umar sedang menempuh pendidikan dokter bedah di Harvard. Jadi, bagaimana mungkin pria itu ada di sini?
Bila Jayden tahu, ia pasti akan marah besar. Namun, suamiku ditahan polisi dan aku amat kecewa telah dibohongi. Jadi, seandainya aku memang tidak berdelusi, kubiarkan saja Umar masuk.
Meskipun sekarang aku sendirian menghadapi ini, dan seandainya memang benar Umar di sini, apakah keadaanku lantas akan membaik? Aku pikir tidak. Malah justru sebaliknya. Perasaanku kian memburuk dengan hadirnya rasa bersalah. Perasaan yang menyeretku kembali ke masa lalu.
Aku sudah menyakiti Umar sedemikian rupa. Ia memang sudah mengungkapkan rasa kecewanya dengan kata-kata kasar kepadaku. Namun, di titik tertentu, di saat emosi kami sudah sama-sama surut, aku mencoba menemuinya di London untuk meminta maaf secara baik-baik.
Kami lantas pulang ke Jakarta untuk mengabari keluarga kami masing-masing. Kemudian keluarga kami bertemu untuk membicarakan pembatalan pernikahan kami.
Keluarga Umar yang notabenenya keturunan Arab dan menetap di Indonesia memang tidak memegang tradisi perjodohan yang mengharuskan anak-anak mereka memilih pendamping hidup dengan keturunan yang sama. Umar dibebaskan memilih calon istri. Yang mana kala itu adalah aku. Dan baik dulu maupun sekarang, pembatalan pernikahan kami sangat menjadi beban tersendiri bagiku. Lebih-lebih waktu itu. Aku takut membuat keluarga Umar yang begitu baik padaku akan kecewa. Dilemanya, di waktu yang sama, aku tidak bisa menahan perasaan cintaku untuk Jayden yang kembali hadir di hidupku.
Umi dan Abinya Umar sempat menyayangkan keputusan kami, tetapi menghormati dengan mengembalikan semuanya kepada kami. Bahwa, yang menjalani pernikahan adalah kami. Maka sudah seharusnya kamilah yang menentukan ke mana arah langkah yang akan kami tuju. Daddy dan Mamiku juga demikian.
Aku pun merasa sangat berutang budi pada Kak Brian. Aku merecokinya untuk membantuku membicarakan pembatalan pernikahanku dan Umar kepada Daddy dan Mami. Aku tidak ingin menebak bagaimana perasaan kakakku sekarang bila mengetahui kondisiku kini. Pasti Kak Brian sangat kecewa. Hal itu pulalah yang membuatku makin yakin tidak ingin menyalakan ponsel.
Kemudian bagai tongkat sihir yang diayunkan dengan mantra. Secara ajaib dan cepat, urusanku dengan Umar pun beres kala itu. Pertemuan kami di Jakarta beberapa bulan lalu pun tidak menjadi masalah. Aku juga sudah tidak memikirkan cerita kami dulu. Namun, sekarang? Aku tak bisa tidak memikirkannya. Lalu, apakah kehadiran Umar di sini untuk menertawakanku?
Aku memperhatikan pria keturunan Arab bercambang itu. Ia mengenakan kemeja putih yang dilapisi jas dokter lengkap dengan stetoskop menggelantung di lehernya. Celana bahan hitam yang dikenakannya disetrika sampai licin. Pantofel hitamnya juga mengilat. Seperti biasa, secara keseluruhan penampilannya rapi. Berkebalikan denganku yang mirip orang gila, yang sewaktu-waktu dikhawatirkan akan membenturkan kepala ke dinding agar mendapatkan kewarasan kembali.
Umar memindah bobot tubuhnya ke ranjang rumah sakit yang kubaringi sambil menenteng tote bag putih.
“Kamu ini beneran atau cuma delusiku aja, sih?” Aku menemukan diriku bertanya secara impulsif. Diikuti denyut di hatiku yang memperdalam rasa sakitku akibat mengingat apa yang telah kuperbuat padanya dulu.
“Aku nyata, Mel. Kamu nggak lagi delusi, kok,” jawab Umar. Setelah meletakkan stetoskop dan tote bag di nakas samping ranjang, ia menggeret kursi di sampingnya agar lebih dekat dengan ranjangku sebelum mendudukinya.
Debar jantungku bertambah cepat. Kekonyolan apa lagi ini?
“Kok, kamu bisa di sini?” tanyaku sungguh tidak mengerti.
“Meggy nelepon aku kemarin. Katanya kamu—“ Umar menghentikan kalimatnya dan melihat perutku. Seperti berpikir memilih kata yang tepat untuk diungkapkan kepadaku. Kemudian ia menatapku lagi. “Katanya kamu lagi sakit. Jadi, aku buru-buru beli tiket dari Boston ke sini. Tapi nggak secepet yang kupengin. So, how’s your feeling, Mel?”
Kenapa Meggy harus melakukan itu? Padahal ia sendiri belum menjengukku. Maka dari itu aku menjawab sekenanya. “Kayak yang kamu lihat. Kamu juga pasti udah denger dari Meggy dan Diana soal keadaanku.”
Umar membuka mulut kemudian menutupnya lagi. Kepalanya sedikit menggeleng. Lalu ia berkata, “Tapi aku harap kamu baik. Walau, kantong mata sama semua peralatan ini nggak bisa ngelabuhi aku soal kondisimu. Omong-omong—”
“Kenapa, Umar?” potongku yang sungguh tak mengerti. Aku sudah menyakitinya sedemikian rupa. Ketika kami tidak sengaja bertemu di Jakarta aku pun berusaha menghindar. Aku bahkan tak membalas pesannya dan malah memblokir nomornya. Kenapa ia masih mau datang ke sini?
“Kenapa apanya, Mel?”
“Kenapa kamu ke sini? Emangnya kamu nggak baca atau nonton berita? Meggy sama Diana aja belum ke sini. Kenapa kamu malah ke sini duluan, Umar? Masih pakai jas dokter pula. Apa kamu sengaja ke sini buat ngetawain aku?” Suaraku terdengar memilukan di telingaku ketika mengumandangkan kalimat tersebut.
Pria itu menatapku dengan mata sayu dan alis berkerut. “Aku khawarir, Mel. Nggak ada sedikit pun niatan buat ngetawain kamu. Meggy dan Diana juga khawatir, tapi mereka masih sibuk, jadi belum bisa ke sini.”
Sibuk, ya? Aku tidak yakin. Mereka pasti takut padaku. Iya, kan?
“Omong-omong, katanya kamu belum mau makan sejak kemarin. Kayaknya kamu juga nggak tidur semaleman. Aku inget kamu suka bubur kepiting. Jadi, aku bawain. Tadi beli di restoran langgananmu. Biar kamu nafsu makan. Siapa tahu habis makan ini kamu ngantuk dan mau tidur.”
Tiba-tiba pandanganku buram. Dari sekian miliyar manusia yang hidup di muka bumi dan sebagian kecil yang mengenalku, kenapa harus Umar yang peduli? Kenapa?
Aku menarik napas begitu berat sambil memandang langit-langit agar tidak menjatuhkan butiran-butiran hasil produksi air mataku yang sudah menggenang. Aku tidak boleh menangis dan terlihat semakin menyedihkan di mata Umar.
“Menurumu, apa aku bisa makan dan tidur, Umar?”
“Dicoba dulu. Siapa tahu bisa. Ya?” bujuk Umar.
Tanpa menunggu responsku, pria itu kini membantuku duduk sembari menaikkan pengaturan ranjangnya. Lalu ia mengambil mangkok kaca berisi bubur kepiting, membuka tutupnya, mengambil sendok, dan memberikannya kepadaku. Namun, gerakannya tiba-tiba berhenti sewaktu melihat jari-jariku.
“Jari-jarimu kenapa, Mel?” tanya Umar yang langsung mengambil tanganku untuk diperhatikan dan dianalisa secara saksama. Ingin sekali kutarik dan kusembunyikan tanganku, tetapi kenyataannya aku tak kuasa menepisnya. “Darahnya udah kering,” lanjut pria itu.
“Nggak sengaja kegigit,” bisikku yang tak berani memandang Umar.
Bubur kepiting yang masih berada dalam genggaman tanganku yang satunya pun Umar ambil dan ia letakkan di nakas. “Kebiasaanmu balik lagi?”
Aku tak menjawab. Namun, Umar pasti sudah bisa menebak jawabaku.
“Padahal dulu selama kuliah kamu udah nggak sering gigit kuku,” gumam pria itu yang tampaknya memang diperuntukkan bagi dirinya sendiri, tidak membutuhkan jawabanku. “Aku obatin dulu.”
Lima menit kemudian, jari-jemariku sudah dibersihkan menggunakan cairan ingus, chlorhexidine dan lanjut dibersihkan dengan cairan infus lagi yang ia bawa, kemudian diberi povidon iodin, lalu terakhir diperban. Kata Umar, selain bisa melindungi luka dari bakteri yang bertebaran di udara atau lalat—yang kami berdua sama-sama tahu tentang itu, perban ini juga mencegah diriku supaya tidak memiliki keinginan menggigiti kuku.
“Nggak mungkin kamu bakal makan perbannya,” candanya, “sekarang ayo makan.” Ia memberikan mangkok kaca itu kepadaku lagi. “Tuh, banyak kepitingnya. Aku sengaja minta ektra daging kepiting biar kamu nggak protes, Mel. Biasanya kamu paling cerewet soal ginian.”
Setelah memandangi jari-jemariku yang diperban, aku memandangi makanan itu.
“Banyak, kan, kepitingnya? Cobain, Mel. Jangan dilihatin doang. Mau aku suapin?”
Aku menggeleng. Lalu dengan patuh, aku mengambil sesendok bubur kepiting dan menyuapkannya ke mulutku.
“Enak, nggak?” tanya Umar antusias dengan senyum hangat. Lesung pipi di antara cambangnya terlihat. Hatiku makin teriris.
Aku mengangguk sambil mengunyah walau tak yakin lidahku bisa merasakannya.
“Makan yang banyak, Mel.”
Aku kembali mengangguk dan menyendoki bubur kepiting agar kesedihanku teralihkan. Aku benar-benar tidak boleh terlihat menyedihkan di depan Umar. Hingga tidak lama kemudian, aku telah menghabiskan makananku. Umar mengambil mangkokku dan menggantinya dengan air mineral. Setelahnya, aku menggelontorkan air itu ke tenggorokanku dan Umar kembali mengambil botol itu serta meletakkannya di meja.
“Makasih, Umar.”
“Ya. Well, sebenernya, berisiko banget dateng ke sini sambil bawain kamu bubur kepiting dan nungguin kamu makan sampai habis. Dinding di sini kayak dinding di istana. Dindingnya punya mata dan telinga. Itu juga alasanku pakai jas dokter dan bawa stetoskop.”
“Maksudmu?” tanyaku tak paham.
“Semua staf di rumah sakit ini tahu siapa suamimu jauh sebelum berita kemarin nyebar. Cuma mereka takut salah ngomong atau salah ngelakuin sesuatu. Jadi, mereka hormat sama kamu. Tapi sejak kejadian kemarin, mereka makin takut sama suamimu.”
“Maksudmu gimana?” tanyaku semakin bingung.
“Mel, emang kamu nggak curiga semua staf di rumah sakit ini orang Italia? Kecuali Diana dan Meggy, mereka imigran ilegal yang dibantu suamimu biar bisa hidup dengan jaminan layak di negara ini. Sebagai gantianya, mereka harus ngawasin kamu, ngelaporin setiap tindakanmu ke suamimu. Biar nggak ada yang bocorin siapa sebenarnya dia ke kamu. Sekuruti-sekuruti di sini juga mata-mata suamimu. Aku juga yakin, sebentar lagi suamimu tahu aku di sini.”
Aku membekap mulut setelah menyimpulkan, “Itu sebabnya Meggy selalu bilang Jayden bakalan tahu aku lagi ada di mana dan ngapain.”
Aku ingat pernah bertanya dari mana Jayden tahu aku ada di rumah Meggy. Dan Meggy juga yakin Jayden akan segera menyusulku waktu itu. Jayden dulu menjawab hanya mengandalkan nalurinya, tetapi aku mengira karena GPS. Aku lantas tidak mempermasalahkannya lagi sebab terbuai oleh omongan Jayden yang mengambil cuti beberapa hari sampai aku masuk kerja.
Jayden pun lebih memilih membuka pesan dari dokter jantung yang dulunya memberi kabar keadaan Papa dibandingkan denganku. Itulah sebabnya suamiku tahu keadaan Papa.
Belum lagi soal aku makan siang dengan Diana yang tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Jayden. Lalu aku diminta pulang detik itu juga. Dulu aku tak curiga sama sekali. Sekarang aku menjadi paham.
Semuanya yang dulu masih terlihat buram, kini mendadak terang benderang. Mataku seolah-olah dibuka lebar-lebar oleh Umar. Meski seluruh staf di rumah sakit ini seperti membicarakanku, tetapi mereka tetap bekerja dengan baik saat menanganiku. Itu karena Jayden mengawasi gerak-gerik mereka.
Jikalau Jayden bisa melakukan semua itu kepadaku serta menghilangkan nyawa seorang pemimpin mafia, aku ragu ia tidak bisa mengambil tindakan lain untuk memberikan mara bahaya bagi Meggy, Diana, dan seluruh staf di rumah sakit ini. Termasuk Umar.
Pantas saja Meggy dan Diana tidak menyukai Jayden dan tidak berani kemari. Sekarang semuanya masuk akal.
“Meggy dikasih rumah baru dan dilunasi utang-utangnya sama suamimu. Diana pernah dapet kekerasan rumah tangga dari suaminya, tapi suamimu bantuin jeblosin suami Diana ke penjara. Dan aku ..., suamimu ngasih aku bantuan beasiswa ke Harvard, Mel. Biar aku jauh-jauh dari kamu. Dia pernah nyinggung-nyinggung soal kotak musik hadiahku buat pernikahan kalian. Jadi—”
“Umar,” potongku yang tiba-tiba diliputi amarah, “intinya, aku tolol. Karena cuma aku yang nggak tahu siapa Jayden.”
“Nggak, kamu nggak tolol. Dia yang manipulatif ke kamu, Mel.”
Aku menggeleng dengan kepala makin berat. “Tapi kenapa kamu malah dateng ke sini dan ngasih tahu aku semuanya? Padahal Jayden udah—”
“Bodoh amatlah sama beasiswaku. Itu bisa dipikirin entar. Mau kedatanganku di sini dilaporin ke suamimu, aku nggak masalah. Aku beneran khawatir sama kamu, Mel. Aku nggak bisa bayangin kamu harus ngadepin ini sendirian,” potong Umar. “Makanya, aku pengin ngajak kamu keluar dari ini.”

____________________________________________________
Thanks for reading this chapter
Thanks juga yang udah vote, komen, atau benerin typo-typo meresahkaeun
Kelen luar biasa
Bonus foto My twin

Bonus foto Allecio Michelle

Jangan lupa follow sosmed saya lainnya ygy

Well, see you next chapter teman-temin
With Love
©® Chacha Nobili
👻👻👻
Sabtu, 27 Agustus 2022
Remake and repost: Kamis, 28 September 2023
Repost: Minggu, 20 Oktober 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top