Chapter 20 [Berlian Melody]
Selamat datang di chapter 20
Tinggalkan jejak dengan vote, komen atau benerin typo-typo meresahkaeun
Thanks
Happy reading everybody
Hopefully you will love this story like I do love Jayden and Melody
❤️❤️❤️
____________________________________________________
“Bukankah kadang hidup ini sungguh aneh? Tak jarang orang yang menyakiti kita, juga merangkap sebagai penyembuh.”
—Berlian Melody
____________________________________________________
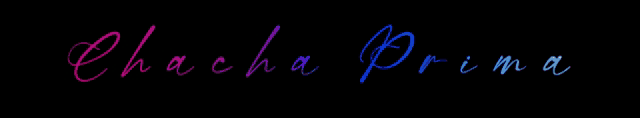
Musim semi
Clifton Hampden, 15 April
Pukul 07.45
This is ridiculous. Bagaimana mungkin Jayden sudah ada di sini? Apakah pria itu sungguh manusia normal pada umumnya yang bertanya orang-orang tentang keberadaanku? Atau jangan-jangan selama ini ia memiliki kesaktian dengan level setara dukun atau penyihir yang bisa melihat dengan mata batin?
Ataukah memang Meggy yang ahli meramalkan sekelumit masa depan dengan dua bukti yang sudah kukantongi? Pertama, wanita itu membuktikan ramalan Jayden tahu kondisi mendiang Papa tanpa aku perlu memberitahu suamiku itu dan datang ke rumah sakit. Kedua, pagi ini.
Meski bukti pertama telah dipatahkan oleh jawaban masuk akan bin bisa membuatku sakit hati oleh Jayden, tetap saja rasanya Meggy bisa meramalkannya, kan? Lalu dengan entengnya Meggy memintaku melupakan hal itu. Apa-apaan?
Padahal beberapa puluh menit belakang setelah meninggalkan Smitten Tatto, aku masih tidak tahu harus bagaimana lagi. Ingin menelepon Karina, tetapi apa yang harus kuceritakan? Ini rumah tanggaku bersama Jayden. Bagaimanapun, aku tidak ingin mengumbar keburukan suamiku ke sahabatku yang tinggal di Jakarta itu. Lagi pula, aku lupa membawa ponsel dan dompet.
Dari penthouse lama, aku lantas memutuskan pergi ke rumah Meggy sebab ingat ia sedang libur hari ini. Maka, selepas memarkir mobil secara rapi di bahu jalan depan rumahnya, aku merapatkan jaket yang kukenakan saat berjalan menuju pintu depan, sebelum menekan belnya dengan tidak sabaran.
Sewaktu pintu terbuka, sang pemilik pun memancarkan wajah kaget. “Melody?” Ia lantas menelitiku dari atas hingga bawah. “Apa yang terjadi? Kenapa kau menggigiti kuku begitu dan hanya mengenakan satu sandal?”
“Boleh aku masuk, Meg?” pintaku.
Ia lantas celingukan. “Tentu. Apa yang terjadi? Di mana suamimu?”
“Boleh aku masuk dulu?”
“Ya, masuklah.”
Meggy menepi agar aku bisa masuk rumahnya. Susana hangat nuansa klasik segera menyambutku. Tanpa permisi, aku duduk di sofa ruang tamunya yang luas.
“Apa yang terjadi? Kau kelihatan kacau dan berantakan,” tuntut Meggy dengan nada dan wajah begitu khawatir.
Sialnya, aku belum memikirkan jawaban dari pertanyaan Meggy. Jawabanku pada pemilik Smitten Tatto tentunya tak bisa digunakan lagi, bukan? Sehingga aku memaksa otakku bekerja untuk mengarang alasan lain yang paling masuk akal menurutku. “Tadinya, aku pergi keluar membeli sarapan untukku dan Jayden. Ta-tapi, seseorang mencoba merampokku.”
“Mel, do you think I’m five years old? I’m not stupid. I know you. Aku tidak yakin kau pergi membeli sarapan dengan sandal dan piyama dilapisi jaket,” bantah Meggy yang makin membuatku dirundung gelisah. Ia yang mengambil duduk di sebelahku seolah-olah ingin mengulik informasi dariku sampai ke dasar jiwaku. Duh! Kenapa tadi aku tak menukar baju di penthouse lama? Padahal aku ingat masih menyisakan beberapa baju di sana.
“Lagi pula, kalau seseorang mencoba merampokmu, kenapa kau tidak lapor polisi atau pulang ke rumah? Aku yakin polisi atau suamimu akan mengatasinya. Jadi, katakan saja padaku yang sebenarnya, Mel,” tambah Meggy.
Kepalaku menunduk dan pandanganku tidak sengaja jatuh pada tato note balok di jari manisku serta cincin pernikahan batu bulan alkemis di jari manis tangan satunya.
“I don’t know, Meg,” jawabku lirih. Pandanganku kini buram oleh produksi air mata yang tiba-tiba sudah menggenang di pelupukku. “Maybe you can guess.”
“Are you okay?”
Mendapat pertanyaan seperti itu, butiran-butiran air mata bergelincir satu per satu di pipiku. Meggy lantas memelukku sambil berkata, “Mel .... Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas, cepat atau lambat, aku yakin suamimu akan ke sini.”
“I beg you, Meg. Don’t call him.”
“Mel, sepertinya kau memang tidak tahu apa-apa. Sudah pernah kukatakan sebelumnya, tanpa aku atau kau memberitahu lokasimu berada saat ini, suamimu pasti bisa mengetahuinya.”
Aku melepas pelukan Meggy. “What do you mean?”
“Nothing. Jangan terlalu dipikirkan. Jadi, kau sedang bertengkar dengannya?”
Aku membuang wajah. “Entahlah.”
Setelah aku cukup tenang, Meggy membawakanku selimut tebal yang kemudian dibalutkan seluruh tubuhku dan memberiku minuman hangat. Ia menawari kamar tamu, tetapi aku tidak ingin berada di kamar sendirian.
“Minumlah, Mel.”
“Terima kasih. Maaf, aku merepotkanmu.”
“Tidak masalah. Omong-omong, ini memang sudah agak lama dan kita sama-sama belum membicarakannya. Tapi aku ingin mengaku kalau aku-lah yang memberitahu Umar soal kau menghadiri pernikahan teman suamimu di New York,” cerita Meggy yang hampir membuatku tersedak.
Aku tak langsung menjawab. Disajikan topik ini secara tiba-tiba menghidupkan ingatanku di hari itu.
Meggy melepas napas berat. “Sayang sekali, kau dan Umar tidak jadi menikah. Padahal kalian sangat serasi. Mungkin, kau juga tidak akan ke rumahku mengenakan satu sandal rumah dalam keadaan kacau seperti ini kalau menikah dengannya.”
Aku hanya bisa menunduk. Bagaimanapun, itu sudah menjadi cerita masa lalu. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Namun, kini aku mulai mempertanyakannya kembali. Apakah jalan yang kuambil ini sudah benar?
“Maaf aku harus mengatakannya secara blak-blakan, Mel. Bahkan aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tidak suka cara suamimu menyelesaikan sesuatu. Contohnya, saat dia mengacau di rumah sakit Summertown.”
Sejujurnya aku benci Meggy terus-menerus mengulang cerita ini seakan-akan pipiku terkena tinju Jayden itu baru saja terjadi. Di sisi lain, itu justru membuatku berpikir Jayden memuntahkan kata-kata kasar kepadaku tadi karena murni tidak sengaja. Hei, Jayden mabuk, oke?
Astaga! Rupanya aku memang sudah gila karena membela Jayden.
Kemudian, seperti yang sudah diduga Meggy sebelumnya. Bel pintu rumah ini berdentang. Meggy menderap ke sana, mengintip dari jendela samping pintu, lantas menghadapku, dan mengatakan, “Mel, suamimu di sini. Kalau kau tidak mau bertemu dengannya, aku akan berusaha mengatasinya.”
Jadi, sembari menatap gelisah Meggy yang mengobrol dengan Jayden di ambang pintu, aku masih bertanya-tanya. Dari mana Jayden tahu aku ada di sini?
Percakapan mereka yang dilafalkan dalam bentuk bisik-bisik hanya memakan waktu beberapa detik. Hasilnya sudah jelas Jayden-lah pemenangnya.
Sebenarnya aku tidak kaget. Siapa yang bisa membelokkan pikiran Jayden dengan berbagai alasan yang dikarang-karang kalau bukan dirinya sendiri?
Dengan mulut dicembungkan, Meggy menggeser tubuhnya agar pria itu bisa masuk. Dan yang pertama kali dilakukan Jayden ialah celingukan. Gugup menyerangkaku ketika ia menemukanku duduk meringkuk di sofa dililit selimut. Aku merasa bagai kucing kecil kedinginan yang menanti seseorang mengadopsinya, memberinya kehangatan serta kasih sayang berlimpah.
Jujur saja, kehadiran Jayden membuatku didera rasa takut kembali. Bagaimana tidak? Beberapa saat lalu suamiku berubah menjadi monster mengerikan. Jayden pria dominan. Ia tegas dalam bertindak dan ambisius terhadap sesuatu sampai-sampai jadi pecandu kerja. Aku sadar itu.
Meski demikian, aku lumayan lega. Setidaknya Jayden berdiri tegak dan berjalan normal. Tidak terseok-seok bak zombi kelaparan yang mencari daging segar.
Aku refleks memalingkan muka ketika melihatnya menjatuhkan tubuh di depanku dengan lutut sebagai penumpunya.
“Hei,” bisiknya.
Melalui ekor mata, bidang pandangku dapat menangkap tangan Jayden yang terulur hendak menyentuhku. Namun, aku spontan beringsut menjauh lantaran takut sentuhannya akan menyakitiku. Sehingga ia menarik tangannya kembali sembari mengembuskan napas berat.
“What are you doing here? Kupikir Meggy udah bilang kalau aku nggak mau ketemu kamu,” ungkapku tak kalah berbisik.
Jayden menatapku lagi. “Aku ke sini buat minta maaf dan jemput kamu pulang.”
“Bagian mana dari kata-kata aku nggak pengin ketemu kamu yang kurang jelas?”
Jayden menghiraukanku dan bersuara rendah. “Maaf, aku ngacau. Aku bener-bener minta maaf.”
“Kamu udah sering ngacau. Jadi apa bedanya kali ini?”
“Ayo pulang dan kita ngomongin ini di rumah. Nggak enak ada Meggy. Lagian, ini rumahnya.”
Suaraku berubah parau saat menegaskan, “Nggak! Aku takut kamu ngamuk kayak tadi. Kamu pasti udah tahu kamu itu nyeremin banget kalau marah. Rasanya aku juga udah pernah bilang kayak gini sebelum kita nikah.”
“Baby ....”
“Jangan coba-coba manggil aku Baby!” desisku yang kini menatapnya lekat-lekat.
“I’m so sorry,” bisiknya, “i’m really, really sorry.”
“Kamu sadar nggak, udah nekan aku di depan dokter-dokter spesialis jantung di Jakarta, tapi aku diem aja? Mereka bahkan maki-maki aku gara-gara kamu, Jayden. Aku ngerawat Papa tanpa pamrih, sampai lama di Jakarta aku nggak pulang sama sekali ke rumah orang tuaku karena fokus ke Papa. Aku bingung ngasih pertolongan pertama waktu Papa gagal jantung di rumah kita. Aku bingung manggil ambulans saat kamu nggak ada. Kok, tega-teganya kamu ngomong Papa meninggal gara-gara aku? Gara-gara aku nggak hamil-hamil? What the fuck was that?”
Sangat jarang aku marah. Sekalinya marah, aku hanya meminta Jayden waktu lima menit untuk mengeluarkan unek-unekku. Tidak lebih, tidak kurang, dan setelahnya, semuanya beres, kami pun berbaikan. Kali ini tidak. Aku marah karena sudah sangat banyak mendapat tekanan dari Jayden yang terus-menerus kucoba memakluminya. Kata-katanya tadi pagi sangat menyakitkan.
Jayden pun beralasan, “I’m drunk and not under control.”
“Kalau gitu jangan mabuk! Aku selalu bilang kamu bisa bagi perasaanmu ke aku. That’s called a marriage! Apa itu nggak cukup? Kalau kamu nggak siap nikah, aku nggak maksa, kok. Aku nggak pernah nuntut kamu mesti nikahin aku sesegera mungkin! Aku bahkan jadi pihak yang pengin nunda pernikahan karena masalah momongan. Karena aku nggak bisa langsung kasih momongan akibat kuliahku. Dan kamu? Apa yang kamu bilang waktu itu?” tekanku.
Jayden menunduk dan terus bergumam, “I’m so sorry.”
“Kamu bilang nggak apa-apa nunda punya anak, yang penting aku jadi milikmu. Malah yang tadinya rencananya kita nikah enam bulan ke depan, kamu majuin. Terus sekarang aku belum hamil, kamu malah nyalahin aku.”
Dan aku masih belum puas mengeluarkan unek-unek. “Ini loh, yang aku takutin, Jayden. Ini! Kamu pikir aku nggak pengin punya anak dari kamu? Aku juga pengin banget. Aku emang udah lulus dan nuruti kamu yang cuma ngizinin aku kerja tiga hari dalam seminggu. Dan per harinya maksimal nggak lebih dari lima jam. Tapi, gimana bayi kita bisa terwujud kalau kamu juga nggak ada effort buat tinggal di rumah lebih lama? Aku bangun kamu jarang ada di sampingku. Aku pulang, kamu kadang baru mau berangkat ngecek kelab. Aku nggak tahu kenapa rasanya kamu semakin jauh dari aku.”
Aku meledak dan Jayden membiarkanku. Tak tahu harus apa lagi, akhirnya aku menangis sejadi-jadinya.
Selama di Jakarta, kami memang menghabiskan lebih banyak waktu berdua dalam melakukan berbagai hal. Termasuk paling sering menjaga Papa yang sakit. Lalu ketika ada Kak Jameka atau Tito yang menganggantikan kami, kami baru pergi berduaan. Namun, setelah kembali ke sini, rasanya agak sulit menyingkronkan jadwal kami. Waktu kami berduaan berkurang banyak. Dan aku tak tahu kenapa itu menjadi salahku.
“Sorry. I’m so sorry. But, can I hug you?”
Pertanyaan itu membuatku kaget. Secara impulsif aku menemukan diriku menerjang Jayden dengan pelukan. Pria itu terhenyak sampai-sampai punggungnya membentur meja rendah yang mengelilingi sofa. Meski demikian, ia tetap balas melingkarkan tangan-tangannya di tubuhku. Aku juga tak peduli soal selimut yang melingkari tubuhku yang jatuh ke lantai.
“I miss you. I miss us,” rengekku.
Dasar! Bisa-bisanya aku cepat luluh begini.
“Aku juga, Baby. Maaf, udah bikin kacau.” Jayden menjatuhkan ciuman di pundak dan di sela-sela rambutku. Kegiatan kami lantas terganggu oleh dehaman Meggy.
“Oh! Sorry, Meg,” ucapku sambil meringis dan kontan melepas pelukan. Aku mengusap air mata menggunakan punggung tangan sambil memandang Meggy.
“Sebaiknya kalian pulang dan pergi ke kamar kalian sendiri,” sindir Meggy dengan tampang lempeng. Wanita yang berdiri tidak jauh dari satu set sofa ruang tamunya itu sekarang melipat kedua tangan di dada.
Meski sangat kentara kalau tidak suka dengan Jayden, setidaknya Meggy menghormati keputusanku untuk memilih pria itu.
Aku pun tidak kuasa menggigiti kukuku seraya menahan senyum rikuh. Lalu berusaha berdiri diikuti Jayden yang mengajak, “Ayo pulang,”
“Ayo,” balasku sambil menunduk. Ketika menatap sebelah sandalku yang teronggok di lantai berlapis karpet putih gading di sebelah selimut Meggy, aku bertanya pada wanita itu. “Meg, bisakah kau meminjamiku sepatu?”
“Kenapa harus minjem sepatu?” tanya Jayden bingung.
“Eh, tadi ke sini cuma pakai satu sendal gara-gara lepas di rumah. Jujur, aku takut banget tadi. Jadi, buru-buru keluar aja gitu. Aku bahkan nggak peduli sama Max.”
“Maaf,” gumam Jayden yang masih bermuka muram. Tatapannya jatuh pada sebelah sandalku. Kemudian ia melanjutkan, “Jangan khawatir soal Max. Dia udah aku kasih makan sama minum.”
“Aku maafin, kok. Tapi tolong jangan diulang lagi,” pintaku tegas, tetapi lembut. Tanganku menyentuh pipi suamiku sebagai isyarat aku serius. Lalu peganganku terlepas begitu saja sewaktu Meggy kembali mengudarakan dehaman keras.
“Jadi? Kau mau meminjam sepatuku atau tidak?” tanya Meggy yang lagi-lagi membuatku rikuh. Baru beberapa menit lalu aku menangis di pelukannya karena Jayden. Kini ia sudah menyaksikan kemesraanku bersama orang yang membuatku menangis.
Dasar aku!
Namun, bukankah kadang hidup ini sungguh aneh? Tak jarang orang yang menyakiti kita, juga merangkap sebagai penyembuh.
“Tidak perlu,” tanggap Jayden yang membawaku ke alam nyata. Suamiku itu kemudian menghadapku lagi. “Maaf, aku nggak bisa gendong kamu soalnya masih pusing. Takutnya jatuh. Jadi, pakai sandalku aja.”
“Tapi—”
“Nggak apa-apa. Kamu yang lebih penting daripada aku,” potong Jayden yang berikutnya menunduk, lalu melepas sepasang sandal rumah putih—yang menurutku seperti—ukuran raksasanya.
Mataku pun membelalak dengan sendirinya lantaran kaget. Sambil menyeka rambut yang jatuh sewaktu menunduk, aku menunjuk-nunjuk sepasang sandal rumah Jayden. “Jayden, kenapa sendalmu merah-merah gitu—astaga, kakimu berdarah!” Kekagetanku bertambah kala melihat Jayden menggeser tubuhnya. Dan warna merah yang mencetak kaki besar Jayden segera terbentuk di karpet Meggy. Entah keberuntungan atau petaka warna darah itu sangat kontras dengan karpet putih gading Meggy.
“Nggak apa-apa, cuma kena pecahan kaca. Ayo pulang,” jawab Jayden gamblang.
Oh Tuhan, aku sampai lupa tadi Jayden sempat menginjak pecahan kaca.
“Nggak, kamu butuh diobatin dulu!” seruku.
“Di rumah aja. Oh, ya, kalau kamu jijik sama sendalku, biar aku gendong kamu aja. Kayaknya aku baru aja dapet kekuatan super dari senyumanmu. Pusingku langsung ilang.”
“Bukannya gitu ...,” selorohku agak tersipu.
Aku sudah terbiasa melihat darah karena profesiku. Ditambah pernah satu kali merasakan ciuman Jayden yang bibirnya sobek dan secara tidak langsung menyalurkan cairan penyusun tubuh tersebut. Jadi, mana mungkin aku akan jijik hanya karena mengenakan sandal Jayden yang berlumuran darah?
Tidakkah Jayden mengerti bahwa aku mengkhawatirkannya?
Jayden yang sudah memosisikan diri merendah sambil membelakangiku pun menelengkan kepala beberapa derajat ke arahku. “Terus?”
“Aku khawatir, Jayden.”
“Kamu boleh khawatir kalau udah sampai rumah. Kamu juga boleh ngobatin lukanya kalau udah di rumah.”
Aku masih mencoba, “Lagian karpet Meggy jadi kotor. Kita harus tanggung jawab.”
“Aku yang bakal ngurus itu.”
Kurasa sudah tidak ada lagi yang bisa kugali sebagai alasan, aku menyerah. “Well, okay ...,” gumamku.
Sebelum naik ke punggung suamiku, aku melipat dan meletakkan selimut Meggy di sofa. Godaan punggung lebar Jayden memang tidak bisa kuabaikan begitu saja. Aku sangat menyukai punggungnya. Dan aku yakin ini merupakan salah satu strategi bujuk rayu Jayden agar aku mau ikut pulang sesegera mungkin.
Tanganku yang memegang pundak-pundak Jayden pun mengetat secara otomatis saat pria beraroma min ini berdiri tegak setelah menenteng sandal rumahku. Saat melewati Meggy, Jayden berkata, “Maaf sudah mengotori karpetmu. Tapi aku akan segera meminta seseorang membersihkannya.”
Meggy memalingkan muka sejenak ke karpetnya kemudian menatap kami lagi. “Tidak masalah, terima kasih.”
“Tidak, aku yang seharusnya berterima kasih,” balas Jayden tegas.
Sedangkan aku berkata, “Terima kasih, Meg. Maaf sudah merepotkan.”
“Tidak masalah. Jaga dirimu baik-baik, Mel.”
Jayden memindah tubuh ke mobil Porsche Black Cayman yang tadi pagi kukendarai. Katanya, ia sudah memesan sopir pengganti untuk mengantar kami ke rumah sehingga tidak sampai sepuluh menit kemudian, kami sudah tiba di penthouse. Kami langsung menuju sofa ruang tengah dengan dapur terbuka disambut Max. Anjingku pun tidur di karpet sebelah sofa.
Sebelum memutuskan sarapan yang sempat kupesan tadi, aku mencuci tangan dulu untuk menangani Jayden.
“Omong-omong, kok, kamu bisa tahu aku ada di rumah Meggy?” tanyaku penasaran tanpa memindah pandangan ke wajah Jayden.
Tanganku sibuk membersihkan luka-luka di telapak-telapak kaki Jayden mengunakan cairan chlorhexidine. Setelahnya, kuguyur luka Jayden menggunakan cairan sodium chloride 10 persen. Selain steril, penggunaannya terhadap luka baru tentu jauh lebih ramah pada jaringan kulit dan otot, daripada membersihkan lukanya menggunakan alkohol yang bisa lebih merusak jaringan kulit dan otot.
“Naluri,” jawab Jayden ringkas. Suaranya teredam bantal sofa ruang tengah gara-gara posisinya yang tengkurap.
“Baby ..., aku serius,” rengekku.
“Kamu pikir, aku nggak dua rius?”
“Hm .... Teknologi sekarang canggih. Pasti mobil itu ada GPS-nya,” dugaku logis.
“Kamu nggak tahu aja aku habis keliling Inggris cuma buat nyari kamu.”
“Ya ampun …, aku terharu ….”
Jayden tidak menanggapi. Ia justru berkata lain. “Oh ya, aku bakal ambil cuti kerja selama beberapa hari. Sampai kamu masuk kerja lagi.”
Gerakan tanganku yang memegang kasa steril pun berhenti mendadak. “Are you sure about this?” tanyaku memastikan. Barangkali aku salah dengar dan terburu-buru terperangkap rasa senang.
“Ya. Mumpung kamu lagi libur juga. Aku pengin kangen-kangenan sama kamu,” terang Jayden yang membuatku menggigit bibir bawah. Yah, seandainya kedua tanganku tidak sibuk, aku pasti sudah mempertajam kuku menggunakan gigi.
“Itu juga kalau kamu mau kangen-kangenan sama aku,” tambah Jayden dengan suara rendah, seolah-olah berbicara dengan dirinya sendiri. Kelihatannya, Jayden sangat menyesali perbuatannya saat mabuk.
Dengan adanya ide ‘kangen-kangenan’ ini saja, Jayden terlihat sedang berusaha keras menyediakan waktu untukku. Jadi, tidak ada salahnya memberinya kesempatan, bukan?
“Aku mau, kok.”
Jayden sontak mengubah posisinya untuk menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ia seolah-olah sangat bersyukur.
“Beneran?” tanya Jayden yang kembali mengeluarkan suara rendah.
Aku mengangguk sambil tersenyum malu-malu.
“May I kiss you now?” pinta Jayden. Kalimat itu pun sukses mengantar kejut ke otakku lalu menyebar ke seluruh tubuhku.
“You’re my husband. Sejak kapan kamu butuh izin dariku?”
“Aku takut nyakitin kamu.”
“Tadi kamu mabuk, sekarang kayaknya udah enggak. Aku percaya kamu nggak akan nyakitin aku,” ungkapku dari hati yang paling dalam. “Lagian rasanya kamu tadi udah nyium pundakku dan leherku waktu kita pelukan di rumah Meggy. So, come here and kiss me.”
Selama hampir lima detik, Jayden tidak merespons. Sepertinya, ia sedang mencerna kata-kataku. Karena pada detik berikutnya, suamiku duduk, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh rahang kiriku serta memajukan wajah secara perlahan-lahan.
Kedua netraku menatap bibir Jayden sejenak, sebelum akhirnya aku memejam untuk menerima ciuman dari Jayden. Dengan sangat pelan dan hati-hati, Jayden menempelkan bibirnya ke bibirku. Tangan-tanganku pun refleks menjatuhkan kasa steril untuk mengusap-usap wajah Jayden.
Pria itu lantas melepaskan diri dan menyentuhkan keningnya ke keningku. Sambil terus membelai pipiku, Jayden berbisik, “Makasih udah ngasih aku izin buat nyium kamu.”
Aku tertawa kecil. “Sounds weird. But, I think, I want you .... I want you, Baby.”
Aku tidak tahu kalau kalimat ini sangatlah sakti. Karena pada detik berikutnya, Jayden kembali menjatuhkan bibirnya di bibirku. Ia tidak memberikan ciuman ringan seperti tadi. Melainkan ciuman dalam, kuat, dan liar. Aku membuka bibir, secara alami mengundangnya agar mengajakku menari bersama.
Tubuhku tersentak oleh gerakan Jayden yang tiba-tiba mengangkatku. “Eh, lukamu, Baby. Padahal kita bisa di sofa aja,” protesku.
“Ada Max tidur.”
Lalu sambil menginvasi bibirku, Jayden membawaku ke kamar kami. Berhubung sangat merindukannya, aku pun menjadi liar. Tubuhku panas seolah-olah terbakar apabila Jayden tidak menyentuhku. Dengan kecepatan yang tidak bisa kusangka-sangka sebelumnya, aku memiliki kemampuan melepaskan kaus Jayden.
Sejenak, aku merasa terhipnotis oleh otot-otot Jayden yang tertarik ketika pria itu membuang kausnya sembarangan. Aku lantas menyusurkan jari-jemariku secara perlahan ke tato di dada Jayden secara takzim. Tato itu membuatnya lebih maskulin. Aku sangat menyukainya.
Lalu, tahu-tahu Jayden sudah membawaku terbang bersama jiwa dan ragaku yang kuserahkan pada pria itu seutuhnya.

Musim semi
Abingdon, 16 April
Pukul 08.30
Burcot Brook Lodge CL hari ini dipayungi awan cerah. Hamparan tanah lapang berumput hijau tidak terlalu luas ini menawarkan kehangatan siraman cahaya mentari. Cuaca yang lebih baik daripada berhari-hari lalu.
Sebenarnya, kami tidak merencanakan berkemah. Ide ini didapat Jayden saat kami menonton TV yang menampilkan sekelompok orang sedang berkemah dan masak-masak di lahan terbuka. Maka pada detik itu pula, Jayden menelepon jasa sewa transportasi.
Katanya, “Daripada kita naik Rubicon dobel kabin terus repot masang tenda, lebih baik sewa karavan dengan fasilitas lengkap. Yang ada kasur, TV, kulkas, toilet, dan dapur mini.”
Aku pun sangat penasaran bagaimana rasanya berkemah di lahan terbuka seperti ini sehingga tak berpikir dua kali untuk menyetujui ide Jayden. Kami sepakat tidak mengajak Max karena ingin acara ‘kangen-kangenan’ ini lebih intim. Jadi, kami menitipkannya di penitipan hewan langgananku, yang setiap hari selalu memberi laporan kondisi Max selama dititipkan. Pihak Golden Care and Clinic selalu mengirim video Max saat makan atau saat exercise bersama para perawatnya. Kadang-kadang ketika Max drama juga.
“Baby, ada tupai,” seruku sewaktu kami baru tiba dan aku keluar karavan untuk melihat-lihat sekitar. Lahan ini kecil, maka dari itu jarang ada yang ke sini sehingga terkesan eksklusif. Dan ketika pandanganku tidak sengaja jatuh ke akar pohon, ada tupai.
Jayden lantas keluar karavan dan berdiri di sampingku sambil merangkulku. “Kayaknya dia laper.”
“Kita kasih makan, yuk. Aku inget tadi juga beli kenari di supermarket sebelum ke sini.” Aku mengambil biji-biji kenari di pantri kecil dalam karavan. Namun, ketika hendak keluar, aku tak sengaja melihat dan mendengar ponselku berdering. Aku mengambil alat komunikasi tersebut yang terletak di nakas samping kasur. Rupanya, telepon itu berasal dari Golden Care and Clinic.
Meski sedikit aneh sebab bukan panggilan video yang mereka lakukan, tetapi aku cukup semangat mengetahui sikap dramatis apa lagi yang dibuat Max. Mengingat ini belum jadwal makannya.
“Ya, halo?” sapaku setelah sambungan terhubung.
Bernada campuran antara sedih dan panik, pria di ujung sambungan telepon itu mengabarkan, “Maafkan aku, Mrs. Wilder, Max ditemukan mati di kandangnya.”
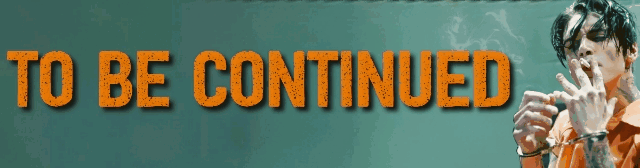
____________________________________________________
Thanks for reading this chapter
Thanks juga yang udah vote, komen, atau benerin typo-typo meresahkaeun
Kelen luar biasa
Bonus foto My twin

Jangan lupa follow sosmed saya lainnya ygy

Well, see you next chapter teman-temin
With Love
©® Chacha Nobili
👻👻👻
Kamis, 18 Agustus 2022
Remake and repost: Rabu, 20 September 2023
Repost: Kamis, 17 Oktober 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top