Chapter 18 [Berlian Melody]
Selamat datang di chapter 18
Tinggalkan jejak dengan vote, komen atau benerin typo-typo meresahkaeun
Thanks
Happy reading everybody
Hopefully you will love this story like I do love Jayden and Melody
❤️❤️❤️
____________________________________________________
“Pacaran dan berumah tangga itu sangat jauh berbeda. Tidak peduli seberapa lama kau berpacaran dengan seseorang, apabila kalian menikah, sifat-sifat asli pasangan masing-masing baru muncul.”
—Berlian Melody
____________________________________________________
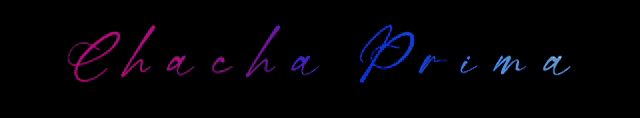
Musim semi
Clifton Hampden, 15 April
Pukul 07.10
Gelombang kejut begitu besar menerjangku ketika mendengar susunan kata yang merangkai kalimat kasar itu keluar dari mulut Jayden. Sekujur tubuhku berhenti bergerak karena mendadak kaku. Debar jantungku yang kencang rasanya menghantam-hantam gendang telingaku. Satu-satunya yang bisa kulakukan selain bertahan di posisiku, ialah mencoba tindakan lain dengan mendorong pikiranku bekerja memahami situasi.
Ini pasti efek kompilasi dari duka yang mendalam akibat kehilangan Papa dan hampir sebotol minuman keras yang ditenggak suamiku. Sehingga, ia bisa berkata demikian. Dalam dunia medis, minuman beralkohol tinggi sudah terbukti akurat dapat mengambil alih kontrol otak si peminumnya.
Sejak Papa meninggal, Jayden memang berubah menjadi sosok yang jauh lebih pendiam ketimbang dulu. Tidak ada senyum yang tersungging di bibirnya. Padahal beberapa waktu belakangan ia sudah mulai terbiasa dengan kata-kata agak panjang yang dibumbui humor-humor khasnya. Kadang-kadang, ia membagi perasaannya denganku dan itu membuatku merasa amat istimewa. Merasa sedikit berguna sebagai seorang istri selain bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Dan satu lagi. Jayden bahkan tak marah besar soal Umar. Jangankan marah. Ia bahkan tidak pernah membahas perihal ketidaksengajaanku bertemu Umar di minimarket.
Pasti saat ini merupakan masa paling sulit bagi Jayden untuk menerima keadaan dan tindakan paling mudah ialah menyalahkan orang lain. Meski tidak sependapat dengan tindakannya, tetapi bukankah sudah sepatutnya aku bisa memakluminya?
Setelah Jayden pulih nanti, aku akan mencoba menenangkannya secara perlahan-lahan dan penuh kehati-hatian.
“Baby, you’re drunk. I know you didn’t mean it,” ucapku dalam intonasi pelan yang sebenarnya diperuntukkan bagi diriku agar tidak memasukkan kata-kata kasar itu ke hati. Jangan sampai aku terpengaruh oleh ini.
Mencoba sekali lagi. Tanganku terulur meraih botol minuman keras di genggaman Jayden. Sayangnya, aku masih belum mendapat respons baik. Terulang kembali, pria berambut acak-acakan berkaus hitam bergambar tengkorak lusuh itu menepisku kasar. Akibatnya botol bersepuh emas itu terlepas dari genggamannya dan terlempar ke lantai marmer tidak berlapis karpet. Minuman yang tinggal sedikit pun habis tak bersisa.
Belum sempat aku diberi jeda waktu untuk meredakan kekagetan, kala aku refleks berjingkat mundur agar tidak terkena serpihan kacanya, Jayden memaki, “Drunk or not, I mean it! I really mean it!”
“No, you didn’t.” Aku menggeleng pelan, linier dengan suaraku yang hampir hilang lantaran benar-benar tidak ingin mempercayai hal tersebut.
“Yes, I do mean it,” tekan Jayden tak kalah berbisik.
Dengan mata memerah dan berkaca-kaca, ia berdiri. Sosoknya yang menjulang tinggi di hadapanku diselimuti kegelapan. Cahaya yang meyorot dari jendela di belakangnya membuat wajah dan bagian depan tubuhnya bagai ditelan bayangan.
“J-Jayden,” cicitku bagai tikus kecil terjebak ular raksasa yang hendak menyuntikku dengan bisa mematikan, sebelum menelanku.
“Gara-gara kamu, Mel. Semuanya gara-gara kamu.”
Suara rendah dan serak Jayden menusuk telingaku serta berhasil menembus lapisan demi lapisan pertahanan hatiku. Wajahnya memerah dan berkantung mata hitam. Dengan susah payah, tak peduli pada serpihan-serpihan kaca, ia lantas mendekatiku secara perlahan.
Aku spontan mundur sebab takut. Kedua tanganku pun terangkat ke dada membentuk benteng pertahan diri sekaligus memberi aba-aba agar ia berhenti mendekat. Dan aku harus menahan diri agar tidak menggigiti kuku atau menutup mulut menggunakan tangan akibat bau alkohol menyengat menguar dari mulut Jayden bercampur aroma min kesukaanku.
“Seandainya kamu nggak nunda-nunda punya anak, Papa pasti nggak akan sekecewa ini sama aku. Pasti Papa masih bisa ngelihat anak-anak kita sebelum meninggal,” bisiknya amat lirih. Kekecewaan di wajahnya dapat terbaca jelas olehku.
Omongan Jayden itu pun mulai mempengaruhi mentalku. Sehingga aku berimpulsif mengatakan, “Tapi sebelum nikah kamu udah setuju buat nunda punya anak sampai kuliahku kelar. Bahkan kamu sendiri yang minta kita nikah dulu, urusan punya anak belakangan. Kamu juga bilang asal aku jadi istrimu, milikmu, nunda punya anak nggak masalah.”
Tentu saja dengan kondisi seperti ini, Jayden bermanuver. Pikiran logisnya hilang sama sekali. “Kuliahmu udah kelar beberapa bulan lalu. Kenapa kamu nggak hamil-hamil juga?”
Aku tahu seharunya aku tidak perlu memasukkan kata-kata pedas itu ke dalam hati lantaran Jayden mabuk. Omongannya tidak terkontrol dan bermacam-macam emosi yang campur aduk menguasai dirinya. Sayangnya, aku tidak bisa mencegah perasaan itu lebih giat menusuk hatiku. Apabila orang lain yang mengatakannya, aku akan menganggap itu sebagai angin lalu. Seperti ibu-ibu yang kepo di minimarket waktu itu atau penjaga kasirnya. Masalahnya, ini Jayden. Jayden-ku. Suamiku. Bagaimana mungkin ia setega ini?
Memangnya ia pikir, aku tidak ingin punya anak darinya? Memangnya ia pikir, setelah tidak menunda memiliki momongan, aku tidak ingin segera hamil?
Aku ingin! Aku sangat ingin!
Oleh karena itulah aku pun membantah, “Kamu sendiri sibuk, jarang pulang. Jangan salahin aku doang—”
“Aku sibuk itu gara-gara kamu. Aku kerja kayak gitu gara-gara kamu,” potong Jayden dengan menekan kata-kata “kayak gitu” tepat di waktu punggungku terantuk pintu ruang kerja sampai-sampai membuatku berjingkat.
Tangan-tangan Jayden kontan memerangkapku. Wajahnya menunduk. Jaraknya hanya sejengkal dari wajahku.
Kupejamkan mata erat-erat sambil menelengkan wajah sebab benar-benar diselimuti rasa takut. Diriku kini mirip model empirik istri yang tersakiti oleh suami yang bertindak absurd di sinetron tontonan Mbak Mar.
“G-gimana bisa itu gara-gara aku? Kamu ngajak ke tempat kerjamu aja cuma sekali dan aku nggak tahu apa-apa soal itu. Kamu juga nggak pernah cerita gimana mulai bisnis tongkronganmu. Kamu nggak pernah ngenalin karyawan-karyawanmu padahal itu penting buat aku juga, biar aku bisa hubungin mereka kalau kamu nggak bisa dihubungin. Bahkan kata Papa kamu juga punya bisnis lain selain properti yang nggak aku tahu itu ap—argh!”
Jayden mencengkram rahangku kuat-kuat yang otomatis membuatku membuka mata lebih lebar. Padahal tubuhku sudah akan kabur, tetapi cengkraman itu mencegahku, memaksaku mendongak untuk menatapnya. Tanganku pun berusaha mencegahnya. Namun, seperti halnya semua orang di dunia ini ketahui, kekuatan pria tentu tidak sebanding dengan kekuatan wanita. Tindakanku jelas amatlah sia-sia. Hanya membuang-buang waktu.
Keringat dingin mulai bergulir di pelipisku saat Jayden mendesis dengan suara serak dan parau. “Gara-gara kamu ngilang waktu itu, aku jadi harus kerja kayak gitu. Papa kecewa sama aku gara-gara kamu.”
Lagi dan lagi, ia menekan kata-kata “kayak gitu” yang membuatku beranggapan kalau itu memiliki makna tersendiri. Entah apa maksudnya, aku tidak memiliki waktu untuk berpikir atau mengira-ngira.
“Jayden, kamu mabuk! Lepasin aku! Kamu mabuk! Lepasin aku, Jayden. Sakit banget ....”
Selain menahan nyeri tak kira-kira serta berusaha bersuara sejelas mungkin, aku masih mencoba meloloskan diri. Aku mengingat pintu di belakangku. Sebelah tanganku terpaksa meraba gagang pintu dan menekannya sekuat tenaga.
Pintu di belakangku resmi terbuka. Aku hampir terjungkang ke belakang seandainya tidak berpegang erat pada daun pintu. Sayangnya, tidak semudah itu aku bisa menyeimbangkan diri sehingga menyebabkan diriku terperenyak. Sandal rumahku lepas sebelah, tetapi aku belum mampu menggubrisnya karena ketakutan yang makin menjadi-jadi saat Jayden mendekat dengan langkah terseok-seok mirip zombi.
“Give me a baby now,” gumamnya sambil mengulurkan tangan.
Aku ingin berteriak, tetapi tidak ada siapa pun di penthouse ini kecuali kami dan Max. Unit ini berada di lantai paling atas yang sangat eksklusif sehingga menawarkan privasi unggulan. Tidak akan ada tetangga-tetangga yang bisa mondar-mandir di sekitar. Sistemnya pun menggunakan teknologi supercanggih dengan pendeteksi suara dan sidik jari. Rumah kami memiliki lift khusus yang tidak bisa dinaiki selain penghuninya.
Selagi Jayden berusaha menggapaiku dengan jarak makin dekat, aku harus menggunakan kesempatan minim yang kupunya ini untuk bergegas bangkit dan berlari menuruni tangga.
“Jangan takut sama aku, Mel. Aku suamimu. Come here. Give me a baby now!” teriak Jayden mirip orang sakit mental.
Aku mendengar suara ia terjatuh dan memaki dalam bahasa Belanda serta bahasa Inggris. Namun, aku belum bisa menghidupkan saraf empatiku. Max terdengar menggonggong dari ruangan sebelah. Bisa saja aku menyuruhnya menggigit Jayden, tetapi Max amat setia pada Jayden. Selain itu, Jayden pasti akan terluka—mengingat ukuran Max. Dan aku tidak ingin Jayden terluka karena Max. Sudah pernah kukatakan bahwa Max pernah sekolah dan ia bisa melakukan trik. Salah satunya bila pemiliknya mendapat ancaman.
“Jangan pergi, Mel. Jangan tinggalin aku, Baby .... Kamu istriku. Kamu istriku. Jangan tinggalin aku ....”
Suara Jayden berubah parau mirip orang hampir menangis. Namun, aku berusaha menulikan pendengaran oleh rengekannya. Sambil menggigiti kuku dan tak peduli rambutku yang lengket di dahi serta pipi, aku terus berlari ke pintu depan, menyambar jaket kulit di gantungan, dan meraih kunci mobil Porsche Black Cayman yang biasa kugunakan untuk pergi bekerja.
Gonggongan Max makin terdengar jelas.
Jantungku bertalu-talu tangkas. Aku bahkan menggigil, yang kuyakini bukan dampak dari cuaca pagi. Melainkan karena ketakutan.
Kenapa Jayden bisa sampai seperti itu ketika mabuk? He looks like a terrible beast.
Aku butuh tempat berlindung dan butuh meluruskan pikiranku yang bengkok-bengkok. Oleh sebab itu, tanpa ingin membuang waktu dan kesempatan akan akan segera pergi. Namun, saat aku hendak membuka pintu, Max tiba.
“It’s okay, Buddy. Aku cuma mau keluar bentar. Kamu di rumah aja sama Jayden.”
Sambil gemetaran aku mengelus-elus Max. Anjingku malah mendramatisir keadaan dengan menggonggong sambil menowel-nowel lenganku.
Sesekali kulihat belakang Max, berjaga-jaga barangkali Jayden bisa menyusul. “Cuma bentar. Aku nggak akan ninggalin kamu, Max.”
Aku meraih gagang pintu dan Max menggigit bagian bawah jaket kulitku. Dan aku segera berseru sambil mengancungkan tangan ke Max. “Duduk!”
Setelah memastikan Max duduk, aku segera pergi. Tak mau membuang waktu lagi, aku turun menggunakan lift khusus yang harus menggunakan sidik jariku, menuju basemen, dan mengemudikan mobil ini entah ke mana. Bagian terpenting, aku harus keluar dulu dari gedung megah ini.
Ketika aku melewati gerbang, petugas keamanann mengernyit keheranan dan mengawasi plat mobilku layaknya orang kebingungan. Tentu saja aku tidak sempat berpikir lebih jauh dengan itu. Aku tak membuka kaca jendela untuk menyapanya seperti biasa sebab buru-buru menginjak pedal gas agak dalam serta bergabung dengan mobil-mobil lain di jalan raya.
Kata orang, pacaran dan berumah tangga itu sangat jauh berbeda. Tidak peduli seberapa lama kau berpacaran dengan seseorang, apabila kalian menikah, sifat-sifat asli pasangan masing-masing baru muncul. Apakah itu yang terjadi pada Jayden? Sifat aslinya yang baru kuketahui?
Pikiranku kalut dan aku tak tahu sudah berkendara berapa lama serta ke mana. Kemudian tahu-tahu aku telah memasuki jalanan Oxford yang sangat kukenal. Artinya aku telah berkendara kurang lebih hampir setengah jam dan batinku masih belum tenang. Satu-satunya yang kupikirkan saat ini ialah aku membutuhkan seseorang untuk meredakan ketakutanku dan pas sekali mobil ini melewati Smitten Tatto.
Tak bisa berpikir jauh. Secara impulsif segera kutepikan mobil tersebut di depan Smitten Tatto.
Ketika pertama kali kemari, bagian kaca yang menjadi dinding depan toko masih transparan dan bisa dilihat dari luar. Kini, sebagian dindingnya dilapisi berbagai stiker. Di bagian pintunya masih tertulis “closed”. Itu artinya belum ada pukul sepuluh pagi seperti jam buka toko ini. Namun, mana aku peduli? Aku pun buru-buru mengetuk-ngetuk pintunya.
“Kami belum buka!” Terdengar teriakan wanita dari dalam dan aku mengenal baik itu sebagai suara Fani.
Maka, aku lebih giat mengetuknya sambil mengintip dari pintu kaca yang tidak tertutup stiker. Fani terlihat sedang mengelap kursi yang digunakan untuk menato. Sedangkan Gibran sedang mengeringkan alat-alat menato yang kelihatannya baru saja disterilkan.
“Fan, ini gue. Tolong bukain pintunya,” teriakku dengan napas ngos-ngosan sebab debar jantungku masih tidak karu-karuan sejak terakhir kali Jayden berkata menyakitkan.
Mendengarku, gerakan Fani dan Gibran berhenti. Mereka kompak menoleh ke pintu kaca. “Melody?” raung Fani dengan wajah sumringah dan segera meletakkan lap untuk membukakan pintu.
“Iya, ini gue, Fan. Tolong bukain pintunya.”
Pintu terbuka. Wajah Fani yang semula penuh senyum kontan luntur saat melihat kondisiku. “Ya Tuhan! Mel, lo kenapa?” tanyanya sembari menggeretku masuk dan mendudukanku di sofa. Gibran sontak meninggalkan peralatan menatonya untuk menghampirku.
“Lo kenapa, Mel?” tanya pria itu. “Jayden mana?” Pandangannya keluar sambil celingukan.
“Di-di rumah,” jawabku terbata-bata. Apakah aku sudah mengambil tindakan tepat dengan bertandang kemari? Aku masih belum memikirkannya lebih lantaran masih syok. Aku hanya berharap di sini dapat memberiku tempat perlindungan sementara sampai semua memadai. Terutama kondisi hatiku.
“Tapi Jayden udah tahu kalau lo ke sini, kan?” tanya Gibran lagi.
Aku terpaksa bohong. “Iya, dia tahu gue emang mau ke daerah sini. Tapi nggak tahu kalau mau ke toko kalian.”
“Terus kenapa lo sampai bisa berantakan kayak gini?” Gantian Fani yang bertanya. Tangannya mengusap rambutku yang acak-acakan.
“O-orang mabuk. Ya, orang mabuk.” Aku tidak sepenuhnya bohong. Aku hanya menutupi siapa yang sebenarnya mabuk dan sebagian faktanya.
Fani yang tampaknya kurang memahami ucapaki pun menegaskan, “Lo diganggu orang mabuk?”
Kepalaku mengangguk-angguk cepat. “Iya, gue diganggu orang mabuk.”
“Gimana kronologinya? Tapi lo udah lapor polisi belum?”
Bagaimana kronologi yang bisa kuceritakan dan bagaimana mungkin aku akan melaporkan suamiku ke polisi? Apa yang harus kujelaskan? Otakku benar-benar macet untuk sekadar mencari-cari alasan logis. Jadi, aku hanya bisa menggeleng untuk menjawab pertanyaan Gibran.
“Ya ampun, Mel. Kenapa lo nggak lapor polisi?” keluh Fani sambil mengusap-usap lenganku. Sesekali ia mendongak untuk menatap Gibran yang berdiri di depan kami. Sepasang suami istri itu tampak begitu cemas.
“Aku udah bisa kabur. Makanya buruan ke sini.”
Lalu dengan cekatan, Fani menyuruh suaminya. “Telepon si Jay, Bi. Suruh jemput Mel ke sini.”
“Jangan! Jangan telepon Jayden! Gue cuma bentar doang, kok, di sini. Abis ini gue mau pulang. Gue cuma agak syok,” cegahku.
“Eh, tapi si Jay harus tetep tahu dulu, Mel,” bantah Gibran yang kemudian berjalan ke meja konter dan mengambil ponsel.
Aku spontan berdiri. “Gibran, beneran gue nggak apa-apa. Jangan telepon Jayden. Entar dia malah panik. Ini gue udah mau balik, kok. Gue udah lumayan tenang setelah cerita kalian.”
“Tapi lo masih gemetaran, Mel. Seenggaknya minum dulu,” tawar Fani.
“Thanks, beneran nggak usah. Thanks juga udah bukain pintu buat gue,” pungkasku yang lantas berjalan ke pintu keluar setelah memastikan Gibran tidak menelepon Jayden.
Namun, Fani seperti tak yakin. “Mel, beneran lo nggak apa-apa nyetir sendiri? Mending kami antar sampai rumah, ya?”
Aku mulai berperan jadi manusia dengan perasaan normal, dengan senyum yang semoga saja terlihat natural. “Enggak usah, takut ngerepotin. Kalian juga mau buka toko, kan?”
“Toko, mah, buka entar,” jawab Gibran.
Tentu saja aku menolak, “Nggak apa-apa, kok. Kalau gitu gue cabut dulu, ya?”
“Ya udah hati-hati,” pinta Fani. Masih dengan wajah khawatir, ia bersama Gibran mengantarku sampai depan mobilku terparkir. “Btw, Mel. Kenapa lo pergi pakai baju tidur sama sandal rumah yang tinggal satu gitu?”
Aku sempat berhenti bergerak, kemudian memutuskan pura-pura tak mendengar dan lanjut masuk mobil. Aku ingin segera angkat kaki dari sini, tetapi yang jelas tujuannya bukan pulang.
Jujur saja aku agak neyesal kenapa malah ke Smitten Tatto yang jelas-jelas pemilik-pemiliknya sangat kenal Jayden. Rasa khawatir kini mulai merasuki akal pikiranku dan membuatku bertanya-tanya bagaimana kalau mereka benar-benar menelepon Jayden?
Aku tak tahu jawabannya dan hanya mampu berharap semoga Jayden tidak mengangkat telepon mereka.
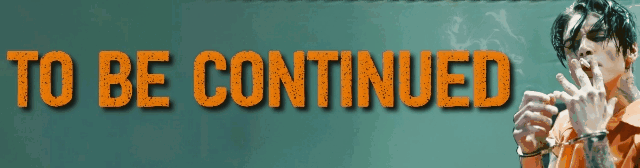
____________________________________________________
Thanks for reading this chapter
Thanks juga yang udah vote, komen, atau benerin typo-typo meresahkaeun
Kelen luar biasa
Bonus foto My twin

Jangan lupa follow sosmed saya lainnya ygy

Well, see you next chapter teman-temin
With Love
©® Chacha Nobili
👻👻👻
Senin, 15 Agustus 2022
Remake and repost: Senin, 18 September 2023
Repost: Rabu, 16 Oktober 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top