Chapter 11 [Jayden Wilder]
Selamat datang di chapter 11
Tinggalkan jejak dengan vote, komen atau benerin typo-typo meresahkaeun
Thanks
Happy reading everybody
Hopefully you will love this story like I do
❤️❤️❤️
____________________________________________________
“Seperti yang ia baca, aku jatuh cinta sebagaimana caramu tertidur: perlahan dan semuanya sekaligus”
—John Green
____________________________________________________

Musim panas
Oxford, 22 September
Pukul 09.15
Kemarin aku mengomeli anak buah-anak buahku gara-gara membiarkan calon wali kota terpilih memberiku hadiah yang dikirim ke penthouse. Aku menekankan pada mereka bahwa peran penting klan Davidde dalam memenangkan pemilihan umum haruslah dirahasiakan dari siapa pun. Tak terkecuali istriku. Aku tak ingin hadiah apa pun. Aku hanya ingin beliau mempromosikan semua bisnis propertiku agar ramai—melihat dari posisinya sekarang, beliau tentu memiliki cukup banyak relasi penting. Bayangkan saja bila seluruh propertiku dipromosikan. Aku pasti akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Tidak perlu pencucian uang untuk hal semacam ini. Oleh sebab itulah aku menerima permintaan ini. Karena aku telah memperhitungkan segalanya; terutama keuntungan bagiku.
Gara-gara hadiah jam tangan kemarin, Melody hampir mengetahuinya. Beruntungnya aku bisa membelokkan pikirannya dan ia tak lagi membahas-bahas soal itu. Dan, tentu saja aku mengembalikan jam tangan tersebut serta mewanti-wanti agar tidak memberikan hadiah berupa apa pun—kecuali seperti yang sudah kutekankan sebelumnya.
Kuanggap ini beres sehingga aku bisa melanjutkan membangun rencana balas dendam kepada Cavez setelah memberi kejutan kepada istriku di Smitten Tatto. Namun, rupanya aku malah dihadapkan oleh perkara lain yang jauh lebih penting.
Papa jatuh pingsan di depan kaskade sewaktu baru tiba di mansion. Sebagai seorang anak laki-laki yang baru merasakan kedekatan berupa kasih sayang Papa dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan, apa yang lebih buruk bagiku saat ini selain hal tersebut?
Pikiran tentang pekerjaan yang ruwet berganti menjadi kepanikan. Memacu kinerja otakku dalam mempercepat proses menghitungan mundur tujuh jam dari detik ini sesuai jam dinding dan mendapatkan hasil pukul satu dini hari di Jakarta.
Dari kesimpulan sederhana itu, isi dalam batok kepalaku lantas dijejali berbagai macam pertanyaan. Salah satunya yang paling mendominasi ialah hal apa kira-kira yang sangat mendesak sehingga membuat Papa pergi malam-malam dan baru pulang dini hari?
Maksudku, apabila Papa sudah tahu kondisi tubuhnya sedang kurang stabil, kenapa tidak berdiam diri dan istirahat di rumah saja? Sebegitu tidak bisa ditundanyakah urusan itu?
“Kagak tahu acara apaan yang didatengin Papa sampai pulang pagi buta gitu, Jay. Mana perginya sendirian. Udah gitu naik taksi online. Gue masih belum bisa nanya-nanya soalnya kondisi Papa masih belum stabil,” terang kakakku di seberang sambungan telepon tanpa kumintai penjelasan. Mungkin inilah yang disebut orang-orang sebagai koneksi saudara sedarah—meski kami terpisah berjuta-juta kilometer.
Menyadari hal itu, bulu kudukku tetiba meremang lantaran membayangkan bagaimana kalau Jameka bisa membaca pikiranku? Pasti mengerikan.
Aku lantas memejam sejenak untuk mengenyahkan pikiran tidak penting itu. Kemudian membalas, “Ya udah, gue sama Mel bakal ke sana secepetnya.”
Daripada benakku sibuk mereka-reka, lebih baik aku segera mengakhiri percakapanku dengan Jameka. Lalu aku beralih mewujudkan niat menelepon Nicolo untuk meminta bantuannya menyiapkan penerbangan tercepat dari waktu ini menuju Jakarta.
Gerakanku sedikit terhambat akibat Melody menarik-narik lengan kausku mirip anabul minta dimanja-manja. “Baby, ada apa?” tuntutnya bernada khawatir.
Sayang seribu sayang, dengan amat terpaksa aku mengangkat tangan, berisyarat memintanya sabar menungguku selesai menelepon Nicolo.
Sekadar informasi, aku selalu menggunakan identitas palsu bila bepergian ke negara mana pun dan lebih mengutamakan terbang menggunakan jet pribadi ketimbang pesawat komersil. Menurutku, jet pribadi jauh lebih aman. Beberapa anak buahku bisa ikut sekaligus dan jelas lebih bisa dipercaya daripada terjebak dalam ruang sempit beribu-ribu kilometer di atas permukaan tanah bersama ratusan orang asing yang tidak kutahu asal usul serta latar belakang mereka.
Memalsukan identitas juga merupakan serangkaian protokol wajib yang kulakukan agar tidak mudah dilacak atau kepergianku di negara bagian lain akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan ingin menjatuhkan bisnisku. Tak terkecuali ketika aku pergi bersama Melody.
Setelah mendaftar barang-barang penting yang harus kuambil di penthouse—dalam benakku—seperti paspor palsu, termasuk revolver beserta beberapa kalibernya, dan jadgkommando yang harus kubungkus kantong anti pendeteksi, aku baru menjelaskan telepon dari Jameka soal keadaan Papa pada Melody.
“Aku udah minta tolong temenku buat mesenin tiket kita ke Jakarta. Pesawat kita jam sepuluh,” lanjutku sedikit berteriak supaya Melody bisa mendengar suaraku di tengah suara-suara mesin kendaraan yang berseliweran di sekeliling kami, klakson-klakson yang ditekan penuh semangat oleh para pengemudi yang kulewati, dan desau angin musim gugur yang berisik.
“Astaga, semoga Papa baik-baik aja. Kamu juga hati-hati nyetirnya, Baby. Jangan ngebut-ngebut gini. Aku nggak pengin kita celaka. Orang-orang juga pada marah-marah, tuh,” teriaknya sambil berpegangan erat pada pinggangku.
“Jangan khawatir. Aku mantan pembalap MotoGP. Jadi, bisa sat-set dan tetep slay,” balasku asal tanpa mengendorkan kehati-hatianku dalam mengemudikan motor baru ini.
Hei! Mana bisa aku tidak ngebut di situasi genting seperti ini? Iya, kan? Seandainya alat teleportasi benar-benar nyata serta kumiliki, tentu aku tidak perlu repot-repot dan grasah-grusuh seperti sekarang.

Selama lebih dari 17 jam di waktu tanda peringatan kencangkan sabuk pengaman dimatikan, aku tak henti-hentinya mondar-mandir di pesawat mirip setrika. Melody pun senantiasa menenangkanku. Istriku itu juga memintaku agar memakan sesuatu, tetapi nafsu makanku seolah-olah terbang bersama jet pribadi ini.
Ia pun mengomel, “Kamu perlu makan, Baby. Kalau kamu nggak makan, aku takut kondisi kamu ikutan drop. Makan, ya? Aku suapin, mau?” bujuknya.
Jikalau tidak sedang bersama beberapa anak buahku dan aku diharuskan tetap menjaga wibawa sebagai pria sejati yang membangun karakter tidak lemah terhadap godaan dunia bernama wanita, terlebih seorang istri sah di mata hukum mau pun agama, pastilah aku dengan senang hati menyambut niat baik istriku. Jadi, aku terpaksa menolak, “Makasih, Baby. Tapi aku makan sendiri aja.”
Kendati hatiku tercubit melihat Melody mengangguk lemah serta tersenyum kaku, aku harus tetap pada kendali diriku. Dan meskipun aku hanya menelan makananku tanpa bisa merasakan bagaimana nikmatnya makanan itu, tetapi itu jauh lebih baik ketimbang melakukan aktivitas dengan perut kosong melompong.
Penerbangan ini terasa seperti selamanya dan nyaris membuat kesabaranku terkuras habis. Syukurlah, kami tiba di bandara Soekarno Hatta disambut langit berselimut kegelapan dan bertabur bintang. Bak kain sutra hitam pugasan berlian-berlian berkilauan.
Kami dijemput Tito Alvarez dan Lih Gashani serta mobil-mobil SUV hitam lain untuk beberapa anak buahku yang ikut—kupastikan Melody tidak menyadari kehadiran mereka. Dan kami langsung menuju rumah sakit sebab berpacu dengan waktu jam besuk yang mulai menipis. Kalaupun kami telat dan pihak rumah sakit tidak mengizinkanku menjenguk Papa, aku bersumpah akan membuat perhitungan pada mereka.
Selama perjalanan, Tito memberi informasi letak ruang rawat inap Papa agar nanti tidak kesulitan dan tidak melahap banyak waktu untuk mencarinya. Selain itu, ia juga menyarankan, “Kalau soal kondisi Om Alle, biar Yang Mulia Ratu Jameka aja yang jelasin. Atau besok pagi, lo bisa konsultasi sama dokter yang nanganin Om Alle. Terus, minta pendapat Mel yang pasti ngerti hal-hal kayak gitu.”
Aku bergumam sebagai jawaban. Lalu menggenggam tangan Melody yang tertangkap basah sedang menutupi mulutnya yang menguap.
“Udah ngantuk?” bisikku sambil mengusap puncak kepala Melody yang disandarkan di pundakku. Aku menyugar rambut hitam panjangnya untuk membawanya ke belakang telinga. Sehingga, terpampanglah wajah manisnya dalam keremangan lampu-lampu jalan raya. Wajah itu seolah-olah memintaku untuk menciumnya. Aku pun tak kuasa melawan dorongan tersebut. Setelah membubuhkan bibir di kening Melody, aku kembali bertanya, “Mau aku anterin pulang ke apartemen dulu? Atau ke rumah Daddy?”
Istriku mendongak untuk membalas tatapanku. Dengan mata sayu, ia menjawab, “Enggak usah, Baby. Aku masih bisa nahan, kok. Aku mau sama kamu. Aku juga khawatir sama Papa.”
Sekali lagi sambil menyugar-nyugar rambutnya, kububuhkan bibir serta hidung di puncak kepala Melody. Tidak lupa menghidu harum shamponya, aku kembali melayangkan sebuah pertanyaan. “Yakin masih bisa nahan ngantuk?”
“Yakin kuadrat,” jawab Melody yang lantas memelukku. Ia tersenyum tulus sehingga membuat matanya terlihat seperti garis tebal dengan bulu mata panjang.
“Mau mampir beli kopi dulu?” tawarku, masih berusaha. Meski berharap ia tidak menggubris perkataanku sebab kami diburu waktu.
Melody menggerak-gerakkan tangan dengan lemas. Doaku pun terkabul dengan ia yang menjawab, “Nggak usah, aku beneran bisa tahan, kok. Bentar lagi sampai, kan?”
“Kalau kamu ngantuk banget, tidur dulu aja, nggak apa-apa.”
Tito yang duduk di jok depan berdeham beberapa kali sambil menggerutu dan Lih yang duduk di sebelah kadal buntung itu bergumam tidak jelas. Sepertinya mereka bermetamorfosis menjadi cacing kepanasan gara-gara baru saja menelan pameran kemesraanku bersama Melody lalu tersedak perasaan iri dan dengki.
Teruntuk perihal ini, hanya di depan sahabat-sahabat sejatiku seperti mereka-lah aku tidak akan sungkan-sungkan mengumbar kemesraan. Mereka mengenalku sejak kami masih remaja sampai sekarang. Hafal semua seluk-belukku sehingga aku tidak perlu mengambil sikap kaku layaknya pemimpin organisasi hitam.
“Sumpah! Kuping sama mata gue sakit gara-gara lihat di spion dan denger kemesraan kalian!” cerca Tito di antara suara musik R and B yang diputarnya pelan untuk menemani perjalanan kami.
Aku lantas beralih ke kadal buntung satu ini. “Diem lo. Fokus nyetir aja sana,” ancamku menggunakan nada rendah.
Namun, bagi Tito tidaklah cukup hanya dengan diancam menggunakan nada berat. Terbukti dengan gaya kurang ajarnya yang khas, ia kembali mengejek, “Halah, kemaren-kemaren aja bilangnya: gimana kalau Mel nggak mau sama gue, To? Gimana kalau Mel benci sama gue? Gue mesti gimana biar Mel mau balik sama gue lagi dan nggak jadi kawin sama si onoh?” Tito menirukan suaraku, tetapi dengan mulut monyong-monyong yang ingin kukucir menggunakan karet dobel. “Gue bilang, bodoh amat,” lanjutnya sengak.
Melody tertawa kecil. “Masa Jayden kayak gitu, To?”
“Ho’oh!” jawab Tito tanpa jeda dan tanpa ragu.
Aku menghadiahinya dengan tendangan-tendangan di belakang jok yang didudukinya sambil ngedumel, “Gue kebiri baru tahu rasa lo! Kapan gue ngomong kayak gitu? Ngarang lo!”
“Jangan pura-pura amnesia, Bos. Entar jadinya kayak sinetron-sinetron yang ditonton Mbak Mar!”
“Oh, jadi sekarang lo nargetin Mbak Mar jadi korban kekadalan lo berikutnya? Yang kemarin emang nggak jadi?” todongku yang makin rajin menendang-nendang jok sampai kadal buntung satu ini beringsut maju. Dadanya kini hampir berhimpitan dengan stir.
Lih menyahut, “Bukan Mbak Mar ART-nya Om Alle, Bos .... Tapi—”
“Diem lo, Bujang!” gertak Tito yang secara otomatis membungkam mulut Lih. Pria pendiam itu pun merespons Tito dengan cengar-cengir.
Aku memang jadi penasaran, tetapi tidak sepenasaran itu sampai-sampai membuatku ingin mengetahui detik ini juga siapa wanita yang digadang-gadang membuat kadal buntung ini jatuh cinta sampai tobat. Apakah benar si resepsionis Heratl?
Hoek!
Sisi positifnya, berkat candaan itu, kepanikan yang sempat melanda diriku dan rasa kantuk yang menjangkit Melody bisa sedikit berkurang.
Aku lantas meminta Tito lewat jalan pintas sehingga tidak sampai seperempat jam kemudian kami tiba di rumah sakit di penghujung jam besuk. Lalu kami buru-buru menggerakkan kedua kaki menuju ruang rawat inap VVIP Papa. Anak buahku yang lebih dulu sampai pun sudah terlihat menyebar di beberapa titik.
Aku membuka pintu ruang rawat inap dan Jameka menyambut kami dengan wajah lelah, tanpa penampilan cetar membahana seperti normalnya Jameka. Ia hanya mengenakan celana olahraga panjang hitam, sandal jepit, dan jumper abu-abu gombrong yang sepertinya pernah kulihat, tetapi tak sempat memikirkan siapakah pemiliknya; mungkin milik pacarnya yang menyusulnya ke Samarinda.
Melihatku, Melody, Tito, serta Lih melesak ke ruangan, Jameka yang berambut acak-acakan sontak menghambur ke pelukanku dan Melody. Tito merentang tangan dengan senyum lebar tanda minta dipeluk juga, tetapi kutampel mukanya itu sampai ia mundur-mundur. Sedangkan Lih menahan tawa karena melihat tingkahku. Walau sebenarnya aku heran kadal satu itu berani bercanda semacam ini dengan Jameka.
“Kalian mending keluar aja biar oksigen di sini kagak habis,” titahku pada Tito dan Lih yang kemudian mereka laksanakan dengan ogah-ogahan.
“Papa baru aja tidur,” bisik Jameka sembari menyelimuti tubuh Papa sesudah menjelaskan kondisi beliau berdasarkan keterangan dari dokter yang merawat Papa. Tadi, Melody juga sempat mengecek keadaan Papa, tetapi belum berkomentar.
“Mending lo pulang, deh. Gantian gue yang jaga Papa,” perintahku pada Jameka sambil memandangi Papa yang pucat, dengan selang infus menancap di tangan kanan beliau.
“Mel gimana?” tanya Jameka. Kami pun serempak menoleh ke sofa berlengan di sebelah pintu masuk. Dan Jameka kembali bersuara. “Bini lo ketiduran, tuh.”
Aku memperhatikan istriku lagi. Melody menyandarkan kepalanya di bahu tempat duduk itu. Wajahnya yang imut terhalangi rambutnya yang menjutai.
Hm ... dasar istriku sayang! Katanya tadi sudah tidak mengantuk. Giliran kutinggal mengobrol sebentar dengan Jameka, eh, langsung pergi ke pulau kapuk.
Betapa imutnya ....
“Kalau gitu, gue anterin Mel pulang ke Daddy dulu. Entar balik sini lagi.”
Jameka jelas tidak setuju. “Udah, lo pulang ke apartemen aja. Nggak usah ke rumah mertua lo. Malem-malem gini, takutnya ganggu. Biar gue yang jaga Papa. Kalian baru dateng, pasti capek dan jet lag. Besok pagi-pagi, baru ke sini lagi.”
“Tapi gue khawatir sama Papa, Jame,” bisikku, tetapi menekan setiap kata yang kuucapkan.
Kakakku berdecak sambil memejam. Ia juga mendesis, “Sumpah! Kalau kagak dalam keadaan kayak gini, udah gue geplak kepala lo, Bambang! Kebiasaan banget, sih. Manggil-manggil gue tanpa embel-embel Kak. Giliran nyangkut-nyangkut Mel aja baru manggil gue Kak Jameka!”
Aku kaget sampai melongo. “Serius lo masalahin hal sepele itu sekarang? Lagian, lo juga sering manggil gue Bambang ketimbang nama asli gue. Tuh, barusan juga,” bantahku yang tak mau kalah.
“Udahlah, pulang berdua sono!” Jameka mendorong-dorong lenganku sambil mengusirku mirip menggusah ayam. “Hus ... hus ....”
Dikarenakan tidak ingin terjadi keributan ektra perkara hal super duper tidak penting, aku akhirnya terpaksa menuruti kakak perempuanku yang kamvretoz itu.
“Oke, gue pulang ke apartemen aja.” Selain itu, aku juga berpesan, “Kalau ada apa-apa, langsung hubungi gue.”
“Beres. Nih, bawa aja mobil gue.”
Setelah menerima kunci mobilnya Jameka, aku menghampiri Melody dan berjongkok di depan sofa. Secara perlahan, kusingkirkan helaian-helaian rambut Melody yang menutupi sebagian wajahnya menggunakan ujung telunjuk dan jari tengahku. Dampaknya, ia bergumam, “Jayden ....”
“Ya. This is me. Let’s go home, Baby,” bisikku yang sebenarnya dalam keadaan takjub karena mendapati Melody masih ngiler seperti biasanya. Aku pun terpaksa menggendongnya menuju mobil dan pulang.
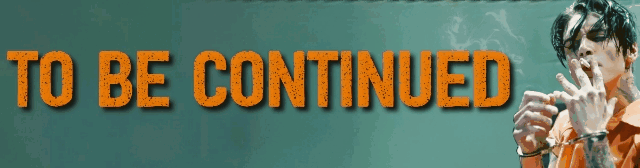
____________________________________________________
Thanks for reading this chapter
Thanks juga yang udah vote komen atau benerin typo-typo meresahkaeun
Kelen luar biasa
Bonus foto Jayden akoh

Follow may sosial media ygy

Well, see you next chapter teman-temin
With Love
©®Chacha Nobili
👻👻👻
Jumat, 5 Agustus 2022
Remake and repost: 11 September 2023
Repost: Sabtu, 12 Oktober 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top