MKSUK 2
gaes asli dah aku mo minta maap dlu sama orang Malang.
Aku coba ambil setting Malang karena selama ini cuma sekitaran Jakarta sama Depok aja. Huahahha.
Kalo ada yang salah, feel free to correct me yaa.
Chapter ini tuh hasil tanya2 ke beberapa teman sesama penulis yang tinggal di Malang sama liat GMaps. Ahahhaha
Aku mau sekalian kasih tau. Lily pending PO dulu. Aku masih belum selesai revisi naskah. Sudah lihat belum cover nya?

IItu cover nya.
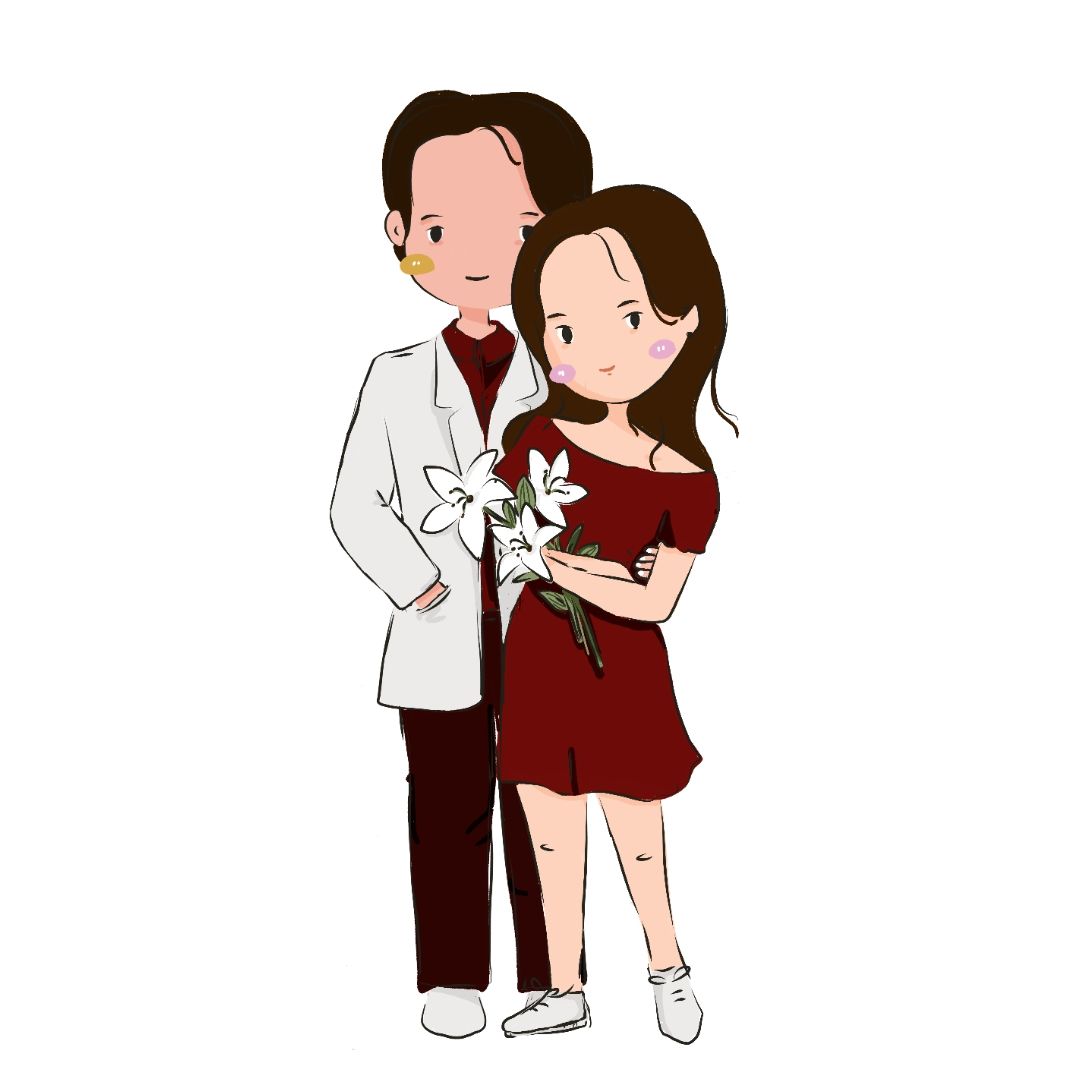
Ini yang bakal menyambut kalian di setiap pembukaan babnya.
Tunggu yaaa!!!
Enjoy!!!
Tanpa sadar, air mata turun membasahi pipinya saat Naina menonton file video yang baru saja dikirimkan Bu Meysa ke nomornya. Itu video saat putrinya—Aluna maju ke depan kelas untuk membacakan karangan buatannya. Ada rasa bangga sekaligus sedih yang bercampur menjadi satu di hati ibu satu anak itu. Ia bangga karena anaknya berani maju ke depan kelas dan membacakan karangan dengan begitu lancarnya di hadapan teman-teman sekelas. Namun, sedih tak juga mau kalah menyelinap di relung hati. Derai air mata yang luruh di pipi puteri semata wayangnya membuatnya semakin bersalah dengan apa yang terjaddi di masa lalu—delapan tahun yang lalu. Kalau saja kenangan itu tak pernah terjadi, mungkin putrinya merasakan hal sama yang dirasakan teman-temannya, mempunyai sosok seorang ayah di hidupnya.
Isakkannya seketika patah saat satu tepukan mendarat di punggung rapuhnya. Wanita paruh baya yang selama ini membersamai langkahnya sudah duduk di hadapannya. Tatapannya begitu sendu. Anehnya, tatapan itu justru membuat tangis Naina kembali menderu.
"Kenapa, Nai?" tanya Amalia. Naina tak segera menjawab. Wanita itu menyodorkan ponselnya ke tangan Amalia. "Video apa ini?"
"Wali kelas Luna kirim video itu, Ma," sahut Naina seraya berusaha untuk menghentikan laju air mata yang tampak enggan berhenti mengalir. Dua lembar tisu itu sudah benar-benar basah. "Nggak tau kenapa, hatiku sakit banget lihat anakku nangis kayak begitu. Luna nggak tau apa-apa, Ma."
Tangan Amalia yang keriput dari tahun ke tahun mendarat di wajah Naina. Wanita paruh baya itu menatap wanita yang selalu berusaha tegar di hadapannya dengan nanar. Naina begitu hebat karena bisa bertahan dengan sangat baik sampai detik ini membesarkan anaknya tanpa sosok seorang suami yang mendampingi.
Didekapnya Naina yang masih larut akan kesedihan. Kasih sayang seorang ibu pada putrinya seketika mengalir otomatis melaui pelukan yang tercipta. Berusaha memberikan ketenangan, hanya itu yang ia bisa.
"Temui dia, Nai." Ucapan Amalia sontak membuat Naina menggeleng dan mengurai pelukan. Wanita itu menggeleng di hadapan Amalia. "Kenapa? Dia masih suami kamu."
"Ma ... ini nggak segampang itu. Aku pernah kabari dia waktu Luna baru lahir. Tapi ... setelah itu semua akses ditutup. Mas Bhumi sama sekali nggak bisa tersentuh."
"Itu dulu, Nai. Sudah delapan tahun yang lalu." Naina tetap saja menggeleng. Tak ada yang membedakan delapan tahun yang lalu dan saat ini. Harusnya Amalia juga tahu bagaimana sifat suami Naina yang tak pernah bisa menerima yang namanya sebuah pengkhianatan.
Hanya gelengan yang diberikan Naina sebagai respons atas saran yang diberikan Amalia. Wanita itu kembali terdiam. Tatapan kedua matanya tertuju pada layar ponsel yang menampilkan video Aluna.
Musim hujan membuat udara kota Malang semakin mendingin. Naina mengambil sebuah payung dari guci besar yang memang sengaja dijadikan tempat penyimpanan payung selama ini. Hujan turun semakin lebat mengguyur bumi. Kedua kakinya memimpin jalan menuju tempat di mana putrinya bersekolah.
Tak hanya dirinya. Ada banyak orang tua murid yang juga datang menjemput anak-anak mereka. Naina menunggu di teras ruang piket sekolah. Matanya melirik ke arah jam dinding yang terpasang di sana. Masih 15 menit lagi.
Bel tanda pulang sekolah mengalun kencang. Satu per satu anak mulai terlihat memenuhi ruang piket. Naina mencari-cari di mana keberadaan putrinya.
Itu dia!
"Halo, Sayang." Kehadirannya yang tiba-tiba jelas saja sukses membuat Aluna terkejut. Putrinya tersenyum bahagia.
"Bunda jemput aku?" tanya Aluna polos. Bocah itu sudah mengenakan jas hujan dan siap dengan payung yang dibawanya. "Aku kan bisa pulang bareng teman-teman."
"Nggak apa-apa. Kita kan masih bisa pulang bareng sama teman-teman Luna."
***
Naina menatap pilu foto keluarga yang tergantung di dinding rumah. Keempat orang yang berpose di sana tertawa dengan begitu bahagianya. Naina dan adiknya Kiara berdiri di belakang kedua orang tua mereka. Sepuluh tahun yang lalu. Andai waktu bisa diputar kembali, ia rela menyerahkan semua yang dimiliki. Asalkan kebahagiaan itu bisa kembali dirasakannya.
Beberapa bulan setelah foto itu dibuat, Naina resmi menjadi yatim piatu. Sebelumnya, mereka berencana untuk membuat foto lainnya Orang tua dan adiknya—Kiara meregang nyawa di sebuah kecelakaan naas hari itu—hari di mana seharusnya mereka sekeluarga datang menghadiri acara wisuda kelulusan Naina. Ia selamat karena tak ikut berada di mobil malang yang dikemudikan ayahnya. Seluruh dunianya benar-benar runtuh. Tak ada lagi keluarga yang bisa dijadikannya tempat untuk pulang saat rindu begitu menggebu.
Baru lima tahun ia kembali ke rumah ini setelah beberapa tahun lamanya berpetualang di kota lain demi bisa menenangkan diri. Naina sadar laki-laki itu tak akan bersusah payah mencari keberadaannya. Itu pasti. Namun, yang ada di kepalanya saat itu hanyalah pergi sejauh yang ia bisa.
"Bunda nggak jadi antar pesanan kuenya?" tanya Aluna.
Kepergian kedua orang tuanya memang tak serta merta tanpa meninggalkan sesuatu. Namun, Naina tak ingin terlena dengan semuanya. Wanita itu tetap berusaha agar bisa menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sejak kembali lagi ke rumah ini, Naina mencoba memberanikan diri untuk membuka usaha pemesanan kue. Respons yang didapatnya di awal amatlah bagus. Ia membuang jauh angan-angan menjadi wanita karier dan banting stir menjadi pedagang kue. Pelanggannya banyak. Yang awalnya hanya sekitaran kompleks perumahan, sekarang merambah ke mana-mana. Bersama dengan Amalia dan bantuan dua asisten rumah tangganya, Naina tak pernah kesulitan memenuhi pesanan yang membanjir.
"Jadi, Sayang. Tapi, Luna nggak usah ikut, ya. Sudah mendung banget." Raut wajah sang putri seketika berubah kecewa. Biasanya, gadis kecil itu akan selalu bersemangat tiap kali bundanya mengantarkan pesanan kue. "Bunda nggak mau Luna kehujanan."
"Kan ada jas hujan, Bunda."
Mengendarai sepeda motor matic, Naina membelah jalanan menuju Alun-alun Malang. Di sepanjang jalan, sepasang ibu dan anak itu asyik bernyanyi, tak menghiraukan orang-orang yang mungkin saja menatap keduanya aneh. Begitulah cara mereka menikmati waktu-waktu bersama. Naina tak ingin melewati saat-saat betapa putrinya begitu manja padanya. Waktu berputar begitu cepat. Rasanya baru kemarin Aluna kecil menangis begitu nyaring memenuhi ruang bersalin saat dilahirkan.
"Sepurane lho Nai nggak bisa ke rumah." Mbak Dita sudah menjadi pelanggan kuenya sejak lama. Biasanya, ia yang akan datang ke rumah untuk mengambil kue pesanannya. Namun, tidak hari ini. Sepertinya ada keperluan mendesak yang memaksa dirinya meminta Naina mengantarkan pesanan ke rumahnya.
"Halah, nggak apa-apa. Sekalian aku sama Luna jalan-jalan sore. Kok tumben pesan kuenya banyak banget. Mau ada acara, tah?"
"Koncone bojo mau main. Suamiku kan kuliahnya dulu di Jakarta, nah kebetulan ada beberapa temannya mampir setelah seminar. Mau sekalian reuni, katanya. Aku seharian masak, makanya nggak bisa ambil pesanan ke rumahmu. Nah, bojoku njaluk bolu kukus karena temannya doyan banget sama bolu kukus yang hijau."
Naina refleks menggeleng pelan. Pikirannya terlalu sempit kalau sampai mengira orang yang dimaksud Mbak Dita itu adalah ayah dari anaknya. Dunia ini luas. Ada banyak orang yang senang memakan bolu kukus hijau. Bukan cuma Bhumi seorang.
"Ya sudah, Mbak. Aku tak pulang. Sudah mendung."
"Lho, ora mampir sek?" Mbak Dita menawarkan. Naina menggeleng. "Yo wes tunggu sebentar. Aku masak rawon sama perkedel. Nganti lali wes tak pranteni."
"Nggak usah repot, Mbak."
"Untuk Luna. Bukan untuk kamu." Mbak Dita berlalu masuk ke dalam rumah sambil tertawa. Tak lama, ia pun kembali dengan bungkusan plastik yang disodorkan pada Naina. "Ini untuk Luna, lho."
"Iyo. Ben mbok'e maem karo sambel korek wae. Luna, bilang apa sama Budhe?"
"Terima kasih ya, Budhe," ucap Aluna sopan.
Naina kembali melajukan motornya. Sebelum pulang, ia memenuhi keinginan sang putri untuk membeli es krim favoritnya di sebuah restoran legendaris yang menurut penuturan orang-orang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1930. Sembari menunggu Aluna selesai menikmati es krimnya, Naina memesan sebungkus gado-gado pedas yang akan disantapnya bersama dengan kuah rawon buatan Mbak Dita di rumah nanti.
"Kita pulang, ya. Keburu hujan."
Naina menggandeng putrinya dan berjalan keluar dari restoran. Keduanya menghampiri sepeda motor yang terpakai. Wanita itu membantu Aluna memakai helm di kepalanya. Motor siap untuk melaju pulang. Tepat di jalan besar depan restoran—saat keduanya sudah di atas motor, sebuah mobil melaju pelan. Jendela mobilnya terbuka. Naina bisa melihat dua orang yang ada di dalamnya. Dua sosok itu terlihat begitu familiar. Bahkan, sangat familiar.
"Mas Bhumi," gumamnya pelan. "Benar kamu, Mas?"
Naina terdiam. Mobil itu semakin menjauh. Laki-laki itu masih terlihat sama, selalu tampan. Senyuman itu juga masih begitu menawan.
"Bunda kenapa?" sahut Aluna dari jok belakang. "Kok nggak jalan motornya? Ayo, keburu hujan. Aku sudah kena tetesan air."
"Iya, Sayang. Kita pulang."
-to be continued-
1342 words
Gimana gimana gimana?
Sudah chapter 2 nih.
Sudah bisa nebak bakalan gimana?
Ada apa sih sebenernya sama mereka?
Huahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top