08 | a forgotten friend
Meski baru sekadar berjabat tangan dan belum terjalin kisah persahabatan picisan, tubuhku bereaksi aneh. Tidak, bukan reaksi girang atau semacamnya. Tak akan ada yang senang mendengar penjabaranku: Seperti dikejar gerombolan bayangan hitam yang menarik organ-organ dalamku keluar, lalu aku menjerit tak karuan seolah terjun bebas dari langit ketujuh. Atau ada jarum yang menusuk-nusuk otakku di berbagai sisi; sebongkah tangan meremas jantungku; paru-paru yang mendadak terasa kecil dan sempit; serta darah mengalir dari mata, mulut, lubang hidung dan telinga─membasahi rumput yang kupijaki hingga sepenuhnya merah.
Aku berguling-guling menahan euforia pedih di rumput merah sampai kehabisan darah, sekarat, kemudian mati mengenaskan dalam kubangan darah sendiri dan organ dalamnya berceceran. Polisi memberi garis kuning. Reporter datang untuk memotret dan mengusung berita, tapi bangkaiku dibiarkan di sana; membusuk dan kedinginan, sendirian dan menyedihkan.
Kentara sekali jika ini sebuah kesalahan. Serangan kecemasanku menjadi berkali-kali lipat akibat tindakan sendiri. Tidak seharusnya aku memperburuk keadaan yang jelas-jelas tak akan pernah berubah. Jauhi keramaian. Jauhi orang-orang. Aku dikutuk untuk tumbuh menjadi pemuda malang yang memeluk sepi. Kutukan ini akan menggerogotiku selamanya, atau sampai aku memutuskan kematianku lebih cepat.
Aku ini cuma pembawa sial di antara kedua belah pihak. Jika ada yang berteman denganku, mereka akan tertimpa hal buruk dan akulah penyebabnya.
Ada masa-masa di mana aku memang pernah punya teman meski hanya seorang, bahkan setelah rumor tentang Ayah beredaran tak jelas. Suatu hari sepulang sekolah, aku tengah menangis dalam ruang kelas yang sepi. Aku duduk di lantai belakang, menyandarkan punggung ke dinding, dan memeluk lututku erat. Cahaya matahari sore menyusup lewat jendela. Kak Jisung tidak menjemputku, tadi pagi dia sudah mengatakannya dan berpesan supaya aku pulangnya hati-hati. Di rumah aku merasa tak memiliki kebebasan untuk menangis─sungguh, waktu itu Ayah pasti terluka─jadi kulakukan di sini.
Bayangan Ong Seungwoo yang tadi siang meneriakiku di depan kelas terasa begitu nyata: Tidak ada yang mau berteman denganmu soalnya ayahmu penjahat! Dan wajah-wajah anak kelas dua lainnya yang memandangku hina disusul tawa. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nanti kau akan tumbuh seperti dirinya dan menyakiti kami, makanya kami memberi pelajaran padamu duluan!
Mereka pikir itu lucu. Bagiku, seperti ada retakan besar tepat di dada. Kenapa mereka bisa begitu jahat? Padahal kami masih sama-sama manusia. Padahal awal kelas dua kami masih bermain bersama. Mereka bahkan tidak tahu kebenaran mengenai Ayah. Rasanya sakit sekali. Namun tetap saja, sepulangnya nanti aku harus bersikap biasa.
Aku terlalu larut dalam kesedihan sampai tak menyadari kehadiran orang lain. Sebuah suara menyelinap ke telingaku─lembut sekaligus khawatir, "Kau kenapa sendirian di sini? Sedang menangis?"
Sedikit terperangah, aku berlagak defensif; bergerak menjauh, hapus air mata, kerutkan kening, dan menatap lawan bicara secara tajam. Sebentar lagi, sosok itu pasti menertawakanku seperti yang lainnya. Tapi tidak, dia malah memberiku tatapan lunak. Dia bukan musuh.
Dia seumuranku, tapi dari kelas yang berbeda (aku belum pernah lihat eksistensinya selama pembelajaran di kelas). Dia khawatir pada orang yang menangis sendirian di kelas karena memang seharusnya khawatir. Dia tidak memandangku hina, jadi kurasa dia tidak tahu rumor tentangku.
"Sebaiknya jangan pedulikan aku," balasku, masih defensif, "dan ke depannya juga aku bakalan baik-baik saja. Nanti kau bisa terluka." Kuharap dia mengerti kode tersiratku. Lalu aku melewatinya, berdiri di ujung pintu, menunggu, dan hampir menumpahkan air mata lagi. Ini bukan yang kumau. Aku pembohong payah.
Namun hari itu, Tuhan sedang berbaik hati.
Sosok tadi mengerti kodeku. "Kalau kau butuh teman, aku bisa menjadi temanmu. Kelasku ada di sebelah, kita bisa bertemu setiap hari," katanya. Dia menarik lenganku dan kami pulang bareng. Kami berkenalan. Kami saling cerita. Aku jujur alasanku menangis. Dia menghiburku. Dia mentraktir es krim. Aku berterima kasih. Kami menikmati es kirimnya. Kami berpisah di persimpangan.
Besoknya, kami meneruskan pertemanan ini. Kadang-kadang dia ke kelasku, kadang-kadang aku yang ke kelasnya. Makan siang, ke perpustakaan, bermain di taman sekolah, bermain sepak bola dan video games-nya, pulang, semuanya kami lakukan bareng. Tak peduli kata orang, dia selalu berada di sampingku, mendukungku, menyelamatkanku. Tak peduli jika pada akhirnya ikut dikucilkan, dia tetap ingin berteman denganku.
"Teman selalu ada dalam suka dan duka," katanya sewaktu main ke rumahku. Dia orang pertama yang kuajak ke rumah. Waktu itu watak Ayah sudah mulai berubah. Aku cerita betapa takutnya diriku menghadapinya. Dia menyemangatiku dan bilang ingin ke rumah supaya mengajariku caranya melawan. Tentu saja aku langsung takut dan bersikeras melarang, tapi dia juga memaksa. Untungnya dia cuma bertemu Kak Jisung.
Ia menambahkan, "Teman juga saling membutuhkan, tak ada salah satu pihak yang dirugikan. Jika tidak begitu, bukan teman namanya."
"Tapi kau dirugikan karena dijauhi juga," balasku lesu. "Kita bukan teman?"
Dia tertawa dan menepuk-nepuk pipinya. "Sebelumnya temanku sedikit dan payah. Mereka payah karena mau-mau saja dibohongi gosip dan ajakan sesat. Membuang mereka demi dirimu yang memiliki banyak kemiripan tak ada salahnya, bukan? Aku berhak memilih dengan siapa ingin berteman."
Aku mengaguminya yang pintar sekali berbicara, tak gentar, dan punya prinsip kuat. Hubungan kami semakin dekat. Sewaktu anak-anak lain mencemooh, dialah yang akan membelaku. Kadang-kadang kami main bertiga bersama Kak Jisung, tapi setelah dia masuk SMP menjadi sangat jarang.
Pada libur musim panas kelas lima, aku diajak liburan oleh keluarganya. Kak Jisung juga diajak meski awalnya menolak. Dengan begitu kami bisa mengelabui Ayah yang bilangnya acara inap di sekolah. Aku pun merasa tidak enak, tapi dia tampak girang sekali mengajakku. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Dia bersikeras. Lagi pula, ini juga liburan pertamaku setelah sekian lama.
Sayangnya setelah liburan tersebut, pertemanan kami kandas.
Aku tidak ingat namanya, pun wajahnya. Ingatan tentang itu samar-samar dan gelap. Hanya sampai sana yang mampu kuingat. Jika memaksakan diri kepalaku bakalan mendadak sakit, jantung seolah meledak, keringat mengalir deras, atau timbul perasaan tak aman dan dikejar-kejar sesuatu. Meski potongan ingatannya tak lengkap, aku tahu lebih baik tak menguak kebenarannya daripada gila sendiri.
Yang kuingat, dia temanku selama tiga tahun.
Yang kuingat, terjadi kecelakaan pada saat libur musim panas kelas lima.
Yang kuingat, aku terbangun di rumah sakit ditemani Kak Jisung yang menangis dan menggenggam tanganku erat. Segalanya terasa kosong. Aku kebingungan.
Tanpa kusadari, sejak saat itu aku berubah menjadi pemurung sekaligus memiliki ketakutan akan sesuatu. Kondisiku memburuk─yang bahkan aku tidak tahu kenapa. Dia tak pernah muncul lagi di hadapanku, seolah kami tidak pernah berteman sebelumnya. Aku bisa saja bertanya pada Kak Jisung atau Ong Seungwoo (hell, tentu tidak), siapakah dia itu? Apa yang terjadi saat libur musim panas kelas lima? Rasanya Kak Jisung atau dokter sering menjelaskan berulang-ulang, tapi kurasa alam bawah sadarku menolak untuk menerima. Jadi Kak Jisung memutuskan untuk tak mengungkitnya lagi di depanku.
Kami berdua dimarahi dan dipukuli Ayah. Kami telah membohonginya, tentu saja dia marah. Aku drop, memaki diri karena merasa tak berguna. Anak-anak kelas lima lain mengetahui kabar kecelakaanku dari guru. Bukannya bersimpati, mereka malah semakin mengolok-ngolok. Kasihan, kasihan, kasihan, lantang mereka. Kasihan kesepian lagi.
Yang kuingat, dia meninggalkanku di saat aku terpuruk.
Lalu aku berjuang menghadapi neraka di sekolah sendirian. []
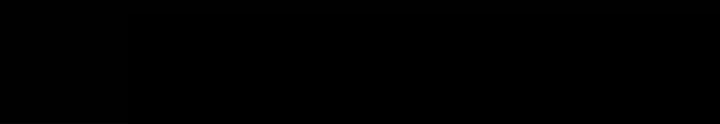
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top