Arata: Keping yang Tak Pernah Terungkap - Bonus Chapter
Arata menatap sepucuk surat di tangan. Teruntuk: Akikawa Ayumi. Tertulis jelas di sudut kanan atas amplop. Pemuda itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak bertahan lama. Digantikan ekspresi tak terdefinisi saat meletakkan surat tersebut di pangkuan. Sudut matanya beralih ke surat lain. Tergeletak di dekat bantal. Surat lain yang ia tulis untuk penerima yang berbeda. Akikawa Aisha.
Setelah sekian lama, Arata akhirnya menulis balasan untuk wanita itu. Wanita yang bukan lain adalah ibu Ayumi.
Sela bibirnya mengembuskan napas panjang, berusaha untuk memaklumi. Wajar jika Aisha bersikap seperti itu, pikirnya. Mungkin begitulah cara Aisha melindungi Ayumi. Cara seorang ibu yang menginginkan agar putrinya bahagia. Arata, sebagai laki-laki asing di keluarga Akikawa—begitulah Aisha menyebutnya dalam surat—memutuskan untuk mengerti. Mengenai alasan Aisha. Juga, memahami siapa dirinya.
Aisha benar. Sudah saatnya berpikir realistis. Dia dan Ayumi sudah bukan remaja tanggung lagi. Ada tanggung jawab, juga masa depan yang harus ditata.
Arata menghela napas. Disisirnya keadaan sekitar. Ia akan merindukan tempat ini. Pasti. Terlalu banyak hal yang tak bisa dilupakan. Pemuda itu tersenyum, menyemangati diri. Ayolah, Arata! Ditepuknya kedua belah paha satu kali sebelum berdiri dan menyelipkan dua buah surat siap kirim di tangan ke saku kemeja.
Terdengar ketukan dari luar, tepat saat Arata akan membuka pintu apato. Ketukan kedua. Ketiga. Keempat. Tidak sabaran. Arata mengurungkan niat. Demi keamanan, lebih baik memastikan terlebih dahulu siapa orang di luar sana.
Baru Arata ingin bertanya, satu suara yang familier mendahului. Ini aku. Begitu katanya. Hal yang membuat Arata mengernyit. Jelas sekali bukan itu yang ia perlukan. “Aku, siapa?”
Terdengar decakan pelan sebelum yang ditanya menjawab, “Fujiwara Fumio. Apa kau akan tetap bertanya sepanjang hari?”
Arata ber-oh pelan, buru-buru membukakan pintu. Bisa dilihatnya Fumio bersedekap. Raut wajah sahabatnya itu tampak kaku. Tanpa sengaja Arata berkedip, membuat wajah di depannya kembali menjadi sosok asing. Seakan-akan ini pertama kalinya mereka bertemu. Hal yang membuat Arata menggeleng frustrasi.
“Jangan memaksakan diri. Ini benar-benar aku. Pukul saja jika kau tidak percaya.”
Arata kembali menggeleng. Kali ini seulas senyum ia suguhkan. “Maafkan aku.” Pemuda itu membukakan pintu apato lebih lebar seraya memberi isyarat dagu pada lawan bicaranya sekarang ini. “Masuklah. Aku harus keluar sebentar. Ingin menitip sesuatu?”
“Kantor pos?”
Arata menaikkan alis. “Kau minta dibawakan kantor pos? Wah, Kak! Berat sekali titipanmu.” Pemuda itu terkekeh saat mendapati Fumio memberinya tatapan paling datar sedunia. “Hanya bercanda. Ya, untuk mengantarkan surat. Kenapa? Kau mau ikut?”
“Oke.” Singkat, jelas, dan padat. Seperti yang bisa diharapkan dari seorang Fujiwara Fumio.
Arata mengangguk, mengunci pintu apato dengan cepat, lantas menggamit lengan Fumio. “Ayo!” ajak Arata, dengan Fumio berjalan di sisinya. “Harusnya kau menghubungiku jika ingin datang,” kata Arata, membuka percakapan saat dirinya dan Fumio mulai menuruni anak tangga.
“Jadi, kau tidak menginginkan kedatanganku?” Fumio menyahut tanpa perlu repot-repot menoleh.
“Kau terlalu sensitif!” Arata meninju lengan Fumio, gemas. “Jika kau menghubungi terlebih dahulu, setidaknya aku bisa menyiapkan kudapan.”
“Seakan-akan aku orang asing yang bertamu.” Fumio memutar bola mata jemu. “Aku sudah mengirimkan pesan pendek. Menelepon. Semua tidak bersambut,” katanya lagi. Kali ini diiringi helaan napas pendek.
“Oh.” Arata tampak berpikir beberapa detik sebelum mengangguk-angguk. “Mungkin ponselku kehabisan daya. Maaf untuk itu. Aku benar-benar sibuk berbenah dan mengepak barang beberapa hari ini.”
“Kapan kau berangkat?”
Hening. Tidak ada jawaban. Senyum Arata berikan sebagai respons, membuat lawan bicaranya langsung paham. Keduanya terus berjalan. Menapaki anak tangga terakhir yang menghubungkan lantai dua dengan lantai satu. Keluar dari area apartemen menuju kantor pos yang tak jauh di sebelah kanan. Kurang lebih sepuluh menit dengan berjalan.
“Sudah bicara dengan Nyonya Hana?” Fumio berinisiatif memantik obrolan. Begitu dilihatnya Arata mengangguk, Fumio melanjutkan, “dia akan merindukanmu.”
“Apa kau juga akan merindukanku?” Arata menyeringai, usil menggoda laki-laki yang berteman baik dengannya selama empat tahun terakhir itu.
“Siapa kau sehingga aku harus merindukanmu?” Fumio memutar bola mata jemu untuk kesekian kali.
“Ah, kau hanya tidak mau mengakuinya.” Arata menyikut rusuk Fumio, membuat yang disikut memelotot karenanya. Alih-alih berhenti, Arata justru makin getol menggoda, “aku akan merindukanmu sepenuh hatiku.”
“Enyahlah kau!”
Arata terbahak. Tidak peduli dengan beberapa orang di sekitar yang menatap bingung. “Tolong! Cubit aku! Aku tidak bisa berhenti tertawa.”
Fumio mendengkus, melayangkan, bukannya cubitan, melainkan satu jitakan telak di kepala Arata. Jitakan yang membuat si objek jitak mengaduh pelan dan perlahan berhenti tertawa. “Sudah puas tertawamu?”
Arata menyengir, kembali menyejajarkan langkah dengan Fumio. Sorot matanya melembut ketika berkata, “Aku serius. Aku akan merindukanmu. Nyonya Hana. Apato. Kalian semua. Hal-hal yang tidak mungkin kusebut satu per satu.”
“Terdengar seperti kau tidak berminat kembali ke sini suatu hari nanti.” Fumio berkomentar pendek.
“Siapa yang bisa menjamin apa aku akan kembali atau tidak? Perkara takdir terkadang tidak sejalan dengan yang kita mau, kan?” Arata tersenyum. Sebelum dilihatnya Fumio yang ingin berkata sesuatu angkat suara, buru-buru ia menyela. “Kau sendiri? Kapan akan berangkat?”
“Secepatnya.” Fumio menjawab sekenanya, tampak tidak tertarik dengan pengalihan topik yang dilakukan Arata. “Apa kau sudah memberitahu-nya tentang keberangkatanmu?”
Mendengarnya, Arata menaikkan sebelah alis. Perlu waktu beberapa detik untuk memahami siapa yang dibicarakan Fumio. Perlu beberapa saat pula sebelum senyum di wajah pudar begitu saja. “Aku hanya memberitahu kalau aku akan kembali ke kampung halaman.”
“Apa kau menyebut kapan dan di mana tepatnya?”
Gelengan Arata berikan sebagai jawaban. “Ada sesuatu yang menghalangiku untuk memberitahunya saat ini.” Arata menambahkan. Lalu, hening. Ada jeda beberapa lama sebelum ia kembali bersuara, “hei, Fumio!”
Fumio menoleh sebagai respons.
“Bagaimana pendapatmu jika aku melamarnya?” Tercetus juga pertanyaan itu. Hal yang kerap mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Sejak Aisha mengirimkan surat ultimatum sebulan yang lalu, Arata tidak bisa berhenti untuk memikirkannya.
Arata kira, Fumio akan menanggapi sekenanya saja. Atau, menganggap Arata hanya bergurau dan memutar bola mata jemu sebagai jawaban. Ternyata, jawaban yang Arata dapat di luar dugaan. Jawaban yang, sebenarnya, bukan jawaban. Lebih seperti pertanyaan sebagai respons balik.
“Apa kau sudah berhasil meyakinkan ibunya?”
“Justru itu.” Arata menunduk. “Ibunya memperingatkanku. Meminta kalau aku memang serius, aku harusnya menghadap dan menyatakan keseriusan. Bukannya terus-menerus mengirimkan surat seperti remaja tanggung yang sedang kasmaran.”
Ada jeda yang cukup lama sebelum Fumio menyahut, “Apa kau menyukainya?”
Mendengarnya, Arata mengerjap. Sungguh? Arata menoleh, memberi Fumio tatapan apa kau serius? yang tajam sekarang ini. “Menurutmu?” Arata balas bertanya, entah kenapa kesal sendiri.
“Tidak tahu.”
“Fujiwara Fumio!” Arata mulai dongkol. “Aku menceritakan semuanya padamu. Perasaanku. Hubungan kami. Betapa aku menyukainya. Ralat, mencintainya. Dan kau masih bertanya apa aku menyukainya?”
“Hanya memastikan. Kau tidak perlu berlebihan seperti itu, Arata.” Fumio memutar bola mata jemu. “Jadi,” Fumio memasukkan kedua belah telapak tangan ke saku celana lalu melanjutkan, “kau mencintainya?”
“Sepenuh hatiku.”
“Aku asumsikan kau ingin membahagiakannya suatu hari nanti.” Fumio mendongak, sejenak menatap langit sebelum kembali melanjutkan, “menurutmu, apa cinta saja cukup untuk membahagiakannya?”
Kali ini, Arata sukses terdiam. Seakan rentetan kalimat siap sembur tertahan begitu saja. Perlahan menguap, membuatnya kehabisan kata untuk menjawab.
“Pikirkan lagi.” Fumio menatap lurus ke depan. “Kau akan menemukan jawabannya.”
Setelahnya, hening. Embusan angin mengisi kekosongan di antara mereka. Tidak ada lagi yang berbicara. Keduanya terus berjalan. Membiarkan pertanyaan yang sempat terlontar lesap begitu saja. Fumio dengan ... entah apa yang dipikirkan pemuda itu dan Arata yang tanpa sadar meremas ujung pakaian.
Mungkin, ini memang jalan terbaik bagi mereka berdua.
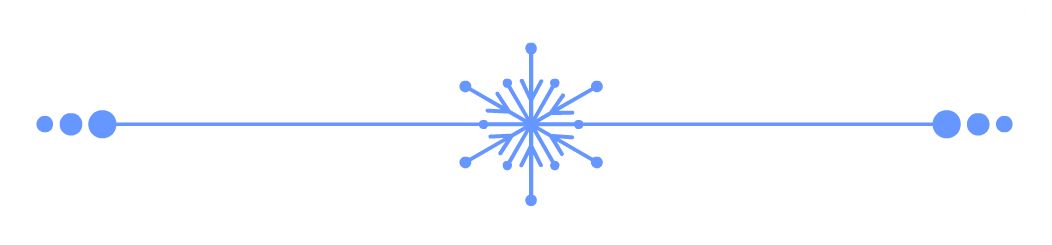
“Terima kasih untuk segalanya, Nyonya.” Arata membungkukkan badan di depan Nyonya Hana, tersenyum lembut. Ada sedikit getar dalam suara ketika pemuda itu berkata, “aku akan merindukanmu.” Diusapnya sudut mata yang basah.
“Wanita tua ini akan selalu berada di sini, Nak.” Nyonya Hana menepuk pundak Arata, ikut menyuguhkan senyum. “Kau bisa kembali kapan pun kau mau.”
Arata terdiam sebentar, tahu benar apa yang dimaksud Nyonya Hana. “Kau tidak perlu melakukannya, Nyonya.”
Nyonya Hana menggeleng. “Apato itu akan menunggumu, Nak. Hingga kau kembali.” Wanita setengah baya itu kembali tersenyum. “Aku juga akan merindukanmu.” Nyonya Hana mengambil satu langkah ke depan, tanpa ragu mendekap Arata. “Jangan lupakan wanita tua ini, ya?”
Arata tersenyum sendu, membalas pelukan tersebut. Nyonya Hana. Pemilik Apartemen Origin yang sudah ia anggap layaknya keluarga sendiri. Hari ini, di apato yang wanita tua itu tempati, Arata pamit setelah empat tahun menorehkan banyak kenangan dan cerita. “Bagaimana mungkin, Nyonya?” Arata menepuk lembut punggung Nyonya Hana.
Nyonya Hana melepaskan pelukan di antara mereka. Ditatapnya Arata sejenak sebelum berkata, “Jaga dirimu baik-baik.”
“Kau juga, Nyonya.” Arata meraih koper di dekat kaki seraya melemparkan senyum terakhir sebelum benarbenar berbalik dan pergi. “Sampai jumpa lagi, Nyonya.”
Arata menghela napas panjang untuk beberapa saat. Dibukanya pintu apato Nyonya Hana dengan perasaan tak menentu. Akhirnya, ia akan memulai babak baru dalam hidup. Meninggalkan Nagoya dan beribu kenangan yang tercipta. Pemuda itu mendongak, menatap lama apato paling ujung di lantai tiga. Senyum hinggap di wajah. Ia akan merindukan tempat itu.
Padahal Arata sudah mencegah ketika Nyonya Hana melontarkan janji bahwa dirinya tak akan pernah menyewakan apato itu pada orang lain. Namun, Nyonya Hana tetap teguh dengan pendiriannya. Apato itu akan selalu menjadi milik Arata. Apa pun yang terjadi. Begitu katanya. Hingga beberapa saat lalu, untuk terakhir kali, Arata menolak dengan halus sebelum menyerah juga akhirnya. Tidak bisa melakukan apa pun selain mengucap terima kasih.
Arata bersyukur. Sangat. Ia selalu bertemu dengan orang-orang baik. Mereka yang selalu menjaganya. Bersedia menerima kekurangannya.
“Hei!”
Lamunan Arata buyar begitu saja. Pemuda itu menoleh ke samping kanan—di mana sapaan itu terdengar, mendapati seseorang bersandar di salah satu pohon. Arata mengernyit, berusaha mengenali. Sia-sia saja. Sekeras apa pun usahanya, wajah itu terlihat asing. Satu-satunya yang menjadi tanda adalah pakaian yang orang itu kenakan. Pakaian yang sama dengan orang yang menemani Arata menuju kantor pos pagi tadi. Juga, membantu mengepak beberapa barang yang tersisa.
Siapa lagi kalau bukan Fumio?
“Aku akan baik-baik saja.” Arata paham benar maksud Fumio saat berjalan mendekat dan berdiri tepat di depannya.
“Terminal Highway Bus Nagoya?” Fumio memastikan. Lebih memilih abai dengan kata-kata Arata barusan.
Seharusnya Arata sudah tahu. Dia mendesah. Apa ia seperti punya pilihan lain sekarang ini?
“Ya.” Arata merespons pendek.
Fumio mengangguk, memberi isyarat dagu dan berjalan lebih dulu. Meninggalkan Arata yang mengembuskan napas pendek beberapa langkah di belakang.
Buru-buru Arata berjalan cepat dan menyejajarkan langkah. “Sungguh. Aku akan baik-baik saja.” Sekali lagi, Arata mencoba meyakinkan.
“Aku tahu.”
“Lalu?”
Kali ini, giliran Fumio yang mendesah frustrasi. Sudut matanya melirik Arata dan berucap, “Kau tahu?” Ada jeda beberapa saat sebelum Fumio melanjutkan, “kau adalah laki-laki paling cerewet yang pernah kutemui.”
“Aku hanya tidak ingin merepotkanmu.”
“Tidak masalah.” Fumio memasukkan kedua belah tangan ke saku celana. “Kau tahu?”
Arata tidak menjawab. Hanya menunggu. Menyisakan keheningan beberapa saat.
“Kurasa kau tidak ingin tahu.” Fumio mengangkat bahu, terus berjalan. Tidak tahu saja kalau orang yang ia ajak bicara mulai kesal sampai mengubun-ubun.
“Oh, sungguh!” Arata mendengkus, membuang wajah ke samping. “Ya, aku memang tidak ingin tahu.” Ditekannya kata per kata, menyiratkan kekesalan.
Setelahnya, benar-benar hening. Tidak ada lagi yang berbicara. Menyisakan hiruk pikuk yang perlahan mengisi kesunyian. Menandakan mereka sudah berjalan cukup jauh dan akan sampai di terminal sebentar lagi.
“Hei!” Arata mencolek pergelangan tangan Fumio, membuat yang dicolek menoleh. “Maafkan aku,” katanya pelan.
Arata sadar, tidak seharusnya mereka bertengkar di saat seperti ini hanya karena hal sepele. Bisa saja, ini terakhir kalinya mereka bertemu dan bicara. Bertengkar hanya akan merusak suasana.
“Aku hanya ingin memastikan kau aman. Itu saja.”
“Aku tahu.” Arata menunduk, menatap ujung sepatu yang ia kenakan. “Entah kenapa aku merasa lebih sensitif hari ini. Maaf soal itu. Tadi kau ingin bilang apa?”
“Bukan apa-apa.” Fumio menyahut tanpa perlu repot-repot menoleh. “Perhatikan langkahmu.” Laki-laki dengan anting di telinga kanan itu menarik ujung lengan pakaian Arata, menuntun agar sahabatnya itu tidak hilang arah dan kehilangannya di keramaian.
Terminal Highway Bus Nagoya memang selalu ramai. Tidak pernah, tidak. Dipenuhi oleh orang-orang yang datang dan pergi. Keadaan seperti ini rawan sekali baginya dan Arata untuk terpisah. Ditambah, Arata yang mengidap prosopagnosia memperbesar risiko hal-hal tidak diinginkan. Salah-salah, laki-laki itu bisa hilang arah seperti anak ayam ditinggal induk di keramaian seperti ini.
Begitu mereka mendapatkan terminal jurusan Nagoya–Takayama, barulah Fumio melepaskan ujung lengan pakaian Arata. “Pergilah,” katanya diiringi isyarat dagu.
“Kau tidak ingin memelukku?” Arata memasang ekspresi yang, alih-alih terlihat tidak berdosa, malah menimbulkan hasrat Fumio untuk menggaploknya. “Tidak ada kata-kata terakhir? Salam perpisahan? Pelukan hangat?”
Fumio memutar bola mata jemu, enggan menanggapi keusilan Arata. Hanya dua kata yang ia ucapkan, “Jaga dirimu.”
Arata tersenyum, mengangguk. “Kau juga. Jaga dirimu baik-baik.” Diangkatnya kelingking, tersenyum lebih lebar. “Kalau kau sudah selesai dengan studimu dan kembali ke Jepang, hubungi aku. Aku ingin mendengar cerita soal London dan apa pun itu.”
Fumio tersenyum tipis, menggeleng-geleng. Ditautkannya kelingking mereka, bersama-sama. “Tentu.”
“Aku akan merindukanmu—” Arata maju selangkah, memeluk Fumio hangat. Tidak peduli meski laki-laki itu akan memukul atau mendorongnya menjauh. “—Kak,” katanya lagi, menyelesaikan ucapan yang terputus.
Fumio terpaku. Geraknya kaku ketika mengangkat tangan dan membalas pelukan itu. Hanya sebuah pelukan singkat. Dekapan antar saudara. Sahabat. Kakak dan adik. “Kita hanya selisih tiga bulan, Arata. Dan, kau bahkan tidak memberitahuku di mana kampung halamanmu itu.”
“Rahasia. Akan kuberitahu jika aku sudah tiba di sana.” Arata tertawa pelan. Senyumnya tak kunjung lekang, bahkan sampai pemuda itu menaiki bus dan melambaikan tangan sambil berseru lantang. Meninggalkan Fumio yang—
“Sampai jumpa lagi, Kak!”
—perlahan membisikkan selarik kalimat yang tak terucap. Tepat saat pemuda itu melepas kepergian bus yang membawa Arata tak lama kemudian. Meninggalkan Nagoya. Menyisakan kenangan yang berceceran.
“Aku juga akan merindukanmu, Arata.”
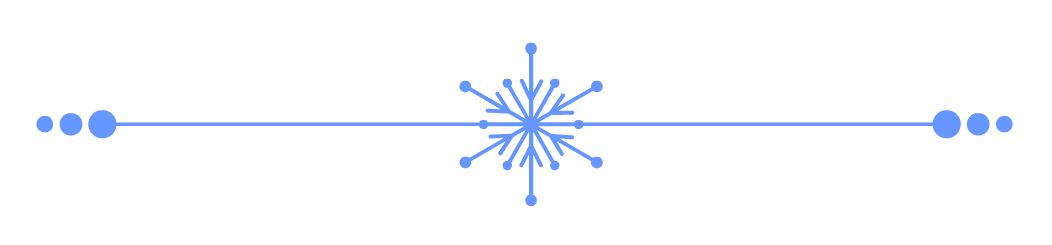
“Aku mengirimkan surat tadi pagi. Dalam beberapa hari, seharusnya sudah sampai.”
Dalam sunyi keadaan bus, Arata menekan tombol kirim. Hanya sebuah pesan pendek. Sekadar memberitahu Ayumi. Arata sadar betul dia pelupa, terutama untuk hal “remeh” seperti ini. Sebisa mungkin ia memberitahu Ayumi kalau dia telah mengirimkan surat. Seperti yang selalu ia lakukan sebelum-sebelum ini.
Bertahun-tahun menjalin hubungan, Arata hanya menggunakan tiga media untuk tetap berhubungan dengan Ayumi. Surat, pesan pendek, dan sesekali saja panggilan—itu pun jarang sekali, mengingat sikap defensif Aisha kepada Arata. Favoritnya adalah surat. Surat berbeda dengan sekadar pesan pendek.
Bagi Arata, surat jauh lebih romantis. Lebih leluasa baginya mengekspresikan diri melalui tulisan tangan. Sensasinya berbeda dengan pesan pendek via ponsel ataupun panggilan. Ditambah, Ayumi tidak keberatan. Berkirim surat itu menyenangkan. Begitu kata kekasihnya itu. Hal yang disetujui Arata.
Satu getar halus sukses menarik fokus Arata kembali. Balasan dari Ayumi.
“Ah, baiklah. Akan kutunggu.” Jeda beberapa detik sebelum balasan berikutnya tiba. “Kau tahu? Aku baru saja kembali dari kantor pos. Mengirimkan surat untukmu. Kebetulan yang menyenangkan, ya?”
Membacanya, mau tidak mau membuat Arata tersenyum. Hanya sebentar. Suram datang menggantikan. Salah satu sudut bibirnya berkedut. Bukan menahan tawa, tapi justru sebaliknya.
“Mungkin ini yang mereka bilang dua perasaan saling bertaut. Tak peduli sejauh apa pun itu,” balas Arata.
“Mungkin.” Balasan itu datang dengan cepat. “Arata-kun.”
“Ya?”
“Aku merindukanmu.”
Ah, Ayumi. Arata ingin sekali jujur sekarang ini. Mengatakan semua yang akan terjadi dalam hubungan mereka. Tidak akan ada lagi surat-surat. Arata sudah berjanji pada Aisha. Jika saatnya sudah tiba, suatu hari nanti, Arata akan menyatakan keseriusan. Seiring janji itu, tersebut pula janji lain: Arata akan berhenti mengirimkan surat untuk Ayumi.
Berhenti memberikan harapan yang entah kapan akan terlihat juntrungannya. Arata selalu bermimpi, ia dan Ayumi akan bersama selamanya. Menjajaki hidup berdua hingga akhir hayat. Hari ini, Arata memutuskan, akan menunggu juntrungan itu terlihat. Ia pasti bisa. Ayumi pasti mengerti, pikirnya.
Ia akan memberitahu Ayumi. Namun, bukan sekarang. Dia perlu sedikit waktu. Arata tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara Ayumi dan Aisha. Bagaimanapun, meski berat, Arata bisa memahami posisi Aisha sebagai seorang ibu. Ibu yang menginginkan putrinya bahagia. Ingin Ayumi mendapatkan yang terbaik. Wanita yang tak ingin melihat anak yang ia lahir dan besarkan suatu saat terluka karena ketidakpastian.
Hingga saatnya tiba, Arata akan bersabar. Sedikit banyak, apa yang dikatakan Aisha benar. Mereka bukan lagi remaja tanggung. Begitu juga dengan yang Fumio tuturkan. Benar. Apa cinta saja cukup untuk membahagiakan orang yang ia sayangi?
Arata menghela napas, mengetikkan balasan sebelum mematikan ponsel dan bersandar. Membiarkan lelap mulai menggelayut hingga ia sampai di tujuan: Kanazawa.
“Aku juga merindukanmu, Ayumi.”

Arata sempat singgah di Shirakawago. Hanya bagian dari perjalanan menuju Kanazawa. Sempat tebersit niat mengunjungi Ayumi, tapi Arata tahu, ia tidak perlu dan sebaiknya tidak melakukannya. Muncul di kediaman Akikawa hanya akan menimbulkan risiko masalah. Arata tidak ingin itu terjadi.
Arata terbangun setelah seorang nenek yang duduk di belakangnya membangunkan. Arata menggeliat, mengucap terima kasih sembari menguap. Disisirnya keadaan sekitar. Tampak ramai. Benar. Ia sudah tiba di Kanazawa. Buru-buru Arata merapikan diri dan meraih koper serta barang bawaan. Antre sebentar untuk turun.
Kanazawa ....
Arata melihat sekeliling. Rasanya, seperti mengulang masa lalu. Ia besar di sini. Menghabiskan masa-masa sekolah di sini. Bertemu dan menjalin hubungan bersama Ayumi di sini pula. Ah, tanpa sadar Arata bersemu saat mengingatnya.
Sekarang, yang perlu ia lakukan adalah mencari Apartemen Aizawa.
Arata merogoh saku celana, di mana ia menyelipkan secarik kertas berisi alamat Apartemen Aizawa. Ini dia! Arata menemukannya. Sedikit terselip. Ditatapnya lamat-lamat alamat tersebut. Sebelah tangannya meraba saku celana lain, mencari ponsel. Aneh. Tidak ada. Arata beralih ke saku kemeja. Tidak ada juga.
Ke mana ponselnya?
Buru-buru Arata menurunkan ransel di punggung. Menggeledah setiap sudut dan kantung. Nihil. Tetap tidak ada.
Oh, yang benar saja? Arata mulai frustrasi sendiri. Sudah tiga kali ia melakukannya, tapi tak kunjung ditemukan jua benda persegi panjang tersebut.
Arata beralih ke koper, meski kecil kemungkinan karena ia tak pernah mengutik-utik benda tersebut. Masalahnya adalah ponsel itu tidak bisa ia temukan. Perlu waktu lama bagi Arata untuk menyusuri setiap inci, sudut, kantung, dan lipatan. Benar-benar seperti hilang tanpa bekas.
Arata sudah memastikan tidak ada yang tertinggal saat akan turun dari bus. Lama sekali Arata mencari. Satu senggolan di bahu membuyarkan lamunan. Arata mendongak, mendapati seorang pria berlalu sambil menggerutu. Mungkin kesal karena Arata menghalangi jalan.
Perlahan, matahari sore kian jingga. Menyisakan Arata yang menyadari bus yang ia naiki telah pergi. Juga, ponsel yang tak kunjung ditemukan. []
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top