Halilintar: Layaknya Cahaya Kecil (3/3)
"Suster, bagaimana keadaan cucu saya?"
"Sabar, Pak. Pasien sedang ditangani oleh dokter IGD."
.
.
"Saat ini pasien memerlukan transfusi darah, tapi stok golongan darah AB di sini sedang kosong. Apakah di antara keluarga ada yang bergolongan darah sama?"
"Ambil darah saya, Dokter!"
"Saya juga, Dok. Kami bertiga kembar. Golongan darah kami sama."
"Baik. Adik berdua, silakan ikut saya."
.
.
"Dengan keluarga Taufan?"
"Ya, Dok? Kami keluarganya. Bagaimana keadaan Taufan sekarang?"
"Tim Dokter sudah berusaha melakukan yang terbaik."
"M-Maksudnya ...?"
"Sudah tidak ada lagi yang bisa kami lakukan ..."
.
.

Gambar: Ilustrasi penanganan pasien gawat darurat
.
.
"Sudah tidak ada lagi yang bisa kami lakukan ..."
Halilintar memucat ketika mendengar kata-kata dokter wanita seumuran orangtuanya itu. Lututnya lemas seketika, dan ia tiba-tiba merasa sulit bernapas. Andai tak ingat ada Tok Aba di situ, mungkin dia tidak akan mampu menguatkan diri. Sang kakek sudah cukup khawatir dan sedih memikirkan Taufan. Mana boleh dia menambah lagi beban beliau?
"Kita harus menunggu sampai Taufan sadar." Halilintar tersentak saat dokter itu melanjutkan ucapannya. "Untuk sementara, Taufan belum bisa dijenguk. Tim dokter masih harus terus memantau kondisinya sampai benar-benar stabil."
"Maksud Dokter, Taufan ...?" Gempa berkata, mewakili Halilintar yang tak mampu bicara sepatah kata pun.
"Taufan masih kritis," dokter itu menjawab. "Dan beberapa jam ke depan, akan jadi saat-saat yang sangat menentukan."
"Kritis ...?" Gempa kembali berkata. Kecemasan jelas tersirat di wajahnya.
"Dokter," Tok Aba ikut bicara. "Tolong selamatkan cucu saya."
"Kami akan melakukan yang terbaik." Dokter itu berkata dengan nada menenangkan. "Keluarga bisa membantu dengan doa."
Dokter itu masih bicara sebentar dengan Gempa dan Tok Aba, tetapi Halilintar sudah tidak mendengarkan apa-apa lagi. Bahkan ketika Yaya membimbingnya untuk duduk, pemuda itu hanya menurut, antara sadar dan tidak.
"Halilintar? Kamu nggak apa-apa?"
Suara lembut Yaya akhirnya mampu menarik kesadaran Halilintar kembali. Ia menoleh ke kanan, dan melihat Yaya sudah duduk di sampingnya.
Pemuda itu seolah baru sadar dirinya ada di mana. Ya, ini adalah Rumah Sakit Pulau Rintis. Dia sekarang ada di depan ruang Instalasi Gawat Darurat tempat Taufan dirawat. Hanya dia dan Yaya yang duduk di deretan bangku yang tersedia tepat di depan ruang IGD. Sedangkan Gempa, Tok Aba, dan Ochobot, masih ada di depan pintu ruangan itu. Halilintar sudah tidak melihat dokter wanita tadi, mungkin sudah masuk lagi ke dalam.
"Hali ... wajahmu pucat sekali!" Tiba-tiba Gempa mendekat, lantas ikut duduk di samping kiri kakaknya. "Kamu sakit? Ja ... Jangan-jangan ... kamu terluka?!"
Halilintar cepat-cepat menggeleng, tak ingin kecemasan adiknya bertambah tanpa alasan.
"Aku baik-baik saja," kata Halilintar lirih.
Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, mencari kelegaan. Saat itu juga, dia baru sadar, tubuhnya yang sejak tadi dijalari hawa dingin, kini sudah kembali menghangat. Detak jantungnya pun berangsur normal, seiring kecemasan yang mulai terangkat.
"Jangan bohong," kata Gempa. "Kalau sakit, bilang."
Halilintar hanya menggeleng. Gempa menatap kakaknya dengan kening berkerut. Memang tidak ada tanda-tanda kesakitan atau semacamnya. Hanya saja, wajah Halilintar jelas terlihat letih dan cemas. Gempa berinisiatif menggenggam kedua tangan sang kakak yang tertaut. Pemuda beriris keemasan itu langsung tersentak kaget.
"Tanganmu dingin sekali!" kata Gempa. Ditangkupkannya kedua tangan melingkupi tangan Halilintar yang gemetaran, ingin memberinya kehangatan.
Halilintar menunduk dalam-dalam, hingga wajahnya tersembunyi di balik lidah topi. Dibiarkannya rasa hangat dari tangan Gempa, tersalur ke tangannya, lalu menyebar lebih luas. Namun, gemetar di tubuhnya masih tersisa.
"Gempa ...," tiba-tiba Halilintar berkata. Pelan dan bergetar. "Aku ... Aku ini ... mungkin pembawa sial, ya ...?"
Gempa tercenung. Ia bisa merasakan tangan Halilintar masih gemetar di genggamannya. Begitu pula kepedihan mendalam di dalam kalimat yang baru saja terucap.
"Hali ..." Untuk sesaat, Gempa benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Hei ... Itu sama sekali nggak benar—"
"Tapi memang begitu kenyataannya! Tanganku ini ... sudah berkali-kali menyakiti kalian!" Halilintar mulai membiarkan emosinya naik ke permukaan. "Dan Taufan ... Dia selalu terluka kalau berada di dekatku! Aku ... Padahal aku terus menyakitinya ... tapi kenapa dia tetap saja mendekat ...?"
Halilintar mengeratkan kepalan tangannya. Kepalanya pun tertunduk semakin dalam. Gempa terdiam di sisi sang kakak. Tahu apa pun yang diucapkannya sekarang tak akan bisa menghibur Halilintar.
Sementara itu, Tok Aba yang mendengarkan pembicaraan kedua cucunya sejak tadi, perlahan mendekat. Yaya menyingkir ke dekat Ochobot, sehingga Tok Aba bisa duduk di sebelah Halilintar.
"Halilintar ..."
Panggilan lembut Tok Aba membuat Halilintar tersentak. Ia mengangkat wajah, dan mendapati sang kakek tiba-tiba sudah duduk di dekatnya.
"Nak, dengarkan Atok," Tok Aba berkata lagi, masih dengan nada penuh kasih sayang yang sama. "Tidak ada yang namanya 'pembawa sial'. Semua yang terjadi di dunia ini, sudah kehendak Sang Pencipta. Termasuk apa yang menimpa Taufan sekarang."
"Tapi ... Atok ..." Halilintar menatap kakeknya dengan tatapan nanar. "Taufan terluka gara-gara aku ... Semua ini salahku ..."
Tok Aba menggeleng, lantas memeluk cucu pertamanya. Halilintar terkejut, tetapi tidak menolak. Alih-alih, ia memejamkan mata. Pelukan sang kakek selalu membuatnya merasa nyaman.
"Halilintar," ujar Tok Aba. "Atok tahu, kau sangat menyayangi Taufan dan Gempa. Kau selalu memikirkan kebahagiaan adik-adikmu. Dan kau selalu melindungi mereka."
"Tapi, aku ... aku tidak bisa melindungi Taufan—"
Ucapan Halilintar terputus. Akhirnya ia membalas pelukan sang kakek. Berusaha keras menahan tangis yang menyesakkan dadanya. Sementara, Tok Aba hanya diam sambil mengusap-usap punggung cucunya.
"Atok ...," Halilintar berkata lagi. Lirih, nyaris berbisik. "Kalau ... Kalau terjadi sesuatu pada Taufan ... aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri ..."
Set.
Tiba-tiba Gempa ikut memeluk kakak sulungnya. Halilintar hanya tersentak kecil, tetapi lagi-lagi membiarkannya.
"Taufan itu kuat," kata Gempa. "Kita harus yakin, dia pasti akan baik-baik saja."
Halilintar terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ia lantas melepaskan pelukannya, dan menegakkan tubuh kembali.
"Kamu benar, Gempa," kata Halilintar kemudian. "Maafkan aku."
"Betul, betul." Tok Aba tersenyum tipis. "Berdoalah untuk Taufan. Jangan putus asa."
Halilintar mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Masih terlihat sedih. Hanya sedetik, senyum itu mendadak terhapus. Digantikan oleh ekspresi dan tatapan yang kosong tiba-tiba.
Bruk.
"Hali!?"
Halilintar masih mendengar seruan cemas Gempa, sementara ia merasakan tubuhnya mendadak lemas kehilangan tenaga. Pandangannya pun berkunang-kunang. Mengabur, seiring kesadaran yang menipis. Samar-samar, ia masih bisa merasakan Gempa yang menahan tubuhnya. Memeluk dan memanggil-manggil namanya.
Lalu, semuanya jadi gelap.
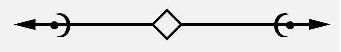
Saat membuka mata kembali—setelah entah berapa lama waktu berlalu—Halilintar mendapati dirinya sudah berbaring di kasur yang empuk. Bau khas rumah sakit sudah tak lagi memenuhi indra penciumannya. Bahkan dia sangat mengenali tempat di mana dirinya berada saat ini.
Kamarnya sendiri.
Kenapa aku ada di sini? Begitu pikirnya. Dia bangun, lalu duduk di tepi tempat tidur. Baru saja ia hendak beranjak, pintu kamarnya terbuka perlahan.
"Hali, sudah bangun?" Gempa yang barusan membuka pintu, hanya berdiri di ambangnya. "Kebetulan, aku hampir selesai masak—"
"Kenapa kita di rumah?" Halilintar menyela.
Gempa menghela napas pelan. "Kamu pingsan di rumah sakit. Tapi kata dokter nggak ada yang serius, cuma kelelahan. Dan mungkin juga ... efek sehabis donor darah. Karena itu, Atok menyuruh kita pulang supaya bisa istirahat."
"Kamu yang membawaku sampai ke sini?"
"Hehe ... Ochobot yang mengantar kita pakai teleportasi. Habis itu, dia kembali lagi ke rumah sakit, menemani Atok."
"Ooh ..."
Halilintar melihat jam dinding di atas meja belajar. Sudah hampir Maghrib. Padahal seingatnya, waktu di rumah sakit tadi dia dan Gempa baru saja menunaikan salat Ashar di mushola.
Berarti, dirinya sudah tidur cukup lama.
"Lebih baik kamu mandi dulu," Gempa memecah keheningan. "Nanti kita Maghrib berjamaah, ya! Habis itu, baru makan malam. Kita balik ke rumah sakit setelah Isya', biar bisa gantian sama Atok buat jagain Taufan."
"Tapi—"
"Ngobrolnya nanti aja sambil makan."
Halilintar hanya mendesah pelan. Nada bicara Gempa sejak tadi seperti memerintah tanpa bisa dibantah. "... Baiklah."
Waktu seperti berlari bagi Halilintar setelah itu. Tahu-tahu, dia sudah duduk di meja makan, kali ini hanya bersama Gempa. Sepi juga rasanya. Tidak ada Tok Aba dan Ochobot. Tidak ada Taufan yang biasanya tak bisa diam.
"Hali ... dimakan, dong ... Aku 'kan sudah capek-capek masak," kata Gempa tiba-tiba.
Memang, sejak tadi Halilintar hanya diam sambil mengaduk-aduk makanannya. Baru sesuap yang masuk ke perutnya. Setelah itu, dia seperti tidak berselera sama sekali untuk makan.
"Aku nggak lapar—"
"Jangan pakai alasan itu!" potong Gempa. "Kamu sudah hampir kehabisan tenaga di pertarungan. Lalu masih donor darah untuk Taufan. Mana mungkin bisa nggak lapar?"
Halilintar hanya diam, membiarkan Gempa mengomelinya.
"Kalaupun nggak selera, paksakan aja. Kamu harus makan. Nggak lucu 'kan, kalau sampai sakit gara-gara kurang makan. Kasihan Atok, nanti beliau makin cemas."
Halilintar menatap Gempa, lalu beralih memandangi hidangan yang tersedia di meja makan. Semuanya makanan kesukaan Halilintar. Ditambah segelas cokelat panas yang sama seperti khas Kedai Kokotiam. Di antara ketiga cucu Tok Aba, hanya Gempa yang bisa membuatnya sesempurna itu.
"Kalau Taufan melihat kita terlalu larut dalam kesedihan," Gempa melanjutkan ucapannya, "dia nggak akan bisa tersenyum lagi. Ya, 'kan?"
Halilintar tidak menyahut. Ia mulai menyantap makanan di piringnya lagi. Masakan Gempa selalu enak, sama seperti masakan Tok Aba yang pandai memasak. Dan kali ini, Gempa membuat semuanya sesuai dengan selera Halilintar. Jadi, mana mungkin dia tidak menyukainya?
Tiba-tiba pemuda beriris merah delima itu merasa terharu. Begitu besar perhatian Gempa padanya, sampai berbuat sejauh ini. Padahal lebih gampang membeli makanan di luar daripada harus memasak. Gempa sendiri pasti juga lelah, 'kan?
"Gempa ... kamu belum istirahat sejak tadi?" tanya Halilintar.
"Hm?" Gempa teralih sejenak dari makanan di piringnya. "Sudah, kok. Tenang saja."
Halilintar mengerutkan kening, tak percaya begitu saja. "Yang benar?"
"Aku tadi sempat ketiduran pas nungguin nasi yang ditanak. Untung pakai magicom, udah otomatis. Hehe ..."
"Bagus, deh. Lebih nggak lucu lagi kalau kamu yang sakit gara-gara kurang istirahat."
Gempa hanya tertawa kecil. Kedua bersaudara itu melanjutkan makan malam mereka dengan tenang. Gempa lega ketika melihat sang kakak menghabiskan makanan di piringnya tanpa sisa.
"Oya," tiba-tiba Halilintar membuka pembicaraan lagi. Ia baru saja menikmati minuman cokelatnya satu-dua teguk. "Bagaimana keadaan Taufan? Sudah dapat kabar?"
Sambil meraih cangkirnya, Gempa menjawab, "Terakhir kali aku menghubungi Ochobot, katanya Taufan sudah dipindahkan ke ruang ICU."
"Berarti ... kondisinya sudah stabil?"
Gempa mengangguk. "Tapi dia masih belum sadar. Makanya, masih butuh perawatan intensif."
Hening kembali. Sementara Gempa dan Halilintar menyesap cokelat masing-masing sampai tandas. Kecemasan masih mencengkeram pikiran masing-masing. Namun, mereka tak ingin memperlihatkannya.
"Ya udah, siap-siap, yuk!" kata Gempa kemudian. "Habis Isya' kita langsung berangkat."
Dijawab oleh Halilintar dengan sebuah anggukan.
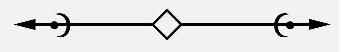
Halilintar memasuki ruang ICU dengan langkah ragu. Dia—bersama Gempa—harus mengenakan pakaian khusus berwarna hijau, baru diperbolehkan melihat Taufan. Itu pun hanya beberapa menit.
Gempa sudah duduk di sebuah kursi kecil, tepat di samping kiri ranjang Taufan. Ia menggenggam tangan saudaranya, sembari membisikkan nama 'Taufan' satu-dua kali. Halilintar ikut mendekat ke sisi kanan ranjang, sambil menarik kursi lain untuk tempatnya duduk. Setelah itu, ia hanya diam memandangi adik pertamanya yang masih terlelap.
Beberapa selang tampak menghubungkan Taufan dengan kantong infus dan tabung oksigen. Tubuhnya juga masih terhubung dengan alat monitor jantung. Halilintar miris melihatnya, betapa Taufan yang selalu ceria kini terlihat tak berdaya. Setidaknya, Halilintar sudah cukup lega melihat anak itu bernapas dengan tenang, meskipun masih harus menggunakan masker oksigen. Raut wajahnya pun sudah tidak menampakkan kesakitan.
Halilintar mengulurkan tangan perlahan. Ingin meraih tangan Taufan, sebelum ia tersentak. Gerakannya terhenti, lantas dikepalkannya tangan itu dan ditariknya kembali. Iris merah delima itu meredup, seiring pemiliknya yang menunduk dalam-dalam.
Tiba-tiba Halilintar takut menyentuh Taufan, seolah sentuhan itu akan menyakiti sang adik.
"Siapa yang melakukan pertolongan pertama pada luka di perut Taufan?"
Mendadak Halilintar teringat percakapan singkatnya dengan dokter, sebelum dirinya dan Gempa memasuki ruang ICU.
"Saya, Dok ... A-Apa ada yang salah?"
"Ah, tidak. Justru penanganannya bagus sekali. Oh ya ... menurut informasi, napas dan detak jantungnya juga sempat berhenti. Apakah Adik juga yang melakukan CPR dan memberikan napas buatan?"
"Iya, Dokter."
"Yang Adik lakukan itu bagus sekali. Bisa jadi, itulah yang sudah menyelamatkan nyawa Taufan."
Halilintar memandangi tangan kanannya, lantas mengangkat wajahnya kembali. Ditatapnya Taufan yang begitu damai dalam tidur. Kalau boleh jujur, saat mendengar ucapan dokter itu, hatinya terasa hangat. Rasanya seolah beban yang sangat berat telah diangkat darinya.
'Menyelamatkan nyawa Taufan' ... ya?
Benarkah?
Kalau sekarang, harusnya sudah tidak apa-apa, 'kan?
Set.
Akhirnya Halilintar meneruskan niat. Memberanikan diri, digenggamnya tangan kanan Taufan dengan hangat. Rasanya baru tiga detik, ketika tiba-tiba ada gerakan kecil.
"Tau ... fan?" Halilintar memanggil ragu, lantas beralih memandang adik bungsunya. "Gempa ... jari Taufan tadi bergerak ..."
Gempa tersentak kecil. Ia pun ikut memanggil Taufan. Sampai beberapa detik, tak ada reaksi.
"Taufan."
Barangkali kebetulan, saat Halilintar dan Gempa tanpa sengaja memanggil bersamaan, Taufan membuka matanya perlahan. Kelegaan luar biasa sontak memenuhi dada kedua saudaranya, hingga terwakili di dalam senyum yang terlukis tipis. Untuk beberapa saat, wajah Taufan tampak berkerut. Seperti merasa terganggu oleh sesuatu.
"Kenapa? Rasanya nggak nyaman, ya?" Halilintar berkata lembut. "Tahanlah sebentar. Alat-alat ini belum boleh dilepas."
"Taufan, tenanglah," tambah Gempa. "Kami di sini menjagamu."
Kata-kata Halilintar dan Gempa, sebagaimana keberadaan mereka yang begitu dekat, membuat Taufan perlahan tenang kembali. Sampai dokter datang untuk memeriksa keadaannya. Halilintar dan Gempa harus keluar tak lama seperti itu, supaya Taufan bisa beristirahat. Namun, kali ini mereka sudah merasa lebih lega.

Senin siang, Sekolah Menengah Atas Pulau Rintis.
Sesuai saran Tok Aba, hari ini Halilintar dan Gempa masuk sekolah seperti biasa. Hari sebelumnya, keduanya terus menjaga Taufan bergantian dengan sang kakek. Kondisi Taufan semakin membaik dari waktu ke waktu, tetapi Halilintar tetap saja merasa khawatir. Dia yakin, Gempa juga pasti merasakan hal yang sama.
"... lintar ..."
Bagaimana keadaan Taufan sekarang? Apa dia masih di ICU?
"... Halilintar?"
Sejak semalam, Tok Aba yang menjaga Taufan bersama Ochobot. Dan beliau cuma sempat pulang sebentar. Kasihan Atok, pasti capek, 'kan?
"BoBoiBoy Halilintar!"
Halilintar tersentak kaget saat tiba-tiba mendengar namanya dipanggil. Nama lengkap, pula. Jarang-jarang dirinya dipanggil seperti itu. Dan suara tadi begitu dekat—
Eh? Cikgu sejarah?
"Kamu tidak mendengarkan pelajaran Cikgu sejak tadi," Guru muda berhijab itu berkata tanpa menaikkan nada suara. Entah sejak kapan, ia sudah berdiri tepat di samping meja Halilintar.
"Maafkan saya, Cikgu."
Halilintar menundukkan kepala begitu sadar dirinya ada di mana. Ini ruang kelasnya, dan mereka sedang mengikuti mata pelajaran terakhir untuk hari ini. Mendengar ucapan Halilintar yang penuh penyesalan, sang guru tersenyum tipis. Maklum dengan keadaan anak didiknya.
"Cikgu paham, kamu pasti memikirkan Taufan yang masih dirawat di rumah sakit," kata guru itu. "Cikgu bisa memberi izin kalau kamu dan Gempa ingin pulang lebih awal. Hari ini tidak ada tes. Dan materi kita tidak terlalu sulit. Kalian bisa mempelajarinya sendiri di rumah."
Halilintar agak terkejut dengan tawaran itu. Ia pun saling melempar pandang sejenak dengan Gempa yang duduk terpisah tiga meja darinya. Adik bungsunya itu hanya tersenyum tipis.
"Tidak perlu, Cikgu. Sebentar lagi juga sudah jam pulang sekolah." Halilintar kembali memandang gurunya. "Maaf. Saya akan memerhatikan pelajaran setelah ini."
"Baik." Guru sejarah itu tersenyum sekali lagi, baru kemudian kembali ke depan kelas. "Kita lanjutkan pelajarannya. Buka buku kalian di halaman 45 ..."
Halilintar berusaha fokus sepanjang sisa jam pelajaran, walaupun tidak mudah. Bagaimana bisa, kalau pikirannya terus-menerus melayang kepada Taufan? Namun, pada akhirnya dia bisa juga melewati jam terakhir dengan selamat. Sampai tiba waktu pulang sekolah.
"Kalian mau langsung ke rumah sakit?" Yaya yang duduk tepat di depan Halilintar, melontarkan pertanyaan itu ketika melihat Gempa menghampiri kakaknya.
"Nggak, Yaya," Gempa yang menjawab. "Kami pulang dulu. Ganti baju, makan, terus istirahat sebentar."
"Taufan sudah bisa dijenguk belum?" Yaya bertanya lagi, sementara beberapa teman sekelas mereka ikut mendekat.
Halilintar menggeleng pelan. "Taufan masih di ICU. Hanya keluarga yang diizinkan masuk."
"Kalau mau jenguk nanti saja, setelah Taufan keluar dari ICU," Gempa menambahkan. "Atau sekalian, kalau dia sudah boleh pulang."
"Kalau begitu, titip salam untuk Taufan. Semoga dia cepat sembuh."
"Aamiin," Halilintar dan Gempa menyahut bersamaan, diikuti beberapa teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan mereka.
"Thanks, Yaya," tambah Halilintar sambil tersenyum tipis.
Yaya tersenyum lembut. Dia sedikit merona saat menyadari Halilintar menghindari tatapannya. Apalagi, wajah pemuda itu juga tampak memerah walaupun samar.
Sementara itu, Gempa hanya tersenyum kecil menyadari kecanggungan tiba-tiba di antara kakaknya dan Yaya.
"Ya sudah," kata Gempa kemudian. "Kami duluan, ya?"
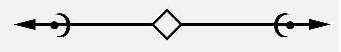
Halilintar tak menyangka akan mendapati kejutan yang melegakan hari itu. Waktu dia dan Gempa datang ke rumah sakit, ternyata Taufan sudah tidak berada di ICU. Tepatnya, sudah dipindahkan ke sebuah ruang rawat inap kelas V.I.P.
Ruangan itu cukup luas dan sangat nyaman. Bahkan ada sebuah sofa panjang di dekat pintu. Keluarga yang menunggui pasien bisa menggunakannya untuk istirahat.
Halilintar duduk sendirian di sofa itu. Gempa sedang ke toilet. Dan si pemilik iris merah delima tak melakukan apa pun sejak tadi, selain memandangi Taufan dari jauh. Anak itu masih tidur di ranjangnya. Tubuhnya sudah tidak dipasangi selang infus, masker oksigen, atau alat apa pun lagi. Sampai saat ini, dia sempat bangun beberapa kali. Namun, setiap terbangun, anak itu tidak mengatakan apa-apa. Halilintar diam-diam merasa cemas, tetapi Gempa menenangkannya dengan mengatakan, mungkin Taufan masih butuh banyak istirahat.
Entah tertarik oleh apa, tiba-tiba Halilintar beranjak. Ia mendekat sampai berdiri tepat di sisi ranjang Taufan. Sambil terus menatap wajah tidur sang adik, dia mengulurkan tangan perlahan. Maksud hati ingin mengelus rambut Taufan yang sedikit berantakan, tetapi gerakannya terhenti.
Ternyata ia memang masih takut menyentuh anak itu.
Set.
Halilintar tersentak ketika seseorang tiba-tiba memegang tangannya yang terulur. Lantas mendorongnya tanpa peringatan, sampai benar-benar menyentuh kepala Taufan.
"Gempa?" Halilintar berkata setelah menoleh untuk melihat siapa yang melakukannya.
"Tidak apa-apa." Gempa tersenyum lembut. "Tanganmu ini ... juga sudah menyelamatkan banyak orang. Termasuk Taufan."
Mata Halilintar berkaca-kaca sejenak, sebelum ia kembali beralih menatap Taufan. Diusapnya rambut anak itu dengan lembut. Disertai harapan, sang adik akan segera pulih seperti sedia kala. Tersenyum dan tertawa lagi. Atau bahkan bertengkar dengannya. Apa pun itu, asalkan dia baik-baik saja.
"Taufan?"
Halilintar tersentak kecil ketika Gempa yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba memanggil nama Taufan. Dilihatnya, anak itu membuka matanya perlahan.
"Taufan?" Halilintar ikut memanggil.
Sampai beberapa detik, tampaknya Taufan tidak bereaksi terhadap suara Halilintar maupun Gempa. Ia mengedarkan pandang, terlihat sedikit bingung.
"Ini ... di mana ...?"
Untuk pertama kalinya sejak dirawat di rumah sakit, akhirnya Taufan bersuara. Masih terdengar lemah, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk menenangkan hati kedua saudaranya.
"Kau ada di rumah sakit," Halilintar yang menjawab.
"Rumah sakit ...? Aku ... kenapa?"
"Kau tidak ingat? Kau terluka karena—"
"Hali," tiba-tiba Gempa memotong ucapan kakak sulungnya.
Halilintar menoleh sejenak dan mendapati Gempa menggeleng pelan.
"Taufan," Gempa mengambil alih pembicaraan yang terputus. "Jangan memikirkan apa-apa dulu. Yang terpenting sekarang adalah kesembuhanmu. Oke?"
Taufan memandang Gempa dalam diam, sebelum mendadak berusaha bangkit. Kedua saudaranya tentu saja kaget dan melarang, tetapi tidak didengarkan. Akhirnya mereka mengalah, lalu membantu mengatur posisi tempat tidur agar Taufan bisa duduk bersandar dengan nyaman.
Setelah itu, ruangan hening. Taufan hanya diam sambil terus memandangi Halilintar serta Gempa.
"Taufan?" Rupanya Gempa tidak tahan lagi untuk terus diam. "Kenapa melihat kami seperti itu?"
"Kau baik-baik saja, 'kan, Taufan?" Halilintar mulai cemas lagi.
Sepasang iris safir itu masih tak lepas menatap kedua sosok di hadapannya bergantian. Sorot mata yang begitu bening. Namun, Halilintar merasakan seperti ada sesuatu yang aneh. Begitu pula Gempa.
"Taufan?" Akhirnya pemuda berpembawaan ceria itu bicara juga. "Siapa itu Taufan?"
DEG!
Satu desiran tajam menghantam dada Halilintar. Ia yakin, Gempa juga merasakan hal yang sama. Apa ... Apa yang dikatakan anak itu ...?
"Kalian siapa?"
Satu pertanyaan lagi terucap begitu saja dari bibir yang masih sedikit pucat itu. Kedua matanya masih menatap Halilintar dan Gempa. Polos dan penuh tanya.
"Ka ... Kau ini bicara apa?" Halilintar merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Taufan itu namamu!"
"Namaku?"
Halilintar terdiam. Taufan terus menatapnya sejak tadi, tetapi tatapan itu terlalu tenang—entahlah. Terlalu ... polos. Tak tahan lagi dengan gejolak di hatinya, Halilintar meraih kedua bahu sang adik.
"Taufan, kau—" Ucapan Halilintar terputus. Ada satu pertanyaan di ujung lidah yang—jujur saja—takut diucapkannya. "Kau ... tidak ingat kami?"
Taufan hanya menggeleng. Tatapannya tampak bingung.
Halilintar menggeretakkan rahang. Tanpa sadar ia mencengkeram bahu Taufan lebih keras, sehingga yang bersangkutan tersentak kaget.
"Taufan!" Halilintar berkata lagi, setengah panik. "Kau ... Kau ... tidak ingat aku?!"
Taufan menggeleng lagi, kali ini lebih pelan. Ia mulai kelihatan gelisah, mungkin karena melihat reaksi Halilintar barusan.
"Hali, tenanglah!" Tiba-tiba Gempa menarik Halilintar mundur. "Kamu membuatnya takut."
Halilintar memandang Taufan sekali lagi. Anak itu masih memandanginya dan Gempa bergantian. Tampak lebih bingung daripada sebelumnya. Melihat itu, Halilintar menarik napas panjang. Gempa benar, dia tidak boleh panik. Apalagi di depan Taufan.
"Kenapa dia, Gempa?" Halilintar lebih mendekatkan diri kepada Gempa sambil merendahkan suaranya.
Gempa mengangkat bahu. "Kata dokter waktu itu, mungkin Taufan mengalami benturan di kepalanya, 'kan? Mungkin karena itu ...?"
"Apa ...?" Halilintar menggeleng pelan, tampak sedih. "Maksudmu ... dia ... hilang ingatan?"
"Jangan panik dulu." Gempa berusaha menenangkan kakak sulungnya, walaupun dia sendiri sebenarnya juga khawatir. "Mungkin ini cuma sementara."
"Apa kita panggil dokter saja sekarang?"
Gempa diam sebentar, mempertimbangkan usul Halilintar. "Yah ... kurasa sebaiknya begitu—"
"Uph ..."
Kata-kata Gempa terputus ketika tiba-tiba terdengar tawa tertahan. Dia dan Halilintar spontan menoleh ke sumber suara. Taufan, tampak kaget ditatap tiba-tiba. Ia seperti berusaha mengembalikan ekspresi wajahnya seperti semula, tetapi tidak terlalu berhasil.
"Barusan kamu ketawa?" tanya Gempa.
"Nggak."
Jawaban yang terlalu cepat, sementara Taufan berusaha mengalihkan pandang. Semakin jelas dia memang berusaha menahan tawa, yang gagal total tak lama kemudian.
"Hahaha ... Muka kalian lucu banget ...!" Taufan berkata sambil memandang saudara-saudaranya lagi. Tawanya belum berhenti, walaupun ia juga seperti berusaha menahan diri agar tidak tertawa terlalu keras. Mungkin karena luka di perutnya.
Gempa bengong. Halilintar tidak jelas ekspresinya, entah mau menangis, tertawa, atau malah marah.
"Taufan?!" Akhirnya Gempa bisa bersuara lagi setelah terbebas dari shock. Nada suaranya antara memprotes tetapi juga lega. "Yang tadi itu iseng?!"
Taufan tersenyum lebar. Senyum khasnya yang biasa.
"Wajah kalian tegang banget, sih!" katanya kemudian, yang kembali disambung tawa kecil. "Hahaha ... Aduh ..."
Mendadak tawa Taufan terhenti, sementara ia memegangi daerah sekitar perut.
"Tuh, kan ..." Gempa berkata, tak urung merasa cemas. "Kenapa? Lukamu sakit lagi?"
"Hehe ... Nggak apa-apa, kok ..."
Gempa menarik napas lega. "Dasar! Kalau lukamu terbuka lagi, gimana? Udah, jangan ketawa!"
"Iya, iya. Tapi mukamu jangan cemberut gitu, dong."
"Habisnya ..."
"Aku cuma mau menghibur kalian dengan lelucon kecil—"
"Nggak lucu." Taufan tersentak ketika ucapannya mendadak dipotong dengan dingin. "Sama sekali nggak lucu."
Halilintar yang barusan bicara, tampak menundukkan kepala dalam-dalam. Seolah hobinya adalah menyembunyikan wajah di balik lidah topi.
"Ha-Hali—"
"Aku dan Gempa sangat mencemaskanmu!" Halilintar memotong ucapan Taufan dengan nada membentak, membuat anak itu tersentak kaget.
Saat itu juga, Halilintar mengangkat wajahnya kembali. Sepasang iris merah delima itu menatap teramat tajam. Taufan langsung ciut. Ditatapnya Gempa dengan isyarat meminta bantuan, tetapi adiknya itu hanya membalas dengan tatapan tuh-kan-Hali-marah. Akhirnya, Taufan hanya bisa pasrah, memberanikan diri menghadapi kemarahan sang kakak.
"Sorry ... Aku cuma bercanda ... Hehe ..." Taufan masih tertawa kecil, walaupun kali ini terdengar canggung.
"Jangan cengar-cengir nggak jelas kalau aku sedang memarahimu!"
Halilintar masih membentak. Namun, Taufan bisa melihat tangan kakaknya yang terkepal, tampak bergetar samar. Ia pun mulai merasa tidak enak hati.
"Maafkan aku ..."
Kali ini Taufan berkata dengan ekspresi yang lebih serius. Halilintar yang melihat adiknya tampak menyesal, akhirnya menghela napas pelan.
"Dasar!" kata Halilintar kemudian. Masih ada kesal tertinggal di dalam suaranya, tetapi mungkin hanya sedikit. "Ada hal yang boleh dibuat bercanda, dan ada yang tidak. Kau juga harus tahu tempat dan waktu!"
Taufan menunduk, membiarkan Halilintar mengomelinya panjang lebar.
"Kau ini ... selalu saja main-main! Ada lagi ... Kau itu suka bicara dan berbuat tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain!" Omelan Halilintar tampaknya jadi melebar. "Dan juga ... jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hatimu! Jangan tertawa kalau kau tidak ingin tertawa."
"Eh?" Taufan mengangkat wajahnya kembali.
"Jangan tersenyum kalau dalam hati sebenarnya kau menangis," Halilintar masih melanjutkan ucapannya. "Kalau ingin marah, marahlah. Kalau perlu, hajar saja orang yang sudah berani menyakiti hatimu! Termasuk aku ..."
Taufan memandang Halilintar dengan mata berkaca-kaca. Hatinya telah diliputi haru sejak beberapa detik yang lalu. Namun begitu, entah kenapa ekspresi Halilintar kembali mengeras.
"Kau ini—!"
Taufan kaget ketika tiba-tiba Halilintar mengulurkan tangan ke arahnya. Ekspresi sang kakak yang kembali terhias amarah, membuatnya spontan memejamkan mata. Rasanya tidak mustahil Halilintar akan memukulnya atau apa. Namun, sampai beberapa detik lewat, Taufan tak merasakan apa pun.
Dan di hadapannya, Halilintar terdiam. Tangannya masih setengah terulur, terhenti di tengah jalan. Akan tetapi, begitu melihat Taufan membuka mata, ia kembali bergerak secepat kilat.
Tuk.
"Aduh!" Taufan tak sempat berbuat apa-apa ketika Halilintar menyentil dahinya tiba-tiba. "Uuh ... Sakiit ..."
Taufan masih mengusap-usap keningnya. Tidak sesakit itu sebenarnya. Sebaliknya, dia justru merasa lega. Entah kenapa, rasanya kebekuan di antara dirinya dan Halilintar perlahan mencair. Rasanya begitu hangat di dalam dada, sehingga Taufan tanpa sadar tersenyum tipis. Bukan senyuman iseng yang lebar, tetapi senyum kecil yang lahir karena dia benar-benar merasa bahagia.
"Eh? Hali?"
Taufan terkejut ketika mendadak Halilintar kembali menunduk dalam-dalam setelah menatapnya lama. Satu hal yang tidak diketahuinya, Halilintar pun merasakan hal yang sama. Bahwa dadanya telah dipenuhi kehangatan sampai sesak rasanya. Tetapi bukan dalam artian yang buruk.
Sungguh, bukan.
"Ha-Hali? Kamu nangis?!"
Tapi rasanya memang sesak sekali.
"Eh ... So-Sorry ... Aku nggak bermaksud membuatmu sedih ..."
Begitu sesaknya, sampai sebutir air mata tak sanggup lagi ditahannya.
"Heei ... Aku 'kan sudah minta maaf ..."
Nggak keren banget ... Masa' seorang Halilintar menangis?
"Gempaa ... gimana ini? Tolongin, dong ..."
Yah, tapi ... tidak buruk juga.
Terdengar suara tawa Gempa di ruangan serba putih itu. Taufan memprotesnya, tetapi Gempa tetap tertawa. Sementara, Halilintar masih membiarkan sisa-sisa air mata terakhir itu mengalir. Dan entah kenapa, hatinya terasa sangat lega. Di sini, di tempat yang tak pernah terpikirkan olehnya ini. Akhirnya dia bisa mendapatkan kembali salah satu hartanya yang hilang.
Dengan lembut, Halilintar terus menatap kedua adiknya yang masih sibuk sendiri, belum menaruh perhatian padanya lagi. Merekalah penyemangatnya, alasannya untuk berjuang, bahkan penyelamatnya. Cahaya di dalam hidupnya. Cahaya kecil yang takkan pernah membiarkannya jatuh di dalam kegelapan.
"Hali!"
Seruan Taufan membuat Halilintar tersentak. Akhirnya anak itu menyadari bahwa kakaknya sudah mengangkat wajah lagi. Dia memandangi wajah Halilintar dengan ekspresi khawatir.
"Ka-Kamu baik-baik aja?" Taufan agak bingung apa yang harus dikatakannya. Sementara Halilintar terus memandangnya dalam diam dengan ekspresi tak terbaca. "Hali?"
"Taufan ..."
Sepasang iris merah delima itu kembali berkaca-kaca sejenak. Kemudian—tak terduga—Halilintar mendekat ke sisi Taufan. Sangat dekat, sampai dia bisa memeluk adik yang sudah lama diabaikannya.
Dirindukannya.
"Ha ... li?"
Taufan terdiam. Bingung. Lantas berpikir apa dirinya sedang bermimpi. Setelah itu, dia tidak tahu harus berpikir apa lagi.
Tapi, Halilintar sedang memeluknya. Dan ia tahu, kehangatan yang sangat dekat ini nyata.
"Hali ..."
Taufan membalas pelukan itu. Dia sangat merindukannya. Dia sangat merindukan kakaknya. Semua kerinduan tertumpah dalam satu pelukan hangat. Dan juga air mata yang kemudian mengalir dari kedua mata berhias iris safir itu.
"Hali ... aku menyayangimu ..."
Mungkin Taufan tidak bisa melihatnya. Namun, saat ini kedua mata Halilintar pun berkaca-kaca. Bahkan ia membiarkan satu bulir air mata lagi mengalir turun.
"Maafkan aku, Taufan. Aku juga ... sayang padamu ..."
Kakak beradik itu tak melepaskan pelukannya sampai lama sekali. Sampai air mata mereka mengering, dan tergantikan oleh senyuman di bibir masing-masing. Senyum bahagia yang sama dengan milik Gempa, yang sejak tadi terus memandang kedua saudaranya penuh haru.
Dada mereka bertiga disesaki oleh satu perasaan yang sama. Rasa sesak yang membuat mereka ingin menangis sepuasnya. Akan tetapi, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Yang bernama 'bahagia'.
SELESAI
Layaknya Cahaya Kecil; Heidy S.C. 2017©
BoBoiBoy; Animonsta Studio 2011-2016©
====================================================
Trivia:
Perbedaan UGD, IGD, dan ICU
Pada dasarnya, UGD dan IGD memiliki fungsi yang sama. Yaitu untuk menangani pasien dengan penyakit atau luka serius yang membahayakan nyawa, serta memerlukan penanganan secepatnya.
Unit Gawat Darurat/UGD biasanya ada di rumah sakit kecil sampai sedang. Dokter yang berjaga 24 jam di UGD adalah dokter umum.
Sedangkan Instalasi Gawat Darurat/IGD biasanya terdapat di rumah sakit besar. Ada dokter dengan empat keahlian besar yang berjaga selama 24 jam di IGD. Mulai dari ahli kebidanan, ahli anak, ahli penyakit dalam, dan ahli bedah.
Pasien UGD/IGD yang telah stabil bisa dipindahkan ke Intensive Care Unit/ICU atau Ruang Rawat Intensif.
====================================================
Author's Corner

Halooo~! \(^o^)
Akhirnyaaa~bisa juga nulis adegan yang sudah kurencanakan sejak mulai menulis chapter 1. Dan hasilnya sesuai keinginanku. Adegan terakhir yang menyenangkan, bukan? Hehe ... :") *happy*
Anyway~aku sangat senang, fanfic "Layaknya Cahaya Kecil" bisa selesai dengan selamat. Terlebih bisa rutin update nyaris seminggu sekali! Yah, kalau aja waktu itu aku nggak sakit sehingga harus libur update sekali (sebelum bagian kedua arc Halilintar).
Akhir kata, Taufan memang TERBAIK~! Hahaha ... Selamat, Nak! Kamu sudah membuktikan lewat ending ini, bahwa LCK bukan cerita angst (harusnya). Maaf para pembaca yang budiman, kemarin-kemarin tuh saya rada khilaf. Pas adegan sedihnya agak keterusan, jadi angst,deh~ :"D *plak*
/padahal seneng nulisnya
Oke, semuanya~! Sampai jumpa di fic-ku yang berikutnya (mudah-mudahan ada, hehe ...). Oya, minggu depan masih ada Epilog. Rencananya nggak terlalu panjang, tungguin aja kalau masih berminat. :")
Solo, 23 September 2017
Heidy S.C.
====================================================
Mulmed:
BoBoiBoy "The Original Trio" fanart by Aruella
https://alezz1a.deviantart.com/art/The-Original-Trio-622349427
Kunjungi akun DeviantArt Aruella untuk gambar-gambar indah nan menghangatkan hati lainnya. ^_^

Nyaris saja, aku kehilangan orang-orang yang paling berharga di dalam hidupku. Bukan karena ada seseorang atau sesuatu yang merampasnya. Semua karena kesalahanku sendiri. Taufan dan Gempa, adik-adikku yang mencintaiku tanpa syarat. Lalu ... Yaya. Aku tidak pernah mengerti kalau selama ini dia memerhatikanku, dengan caranya sendiri.
Anugerah itu mungkin terlalu indah untuk kumiliki. Tapi ... sekarang aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Aku tenggelam di dalam prasangka, dan melupakan kebaikan hati mereka.
Padahal, jauh di lubuk hati, aku tahu ... mereka menyayangiku. Dan aku juga sangat menyayangi mereka.
Cahaya-cahaya kecilku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top