Gempa: Yang Melindungi, Yang Dilindungi (2/2)
Gempa berlari menuju halaman belakang sekolah. Yaya mengikutinya dari belakang. Bahkan sampai detik ini pun, ia masih tak percaya pada pendengarannya. Tidak sebelum dia melihatnya sendiri.
Halilintar dan Taufan berkelahi?!
Itulah yang dikatakan Yaya tadi. Bagaimana bisa? Gempa tak habis mengerti. Ia tahu, sejak dulu hubungan kedua kakaknya memang 'unik'. Mereka adalah dua pribadi yang bertolak belakang, tak pernah bisa akur. Namun, Gempa juga tahu, keduanya saling menyayangi, walau tak pernah diungkapkan. Hanya, hubungan mereka memang merenggang sejak 'kejadian itu'. Dan mereka seperti menjaga jarak.
Karena itulah, aneh kalau tiba-tiba mereka berkelahi. Masih di area sekolah, pula! Bukan berarti mereka tidak pernah berkelahi sebelumnya. Seperti saat pertama kali Taufan membangkitkan kekuatan sejatinya. Dia lepas kendali, sehingga Halilintar terpaksa coba menghentikannya dengan kekerasan.
Oke, itu beda. Gempa menggelengkan kepala. Kebiasaan buruknya kalau sedang panik, pikiran pasti melantur ke mana-mana. Ah, sebentar lagi sampai ke halaman belakang.
"Tombak Halilintar!"
"Cakhra Udara!"
"BERHENTI!!"
Tepat ketika kedua serangan itu akan dilepaskan, Gempa berteriak. Ternyata suaranya mampu menghentikan pertarungan. Baguslah, setidaknya Halilintar dan Taufan masih mau mendengarkannya.
"Hali! Taufan! Ada apa ini?" Gempa mendekati kedua saudaranya. Sedangkan Yaya memilih tinggal, agak jauh di tepi. "Kenapa kalian berkelahi?"
"Gempa?" Taufan menyahut lebih dulu.
"Jangan ikut campur!" Halilintar menyentak.
"Aku pasti akan ikut campur!" Gempa menatap mata kakak-kakaknya dengan sorot yang tak kalah keras. "Apa-apaan serangan tadi itu? Kalian mau saling bunuh? Hah?!"
"Cih!" Halilintar melenyapkan tombak yang berkilat-kilat merah di tangannya. Cakhra udara Taufan juga sudah batal dikeluarkan. Diam-diam Gempa menarik napas lega. Bagaimanapun mengeluarkan kedua senjata elemental sekuat itu memang sudah berlebihan.
"Sudah kubilang, jangan ikut campur," Halilintar berkata dingin.
"Minggir, Gempa. Biar kuberi pelajaran manusia satu ini!"
Gempa terpana. Apa benar barusan Taufan yang bicara? Namun, ia tak sempat berpikir lebih lanjut. Kata-kata seperti itu sudah jelas akan menyulut amarah Halilintar lebih jauh.
"Apa katamu?!"
Tuh, 'kan.
"STOP!" Gempa mengeluarkan nada suara paling tegas yang dimilikinya. "Sekarang jelaskan padaku, ada apa?"
Halilintar mendengus.
"Aku hanya bertanya soal—" Kata-kata ini terputus ketika Halilintar menangkap sosok Yaya dari sudut matanya. Gadis berhijab pink itu sedang berdiri di bawah pohon, agak jauh di pinggir halaman luas ini. "Aku hanya bertanya. Dia saja yang bereaksi berlebihan."
Taufan tertawa kecil. Sinis, berbeda dengan tawanya yang biasa. "Aku atau kau yang berlebihan? Dengar. Selama ini aku diam saja. Tapi asal kau tahu, Hali—" Taufan mengucapkan nama saudaranya dengan cara yang tidak menyenangkan, "—aku sudah muak dengan segala keegoisanmu itu!"
"Hoo ... Berani kau sekarang bicara seperti itu padaku?!"
"Huh! Kenapa mesti takut?"
Ekspresi Halilintar mengeras. Sorot matanya pun menajam. Kilatan-kilatan merah tampak menari-nari di jemarinya. Taufan yang menyadari itu pun diam-diam bersiaga. Suasana tenang mendadak menyelimuti tempat itu. Namun, Gempa—bahkan juga Yaya—bisa merasakan sesuatu yang buruk akan segera datang.
"Hoverboard Taufan!"
"Pedang Halilintar! Gerakan Kilat!"
Taufan menang sedetik untuk mendahului apa pun serangan yang mungkin datang dari kakaknya. Namun, itu nyaris tak ada artinya di hadapan kecepatan Halilintar. Selanjutnya, Gempa hanya bisa melihat kilasan-kilasan merah dan biru saling beradu. Berpindah-pindah dengan kecepatan luar biasa di seantero halaman belakang itu.
"Hali! Taufan! Berhenti!!" Gempa berseru sia-sia. Pemuda itu menggeretakkan rahang dengan tangan terkepal. Kalau seperti ini, ia takkan bisa berbuat apa-apa. Pertahanannya boleh jadi adalah yang terkuat, tetapi soal kecepatan, dia bukan tandingan Taufan. Apalagi Halilintar.
Bagaimana caranya dia bisa menghentikan mereka sekarang?
Selagi Gempa berbingung ria, tak terduga, kedua kakaknya justru berhenti. Taufan berdiri di sisi kanannya, jauh di tepi tanah lapang itu. Sedangkan Halilintar ada di sisi yang berseberangan, dengan sepasang pedang berkilat-kilat merah tergenggam di kedua tangan. Alih-alih lega, Gempa malah semakin cemas. Bagaimana tidak, kalau Halilintar maupun Taufan masih dalam posisi siaga tempur?
Sebelum kedua saudaranya bergerak lagi, Gempa—yang saat ini benar-benar merasakan firasat buruk—cepat-cepat memperkuat kedua tangannya dengan sarung tangan dari batuan magma hitam. Mengandalkan naluri, ia sudah berlari ke depan. Tepat ke arah tujuan Halilintar dan Taufan yang sama-sama memelesat ke tengah halaman. Siap untuk membenturkan kekuatan!
"Gerudi Taufan!"
"Tetakan Pedang Halilintar!"
Sang penguasa angin maupun petir hanya fokus kepada lawan di depan. Sama sekali tidak memerhatikan pergerakan Gempa. Karena itulah, keduanya sangat kaget ketika tiba-tiba Gempa ada di antara mereka. Sudah tak sempat membatalkan atau membelokkan serangan lagi!
DHUAG!!
Tak terelakkan, benturan tiga kekuatan terjadi di tempat itu. Bor angin Taufan membentur sarung tangan kanan Gempa, dan Pedang Halilintar tertahan oleh sarung tangan kiri sang penguasa elemen tanah. Gempa meringis samar, lantas mengerahkan segenap kekuatannya untuk menolakkan serangan-serangan itu ke dua arah berlawanan.
Taufan dan Halilintar sama-sama terdorong kembali ke belakang. Bahkan tolakan Gempa sebenarnya cukup kuat untuk membuat mereka terlempar jauh. Namun, pada akhirnya kedua pemuda itu mampu bertahan. Bor angin di tangan Taufan sudah menghilang, sedangkan Halilintar masih menggenggam kedua pedangnya.
BRUK.
Gempa jatuh terduduk. Napasnya tersengal. Benturan keras tadi telah menghancurkan sarung tangannya berkeping-keping. Sekaligus menguras staminanya. Tangan kanannya tergores-gores akibat gerakan angin tajam di sekitar bor angin Taufan. Sementara, listrik dari Pedang Halilintar membuat tangan kirinya gemetar kesemutan, sekaligus merasakan sakit yang tajam.
"GEMPA!!"
Suara teriakan Yaya seolah baru mengembalikan kesadaran Halilintar dan Taufan. Mereka melihat Yaya terbang memelesat ke arah Gempa secepat mungkin, lalu ikut berlutut di dekat pemuda itu.
"Gempa! Kamu nggak apa-apa?" Yaya bertanya cemas. Gempa masih tertunduk, tidak menjawab. Dengan ekpresi kemarahan yang tak ditahan-tahan, Yaya beralih menatap Halilintar dan Taufan bergantian. "APA YANG KALIAN LAKUKAN?!"
Taufan terdiam dengan mata berkaca-kaca. Halilintar tersentak, baru sadar dirinya masih menggenggam pedang. Cepat-cepat dilenyapkannya benda itu.
"Sakit."
Satu kata terucap lirih dari mulut Gempa. Halilintar dan Taufan sama-sama merasakan desiran tajam di dada mereka. Sesaat, keduanya bingung harus berbuat apa.
"Ge-Gempa—"
"Sudah, cukup," Gempa menyela ucapan Taufan. Ia berdiri perlahan, dibantu oleh Yaya. Tak mau menatap kedua kakaknya. "Aku ... Aku nggak mau tahu lagi. Terserah kalian saja."

Gempa masih duduk diam di sofa ruang tamu rumahnya. Yaya pun masih ada bersamanya dalam diam yang sama. Sore sudah hampir menjelang, sebentar lagi Tok Aba dan Ochobot pasti akan pulang. Akan repot menjelaskan kondisi Gempa kepada mereka nanti. Sedangkan Gempa masih tampak terpukul atas kejadian yang baru saja menimpa dirinya.
"Gempa?" Yaya berkata hati-hati. "Kamu butuh sesuatu?"
Yang ditanya tersentak kecil. "Nggak. Makasih sudah menemaniku, Yaya. Aku ... mau istirahat di kamar. Kamu pulanglah."
Gempa bangkit dari duduknya. Namun, saat hendak beranjak, tubuhnya seketika limbung.
"Gempa!"
Dengan sigap, Yaya masih sempat menahan tubuh Gempa agar tidak jatuh. Gadis pengendali gravitasi itu menatap Gempa dengan raut wajah dipenuhi kekhawatiran. Ia maklum, menahan dua serangan sekaligus dari Halilintar dan Taufan, bagaimanapun juga terlalu berat bagi Gempa.
"Aku antar ke kamarmu, ya?" kata Yaya kemudian.
"Nggak usah, Yaya. Aku bisa sendi—"
"Nggak, nggak. Gimana nanti kalau kamu jatuh pas naik tangga?" Gempa sudah mau membantah, tetapi di saat seperti ini, Yaya bisa lebih keras kepala dibandingkan Halilintar sekali pun. "Pokoknya kutemani! Cuma sampai di depan pintu, 'kok. Masa' iya aku ikut masuk?"
Gempa tersenyum spontan. Apa Yaya sedang mencoba melucu untuk mencairkan suasana?
"Eh? Lho? Gempa ... kamu demam?"
"Ng?"
Gempa menatap Yaya. Gadis itu sedang mengulurkan tangan, tanpa permisi menyentuh dahinya dengan telapak tangan kanan.
"Tuh 'kan, benar. Kamu demam!" Yaya menarik tangannya kembali, lalu menatap mata Gempa. "Sejak kapan? Kamu nggak ngerasain apa-apa?"
"Aku nggak—" Gempa urung menyelesaikan kalimatnya, ketika tatapan tajam Yaya tak mau beralih darinya. "Mm ... Memang agak pusing. Sedikit. Ini bukan apa-apa, 'kok. Kurasa cuma mau flu. Mungkin gara-gara semalam aku nggak bisa tidur."
"Ya udah, kamu duduk dulu!" Yaya mendorong pelan tubuh Gempa hingga terduduk kembali di sofa. "Sebentar, aku bikinin obat. Dijamin manjur, deh. Pinjam dapurmu, ya!"
"Eh, Yaya ... nggak u—" Yaya sudah memelesat ke arah dapur tanpa menoleh ke belakang lagi. "—sah ..."
Pada akhirnya, Gempa hanya bisa menghela napas. Lantas, direbahkannya tubuh ke sandaran sofa, mencoba untuk rileks. Di saat sendirian seperti ini, ia jadi memikirkan banyak hal. Lagi. Apa yang dilakukan Halilintar dan Taufan sekarang? Apa mereka benar-benar melanjutkan pertarungan setelah itu? Jangan-jangan malah sudah saling bunuh?
Ah ... Gempa merasa kepalanya semakin pusing.
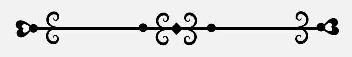
"... pa? Gempa?"
Gempa membuka mata perlahan. Iris keemasannya yang agak suram, tampak menampilkan pantulan sosok Yaya. Gadis itu duduk di sofa yang sama dengannya, tepat di sisi kirinya. Gempa melihat cangkir porselen di tangan kanan Yaya.
"Nih, obatnya sudah jadi." Yaya mengangsurkan cangkir kecil itu ke tangan Gempa. Sama sekali tak mengungkit soal Gempa yang sepertinya sempat terlelap sesaat.
"Obat apa ini?" Gempa mengerutkan kening. Diperhatikannya cangkir berisi cairan cokelat keruh beraroma tajam di tangannya. Dari bau dan warnanya, Gempa memperkirakan 'obat' itu dibuat dari jahe dan beberapa rempah-rempah lain. Ada aroma madu juga.
"Itu resep rahasia turun-temurun di keluargaku," Yaya berkata penuh kebanggaan. "Ampuh untuk mengobati masuk angin dan flu. Dijamin cepat sembuh, deh."
Gempa masih memandangi 'cairan misterius' di tangannya. Sejenak ragu, tidak apa-apakah memercayakan kesembuhannya di tangan seorang Yaya? Tangan yang sehari-hari sangat terampil memproduksi biskuit-biskuit cantik beraroma kematian.
"Kenapa nggak diminum?" Suara Yaya mengejutkan Gempa yang setengah melamun. "Memang agak pahit, sih. Namanya juga obat."
Gempa menghela napas pelan. Tahu bahwa Yaya benar-benar tulus mencemaskannya. Ia tidak suka membuat orang lain cemas karena dirinya. Tanpa berpikir lagi, segera diteguknya obat buatan Yaya. Rasa pedas jahe berpadu dengan pahit khas ramuan herbal. Gempa berusaha mengabaikan semua itu dan menelan seluruh isi cangkir sampai tandas.
"Gimana rasanya?" tanya Yaya seraya mengambil kembali cangkir kosong dari tangan Gempa.
"Rasa obat." Gempa cuma nyengir. "Tapi badanku rasanya jadi hangat. Makasih, ya."
"Sama-sama." Yaya tertawa kecil, kemudian berdiri. "Sebentar, ya. Aku mau kembalikan ini ke dapur dulu."
Gempa kembali bersandar ke sofa ketika Yaya menghilang secepat kilat menuju dapur. Dia yakin, gadis itu pasti akan sekalian mencuci cangkir dan semua perkakas kotor yang terpakai untuk membuat obat tadi.
"Eh?"
Sebelumnya, Gempa tidak menyadari sesuatu yang berbeda di kedua tangannya. Diperhatikannya, bekas-bekas luka kecil akibat sayatan angin dan setruman listrik, tampak telah terawat. Dioles dengan obat antiseptik, sepertinya. Pasti Yaya, pikir Gempa. Gadis berhijab itu ternyata sudah melakukan banyak hal selama ia tertidur sejenak.
Gempa tersenyum kecil. Dipejamkannya kedua mata, sambil menikmati rasa hangat yang berpusar di dalam tubuhnya. Ramuan herbal Yaya tampaknya benar-benar ampuh. Pada saat yang sama, Gempa juga merasakan kantuk mulai mengambil alih dirinya. Sulit untuk ditahan.
Ah ... Obat flu biasanya memang bikin ngantuk, ya ... Apa boleh buat, 'kan? Soalnya, obat paling mujarab untuk penderita flu memang istirahat yang cukup.
"Hei, Gempa ... kamu ketiduran lagi?" Suara yang masih dikenali Gempa sebagai milik Yaya, kembali menariknya dari alam mimpi. "Ayo, jangan tidur di sini. Kuantar ke kamarmu."
Antara sadar dan tidak, Gempa mengikuti arahan Yaya untuk bangkit, lalu berjalan ke kamarnya di lantai dua. Samar-samar, ia merasa Yaya memapahnya. Ah, bukan masalah. Walaupun Yaya perempuan, tapi kuasa gravitasi miliknya membuat gadis itu lebih kuat dari rata-rata manusia di planet ini. Gajah pun bisa diangkatnya tanpa meneteskan keringat.
"Gempa, aku pulang dulu, ya?"
"Hm ..."
Gempa masih sempat membuka mata saat Yaya berpamitan padanya. Meskipun kesadarannya tinggal beberapa persen saja. Sementara, ia bisa merasakan tubuhnya sudah terbaring di ranjang. Yaya masih mengatakan sesuatu setelah itu, tetapi Gempa sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Pemandangan terakhir yang dilihatnya adalah Yaya yang keluar kamar, lalu pintu kayu itu ditutup. Nyaris tanpa suara.
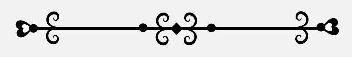
"Ng ..."
Gempa terbangun dengan badan yang terasa lebih ringan. Ia meregangkan tubuh sejenak, baru kemudian menengok ke jam dinding di atas meja belajarnya. Rasanya ia tidur cukup lama, tapi ternyata baru jam 4 sore. Gempa segera bangkit, lantas mengambil perlengkapan mandi dan baju ganti.
Pintu kamar Halilintar maupun Taufan tertutup rapat ketika Gempa melewatinya menuju tangga. Entah apakah kedua kamar itu kosong atau ada penghuninya. Gempa hanya mendesah pelan, melanjutkan langkah ke kamar mandi yang ada di lantai satu.
Tak sampai 15 menit, Gempa sudah selesai. Saat bermaksud kembali ke kamarnya, ia berpapasan dengan Ochobot yang tengah berada di ruang tamu.
"Gempa!" sang robot kuning berseru sambil melayang mendekat. "Lho, kamu sudah bangun? Kata Yaya kamu sakit, ya?"
Gempa tersenyum lembut. "Aku nggak apa-apa 'kok, Ochobot."
"Eh ... Gempa?" Saat menoleh ke sumber suara, Gempa melihat sang kakek, Tok Aba, tengah mendekatinya. Sepertinya beliau baru saja dari dapur. "Kamu sudah sehat, Nak?"
Tanpa menunggu jawaban, Tok Aba meletakkan telapak tangan kanannya di dahi Gempa.
"Gempa sudah mendingan 'kok, Atok," kata Gempa yang tak mau kakeknya cemas.
"Hmm ... Masih agak hangat." Tok Aba menarik tangannya kembali. "Kamu pusing?"
Gempa menggeleng. "Sekarang sudah enggak, Atok."
"Syukurlah, kalau begitu. Ya sudah, kamu kembali saja ke kamar, istirahat. Hari ini tidak usah bantu-bantu dulu di dapur."
Gempa ingin membantah, tetapi diurungkannya niat itu ketika melihat tatapan tajam Tok Aba.
"Oh, iya," tiba-tiba Gempa berkata sebelum beranjak. "Hali dan Taufan sudah pulang?"
"Halilintar sepertinya sudah pulang, tapi pergi lagi," Ochobot yang menjawab. "Kalau Taufan, nggak tahu. Aku belum melihatnya."
"Ooh ... Ya udah, Ochobot. Aku ke kamar, ya."

Entah sudah berapa lama Gempa hanya berdiam diri di dalam kamarnya. Pemuda itu berbaring-baring gelisah di kasur. Pikirannya tidak bisa tenang setiap kali teringat kedua kakaknya. Kamar sebelah—yang merupakan kamar Taufan—terlalu senyap. Gempa yakin 99% Taufan tidak ada di sana. Semua orang tahu, Taufan itu paling tidak bisa disuruh diam.
Ke mana mereka?
Gempa mendesah tanpa ditahan-tahan lagi. Ia lantas bangkit, duduk di tepi ranjangnya yang bernuansa cokelat keemasan dan hitam. Berlawanan dengan sifatnya, kali ini Gempa benar-benar melamun. Ia tidak bisa melupakan kejadian di halaman belakang sekolah. Iris keemasan itu berkaca-kaca, mengingat setiap rasa sakit yang diterimanya akibat menahan serangan Halilintar dan Taufan. Namun, dibandingkan itu, hatinya masih jauh lebih sakit.
Kenapa?
Satu kata itu memenuhi benak Gempa. Ia mengingat setiap detil kejadian yang belum lama berselang itu. Jelas sekali. Sorot mata Halilintar yang sempat dilihatnya, sangat dingin. Hampir seperti sorot mata sang kakak lima tahun silam, ketika dia sempat 'mengamuk'. Taufan juga sama, dia seperti kehilangan kendali diri. Lagi. Seperti saat kekuatan barunya lepas kontrol dahulu.
Tentu saja, kali ini tidak sama. Mereka berdua selalu saja begitu. Egois! Mereka hanya memikirkan diri sendiri, sama sekali tidak memandang dirinya. Padahal, dia—Gempa, adik mereka—selalu mengkhawatirkan kakak-kakaknya itu. Gempa selalu peduli pada Halilintar dan Taufan. Selalu ingin melindungi mereka. Tetapi, kenapa mereka tidak pernah mau menghargai usahanya?
Gempa lelah.
Tes.
Sebutir air mata lolos dari pelupuk mata kiri Gempa, lantas turun membasahi pipinya. Diusapnya aliran bening itu dengan kasar, tetapi butiran-butiran yang lain malah turun susul-menyusul. Gempa tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap, wajahnya telah basah oleh air mata. Dadanya terasa sesak, sementara ia menangis tanpa suara.
Iya, 'kan? Mereka memang jahat. Sampai kapan aku harus terus berada di antara mereka? Aku nggak bisa terus-terusan menjaga mereka. Aku cuma manusia biasa. Aku juga bisa merasa sakit!
Gempa terisak pelan. Di antara perasaannya yang kacau balau, ia masih bisa berpikir, kenapa tiba-tiba ia merasa seperti ini? Lantas, ia teringat kata-katanya sendiri kepada Halilintar dan Taufan.
Aku nggak mau tahu lagi. Terserah kalian saja.
Kenapa? Kenapa waktu itu mulutnya mengucapkan kata-kata yang demikian? Kenyataannya, itu sama sekali tidak benar. Tak mungkin seorang Gempa bisa tidak peduli kepada orang-orang yang disayanginya. Apalagi kedua saudara kembarnya. Mereka adalah separuh nyawanya. Seabsurd apa pun perilaku mereka, Gempa akan tetap menyayangi mereka dengan setulus hati. Melindungi mereka dengan seluruh jiwa raganya.
Lalu, kenapa kata-kata itu bisa terucap? Kenapa saat itu Gempa tak sanggup mengendalikan perasaannya? Sama seperti tangisnya yang kini meluap laksana air bah. Diam-diam, Gempa mulai merasa bersalah.
Tangis Gempa mulai surut, ketika matanya tertumbuk kepada foto di atas meja kecil di samping ranjang. Foto dirinya bersama Halilintar, Taufan, Tok Aba, dan Ochobot lima tahun lalu. Foto keluarganya. Lama hanya ditatapnya foto itu, sambil membiarkan air matanya mengalir bebas.
"Hali brengsek ... Taufan bodoh ... Taufan gila ..."
Gempa tercekat. Isakannya perlahan berubah menjadi tangisan nyata. Nyaris tanpa sadar, tangannya bergerak menampar foto berpigura kayu itu hingga jatuh ke lantai.
Prak!
Gempa memandangi foto yang terjatuh dengan gambar menghadap ke atas. Dibiarkannya air mata yang mengalir deras, tangis yang terkuras sampai habis. Sampai Gempa merasa lelah sendiri dan berhenti menangis. Setidaknya kini dia sudah merasa lebih lega.
Set.
Perlahan, Gempa mengambil foto itu. Lantas menaruhnya kembali di tempat semula. Dalam hati, Gempa bersyukur benda itu tidak rusak.
Tok. Tok. Tok.
Ketukan pelan di pintu kamarnya membuat Gempa tersentak. Sang pemilik kuasa elemen tanah itu menghapus sisa-sisa tangisan di wajahnya. Baru kemudian bangkit untuk membuka pintu.
"Eh? Taufan?"
Gempa menatap heran ke arah pemuda berpenampilan dominan biru di hadapannya. Kakak keduanya itu berdiri diam dengan kepala tertunduk. Tak perlu waktu lama, disadarinya getaran halus di tubuh Taufan.
"Ge ... Gempa ...," Taufan berkata ragu-ragu. Ia lantas mengangkat wajah, menatap Gempa dengan netra beriris safir yang tengah berkaca-kaca.
"Gempa!" Tiba-tiba Taufan menubruk Gempa, memeluknya erat. "Gempa ... maafin aku ... Maaf ..."
"Ta—Taufan?" Gempa nyaris kehilangan kata-kata. "Kamu kenapa?"
Taufan menggeleng kecil beberapa kali. Gempa pun mendengar sang kakak menangis. Masih sambil memeluknya.
"Aku tahu ... aku ... memang bukan ... kakak yang baik ...," Taufan bicara tersendat di antara tangisannya. "Aku memang bodoh ... Gila ... Selalu merepotkanmu ... Aku sudah menyakitimu ... Maaf ..."
"E—Eeh ...?" Gempa terdiam sejenak, lantas wajahnya memerah dengan cepat. "Kamu ... mendengar kata-kataku tadi? Ja ... Jangan-jangan ... kamu tadi ada di kamar ...?!"
Gempa bisa merasakan Taufan mengangguk pelan. Jadi, tadi Taufan mendengarnya menangis dan marah-marah tidak jelas?
"Gempa ... maaf kalau aku dan Hali manja ... Padahal kami kakakmu ... Harusnya ... kami yang menjagamu ... Bukan sebaliknya ..." Taufan masih bicara sambil terisak-isak. "Tapi ... aku ... sangat menyayangimu ..."
Gempa tersentak pelan. Sejenak, ia salah tingkah, sebelum sorot matanya melembut. Dasar! Kadang-kadang Gempa iri. Kenapa Taufan bisa segampang itu menunjukkan emosinya di hadapan orang lain? Perlahan, ia pun membalas pelukan Taufan.
"Ya sudah, kumaafkan. Aku ... Aku juga sayang kalian." Gempa melepaskan Taufan dari pelukannya. Rona merah tipis mewarnai pipinya sekejap, membuat Taufan hampir saja tertawa melihatnya. Iris keemasan Gempa lantas menentang pandangan Taufan dengan sorot yang lebih keras. "Tapi, kumohon ... jangan begitu lagi."
Taufan mengangguk pelan. "Aku janji."
Gempa tersenyum lega saat melihat Taufan menghapus sisa air mata di wajahnya. Sedetik kemudian, senyum cerah itu sudah kembali menghias wajah sang kakak. Senyum yang sangat disukai oleh Gempa.
"Oh iya ... Hali belum pulang, ya?" tiba-tiba Taufan bertanya.
Gempa mengangkat bahu. "Kata Ochobot, dia tadi sudah pulang, tapi pergi lagi."
Taufan terdiam entah kenapa. Sedangkan Gempa melihat jam di tangannya.
"Sudah setengah lima lebih," kata Gempa. "Aku jadi khawatir ..."
"Kurasa aku tahu Hali ke mana," Taufan menyahut. "Biar aku yang mencarinya."
"Aku ikut!"
"Nggak usah, Gempa. Kamu istirahat aja di rumah. Aku akan segera kembali."
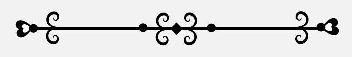
Aku akan segera kembali.
Ya, Taufan bilang begitu. Lima belas menit yang lalu. Gempa tidak tahu, apakah ini sudah terhitung 'terlalu lama' atau tidak. Mengingat Taufan maupun Halilintar bisa bergerak sangat cepat dengan kekuatan mereka. Yang jelas, saat ini kecemasan Gempa sudah sampai di ubun-ubun.
Nggak. Aku nggak bisa cuma diam menunggu!
Akhirnya Gempa beranjak juga dari kamarnya. Selepas dari tangga, ia melihat Tok Aba yang sedang bersantai bersama Ochobot sambil menonton TV di ruang tengah.
"Gempa?" Tok Aba menoleh saat Gempa mendekat untuk berpamitan. Sekali lihat saja, tampaknya sang kakek sudah mengerti bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran cucunya. "Ada apa, Nak?"
"Atok, Gempa ... mau mencari Taufan dan Hali," Gempa menjawab dengan jujur.
"Lho? Mereka belum pulang?" tanya Tok Aba.
"Tadi Taufan juga pergi mencari Halilintar," Ochobot yang menjawab. "Apa belum ketemu, ya ...?"
"Gempa, duduklah." Tok Aba memberi isyarat supaya Gempa duduk di sofa, di sebelahnya. "Kita tunggu saja sebentar lagi."
"Maaf, Atok ... tapi Gempa harus pergi," tolak Gempa. "Entah kenapa, perasaan Gempa tidak enak."
"Coba hubungi mereka lewat Jam Kuasa-mu," Ochobot memberi saran.
"Sudah kucoba, tapi nggak dijawab."
"Ya sudah, pergilah," Tok Aba yang paham perasaan sang cucu, akhirnya berkata. "Tapi kamu tenang dulu, ya?"
Gempa menarik napas panjang, hingga dadanya terasa lapang.
"Terima kasih, Atok. Gempa pamit dulu."
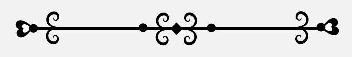
Hanya ada satu tempat yang terpikirkan oleh Gempa saat ini. Sebuah bukit yang hanya bisa dicapai dengan mengambil jalan pintas—yang sebenarnya adalah satu-satunya jalan—dari perkebunan karet. Dari sana, laut bisa terlihat dengan jelas. Juga matahari terbenamnya yang memesona. Gempa yakin, tempat inilah yang dimaksud oleh Taufan tadi.
Memang terbaik.
Pemandangan elok itu masih memukau Gempa ketika ia melangkahkan kakinya lagi ke sana. Rasanya sudah lama sekali ia tidak ke tempat itu. Bukit itu. Bukit kesayangan mereka bertiga.
Seperti baru kemarin terjadi, kenangan berputar cepat di benak Gempa. Ia 'menemukan' bukit hijau ini bersama dengan Halilintar dan Taufan, ketika mereka datang ke Pulau Rintis untuk yang pertama kalinya. Mereka masih sangat kecil waktu itu, dan masih belum berjumpa dengan Ochobot. Pertemuan mereka baru akan terjadi bertahun-tahun kemudian.
Saat itu, mereka bertiga tiba di tempat yang luar biasa ini, boleh dibilang secara tidak sengaja. Jelasnya, tersesat. Bagi mereka saat itu, tempat ini cukup sulit dicapai. Juga sebaliknya, sulit untuk kembali ke rumah dari sini. Alhasil, mereka baru berhasil pulang menjelang Maghrib. Dan sukses kena jewer dari kakek tercinta.
"Hah?!"
Pemandangan yang menyambut Gempa ketika ia sampai di bukit itu, sontak merenggut napasnya. Halilintar ada di sana, tetapi dia tidak sendirian. Rupanya Taufan memang mencari sang kakak ke sini dan berhasil menemukannya. Hanya untuk menghadapi amarah kakak satu-satunya itu.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gempa berlari mendekat. Saat itu, Halilintar baru saja menghempaskan tubuh Taufan ke sebatang pohon besar. Begitu kerasnya, hingga Taufan merintih kesakitan. Gempa melihat Halilintar mencengkeram kerah jaket Taufan, sambil membisikkan sesuatu ke telinga Taufan yang tak bisa didengarnya.
"HALI! TAUFAN!"
Gempa tiba di sisi kedua saudaranya dengan perasaan campur aduk. Ia melihat wajah Taufan pucat pasi. Shock, entah karena apa. Dilihatnya juga Halilintar seperti sudah nyaris gelap mata. Gempa berharap ia salah sangka, tetapi kakak sulungnya itu tampak sudah siap melayangkan tangannya yang terkepal.
"Cih!" Halilintar menghentikan niatnya. Ia hanya melihat Gempa sekilas pandang, sebelum akhirnya berkelebat pergi secepat kilat. Gempa masih terpaku beberapa detik lagi, mengingat tatapan Halilintar barusan yang tajam menusuk.
"Taufan!" Gempa tersentak saat tatapannya kembali kepada kakak keduanya. Ketika itulah, ia baru menyadari tubuh Taufan yang gemetar. "Apa yang terjadi? Kamu nggak apa-apa?"
Taufan tampak menggeleng dengan susah payah. Lantas dengan suara bergetar, ia mencoba bicara meskipun tersendat, "Aku ... Le—Lebih baik ... kita pulang ... sekarang ..."
"Oke. Tapi kamu jangan mengudara dalam kondisi begini. Jalan bareng saja denganku pelan-pelan."
Taufan cuma mengangguk, kemudian mengikuti adiknya. Gempa sendiri berjalan sambil sesekali memerhatikan Taufan dengan tatapan khawatir. Belum lagi ingatannya yang tidak bisa lepas dari sorot mata Halilintar belum lama berselang. Sorot mata yang mau tak mau membuatnya gemetar, sama seperti lima tahun silam.
Kenapa?
Kenapa sorot mata beriris merah delima yang indah itu harus kembali ternoda seperti waktu dulu? Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Gempa kembali merasakan takut yang mencekam di dalam hatinya.
oO)-----------------♦-----------------(Oo
Aku masih ingat sorot mata Halilintar waktu itu. Saat dia menatapku, menatap Taufan, menatap kakek kami, dan juga teman-teman kami. Begitu dingin. Begitu gelap. Tajam menusuk. Saat itu, aku benar-benar takut, kami telah kehilangan dia untuk selamanya.
Tapi dia kembali. Kembali menjadi Halilintar yang kami kenal. Meskipun aku tahu, peristiwa itu telah menorehkan luka yang teramat dalam di hatinya. Dia sudah berjuang sangat lama untuk menyembuhkan luka itu. Lama sekali.
Aku ... sudah nggak mau kehilangan dia lagi ...
oO)-----------------♦-----------------(Oo
Bersambung ...
Layaknya Cahaya Kecil; Heidy S.C. 2017©
BoBoiBoy; Animonsta Studios 2011-2016©
====================================================
Author's Corner

Halooo~! \(^o^)
Semangat pagiii~! Entah kalian baca tulisan ini pas siang, sore, malam, atau dini hari. Pokoknya, setiap saat harus tetap secerah pagi hari~he he he ... :3
//Padahal ini ceritanya lagi suram. *apalah Heidy ni*
//Jadi pengin peluk Gempa ... >///< *dihajar massa*
Arc-nya Gempa sudah selesai sampai di sini. Bab selanjutnya, kita mulai nge-stalk si handsome Taufan. ;-) *halah*
Tapi ... maaf banget, yah~khusus minggu depan sepertinya LCK libur dulu. Soalnya diriku mau fokus ke event ultah Yaya yang bertajuk #HBDOurGravityQueen (yang mau baca, nanti silakan cek di kumpulan fanfic-ku pas di hari ultah Yaya, tanggal 5 Agustus 2017).
Okay then. See you next chapter~! Bye-bye~ ^_^
Solo, 29 Juli 2017
Heidy S.C.
* Mulmed:
Video clip "Tak Ada Yang Abadi" punya grup band NOAH (dulu Peterpan). Anggaplah BGM. Cocok tak? ;-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top