One
|•MEET HIM•|
Enggar menatap pemandangan di depannya tanpa selera. Lengan bawahnya yang bertautan bertengger di depan dada--menunjukkan rasa bosan sekaligus malas nan kentara. Punggung ia sandarkan ke dinding berlapis keramik pada setengah bagiannya, agak menekuk hingga tatapan pemuda itu sedikit menghunjam ke bawah beberapa derajat.
Apa menariknya, sih, berdesakan hanya untuk melihat hasil ujian?
Cih. Buang-buang tenaga saja. Toh menurut pemikiran Enggar, tidak ada sekolah yang merelakan satu pun muridnya menerima kegagalan ujian. Bahkan seniornya dulu yang terkenal teramat-sangat-bebal dan berotak-kosong lulus sekolah juga meski dengan nilai minim. Jadi, buat apa sibuk menyalip celah sana-sini kalau hasilnya juga sudah pasti; lulus, entah dengan nilai seperti apa.
Cowok itu masih bertahan pada posisinya. Beberapa pasang mata dari kerumunan di dekat papan hasil ujian menatapnya dengan kesan tidak baik; sedikit cemooh, juga gunjingan karena dirinya memisahkan diri dari sana.
"Itu siapa, sih? Sok banget gak ikutan liat pengumuman. Hahaha. Takut dilihatin soalnya nilainya kecil? Atau gimana?"
"Eh, itu si Enggar kan? Yang kata guru-guru insyaf sebelum ujian?"
"Bentar, deh. Denger-denger, ada dua anak yang nggak lulus, loh. Kasian banget."
Bisik-bisik itu merambat masuk ke telinganya, membuat Enggar mendengus. Ia berpaling dari tembok, melangkah menuju salah satu kelas terdekat yang diyakininya sebagai kelas tempat dirinya belajar.
Ketika tubuhnya melenggang masuk ke dalam sana, bisik-bisik itu bertambah banyak. Dan kali ini, diiringi tawa bermacam nada. Beberapa kali terdengar juga jerit bahagia, disusul dengan tepukan tangan meriah--yang menurut Enggar terlalu berlebihan.
Enggar menggerakkan tungkai kaki menuju salah satu bangku, kemudian mendudukkan badannya dengan nyaman. Ditumpuknya kedua lengan bawah di atas meja, lantas menaruh kepalanya di sana. Napas dia embuskan sedemikian panjang, berusaha menikmati ketenangan kelas yang kosong tanpa adanya penghuni lain.
Menit demi menit berlalu. Pemilik rambut hitam kecokelatan itu nyaris saja tertidur kalau salah seorang temannya tidak menapakkan kakinya ke kelas ini dan memanggil namanya dengan nyaring.
"Enggar! Gua nyariin lo ke mana-mana, tau. Udah sepi, tuh, kalo lo mau liat pengumuman. Gua temenin, deh. Ayok!"
Enggar lantas membuka mata, mengedipkannya beberapa kali agar kantuknya hilang, dan membalas dengan nada tak bergairah sama sekali. Diarahkannya pandangan pada jendela yang berhadapan langsung dengan lapangan, lalu bersitatap dengan manik mata si pemanggil namanya.
"Hmm, ya udah. Ayo liat."
Fajri, orang yang memanggilnya tadi, mengangguk mengiyakan. Matanya berbinar dengan janggal saat beberapa detik lalu Enggar menatap matanya. Entah apa, tetapi yang jelas, Enggar berusaha mengabaikannya. Toh, Fajri ketua murid di kelasnya, yang secara tidak langsung, punya imej yang bagus. Jadi menurutnya, menaruh curiga pada cowok berkacamata itu tak akan berguna.
Terik matahari menyambut kulit mereka saat papan pengumuman ada di depan mata. Masih terlihat puluhan pasang kaki berjajar, berdesakan demi melihat hasil Ujian Nasional. Jumlahnya memang sudah berkurang dari kerumunan tadi pagi. Gerombolan itu terpecah di dua bagian, sayangnya Enggar tidak acuh dengan hal itu.
Niatnya cuma satu, melihat namanya terpampang di kertas-kertas yang kini lecek karena penuh bekas tangan siswa-siswi. Artinya, dua kubu yang bergumul itu tak akan membuatnya tertarik untuk mencari tahu barang sedikit saja.
Setelah berhasil mencari celah kosong, Enggar dan Fajri segera menempatinya sebelum diambil alih yang lain.
"Lo cari yang dari paling bawah aja, Gar. Gua dari yang atas," ucap Fajri memberi usul. Enggar setuju. Diarahkannya jari telunjuk ke arah tabel-tabel berisi ratusan nama dengan nilai terminim.
Butuh waktu lama memang. Jadi karena sebab itu, baik Enggar mau pun Fajri memasang mata baik-baik agar tak ada satu pun nama terlewat.
Beberapa menit kemudian, jari mereka bertemu. Enggar menolehkan kepalanya, menatap Fajri dengan pandang bertanya.
"Nggak ada, Gar. Enggak ketemu. Coba lo cari dari yang paling atas, terus gua dari yang paling bawah. Oke?" Nada bicara Fajri terdengar tenang, meski terselip nada khawatir dan ketidakyakinan yang samar. Mendengarnya, darah Enggar berdesir. Keringat dinginnya muncul bersamaan dengan anggukan ragu.
Nihil.
Kedua remaja itu tak menemukan nama Enggar Satria Aji di sana. Badan Enggar mendingin. Sementara itu, Fajri berdiri kaku seolah tidak percaya.
"Gar, saba-"
Tanpa mendengar kata-kata Fajri, Enggar berlari mencari daftar nama anak-anak yang tidak lulus di papan pengumuman yang lain. Kondisinya ternyata jauh lebih ramai, hingga cowok itu harus bersusah payah menyalip ruang kosong.
"Eh, ada orangnya. Minggir, minggir!"
"Mampus. Belagu sih jadi orang. Ngebuli adek gue seenak jidat. Rasain!"
Menebalkan telinganya, Enggar menajamkan mata memastikan. Hanya ada dua nama yang tertera. Dengan mudah, pemuda itu membaca kedua nama itu dalam hati.
Napasnya tercekat.
Enggar Satria Aji, tertulis di urutan kedua sekaligus terakhir.
Lututnya bergetar hebat. Tak menunggu lama, pertahanannya runtuh tertarik gravitasi.
Mustahil. Ini ... bohong, kan? Hati Enggar meracau penuh rasa tidak percaya. Cemooh orang-orang di sekitarnya berdengung menyakitkan, membuat dirinya tersadar bahwa ini bukanlah suatu dusta belaka.
Lantas di sisi lapangan yang lain, Fajri bergegas menghampiri anggota kelasnya itu. Tangannya menepuk bahu Enggar pelan, mentransfer semangat dan ketenangan yang cowok berkacamata itu miliki. Enggar bergeming di tempat. Pikirannya bercabang tanpa bisa ia kendalikan.
Kerubungan siswa-siswi kelas dua belas mulai menipis kala Fajri membuka mulutnya.
"Sori, Gar. Gua sebenernya ... udah tau kalo elo nggak lulus."
Enggar tak menggubrisnya. Hatinya perih, dan pernyataan Fajri tak akan mengobati apa pun.
Waktu itu, pukul sebelas lebih empat puluh tiga pagi, Enggar seakan kehilangan harapan hidup.
Tuhan tidak adil padanya. Sama sekali tidak.
***
Hati Enggar menampik pemikiran orang-orang tentang 'usaha tak akan mengkhianati hasil'. Bodoh sekali, pikirnya. Percuma saja ia belajar tiap malam, ikut les sana-sini sekitar tiga bulan menjelang ujian, berhenti membuat onar, dan meninggalkan segala rasa malasnya saat di kelas. Untuk apa? Karena buktinya sekarang, ia gagal.
Matanya memerah karena menahan tangis. Enggar rasa, sia-sia waktu ujian itu, ia menolak untuk berbuat curang. Menolak untuk saling kerja-sama ketika mengerjakan deretan soal penentu kelulusan itu. Naif sekali. Hati Enggar merutuk lagi.
Ayahnya belum pulang kerja. Entah apa yang terjadi nanti kalau ayahnya sudah kembali ke rumah. Yang pasti, hal buruk. Ayah selalu menganggapnya salah dalam hal apapun. Enggar tak tahu apa alasan ayahnya tak pernah berhenti mencaci saat ia gagal. Seperti gagal mendapat posisi lima belas besar di kelas, atau seperti--
"Gimana ujianmu? Gurumu bilang, nilaimu tidak cukup untuk sekadar lulus sekolah. Memalukan."
--sekarang ini.
Ayah berdiri di dekat pintu kamarnya yang sudah terbuka lebar. Jas kantor yang ia kenakan masih rapi seperti biasa, tanda kalau Ayah baru saja selesai kerja, juga sebagai simbol tersirat bahwa ayahnya punya jabatan tinggi. Dan tak lupa, perfeksionis.
Enggar tetap bergeming, meringkuk di kasurnya dengan bantal menutupi bagian hidung ke bawah. Tak ada nyali barang secuil pun dalam dirinya untuk menjawab ucapan sang ayah yang bernada tenang, namun sarat akan kenyinyiran dan cemooh menyakitkan.
"Nilai terburuk di kelas. Tidur saat jam pelajaran. Pembuli. Dan sekarang apa? Gagal lulus ujian. Kamu hanya bisa bikin malu!" seru ayahnya kasar. Perasaan Enggar bagai ditoreh sembilu.
"Percuma saya punya anak kalau tidak bisa buat bangga keluarga," lanjut Ayah dengan nada tajam. Enggar menegang di tempatnya. Buku-buku jarinya memutih dan terasa dingin.
"Pergi dari rumah saya sekarang. Kamu yang janji, kan, akan pergi dari sini kalau gagal Ujian Nasional? Sekarang, silakan pergi. Saya malu punya anak seperti kamu, Enggar." Nada yang dilontarkan pria itu terdengar penuh penekanan.
Enggar hanya bisa menurut. Diambilnya beberapa stel baju dan memasukkannya ke dalam tas sekolah. Juga beberapa lembar uang tabungan di atas meja.
Tanpa berkata-kata lagi, Enggar melenggang pergi melewati sang ayah yang masih menatapnya tajam. Hatinya terlalu sakit untuk sekedar mengatakan sesuatu barang sepatah kata saja.
Untuk pertama kalinya saat SMA, Enggar menangis. Hidupnya benar-benar kelam sekarang.
Ia benci Tuhan, tanpa tahu, kalau Tuhan selalu punya rencana.
***
Hujan turun membasahi bumi. Enggar mendesah pelan, mengusap matanya yang memerah dengan kasar. Udara mendingin. Seketika, ia teringat kalau jaketnya tertinggal di rumah. Hati Enggar lantas merutuk menyesali kebodohannya.
Matanya sontak menjelajahi sekeliling, mencari tempat berteduh. Pandangannya terhenti pada pos ronda kecil yang letaknya cukup membuat Enggar meringis.
Ah, masa bodoh dengan jaraknya.
Tanpa pikir panjang lagi, Enggar berlari menerobos air hujan yang makin menggila. Becek tanah yang terguyur air nyaris membuatnya terpeleset beberapa kali.
Hingga akhirnya, kakinya memijak tanah yang kering terlindung sisa atap pos ronda beberapa menit berselang. Suhu sekitar seolah membeku karena hujan bertambah deras. Enggar menggigil samar, lalu segera mendudukkan tubuhnya di lantai pos ronda.
Beruntung, baju yang ia kenakan menutup sempurna tubuh bagian atasnya, alias berlengan panjang. Namun sayang, basah di beberapa tempat. Jadi, dibukanya resleting tas yang dia bawa, dengan harapan ada pakaian yang dapat digunakan untuk berganti baju.
Tetapi harapannya kandas saat melihat seluruh bajunya basah tanpa ada satupun yang cukup kering untuk dipakai. Enggar mendesah lagi. Badannya menggigil sempurna sekarang.
Dengan terpaksa, ia membaringkan tubuh dan menaruh tas sebagai bantal. Beberapa baju yang sengaja dikeluarkannya diposisikan sebagai selimut-meski kondisinya tak lagi kering.
Kantuk menghampiri. Matanya mengerjap pelan, mencoba tertidur. Dengan menyingkirkan seluruh rasa malu karena menginap di tempat seperti ini, kesadaran Enggar menipis perlahan-lahan. Ia jatuh tertidur sejenak kemudian.
Namun selang beberapa waktu, Enggar mengerang kecil. Seseorang menggoyang-goyangkan tubuhnya, membuat tidurnya terganggu. Menahan godaan untuk kembali terlelap, Enggar bangkit duduk dan membuka mata dengan paksa.
Semburat wajah tegas dan pucat tampak menatapnya datar. Di sampingnya, seorang gadis kecil tersenyum manis.
"Enggar, kan?" Sosok itu bertanya masih dengan ekspresi minim. Sementara itu, gadis cilik di dekatnya ikut bicara.
"Daripada tidur di sini, Kakak mau enggak nginep di rumah kita?"
Enggar terdiam. Suaranya terbelenggu di tenggorokan. Memorinya tersadar akan beberapa hal.
Si wajah datar itu, satu sekolah dengannya.
"Ayo, Kak. Di sini dingin, loh."
Seingat Enggar, namanya Devon. Bukan tipe murid baik-baik. Namanya dikenal seisi sekolah karena sering digosipkan punya riwayat dengan narkoba. Atau mungkin, masih hingga sekarang.
Dan seingatnya lagi, Devon-lah pemilik nama pada urutan pertama di daftar siswa yang gagal.
"Jadi, lo mau ikut atau tetep tidur di sini?" Devon masih menunggu jawabannya.
Entah atas dasar apa, Enggar lalu mengangguk--tanpa paksaan sama sekali. Devon seolah punya daya magis luar biasa yang dapat mempengaruhi seseorang dalam sekali atau dua kali ajakan saja.
"Masuk," titah pemuda itu kemudian, tanpa berbasa-basi.
***
Aoi's note
Thanks for my emak aminahwahyudin. You're my hero, Mak! :)))
Hmm kumerasa ini panjang gitu ya. Tumben. Hahaha. Makasih yang udah bacaa :33.
(Entah kenapa kumerasa note kali ini gada ekspresi. Hm yasudahlah)
Salam dari Otosaka Yuu lover, kawan-kawan!
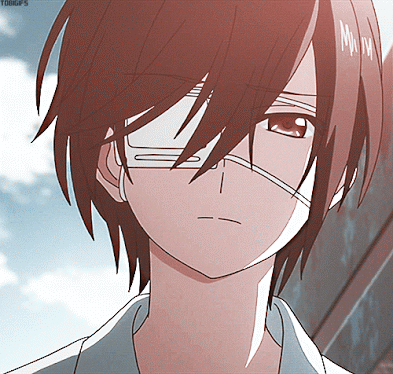
*matanya satu doang aja cakep. Wkwk.*
See you next chap! (Yang sepertinya akan ngaret sengaret-ngaretnya.)
Salam (lagi) dari Aoi, sang #penulisnista.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top