21| Masih Sama
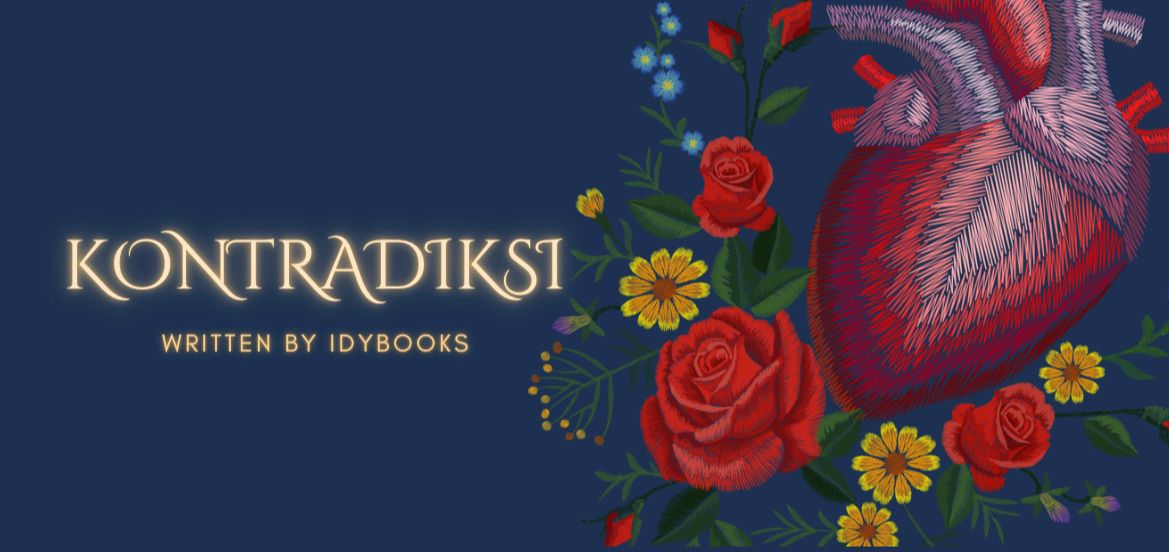
Jangan lupa tekan bintang dan komennya guys
***
Dalam dunia medis, Adnan pernah pelajari tentang paradoxical breathing, kondisi di mana dada seseorang justru mengempis saat menarik napas dan paru-paru tidak mampu berkembang sebagaimana mestinya saat mengembuskan napas.
Fenomena ini bertentangan dengan fungsi alami tubuh. Kerap kali ia hadapi kasus seperti itu di ruang operasi, di mana setiap detik tentukan hidup atau mati.
Namun di koridor rumah sakit ini, Adnan bisa rasakan jenis lain dari paradoks itu. Napasnya yang beberapa saat lalu terasa stabil, mendadak terasa berat. Langkahnya melambat ketika matanya menangkap sosok wanita berjalan perlahan menuju ke arahnya. Tangannya menggandeng seorang gadis kecil. Gadis kecil itu balas menggenggam erat tangan si wanita. Rambutnya yang lurus bergerak ringan mengikuti ayunan langkah.
Secara keseluruhan tidak ada yang salah dengan degupnya. Lama tidak ia rasakan degup seperti ini hadir.
Sharon.
Sharon Katandira Wiradi.
Nama itu melintas seperti bisikan lama. Adnan membeku, memandangi sosok yang pernah mengisi hari-harinya. Wanita yang beberapa tahun silam pernah katakan akan selalu ada di sisinya, kini berdiri di depannya dengan wajah baru. Seorang ibu.
Semakin wanita itu mendekat, semakin Adnan menahan napas. Muncul sesak yang tak biasa. Adnan tak mau mengasosiasikan degupnya sebagai bentuk cinta maupun rindu.
Hanya saja ada sesuatu yang bahkan otaknya sendiri tak mengerti itu apa.
"It's been ages, ya, Nan?" Sharon menyapa manis, seakan-akan tidak pernah ada waktu yang pernah memutus mereka sebelum wanita itu menampakkan wajahnya lagi. "Hasn't it?" Suara Sharon punya cara menghantam tanpa permisi.
Diam-diam lakum Adnan menelan ludah. "It has," jawabnya pendek. Hampir tak terdengar.
Sharon melirik putri kecil yang menggenggam tangannya, lalu kembali menatap Adnan. "Akhirnya kita ketemu lagi," ucap Sharon dengan nada lega. "Akhirnya aku punya sedikit keberanian buat ketemu kamu lagi."
Adnan terdiam. Itu adalah kata-kata yang cukup tidak masuk akal. Adnan tak pernah ke mana-mana. Bukankah wanita itu yang sempat kabur?
"Terakhir kita ketemu kapan ya?" tanya Sharon mencoba meredam sedikit canggung yang melingkupi. Kedatangannya sendiri ke Jakarta sudah hampir satu tahun, tetapi tak ada cukup keberanian untuk hubungi Adnan lebih awal. "Waktu kamu baru lulus fellowship kalau nggak salah deh." Dia membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara sejenak, memperhatikan reaksi Adnan.
Kemudian, dengan senyum tipis di bibirnya, Sharon melanjutkan, "Now look at you, Nan. Dr. Adnan Akhtar, Spesialis Bedah Saraf," katanya mengeja nama Adnan seperti caranya membaca naskah dengan untaian nada bangga. "I'm proud of you."
Dan Adnan tak butuh kata-kata itu.
Rahang Adnan mengeras, nyaris tak kentara. Ia tak langsung bicara, hanya memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Pandangannya sempat tertuju anak kecil di sisi kiri Sharon, sebelum kembali menatap wajah wanita itu dengan intensitas yang sulit terbaca.
Masih Sharon yang sama.
Masih Sharon yang sama. Sharon itu. Mata itu. Tatapan yang dulu mampu membuatnya merasa dimiliki. Mengingatkan Adnan pada saat tubuh mereka pernah terjerat dalam malam-malam panjang tanpa batas. Mata itu, mata yang berbicara lebih banyak daripada bibirnya, menguasai setiap inci dirinya, membuatnya sempat terjatuh, hilang arah, sepenuhnya milik wanita itu.
Tapi sekarang? Tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan masa lalu yang terasa terlalu jauh untuk disentuh lagi.
Sharon pun menyadari apa yang berbeda dari tatapan pria di depannya. Dua iris Adnan selayaknya cermin retak yang hanya memantulkan bayangan buram.
"Some things never change, ya." Pundak Sharon mengedik. Dagunya sedikit terangkat, seolah menunggu, atau lebih tepatnya menantang Adnan untuk kembali mengatakan sesuatu.
Tetapi Adnan masih terus berdiri. Memandanginya dengan sepasang iris legam, dan Sharon justru balas tersenyum. "Congratulations on your wedding, Nan. It's a little late, but I'm happy for you."
Adnan enggan menjawab, dan memang tidak berniat mengatakan sesuatu.
"Anyways, ini Sheryl, my daughter. Masih inget?" tanya Sharon, suaranya terdengar akrab. "Terakhir kamu lihat masih kecil banget. Masih bayi. Waktu Sheryl bayi, kamu yang bantu rawat dia, ya walau nggak pernah mau disuruh ganti popok sih," lanjutnya, seperti menantikan reaksi Adnan. "Sheryl, ini..." cukup lama terdiam, menimbang sesuatu, lalu meneruskan, "Ini Papi. Papi Adnan yang suka Mami ceritain itu."
Sharon tidak sepenuhnya salah. Tetapi kata-kata itu pun tidak cukup benar diucapkan saat ini.
Mata anak itu berbinar girang. "Iya, Mami?"
"Iya. Nanti kenalan lagi sama Papi, ya?"
Sheryl mengangguk dan menatap Adnan penuh harap.
Sedang Adnan hanya memandang Sheryl sekejap, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke wajah Sharon. Tatapannya datar, tidak ada jejak perhatian khusus atau rasa ingin tahu di sana.
Sesaat kemudian ia berkata dengan nada netral, "I should get back to work."
Bahkan belum sempat Sharon kembali angkat suara, Adnan sudah membawa langkahnya menjauh. Melewati tubuh ibu dan anak itu, saling memunggungi.
Hingga tiba-tiba Sharon berkata, "He left us. You're right. My husband... he left us." Kalimat itu keluar begitu saja tanpa ragu.
Langkah Adnan seketika tersendat, tubuhnya kaku sejenak, tapi dia tetap tidak menoleh.
Dalam diam yang terjadi setelahnya, Sharon memutar tubuh, menunggu reaksi dari pria yang kini berdiri memunggungi. Namun Adnan tetap di sana, seperti sudah terlatih untuk menahan segala bentuk luapan emosi.
Adnan berdiri selama beberapa detik, punggungnya kaku, sebelum akhirnya ia melangkah maju, mengabaikan kata-kata, bahkan kehadiran Sharon itu sendiri.
***
Hampir seminggu setelah menikah, Inka memutuskan kembali ke kantor. Sudah rapi dengan setelan jas kerja pas badan, celana panjang navy, dan sepasang sepatu hak tinggi. Apa gunanya ambil jatah cuti jika di rumah cuma menanti suami yang entah kapan pulang atau pergi. Pun, terjaga hingga pagi tak membuat ia bertemu Adnan.
Sepertinya pria itu serius tidak mau melihat wajahnya lagi setelah pertemuan terakhir mereka. Membuatnya mau tak mau tampak seperti pengangguran yang terpaksa diungsikan.
Mendadak Inka punya tekad baru. Lihat saja, setelah ini ia akan muncul lebih sering di depan wajah suaminya. Bagaimana pun caranya Adnan harus lihat wajah cantik istrinya minimal dua kali setiap hari.
Lihat saja.
Lihat saja, Adnan Akhtar.
Mana boleh meninggalkan istrinya yang baru tiga hari dinikahi di rumah sendiri.
Ironisnya, antusiasme berangkat kerja tidak sejalan dengan kenyataan. Mobilnya malah mogok di tengah jalan. Mesinnya mati. Untung saja mobilnya tak merajuk di jalan raya.
Inka menghela napas panjang, menatap setir dengan frustrasi. "Perfect," gumamnya dengan nada sinis. Ia rogoh ponsel dari tas tangan, mencari nomor Layanan Darurat terdekat, tapi sejenak berhenti.
Adnan. Nama itu tercetak tebal di pikiran. Namun mendadak merasa enggan. Memangnya suami seperti itu layak dimintai tolong? Pria yang bahkan tidak peduli apakah istrinya hidup atau mati di rumah sendirian?
Tidak, lagi pula dia bukan tipe perempuan yang akan terlihat lemah di depan laki-laki seperti Adnan. Sejak sebelum ada Adnan pun hidupnya sudah mandiri; mau apa-apa bisa sendiri.
Pilihan terbaik jatuh pada Layanan Roadside Assistance.
Ia mendesah parau saat turun dari mobil. Tidak lakukan apa-apa. Hanya tatap nelangsa mobil malang yang sudah temaninya selama tujuh tahun terakhir.
Hampir saja ia menyentuh tuas pintu mobil tatkala matanya menangkap sosok yang tak asing. Tangannya terhenti di udara. Di seberang jalan, Sadam dengan motor matiknya, berhenti lalu menaikkan kaca helm. "Mbak Inka?"
"Bukan," jawab Inka yang langsung ditimbun renyahnya bunyi tawa Sadam.
"Lo ngapain di sini, Mbak? Bukannya lagi honeymoon ke Paris?"
"Ke Paris? Kata siape gue ke Paris? Sekate-kate."
Sadam berkedip. Alis tebalnya turut mengerut. "Kata Mbak Nita."
"Nggak. Gue cuma kibulin dia. Belum mau honeymoon. Lo kemarin juga nggak dateng, kan?" Inka bertolak pinggang. "Ke mana coba? Gue nggak ngeliat muka lo di wedding party gue."
Sadam tersenyum serba salah sembari menggaruk belakang leher, kebiasaan yang sudah sering dilakukan di depan Inka. "Ya, sorry deh, Mbak. Ibu sakit." Hatinya pun turut sakit. Tapi bisa apa dia?
Dengar-dengar suami Inka dokter bedah saraf. Bermodal nama, Sadam selidiki melalui banyak jejaring sosial, bahkan membaca serta mengecek LinkedIn suami Inka lebih dari tiga kali.
Rasa iri menyelinap setiap kali mengingat ragam prestasi, karir, serta jenjang pendidikan suaminya yang mentereng.
Kalah telak, bagai dunia yang mereka jalani begitu jauh berbeda. Tak ayal, mengapa takdir berkata wanita seelok Inka tidak diperuntukkan untuknya.
Sudah sepantasnya Sasinka tak ditakdirkan bersama seorang karyawan dengan gaji sebatas UMR Jakarta, yang hanya sanggup tinggal di indekos dengan harga sembilan ratus ribu per bulan. Masih harus berkelahi dengan UKT kuliah adik, serta menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.
Belum cukup puas, kenyataan masih datang menampar saat ingat satu unit mobil Mazda wanita itu bisa ditukar dengan lebih dari 20 unit motor Honda keluaran tahun 2022 miliknya.
"Berarti lo mau ke kantor, Mbak?"
Inka mengangguk. "Gue nebeng deh, ya? Boleh?"
"Aduh. Bukan nggak boleh, Mbak. Tapi memang nggak masalah naik motor? Banyak debu."
"Alah. Dulu gue pernah suruh mandi debu sama Bapak."
Sadam tertawa. "Serius? Mandi debu ngapain, Mbak?"
"Dijilat anjing. Udah buru. Gue mau naik."
Sadam menggeser pantatnya maju, memberi ruang lebih banyak untuk Inka. "Gue nggak bawa helm dua, Mbak. Nggak papa ya lewat jalan tikus?"
"Santai aja." Inka menatap sebentar arlojinya. "Masih keburu. Masih ada sejam."
"Mobil lo?"
"Bentar lagi diambil. Buru jalan." Dua kali Inka tepuk pundak Sadam. Dan lelaki itu melajukan motornya meninggalkan mobil hitam Inka yang berdiri malang.
Rusak mobilnya bisa jadi tanda: 1) Adnan harus belikan mobil baru untuknya, 2) Adnan harus antar istrinya berangkat kerja setiap hari.
Pilihan kedua lebih Inka suka.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top