Hari 6 - Star Cinema (2)
TERMOS kopi, sleeping bag, binokular, planisfer, dan senter yang dilapisi cat kuku berwarna merah yang diberi nama Manis—kependekan dari Si Manis Jembatan Ancol—sudah tertata rapi masuk ke dalam ransel carrier.
Leda menyalakan layar ponsel untuk mengecek jam malam itu. Hampir jam sebelas. Sudah waktunya mengusik Pangeran Tidur yang sesorean tadi menghina habis-habisan peralatan tempur Leda dengan kalimat seperti 'senter kok dikasih nama?', 'gimana fungsinya senter yang kacanya diwarna merah begitu?', sampai 'kamu mau camping atau mau nyerahin diri dimakan macan?'.
Gadis itu menghela napas, menekan emosi. Dia sudah lama menerima kenyataannya jika Benjamin memanglah prick, alias lelaki menyebalkan.
Tok-tok-tok, Leda mengetuk. Tak ada jawaban.
Sedikit ragu, gadis itu memutar kenop pintu. Masih diingatnya wanti-wanti Benjamin tempo lalu, tentang betapa dia tidak suka jika Leda asal masuk ke kamar lelaki itu sembarangan.
Untungnya, sang Pangeran benar-benar tidur. Pulas.
Kekesalan minor di hati Leda dengan cepat meluruh ketika melihat Benjamin yang hilang dalam lelap. Matanya terpejam, wajahnya terlihat damai. Alis yang biasa terpaut dalam kerutan dahi, kini rileks dan sejajar rapi. Leda tak bisa menahan matanya untuk tidak semakin memperhatikan—hidung Benjamin yang penuh, bibirnya yang tipis dan mengatup, serta rambutnya yang mulai tumbuh panjang melintasi kening.
Benjamin tampak ... jinak. Sungguh, beda sekali perawakan Benjamin yang sadar dan sedang lelap begini. Ah, pasti lelaki ini lelah karena seharian ini sudah menempuh jarak hampir empat puluh kilometer demi mencapai ATM di Pandalungan Kota—itu semua demi proyeknya memperbaiki desa.
Leda berpikir, mungkin—hanya mungkin—di balik perangai angkuh dan wajah yang rawan mengernyit ini, terdapat hati baik dan tulus yang bahkan tidak disadari pemiliknya.
"Ben?" panggil Leda sambil menepuk-nepuk pipi lelaki itu. Benjamin mengernyitkan kening.
"Ayo, it's time." Kali ini Leda menarik selimut yang membalut tubuh tunangannya.
"Time for what?" gerutu Benjamin seraya menutupi matanya dengan satu lengan. Tampak sekali lelaki itu enggan terjaga.
"Hujan meteor di konstelasi Lyrid. Ayo!" ucap Leda dengan semangat.
"Hah? Hujan meteor??"
"Tenang, nggak hujan beneran kok. Cuma kayak nonton pertunjukan bintang jatuh aja di langit Timur Laut."
Leda menutup aksi agresi kamar Benjamin dengan satu gerakan mantap, menarik kedua lengan Benjamin hingga lelaki itu bangkit dari ranjang.
"Ayo ... kamu kan udah janji!" erang Leda.
"Jangan ngaco, saya nggak pernah janjiin kamu apa-apa." Sempat-sempatnya Benjamin menggerutu.
"Kamu mengiyakan permintaan aku 'tuh kehitungnya udah janji, Ben! Let's go!" Dan gadis itu pun melangkah pergi setelah melihat Benjamin bisa berdiri sendiri.
"Ribet amat urusan sama cewek sinting," gumam Benjamin diam-diam.
🌟
Benjamin melangkahkan kaki dengan ragu-ragu. Jalan pintas setapak itu terjal dan menukik, membuatnya mengerahkan konsentrasi lebih saat berjalan, agar tidak terjengkal.
Punggungnya menanggung beban yang terasa lebih berat dari seharusnya, sebab ransel gunung yang sedang disandangnya malam ini adalah cindera mata dari Petra. Ternyata perlengkapan survival kit yang dibekali (mantan) sobatnya itu lumayan berguna.
Meskipun enggan mengakui, Benjamin sebenarnya merasa bahwa ransum (makanan tentara), pisau serbaguna, P3K, kompas, senter, dan GPS yang dibekali oleh Petra itu bisa jadi lumayan berguna pada kondisinya saat ini.
Anehnya, Leda melarang habis-habisan Benjamin untuk menggunakan senternya. 'Kita harus biasakan mata sama gelap! jangan nyalakan senter biar mata kita nggak buta karena cahaya berlebih!' begitu dalihnya. Jadi, ya, saat ini Benjamin berjalan tanpa bantuan satu pun alat penerangan. Konyol.
"Ben," panggil Leda, sudah sampai di puncak setapak.
"Hm?" gumam Ben sebagai jawaban.
"Kamu kalo jalan selalu ngeliat jalanan aja, ya? Fokus sama kaki kamu, hati-hati jatuh."
"...." Benjamin menjawab dengan katupan bibir. Dia masih belum terima atas logika Leda yang ngotot kalau mereka tidak boleh menyalakan senter.
"Kenapa, sih, kita harus camping di tempat beginian—jam segini, pula?" keluh Benjamin setelah beberapa langkah diliputi kesunyian.
Lelaki itu bisa mendengar langkah kaki Leda yang berada tepat di depannya. Napas gadis itu tertata, seakan sudah sering melakukan penanjakan ini berulang kali.
"Karena tadi siang, aku ngecewain kamu sama pilihan film jelek di Star Cinema. Nah, malam ini, aku mau balas itu," ucap Leda.
"Kita mau nonton layar tancap? Di atas gunung begini?" ucap Benjamin, terdengar tak percaya.
"No, kita akan nonton star cinema beneran. Yang keren, yang bagus, dan spektakuler! Aku jamin." Leda terdengar yakin.
"Hujan meteor yang kata kamu itu?" tebak Benjamin.
Namun alih-alih menjawab, Leda malah berhenti mendadak, mengakibatkan tubuh mungilnya tertabrak tak terelakkan oleh Benjamin. Untungnya mereka tidak jatuh.
"Sini-sini, ssttt ... dengerin, lihat," panggil gadis itu dengan perhatian lebih
Benjamin baru saja tiba di sisi Leda, kini mereka berdua berada di tepi puncak bukit. Gelap total. Tak ada rumah, tak ada lampu. Benjamin bisa mencium aroma rumput basah berpadu embun subuh, dan juga mendengar suara jangkrik yang mengerik di kejauhan.
Tapi yang mulai Benjamin rasakan adalah kepanikan.
Dengerin? Lihat? cowok itu mengulang kata terakhir Leda.
"Apa?" desis Benjamin. "Kamu lihat apa, Lee? Hantu? Begal?"
Benjamin bukanlah seorang lelaki yang mudah takut. Namun jujur saja, dengan keadaan berdua saja bersama gadis itu, ditambah mereka sudah berjalan menuju tempat antah berantah yang gelap total, mau tak mau membuat parno dalam diri Benjamin muncul.
"Bukan, Ben. Lihat ke atas," instruksi Leda.
Cowok itu merinding seketika. Sambil memejamkan mata, didongakkannya kepala.
"Ya buka dong matanya! Mana bisa liat kalo sambil merem begitu!" desis Leda sambil menarik sang tunangan ke tengah tanah lapang.
"Oke, oke." Benjamin patuh membuka mata, pasrah lengannya digeret oleh Leda.
Sesaat berikutnya, lelaki itu tercengang seketika. Seumur hidup, Benjamin Cokro tidak pernah melihat langit secerah ini—sejelas ini.
Bulan membulat dengan gagahnya, memantulkan cahaya keperakan. Di lepas langit malam itu, tersebar titik-titik bintang yang berkerlip dengan jelas, semakin diperhatikan, rasanya semakin banyak saja.
Benjamin memicingkan mata. Benar, bintang-bintang itu semakin nyata.
Detik itu bagai terjeda. Benjamin Cokro terhipnotis.
"Wow ...." desis lelaki itu.
"Amazeballs, right?" Suara Leda terdengar bangga.
"These are ... nuts." Benjamin melepas ranselnya, membiarkan benda itu jatuh berdebum di atas rumput.
"Hey, ayo sini." Leda memanggil ketika Benjamin masih asyik mendongak, menatap langit malam.
Ternyata perempuan itu sedang menggelar sleeping bag di atas tanah, sambil menata barang bawaan mereka tak jauh dari sana—tas, termos, senter-tak-berguna, dan barang-barang random lainnya.
Benjamin menyusul, sibuk menggelar sleeping bag pula, tepat di sebelah sleeping bag Leda.
"Bakal capek kalo kamu ngedongak terus ngeliatin bintangnya. Paling enak sambil tiduran. Nih, mau kopi?" Leda menawarkan cangkir yang berfungsi sekaligus sebagai tutup termos, sembari menuangkan isi termos kaca ke dalamnya.
"Boleh." Benjamin tak menolak.
Jujur, kantuk terasa mulai menggelayuti matanya. Lelaki itu tak biasa begadang, tak seperti Leda yang terlihat fresh di malam selarut ini. Benjamin jadi bertanya-tanya, apakah gadis itu mengidap insomnia?
Perhatiannya terputus saat Leda menyerahkan cangkir termos yang mengembulkan uap tipis, tepat ke telapak tangan Benjamin. Lelaki itu menyeruputnya—mmmm, kok enak?!
"Ini kopi apa, Lee? Kamu giling sendiri?" tanya Benjamin sambil menghirup tegukan tipis, lagi.
"Enggak, itu mah kopi sasetan. Lawak White Coffee."
"Hmmppff—" Benjamin hampir menyemburkan kopinya, tertawa. Bisa-bisanya gadis sinting itu memainkan kata.
Melihatnya, Leda hanya tersenyum tipis, lalu mulai membuka planisfer—peta bintang.
"Itu apa? Kamu ngapain?" Benjamin mendekat ke arah Leda yang menyoroti peta bintang itu dengan senter merah. "Dan kenapa harus pake senter yang gak guna ini sih?"
Rupanya Benjamin masih sinis pada si senter merah jembatan ancol. Baginya, senter itu sangatlah nirguna—tak ada fungsi!
"Ini namanya planisfer, Benjo. Peta Bintang."
Leda membeberkan benda semacam peta dunia, namun bukannya bergambar negara dan benua, tapi terdapat garis-garis rasi bintang di sana. Benda itu berbentuk bundar, dengan garis-garis seperti penggaris yang mengitari sekelilingnya.
"Aku lagi nyari gugus bintang Lyra, biar akurat jadi lihat di peta, dan sengaja pake senter merah itu supaya nggak silau, biar mata kita adaptasi sama gelap. Nih, gini aja keliatan, kan?" Leda memutar peta tersebut.
Benjamin mulai tertarik. Lelaki itu memperhatikan Leda yang menggeser planisfer dengan teliti. Cara Leda memutar planisfer itu mengingatkan Benjamin pada kompas kiblat yang dibawa Pakde Manu sepulang haji dulu.
"Sekarang tanggal berapa?" tanya perempuan itu sejurus kemudian.
"Dua puluh dua April ... hampir dua tiga sih, udah mau tengah malem soalnya." Ben menjawab sambil melirik arlojinya kesayangannya—si Rolex GMT Master-II—yang dilengkapi dengan slot date calendar kecil di dalamnya.
"Perfecto," gumam Leda seraya mencocokkan peta bintangnya.
"Nah, Ben," panggil Leda tiba-tiba. Perempuan itu mengaduk tas depan ranselnya, mengeluarkan sesuatu. Sebuah ponsel pintar.
Setelah menggeser dan menggulir layar datar, Leda menyerahkan gawai itu pada Benjamin.
"Lah, itu hape? Buset, kenapa nggak dikeluarin dari tadi aja? Kan ada senternya tuh!" protes Ben sambil menerima gawai tersebut.
"Kalau aku nyalain flash, kita bisa buta karena terangnya! Ish, tadi kan udah dijelasin! Ini nih, ambil aja. Aku pengen kamu bantu nyari juga."
Layar itu tampak gelap, namun ada titik-titik samar dan garis-garis yang menyambungkan sebagian titik di sana.
"What am I looking at? Ini apa lagi nih?" tanya Ben.
"Arahin ke atas, seperti kalau kamu mau foto langit," instruksi Leda.
Benjamin menuruti, dan sontak saja layar ponsel itu berubah, mengikuti arah sorotan Benjamin—ke langit!
Kerlipan bintang dengan berbagai konstelasinya, lengkap beserta label nama dan ilustrasi simbol gugusan tertera di sana. Benjamin berkedip. Ini rasanya tak nyata.
"Is this ... real time? Ini aplikasinya akurat?" tanya Benjamin setengah terpana.
"Yep, itu real time. Nama app-nya Stellarium. Coba deh, kamu bantu cari konstelasi Lyra. Itu tujuan kita malam ini," papar Leda sembari mendekatkan wajah ke arah Benjamin, ikut memantau layar gawai yang kini mendeteksi langit.
Lagi-lagi, Benjamin menurut.
Walaupun skeptis, tapi kecurigaan lelaki itu bisa lebur seketika saat melihat betapa akuratnya keterangan di layar kaca dengan keadaan langit di atasnya.
Bintang-bintang besar yang terang memiliki nama yang tercetak jelas, menandakan itu bintang 'inti' dari sebuah rasi konstelasi.
Benjamin teliti dan hati-hati menggerakkan layar, memutar dari rasi Sagittarius dengan sembulan Mars dan Saturnus yang terang, terus ke kiri melintasi rasi Opiuchus dengan bintang Ceres yang berkerlip, hingga akhirnya dia memutar lagi, perlahan, terus ke kiri.
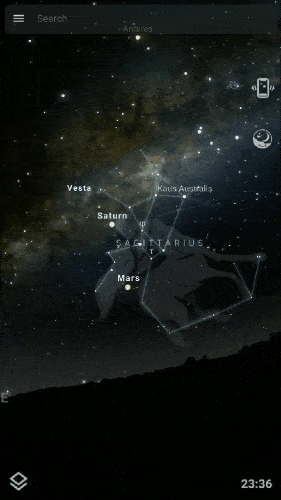
"Cari bintang Vega kalau belum kelihatan konstelasinya. Vega itu bintang terbesar di konstelasi Lyra," lirih Leda dekat telinga Benjamin.
Lelaki itu mengangguk atas instruksi Leda, dan benar saja, kerlip terang Vega yang berhasil ditemuinya di bawah rasi Hercules menandakan tujuan mereka telah ditemukan.
"Ini, ya?" tunjuk Benjamin.
"Betul. Sekarang, kita tinggal nunggu. Habis ini, menjelang tengah malam sampai jam dua pagi, bakal ada sekitar dua puluh meteor—alias bintang jatuh—yang bisa kita lihat dari Bumi perjamnya. Artinya, satu bintang jatuh per tiga menit."
Benjamin tercengang. "Kamu tau itu semua ... dari mana?"
Lelaki itu menoleh untuk mendapati wajah Leda tersenyum di sampingnya, tampak puas telah berhasil memukau sang Cokro.
"Riset, pengalaman, sama trial error. Kamu lupa, ya, Ben? Ini kan pekerjaanku."
Benjamin mengernyitkan kening. "Sampai sekarang saya nggak paham profesi kamu itu sebenarnya apa," gumam lelaki itu kemudian.
"Lah, bukannya aku udah nunjukin, ya, waktu itu? Inget, kan? Sore-sore, kita ke lapangan, lihat sunset, Venus, Bulan ...?" Nada suara leda terdengar sedikit tidak terima.
"That doesn't prove anything. Kamu ini ... semacam space nerd, kah? Sama kayak Lisa, yang demen sama apa aja berbau luar angkasa?"
"Beda, lah! Kalau Lisa mah cuma hobi, sementara aku ini nggak main-main! Ini kerjaan aku, Ben, ker-ja-an." Leda mengeja kata itu penuh penekanan.
"Oke, oke. Ini kerjaan kamu yang dikasih sama ayah kamu itu, benar?" Lelaki itu mengalah sejenak, namun tetap tak sepenuhnya percaya. Benjamin sedang kumat kepala batunya.
"Betul. Ayahku kerja di BMKG, jadi Klimatolog di sana," aku Leda.
"Jadi, kamu pegawai BMKG? Semacam volunteer atau—"
"Bukan! Nggak ada urusannya sama BMKG. Aku ya kerja untuk ayahku."
Benjamin mengernyitkan dahi, lagi.
"Oke, jadi ... ayah kamu yang gaji kamu, ngebayar kamu tiap bulan?"
"Yap." Leda mengangguk yakin.
"Bukannya memang sudah jadi tugas seorang ayah untuk membiayai kehidupan putrinya?" Benjamin semakin heran.
Leda mengangkat bahu. "Kalau kamu bilang begitu, sama aja kayak ini bakal jadi tugas kamu untuk ngebiayain total hidup aku kalau nanti kita nikah."
"Apa?!" seru Benjamin.
"Bercanda, bercanda! Hahaha." Leda tertawa lepas. "Maksudku, nggak ada salahnya kan, perempuan kerja untuk cari uang sendiri?"
Benjamin mendengkus jengah. "Nggak lucu!"
Tawa Leda masih tersisa. "Oke, oke. Tapi poin aku bener, kan? Aku nggak selalu harus bergantung sama laki-laki untuk ngebiayain hidup, nggak itu ayah, nggak juga suami. Aku juga berhak cari uang sendiri."
"Iya, iya," ucap Benjamin akhirnya. Toh kalau dipikir-pikir, pendapat Leda tidak sepenuhnya salah.
"Terus, kerjaan kamu ngapain aja? Neliti pergerakan benda-benda langit? Prakiraan cuaca? Curah hujan?" selidik Benjamin kemudian. Tak bisa dipungkiri, dia masih sedikit penasaran. Sedikit.
"Ya, itu semua. Kadang aku ngasih info atau warning kalau ada prakiraan cuaca ekstrem, lewat sosmed. Itu loh, pake fitur story yang hilang setelah 24 jam. Terus biasanya kalau bulan puasa, aku bantu cari posisi hilal, mastiin hari raya jatuh di tanggal berapa. Hmmm ... gitu deh, pokoknya."
Benjamin tak habis pikir. Sepertinya gadis di sampingnya ini sedang berbicara ngelantur.
Mana ada orang yang bekerja dengan konsep tidak jelas seperti ini?
Untungnya orang yang mempekerjakan dia apa?
Profitnya dari mana?
Faedahnya apa?
Tak ada kontribusi dalam perkembangan ekonomi sama sekali!
Benjamin menghela napas, entah hendak percaya pada Leda atau tidak. "Oke, jadi intinya, kamu bekerja untuk ayah kamu sebagai weather reporter, begitu?" simpul lelaki itu.
"Bukan, bukan weather reporter. Aku ini Agen Cuaca."
Hah? Benjamin kehabisan kata-kata. Ini cewek beneran sinting.
"That's not a real job," ucap Benjamin dingin. "Itu bukan pekerjaan sungguhan."
"Oh ya?" tantang Leda. "Kalau bukan pekerjaan, terus kenapa aku dibayar tiap bulan, hayo?"
Benjamin menghela napas. "Sepemahamanku, ini adalah pekerjaan bohong-bohongan yang nggak nyata, alias akal-akalan ayah kamu aja supaya dia bisa ngasih kamu kesibukan dan juga ngirimin uang buat kamu."
Hening. Benjamin sedikit merasa kalau kata-katanya mungkin saja menyinggung Leda. Toh pekerjaan ini sepertinya adalah topik sensitif bagi gadis itu—sesuatu yang tampak sangat disukai olehnya—tapi Benjamin malah mendiskreditkan hal tersebut dengan tega.
"Lee, sorry, saya nggak maksud—"
"Oh my God," terdengar suara Leda mendesis. "Kamu bisa ngeliat itu dengan jelas, ya?"
"...." Benjamin tak tau harus berkata apa.
"Terkadang hati sama cinta bisa bikin orang begini buta," gumam Leda kemudian. Tak ada amarah yang terdengar dari suaranya.
"Kamu ... nggak tersinggung?" ucap Benjamin hati-hati.
Terdengar Leda mengembus napas. "No, not really. Untuk apa marah? Toh itu kenyataannya."
Benjamin bisa merasakan gadis itu bergeser, membenahi posisinya dalam sleeping bag.
"Aku rasa ... dia ngelakuin itu karena cinta," ucap Leda.
"Ayahmu?" tanya Benjamin.
"Iya. Dia pasti ngelakuin ini karena dia sayang sama aku. Dan juga, kalau dipikir-pikir, cara ini nggak buruk juga. Hehe."
Setelah jeda beberapa detik, suara Leda kembali terdengar.
"Aku suka cara ini. Tandanya ayahku perhatian." Renyah tawa Leda kembali terdengar.
"Lagipula," lanjut gadis itu."Bisa jadi esensi dari aku bekerja sebagai Agen Cuaca bukan sekadar untuk dinafkahi, tapi untuk bonding dengan ayahku di ibukota sana. Sometimes jarak nggak cuma menjauhkan fisik, tapi juga hati. Aku nggak mau jauh hati dengan ayahku."
Benjamin tak habis pikir bagaimana Leda bisa selalu bersikap positif seperti ini. Apakah kata-kata barusan sama seperti senyum yang sering Leda tampilkan di hadapannya? Penuh kepalsuan dan sebenarnya menyembunyikan luka?
"Kenapa sih, Lee?" Benjamin membuka suara.
"Hm? Kenapa apanya?" Leda balik bertanya.
"Kamu!" desis Benjamin tak sabar. "Ada yang salah sama kamu."
Leda tak mengerti. "Maksudnya?"
Lelaki di samping gadis itu menarik napas singkat, mengumpulkan pecahan pikiran yang membuatnya merasa semakin ... gemas.
"Pak Adi bercerita kapan hari sama saya, kalau kamu ini sebenarnya pernah kuliah di Princeton, New Jersey, tapi kamu malah milih untuk drop out dan pindah ke sini—ke desa antah berantah ini. Kenapa, sih? Kenapa kamu ngebuang peluang besar dalam hidup kamu?"
Alih-alih tertohok atas kalimat sang Cokro, Leda malah tertawa ringan.
"Kamu kayaknya mulai kepo sama calon istrimu ini ya, Benjo? Pake interview ke Lek-ku segala. Dasar stalker!"
Tawa Leda tidak menular pada Benjamin. Lelaki itu malah memandang gadis itu, kaku.
"Lee, seriously—"
"Oh, oh! Itu, ITU! LIAT BEN, LIAT ITUUUU!" Leda memotong kata-kata Benjamin sambil menunjuk-nunjuk langit malam. Arahan telunjuknya berujung tepat pada segaris komet yang silap, menyisakan sebaris ekor cahaya. Bintang jatuh.
"Itu komet pertama yang kita lihat malam ini! Ben, cepat, make a wish!" Leda merepet sambil buru-buru menutup mata, mengatupkan tangan seakan sedang memanjat doa.
Seriusan cewek ini masih percaya sama mitos bintang jatuh bisa mengabulkan permintaan? Benjamin berdecak sebal.
"Saya berharap, cewek di depan saya ini akan menjawab pertanyaan tadi dengan segera dan tanpa pura-pura."
Benjamin melafalkan kalimat itu dengan lantang, membuat Leda yang sedang khusyuk di hadapannya sontak membuka mata.
"Jadi, kenapa, Lee?" tekan Benjamin sekali lagi. "Kenapa kamu menyingkir ke pelosok dunia seperti ini? Kamu ini sedang bersembunyi dari apa?"
🌟
[2544 Words]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top