FIFTY-ONE
Raline diam-diam terinspirasi oleh bondage atau shibari --- teknik tali temali untuk membangkitkan hasrat seksual. Rancangannya itu telah mendapat pengakuan dari Marlena. Karya Raline memang unik sekaligus seksi. Berani tapi elegan dan jauh dari kesan jorok atau seronok. Sangat sesuai dengan budaya Indonesia yang masih memegang teguh kesopanan dalam berbusana.
Setiap rancangannya mengandung detail menyerupai ikatan. Pun tren bordir atau renda bernuansa tali temali. Namun semua Raline perhalus agar tak menimbulkan kontroversi. Sesuatu yang khas dari desainnya adalah aksen jalinan. Entah pada risteting, aksesoris sabuk, atau potongan kainnya.
Hasil karya Raline juga mendapat apresiasi ketika rapat divisi. Terbukti dari Jeffrey yang tak mampu memalingkan tatapan dari sang submisif ketika mempresentasikan rancangannya. Jeffrey begitu mengagumi Raline. Andai saja tak ada orang di sana, mungkin ia sudah merengkuh submisifnya ke dalam pelukan dalam.
Perlahan-lahan, semua cemoohan dan gunjingan terhadap Raline memudar. Mereka tak lagi menilai wanita itu secara sebelah mata. Meski Raline adalah 'bawaan' dari sang CEO, ia ternyata memang layak dan mumpuni.
"Raline, kita duluan, ya, Nek!" pamit Adam. Ia sudah berjalan beriringan dengan Derby dan Agnes.
"Hati-hati. Sampai ketemu besok!" sahut Raline. Wanita itu sibuk mengumpulkan sisa pizza untuk diletakkan ke dalam satu kotak yang sama.
Menyadari kesibukan Raline, Agnes pun menimpali, "Raline, biar aja entar diberesin pramu kantor."
"Ng-nggak apa-apa, Nes. Biar aku saja." Raline mengulas senyum lebar.
"Yaudah kalau gitu kita duluan," kata Derby.
Sejurus kemudian ketiga orang itu pun berlalu pergi. Raline kembali sibuk menata potongan pizza masuk ke dalam box yang sama. Hari ini manajer pemasaran ulang tahun, ia mentraktir pizza untuk seluruh staf. Namun makanan itu terlalu berlimpah hingga banyak tersisa. Raline berpikir membawanya pulang untuk dibagikan pada Sintia dan Evi. Senyum Raline terkembang --- Sintia pasti suka. Pikirnya.
Saat ia hampir selesai, Marlena tiba-tiba masuk ke dalam ruangan.
"Eh, Bu Lena belum pulang?" sapa Raline.
Marlena hanya melirik sepintas. Ia lalu meraih structured bag-nya yang tergeletak pada meja.
"Daripada kamu buang, lebih baik kasih ke pramu kantor," celetuk Marlena.
Raline salah tingkah. "Tidak saya buang, kok, Bu. Mau saya bawa pulang --- kalau boleh," sahutnya.
Langkah Marlena terhenti. Ia menatap Raline dengan penuh kebingungan. "Kamu bawa pulang?" tanyanya.
"Iya." Raline mengangguk. "Buat adik saya, Bu."
Marlena kembali menyorot Raline. Seharusnya, sebagai pacar seorang CEO sekaligus pemilik perusahaan wanita itu tak perlu repot membawa sisa makanan. Seutas rasa penasaran menggelitik perasaan Marlena.
"Memang kamu enggak malu apa? Bawa makanan sisa pulang," kata Marlena.
Raline tersenyum. "Kenapa mesti malu? Toh sudah nggak ada yang makan. Kan mubazir. Adik saya juga pasti suka makan ini," terangnya. Ia menenteng boks cokelat berisi pizza.
"Minta Jeffrey belikan, dong. Dia bahkan bisa kasih kamu se-franchise-nya." Marlena berkelakar.
Raline pun berjalan mengiringi Marlena. "Pak Jeffrey sudah membantu saya cukup banyak."
"Bukannya kalian pacaran." Marlena mendecih.
Raline tertawa getir. "Tidak, Bu. Saya dan Pak Jeffrey tidak berpacaran. Mana mungkin seseorang seperti dia bersanding dengan wanita seperti saya," sanggahnya.
"Tidak pacaran?" tanya Marlena berkernyit.
Raline menggeleng. Sorot mata wanita itu berubah nanar. "Tidak."
"Tapi Jeffrey tak pernah memasukkan orang secara sembarangan ke dalam perusahaan. Seleksi pegawai di sini sangat ketat. Kalau kalian tidak memiliki hubungan spesial, lalu apa?" selidik Marlena. Mereka tiba di depan elevator. Ia berinisiatif menekan tombol bersimbol panah ke bawah.
"Hubungan yang rumit." Raline mengembuskan napas berat. "Yang jelas --- Pak Jeffrey membantu saya keluar dari keterpurukan. Mungkin, beliau kasihan sama saya. Makanya beliau banyak membantu saya. Selain itu, separuh dari gaji yang saya terima, saya gunakan untuk membayar utang-utang saya terhadap Pak Jeffrey."
Utang? Marlena makin penasaran. Pintu lift pun terbuka, ia dan Raline kompak masuk ke dalam.
"Memang orang tuamu ke mana?" selidik Marlena lagi.
"Ibu sudah tiada. Sekarang saya tinggal dengan bapak tiri dan adik saya," ujar Raline.
"Bapak tiri? Lalu bapak kandungmu?" Marlena tak berhenti mengintrogasi Raline bak wartawan.
Raline terdiam cukup lama. Setelah mengambil jeda sejenak, ia pun menjawab, "Hmm. Saya tidak tahu di mana dia." Jangankan keberadaannya, identitasnya saja tidak jelas.
"Oh ..." Marlena pun tertegun.
Saat mereka tiba di lantai bawah, Raline membungkuk sopan dan berpamitan. "Bu Lena, mari."
"Pulang sama siapa kamu?" tanya desainer senior itu.
"Naik transportasi umum, Bu," jawab Raline.
Marlena menelan saliva. Ia kemudian mencegah Raline melenggang pergi. "Bareng aku saja."
"Tidak usah, Bu. Rumah saya jauh," tolak Raline. "Lagian jam segini macet."
"Di mana emang rumahmu?"
"Putat Jaya, Bu ..." terang Raline pelan.
Marlena mengibaskan tangan. "Sudahlah. Ayo, biar kuantar."
"Tapi, Bu ..." Raline mendadak segan. Apa lagi mereka kurang akrab. Semua karena perlakuan Marlena yang ketus.
"Buruan!" Marlena melotot sambil berbelok menuju basement.
***
Sesuai dugaan Raline --- atmosfer yang membalut di antara mereka sangat canggung dan dingin. Ada perasaan aneh juga kenapa tiba-tiba Marlena berbaik hati mengantarnya pulang. Raline mulai curiga. Jangan-jangan wanita tua itu hendak memukulinya di tempat sepi untuk meluapkan kekesalan. Ah, tapi kalau soal tenaga ... Raline jelas lebih kuat. Atau jangan-jangan ... Marlena akan menembaknya di semak-semak?!
"Sudah berapa lama tinggal di Putat Jaya?"
Pertanyaan dari Marlena membuat Raline tersentak dari lamunan.
"Da-dari kecil, Bu. Dari lahir," sahut Raline.
"Putat Jaya mananya? Jauh apa dekat dari kawasan prostitusi dulu?" tanya Marlena lagi.
Raline terkesiap. Bukan jauh atau dekat lagi, justru mendiang ibunya terkadang melayani tamu tepat di rumah. "Lumayan dekat, Bu," sahutnya.
"Jadi waktu kecil senang, dong. Banyak lihat hiburan dan akuarium." Marlena meringis.
(Akuarium adalah istilah yang digunakan untuk memajang wanita tuna susila di sebuah ruangan berkaca lebar)
Raline menjawab dengan senyuman kecut. Sementara Marlena mendadak salah tingkah --- sadar kalau komentarnya sangat tidak etis.
Marlena berdeham untuk mengalihkan pembicaraan. "Adikmu umur berapa?"
"Adik saya usia 12 tahun, Bu."
Marlena mengangguk. "Pasti kesepian karena tidak ada sosok seorang ibu di sampingmu, ya?" ucapnya.
"Nggak juga, Bu." Raline mengenang-kenang. Semasa hidup pun ibunya jarang menghabiskan waktu dengannya. Jadi, ketika ia tiada, tidak banyak hal berubah. Kecuali hadirnya Sintia yang justru membuat rumah lebih ramai.
Dahi Marlena berkernyit. "Kok nggak juga?" selidiknya.
"Semasa hidup, ibu sibuk bekerja. Jarang ada waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Saya lebih banyak mengurus semua sendiri. Ketika ibu tiada, tidak banyak hal berubah," terang Raline.
"Jadi biasa saja waktu ibumu meninggal?" tanya Marlena lagi.
"Memang sedih, tetapi tiada perubahan drastis selepas ibu meninggal," sahut Raline. "Ketika hidup, kami jarang menghabiskan waktu bersama."
Marlena terkesiap. Pandangan wanita itu tiba-tiba buram karena pelupuk mata yang dipenuhi genangan air. Caranya menyetir jadi tidak stabil karena tangan yang gemetar.
"Bu? Bu Lena? Bu Lena kenapa?" Raline panik dan menepuk lengan Marlena. Tatapannya terarah pada depan jalan, khawatir mereka bakal menabrak kendaraan lain. "Bu, menepi dulu, Bu," kata Raline.
Marlena lalu membanting setir ke arah samping. Tanpa menyalakan lampu sein, ia berbelok seenaknya. Kendaraan yang berada tepat di belakang membunyikan klakson keras seraya mengumpat kasar. Beruntung, tak terjadi peristiwa fatal.
Jantung Raline berdebar ketakutan. Dia memang sempat berharap mati. Tapi dulu. Sekarang --- setelah rancangannya bakal keluar sebagai koleksi baru the MAXIMAL, Raline justru berharap hidup 1000 tahun lagi. Menggapai mimpi demi mengubah nasib. Lagi pula, Sintia sama siapa kalau dia mati?!
"Bu Lena kenapa?" Raline memeriksa keadaan Marlena. Mobil sudah berhenti di depan sebuah lahan bangunan ruko kosong.
Desainer senior itu mencengkeram kemudi dengan erat. Kepalanya tertunduk untuk menyembunyikan tangis.
Raline sadar Marlena sedang terisak. Ia pun mengusap lembut punggung atasannya itu. "Bu Lena sakit? Apa perlu saya minta bantuan rumah sakit?"
Marlena menggeleng. Pelan-pelan ia menegakkan kepala dan menampakkan wajah yang penuh air mata. Marlena menyeka cairan bening itu dengan tangannya. "Aku tidak bisa mengontrol perasaanku saat mendengar perkataanmu, Raline."
"Perkataan saya?" Raline terbelalak. Perkataan yang mana yang hampir membuat mereka terlibat kecelakaan?!
"Ya ..." gumam Marlena lirih. "Perkataanmu menusuk tepat di jantungku."
"Ya Tuhan, Bu? Saya tidak bermaksud begitu." Raline makin salah tingkah. Ia benar-benar tak tahu bagian mana yang salah dari ucapannya tadi.
Marlena menggeleng. "Tak perlu minta maaf. Aku yakin kamu pun tak sadar, bukan?" Ia menoleh dan memandang wajah Raline dengan lamat.
Raline dan Marlena cukup lama saling berpandangan.
Sang desainer senior pun menarik napas panjang untuk mengatur emosi. Setelah merasa cukup tenang, Marlena kembali melanjutkan, "Aku memiliki seorang anak lelaki satu-satunya, Raline. Aku begitu menyayanginya dan berencana tidak akan menambah anak lagi. Jadi aku pikir, aku akan memberikan segalanya untuk anak ini. Pendidikan yang baik, materi berlimpah, semuanya ..."
Raline menatap Marlena dengan saksama. Ia sudah tahu kisah itu dari Jeffrey. Namun ia tetap mendengarkan sebaik-baiknya karena berempati.
"Aku bekerja sangat keras untuk mewujudkan kebahagiaan anakku tadi. Tapi aku ternyata salah. Aku bekerja seperti orang gila bukan demi anakku. Melainkan karena obsesiku semata. Aku terlalu ambisius mewujudkan impianku. Aku lupa bahwa aku adalah seorang ibu. Aku lupa berhenti sejenak untuk meluangkan waktu dan duniaku untuk dia." Air mata Marlena kembali tumpah. Ekspresi wanita itu begitu pedih. "Ketika kamu bilang bahwa kamu terbiasa tanpa ibumu, itu membuatku sangat terpukul. Kurasa, itu juga yang dirasakan oleh anakku. Sudah terlambat bagiku untuk menebus semua waktu yang hilang. Meski saat ia sakit aku ada di sisinya, semua sudah terlambat."
"Bu Lena ..." Raline membisik seraya menggenggam tangan Marlena.
"Ketika dia sakit, dia memandangku bak orang asing. Kupikir itu wajar. Mungkin, dia tidak nyaman karena serangkaian treatment dari rumah sakit. Aku mencoba membohongi diri sendiri. Padahal sudah jelas kalau anakku lebih rindu dengan papanya. Bahkan, ia lebih sering mencari pembantu kami ketimbang aku yang ibunya. Aku tidak mau mengakui kalau dia terbiasa tanpa kehadiranku." Tangis Marlena makin pecah.
"Bu Lena, meski terbiasa tanpa ibu, saya tetap mencintai beliau. Kurasa itu juga yang dirasakan oleh anak Bu Lena," ujar Raline mencoba menenangkan.
Marlena menggeleng. "Aku bahkan tak ada saat dia pergi. Aku sibuk menyiapkan pagelaran busana koleksi terbaru the MAXIMAL. Aku memang ibu tak becus! Kasihan anakku, terlahir sebagai seorang anak dari ibu sepertiku! Kesedihan kini menggerogotiku, entah apa pikiran anakku terhadapku. Ia mungkin sama sekali tak menganggapku ada."
Raline mulai berkaca-kaca. Dulu ia pernah dengar --- seseorang yang tampak keras dan ketus dari luar adalah seseorang yang menyimpan kesedihan mendalam. Ia sekarang mengakui itu benar. Marlena bersikap dingin dan tegas demi menyembunyikan kerapuhannya.
"Sekarang semua sudah terlambat. Terlambat untuk menebusnya! Terlambat untuk menebus semua waktu yang terbuang. Oh Tuhan ..." isak Marlena pecah.
Raline membiarkan Marlena meluapkan kesedihan. Percuma meminta orang berduka untuk bersabar. Sabar tak semudah membalikkan telapak tangan. Apa lagi memintanya untuk berhenti menangis. Biarlah air mata Marlena menjadi penghapus perihnya. Raline hanya terdiam dan menemani Marlena tanpa berkata apa pun.
Detik demi detik berlalu.
Tangisan itu pun melemah dan berganti dengan tawa kecut dari Marlena.
"My God! I'm so ridiculous! This is embarassing!" Marlena menarik beberapa helai tisu untuk mengelap hidung yang memerah.
Raline ikut tersenyum getir. Ia memandang Marlena dengan canggung. "Maaf, Bu. Tapi artinya apa?" tanyanya.
Marlena terpegun sesaat. Tawa wanita itu pun pecah. Raline Lara telah mencampur aduk perasaannya. Semula membangkitkan kesedihan, sekarang dengan polosnya membuat komentar tak terduga.
Melihat Marlena terbahak, Raline tertular meringis. "Bu Lena maaf. Tapi saya emang tidak pintar bahasa Inggris," terangnya membela diri.
Marlena berusaha menghentikan tawa. "You're an interesting person, Raline Lara."
***
"Bu Lena. Terima kasih sudah mengantar saya." Raline melepas seat belt dan bersiap turun.
Marlena mengulas senyum tipis. "Jangan sampai kamu membocorkan soal tadi ke orang-orang di kantor. Andai aku mendengar gosip tentangku, aku tidak akan segan merobek mulutmu."
"Tenang saja, Bu. Saya tidak akan menceritakan soal tadi. Justru, terima kasih karena telah membagi kisah hidup Ibu pada saya," ucap Raline.
"Hmm." Marlena bergumam tak acuh.
Sebelum membuka pintu mobil, Raline kembali berkata, "Bu Lena, anak Ibu sekarang sudah bahagia dan tenang. Kurasa, pada akhirnya ia tahu betapa besar cinta Ibu Lena padanya. Berhentilah merasa bersalah dan jalani hidup semaksimal mungkin. Bu Lena dan dia masih tetap terhubung melalui doa." Ia lalu tersenyum.
"Thank you, Raline." Bibir Marlena membentuk garis melengkung ke atas. Hatinya lagi-lagi terenyuh.
Suara berisik dari warung kopi di seberang jalan membuat perhatian Raline terusik. Mata wanita itu kemudian terbelalak begitu menyadari siapa yang membuat rusuh.
"Bu, kalau begitu saya pamit. Terima kasih sekali lagi, ya." Raline tergesa-gesa turun dari mobil.
Marlena mengekori sosok Raline yang terburu-buru menyeberangi jalan. Ia penasaran dengan apa yang akan wanita itu lakukan. Tampak dari kejauhan, Raline sedang menyeret tubuh seorang lelaki yang tampaknya sedang mabuk berat.
"Bapakmu bikin ribut!"
"Bawa pulang sana, Line. Jam segini kok udah mendem!"
(Mendem adalah mabuk)
Raline membungkuk minta maaf. Ia menarik tangan Bayu agar bergegas pergi menjauhi warung kopi. "Sepurane, yo, Mas!" serunya meminta maaf.
Marlena akhirnya melajukan mobil dan pergi menjauh. Semua penilaiannya terhadap Raline Lara berubah total. Kendaraan desainer senior itu pun membaur di antara kemacetan. Ia mengambil jalan yang berbeda dari rumah. Alih-alih pulang, Marlena akan mengunjungi makam mendiang sang anak --- tercinta.
***
Bulan demi bulan berlalu.
Mewujudkan rancangan Raline dalam bentuk fisik membutuhkan waktu tidak sebentar. Setelah memantapkan pola rancangan, tim desainer pakaian akan mendiskusikan bahan kain yang cocok. Derby selaku Textile Designer membantu Raline menemukan material yang sesuai untuk semua pakaiannya. Ketika sudah siap, tugas beralih ke Adam. Ia menjabarkan desain teknis yang berisi detail pakaian, misal di mana jahitan dan kerutannya. Dokumen yang Adam buat merupakan acuan untuk Pattern Maker dalam pembuatan pola. Terakhir, semuanya bakal diserahkan ke Production Assistant untuk di bawa ke pabrik.
The Sinner karya Raline dan La Petite karya Marlena akan diluncurkan sebagai koleksi terbaru the MAXIMAL. Sebuah acara besar yang diadakan bertepatan dengan ulang tahun brand ternama itu.
November. Menjadi bulan yang ditunggu-tunggu Raline. Pada akhirnya semua kerja keras wanita itu terbayarkan. Ia akan melihat rancangannya dalam wujud nyata. Tak hanya dia, semua orang. Orang-orang yang cukup berpengaruh dalam industri fesyen.
Raline sama sekali tidak menduga apa yang akan terjadi saat itu tiba.
***
Anwar melonggarkan ikatan dasi. Ia lalu menghampiri Misye yang sedang membaca buku di atas tempat tidur.
"Kamu sudah melakukan apa yang kusuruh?" tanya Anwar.
"Memesan tiket ke Surabaya?"
Anwar mengangguk. "Ya."
[ KINKY sudah tamat di KARYAKARSA - Naskah utuh tanpa potongan ]
"Sudah, Pa. Bahkan Carissa juga akan ikut dengan kita," terang Misye antusias.
Anwar berdecak. "Anak nakal itu. Kalau dia pergi, siapa yang mengawasi perusahaan?" sungutnya.
"Sudahlah, Pa. Dia juga rindu dengan kakaknya. Lagi pula ada Wisnu, suaminya, yang berjaga di sini." Misye menutup buku tebal di pangkuannya.
"Aku ingin lihat seperti apa acara ulang tahun the MAXIMAL yang sudah dipersiapkan oleh Jeffrey," ujar Anwar.
"Kuharap kamu tidak memberikan kritik pedas untuknya. Jeffrey sudah cukup hebat membangun bisnisnya dari nol," kata Misye berantisipasi.
"Masih belum sebanding dengan Bahadir Sejahtera. Dan kuyakin the MAXIMAL akan lebih besar jika dia menikahi Adinda. Kamu tahu sendiri, Rafli memiliki perusahaan ritel yang sudah berekspansi hingga Paris dan Spanyol."
Misye menghela napas. "Pa, apa jangan-jangan tujuanmu ke Surabaya untuk kembali memaksa Jeffrey segera menikah dengan Adinda?"
"Tentu," sahut Anwar. "Lagi pula itu bukan paksaan, tetapi kewajiban yang harus Jeffrey laksanakan."
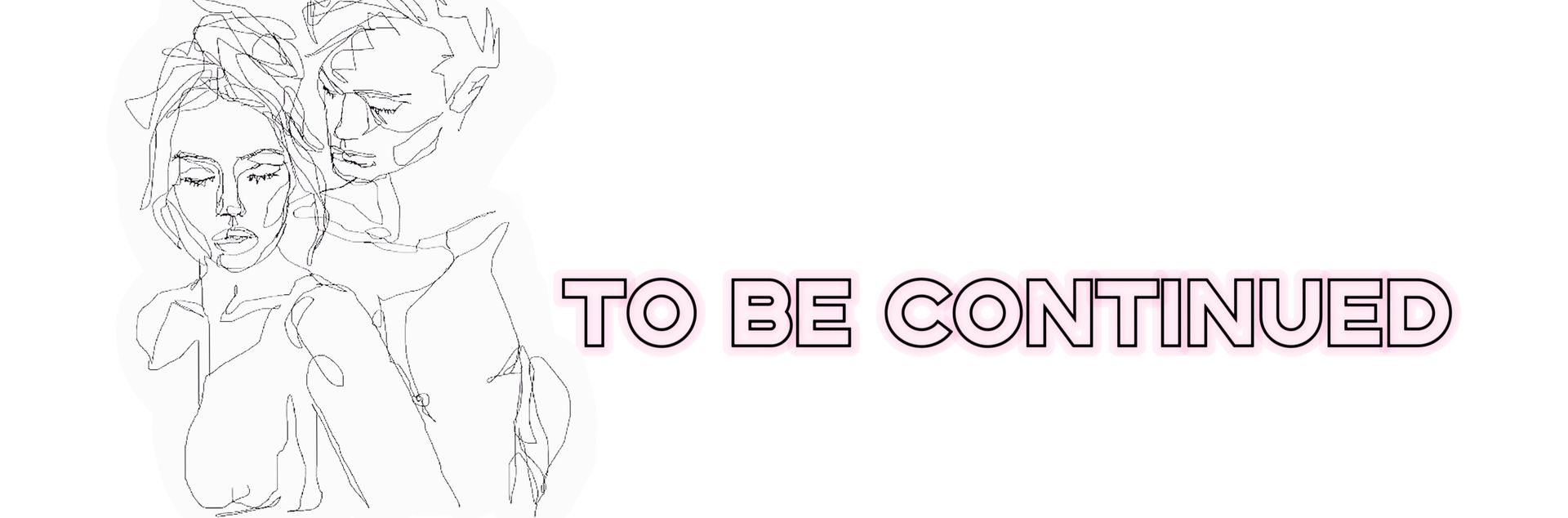
Folks, baca Forbidden Desire di Karyakarsa, yuk. Berkisah tentang Amara - seorang istri kesepian - yang menjalin cinta terlarang dengan Keenan. Duda kaya raya - bos dari suaminya.
Salam sayang! MN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top