16. Ody: Depend on You
Semua orang berlomba-lomba untuk terlihat tegar di depanku. Tapi di belakangku, aku tahu mereka menahan tangis supaya tak menjadi isak. Diam-diam menyeka pipi.
Aku terbangun, entah pukul berapa sekarang. Kepalaku terasa berat hanya untuk mencari letak jam dinding. Tapi aku mengenali, ini ruangan yang sama dengan seminggu lalu. Mataku meninggalkan langit-langit dan mendapati Regan yang duduk—entah sejak kapan—di kursi samping ranjang. Dia segera tersenyum begitu pandangan kami bertemu. Pandanganku menyusuri wajahnya yang terlihat luar biasa lelah, tapi dia berusaha tersenyum—seolah bilang jika masih sanggup duduk di sana beberapa jam ke depan sampai aku bangun lagi. Mencoba menutupi kantuk yang coba ditahan.
Dia kira aku tidak bisa lihat segala raut lelah dan cemas itu.
Bibirku sedikit terbuka, hendak mengatakan sesuatu, tapi suaraku tercekat. Regan yang paham segera bertanya. "Mau minum, Sayang?"
Bukan. Aku hanya ingin kamu tidur dan berhenti terjaga demi aku.
Karena gagal bersuara, akhirnya aku menangis. Aku tahu, aku benar-benar menyusahkan. Regan beranjak dari kursinya, beralih duduk di tepi kasur. Menyelipkan anak rambut yang mencuat ke belakang telinga dengan hati-hati. Dia takut jika rambutku akan rontok jika disentuh dengan gerakan normal.
"Kamu pingsan di kamar."
Iya. Aku ingat. Aku kejang-kejang. Juga ingat teriakan panik dari Mama.
"Kamu tidur tiga jam. Sekarang pukul lima."
Mataku bergerak. Seakan mencari.
"Papa sama Mama di sebelah." Seraya mengusap lelehan air mata di pelipisku dengan jemarinya. Aku tidak sadar jika menangis.
Aku menatapnya lebih dalam. Suaraku kembali, terbata. "Kamu. Tidur."
"Iya, setelah kamu tidur, aku bakal tidur."
Bohong.
"Dih, dih, artinya apa itu? Kamu nggak percaya aku bakal tidur nanti?"
Dia tidak tahu sedang berbohong di depan siapa.
"Ya udah, ya udah. Aku tidur nih." Regan menyibak selimutku. Menempati ruang kosong di tepi ranjang yang sempit. Aku mencoba menggeser tubuh dengan sekuat tenaga, memberinya tempat.
Wajahku berada di antara leher dan bahunya. Dia merengkuhku pelan. Menepuk punggungku dengan lembut. Dalam dekapannya, aku bisa mendengar detak jantungnya. Hangat yang familier segala menjalar. Aku tahu, aku berada di tempat yang benar. Pelukan yang tepat. Lelaki yang mencintaiku.
Bersamanya, aku seharusnya tidak takut dengan apa pun. Tapi aku gagal menepis segala takut yang telanjur merambat di hati. Bagaimana kalau besok, ketika membuka mata, aku tidak bisa melihat wajah lelaki ini, mendengar detak jantungnya dan berada dalam pelukan yang sama?
Bagaimana kalau besok aku kehilangan segalanya?
Saat mencoba terpejam, wajah-wajah orang yang kusayangi membayang satu per satu. Tanpa bisa kucegah, aku kembali menangis—yang mungkin membasahi bahu Regan.
Lantas berikutnya aku merasakan kembali usapan di punggung. Hangat dan tenang.
Kami hanya sama-sama memejamkan mata. Tidak sungguhan tidur. Sepagi itu aku terus merasakan tangan yang mengusap punggung. Regan masih terjaga. Dia tidak tidur seperti yang dia bilang. Lihat, aku bahkan juga merusak jam tidur Regan. Dia sudah lelah bekerja, dan aku harus menambahi beban pikirannya.
Hingga satu jam kemudian, Regan turun dari ranjang. Aku tidak ingin lepas dari peluknya. Aku ... takut menghadapi pagi. Seperti pagi menghantarkan kenyataan yang harus kuterima. Entah penyakit mana lagi yang akan hinggap di tubuhku.
Jendela di ruang inap terbuka. Aku bisa mendengar keritnya ketika dibuka. Mataku mengerjap, menyesuaikan cahaya. Yang pertama kali kulihat adalah punggung Regan. Sebelum dia berbalik dan tersenyum. Dari semua yang berubah, senyum lelaki itu masih sama. Seolah dia bersyukur punya aku di sampingnya. Sekalipun dalam kondisi terburuk seperti sekarang.
Pukul enam.
Regan pamit ke kamar mandi. Terdengar gemericik air. Lantas semenit kemudian kembali dengan baskom dan handuk kecil. Meletakkannya di kursi, kemudian mengatur tinggi ranjangku.
"Mandi ya. Biar wangi." Sambil memeras handuk dan mengusapkannya di wajahku. Hati-hati sekali.
"Mama?"
"Mama sama Papa pulang sebentar, baru aja. Nanti jam sembilan ke sini lagi."
Jadi aku sempat tertidur? Sampai-sampai tidak tahu Mama dan Papa yang pamit pulang.
"Mbak Maya?"
"Belum aku kabari." Handuk berpindah ke leher. "Aku kabari habis ini ya."
"Nggak usah. Nanti ngerepotin." Aku tidak mau Mbak Maya yang sedang hamil harus bolak-balik ke rumah sakit, bahkan sampai harus ikut menunggui di sini. Dia harusnya fokus ke janin di kandungan, banyak-banyak istirahat, tidak perlu repot-repot mengurus aku juga.
Regan mencelupkan handuk dan berpindah ke tangan kiriku. "Oke. Kalau Mas Kinan?"
"Jangan juga."
"Tapi jangan marah sama aku kalau misal mereka muncul sore nanti ya."
Aku cemberut. "Iya sih. Mama pasti ngabarin."
Sarapan datang lima menit kemudian. Regan menyingkirkan baskom dan handuk. Dan aku baru menyadari kalau dia masih mengenakan celana kain selutut—yang dipakainya semalam di apartemen.
"Mas, nggak bawa baju ganti?"
"Nggak sempat, Dy."
Aku menoleh ke jendela, masih mendung. Belum hujan. Ini alasan kenapa Regan tadi membuka gorden. Tidak akan ada sinar matahari yang menerobos masuk pagi ini.
Regan sudah duduk di kursi dan menyuapiku sarapan. "Tadi aku ngobrol sama dokter Tamara, Dy. Kamu bisa mulai terapi minggu depan. Sebenarnya besok pun bisa, tapi biar kamu istirahat dulu."
"Yang kulakukan semingguan ini juga istirahat, Mas."
"Kamu selama ini 'kan kerja terus. Sibuk. Anggap aja sekarang istirahatmu dirapel."
"Nggak ngaca ya?" sindirku.
Regan terkekeh. "Aku kerjanya buat masa depan kita."
"Iya, makasih ya."
"Udah tugas lelaki, bahkan sebelum dia meminang anak perempuan orang, dia harus menyiapkan segalanya."
"Aku ingat percakapan kita waktu itu. Aku nggak nyangka ternyata perempuan itu aku."
Regan mengangkat bahu. "Kamu baru tahu? Padahal pas bilang itu, aku batin nama kamu. Nggak sepeka itu ya kamu."
"Halah. Gombal deh."
Eh, sungguhan?
"Beneran."
"Tapi mana bisa aku peka, sih, Mas. Nanti yang ada aku terlalu berharap. Aku yang cinta sendirian. Sementara kamu, yang suka kabur-kaburan, justru nemuin perempuan yang lebih baik entah di mana."
"Kamu dulu begitu, Dy. Cinta sendirian."
"Eh, nggak ya. Coba yang duluan ngaku cinta siapa?"
"Aku. Tapi kamu duluan yang bilang."
"Terus ungkapin cinta pas Mas Dipta telepon pula. Sengaja banget."
"Ya biar efesien, Dy. Mau nikung dari depan kok kayaknya nggak mungkin. Ya udah, ada kesempatan waktu itu, gas aja. Yang kayak gitu nggak datang dua kali. Aku nggak nyesal kok."
"Rese ya."
Aku hendak tertawa, tapi dorongan dari kerongkongan jauh lebih besar. Alih-alih tertawa, aku justru memuntahkan empat suap bubur yang baru masuk ke perutku. Regan sedikit lengah, hingga muntahanku jatuh di atas tangan dan mengotori selimut.
"Mas ...." Aku menoleh.
Seraya membersihkan muntahan di tanganku dengan tisu, Regan mengusap tengkukku. "Nggak apa-apa, muntahin lagi."
"Selimutnya—"
"Nggak apa-apa, nanti minta ganti."
Seiring dengan usapan tangannya di tengkukku, aku memuntahkan sisa sarapan bersama cairan bening. Kepalaku rasanya berat. Setelah aku minum seteguk, Regan membantuku berbaring. Sementara dia melipat selimut kotor dan membawanya keluar. Hanya sebentar, kemudian muncul di pintu dengan membawa selimut bersih. Membentangkannya hingga sebatas dadaku.
"Dibuat tidur dulu ya. Kalau nggak mau bubur atau nasi, aku belikan yogurt pas kamu bangun nanti."
Aku menatapnya, lagi-lagi sambil menahan air mata. "Kamu nggak kerja, Mas? Ini hari Senin."
"Ngapain sih kerja terus? Nanti aku kaya raya, terus lupa diri."
Dalam hati aku mencibir. Tapi aku tahu dia hanya bercanda.
Namun, sesaat kemudian aku diberi jawaban yang serius. "Aku kayaknya mau ambil jatah cuti tahunan, Dy. Nggak bisa aku ninggalin kamu kerja."
"Maaf, ya, Mas. Aku bisanya cuma bikin repot."
"Aku senang kamu repotin." Regan membenarkan ujung selimut di kaki ranjang. "Aku jadi sangat penting buat hidup kamu. Merasa dibutuhkan. Merasa diandalkan. Dah, tidur gih." Lalu menepuk-nepuk kakiku.
Kakiku yang kebas memang tidak bisa merasakan, tapi mataku melihat gerakan tangannya.
"Kalau aku tinggal tidur, kamu mau ngapain?"
Kepalanya meneleng. "Mungkin mandangin kamu."
Kalimat sederhana yang selalu bermakna. Aku tidak tahu, berapa banyak terima kasih yang harus kuberikan pada lelaki ini.
Kutatap Regan dengan penuh penghargaan.
Bisakah selamanya kamu menjadi bahu yang kutitipkan seluruh semestaku di sana? Apakah tidak apa-apa jika aku terus merepotkan? Aku butuh kamu. Aku mengandalkan kamu.
Apakah aku terdengar begitu egois? Tidak, 'kan? Aku hanya ingin kamu terus di sini, di sampingku.
***
Tidak perlu mengaca, aku tahu jika wajahku membulat. Obat yang diberikan dokter tadi pagi mulai bereaksi. Ruam di wajah memang berangsur hilang, juga di tangan. Dosis obat yang ditambahkan membuat sedikit perubahan. Aku merasa sedikit membaik dan sebagai efek samping; moonface dan aku akan sering muntah ketika mencoba menelan makanan.
Sore ini ruang inapku ramai. Aku senang mereka semua datang, termasuk salah satu di antaranya Mbak Maya. Dokter Tamara baru saja visit dan Papa sepertinya mengajukan beberapa pertanyaan ketika dokter hendak meninggalkan ruangan. Mungkin sengaja, Papa tidak ingin aku ikut dengar.
Sofa sudah dikuasai oleh kedua kakakku. Mas Kinan masih memakai kemeja kerja, lengannya digulung sebatas siku, dasinya dilonggarkan lalu disampirkan, jasnya entah ke mana. Sementara Mbak Maya, duduk meluruskan kaki—kedua kakinya diletakkan di atas pangkuan Mas Kinan. Bukan bermaksud kurang ajar, toh Mas Kinan santai-santai saja, tidak marah. Sementara kedua kakak iparku terpaksa duduk di karpet.
Regan? Kata Mama tadi sempat tidur di kursi sebelah ranjang, lalu dibangunkan dan disuruh Mama pindah ke ruang sebelah—khusus keluarga pasien.
"Halo, halo, halo."
Tebak siapa yang muncul di pintu dengan senyum lebar?
Iya. Kiki.
Sayang, belahan jiwanya sedang tidur di sebelah.
"Eh? Kiki ya? Masuk, Nak, masuk." Mama berhasil mengingat dan mempersilakan masuk.
Kiki menyalami Mama dengan sopan, lantas beranjak ke empat kakakku yang menguasai area sofa. Parsel buah yang besar itu diletakkan di meja sofa sebelum mendekat ke ranjang lagi.
"Duduk, Nak Kiki." Mama berdiri, bergabung dengan anak dan mantunya, membiarkan tempatnya dipakai oleh Kiki.
"Suami yang merangkap calon kakak ipar gue mana?"
Jika dalam keadaan normal, tanganku akan ringan saja melayangkan tabokan. Kali ini aku hanya terkekeh. "Tidur di sebelah."
Alih-alih menanyakan kondisiku, Kiki justru sibuk bercerita soal maminya yang mengamuk karena Kiki memilih EO yang terlalu murah. Bukan, itu bukan pamer. Aku mendengarnya hanya sebatas dia butuh teman berkeluh kesah.
Ada perasaan senang ketika Kiki lancar bercerita. Dia menganggapku normal. Bahwa aku Ody yang biasanya. Bukan Ody yang pesakitan. Meski aku harus mendengar ceritanya dengan berbaring dan selang infus menempel di tangan. Hebatnya, dia sama sekali tidak prihatin atau sungkan.
"Terus gimana?"
"Gue balikin semuanya. Rugi dah gue. Uang DP melayang. Tapi nggak apa-apalah."
"Coba pakai jasa EO yang ngurus nikahan gue sama Regan aja. Bagus terus simpel."
"Nah, iya deh. Nanti gue minta kontaknya ke Adriana. Atau nggak, biar dia aja yang urus, kayak rencana awal."
"Emang sebelumnya gimana?"
"Kita bagi tugas. Gue cari EO sementara Adriana yang ngurus printilan lain. Tapi kayaknya bakal kebalik tugasnya. Belum lagi masalah kain yang dibikin drama sama Mami." Kiki mengacak rambut. Suaranya tetap konstan. Tidak meninggi meski terdengar kesal—sadar tempat sepertinya."Lama-lama gue nikah di KUA aja, nggak usah resepsi, langsung cus honeymoon ke mana ajalah penginnya Adriana gue bakal iyain."
"Tapi kalian 'kan punya keluarga besar."
"Nah, itu masalahnya. Gue nggak bisa ninggalin keluarga besar. Yang ada gue diamuk terus dikebiri, asal banget nikahin anak orang. Istilahnya gitu 'kan para orangtua. Nggak ada acara resepsi berarti gue bakal dicap begitu. Aslinya mah, gue orangnya nggak mau ribet. Nggak maksud remehin atau asal nikahin aja."
"Ya udah, nurut aja, biar lebih gampang."
"Ho'oh." Kiki mengangguk. "Eh, lo gimana kondisinya? Mulai terapi minggu depan ya? Suami lo katanya mau ambil jatah cuti tahunan minggu depan."
Aku ternganga. Setelah curhat singkat itu, akhirnya dia bertanya kondisiku. Tapi kalimat Kiki barusan menunjukkan kalau dia sudah menelepon Regan. Buktinya, seperti biasa, orang ini serba tahu. Ya meski, untuk beberapa hal, dia tetap kecolongan.
"Masih gini aja."
"Yang semangat dong, Dy. Lo punya support system yang bagus banget. Ini aja yang di ruangan baru seperempat 'kan. Coba ngumpul semua, udah kayak mau tawuran." Dia mencerocos. "Terus jangan pernah punya pikiran nggak enak karena ngerepotin Regan, bikin kerjaan dia berantakan dan bla bla bla. Dia sedih malahan kalau lo gitu."
"Regan cerita?"
"Nggak. Udah kebaca dari raut wajah lo."
"Udah malem. Pulang sana."
"Adriana mau ke sini, gue nunggu sekalian." Kiki berdiri, menepuk lenganku pelan dan mengedip. "Gue capek, mau nyusulin suami lo tidur di sebelah. Adriana suruh bangunin gue nanti."
Dasar ya, manusia tidak tahu diri. Anehnya, aku tidak marah. Mataku terus mengikuti punggungnya yang membuka pintu sebelah, melangkah masuk dan beberapa saat kemudian terdengar omelan Regan.
Sambil mengusap wajah, Regan muncul dari sana. Saat mendekat ke ranjang, dia masih mengerjapkan mata. Wajahnya terlihat merajuk. Tapi manalah bisa dia merajuk kalau ruangan ini penuh orang.
"Re, makan." Mas Kinan menawari. "Maya bawa makanan banyak banget. Dia kayak masakin buat orang demo."
Regan menoleh dan mengangguk. Lalu kembali padaku. "Kamu udah makan? Aku tidurnya lama banget kayaknya."
Mama yang sigap sudah mengangsurkan piring berisi nasi dan lauk ke Regan yang memilih duduk alih-alih menuruti kalimat Mas Kinan. "Makan, Re, dari siang belum makan kamu."
"Iya, Ma. Makasih." Regan menerima piring itu. Nyawanya terlihat belum terkumpul sepenuhnya. Sesekali masih menguap dan mengusap wajah.
Dia kembali menatapku.
"Makan, Mas, aku lihatin nih."
"Iya, siap, Nyai."
***
Cerita ini selesai di bab berapa?
Gak sampai bab 25 pokoknya 😚
Juna barusan juga update 🤗🤗🤗
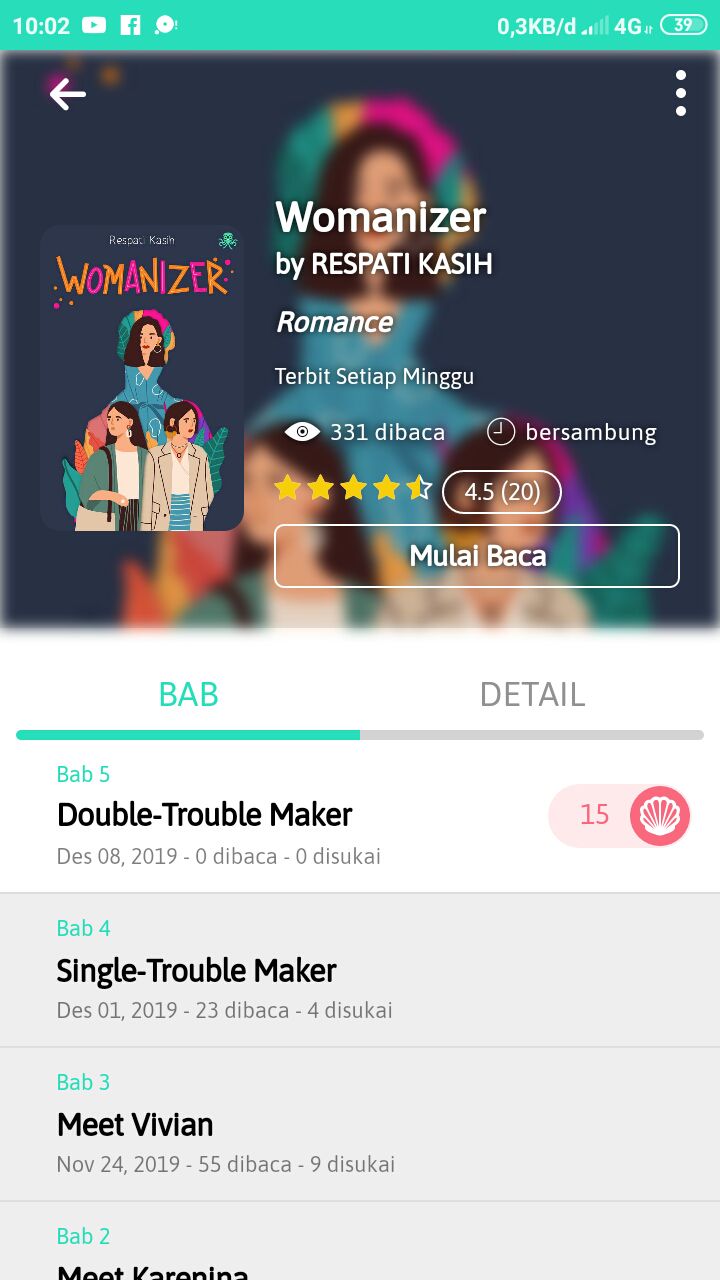
Minggu, 08/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top