Bab 4
Sesekali aku melirik dia yang sedang duduk di meja makan. Dia masih duduk manis menungguku membuatkan sarapan untuknya. Aku tersenyum dalam diam mengingat apa yang terjadi satu jam yang lalu.
Masih teringat jelas derai tawanya. Meski dia belum banyak berbicara. Secepat itu dia bisa meleburkan dirinya. Meninggalkan sosoknya yang nyaris tanpa ekspresi. Aku juga mengingat jelas ekspresi wajahnya ketika mendengar ceritaku. Kisah konyolku dengan teman-teman. Bahkan dia bisa tertawa ketika aku bercerita.
"Hidupmu sempurna. Penuh kisah," ucapnya di akhir ceritaku.
Aku menanggapinya dengan senyuman tipis. Memang penuh warna. Jatuh bangun, sedih, marah juga bahagia. Tapi hal yang tidak dia tahu, ketika aku terjatuh atau terpuruk aku hanya bisa diam menahan. Tanpa bisa mengekspresikan lewat tangis.
"Masih lama?" tanyanya membuatku tergagap dari lamunan.
"Emh, sebentar lagi," jawabku meyakinkan. Aku segera meletakkan dua keping pancake di atas piring untuknya.
Begitu selesai aku segera membawa piring itu ke hadapannya. Dia mengucap thanks tanpa suara.
"Aku suka madu," ucapnya.
"Oke," sahutku pelan sambil mengambil botol madu untuk disiramkan ke atas dua keping pancake miliknya.
"Minum?" tanyaku.
"Air putih di pagi hari itu baik."
Sebuah jawaban yang cukup panjang. Tapi aku suka untuk sebuah permulaan. Dia sudah memulainya dengan cukup baik.
Aku mengambil gelas dan menuangkan air untuknya. Mengamatinya dalam diam.
"Fahsai."
"Hm?" sahutku di antara kunyahanku. Aku mengangkat wajahku, menoleh padanya.
"Kenapa kamu tidak takut?" tanyanya setelah menelan makanannya.
"Takut apa?" tanyaku mengernyit.
Dia diam. Tangannya mengambil gelas miliknya, meneguknya beberapa kali. Seperti biasa, dia tidak langsung menjawab. Dia malah kembali menyantap makanannya.
"Aku."
"Emh, memangnya aku punya pilihan?" Aku berbalik tanya.
Memang benar. Apa aku punya pilihan? Bahkan sejak awal kedatangannya hingga hampir setahun tinggal bersamanya.
"I like you," sahutnya pelan bahkan nyaris tak terdengar.
"Hah?"
"Tidak ada. Aku hanya mendapat jawaban."
"Mengenai?"
Aku semakin bingung. Sedang dia selalu dalam sikap tenangnya. Air telaga bahkan kalah dengannya.
"Orang sepertimu, tidak mudah jatuh. Dan orang sepertimu... Cukup aku saja yang tahu."
Mataku menangkap senyum misterius darinya di balik sikap tenangnya. Sementara dia tidak tahu bahwa kalimatnya hampir saja meloloskan potongan pancake yang belum terkunyah ke dalam kerongkonganku.
"Hm," responku singkat.
"Aku sudah selesai. Aku tunggu di bawah," ucapnya beranjak dari duduknya. Dia membawa piring kotornya, menempatkannya di samping perangkat masak yang kotor.
"Mau kemana?" tanyaku dengan cepat menelan makanan.
"Kamu temani aku," jawabnya.
Belum sempat aku bertanya lagi dia sudah meninggalkanku. Aku hanya melihat punggungnya menghilang masuk ke kamar.
Dengan cepat aku menghabiskan sarapanku. Kemudian masuk ke kamar, mengambil jaket hodie untuk melapisi kaos putih tanpa lengan. Aku menjejalkan kakiku pada sepatu sneakers sedikit asal.
Entah dia ingin pergi kemana. Aku mendapati dia berdiri di depan lobi apartemen menungguku. Tubuhnya hanya terbalut kaos abu-abu dan celana training hitam. Dengan sepatu sneakers membungkus telapak kakinya.
"Mau kemana?" tanyaku mengulangi pertanyaanku tadi.
"Ikut saja," jawabnya meraih tanganku, mengenggamnya kemudian membawaku melangkah.
Sedikit terkejut. Genggaman tangannya begitu erat namun terasa hangat. Sejenak aku merasa asing ketika rasa nyaman itu terhubung.
Dia membawaku berjalan melewati jalan yang sudah tidak asing. Aku sering melewatinya ketika berangkat bekerja. Aku melihat dia menatap lurus. Wajahnya tenang. Tapi hembusan napasnya membuatku menyimpulkan bahwa dia sedang berusaha meyakinkan dirinya.
Masih dalam diam, aku menatapi, tidak ingin bertanya ketika dia berhenti di depan gerbang pemakaman. Hanya sesaat. Setelah kulihat dia menarik napas dalam-dalam, dia mengeratkan genggamannya lalu membawaku masuk ke sana. Berjalan di antara pusara. Hingga berhenti di satu pusara. Tempat yang dia sering datangi.
"Mom," lirihnya menatap pusara itu.
Mom? Aku menahan napas. Ini makam ibunya? Pertanyaan itu muncul di benakku. Aku melihat dia menarik napas, memejamkan matanya dalam diamnya. Seperti dia sedang melebur dalam dimensi lain.
Dia tersenyum tipis, mengangkat genggaman tanganku lalu mengecupnya. Apa yang dia lakukan sedikit membuatku terguncang. Dia melakukan seperti pada kekasihnya sendiri.
"Aku membawanya ke sini, untuk melepasmu pergi. Seseorang yang akan melengkapi kekosonganmu," bisiknya.
Dia terdiam, membuka matanya. Menatap luruh pada pusara itu.
"Mom bisa beristirahat dengan tenang," ucapnya lirih terdengar seperti begitu lega sudah melepaskan apa yang selama ini membelenggu.
Aku menahan napas. Apa yang kusaksikan saat ini membuat perasaanku campur aduk. Tapi aku tidak bisa mengatakan apapun. Hanya mengerjabkan mata karena mataku seperti mulai berembun.
Saat dia membawaku pergi, pun perasaanku belum bisa kukendalikan. Sesekali napasku seperti tersengal-sengal. Tapi dia, aku tidak tahu, sosok tenangnya seperti tidak terusik. Air mukanya masih tenang seperti air telaga. Dia membawaku meninggalkan pemakaman itu. Kali ini dengan langkah seperti tanpa beban.
"Ibumu?" tanyaku membuka suara.
"Ya," jawabnya singkat, melepaskan tanganku dari genggamannya. Kedua tangannya kini tersembunyi di saku celananya.
"Ibu kandung?" tanyaku memperjelas.
Dia menoleh, tersenyum singkat. Aku membulatkan mulutku. Jelas sudah. Jadi yang selama ini dia datangi adalah pusara ibunya. Tapi aku masih merasa aneh. Aku mencium ada kisah sebelum kepergian ibunya. Atau ini hanya sebuah pemikiran konyol efek dari terlalu banyak menonton serial drama?
"Oke," sahutku singkat, mengembuskan napas. Kemudian memasukkan kedua tanganku di saku jaket. Berjalan santai sebagaimana Daniell berjalan.
"Tujuh tahun yang lalu, saat aku 22 tahun. Mom pergi di tangan musuhnya. Persaingan bisnis." Dia mulai menceritakan kisah masa lalunya.
"Mom seorang wanita karier. Pemegang kekuasaan perusahaan keluarga setelah ayahku meninggal.
Hey, kamu tahu? Kejamnya dunia bisnis mengalahkan kejamnya ibu kota," lanjutnya.
"Ayahmu meninggal karena apa?" tanyaku memberanikan diri. Aku tidak tertarik untuk bertanya tentang kejamnya dunia bisnis.
"Sakit," jawabnya singkat, lalu menghampiri sebuah bangku di trotoar, di bawah pohon akasia.
"Terus?" tanyaku, turut duduk di sampingnya.
Dia menarik napasnya, menatap langit. Cukup cerah di waktu menjelang siang ini.
"Aku hidup sendiri. Tidak. Bersama Bram."
Aku mengerang dalam hati. Dia bercerita dengan sangat menyebalkan. Seperti aku sedang menonton serial drama yang endingnya menggantung. Saat ini aku ingin mencekik lehernya.
"Bersamamu juga. Kita baru memulai kan?" Dia menoleh padaku, demi mendapatkan jawabanku.
"Ya," jawabku enggan. Aku masih penasaran dengan kisahnya.
"Fahsai,"
"Hm?"
"Ayo pulang," ujarnya beranjak sambil menarik tanganku.
"Hei!" seruku kesal.
Apa-apaan? Dia masih menggantungkan cerita masa lalunya. Apa dia berniat membuatku mati bunuh diri karena penasaran? Dia hanya terkekeh tanpa melepaskan genggamannya pada tanganku.
"Jangan memprotes. Ingat, kamu sudah berjanji."
"Hm!"
"Menemaniku di sisa hidupku. Oke?"
"Ya!" sahutku sedikit kesal.
"Satu hal yang harus kamu ingat. Apa yang kukatakan tadi di hadapan Mom? Kamu mendengar dengan jelas. Dan apapun nanti yang terjadi, kamu harus mengingat itu."
"Hm!"
"Fahsai," panggilnya dengan nada memperingatkan.
Aku mendengus. Aku mengingatnya. Aku adalah seseorang yang akan melengkapi kekosongan dari bagian ibunya. Entah apa maksud dari perkataannya. Terdengar ambigu bagiku.
"Iya. Aku ingat!"
Senyum tipisnya tercipta begitu singkat. Dalam diam aku berpikir, sepertinya memang aku harus mencari tahu tentang siapa seorang William Daniell. Mungkin nanti aku akan bertanya pada Rania. Atau mencari informasi di internet. Jaman sudah canggih bukan?
"Good girl. That's why I like you," ucapnya tersenyum simpul.
Sedang aku meringis tipis. Tidak tahu harus menjawab apa. Aku bahkan masih tidak mengerti kemana arah yang dia maksudkan. Mungkin sampai dia menemukan seseorang yang dia cintai.
"Sampai kapan?" tanyaku meluncur begitu saja.
Dia menoleh, menyipitkan matanya. Berhenti dari langkahnya.
"Selama aku masih hidup. Di sisa hidupku. Apa yang perlu diperjelas lagi?"
"Jadi kamu akan tetap tinggal di sini?"
"Hm "
"Bersamaku?" tanyaku memperjelas.
Dia mengangguk. Lalu kembali melangkah. Sedang otakku mulai berpikir jauh. Sepertinya aku sudah salah mengiyakan.
"Daniell!" seruku mengejar langkahnya.
"Tapi aku boleh menikah kan?" tanyaku tiba-tiba.
"Menikah?" tanyanya mengulang.
Aku mengangguk. Sudah terlanjur mengucap, mau bagaimana lagi?
"Ya. Maksudku, kalau suatu hari nanti aku bertemu seseorang. Membangun rumah tangga. Kan tidak mungkin seseorang akan hidup terus sendirian," jelasku sedikit terbata.
Dia terdiam, menatapku menyelidik, berhenti dari langkahnya. Tangannya mengacak rambutnya sendiri. Lalu membuang napasnya singkat.
"Akan kupikirkan nanti."
"Hei!" seruku kesal ketika dia kembali melangkah.
"Tidak! Jika itu yang mau kamu dengar!" sahutnya membuatku menjerit kesal.
"Daniell!!!" erangku kesal.
Dalam hati aku memaki dirinya juga kedatangannya. Aku menghentakkan kaki ketika dia mengangkat tangannya, melambai tanpa menghentikan langkahnya. Sebuah tanda bahwa dia tidak peduli.
Aku melangkah gontai, tidak peduli dengan langkahnya yang sudah jauh di depan sana. Sedang aku mulai memikirkan nasib kehidupanku nanti, setelah mendengar ucapannya. Menemaninya selama hidupnya tanpa aku bisa seperti yang lain, menikah berumah tangga.
Mungkin sebentar lagi aku akan mati konyol memikirkan nasib malangku. Demi apapun aku tidak pernah meminta hal ini menghinggapi kehidupanku.
Tapi tunggu, jika aku hanya boleh hidup dengannya? Pikiranku terhenti pada sebuah pertanyaan yang membuat senyumku merekah seketika. Seorang Fahsai tidak akan mudah diperlakukan seenaknya saja oleh siapapun!
Aku berlari mengejar langkahnya yang hampir mencapai depan apartemen.
"Hei!" sahutku tersengal-sengal.
Dia menoleh, berhenti dari langkahnya. Tertawa kecil melihat keadaanku. Tapi aku tidak mempedulikan itu. Aku sedang sibuk mengatur napas, membungkuk dengan kedua tangan bertumpu di lutut.
"Ya?" tanyanya menatapku geli.
Dia pikir aku sedang apa? Aku menarik napas, kemudian menegakkan tubuh. Menatapnya sambil sesekali mengatur napas
"Oke, kalau aku tidak boleh menikah, kamu juga tidak boleh!" ucapku dengan berani lalu mendahuluinya masuk ke gedung apartemen itu.
Aku mendengar langkah lebar. Dia mengejar langkahku. Menjajari langkahku. Tidak berapa lama, dia merapatkan tubuhnya padaku, berbisik.
"Memangnya siapa yang bilang kalau aku akan menikah?"
"Hah?" tanyaku terkejut, "Menikah. Kamu tidak akan pernah menikah?" lanjutku memastikan.
Dia tersenyum hingga kedua matanya membuat garis lurus. Astaga, aku baru menyadari betapa tampannya dia saat ini.
"Aku tidak tertarik mencari wanita lagi," jawabnya membuat kepalaku tiba-tiba pening. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan dari keadaan ini.
***
Tbc
24 april 2018
S Andi
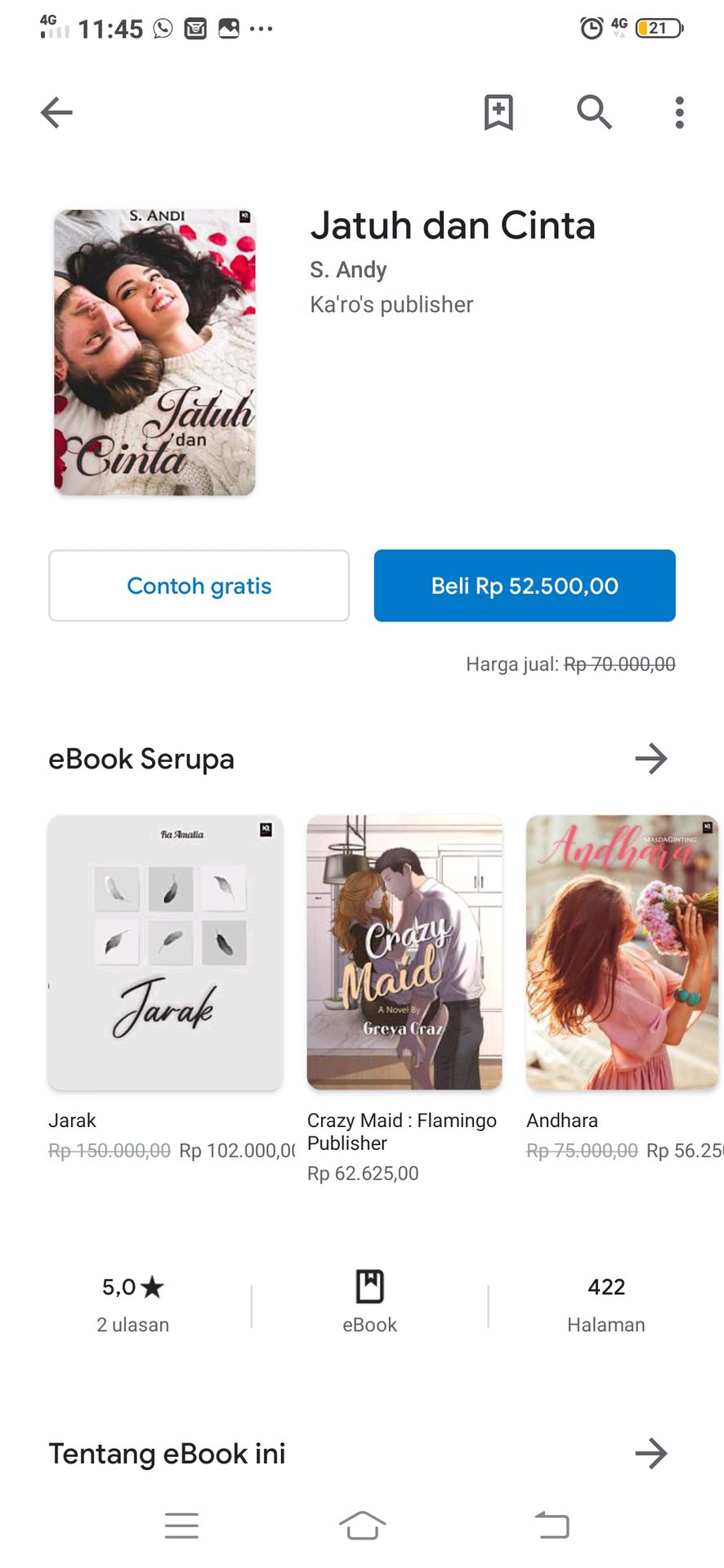
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top