XI. Subuh
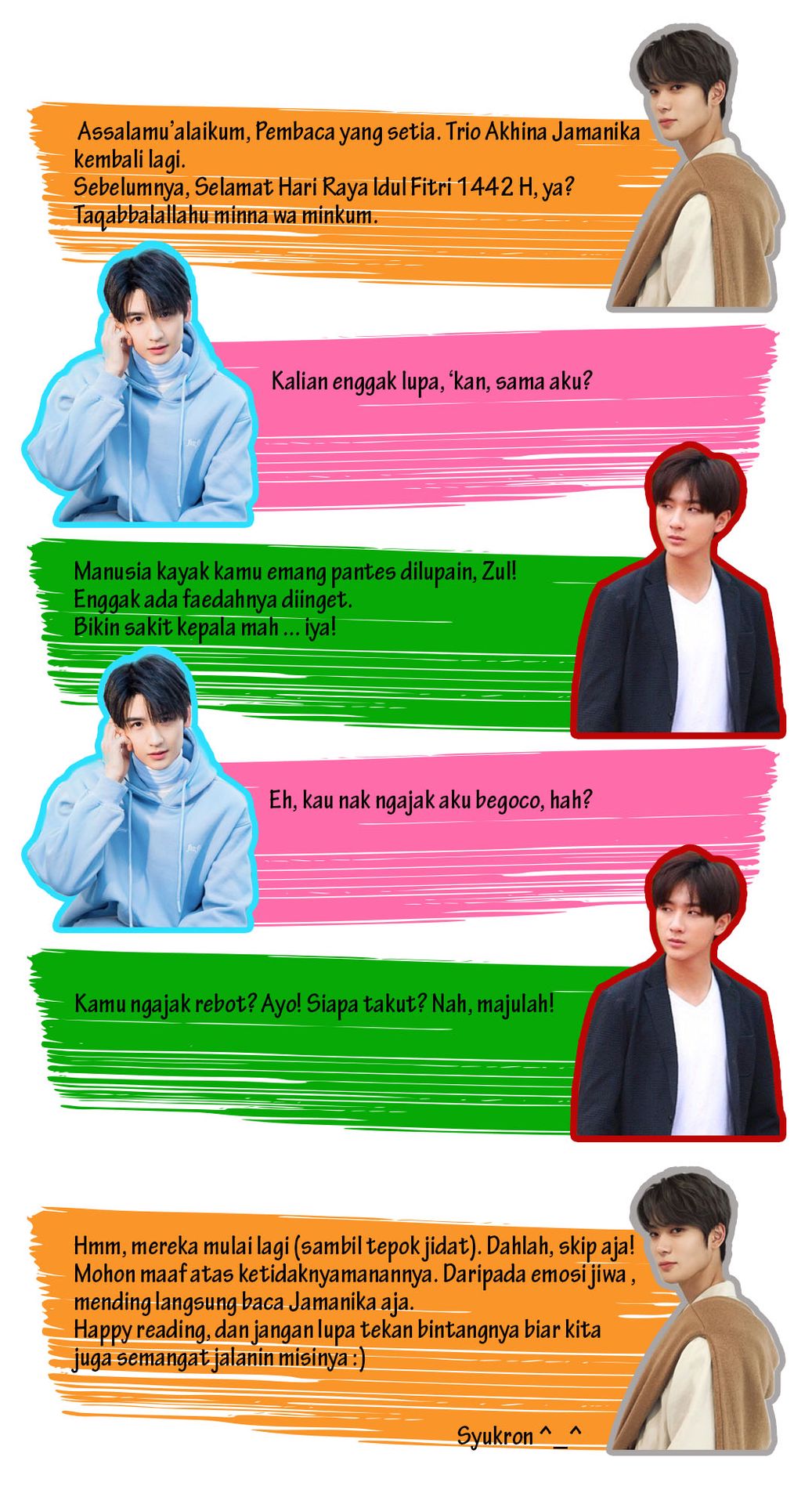
~•~
"Gimana mau menundukkan dunia kalo sholat subuh aja masih ogah-ogahan, masjid juga belum bisa ditaklukan?"
~•~
Suasana kamar Alif seperti biasa, sunyi. Hanya detikan jam yang menghiasi pendengarannya. Jam sudah menunjukkan waktu tengah malam, tapi mata gadis itu masih saja belum terpejam meski ia sudah dalam posisi siap untuk terlelap. Ucapan Ayu di Poskestren tadi terus terulang dalam pikirannya seperti kaset rusak.
Gadis itu mencengkeram erat selimutnya. "Kamu enggak ada di posisiku. Makanya kamu enggak ngerti rasa sakit itu, Yu."
Lamunan itu buyar ketika sebuah bunyi notifikasi pesan masuk ke ponsel Alif. Dalam gelap, ia meraba nakas untuk melihat pengirim pesan di tengah malam itu.
Seratus panggilan tak terjawab. Itu yang menarik atensi Alif ketika ponselnya menyala. Benar, ia mengabaikan panggilan itu seharian. Nama yang ada di sana tidak lain adalah 'Ayuk'―panggilan Alif untuk kakak perempuannya. Seakan tak menunjukkan rasa bersalahnya, Alif langsung menuju WhatsApp untuk menilik pesan yang berhasil membuyarkan lamunannya.
Nama yang sama dengan panggilan tak terjawab itu terpampang paling atas dalam deretan pesan yang belum dibaca. Merasa kasihan karena tak menjawab panggilan, Alif membuka pesan itu. Status dari pengirim itu online, yang seakan sedang menunggu balasan Alif segera.
Ayuk:Dek, Bapak baru aja kecelakaan. Kondisinya parah, dan kemungkinan besar Bapak lumpuh. Dia pengen ketemu kamu, Dek. Pulang, ya? Ayuk juga kangen sama kamu.
Alif bergeming setelah melihat pesan yang diakhiri dengan emot hati berwarna merah. Tak lama ponselnya berdering panjang. Ayuknya memanggil. Rupanya ia bergerak lebih agresif sekarang.
Lama gadis itu berdiam diri, membiarkan panggilan itu berhenti dengan sendirinya sampai kembali panggilan itu masuk. Alif mengembuskan napas. Akhirnya, perlahan dengan keraguan Alif mengangkat panggilan itu. Ia sedikit penasaran, apa yang sebenarnya ingin Ayuknya itu sampaikan. Apakah topiknya sama seperti pesan sebelumnya?
"Dek ... akhirnya kamu angkat juga telepon dari Ayuk."
Suara nun jauh di sana itu tampak bergetar. Apakah ia sedang menangis?
"Pulang, ya?"
Suaranya makin memelas. Apa yang perlu ia tangisi? Pulang katanya? Sekali lagi Alif mendoktrin dirinya sendiri, 'tidak ada rumah untukmu di sana, Alif'.
"Ke mana? Ke mana aku harus pulang? Aku nyaman di sini. Mereka yang tak saling kenal dan bertalian darah bisa menganggapku sebagai manusia yang berhak hidup. Bahkan lebih dekat seperti keluarga. Kenapa harus pulang lagi pada pengharapan yang semu?"
"Dek ... tolong dengerin, Ayuk dulu."
Sebuah penekanan diberikan agar Alif mau mendengar. Namun, hal ini justru membuat pikiran dan batin Alif kembali berperang.
"Kenapa aku harus duluan yang denger?" ucapnya meremehkan. "Padahal dulu aku yang enggak pernah didengerin. Dan ... kenapa baru nyari aku sekarang? Apa setelah ada apa-apa baru kalian sadar keberadaanku?" Alif langsung memasuki jeda kosong di antara panggilan telepon itu. Emosinya kembali membludak tak terkendali. Ia lelah. Ia sangat ingin menjauh, pergi, dan tak kembali pada 'keluarga' yang sama sekali tak mencerminkan kekeluargaan. Hipokrit memang!
"Dek, ini tentang Ba―"
"Apa Ayuk lupa kalau aku cuma anak yang enggak diinginkan?" Lagi, Alif memotongnya. Kata-katanya sangat tajam bagai sebilah pedang.
Gejolak yang sempat padam kembali menggebu. Beruntung dia bisa menekannya selama ini, tapi sekarang ... kenapa lagi? Luka itu seakan kembali menganga. Perlakuan acuh keluarganya ketika Zulfikar mengkhitbahnya tempo hari juga masih membekas. Belum lagi dengan luka yang ia kubur dalam-dalam sebelumnya. Punya keluarga, tapi seperti hidup sebatang kara. Sesak!
Hening. Tiada pembicaraan pada telepon yang masih tersambung. Baik Alif maupun saudarinya itu tak ada yang mencoba memecah sunyi.
"Udah, ya, Yuk. Alif capek," sela Alif. "Besok Alif masih harus kerja biar bisa bertahan hidup di sini," sindir Alif secara tersirat, dan menusuk.
"Assalamu'alaikum!" Tanpa menunggu jawaban salam dari kakaknya, Alif langsung memutuskan sambungan telepon. Masa bodoh kalau kakaknya marah, toh Alif lebih berhak bukan?
Alif memasang mode pesawat pada teleponnya, dan kembali meletakkannya ke atas nakas. Pelan, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan batinnya yang memang sempat sakit sangat parah.
Air matanya yang telah bermuara pun luruh. Jatuh bebas di atas pipi. Panas. Air mata itu terasa sangat panas. Sunyi pun menjadi teman terbaiknya ketika lara kembali menganga. Tangisnya pecah dalam kegelapan kamar tanpa seorang pun mengetahuinya.
***
Husain baru kembali dari kamar mandi. Ia mendesis ketika melihat Zulfikar masih bergulung dalam selimut. Kesal, ia masuk dan langsung menarik selimut Zulfikar. "Bangun, Akhi soleh! Matahari udah mau terbit dari barat tuh!"
Zulfikar hanya menggeliat, membuka sejenak matanya, dan kembali terpejam dalam posisi miring.
Pangeran Steril yang minim kesabaran menghadapai Zulfikar itu beristigfar dalam hatinya. "Bocah ini ... hmmm." Ia lalu melipat kedua tangannya ke depan dada, komplit dengan tatapan dingin yang terkesan cuek. Tak lupa bibir yang dengan sengaja ia cebikkan sesaat. "Gimana mau menundukkan dunia kalo sholat subuh aja masih ogah-ogahan, masjid juga belum bisa ditaklukan? Astagfirullah, Akhi." Ia berusaha menyindir Zulfikar.
Tak ada respons, Husain mengembuskan napasnya keras-keras, memberi aksen agar Zulfikar mendengarnya. "Bisa-bisanya Alif mau sama laki model begini."
Husain bergumam dan langsung melongo ke arah teras tempat Mirza menunggu. Ia pun berkata lantang, "Mas Mirza, duluan aja yuk. Zulfikar kayaknya udah dipanggil sama Yang Maha Kuasa nih. Tuh, buktinya enggak bangun-bangun. Nanti balik dari masjid kita sholatin."
"Aku bangun kok!" Zulfikar terduduk dengan mata yang terbuka lebar dan memunggungi Husain. Sedetik kemudian ia berbalik. "Aku udah bangun, Hus! Tolong jangan disholatin."
Sudut bibir Husain tertarik, menampilkan senyum kemenangan yang begitu kentara meski pandangan Zulfikar masih kabur tertutup kabut mimpi yang tersisa dan tak bisa melihatnya. "Kalo gitu buru! Keburu syuruk, Akhi!"
Zulfikar sontak mengangguk lemah. Ia bangkit dengan susah payah, sampai ia terdiam sejenak. "Eh, Hus, kita enggak sahur, ya?" tanyanya dengan raut panik dan mata yang membulat sempurna. Ia baru sadar akan hal itu.
"Iya."
Zulfikar melongo. "Kok bisa sih, Hus? Emang alarmnya enggak idup? Kamu gimana sih!"
"HP-nya koid."
"Ngapa enggak di-charge semalem?"
"Ya udah sih, enggak sahur sekali aja kayak udah mau mati habis ini," balas Husain dengan sengak seperti biasanya. "Udah buru!"
"Tap―"
"Kalo kamu mau orasi, nanti kusediain mimbar abis subuhan. Sanalah kalo kamu mau orasi uneg-uneg. Un-li-mi-ted!"
"Siapa yang mau aku orasiin? Warga? Atau akamsi?" Kedua alis Zulfikar bertaut.
"Itu ... angin sepoi-sepoi, ilalang sama belalang."
Zulfikar mendelik tak percaya. Keningnya berkerut. Sampai detik berikutnya ia mengalihkan pandangannya. "Hillih, sok bener ngomongin belalang. Kamu aja takut!"
Zulfikar melipat kedua tangannya. "Yang ada nanti nemplok ke kamu lagi? Terus Yang Mulia Husain Altharafisqi Said yang sungguh soleh pingsan seketika." Ia tertawa meledek.
"Sepuluh detik." Bukan balasan seperti biasanya, justru Husain mengatakan sesuatu yang membuat otak Zulfikar nge-bug.
"Ha?" Zulfikar melongo kebingungan.
"Sepuluh detik, kalo kamu belum siap ... kami tinggal!" Husain berbalik dan berjalan mendekati Mirza yang sudah stay di teras sejak tadi. Sementara Zulfikar, masih dengan kebingungannya.
"Hei, aturan macam ap―"
"Sepuluh!" Husain mulai berhitung mundur dari arah depan memunggungi Zulfikar.
"Hus―"
"Sembilan!"
"What the―"
"Delapan!"
Kini Zulfikar yang mendecak kesal. Bukannya berhenti, Husain justru melanjutkan hitungan mundurnya. Dengan terpaksa, Zulfikar buru-buru berlari ke arah kamar mandi untuk bersiap.
"Ck, memangnya dia itu pembina taruna? Enggak, 'kan? Sepuluh detik bisa beberes apa coba? Dasar Pangeran Steril yang nyebelinnya sampe ke DNA!!"
***
Langkah ketiga pemuda itu terhenti di atas jalan utama desa. Sebuah pemandangan mengerikan dalam temaram yang samar di ujung pandang sungguh membuat mereka tak bisa berkata-kata. Guna memastikan, mereka berjalan sedikit mendekat, menyinari pemandangan itu dengan petromaks yang dibawa.
"I―ini ... siapa yang ngelakuin hal semacam ini?"
Ada amarah yang ingin diluapkan seketika itu juga. Sungguh, jika saja ini bukan bulan suci, sudah pasti akan ada yang mengamuk.
_________bersambung________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top