16. Alif Mengingkari Janjinya

Kepergian nenek telah membuat pertahanan emosi kakak tidak bisa dikontrol. Dia marah besar padaku karena telah membawanya pergi hari itu. Tahu-tahu saat kembali ke rumah sakit, nenek sudah tidak ada.
Setiap malam, karena kamarku bersebelahan dengan kamarnya, aku mendengar
isakan kecilnya. Aku dihantui rasa bersalah, seakan kesedihan kakak dikarenakanku.
Berkali-kali aku membujuknya untuk berbicara, tetapi kakak menghindariku, bahkan saat di meja makan.
"Kakak hanya butuh waktu." Begitu kata mama, yang seharusnya bisa membuatku sedikit lebih tenang, tetapi hal itu sama sekali tidak bisa menghilangkan kecemasanku saat ujian berlangsung.
Namun, aku bersyukur kakak tidak mengurung diri saat teman-temannya datang untuk menghibur.
Alif juga datang saat mendengar kabar nenek. Dia sedikit meringankan beban pikiranku. Hanya saja, dia datang sendiri, padahal aku berharap Azul juga datang, atau lebih berharap lagi hubungan kami berjalan seperti sebelumnya.
Selama hampir seminggu aku ditimpa beban yang lebih berat dari sebelumnya. Mama menyarankanku untuk pergi bersenang-senang bersama Alif dan Azul. Mama tak tahu hubunganku dengan Azul merenggang, dan itu lebih baik daripada mama mengetahuinya.
"Kamu masuk tim kami, ya. Harapan kami cuma ada di kamu, loh." Yeni datang ke tempat dudukku, membuatku tersentak kecil, dan juga berhasil mengeluarkan decihan Alif. Cewek itu tak mengabaikannya, lebih fokus akan tujuannya membujukku masuk tim voli untuk pertandingan pasca ujian.
Kurasa itu tidak buruk. Aku butuh pengalihan perhatian dari hanya sekadar mengobrol dengan Alif. Aku menjawab, "Baiklah."
Warna kuning Yeni langsung muncul. "Bulu tangkis, bola tangan, dan tenis meja."
"Apa?" Aku mengernyit mendengar serentetan jenis olahraga dari mulutnya.
"Kamu ikut bersama kami. Kamu, kan, jago. Sudah, ya. Temanmu bikin aku sakit perut." Kemudian Yeni meninggalkanku yang hendak protes.
Sementara itu, Alif terkekeh mendapati raut kesalku. Sesaat aku ingin memukulnya, tetapi dia lebih dulu berkata, "Itu bagus buat kamu, tahu. Aku juga ikut. Bahkan lebih dari tiga." Dia menyombongkan diri dengan mengangkat hidungnya tinggi-tinggi. Dia berbohong, padahal hanya ikut basket saja.
Aku mengibaskan tangan di depan wajah Alif, melirik sekilas pada Azul yang berkumpul di pojok kelas bersama beberapa cowok. Sebagai ketua kelas, seharusnya dia aktif mempersiapkan class meeting. Namun, dia hanya berbicara singkat di depan kelas sesuai arahan bu Yanti, kemudian menyerahkan tugas lainnya pada Yusril.
"Lif. Azul juga satu tim denganmu?"
Sesaat setelah aku mengatakannya, ungu muda keluar dari kepala Alif. Dia tampak kesal setiap kali aku membicarakan Azul.
"Entahlah. Aku nggak tahu." Alif menjawab tak acuh. Ungu muda di kepalanya masih melayang-layang seolah-olah bau tidak enak keluar dari otaknya.
Aku meluruskan kaki, condong ke arah Alif yang sedang membaca komik online. "Boleh aku curhat?"
Mendengar itu, Alif langsung mematikan ponselnya, menatapku penuh keingintahuan.
"Dan ... aku boleh jujur?"
Terdiam sesaat, kemudian Alif mengangguk. Tentu saja dia tidak akan keberatan. Alif-tentunya juga Azul-merupakan pendengar yang baik.
"Akhir-akhir ini, masalahku semakin buruk." Aku memulai. Alif yang mendengarnya, dan sepertinya juga tahu ke mana arah pembicaraan ini, dia menunduk. "Kakak membenciku."
Alif segera menatapku seolah-olah perkataanku ini adalah kodok yang melompat ke depan wajahnya.
"Aku yang telah membuatnya sedih berkepanjangan," lanjutku. Mengingat hal itu, seketika dadaku serasa diremas. "Aku tidak tahu sampai kapan dia akan seperti ini."
"Maaf." Alif menyela sembari menunduk. Warna biru muncul, menyatu dengan kelap-kelip di sekita kepalanya. "Karena aku, kamu ... mengalami hal yang sulit. Aku minta maaf."
Aku tersenyum. Tujuanku memang untuk membuat Alif menyesali perbuatannya tempo lalu, dengan harapan agar dia bisa membicarakan hal ini dengan Azul. Sulit sekali mengangkat topik ini dengannya di setiap ada kesempatan. Aku takut Alif akan menjauhiku seperti Azul, dan ternyata dia tidak demikian.
"Bukan aku." Ini baru permulaan. Kuharap Alif benar-benar tidak akan meninggalkanku. Kutatap wajah Alif takut-takut, lalu melanjutkan, "Azul yang seharusnya mendengar itu darimu."
Aku kira, Alif akan marah padaku lantaran dia terdiam tanpa ada warna di sekitar kepalanya. Namun, ketakutanku sirna saat ia berucap, "Akan kucoba ... lain waktu."
Entah lain waktu itu kapan. Aku sudah tidak sabaran melihat mereka saling berhadapan dan mengobrol, padahal Alif baru satu jam mengatakannya padaku. Kendati demikian, setelah mendengarnya, aku sudah tidak lagi pusing kepala memikirkan mereka.
Tinggal satu masalah yang harus kuselesaikan: kakak. Setelah pulang sekolah, aku buru-buru mengejarnya yang sedang duduk santai di teras. Seperti biasanya sejak beberapa hari ini, kakak segera menghindar, meninggalkan ponselnya di meja seakan-akan dia telah melihat sesuatu yang mengerikan, dan itu membuatku sakit hati.
Menghela napas, aku mengambil ponselnya, dengan harapan kali ini kakak mau mendengarkanku. Hanya mendengarkan ... dan berbicara (kutambahkan), setidaknya hatiku bisa sedikit bersih dari rasa bersalah. Namun, kakak masih saja tidak membukakan pintu, bahkan saat aku mengancam untuk melemparkan ponselnya ke lantai satu.
"Kak! Setidaknya jangan menghindar. Sudah kubilang, 'kan, aku hanya mengikuti permintaan menek. Lima hari itu apa nggak keterlaluan?" Aku meracau, tanpa sadar hampir melempar ponsel Kakak ke lantai. "Nenek nggak mau lihat Kakak nangis, makanya nenek minta tolong padaku. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, loh, Kak. Aku kira otak Kakak diberi pencerahan setelah lima hari mengurung diri."
Tiba-tiba saja aku merasa kesal. "Kakak, kan, sudah bukan bocah lagi. Nyebelin banget! Aku lempar, nih, ponsel Kakak―"
Pintunya terbuka. Kakak muncul dari baliknya, masih tidak menatapku, tetapi aku senang dia tidak mengabaikanku kali ini. Apalagi saat ia mengatakan sesuatu untuk pertama kalinya sejak beberapa hari ini setelah merebut ponselnya dari tanganku. "Pergi. Aku mau tidur."
Setidaknya, masalahku dengan kakak sudah selesai. Sisa satu masalah lagi yang harus kuselesaikan―tentunya bersama Alif.
✨✨✨✨✨
Esoknya, aku dengan tidak sabaran memaksa Alif menemui Azul. Namun, Azul susah sekali untuk berdiri di hadapan kami. Dia menghindar setiap kali melihat kami, dan itu telah membuat Alif kesal.
"Bodo amat!" gerutu Alif. Ungu muda di sekita kepalanya berputar-putar sebelum membesar, hingga warna merah pun ikut menari di sana.
"Kamu mau menyerah?" sungutku, menariknya untuk duduk di tangga bawah, mengabaikan teriakan heboh para suporter di pinggir lapangan.
Aku tidak heran mendapati para cewek begitu heboh sampai menggetarkan tanah sekitar sekolah. Class meeting kali ini dibuka dengan pertandingan basket putra. Entah kelas apa yang ada di lapangan sana, tetapi aku yakin sekali mereka dari kelas dua belas. Sementara kelasku, akan bertanding dengan kelas 11 IPS 3 setelah makan siang gq.
"Azul masuk tim basket, 'kan?" Alif terdiam, dan kuanggap itu sebagai jawaban ya. "Ada kesempatan. Kalian harus berbicara. Ingat, sebentar lagi libur semester-"
"Masih tiga hari lagi." Alif memprotes.
"Itu cepat, tau!" ketusku. Aku malahan ingin melihat keadaan membaik sekarang.
"Lagi pula, aku, kan, nggak mau melakukannya sendiri."
Seketika aku terdiam. Aku tidak bisa marah pada Alif begitu kata-kata itu keluar darinya. Aku juga bersalah pada Azul.
Jadi, aku terus menempel pada Alif setelah satu kelas berisik meneriakkan yel-yel, mengabaikan kalimat pedas Maliqa. Namun, Azul sepertinya tahu tujuanku berada di tim basket cowok. Dia terus-terusan menempel dengan Yusril dan beberapa anak cowok, tidak memberi kami kesempatan untuk mendekatinya. Kendati aku sudah meminta bantuan pada Yusril dan yang lainnya, aku tetap tidak bisa berbicara dengan Azul.
Menghela napas kecewa, aku mengikuti Yeni untuk bergabung bersama Janti di pinggir lapangan, duduk di kursi panjang yang disediakan. Masih ada waktu tiga hari sebelum libur semester, dan kuharap dalam waktu singkat itu hubungan kami sudah membaik.
Lapangan menjadi heboh beberapa menit kemudian saat pak John berbicara pasal pertandingan kali ini. Beliau berbicara panjang memuji tim basket dengan berlebihan sebelum ke inti acara. Janti di sebelahku, menggigit kuku ibu jarinya sementara fokusnya pada lapangan. Rasa kagumnya pada Alif masih bertahan. Sering kali aku memergokinya mencuri pandang pada Alif, tetapi entah kenapa sejak hubungan kami dengan Azul, Janti tidak lagi melakukannya.
"Gila! Kakak kelasnya bongsor. Umur mereka berapa? Enam belas? Tujuh belas? Nggak mungkin banget." Yeni terus bergumam. Teman-teman di sebelahnya mengangguk, dan aku diam-diam menyetujuinya.
Mereka pemuda berbadan besar dan tinggi-mungkin dari tim basket sekolah-berbeda jauh sekali dengan cowok di kelasku yang berbadan seperti ranting kayu. Cewek-cewek di kelasku berbisik-bisik heboh, takut tim kami kalah atau bahkan ada yang cedera. Walaupun di sekitarku berisik, fokusku terus pada Alif. Kelap-kelipnya telah menarik perhatianku. Apalagi saat pertandingan dimulai. Terkadang aku melirik Azul, dan dia bermain dengan baik, mengesampingkan hubungan tak baiknya dengan Alif.
"Oh, ya! Pemain kelas sepuluh dengan nomor punggung 9 mengoper pada si nomor 21. Si 21 berlari. Aduh ...! Para cewek berisik di tribune. Alip! Namanya Alip!"
Pak John, sebagai komentator, berhasil memuntahkan protes para penggemar Alif lantaran salah menyebut namanya.
"Oh! Oh ...! Wandi, nomor punggung 12 berhasil menghalau poin dari kelas sepuluh dengan pemukul bisbol. Sori, dengan tangan, maksud hamba."
Aku ikut-ikutan berteriak marah karena pemuda besar itu telah menggagalkan Alif memasukkan bola ke ranjang. Berulang kali kelas kami gagal. Badan besar dan keahlian mereka telah membuat poin tim Yusril tertinggal.
"Nomor punggung 21 ini lincah, ya!" Pak John berteriak, dan penggemar Alif berteriak heboh karenanya.
Alif berhasil merebut bola dari tangan lawan, semudah mengambil permen dari anak kecil. Namun, dia terlalu memaksakan diri, mengabaikan wajahnya yang pucat. Dia terlalu bersemangat setelah berjanji padaku untuk memenangkan pertandingan, bahkan beberapa kali dia menoleh ke arahku dengan binar kuningnya seolah-olah dia tidak akan mengingkarinya. Padahal dia tidak perlu begitu, apalagi ini baru pertengahan pertandingan.
Aku diliputi rasa khawatir, terlebih lagi sedikit demi sedikit kilauan di sekitar kepalanya mulai berkurang. Azul sepertinya menyadari hal itu. Dia menepuk bahu Yuda, memintanya untuk berbicara pada Alif. Namun, Alif menggeleng, menunjukkan ibu jarinya bersama cengirannya yang sama sekali tidak cocok dengan wajah pucatnya.
"Nomor punggung 7 dari kelas sepuluh, bermanuver, menukik, mendarat. 21 lagi, Kawan! Dan para penggemar Alip di tribune sana membuat ombak! YA! MASUK!"
Alif berhasil mencetak poin untuk pertama kalinya. Walaupun selisihnya bisa dibilang jauh dengan poin lawan, tetapi satu poin itu telah membuat kami berteriak heboh.
"Beberapa menit menuju waktu istirahat, kapten dari kelas sepuluh membagikan semangat kepada para anggotanya. Sementara itu di kelas sebelas ...."
"Apa kita bisa menang?" Yeni bergumam, mengalihkan atensiku pada Alif.
"Kita masih punya kesempatan." Aku bahkan tidak yakin dengan kata-kataku. Aku lebih mengkhawatirkan kondisi Alif daripada poin yang tertinggal.
Alif masih terlihat sama, tetapi kali ini semangatnya berkurang. Dia tidak selincah sebelumnya. Yuda berbicara sesuatu, lalu meninggalkan Alif untuk mengejar bola. Aku masih memperhatikannya. Sesekali ia membungkuk, untuk mengatur napas. Saat ia melihat ke arahku, dia berdiri tegak sembari tersenyum, memberi tahuku bahwa ia baik-baik saja sebelum berlari mengejar yang lainnya.
"Bola terlempar dari tangan sang kapten basket, dan sepertinya kecohan dari lawannya berhasil! Bola ditangkap Alip lagi! Alip! Dia berlari, tapi sepertinya dia kurang minum."
Gerakan Alif tidak selincah sebelumnya. Aku tahu dia berusaha melakukannya, tetapi kondisi badannya tidak bisa digerakkan sesuai kemauannya. Demi menjauhkan bola dari lawan, Alif segera melemparkannya pada Azul. Hingga dia membuat heboh seluruh penghuni lapangan.
Alif terjatuh dengan bedebum keras, telungkup dan tidak bergerak. Dia pingsan. Aku yang melihatnya langsung berdiri, panik, kemudian berlari meninggalkan tribune, mengabaikan teriakan Yeni.
"Kana?" Padahal itu pertama kalinya Azul memanggil namaku setelah hampir seminggu ini, tetapi aku mengabaikannya, lebih memilih melihat kondisi Alif setelah membelah kerumunan.
Kepanikanku bahkan belum ada apa-apanya dibanding bu Yanti. Wali kelasku sudah ada di dekat Alif, berteriak panik kepada anggota PMR setelah mendengar sesuatu dari bu Ze yang―sepertinya―telah selesai memeriksa Alif.
"Bawa dia ke mobil Ibu!"
"Tapi, Bu. Bukannya―"
"Cepat?!" Bu Yanti berteriak, mengalahkan suara heboh di sekitarnya.
Seketika rasa khawatirku semakin besar mendengar kata rumah sakit. Apa yang sudah terjadi dengan Alif? Dia sakit? Sakit apa? Berbagai pertanyaan muncul dalam kepalaku, tetapi aku tidak bisa memuntahkannya dalam kondisi super panik ini.
Aku mengikuti anggota PMR ke mobil Bu Yanti yang ternyata sudah ada di pinggir lapangan. Alif segera dibawa masuk dibantu bu Ze yang sama paniknya dengan bu Yanti.
Sudah pasti ini serius. Lantas, jika ini serius dan kedua guru itu panik, bukankah ....
"Bu, aku ikut!" Aku mendesak, menarik lengan bu Yanti sebelum memasuki mobil.
Karena situasinya tidak memungkinkan berlama-lama, bu Yanti mau tak mau menyuruhku untuk masuk ke mobilnya.
"Aku juga!" Bu Yanti bahkan belum menjawabnya, tetapi Azul sudah menempatkan diri di kursi belakang.[]
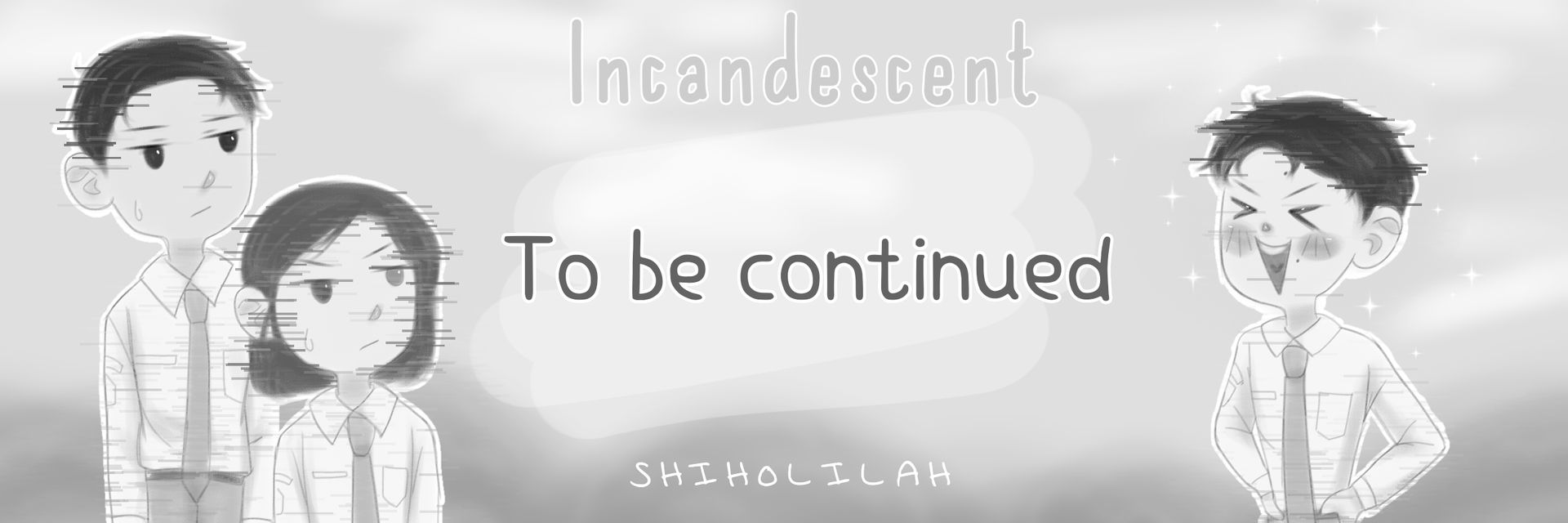
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top