15. Hal Tidak Menyenangkan Ternyata Menyukaiku

Situasi asing ini telah membuatku pusing semalaman, mengalahkan rumus Stoikiometri dan sejenisnya. Aku berusaha menghubungi kedua temanku dengan harapan masalah bisa terselesaikan. Namun, hasilnya nol besar. Lebih hilang lagi harapanku saat mendapati Azul keluar dari pesan grup.
Di sekolah malah lebih buruk lagi. Kerenggangan hubungan Alif dan Azul disadari teman sekelas. Maliqa yang masih membenciku, menyimpulkan bahwa akulah yang menjadi penyebabnya. Dia tidak salah. Aku memang yang menyebabkan munculnya pembatas di antara kedua temanku, hingga keinginan kuat untuk menyambung kembali hubungan mereka memenuhi diriku. Farrell dan Farhan bersedia membantu dengan membuat obrolan melingkar. Namun, Azul keluar dari lingkaran dan lebih memilih bermain gim ponsel di pojok kelas.
Saat jam istirahat, aku berusaha menarik lengan Azul, tetapi dia dengan cepat menghindar dan pergi sendirian. Tercetus dalam kepalaku untuk meminta bantuan yang lainnya. Alih-alih mendapat hasil memuaskan, justru situasinya lebih buruk dari yang dikira. Alif berkata kasar, lalu pergi entah ke mana sampai melewatkan satu mata pelajaran.
Selain mudah mengontrol emosi, ternyata Alif pandai mengotori mulutnya.
“Tidak tertolong.” Farrell sama sekali tidak membantu dengan kata-katanya. Dia membuatku semakin menilai buruk diri sendiri.
“Coba kamu pura-pura sakit. Mereka panik. Dan kemungkinan besar hubungan mereka tersambung lagi.” Ide Farhan adalah yang terburuk dari yang terburuk. Berbohong bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah.
Kepusinganku bertahan selama beberapa hari. Lelah hati mendapati kedua temanku melengos satu sama lain. Seolah masalah Alif dan Azul bukanlah beban yang menggoyangkan kepalaku, mama memberiku kabar bahwa kondisi nenek memburuk.
Seminggu lagi menjelang ulangan, konsentrasiku tidak bisa berfokus pada statusku. Nenek terbaring lemah tanpa bisa menggerakkan tangannya barang untuk mengusap wajah kusut cucunya, dan aku tahu mama diam-diam menangis di sudut musala.
Tante Wina datang dengan sekonyong-konyong membuat heboh rumah sakit. Tas bermerknya menampar wajahku tepat saat ia berbalik lalu menyadari keberadaanku. Tanganku berusaha ditarik olehnya, ingin berbicara, tetapi aku dengan gesit berlari sampai ditegur perawat yang berpapasan denganku.
Kacau. Masalahku terus datang seolah-olah badanku ini magnet. Tepat saat di persimpangan, aku menabrak seseorang. Cowok, yang selama ini kuhindari. Aku ingin bersujud, berpura-pura menjadi orang gila saat itu juga. Sepupuku yang genit ini justru nyengir padahal aku ingin menangis keras.
“Lama nggak ketemu, kok, nangis.”
Aku tidak menangis, aku hanya ingin ... menangis dan kabur.
“Maaf, Anda ini siapa?” Aku dengan tololnya melontarkan pertanyaan sampai Alfie terkekeh sembari menjulurkan tangannya untuk mengelus kepalaku. Namun, sebelum itu, aku menghindar dan hendak pergi, tetapi Alfie lebih gesit dariku.
“Melihatmu lari-lari semenit yang lalu membuatku khawatir. Apa nenek baik-baik saja?”
Terdapat warna biru yang keluar dari kepalanya. Aku berdeham, masih menjaga jarak. Nenek tidak baik-baik saja, tetapi yang kulakukan justru menjawab, “Ya .... Nenek baik.”
Ingin sekali aku menghilang saat itu juga, atau menyusut dan meloncat ke dalam tas seseorang yang lewat. Alfie dengan gesit meraih lenganku dan berkata, “Kalau begitu, ayo, ikut aku.”
“Eh!” Alfie sudah bukan anak berusia sembilan tahun lagi. Dia sudah besar, bahkan tingginya menyamai kakak. Aku yang hanya gadis pendek tak bertenaga dan bersuasana hati buruk, tidak bisa melepaskan diri seperti yang kulakukan pada Tante Wina. Yang ada tanganku malah sakit. Jadi, aku dengan cepat mengatakan hal yang sebenarnya. “Kondisi nenek memburuk.”
“Makanya .... Ayo kita ngobrol.”
Seberusaha apapun aku menghindarinya, pada akhirnya Alfie berhasil membawaku ke taman rumah sakit, duduk di bangku mendengar ocehan cowok itu mengenai waktu yang mengubah semuanya, terutama diriku. Kendati dia masih saja menyebalkan, harus kuakui mendengarkan dia berbicara lebih baik daripada memikirkan masalah yang menimpaku akhir-akhir ini.
“Bagaimana sekolahmu? Tidak seperti dulu, 'kan?”
Sesaat setelah itu, aku menoleh pada Alfie. Dia memang tahu kehidupan sekolahku yang buruk saat SD. Mama menceritakannya pada tante Ayu. Alfie yang mendengarnya tiba-tiba ingin pindah sekolah bersamaku. Namun, karena tempat tinggal kita berjarak jauh, Alfie mau tak mau harus menerimanya, dan aku senang karena tidak harus satu sekolah dengannya.
Aku terdiam beberapa saat. Alfie masih menunggu, kemudian aku menjawab, “Baik. Bahkan lebih baik.”
“Dari yang aku kira?” tanyanya, sedikit tidak percaya.
“Ya. Dari yang kamu kira.” Aku menjawab malas sembari menyingkirkan kerikil dengan kakiku. Sekolahku berjalan dengan baik berkat kedua temanku. Tidak ada lagi yang bisa merundungku kendati beberapa cewek masih menatapku sebagai musuh. Namun, semuanya kacau karena aku. Ini sudah berhari-hari, aku sudah tidak lagi mendengar kecerewetan mereka.
“Sepertinya nggak baik.” Alfie berucap, membuatku menoleh padanya. “Muka kusutmu bukan hanya karena kondisi nenek, 'kan? Kamu punya masalah. Bukan dalam pelajaran, tapi dalam hal lain. Aneh kalau kamu galau karena rumus Kimia sampai seperti ini. Ayo, cerita. Sepupu gantengmu akan menjadi pendengar yang baik. Siapa tahu setelah bercerita, bukan hanya hati kamu yang plong, tapi juga masalah kamu.”
Kuabaikan cengiran menyebalkannya. Aku menatap lurus ke depan, menimbang-nimbang apakah aku bisa menceritakannya pada Alfie. Cowok itu benar. Aku pernah melakukan hal itu sebelumnya. Alif dan Azul merupakan pendengar yang baik, dan berkat itu sesuatu yang selama ini membebaniku menghilang begitu saja.
Alfie bukanlah orang asing walaupun aku tidak menyukainya. Dia sepupuku, yang punya perhatian layaknya seorang kakak. Rasa pedulinya akan kehidupan sekolahku yang buruk telah membuatnya memiliki afeksi—yang menurutku—menyimpang. Walaupun begitu, dia tetaplah sepupuku yang baik.
Menghela dan mengembuskan napas pelan, aku menunduk lalu berucap, “Aku punya dua teman.”
“Teman atau sahabat?” Alfie menyela. Kala aku menatapnya, dia tersenyum lebar.
Aku kembali menunduk, tiba-tiba pertanyaan Alfie berputar dalam kepalaku. Sudah beberapa bulan semenjak kebersamaanku bersama Alif dan Azul. Selama ini ... apa mereka menganggapku sebagai ...?
Sepengetahuanku, sahabat merupakan orang yang selalu bersama sejak lama. Aku dan mereka baru beberapa bulan. Apa tidak terlalu egois jika aku menganggap mereka sebagai sahabat?
“Kalau kamu memikirkan mereka sampai seperti ini, itu artinya kamu sangat peduli. Tahu arti lainnya?” Alfie menelengkan kepalanya demi melihat wajahku.
Otakku kembali dibuat berputar, tetapi hanya sebentar sampai aku menjawab dengan ragu. “Sa ... sayang?”
“Aku juga sayang kamu.”
Kuinjak kaki Alfie sampai ia memekik pelan.
“Sayang itu artinya kurang lebih sama dengan sangat peduli.”−kedua jari Alfie bergerak mengutip dua kata terakhir−”Arti lainnya ialah ... kalian itu bersahabat. Peduli satu sama lain.”
“Teman juga—”
“Beda. Rasa pedulimu dengan kedua temanmu beda.”
Jika benar begitu, apa Alif dan Azul memiliki pendapat yang sama?
Lupakan! Lupakan apakah mereka menganggapku sebagai sahabat atau bukan. Ada hal yang lebih penting dari sekadar status pertemanan. Kutatap Alfie sampai ia salah tingkah. Aku sudah memutuskan untuk menceritakan semuanya, dan harap-harap bukan hanya perasaanku saja yang ringan. Siapa tahu Alfie yang bijak ini bisa memberiku solusi untuk menyatukan kembali kedua sahabatku.
Kuceritakan semuanya, bahkan kesalahanku yang telah membuat Alif dan Azul bertengkar. Alfie mendengarkan dengan seksama. Dan benar saja, sesuatu yang membebaniku dalam dada seolah terbang bersama perasaan sedihku akan nenek.
“Rumit juga, ya ....”
Memang seharusnya aku tidak terlalu berharap pada Alfie.
“Biasanya kalau mereka bersahabat sejak lama, masalah bisa mereda, secepatnya satu hari.”
“Tapi ini sudah lebih dari tiga hari,” ketusku. Alfie terkekeh padahal aku ingin sekali menimpuknya dengan batu.
“Penyelesaian masalah itu baaanyak ....”
“Jadi, apa salah satunya?”
“Nggak tahu.”
Aku sungguhan melempar batu sampai mengenai pipinya.
✨✨✨✨✨
Ulangan semester bahkan tinggal beberapa hari. Kelompok belajarku bubar, dan aku sama sekali tidak ada suasana hati mengajari Farrel dan Farhan seperti yang dijanjikan. Beruntungnya mereka berdua mengerti. Tidak protes seperti biasanya.
Namun, hari ini Alif absen, hingga satu hari sebelum ulangan aku tidak bisa menghubunginya. Azul berusaha tidak peduli akan ketiadaan Alif di kelas selama beberapa hari, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan segumpal warna birunya padaku. Karena hal itu, aku menggebrak mejanya pelan, memelotot sampai Azul takut sekaligus bingung.
“Berhenti bersikap bodoh seperti ini!” desisku. Sesaat aku baru menyadari keberadaan Farrel di sebelah Azul. Aku menyuruhnya untuk pergi dengan gerakan kepala, dan dia langsung pergi tanpa protes.
“Apa susahnya berbaikan?!” Aku gemas sendiri memikirkan hubungan mereka akhir-akhir ini. Sudah banyak usaha yang aku coba untuk menyatukan mereka, tetapi hasilnya tidak ada. Aku lelah. Aku merindukan kecerewetan mereka untuk pertama kalinya!
“Kalian sudah berteman selama beberapa tahun. Dan hubungan kalian merenggang hanya karena pertanyaan tidak penting dariku? Tuhan .... Kamu tahu bagaimana perasaanku sejak hari itu?” Aku ingin mencakar wajah Azul dan menangis, beruntungnya aku bisa menahannya dengan mengertakkan gigi.
Azul terdiam, menghindari tatapanku. Aku kira dia enggan menjawab kemarahanku, tetapi beberapa detik kemudian dia menggerakkan mulutnya. “Kamu nggak salah.”
Bagaimana bisa aku tidak menyalahkan diri sendiri?!
“Lalu? Alif yang salah? Kalau begitu, kamu juga salah,” geramku. “Kami salah.” Napasku memburu. Tanpa sadar aku mematahkan penggaris Farrel. Dan cowok itu yang sadar penggarisnya menjadi dua, hanya bisa menunjukkan ibu jarinya padaku dengan sedih.
“Dengar. Alif memang salah. Tapi, apa kamu tahu maksudnya? Dia kesal saat mendengarmu menyerah dengan pendidikan. Aku juga kesal, sebenarnya. Aku kecewa saat kamu bilang tidak ada niatan untuk kuliah. Sebenarnya kamu punya, 'kan? Tapi kamu ragu.”
“Kita sudah berusaha, terutama kamu. Kamu pasti menyadarinya. Kalau kamu juga berusaha seperti sebelumnya, tidak ada yang tidak mungkin. Ibu kamu akan sangat senang kalau usaha anaknya selama ini berjalan dengan sangat baik.” Kutatap Azul tepat pada netra hitamnya, kemudian melanjutkan, “Alif berkata kasar seperti itu punya maksud lain. Bukan ke arah yang buruk. Zul ... kalian sudah berteman lama. Dia sudah pasti kecewa mendapati sahabatnya menyerah begitu saja.”
Lengang. Azul kembali menghindari tatapanku, dan ia tidak mengatakan apapun selama beberapa hari. Bukan hanya Alif, dia juga mogok bicara, bahkan berpapasan dengaku.
Dia membuatku merasa sakit hati untuk pertama kalinya.
✨✨✨✨✨
Tiga hari—hari Minggu tidak termasuk—Azul menghindariku. Alif yang menyadari itu, hanya diam tidak mengatakan apa-apa. Selama tiga hari itu, aku berusaha keras untuk berkonsentrasi pada ulangan alih-alih memikirkan cara untuk menyambung hubungan pertemanan. Beruntungnya aku bisa menjawab soal dengan lancar, tetapi tidak dengan Azul. Aku melihatnya memukul-mukul kepalanya selama ulangan berlangsung. Alif yang duduk di depannya, terlihat tenang, tidak mempermasalahkan soal Matematika yang membuat seluruh ruangan mengeluh.
Pulang sekolah aku menyempatkan diri untuk menjenguk nenek. Kakak selalu meluangkan waktunya untuk menjemputku, lalu mentraktir makan siang sebelum sampai rumah sakit.
Alfie juga sering berkunjung bersama Tante Ayu. Dia berusaha menarikku untuk mengobrol, tetapi aku menghindarinya lantaran kesal dengan kejadian tempo hari.
“Bagaimana hubungan kalian?” Alfie bertanya tiba-tiba saat di depan kamar inap nenek. Cowok itu terus bergeser untuk lebih dekat denganku, tetapi aku segera berkelit ke sana kemari demi menghindarinya.
“Sudah lebih baik, 'kan?” tanya Alfie. Dia sudah menyerah untuk menggerakkan kakinya agar lebih dekat denganku.
Aku mendengkus keras. Diam-diam merutuki orang-orang di dalam sana yang lama sekali keluar. Kami harus bergantian menjenguk nenek lantaran bukan hanya aku dan kakak saja yang datang, tetapi Tante Yuni juga datang bersama suaminya. Aku tidak masalah jika tidak mendapat kesempatan menjenguk. Toh, aku bisa menjenguk kapan saja.
“Kana.” Aku segera menoleh pada mama yang baru keluar, disusul yang lainnya. Mereka menunduk, seperti menghindari tatapanku, bahkan mama sekalipun, dan itu telah membuat seusuatu yang buruk menyambangi benakku.
Tidak! Aku tidak boleh berpikir macam-macam. Mungkin nenek telah mengatakan sesuatu yang tidak mengenakkan seperti: membentak karena ingin tidur, mengingat akhir-akhir ini nenek mendapat banyak kunjungan.
Pada akhirnya mama memberanikan diri untuk menatapku. Walau sebentar, aku bisa melihat warna biru di sekitar kepalanya. Mama berkata, “Nenek sensitif sekali.” Mama mengetikkan sesuatu di ponselnya, tetapi dia tetap melanjutkan, “Katanya, dia ingin berbicara denganmu. Berdua. Entah apa. Coba kamu bujuk nenekmu biar nggak marah-marah lagi.”
Begitu mendengarnya, ada sedikit ketidakpercayaan bersemayam dalam diriku. Mengingat nenek lebih akrab dengan kakak, seharusnya kakak saja yang berusaha meredakan amarah nenek. Kendati begitu, aku tetap masuk ke ruangan nenek.
Hingga, sesaat setelah membuka pintu, aku hanya bisa mematung. Mama berbohong. Itulah sebabnya ia tidak menatap mataku saat berbicara. Nenek bukannya marah, yang mana hal itu tidak bisa nenek lakukan dalam kondisi seperti itu.
Nenek terbaring lemas—bahkan lebih lemas dari sebelumnya—bersama sesuatu yang kutakutkan selama beberapa tahun ini. Bagian bawah tubuhku seolah tak bertulang, nyaris membuatku memeluk lantai, jantungku bergemuruh seolah sesuatu telah memukulnya keras secara bertubi-tubi. Inginnya aku tidak memercayai apa yang kulihat, tetapi kenyataan bahwa warna gelap itu bukan ilusiku, terlihat begitu nyata dan ... sangat menyakitkan.
“Jangan berdiri di situ .... Nenek nggak bisa jalan. Cepat ke sini.” Suara lemahnya telah meruntuhkan pertahanan air mataku. Aku menangis sambil berlari ke arahnya, dan aku bisa merasakan aura dingin saat kepalaku mengenai warna hitam dari nenek.
Seperti ini, kah, rasanya? Jantungku rasanya mau putus oleh pukulan keras nan tajam tak kasat mata, dan kepalaku serasa panas walau aura dari nenek terasa dingin. Perasaan asing ini telah membuatku begitu lemah. Tak pernah terpikirkan olehku, bahwa suatu saat nanti aku bisa melihat warna hitam dari orang-orang terdekatku. Aku selalu dikhawatirkan oleh penglihatanku. Merasa takut setiap kali warna gelap muncul pada orang-orang yang kutemui di jalan. Namun, siapa sangka, ketakutan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya.
“Kana ....”
Aku tidak mau menatap wajah lemah nenek, aku ingin memeluknya lebih lama lagi.
“Nenek tahu ... kamu melihatnya.”
Aku menarik diri, pura-pura tersenyum.
“Nenek ... memanggilmu ke sini karena itu.”
Tanganku berhenti mengusap air mata, menatap nenek penuh tanya. Jadi, nenek memanggilku karena nenek sudah tahu? Segera saja aku menggenggam tangannya yang dingin, lalu berkata, “Nenek ngomong apa, sih? Karena hal apa? Nenek, kan—”
“Kana ....” Nenek tersenyum sembari mengangkat kepalanya susah payah. Aku tahu nenek berusaha menyembunyikan air matanya. “Kamu ingat nasihat mamamu, 'kan? Takdir tidak bisa diubah. Biarkan ia berjalan ... semestinya. Nenek memanggilmu karena ... sepertinya kamu harus mengetahuinya lebih dulu.” Nenek berusaha sekuat tenaga mengeluarkan kalimat panjang itu dari mulutnya. Ingin sekali aku membuatnya berhenti. Aku tak ingin mendengar apapun darinya yang membuat dadaku sakit. Namun ... aku tidak bisa melakukannya. “Nenek tidak ingin ... saat kamu masuk bersama kakakmu ... warna ini terlihat. Setidaknya ... jangan biarkan kakakmu mengetahui hal ini. Setelah keluar dari sini ... ajak kakakmu pergi ....”
Kulirik pintu yang ternyata tertutup rapat bersamaan dengan luruhnya air mataku. Mama pasti yang melakukannya sesuai permintaan nenek. Sementara kakak ... tidak akan bisa mendengar percakapan ini. Tanganku mengepal. Aku tahu tujuan nenek. Hanya saja, jika aku berada di posisi kakak ....
“Tapi, Nek.”
Nenek tersenyum. Air matanya turun merembes membasahi bantal, berusaha menahan rasa sakit akan kalimat yang dikeluarkannya kemudian. “Kana ... Nenek tidak ingin melihatnya menangis ....”[]
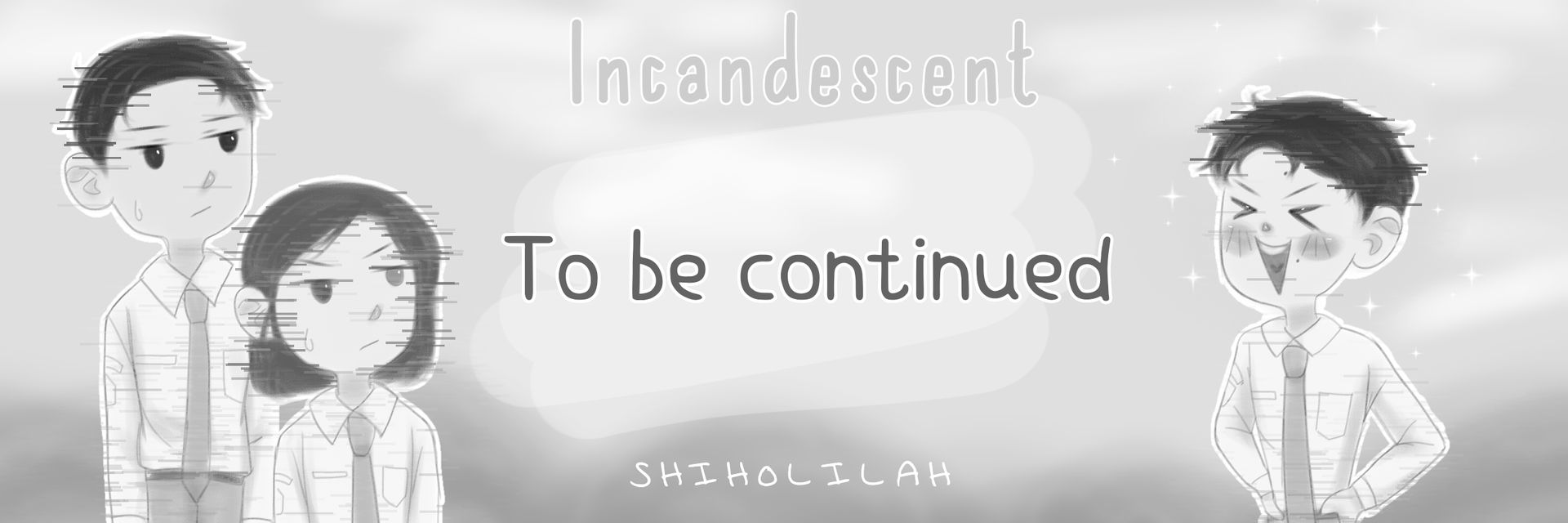
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top