14. Azul Mengemas Barang-barangnya

Ujian awal semester yang datang dua minggu lagi telah menggemparkan kelasku. Terutama Farrel dan Farhan yang terus membujukku untuk membuat kelompok belajar. Namun, Alif dengan tegas menolak seolah-olah dirinyalah yang akan kerepotan mengajari dua cowok itu. Aku juga tidak mau kerepotan lebih dari ini, makanya aku menolak.
Tidak benar-benar menolak, sebenarnya, sebab aku tidak bisa membiarkan niat baik cowok itu pupus lantaran keegoisanku. Selain rumus Matematika yang sering kali ditanyakan Farrel dan Farhan tiap minggunya, aku memperbolehkan mereka bertanya di luar mata pelajaran tersebut, sebagai pengganti kelompok belajar agar Alif tidak merajuk.
Hanya saja, Alif bersikap kekanak-kanakan sampai aku harus memukulnya dengan buku tulis. Dengan alasan aku telah berkhianat lantaran berbuat baik pada Farrel dan Farhan, malam harinya Alif membuat berisik ponselku dengan panggilan video yang terus kuabaikan.
‘Ini sudah larut!’
Aku mengetik balasan dengan cepat, dan secepat itu pula Alif membalasnya.
‘Kok, kamu belum tidur? Wajahku berputar-putar di dalam kepalamu, ya?’
Lantas kumatikan ponsel, menutup buku Fisika, dan beranjak tidur.
Hampir dua jam. Mataku masih terbuka lebar kendati kuap terus muncul di setiap beberapa menitnya. Aku hanya terbaring, mencoba menutup mata, tetapi beberapa saat kemudian terbuka lagi lantaran pesan cowok itu benar. Wajah Alif terus muncul di setiap aku menutup mata! Hingga aku memutuskan untuk turun ke dapur. Mama bilang, susu hangat bisa membuat tidur nyenyak.
Baru saja aku menuruni beberapa anak tangga, aku dikejutkan dengan teriakan mama, mengharuskanku berlari cepat ke sumber suara. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi, tetapi aku tahu sesuatu yang buruk telah terjadi pada nenek. Kepanikan menyeruak dalam diriku. Mama masih berteriak memanggil penghuni rumah, hingga kemudian histeria itu menguasaiku kala mendapati mama berusaha mengangkat nenek yang tergolek tak sadarkan diri di lantai kamar mandi.
Tidak ada waktu untuk bertanya, aku membantu mama mengangkat nenek. Namun, sebelum itu, papa datang dan langsung membawa tubuh ringkih nenek dalam gendongannya. Wajah khawatirnya yang kentara, membuatku tambah takut.
“Siapkan mobil!”
Mama dengan gesit mengambil kunci mobil, dan kakak yang sudah tahu apa yang harus dilakukannya, menelepon rumah sakit dengan tangan gemetar. Yang kulakukan hanya berdiri bersama tremor, menatap para orang dewasa yang sibuk. Kejadian ini seperti setahun yang lalu, di mana nenek jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi padanya, tetapi aku tahu nenek sakit sampai tidak bisa berdiri lama.
Sampai pagi, aku tidak bisa tidur. Mama dan papa masih di rumah sakit, sementara aku dan kakak diharuskan pulang pada pukul tiga dini hari. Esoknya mataku berkantung, meloloskan kecemasan pada diri Alif. Cowok itu mengira aku tidak bisa tidur karena memikirkannya, dan dia meminta maaf berkali-kali. Aku yang malas meladeninya, hanya meresponsnya dengan kibasan tangan.
“Kelihatannya kamu nggak baik-baik saja.” Azul memberiku sebotol susu rasa jeruk, dan satu potong roti isi saat perutku berbunyi keras.
Pagi ini aku tidak sempat sarapan. Bukan karena tidak ada makanan di atas meja. Papa pulang pukul enam pagi, membawa bubur ayam, tetapi aku tidak menyentuhnya karena nafsuku pupus sejak semalam. Mau tak mau aku harus menerima pemberian Azul. “Thanks.”
“Sepertinya bukan karena aku.” Akhirnya Alif menyadari kehebohannya yang sia-sia. Melihat kelap-kelipnya membuat mataku sedikit bugar. “Aku siap, kok, dengar cerita kamu—”
“Kami. Kami siap.” Azul menarik kursi ke samping Alif. “Ya .... Tentunya kalau kamu juga siap.”
Terdiam beberapa saat. Aku sudah pernah menceritakan beberapa hal pada mereka, terutama rahasiaku. Untuk masalah keluarga, aku ragu. Walaupun mereka temanku dan kepercayaan sudah tertanam, tetapi entah kenapa mulutku susah sekali digerakkan. Sekali lagi mataku memaku Alif, dan luar biasanya kelap-kelip itu telah membuatku memiliki keberanian. Sedikit demi sedikit aku menjelaskan kejadian semalam, hingga dadaku kembali dililit sesuatu.
Semalam, aku menahan diri untuk tidak menangis. Nenek bukan sekadar pingsan, tetapi terjatuh dan terbentur. Mama bilang, nenek akan baik-baik saja. Namun, aku tidak bisa memercayai perkataan mama. Mama juga takut, berusaha menyembunyikannya dengan cara menghindari tatapanku.
Kakak yang lebih sering menghabiskan waktu bersama nenek, aku tahu dia menangis selama satu jam penuh di dalam kamarnya. Matanya lebih bengkak dariku sampai ia harus absen dari kuliah paginya. Sekarang, aku tidak bisa menahannya. Berpura-pura mengantuk, aku diam-diam menangis di balik lipatan lengan, mengabaikan tawaran Alif untuk membawaku ke UKS.
✨✨✨✨✨
Aku sungguhan dibawa ke UKS lantaran badanku panas. Alif yang tahu kondisiku, panik tanpa suara dan berusaha membawaku dalam gendongannya. Seharusnya aku memukulnya karena sudah melakukan hal seenaknya, tetapi aku tidak punya tenaga barang untuk menggerakkan tangan.
Dua jam mata pelajaran aku lewati. Bu Ze membujukku untuk menghubungi mama, tetapi aku menolaknya. Syukurlah Bu Ze tidak berusaha melakukannya. Beliau bilang, aku hanya perlu meminum obat dan beristirahat. Alif dan Azul datang menjengukku saat jam istirahat. Namun, sebelum itu, aku yakin sekali mereka melarang beberapa orang masuk ke UKS sebab aku bisa mendengar keributan kecil di luar ruangan.
Mereka berdua membawakanku banyak makanan dari kantin. Berbagai jenis bersama lontaran pertanyaan dari mereka yang membuatku lebih baik alih-alih pusing.
“Sudah lebih baik, kok.” Aku menjawab dengan sabar kendati tangan Alif masih memeriksa dahiku berkali-kali, dan itu membuatku tidak nyaman. “Sudah kubilang, aku sudah—”
“Kurasa belum.” Alif menarik diri dariku. Kecemasannya tidak bisa terelakkan walaupun dia berusaha menyembunyikannya. “Bu Ze bilang, kamu tidak tidur semalam.”
Aku meringis mendengarnya. Bisa-bisanya Bu Ze mengingkari janjinya padaku. Aku memang menceritakan alasanku memiliki kantung mata, tetapi tidak dengan alasan lainnya. Azul yang duduk di kursi tepat di sampingku, hanya memperhatikan walau aku tahu dia tengah heboh seperti Alif di dalam hatinya. Cowok itu punya pengendalian diri yang cukup bagus.
“Jangan memaksakan diri. Absen satu hari tidak akan membuatmu tinggal kelas. Tidurlah. Masih ada waktu ...”−Alif menghitung dengan jarinya−”... sekitar empat jam sebelum menjenguk nenekmu.”
Aku sungguhan tidur selama itu, tahu-tahu Alif dan Azul sudah menguasai UKS saat aku membuka mata. Mereka bilang, jam terakhir kosong, dan inisiatif mereka untuk tinggal di UKS selama sisa waktu sekolah diizinkan Bu Ze. Selain itu, aku dikejutkan oleh satu bungkus nasi goreng di atas meja. Azul bilang, itu untukku. Namun, karena perutku sudah cukup penuh oleh kudapan yang mereka bawa waktu istirahat serta tak ada nafsu, aku menolaknya, dan bungkus nasi goreng itu masuk dalam tas Azul.
“Kalau kamu masih pusing, biar aku telepon Mang Adi. Kamu biar aku gendong.” Ide gila Alif membuatku duduk tegak. Sempat oleng karena aku terlalu lama berbaring, dan itu menggerakkan Alif menahan tubuhku.
“Aku nggak apa-apa. Panasnya sudah turun,” beri tahuku, seraya bergeser ke tepi ranjang agar tangan Alif lepas dari bahuku. Sikapnya yang menyebalkan itu selalu membuatku tidak nyaman, tetapi jika dia tidak ada, entah kenapa aku merasa kesepian. Keberadaan Alif membuat suasana lebih ceria karena memang dia memiliki sifat demikian. Lagi dan lagi aku berpikir, mungkin karena alasan itu Alif berbeda dari yang lainnya di mataku.
“Jangan menatapku seperti itu. Aku, kan, jadi kepikiran masa depan.”
Mataku berkedut mendengar kalimat Alif. Mengabaikan warna kuningnya yang berkobar-kobar, aku turun dari brankar, memakai sepatuku. Namun, sebelum itu, Azul memberikan ponselnya padaku. Di sana tertulis, 'Aku tunggu di gerbang sekolah'.
“Kenapa ngirimnya ke kamu?” Alif protes. Entah merasa iri karena apa. Wajar saja kakakku mengirim pesan pada Azul alih-alih aku. Ponselku selalu ditinggal di rumah setiap kali aku bersekolah.
“Mungkin ... aku yang cocok dengan masa depan Kana.” Azul menggodanya sampai aku bisa melihat sedikit warna merah muncul pada Alif. Sementara aku yang menjadi subjek candaan mereka hanya bisa menghela napas, tidak bisa memprotes atau candaan tolol ini akan berlangsung lama.
Selesai memakai sepatu, aku baru menyadari satu hal. Jam sekolah sudah berakhir dua puluh menit yang lalu. Sesaat itu juga aku bertanya pada Azul. “Pesan itu dikirim kapan?”
Azul memeriksa ponselnya, lalu menjawab, “Tujuh belas menit.”
Tujuh belas menit. Hebat sekali kakak menungguku selama itu. Biasanya dia tidak mau repot-repot menunggu jika adiknya super lelet. Itulah kenapa di setiap kebaikan menempel pada kakak, sebisa mungkin aku sudah siap lebih dulu darinya sebelum kakak menjalankan sepeda motornya—Ah, iya .... Kecuali kakak yang mengajakku lebih dulu.
“Tenang saja.” Aku menoleh pada Azul. Mungkin cowok itu melihat kepanikanku pada wajah yang berusaha kukontrol, hingga ia berkata, “Aku bilang padanya kalau kamu ada urusan di kantor guru. Makanya pulang terlambat.”
Aku menghela napas, berterima kasih pada Azul karena tidak menceritakan kondisiku selama pagi ini pada kakak. Jika jakak tahu, mungkin saja ia akan memberitahukannya pada mama, dan rasa khawatir nama bertambah di saat nenek terbaring di rumah sakit.
Kakak tidak marah telah menungguku selama dua puluh menit sebelum ke rumah sakit walau dia tidak berkata apapun hingga kami mendapati mama tengah membantu nenek minum. Karena kami mendapat waktu besuk khusus, aku membiarkan kakak mengobrol bersama nenek sampai aku bisa mendengar tawa lemahnya.
“Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, nenek harus di sini sampai kondisinya lebih baik.” Mama memberi tahuku dengan suara lemah. Memang itu yang terbaik. Di usia nenek yang sekarang, dengan penyakit yang bisa dibilang mematikan, penanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi rasa khawatir kami. Kusentuh tangan mama, melirik pintu di mana suara kakak terdengar. “Maaf, Mama nggak bisa ada di rumah terus.”
“Ma, aku bukan anak kecil lagi,” kataku.
“Ajak saja temanmu ke rumah. Makan bersama, atau apalah. Asalkan bukan—”
“Ma ....”
Mama terkekeh melihat wajah keberatanku. Walaupun mama di sini menunggu nenek, masih ada kakak dan papa yang bisa menyediakan makanan. Lagi pula, aku tidak masalah sendirian di rumah.
“Ulangan, kan, sebentar lagi. Sering-sering ajak Alif dan Azul ke rumah. Belajar bareng. Mama nggak melarang kamu pergi ke kafe atau ke manapun untuk belajar, kok. Mama bakal senang kalau kamu sering ajak mereka ke rumah.” Mama menepuk-nepuk punggung tanganku pelan, sementara aku memikirkan ucapannya.
Memang selama ini tempat belajar kami lebih mengarah ke tempat umum—Alif yang mengusulkan. Namun, setiap kali mereka merekomendasikan rumahku sebagai tempat belajar, aku selalu menolaknya. Jika mereka tidak berusaha keras membujukku, tempat lain menjadi destinasinya. Mungkin ide mama tidak buruk. Aku selalu merasa bersalah saat ke rumah Azul waktu itu lantaran ibunya menyuguhkan banyak kudapan di hadapan kami.
“Mama sudah menghubungi yang lain, 'kan?” Aku mengubah topik pembicaraan sebab mama menjadi menyebalkan setiap kali membicarakan Alif dan Azul.
Mama mengangguk, mengerti ke mana pertanyaanku tertuju. “Sore ini Tante Ayu menjenguk. Dan kayaknya Mama bisa membagi waktu menunggu Nenek dengan Tante Ayu.”
Hanya Tente Ayu yang jaraknya dekat dengan rumah sakit, sementara yang lainnya tinggal di luar kota. Tante Wina misalnya. Aku tidak berani membayangkan jika dia tinggal satu kota denganku.
“Oh, iya!” Aku sedikit terkejut lantaran mama menepuk tanganku kuat. “Mama bisa minta tolong Alfie buat nemenin kamu.”
Wajahku langsung merengut kesal. “Ma ... aku sudah besar. Lagi pula, ada kakak.”
Mama terkikik geli. Senang sekali mama membuat anak gadisnya kesal karena ulahnya. Pernah sekali aku membenci mama lantaran menyebarkan berita pernikahan anak gadisnya yang masih di bawah umur ke seluruh anggota keluarga. Aku yang saat itu masih berusia sembilan tahun, menangis kendati tahu mama hanya bercanda. Sejak saat itu, aku membenci sepupuku yang genit.
Beberapa menit mengobrol dan perasaan mama jauh lebih baik dari sebelumnya, aku memasuki ruangan nenek, berbicara sebentar sampai perawat datang. Kami pamit pulang, menerima uang dari mama untuk membeli makanan dan uang saku ke sekolah besok. Nenek menyempatkan diri menciumku sampai pipiku basah.
✨✨✨✨✨
Esoknya aku sungguh mengundang Alif dan Azul ke rumah untuk belajar bersama. Alif senangnya bukan main sampai memborong camilan di mini market dekat sekolah walaupun aku sudah melarangnya. Mama pulang sebentar untuk mengambil sesuatu, dan matanya berbinar mendapati kedua temanku duduk cantik di sofanya. Sementara kakak, dia masih di kampus, sibuk dengan tahun akhirnya yang seperti neraka, terlebih lagi dia sempat absen kemarin.
“Seumur-umur, baru kali ini aku senang dengan namanya belajar. Berkat tekanan darimu selama ini, nilaiku jadi naik.” Azul mengungkapkan isi hatinya, bangga akan nilai dan pujian dari ibunya.
Aku yang mendengarnya, sedikit tersinggung. “Jadi ... aku menekan, nih?”
Azul langsung menggeleng heboh, takut aku marah. “Bukan ...! Bagaimana, ya, aku menjelaskannya?” Sebenarnya aku tahu maksud dari perkataannya, tetapi entah kenapa aku terhibur dengan wajah paniknya. Seperti ini, kah, perasaan mama saat menggodaku?
Selama ini aku memang keras mengajari mereka: memaksa untuk menghafalkan rumus serta hal-hal penting, bahkan memarahi mereka saat berbuat kesalahan. Kendati demikian, Alif dan Azul sama sekali tidak tersinggung dengan perlakuan kasarku. Justru sebaliknya. Terutama Alif. Dia senang-senang saja saat aku memarahinya.
“Kalau itu memang membantumu, belajarlah lebih giat lagi.” Sesaat setelah mengatakannya, tiba-tiba saja aku teringat akan sesuatu. Jadi, aku memulai topik pembicaraan baru. “Aku tahu ini masih lama. Tapi aku penasaran.”
Sepertinya, Alif dan Azul yang justru lebih penasaran dengan ucapanku. Mereka berdua diam-diam menggeser posisi duduknya agar lebih dekat denganku. Jadi, aku melanjutkan, “Setelah lulus, kalian akan kuliah di mana?”
Mereka berdua saling pandang. Jelas saja mereka belum memikirkannya. Aku saja yang sudah mendengar pembahasan ini dari mama, masih bingung untuk memilih salah satu universitas di kotaku. Bahkan fakultas yang cocok saja belum terpikirkan.
Azul menunduk, memeriksa sesuatu di kakinya atau apa, sementara Alif tampak berpikir sembari mengetuk-ngetuk pulpen di jidatnya, kemudian menjawab, “Entahlah. Yang pasti aku bakalan bareng kamu.” Bibirku berkedut mendengarnya.
“Azul?” Aku berusaha mengabaikan kilauan Alif yang tiba-tiba saja bertambah banyak, menatap Azul, menunggu jawaban.
“Nggak tahu,” jawab Azul pada akhirnya. “Aku punya dua adik. Aku tidak yakin ibu memperbolehkanku kuliah.” Dia mengakhiri kalimatnya dengan bahu terangkat. Aku bisa melihat sedikit warna biru darinya, dan perasaannya itu menyalur padaku secepat warna itu muncul. Selama ini, yang aku tahu akan cowok itu, ibunya selalu bekerja keras membuat kue, sementara ayahnya .... Aku belum mengetahui pekerjaannya. Pasti berat jika harus membiayai ketiga anaknya yang masih dalam status pelajar.
Melihat aku terus menatapnya, Azul menghindari tatapanku dengan cepat sampai aku merasa bersalah telah menanyakan hal itu padanya.
“Pasti boleh.” Alif menimpali dengan santai sembari mencamil keripik kentang.
Kulirik Azul yang kembali mengangkat bahunya seeolah mengusir serangga di sana. “Kakakku saja tidak kuliah.”
“Itu, kan, kakakmu,” sosor Alif. “Memangnya kamu dan kakakmu itu sama?”
Aku kembali melirik Azul. Mulutnya terbuka untuk merespons perkataan Alif, tetapi Alif lebih dulu berucap, “Masalah biaya itu gampang. Kalau kamu berusaha, masuk kuliah itu mudah.”
“Omongan kamu yang mudah. Orang miskin mana bisa semudah orang kaya.” Azul mencibir. Aku hanya memperhatikan kedua sahabat itu berdebat seperti menonton acara televisi.
Alif mendesis, kesal dengan sahabatnya. “Kamu mau kuliah atau nggak?”
Aku hanya bisa berkedip saat menyadari kemarahan Alif. Pertengkaran ini jelas berbeda dari biasanya. Jika tahu situasinya akan seperti ini, lebih baik aku menanyakannya lain kali. Tidak. Seharusnya aku tidak menanyakannya sama sekali.
“Kamu menanyakan hal yang sudah jelas—”
“Kalau begitu jangan membuatku kesal!” Alif benar-benar marah, dan itu telah menyulut kemarahan Azul.
Kenapa jadi seperti ini?
“Aku membuatmu kesal? Hanya masalah—”
“Aku tahu kamu nggak benar-benar mau kuliah. Apa ekonomi keluarga jadi masalahnya? Banyak, kok, orang yang punya masalah kayak kamu. Tapi mereka sungguh-sungguh dengan niatnya. Bukan hanya sekadar sekolah, menunggu jawaban dari ibu. Kalau ibu tidak mengizinkan, ya sudah, gak jadi kuliah. Kamu seperti itu, 'kan?” Alif menyindir. Emosinya masih bisa ditahan untuk tidak berteriak marah, tetapi perkataannya telah membuat Azul menggeram.
“Kalau aku tidak kuliah, apa itu jadi masalah buat kamu?” Azul mendesis. Tangannya terkepal. Kendati aku tidak bisa melihat warnanya lantaran kami tidak sempat bertatapan, meski begitu aku tahu dia sangat marah.
Sebelum amarah mereka meledak, lebih baik aku mencegahnya. Aku akan sangat merasa bersalah jika hal itu terjadi. “H−hey .... Kita—”
“Orang kaya seperti kamu mana tahu sulitnya mencari uang.”
Seharusnya aku menghentikan pertengkaran ini dengan mudah, tetapi ternyata aku tidak bisa melakukannya. Bahkan menyela pembicaraan saja tidak bisa.
“Jangan bawa-bawa masalah ekonomi!” Alif menggeram. Sesaat itu juga aku mendengar decihan Azul.
“Siapa yang lebih dulu melakukannya? Aku bukan kamu yang bisa masuk universitas manapun dengan mudah. Di luar negeri pun pasti papamu—”
“Kalau kamu berusaha, masuk kuliah itu mudah! Kamunya saja yang tidak ada niat. Malas. Aku tidak heran kakakmu menganggur sampai sekarang.” Ucapan Alif sudah keterlaluan, dan itu berhasil memecah pertahanan Azul. Tunggu. Bukankah kakaknya Azul itu kerja?
“Kalaupun aku tidak kuliah, apa itu ada urusannya denganmu?” geram Azul. Dia membuatku waspada kalau-kalau berteriak dengan tiba-tiba. “Anak kesayangan memang mudah mengatakannya. Duduk santai, uang bisa didapat semudah memetik daun. Makanya kamu nggak tahu rasanya memikul batu.”
Azul menggigit bibir bawahnya. “Kamu bilang berusaha? Kalaupun benar aku bisa masuk kuliah karena beasiswa, apa kampus itu mau membiayai uang kuliahku sampai lulus? Seratus persen? Orang tuaku masih punya tanggungan, nggak seperti kamu yang anak tunggal dan punya usaha di beberapa tempat.”
Alif terdiam. Warna merah masih menyelimutinya. Ini kesempatanku untuk menghentikan pertikaian. Namun, lagi dan lagi aku gagal melakukannya.
“Sebaiknya hentikan saja rasa pedulimu itu.” Azul merapikan bukunya dengan emosi, dan aku panik berusaha menahan gerakannya.
“Eh, Zul. Sebentar—”
“Aku tidak ada niatan kuliah. Percuma saja aku belajar keras. Tapi makasih. Berkat kamu, aku yakin bisa naik kelas.” Azul tersenyum lembut padaku, tangannya masih sibuk merapikan barang-barang ke dalam tas, dan warna merahnya terus saja berkobar.
“Tapi, kan—”
“Biarkan saja.” Alif menimpali. Dia berusaha terlihat santai walau emosinya masih meluap-luap.
“Lif, kamu nggak seharusnya begitu,” sungutku. Di saat yang krusial seperti ini aku tidak bisa melakukan apapun. Ini pertama kalinya bagiku. Aku tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Ubin sudah pecah, dan memperbaikinya bukanlah keahlianku. Akan tetapi, aku berusaha melakukannya. Mereka temanku, tidak seharusnya aku bersikap bodo amat mendapati dua sahabat meretakkan lantai yang dipijak.
“Maaf aku sudah menanyakannya padahal kita masih di kelas sepuluh.” Aku memulai, harap-harap masalah ini terselesaikan. Aku menghadap Azul, cowok itu sudah akan pergi. Jadi, aku menahan lengannya. “Zul, Alif hanya kesal kalau kamu tidak kuliah. Dia hanya ingin melihatmu melanjutkan pendidikan, dan bukannya bekerja.”
“Pengangguran, mungkin.”
Aku memelotot pada Allif, berkeinginan melemparkan vas bunga ke wajahnya.
Azul tak menghiraukan Alif. Dia bersiap pergi, tetapi aku dengan cepat menahan lengannya. “Aku tahu, kok—”
“Sudahlah.” Ingin sekali aku menyembur Alif. Cowok itu tidak tahu usahaku untuk memperbaiki hubungan yang menurutku baru. “Biarkan saja dia seperti itu. Tidak berpendidikan.”
“LIF!” Aku membentak. Benar-benar marah padanya. Apa dia tidak tahu perkataannya bisa membuat situasi menjadi lebih buruk? Bisa-bisanya dia tidak menghargai usahaku.
Lengan Azul lepas dari cengkeramanku. Cowok itu sudah berjalan cepat keluar rumah. Aku berusaha mengejarnya, memanggil namanya, tetapi Azul menjadi tuli. Ini buruk. Pertama kalinya aku memiliki teman, dan pertama kalinya pula kedua temanku bertengkar di hadapanku.[]
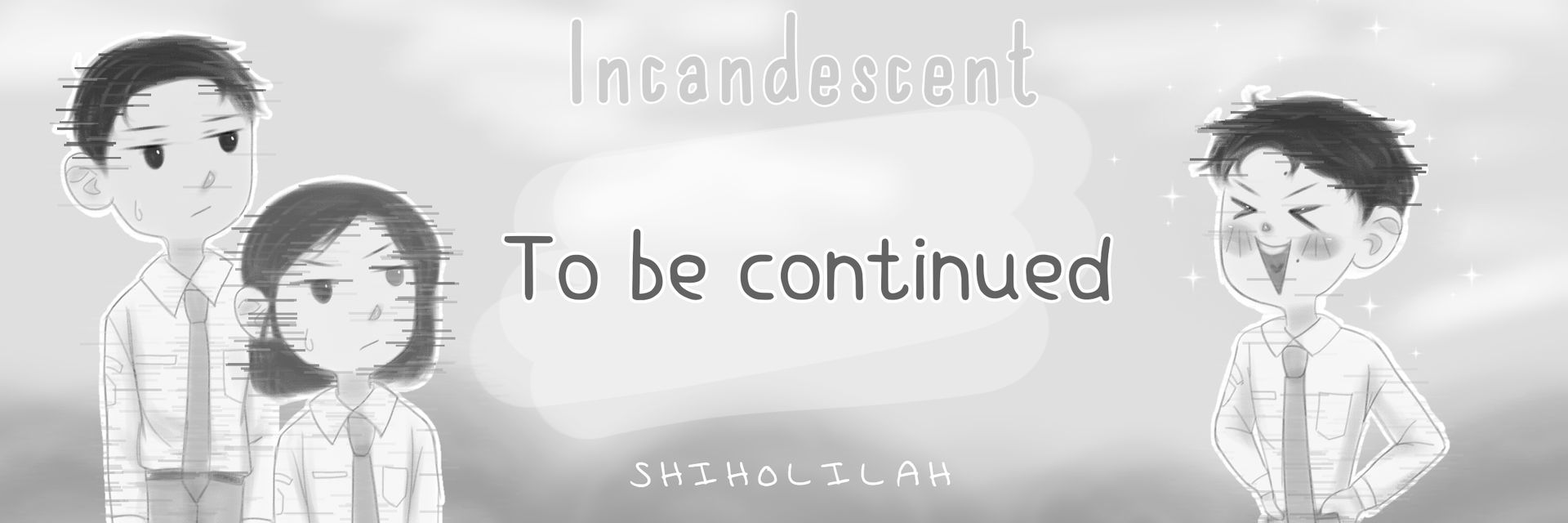
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top