BAB 16: SAKTAH KEDUA
IMAM MASA DEPAN
Written By: Sahlil Ge
BAB 16: Saktah Kedua
Diunggah pada: 26/12/2017
Revisi: --/--/----
***
Hak cipta diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
***















Jangan lupa kasih bintang biar Abang semangat.
🌟
BAB 16
SAKTAH KEDUA
{Dinda Humaira Rasyid}
1
Aku suka sekali embun yang menempel di kaca. Mereka sangat indah dan, ya, aku bisa melihat sesuatu yang hanya bisa dimaknai oleh diriku sendiri. Pagi di desa rasanya begitu menyenangkan. Lega rasanya bisa kembali ke rumah setelah beberapa bulan di Bandung. Memang benar kalau aku bilang antara Bandung dan Pekalongan itu beda cerita. Ahh, tapi apa ya bedanya? Ketika aku sadar perbedaan itu, rasanya pipiku mulai memanas dan bayangan wajah seseorang akan hadir, lalu kabur seketika oleh istighfar bersama senyum.
Aku kembali menghirup aroma kamarku tercinta sekitar pukul tiga pagi. Tidak langsung tidur karena sepanjang perjalanan pulang lebih banyak kuhabiskan untuk lelap di sebelah Mas Alwi. Jadi tidak terlalu banyak obrolan atau membahas apapun. Itu bagus karena aku masih punya kesempatan mengejar sepertiga malam di atas sajadah. Berbisik lirih pada Allah, malu-malu menyebut sebuah nama. Terkadang aku malah cuma menengadahkan tangan ke atas, tersenyum, dan berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu keinginan hamba-Mu. Aamiin."
Kerinduanku pada suasana pesantren Abi membuatku semangat bergegas ke masjid ketika azan subuh berkumandang. Tentu bersama Umi perginya. Karena aku belum bisa menahan diri dengan rasa malu kalau ada yang berkata, "Ustadzah Dinda baru pulang?". Aku belum bisa memikul imbuhan nama itu, hanya Umi yang bisa membuat warga berhenti bertanya. Biasanya dia yang akan melerai mereka yang mencoba menanyaiku banyak hal.
"Banyak sekali yang menanyaimu semenjak pergi ke Bandung, Nduk. Umi sampai lelah menjawab pertanyaan warga," kata Umi saat bersiap sebelum keluar menuju masjid.
"Itulah Umi, kenapa Dinda lebih senang berada di perantauan. Ketika tidak ada yang benar-benar tahu latar belakang Dinda," ujarku dengan senyum sambil menutup kelambu kamar.
"Kadang Umi juga kesal kalau banyak orang yang menanyakanmu."
"Kesal kenapa?"
"Semakin banyak yang bertanya, Umi jadi semakin rindu. Kalau bisa kemarin Umi saja yang ikut jemput kamu. Tapi Alwi kekeh supaya dia saja. Padahal Umi kurang setuju kalau Hasna ikut juga."
"Kan Mba Hasna bersama Bapaknya, itu nggak masalah."
"Iya, Umi paham. Tapi kan apa kata orang? Harusnya mereka ndak bareng-bareng dulu sebelum nikah. Empat hari lagi apa ndak kuat." Aku tersenyum melihat tingkah Umi. Caranya khawatir bisa bikin orang di sekitarnya ikut terpengaruh. "Alwinya mana? Wi...! Ayo kalau mau ke masjid bareng Umi sekalian."
"Tadi keluar duluan sama Razak, Mi."
"Oh ya udah. Lampu kamar matiin dulu."
"Udah."
"Ayo."
Titian ke masjid selalu aku rindukan. Ada aroma fajar yang tidak bisa dilekang oleh zaman. Aku bahagia melihat kesadaran masyarakat desa ini masih sangat kuat untuk menghadiri subuh berjamaah dan dilanjut menyimak pengajian dari Abi. Sosok Kyai yang sangat ngemong masyarakat. Tidak heran beliau ingin siapa saja yang jadi penerusnya, harus memiliki rasa ngemong pada masyarakat.
Kepulangan ini aku juga ingin jujur pada Umi, bahwa aku sedang jatuh cinta dengan seorang pemuda yang baik, tegas, dan aku sangat yakin dia memiliki sifat ngemong, juga sholeh. Tapi ada satu hal yang aku lupa katakan pada Kang Abim. Membuat aku jatuh cinta mungkin mudah, tapi membuat keluargaku jatuh cinta itu adalah lain cerita.
2
Suasana di pesantren ketika musim lebaran haji sungguh meriah. Para santri akan ramai-ramai membuat tusuk sate di pelataran pesantren, dan hasilnya boleh dijual ke masyarakat dengan harga murah, keuntungannya seratus persen untuk santri. Percaya atau tidak, mereka bisa melayani ribuan batang tusuk sate tiap harinya, bahkan Abi berencana akan membelikan mesin pembuat tusuk sate untuk mereka bisniskan. Pesantren juga memiliki lahan wakaf yang biasa dikelola oleh santri, bebas ditanami apa saja untuk keperluan mereka. Ada sayuran, buah sirkaya, nangka, mangga, dan beberapa rumpun bambu. Itu memang program berdikari yang dicanangkan oleh Abi kepada semua santri.
Dalam urusan itu Mas Alwi juga ikut mengambil alih. Santri senior diajari berbisnis supaya setelah menjadi alumni bisa membuka usaha serupa. Itu tidak cuma-cuma, mereka yang bekerja di peternakan Mas Alwi juga mendapat komisi yang layak. Lumayan bisa buat beli sarung baru dan perlengkapan mandi.
Satu hal yang aku kagum adalah, Abi tidak pernah mempermasalahkan biaya pendidikan di pesantren. Tidak ada penekanan apabila santri telat bayar uang bulanan. Yang aku tahu malah banyak donatur yang melunasi kewajiban santri untuk urusan ini. Banyak warga yang juga memberi gabah dan kebutuhan makanan lainnya. Abi bilang, itu semua adalah rezeki dari Allah untuk semua santri sehingga mereka hanya bisa fokus belajar dan belajar.
Siang itu Umi dan Abi sedang berada di pesantren untuk rapat rutin dengan santri dan beberapa warga membahas pembagian daging qurban. Itu dilakukan sekarang supaya tidak mendadak keesokannya. Biasanya rapat dibagi dua termin. Pertama bagian Abi yang memimpin, ini jelas untuk urusan pemotongan hewan qurban. Sedangkan rapat yang diambil alih Umi, bahasannya tentu urusan masak-masak untuk mereka yang bekerja payah mengurus hewan qurban. Jadi, sedari pagi di rumah hanya ada aku dan Mas Alwi.
Aku segera bergegas ketika terdengar suara pintu diketuk. Tidak lupa membetulkan jilbab karena tadi aku sedang mengembalikan energi dengan tidur siang.
Sebelum membuka pintu aku mengintip sebentar dari gorden. Di sana sudah ada seorang laki-laki yang memakai seragam formal berwarna hijau keabu-abuan. Tinggi tubuhnya sedang. Dia berdiri membelakangi pintu sehingga yang terlihat olehku hanya tengkuk lehernya yang putih dan belakang telinganya yang sedikit memerah. Tidak begitu jelas, tapi, topi lapangan yang dia kenakan seperti ada lambang Perhutani. Siapa beliau ini? ada perlu apa bertandang ke mari?
Tanpa berpikir panjang lalu aku membuka pintu. Saat itu juga, laki-laki yang membelakangi pintu itu berbalik. Dia tersenyum tipis awalnya. Namun seketika padam dan langsung menunduk hingga bagian depan topi lapangannya yang lebar berhasil menyembunyikan wajahnya dariku.
"Assalamualaikum," ucapnya hangat.
"Waalaikumsalam," jawabku. Dari pemahamanku, orang ini sudah melakukan adab bertamu dengan baik, yaitu mengucapkan salam ketika tuan rumah membuka pintu. Kadang kita keliru, mengucapkan salam berkali-kali di depan pintu bahkan ketika tidak ada orang. Adabnya memang begini, mengetuk pintu terlebih dulu, ketika pintu terbuka dan tuan rumah keluar barulah ucapkan salam. "Ada perlu sama Abi ya, Mas?" aku berkata duluan karena dia seperti sedang gugup.
Dia menengadahkan wajahnya sebentar untuk berkata, "Bukan. Gus Alwi meminta saya datang ke sini." lalu kembali menunduk.
"Oh, iya, silahkan masuk. Biar saya panggilkan orangnya." Aku melebarkan pintu supaya dia bisa masuk. "Duduk dulu, Mas," kataku lagi. Lalu bergegas ke dalam.
"Mas..." kataku sambil mengetuk pintu kamar Mas Alwi. "Mas Alwi... ada tamu buat Mas."
Tak perlu waktu lama, kemudian terdengar suara seperti benda jatuh dan erangan. "Mas Alwi...?" aku seketika khawatir. Tanpa pikir panjang aku langsung membuka pintu kamarnya. Dan yang langsung tertangkap oleh mataku adalah Mas Alwi yang sedang kejang-kejang di lantai. Kakinya yang kurus terkulai lemas. "Astaghfirullah, Mas Alwi!" aku menubruk dan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Badannya panas tinggi. Keringat dingin mengembun deras di hampir sekujur tubuh. Yang terucap dari bibirnya hanyalah "Allah... Allah... Allah..."
"Tolong... !!!" tidak tahu apakah teriakan panikku ini berlebihan atau tidak. Tapi aku benar-benar butuh pertolongan seseorang. Lalu sosok yang di ruang tamu itu bergegas menujuku. Awalnya dia hanya berdiri di ambang pintu tanpa mendekatkan jarak. Tanpa berkata apa-apa kemudian dia langsung bersusah payah mengangkat Mas Alwi. Aku menolehnya dengan pandangan buram karena genangan air mata. "Tolongin, Mas."
"Awas," katanya agar aku menyingkir. Sambil terus berusaha mengangkat dia berkata, "Gus Alwi, menelepon saya untuk ini. Beliau merasakan demam tinggi dan minta diantar ke dokter, tapi kalau keadaannya seperti ini lebih baik ke rumah sakit saja sekalian. Tadi dari kantor saya langsung ke sini bawa mobil teman," nada bicaranya kaku sekali. Aku masih tidak mengerti maksudnya.
Tanpa sadar aku juga menatap wajahnya untuk mencari penjelasan dari kata-katanya. Namun wajah itu terus memerah tanpa menatapku, apa dia ikutan demam juga?
"Permisi," ucapnya sambil berdiri mengangkat Mas Alwi.
"Tunggu, itu mau dibawa ke mana?" suaraku menahan tangis.
"Mobilnya sudah di depan."
"Masnya ini siapa?"
Dia tidak menjawab, menghiraukanku dan lebih mementingkan tetap berjalan.
"Saya harus ikut!"
"Tidak perlu. Kasih tahu Pak Kiai saja."
"Itu bisa nanti saya telepon. Saya adiknya, saya berhak menjaga dan memastikan Mas Alwi mau dibawa ke mana dan oleh siapa."
Tanpa menatapku, kepalanya bergerak ragu dan berkata. "Bawa bantal dan selimut."
Aku memungut air mata gugup sambil bergegas memasuki kamar. Setelah itu aku mengejar orang itu sampai pada sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan. Rumahku memang tidak terletak di jalan utama. Pemuda itu sedang berusaha membaringkan Mas Alwi di jok belakang. Ada dua bapak-bapak yang ikut membantu.
"Gus Alwi kenapa, Neng?" tanya salah satunya.
"Saya tidak tahu, Pak," jawabku.
"Pak Kiai tahu?"
"Belum, Abi dan Umi sedang rapat di masjid pesantren. Boleh tolong kabarin mereka, Pak? saya tidak sempat, ini harus segera dilarikan ke rumah sakit."
"Oh, boleh boleh. Segera saya ke sana," beliau bergegas pergi.
"Bantal," kata pemuda itu. Setelah mendapatkannya dia lalu mengganjal kepala Mas Alwi dengan bantal itu. Kemudian aku naik di sebelahnya dan membentangkan selimut ke tubuhnya. Aku membiarkan badannya yang panas sekali sedikit bersandar di pundakku karena berbaring pun agaknya susah. Aku tidak bohong, badannya panas sekali dan sudah tidak terlalu berguncang tubuhnya.
Sejurus kemudian mobil itu bergerak cepat di jalanan aspal. Pemuda itu sigap sekali menggerakkan setir. Butuh sekitar setengah jam agar sampai di rumah sakit kecamatan. Jalanan yang dititi pun meliuk dan menanjak. Aku tidak berhenti mengusap pundak Mas Alwi sepanjang perjalanan. Sambil terus menangis tentu.
"Mas Alwi bilang apa sampai Masnya datang cepat-cepat?" tanyaku benar-benar penasaran. Kenapa dia tidak memberitahu keluarganya yang bahkan ada lebih dekat. Apa karena dia tahu tak ada orang yang sedang sedia saat itu? aku sedang istirahat, Umi dan Abi jelas di pesantren. Jadi, siapa laki-laki ini? kenapa harus dia dan bukannya Razak yang biasa nyetir? Mas Alwi memang rentan dengan sakit yang seperti ini. Tubuhnya sagat ringkih.
"Gus Alwi hanya bilang sedang demam dan sudah tidak kuat."
"Sakit apa?"
"Saya tidak tahu. Saya bukan dokter."
"Mungkin malaria. Gejalanya persis," aku sendiri yang menjawabnya.
Lalu ponselku berdering dan ada nama Umi yang memanggil. Tanpa babibu aku langsung mengadu seperti anak kecil. "Umiiii... ini Mas Alwi kenapa?" kataku sambil menangis.
"Memangnya kenapa, Nduk? Tadi pagi sehat-sehat saja," katanya panik. "Sekarang kamu dimana?"
"Dinda ndak tahu. Tadi pas buka kamar Mas Alwi sedang kejang. Ini dalam perjalanan ke rumah sakit kecamatan, Umi."
"Sama siapa?"
Aku belum bisa menjawab untuk ini. "Masnya namanya siapa?" aku bertanya sekali lagi.
"Faris."
"Namanya Mas Faris, Umi."
"Nak Faris? Kok bisa?" Aku kebingungan di sini. Kenapa Umi seperti sudah mengenal orang ini dan aku tidak? "Yo wes. Kamu tenang saja. Pokoknya setiba di sana kamu langsung ikuti prosedur rumah sakit. Kamu bilang saja ke suster atau siapa agar dokter Wawan yang menangani."
"Dokter Wawan."
"Iya. Umi akan segera menyusul ke sana sama Abi," tutupnya dengan nada panik yang tak terhapuskan.
Sesampai di rumah sakit, Mas Faris membopong tubuh Mas Alwi yang masih pingsan. Dua suster langsung membimbingnya ke kamar pasien.
"Sus, dokter Wawan."
"Baik, Bu," jawabnya seolah langsung mengerti.
3
Di depan kamar rawat Mas Alwi, aku duduk di sebuah kursi tunggu yang memanjang. Lalu di seberangku persis, pemuda yang namanya Faris itu juga sedang duduk dengan kedua tangan ditopangkan di atas lutut. Salah satunya menggenggam topi. Jadi sekarang aku bisa melihat dengan jelas seperti apa wajahnya.
Aku bisa tahu ada tahi lalat kecil di atas sudut bibir kanannya dekat hidung. Semua orang tahu kalau tahi lalat di titik itu adalah pemanis alami yang menjadi karunia semesta. Kulitnya putih terang. Rahangnya cukup jantan, lebih pantas lagi dengan seragam polisi hutannya. Rambutnya lepek bekas topi, tapi tidak menghilangkan sisi rapi pada penampilannya.
Astaghfirullah, apa yang baru saja aku amati ini.
Bagaimana Mas Alwi mengenal orang ini? apakah dia pemuda dari desaku? Tapi siapa? Berada cukup lama di perantauan membuatku kadang tak ingat dengan wajah banyak orang.
Udara canggung membeku di antara kami. Di dalam kamar rawat seperti masih ada pekerjaan medis.
"Terima kasih sudah menolong, Mas," kataku.
Demi Allah, hentakan dahsyat meninju ulu hati manakala dia tersenyum dan tahi lalat di posisi favoritku itu terangkat. "Sama-sama."
Sekarang aku tidak melihat ketegangan di wajahnya lagi.
"Saya tidak tahu kenapa Mas Alwi lebih memilih menelepon Mas Faris dari pada bilang langsung ke saya yang jelas-jelas ada di rumah."
"Katanya tidak ingin merepotkan yang sedang istirahat."
"Bukannya Mas Faris sendiri sedang bekerja? Katanya tadi langsung dari kantor. Itu lebih merepotkan dan mengganggu."
"Itu tidak masalah."
"Mas Alwi lebih memilih merepotkan orang lain dari pada keluarganya sendiri."
"Saya bukan orang lain baginya. Tapi lebih dari itu kami adalah teman semasa kecil."
Aku semakin takut kalau Mas Faris ini juga orang yang pernah kukenal dan terlupakan. Tidak sopan jadinya.
"Oh, begitu."
"Iya," katanya. Tak lama kemudian dia berkata, "Masmu pasti akan segera pulih," seolah berusaha menenangkanku.
"Meski yakin begitu, tetap saja saya khawatir, Mas. Semalam kami baru saja pulang dari Bandung. Mas Alwi menjemput saya."
"Begitu ya."
"Iya. Mungkin dia kelelahan atau saya tidak tahu kenapa."
"Ooh... bagaimana kuliahnya, Dinda?"
Aku menelan ludah. Mengejutkannya dia tahu namaku dan cara dia mengucapkannya terdengar begitu akrab. Sekali lagi aku mengorek memori di dalam kepala barang kali aku melupakan sesuatu tentang orang ini.
"Baik-baik," aku tak berani menatap karena sepertinya dia sedang melihat ke arahku yang menunduk.
"Syukurlah."
Aku mengangguk saja.
"Kamu sepertinya tidak mengenali saya."
Hanya Allah yang tahu betapa menggigilnya ulu hatiku. Takut kalau aku sungguh melupakan sesuatu.
"Maaf," aku menggeleng dengan sedikit malu-malu.
"Harusnya kamu tidak asing dengan nama saya. Faris Kamil."
Sekali lagi aku hanya bisa menggeleng.
"Mungkin kamu kenal Nabila yang rumahnya di tengah perkebunan itu."
"Nabila, dia adik kelas saya waktu masih MI. Tidak begitu akrab, tapi saya tahu."
"Saya Masnya."
Dengan informasi sejelas itu pun aku masih tidak mengenali dia! Astaghfirullah.
Aku jelas sekali mendengarnya tertawa sedikit. "Bercanda. Saya tahu kamu susah mengenali saya. Sejak umur 13 tahun saya ikut Bapak ke Jakarta. Lanjut sekolah di sana sampai lulus SMA. Setelahnya bekerja dua tahun di lini usaha budidaya tanaman hias, lalu pulang ke desa karena Ibu saya sakit. Akhirnya tidak pernah ke mana-mana lagi karena mendaftar jadi polhut kabupaten dan lolos. Setahun di desa, Ibu saya wafat, lalu disusul Bapak tepat setahun setelahnya," aku menyimak biografi singkatnya itu.
"Maaf, saya teralu banyak mengoceh."
"Tidak apa-apa," kataku gugup. "Maaf karena saya tidak bisa mengenali. Saya tahu kalau Nabila punya kakak laki-laki, tapi tidak begitu paham kalau itu, Mas Faris."
"Saya memaklumi," dia tersenyum lagi. Oh... cukup.
Aku setengah berdiri untuk melongok apakah di dalam sana sudah selesai perawatannya. Dari tadi suster keluar masuk ruangan. Tapi tidak ada ekspresi panik di wajahnya. Semoga itu pertanda baik.
"Dinda," kata Mas Faris tiba-tiba.
"Iya." Aku kembali duduk.
"Bagaimana jem apelnya? kamu suka?"
.
.
.
Kau tahu? Aku pernah mengalami saktah dengan seseorang untuk yang pertama kali. Sekarang, di dalam kepalaku sedang ada kepingan memori yang dengan cepat menyusun jadi satu fakta utuh. Dan kenyataan itu menghisap habis napasku kali ini. Sangat lama. Begitu dalam. Seolah aku harus berusaha menggapai-gapai udara untuk dihisap oleh paru-paru. Tidak salah lagi ini seperti saktah. Tetapi lebih kuat dan menghantam sampai aku susah sekali menghirup dan menghembus pada napas berikutnya.
Aku terduduk lemas. Menatapnya sesaat lalu mengalihkan. Dia juga seperti tidak mengharapkan aku menjawab cepat-cepat. Wajahnya sangat tenang. Terang seperti selingkar purnama, tidak menyilaukan, atau terlalu redup. Untuk sesaat aku mencari senyumnya itu. Hanya berharap kalau dia melakukannya, dia akan mengatakan bahwa ucapannya tadi adalah bercanda. Tapi aku tidak menemukan itu. Yang ada hanya sebuah kesungguhan yang mustahil aku sangkal.
Langkah kaki Abi dan Umi yang tergesa seperti berhasil menjebloskan aku ke dalam bumi bersama segunung pertanyaan. Membuat kepingan yang baru saja tersusun runtuh berantakan. Aku buyar tak sempat menemukan jawaban dari pertanyaannya tadi.
Aku jelas sekali melihat bibir Umi dan Abi mengatakan sesuatu. Tapi tak ada satu suara pun yang berhasil ditangkap pendengaranku. Mereka seperti bisu, atau aku yang seketika menjadi tuli.
---o0o---

Baca sampai akhir, cermati!
Kangen ya?
Hee...
Saya nggak ke mana-mana. 💛
Oh iya, BAB 17 akan langsung saya unggah kalau BAB 16 ini sudah mencapai lebih dari 40 bintang.
Jangan lupa siapkan tisu dan kencangkan sabuk pengaman untuk bab-bab selanjutnya.
|
|
|
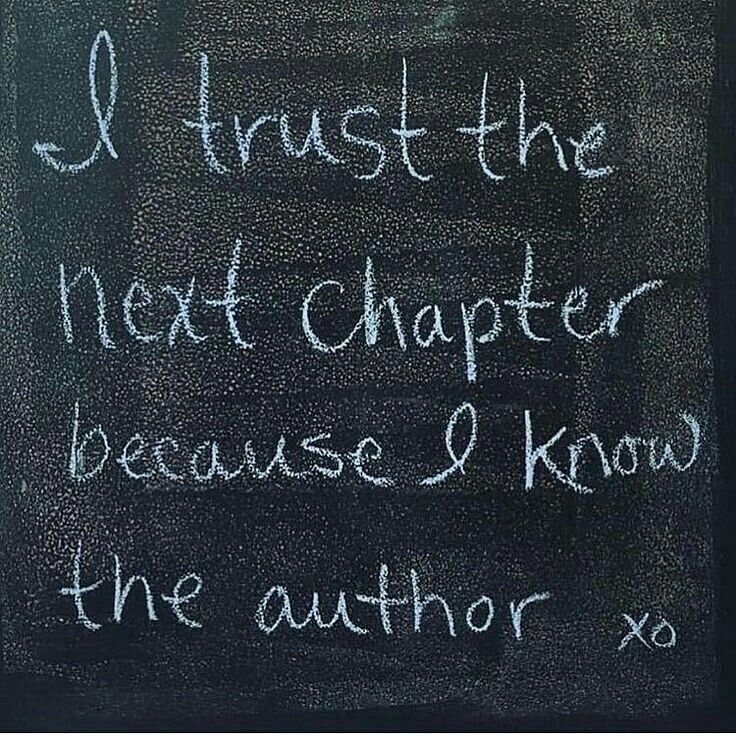
Artinya: Dilarang kepo & sok tahu nebak-nebak jalan cerita. Percayakan saja sama saya.
With love:
Sahlil Ge

COMING SOON:
2018
(Kondisional)
Judul: PUTUS MULAI BESOK
Genre: Metropop
Jumlah Bab: 30+
Usia Pembaca: 18+ (Ini bukan cerita porno) / Hanya saja butuh pikiran dewasa untuk memahami pelajaran hidup yang akan disajikan.
Doakan semoga saya panjang umur dan tetap bisa menyelesaikan segala urusan dengan baik.
💛
Silahkan komentar sepanjang-panjangnya terserah kalian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top