Bab 1 - Alam Semesta
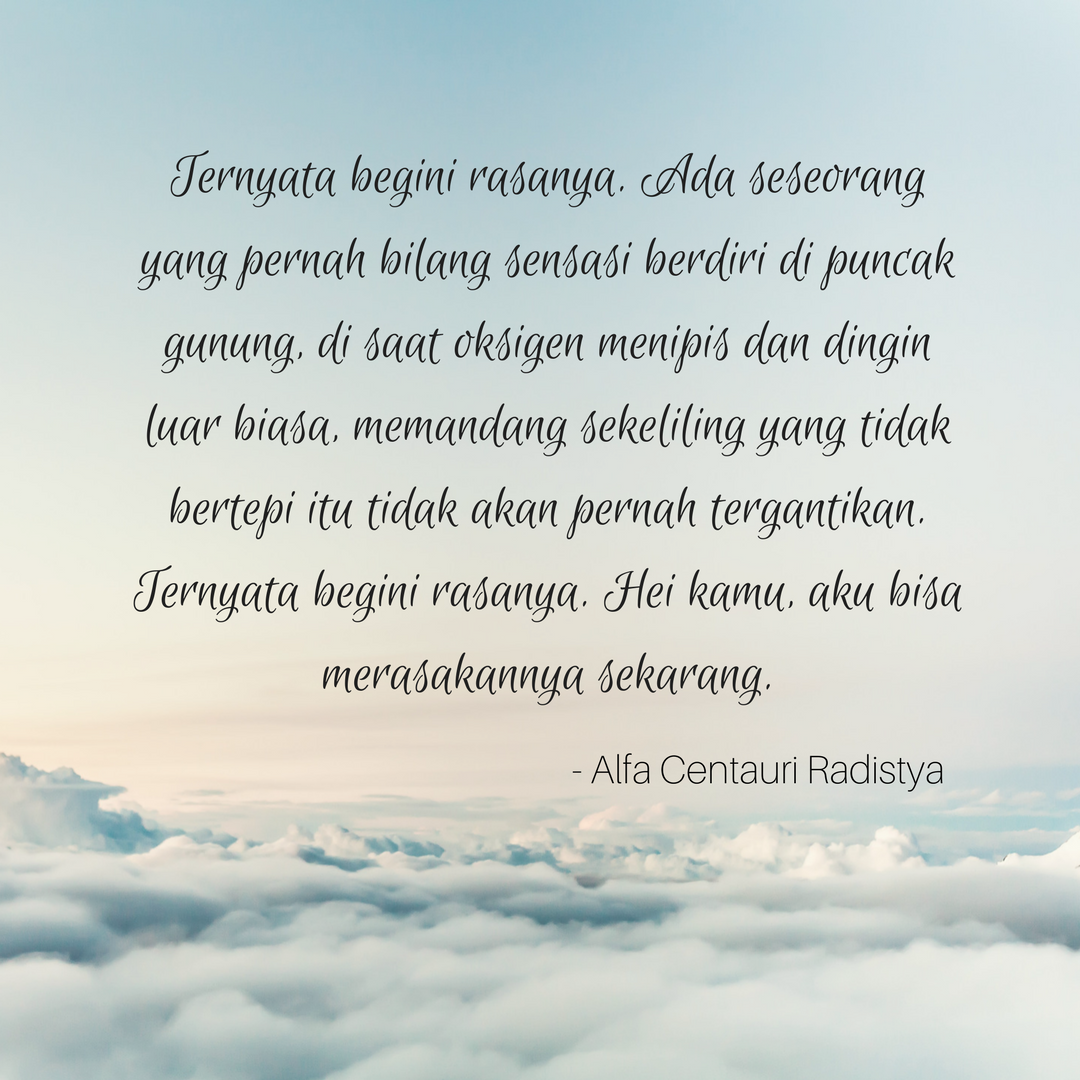
Yay! Akhirnya Alfa naik gunung! Yay! Yay! Yay! Norak sedikit enggak dosa kan, ya? Kakiku masih gemetaran saking capeknya. Naik gunung ternyata memang penuh perjuangan. Pantas saja Bunda suka wanti-wanti kalau memang bukan karena kewajiban kuliah, mending enggak usah pengen-pengen naik gunung. Tapi kalau udah berdiri begini, di sini, rasanya aku pengen bilang ke Bunda, "Bun, ini nih yang namanya hidup!"
Asli, kacau sih ini. Wow! Wow! Rasanya pengen teriak-teriak terus. Ya gimana, ini adalah saat pertamaku naik gunung dan rasanya memang seajaib itu. Setelah mengucap syukur, sekarang yang pengen aku lakukan cuma loncat-loncat dan bilang, "You did great, Alfa!" Sayangnya, kata si Miras yang sudah lumayan expert naik gunung, jangan kebanyakan polah kalau enggak mau kenapa-kenapa. Jadinya cuma bergejolak di dalam dada.
Aaaaaa....! Kurang lebih begitu sih isi teriakan di dalam kepala sama di dalam hatiku. Sesenang itu, serius. Apalagi mengingat perjuangan naiknya yang penuh drama. Sebagai seorang newbie, semua teori tentang perjalanan di alam bebas rasanya cuma jadi sekedar teori. Belum juga sampai di pemandian air panas, rasanya udah mau mati saking capeknya. Untungnya nih, partner naik gunungku sekarang ini semuanya solid. Cinta banget deh sama mereka.
Mereka enggak capek menanggapi rengekanku, 'Masih jauh?' dan semua kompak menjawab, 'Sebentar lagi'. Sebentar lagi, yang artinya masih berjam-jam perjalanan penuh drama lainnya. Dan Miras berkata, "Mending lo nyanyi lagu koplo aja deh Al, kayak si Agam kalau di kelas. It works. Cobain deh!" Akhirnya dia sendiri yang mengorbankan diri menjadi badut perjalanan demi menguatkan sahabatnya yang letoy ini. Cinta banget sama Miras! Dan 2.958 mdpl ini menjadi jawabannya. Bahwa aku bisa. Biasanya kan cuma mentok di 1.675 mdpl saja. Dan di sinilah aku, di Puncak Gunung Gede.
Kalau pemandangan dari atas puncak gunung memang selalu semengagumkan dan semendebarkan ini harusnya aku sudah dari dulu merengek izin dari Bunda biar diizinkan naik gunung bareng teman-temanku. Mereka saja sudah dari semester satu sering naik ke Gede, katanya sudah bosan, termasuk si Miras. Lah aku? Ckckckck so pathetic.
Selalu berdalih belum siap fisik dan mental. Untung saja di antara kebosanan Miras, Kak Ziko, Deni, dan Silvia mereka masih mau 'mengantarku'. Kalau Miras sih jelas alasannya karena Denta ikut, sok heroik saja dia katanya demi aku. Halah! Tapi dia berjasa bantuin aku minta izin ke Bunda. Jadi ya, aku tetap cinta Miras.
Aku mau serius menikmati sunrise terindah selama hampir 19 tahun hidupku. Deru napas lelah yang mengeluarkan uap menjadi hal yang menyenangkan untuk dirasakan. Ada kekuatan yang tak bisa tergambarkan mengenai betapa sempurnanya pagi pukul 05.15 ini. Di saat posisi bumi dan matahari hampir berhadapan, maka cahaya-cahaya kemilau sudah menjadi pertanda hadirnya hari baru. Dan tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan matahari terbit dari atas gunung.
Ternyata begini rasanya. Ada seseorang yang pernah bilang sensasi berdiri di puncak gunung, di saat oksigen menipis dan dingin luar biasa, memandang sekeliling yang tidak bertepi itu tidak akan pernah tergantikan. Ternyata begini rasanya. Hei kamu, aku bisa merasakannya sekarang.
Udara manis dari oksigen yang semakin menipis ini membuat manusia terasa kecil sekali. Perjalanan hati, katanya. Di saat sedang lelah-lelahnya kaki berjalan, tapi tekadnya tidak pernah lelah. Aku setuju.
"Heh! Congrats, ya! Jangan ngelamun mulu. Bahaya!" kata seorang cewek yang hidungnya sudah merah kembang kempis dan hanya terlihat wajahnya saja karena outfit gunung menutupi semua tubuhnya. Dia Mir—Elmira—sahabatku. Aku sering memanggil dia Miras, ngikutin anak-anak. Kenapa anak-anak memanggilnya begitu, karena kalau ngomong dia kayak orang mabok. Banyak nggak jelasnya. "Foto-foto yuk, terus turun!"
"Al, buruan!" seru suara dari sisi barat. Teman-temanku yang lain yang sepertinya sudah sibuk mengambil gambar dari tadi. Itu suara Denta, pacarnya Miras. Sahabatku dari SMA. Kata Miras, dengan naik gunung ini sekalian jadi momen dia bisa pacaran sama Denta dengan proper.
Di kampus tidak banyak yang tahu mereka pacaran, menurut Miras bahaya karena fans Denta ada banyak. Yah, tipikal anak BEM, kandidat kuat calon Presma, ganteng dan baik. Kata Miras lagi, membawaku ke gunung adalah salah satu tanda terima kasihnya karena aku sudah mencomblangkan dia dengan Denta. Dih, mana ada! Padahal dia sendiri yang suka alay cari-cari perhatian Denta.
Walaupun mereka suka enggak tahu diri pacaran di depanku, tapi menyenangkan rasanya melihat dua sahabatku bersama. Soalnya kalau mereka lagi kencan, mereka sering mengajakku dan suka traktir. Itu alasan paling masuk akal kenapa aku bersyukur mereka bersama.
"Ih ... masih betah," kataku menolak beranjak cepat-cepat.
"Ye, udah mulai susah nafas nih gue. Ayo ih! Enggak boleh lama-lama di sini. Nanti lagi lo ke sini sama Kak Ziko biar romantis! Otak liar lo kan, yang suka berandai-andai mau pacaran di gunung?"
"Kenapa jadi Kak Ziko, deh?" kataku mengelak. Kak Ziko adalah seniorku dan Miras yang juga ikut dalam pendakian ini.
"Ngeles ... ngeles. Iya, ngeles aja terus. Itu orang dari tadi gue perhatiin udah enggak kehitung ngelihatin lo berapa kali. Takut lo nyungsep ke kawah apa ya? Padahal doi maunya lo nyungsep ke hati dia. Cia ... cia ... cia...."
Kan, apa kubilang? Kayak orang mabok memang si Miras kalau ngomong. Begini ini contohnya, ngelantur ke mana-mana omongannya.
"Apa deh Mir? Garing tahu, enggak?"
"Eh tapi serius Al, gue yakin kalau Kak Ziko beneran ada rasa sama lo. Emang beneran selama ini manuver dia lempeng-lempeng aja ke lo? Hati-hati ditembak di sini, lho."
"Ck, manuver apa pula. Pesawat kali manuver segala? Udahlah, ayo ke sana. Lapar aku." Aku mulai bergerak turun dari atas batu yang sedari tadi kujadikan sebagai pijakan.
"Giliran perut aja cepet lo! Eh nanya serius ini gue, beneran lo enggak ada rasa sama Kak Ziko?" tanya Miras buru-buru sambil menyejajari langkahku, "udah setahun kan dia modus-modus lucu gitu?"
"Enggak! Jangan gosip deh Mir, enggak enak kalau kedengeran yang lain."
"Ini orang enggak capek apa jomlo menahun? Emang kurang apa sih Kak Ziko? Ganteng iya, ketua angkatan, wibawa jangan ditanya, pinter ... kayaknya pinter sih, enggak aneh-aneh anaknya. Demenan lo banget nggak sih, tipe begitu?"
"Udah ngawurnya?"
"Al...." Miras tiba-tiba menghentikan langkahku. Mau tak mau aku berhenti. "Lo masih kepikiran dia yang jauh di sana?"
Aku diam saja. Tidak tahu mau jawab apa.
"Gila sih lo, dari SMA lho, Al. Enak emang jatuh cinta sendirian?"
Jatuh cinta sendirian.
Aku masih tidak mampu menjawab pertanyaan Miras.
"Lo enggak mikir aneh-aneh ala sinetron kalau suatu saat lo bakalan ketemu sama dia, kan? Ya mungkin aja sih ketemu, kalau jodoh mah nggak akan ke mana.
Tapi kan tetap aja lo enggak tahu nama dia siapa, orang mana aslinya, masih muda apa udah kakek-kakek. Enggak capek emang? Lo sendiri aja enggak yakin dia tergapai kan? Apa yang lo bilang dulu? Dia kayak ada di Parallel Universe? Segitu sureal-nya?"
"Ngomong naon sih maneh teh?" jawabku akhirnya. Aku lagi enggak pengen bahas apa pun tentang dia. Momen yang ada sekarang hanya satu dari sekian pertanda bahwa 'kebebasan' yang dia bicarakan ketika ada di alam bebas juga bisa aku rasakan.
Aku bersyukur terprovokasi olehnya dulu dan akhirnya bisa merasakan pertama kalinya naik gunung, walaupun baru kejadian sekarang.
Aku cuma ingin berterima kasih untuk provokasinya yang terlalu persuasif sehingga akhirnya aku bisa memandang alam semesta dengan sudut pandang yang berbeda. Berterima kasih dan sekedar mengingat bukan berarti bahwa aku akhirnya terlalu terbawa perasaan, kan? Begitu, kan? Atau enggak?
***
Semalam, di Alun-Alun Suryakencana, di saat semua orang sedang tidur, aku melihat langit gelap dan udara yang membelai malam dengan lembut. Dan saat itu yang kurasakan adalah dingin dan kesendirian.
Seseorang itu pernah merasakan hal yang sama saat dia sedang kemping di Faroe Island di antara Skotlandia dan Islandia. Dia juga merasakan betapa gunung, sendiri, dan sepi itu berhubungan erat.
Lalu dengan sok filosofisnya orang itu mengutip kata-kata Italo Calvino, segitunya banget kamu mau aku melakukan sebuah perjalanan, hm?
Aku belum sempat baca buku si Calvino ini, tapi aku masih ingat kutipan yang dia kirimkan melalui surel beserta dengan niat terselubung pamer-pamer foto indahnya Faroe Island. Huh!
Begini kata-katanya: to fly is the opposite of traveling: you cross a gap in space, you vanish into the void, you accept not being in a place for a duration that is itself a kind of void in time; then you reappear, in a place and in a moment with no relation to the where and when in which you vanished.
Aku enggak ngerti-ngerti banget interpretasi dari kata-kata itu, tetapi satu yang pasti dan kualami saat itu adalah pikiranku yang terbang ke mana-mana, terlebih tentang kebaikan Tuhan yang menyajikan berbagai bintang dengan begitu meriahnya yang tidak pernah aku lihat di kota. Sampai mau loncat-loncat juga rasanya.
Tapi malam itu perasaan ... hmm ... apa ya namanya, perasaan ingin diam dan menikmati suasana saja yang mendominasiku. Jadi malam itu aku kalem dulu.
Aku banyak memikirkan tentang perjalanan panjang yang baru saja kulalui. Lelah di kaki, badan dan dingin yang membuat tulang-tulang nyeri. Tetapi entah kenapa, gunung ini, gunung pertama yang aku daki, seolah memberikan kekuatan baru bahwa aku tidak boleh tidak ke mana-mana.
Masih ada puluhan gunung lain di Indonesia yang bisa aku daki, ratusan gunung di dunia yang bisa aku impikan. Seperti dia yang sudah banyak mendaki gunung-gunung di dataran tinggi Eropa Utara. Aku pun juga ingin sampai di sana.
Satu kelebat pikiran yang dengan kurang ajarnya mampir ke otakku juga adalah aku ingin membuktikan pada dia bahwa aku bisa dijadikan partner untuk berkelana. Entah kapan ... kalau mungkin.
Mimpi terus kamu, Al!
Orangnya sekarang ke mana juga nggak tahu. Akhirnya malam itu aku lalui dengan memandangi bintang di atas langit, menyenangkan bisa melihat rasi Cygnus dan Scorpio dengan jelas.
Kalau sudah keasyikan melihat bintang begini, mau tak mau pikirkanku berkelana lagi. Yah, melankolinya seorang cewek yang sedang berada di tempat semagis gunung, pikirannya tak lepas dari khayalan indah.
Dalam hati aku ingin membawa dia ke sini dan menunjukkan semua keindahan yang aku lihat ini. Berkhayal masih gratis, kan?
Aku mengembuskan napas panjang lagi pada akhirnya. Dia yang tidak pernah jelas siapa, bahkan sampai sekarang, hanya menjadi provokator ulung yang seringkali menjadikan aku kerdil.
Sampai merasa terusik sendiri untuk menunjukkan kalau aku juga bisa pergi melakukan perjalanan.
Aku kan juga ingin memamerkan foto-foto di Gunung Gede ini. Memamerkan keindahan edelweis. Di Skotlandia atau Islandia emang ada?
Ingat itu orang yang dulu dengan semangat menceritakan tentang penemuan edelweis oleh Georg Carl Reinwardt di gunung ini. Katanya itu membuat dia penasaran dengan gunung ini.
Nih, aku udah berdiri di sini nih, eh orangnya menghilang entah ke mana. Aku kan juga mau pamer cantigi!
Heh! Bisa balik nggak sih? Ini udah mau setahun, lho. Enggak kangen debat bahas dark matter di konstelasi Eridanus lagi? Kan belum kelar itu! Atau bahas Iris Murdoch, John Khoury, Lawrence Rudnick atau siapapun nama aneh yang enggak aku tahu itu.
Kalau emang mau menghilang, seenggaknya ngucapin selamat tinggal apa susahnya? Lagi, aku cuma bisa mengeluh kalau sudah menyangkut dia. Dia yang membuatku akhirnya terdampar kuliah di Bogor.
Hanya dengan menceritakan betapa dia kagum dengan alam Indonesia yang hanya dilihatnya dari gambar atau dibacanya dari jurnal.
Cerita menggebu-gebunya tentang perjalanannya ke Brazil, lalu akhirnya kepalanya pop up ingin merasakan hutan di Zaire dan Indonesia suatu saat nanti. Mana ... mana? Kapan ke Indonesia? Keburu hutannya habis! Aku pernah bilang begitu.
Lalu, dia ceramah panjang lebar. Sebagai anak koservasi, aku harus bisa menjaga hutan tetap lestari. Buset! Dikira segampang itu?
Nyatanya, omongannya memang semanjur itu untukku. Bogor dan konservasi tidak pernah ada di otakku sebelumnya.
Sampai akhirnya dia datang dan membuat kita berdebat panjang. Katanya dia akan sangat senang melihat perpaduan hutan, Bogor dan hujan. Tapi di Indonesia enggak bisa lihat Aurora, enggak apa-apa emang? Tapi, hutan hujan primernya betulan indah kok. Aku berani jamin!
Semua ini sia-sia nggak sih? Selama ini aku kayak orang bego enggak sih penasaran segitunya sama orang itu? Aku takut kalau itu jadi toxic untuk diriku sendiri. Lagi pula dia juga udah sebegini lamanya enggak pernah muncul.
Dua dari sekian hal yang ingin aku lakukan di gunung ini yang pertama adalah membuktikan bahwa aku bisa pergi sejauh ini. Yang kedua, mungkin ini waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Lelah kalau setiap hari hanya dihadapkan pada harapan kosong. Kalau saja dari awal dia tidak harus merasa begitu perlu menyembunyikan identitasnya.
Tapi, ya sudahlah.
Dia juga bukan prioritas selama ini. Hanya orang yang aku syukuri keberadaannya karena banyak berguna untuk pendewasaanku. Begitu, kan? Daripada ini semakin enggak jelas ke mana arahnya dan aku semakin dimakan harapan, mungkin ini waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal dengan layak.

Haaaaaaaaaai! Apa kabar hampir sebulan menjalani tahun 2018? Hope you guyssss stayyyyy awesomeeeeeee XD
Nihhhhh ada yang baru nihhhhh wkwk
Asli sih aku sampai sekarang masih sangat amat surprise masih ada aja yang baca cerita ini, masih komentar, vote juga. Itu sangat-sangat membahagiakan dan membuat terharuuuuu. Terima kasih banyaaaak ya semuanyaaaaaa :) Nggak tahu, beneran nggak tahu harus bales gimana baik-baiknya kalian semuaaaaa huhuhu :3
Dannnnnnn... aku mau bikin pengumuman sesuatu huhuhu
.
.
.
Karena satu dan lain hal, terpaksa aku harus menghapus cerita ini per tanggal 28 Februari 2018. Maaf yaaaa :(
Semoga nanti kalau ketemu lagi dengan cerita ini, sudah dalam mode yang jauh lebih baik aamiin :)
Kalau ada yang mau posting tentang ini bolehhhhhh bangettttt lohhhh ehehehe jangan lupa mention aku di ig @nauraini atau @ceritanau yaaaa hehehehe thankyouuuuu semuanyaaaaa wufffffffff youuuu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top