Chapter 9
Arsad mengecek jam yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Kadatangan kereta yang dia tunggu tinggal lima menit lagi. Dia mengusahakan datang tepat waktu agar seseorang yang dia jemput tidak perlu menunggu lama.
Sebuah kereta merapat di peron. Seharusnya kereta yang itu. Dari tempatnya berdiri, Arsad memperhatikan awas pintu kereta yang mulai memuntahkan para penumpang. Matanya meneliti satu per satu. Saat pintu sudah lengang, dia akhirnya menemukan yang dia tunggu. Profilnya tidak berbeda jauh dari yang terakhir dia ingat.
Perempuan itu mengangkat sebelah tangan, melambai ringan, begitu menemukan Arsad di antara kesibukan stasiun. Langkahnya berubah tidak sabar, menggeret koper besar sedikit cepat, hanya agar sampai di depan Arsad dengan segera.
"Hai." Laras memberinya senyum yang masih sama dalam ingatan Arsad.
Arsad mengangguk seadanya, mengambil alih gagang koper. "Ngobrolnya di mobil aja. Takut kejebak macet."
Laras nyaris mengacak rambut Arsad seperti yang biasa dulu dia lakukan. Sadar kalau anak ini sudah memiliki istri sekarang, dia menahan gestur akrab. Tapi seperti melihat Arsad yang berbeda dengan versi yang pernah dia kenal, Arsad yang sekarang terlihat dewasa, matang dan semakin dingin—yang terakhir tidak berubah sejak dulu.
Ini kepindahan yang mendadak bagi Laras yang mutasi ke kantor di Jakarta. Yang terlintas pertama dalam benaknya adalah menghubungi Arsad. Dia iseng menelepon minggu lalu, mengabarkan tentang kepindahannya, juga mengirim pesan pagi tadi tentang jadwal kereta. Ternyata nomornya masih aktif dan anak ini menawarkan diri menjemputnya di stasiun.
Laras tahu kabar jika Arsad sudah menikah, dirinya pun diundang. Tapi hari itu bertepatan dengan pernikahan sang adik. Dia hanya mengucapkan selamat lewat pesan tapi mungkin karena sibuk Arsad tidak sempat membalasnya. Selebihnya, mereka jarang berkomunikasi atau nyaris tidak pernah sejak tiga tahun lalu.
Tiga tahun lalu, ketika Nadia meninggal, dia sering menghubungi anak ini. Sekadar untuk tahu kalau keadaannya.
"Gimana kabarnya, Ar?"
"Baik." Tanpa mengalihkan fokus dari jalanan di depan.
"Istri kamu nggak ikut?" Laras berpikir akan melihat istri Arsad ikut menjemput lalu dikenalkan padanya. Dia hanya melihatnya dari media sosial Tante Elma. Cantik dan tampak serasi berdiri di sebelah Arsad.
"Nanti aku kenalin ke istriku kalau waktunya tepat, Ras." Tanpa embel-embel 'Kak', dari dulu Arsad memanggilnya demikian meski sudah ditegur Mama dan kakak perempuannya.
Laras pun mengerti. Lebih baik memang tetap begitu, tidak banyak yang berubah dan cukup Nadia yang pergi lebih dulu meninggalkan mereka. Dia akan sedih kalau anak ini ikut-ikutan berubah banyak.
"Oke."
Arsad tidak mendengar Laras mencoba mengajaknya bicara lagi. Mereka mengenal sejak kecil karena Laras berteman baik dengan Nadia, menjadi temas kelas pula. Berteman sangat baik sampai wajah keduanya lama-lama terlihat mirip. Kepergian Nadia yang mendadak juga menjadi pukulan keras untuk Laras.
"Kamu kenal istrimu di mana, Ar? Bukan karena dijodohin Tante Elma, 'kan?" Dia hanya menggodanya. Arsad sulit dekat dengan perempuan, dulu banyak yang naksir tapi mereka kabur menghadapi sikap dingin anak ini. Perempuan yang sekarang menjadi istrinya pastilah seseorang yang kuat mentalnya, kokoh hatinya.
"Aku kenal sendiri kok." Hanya itu. Dia tidak berminat menjelaskan hubungan rumit antara dirinya dan Indira. Kalau iya, nanti-nanti saja. Tidak sekarang.
Laras baru menyadari jika di spion tengah terdapat gantungan berisi foto kecil yang dibingkai. Tangannya menangkap bingkai tersebut, melihat potret itu cukup lama. Arsad membiarkan dan menunggu komentar berikutnya.
"Istri kamu cantik."
Sudah dia duga akan mendengarnya. Banyak yang bilang begitu.
Tangannya melepas gantungan foto, berseloroh lagi. "Kok dia mau jadi istrimu sih? Dengan wajah secakep ini dia bisa dapet yang lebih dari kamu."
Arsad berdeham. Ceritanya panjang.
"Pasti kamu yang cinta banget ke dia, makanya kali ini beda kayak dulu. Istrimu nggak punya kesempatan buat kabur ya? Aku sama kakakmu selalu penasaran dari dulu, kayak apa kalau kamu udah serius sama perempuan."
Andai saja Laras tahu yang terjadi justru sebaliknya. Tapi lagi-lagi, Arsad merasa tidak perlu meluruskan apa pun sekarang.
Mereka sampai di sebuah kompleks, berhenti di salah satu rumah yang tampak asri dan memiliki pagar yang lebih rendah daripada rumah di kanan-kiri.
"Ini dulunya rumah Kakekku, Ar. Itu kenapa desainnya masih kuno di antara yang lain. Tapi semuanya masih bagus kok, masih layak huni banget. Ketimbang aku pusing nyari tempat lagi." Laras turun lebih dulu, menghampiri bagasi untuk mengambil koper sambil menjelaskan tanpa ditanya.
Arsad menyergah cepat, mengambil alih sepenuhnya urusan menurunkan koper besar itu.
"Kamu mau masuk dulu?"
Arsad menggeleng, menaruh koper di dekat pintu tapi juga tidak langsung pulang. Dia memilih duduk sebentar di kursi teras.
Laras urung membuka pintu, membiarkan kuncinya masih menggantung di tempatnya, menyusul duduk. Lampu teras dan lampu pagar sudah menyala karena rumah ini ada yang mengurus setiap harinya.
Teras itu sempat lengang. Laras bukan sengaja memesan khusus tiket pada tanggal ini. Dia baru teringat ketika di dalam kereta tadi kalau hari ini tidak seperti hari-hari lainnya di kalender hidup seorang Arsad.
Atau kalau anak ini masih ingat tanggal mamanya berpulang, atau papanya yang pergi entah ke mana, atau kepergian eyang putri dan kakungnya. Maka bertambah banyak tanggal kelam di hidup Arsad, yang mau tak mau harus dilalui.
Tapi hari ini, mungkin yang paling berat.
"Hari ini, ya?" Laras menoleh sejenak.
"Masih ingat?"
"Ingatlah." Yang pertama dia ingat adalah peristiwa sedihnya, tapi tetap saja dia harus mengucapkan sesuatu. "Selamat bertambah umur, Ar. Senang lihat kamu dalam keadaan baik dan sehat. Nadia pasti bangga lihat kamu yang sekarang, dia tenang adiknya nggak sendirian. Dia nggak penasaran lagi perempuan mana yang menemani adiknya."
Arsad hanya diam. Tidak menyergah, tidak juga bilang terima kasih. Tapi ada sedikit pias di wajahnya.
"Besok aku mau ketemu Nadia."
"Jam berapa? Aku bisa antar."
"Aku agak lupa daerahnya, kasih aja alamatnya. Biar aku ke sana sendiri."
"Tapi aku bisa antar."
Tatapan Laras turun, terhenti pada noda kecokelatan yang tidak sepenuhnya bisa diseka di celana hitam bagian lutut itu. "Kamu udah dari sana hari ini. Besok aku sendiri aja."
Arsad tidak memaksa.
"Kamu nggak sibuk?" Bukankah tetap harus ada perayaan kecil untuk anak ini? Tante Elma, atau mungkin istrinya, mungkin menyiapkan makan malam dan tentu saja kado?
"Nggak."
"Bukan sibuk kerjaan." Laras sedikit gemas. "Makan malam spesial, mungkin? Aku beneran nggak ganggu waktu kamu, 'kan?"
Justru Arsad butuh alasan untuk tidak datang ke makan malam itu. Dia mematikan ponsel setelah melihat ada panggilan masuk dari istri dan juga tantenya. Dia sudah bilang tidak akan datang, jadi bukan karena ingin menjemput Laras. Dia butuh ini untuk dijadikan alasan. Meski nanti dia juga tidak akan bilang ke Indira atau Tante Elma—tantenya itu mungkin sudah tahu dia menghilang ke mana.
Jadi, dia menggeleng. Laras seperti tidak percaya tapi memilih menyerah.
Tidak banyak percakapan lagi. Arsad pamit dan Laras mengantarnya hingga keluar gerbang. Tapi alih-alih membuka pintu, Arsad justru berbalik dan memeluk Laras.
Laras bisa merasakan kesedihan yang tertular begitu cepat. Arsad memang bukan lagi adik kecil yang dulu suka dia jaili karena terlalu kaku dan pelit senyum. Bukan anak kecil yang menyimpan banyak luka di balik diamnya demi terlihat tegar. Bukan anak serba-tanggung yang sulit memahami perasaannya sendiri.
Tapi Arsad tetaplah Arsad. Yang ketika sulit menahan kesedihan, hanya minta dipeluk. Nadia yang bilang ini. Ternyata benar.
Sebagai seseorang yang melihat semuanya, mengenal baik keluarga Arsad, Laras mau tak mau juga mengenal baik luka-luka yang selama ini hanya dibiarkan. Luka itu, sayangnya, masih membayangi punggung ini.
Laras balas memeluknya, layaknya seorang kakak ke adiknya. Pelukannya semakin erat. Sama seperti ketika dia memeluk Arsad saat ibunya meninggal. Pelukan yang ini terlambat dia beri tiga tahun lalu. Dia baru bisa datang seminggu kemudian, saat itu.
Arsad merasakan tenang dan nyaman yang lama hilang. Seolah dipeluk kakaknya sendiri, lalu diam-diam dia mengadu banyak hal.
Laras memberi tepukan-tepukan ringan di punggung kokoh itu. "Dunia ini nggak semenakutkan dulu, Ar. Kamu tetap punya orang-orang yang sayang kamu. Nggak ada yang ninggalin kamu lagi dengan cara menyakitkan."
Arsad tidak memercayainya. Tapi dia hanya diam dan terus memeluk. Sekarang mungkin tidak ada lagi orang itu. Orang yang Laras maksud. Orang yang ketika pergi, membuat dunianya ikut runtuh. Rasa-rasanya tidak ada lagi yang begitu.
Semua sedihnya, sakitnya, habis di Kak Nadia.
***
Masih terlalu pagi ketika Arsad terbangun. Belum ada cahaya yang menembus dari jendela yang persis menghadap timur. Dia berbalik, sedikit menyibak selimut bagian atas untuk menatap bahu yang bergerak teratur, menandakan jika seseorang di balik selimut masih bernapas dengan normal. Hal seperti ini yang pertama dia lakukan ketika membuka mata. Seperti kebiasaan Eyang kakung-nya dulu yang diam-diam dia ketahui.
Ternyata kebiasaan ini sudah dia lakukan sejak pertama Indira tidur di sebelahnya.
Takut kehilangan Indira? Dia hanya tidak suka orang pergi seenaknya dari hidupnya. Dia benci mendengar kabar buruk dan sebagainya.
Arsad kembali menaikkan selimut Indira, lalu beranjak duduk di tepian kasur. Meraih ponsel untuk mengirim pesan yang lupa dia kirim semalam. Sebuah alamat tempat pemakaman. Khawatir jika Laras mungkin nyasar, dia memberi petunjuk yang lebih mudah. Mengakhiri dengan pertanyaan yang sama seperti kemarin, apakah ingin ditemani.
Meletakkan ponsel kembali ke meja, Arsad mengambil benda lain dari laci paling bawah yang selalu dalam keadaan terkunci. Satu ponsel yang bagian layarnya retak di mana-mana tersimpan rapat di sana. Arsad jarang membukanya, hanya sesekali ketika dia teramat rindu dengan kakaknya sekaligus memastikan jika benda itu masih bisa berfungsi meski tidak sempurna.
Dengan membiarkan ponsel itu dalam keadaan utuh, sama seperti ditemukan ketika kakaknya kecelakaan, tanpa memperbaikinya, Arsad merasa dekat dengan kakaknya.
Menghubungkan dengan kabel charger, dia menunggu proses booting dan kemudian membuka aplikasi chat. Dia selalu melihat history pesan mereka. Membacanya dari atas sampai terakhir. Hari itu. Saat semua chat-nya tidak pernah sampai.
"Ar, kamu udah bangun?" Suara serak bertanya dari arah belakangnya.
"Hm." Arsad kembali ke halaman depan ponsel, menekan tombol off dengan tenang.
"Tapi ini masih pagi banget, tidur lagi yuk."
Arsad mengembalikan ponsel ke laci paling bawah, menguncinya dan menyimpan kunci di antara tumpukan benda di laci paling atas.
"Hari ini ke rumah Ibu lagi?"
Jawaban datang lebih lama tapi berupa pertanyaan. "Kamu ngelarang aku ke sana?"
Mana pernah Arsad melarang-larang. Dia membebaskan istrinya mau ke mana pun, jam berapa pun. Terserah. Kecuali dua tempat. Lapas dan rumah Ibu. Setidaknya izin dengannya terlebih dulu.
Dua tempat itu hanya membuat Indira banyak terdiam dan pulang dalam keadaan sedih. Di rumah ini cukup dirinya saja yang beku. Indira tidak perlu menambahi kesuraman yang lain.
"Ar, aku mimpi buruk."
Arsad menoleh tanpa membalik badan. Indira masih memejamkan mata, hanya bibirnya yang bergerak. Seperti meracau. Refleks dia menempelkan punggung tangan di kening istrinya.
Disingkirkan pelan. "Nggak, nggak. Aku nggak demam. Tapi kayaknya aku ketindihan. Mau teriak nggak bisa."
"Untuk orang yang tidurnya kayak orang koma, bisa ketindihan?"
Indira benar-benar tenang ketika tertidur, bahkan dengkuran halusnya tidak terdengar, jadi wajar kalau Arsad sering memastikan istrinya itu masih bernapas atau tidak. Hanya gempa bumi, angin ribut dan suara klakson yang bisa membangunkan Indira.
Benaknya sesaat melayang ke satu hari di tiga tahun lalu, di sebuah halte bus, saat dia menemukan Indira tertidur karena kelelahan. Malam itu dia belum tahu jika takdirnya dengan perempuan ini akan terus berlanjut.
"Aku mimpi buruk," ulangnya.
"Kamu lari-larian di padang bunga tandus?" Dia lihat obat sakit kepala yang diminum Indira tadi malam, ini entah racauan karena lelah atau efek obat.
"Itu kan tahun lalu."
Siapa tahu mimpi yang sama. Bagi seseorang penyuka bunga, sekaligus penjual, itu mimpi buruk sekali.
Arsad menunggu lanjutan tapi cukup lama hanya suara denging pendingin ruangan. Saat dia ingin bangkit dari tepian kasur, ujung piamanya tiba-tiba ditarik.
Masih terdengar seperti igauan. "Aku selalu bergantung ke kamu. Kapan-kapan, sekali aja lakukan yang sama. Biar aku sedikit berguna buat kamu. Jangan jauh-jauh."
Arsad membiarkan tangan itu masih di ujung piamanya meskipun dia tidak jadi beranjak. "Mimpi buruk kayak apa?"
"Buruk."
"Yang gimana?"
"Aku lihat kamu nangis ... sendirian."
Indira tidak—atau belum—pernah melihatnya menangis. Mengada-ada saja mimpinya. "Di mana?"
"Kayak di tempat yang belum pernah aku datangi. Aku udah sekuat tenaga lari ... tapi aku nggak pernah bisa sampai ke kamu."
Dia salah sudah menanggapi sejak awal. "Terus?"
"Seseorang tiba lebih dulu ... kakiku luka ... masih bisa buat jalan tapi."
"Kamu berhenti?"
"Enggak. Aku terus jalan." Ada jeda beberapa lama. "Tapi kamu udah nggak terlihat. Harusnya aku tetap lari. Ar ... kamu ke mana?"
Bibir Arsad terkatup rapat sekarang. Ujung piamanya tidak lagi digenggam. Kali ini Indira benar-benar kembali tertidur setelah menceritakan sepotong mimpi yang katanya buruk.
Sepotong mimpi yang barangkali menjadi nyata suatu hari. Atau tidak. Siapa yang tahu.
***
Ada yg udah baca di sebelah? Makasiih banyak yaa😘
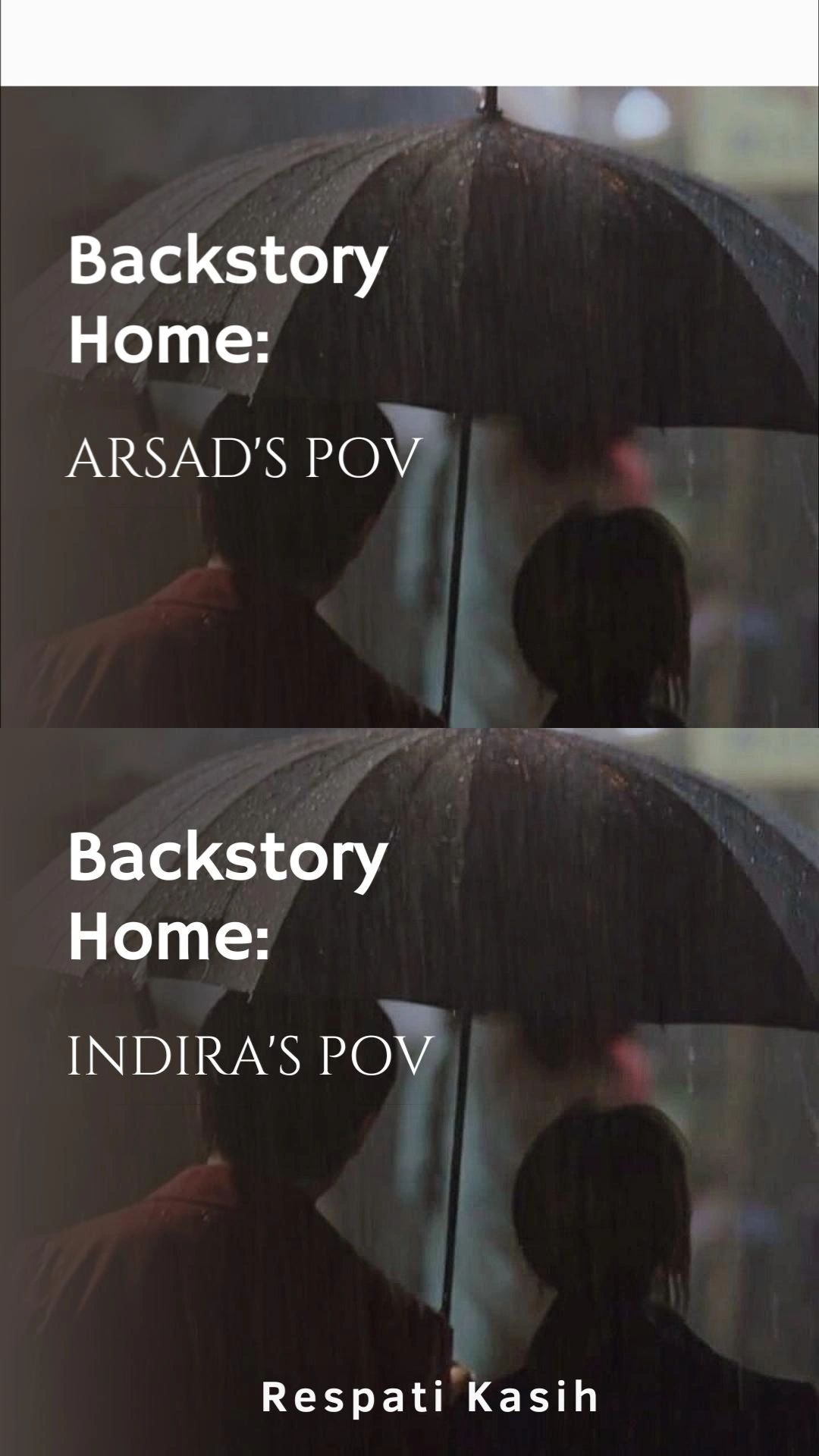
Next chapter insyaAllah Minggu yaa. See youu!🐣
Kamis/10.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top