Chapter 11
Entah hanya perasaannya saja atau bagaimana, tantenya semakin menyayangi Indira ketimbang dirinya. Tidak tahu kapan persisnya Indira bisa mengambil hati tantenya sebanyak ini. Lebih banyak dari yang sempat dia kira.
Indira baik. Ya baik seperti orang pada umumnya. Tidak tahu kenapa jadi terlalu spesial begini untuk tantenya.
"Nggak tidur di kamarmu sendiri?" Om Tama lewat di ruang tengah, ada Arsad yang berbaring di sofa, mengganti channel TV tanpa berminat menonton salah satu.
Dia di sini juga bukan tanpa alasan. "Om nggak kehilangan istri?"
Om Tama tertawa, mampir sebentar. "Sudah, ikhlas saja kalau istrimu dimonopoli, Ar. Tantemu dulu pengin sekali anak perempuan, sudah kesampaian sekarang. Dia ketemu sama yang mirip dirinya."
Tantenya punya banyak anak perempuan sejak beberapa tahun terakhir menjadi donatur tetap sebuah panti asuhan. Dia mengira kalau salah satu atau dua anak dari panti akan dibawa ke rumah ini, ternyata tidak. Mungkin ada pertimbangan lain atau karena sudah ada Indira—bagi tantenya sudah cukup.
Om Tama berlalu ke kamar. Arsad akhirnya mematikan TV yang sebenarnya tidak minat dia tonton.
Arsad bangkit. Menuju ke kamar lamanya. Membuka pintu hati-hati, berbeda dengan dugaannya, justru Indira yang masih terjaga. Istrinya menepuk-nepuk lembut selimut di bagian lengan Tante Elma. Bergumam seperti menyanyikan lagu yang Arsad tidak tahu judulnya. Berbeda saat bersamanya, Indira selalu lebih dulu terlelap. Tidak adil.
Dia masih bergeming, mengintip dari celah pintu, sengaja sampai Indira menyadari keberadaannya.
"Kamu nggak tidur?" Indira bertanya lirih.
Tatapan Arsad membalas, emang aku bisa?
Masih tanpa suara, hanya gerakan bibir tapi Arsad bisa menangkapnya. "Mau ditemenin?"
Kali ini dibalas gerakan alis. Tidak peduli akan diartikan bagaimana. Biar saja dipikir sendiri.
"Sebentar lagi. Kamu tunggu."
Arsad menutup pintu. Kembali ke sofa ruang tengah. Tunggu, katanya. Tidak akan dia tunggu. Dia bisa tidur sendiri tanpa perempuan itu.
Dia malas ke kamar tamu meski tempatnya selalu dibersihkan. Jadi coba memejamkan mata di sofa yang cukup lebar. Menyugesti diri agar cepat masuk ke alam mimpi. Tapi yang terjadi setiap beberapa menit matanya terbuka, telinganya pun menajam.
Belum ada langkah mendekat.
Mana yang bilang sebentar?
Berbalik dan menyembunyikan wajah di punggung sofa, Arsad mengulang niatnya untuk tidur. Tak lama tubuhnya yang tidak menggunakan selimut tiba-tiba terhalang dari dinginnya AC. Hanya hitungan detik, ada bantal yang mendarat di dadanya, diikuti dengan sebuah beban. Barulah dia sadar kalau tubuhnya kini sedikit melesak dan terhimpit karena Indira seenaknya berbaring di atasnya.
Ini sudah malam, bukan saatnya main-main begini.
Bantal tersebut bergeser naik, ke arah muka. Arsad cuma bisa pasrah kalau Indira sedang mode anak kecil. Dia juga tidak bergerak karena tidak tahu persis berapa sisa tepian sofa yang mereka tempati berdua. Satu gerakan kecil bisa membuat Indira terpental ke lantai.
Sebelum dia sulit bernapas, bantal sudah enyah dari mukanya. Pemandangannya bukan lagi gelap kosong, berganti puncak kepala Indira. Tangan kirinya yang tertindih pinggang istrinya, bisa lolos dan melingkar di punggung itu. Agar tidak meleset dari sofa.
"Kamu nyanyi apa tadi?"
"Mau denger?"
"Ngga—"
"Coba dengerin. Suaraku lumayan, nggak buruk-buruk amat."
Arsad menaruh telapak tangan di mata istrinya, menyuruhnya tidur saja.
Indira tidak menerima penolakan, menyingkirkan tangan dari matanya. Berdeham dua kali. "Riuh rasa diembannya ... melewati hari. Menyeruak ... mengumbar wewangi."
Arsad membiarkan. Bagi istrinya larangan adalah perintah.
"Menuruti rindu yang tiada habis. Mewangi. Mewangi."
Ingin menyela tapi dia memilih memejamkan mata saja.
"Ke mana kau menuju anakku. Kalah atau menang kita kan jadi arang dan abu."
Satu tarikan napas berat ikut Arsad rasakan.
"Arang dan abu ... arang dan abu."
Senandung diulang dari lirik awal disertai tepukan ringan di lengan Arsad. Persis yang didapat tantenya tadi. Arsad seakan merasakan kembali timang-timang dari tangan yang familier. Sudah lama, lama sekali, tapi dia masih mengenalinya. Tidak jauh berbeda.
Tidak seharusnya Indira tumbuh seperti ini, 'kan? Tepukan ringan dari tangannya tidak boleh sehangat ini. Debar jantung miliknya tidak boleh setenang ini. Dan suaranya, suaranya tidak boleh sehanyut ini. Jika dia berasal dari kotak kaca yang penuh retakan.
Tante Elma pernah memperingatkan. Sejak jauh hari, sejak awal. "Kamu salah orang, Ar. Indira nggak tahu apa-apa soal Nadia, terlihat sekali dari matanya. Dia tidak mengenali kita. Dia terlihat baik, apa kamu tega?"
Beberapa saat, siapa yang dininabobo, siapa yang tertidur. Arsad menatap langit-langit ruang tengah yang senyap. Matanya yang mulai kebas akibat cahaya lampu, memejam tapi tetap terjaga. Sebelah tangannya tidak bergeser dari punggung Indira.
Anehnya, tidak ada satu pun yang datang ke pikirannya. Kenangan baik, kenangan buruk. Atau gemuruh apa pun. Hanya tenang.
Dia memundurkan sedikit kepala demi memandangi mata yang terpejam satu jengkal darinya. Cukup lama. Lama sekali.
Bibirnya terbuka, bertanya sunyi. "Kenapa kamu harus tumbuh di keluarga itu? Kenapa nggak pergi?"
***
Indira mencari Arsad yang tidak terlihat di mana pun. Dan dia terbangun di kamar, di sebelah Tante Elma, bukannya di sofa bersama Arsad.
Semua penghuni rumah masih tidur. Jadi dia mencari diam-diam ke lantai dua, kosong, kemudian turun lagi. Dapur dan halaman belakang tidak ketinggalan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan lelaki itu.
Saat dia mengintip dari gorden depan, mobil Arsad tidak ada di halaman. Sambil merapatkan kardigan, dia membuka pintu, lalu berjalan ke pos satpam. Melewati halaman yang luas. Dingin masih menusuk tulang dan ke mana pula suaminya pergi pagi-pagi begini.
Tidak cukup pernah menghilang siang dan malam, sekarang malah pagi buta pula. Dia menikahi orang dewasa yang masih tantrum atau bagaimana.
"Pak Budi, lihat Arsad ke mana nggak ya?"
"Mas Ar nggak bilang? Sudah dua jam yang lalu, Mbak, sebelum azan Subuh. Saya sempat tanya, tapi cuma dijawab keluar sebentar."
Indira mengusap dahi. Berterima kasih, berbalik dan mengeluarkan ponsel dari saku kardigan. Dia menelepon, terus mengulangi, bertekad tidak akan berhenti sampai diangkat.
Sampai kemudian, sebelum dia mencapai teras, suara deru mesin terdengar dari arah gerbang. Indira mendesah lega, mematikan panggilan dan menepi. Seperti seorang ibu yang melihat anaknya keluar pagi-pagi tanpa izin, dia pun berkacak pinggang.
"Ngapain kamu di luar?"
Sekali, sekali saja, Indira ingin lihat raut penyesalan atau rasa bersalah dari Arsad. Tapi agak sulit. Bukan agak lagi, sudah sangat. Lelaki ini cukup santai bertanya kenapa istrinya bisa di luar.
"Bangun-bangun aku kehilangan induk."
"Kamu bukan ayam, bebek dan sejenisnya."
Indira mengekor di belakang suaminya. Menggumam. "Iya, nggak mungkin, sementara kamu kura-kura."
Tanpa berbalik, membuka pintu utama. Ternyata dengar. "Kamu ngatain aku kura-kura?"
"Tempurungnya."
"Kalian dari mana?" Elma yang baru bangun, membuka pintu kamar Arsad yang dia tempati semalam dengan bingung. Keponakannya tampak rapi memakai jaket dan topi. Seperti habis pergi dari luar.
"Habis keluar, Tan."
"Nyari sarapan?" Tapi melihat tangan keponakannya yang kosong, dia jadi ragu. "Atau ke mana?"
Indira tidak bisa membantu. Dia juga penasaran ke mana Arsad pergi, atau mesti dia katakan menghilang jilid sekian.
"Aku habis jalan-jalan."
Elma menggeser tatapan ke belakang Arsad, bertanya lewat mata, dan Indira memberinya sebuah gelengan.
Arsad menyela sebelum terjebak. "Ini masih kamarku kan, Tan?"
"Eh? Tentu, tentu." Elma menyingkir dari depan pintu, membiarkan Arsad lewat dan masuk ke kamar.
Indira menyusul ke kamar. Tapi Arsad benar-benar menghindar. Lelaki itu masuk ke kamar mandi. Terlihat buru-buru padahal ini masih cukup pagi.
Selagi menunggu, Indira merapikan tempat tidur, menyibak gorden lalu menyiapkan baju kerja Arsad yang beberapa masih tertinggal di lemari, tidak ikut dibawa pindah. Menaruhnya di atas kasur. Kemudian suara getar ponsel membuatnya menoleh, mencari sumber suara.
Jaket yang tersampir di kursi. Indira merogoh bagian saku, siapa tahu penting. Dia tidak akan mengangkatnya, hanya ingin lihat siapa yang—
Laras is calling ....
Oh. Laras.
Siapa Laras?
Indira coba mengingat-ingat. Laras, Laras, Laras. Di mana sekiranya dia bisa menemukan nama itu. Apakah salah satu staf Arsad? Rekan kerjanya dari divisi lain? Klien? Kerabat jauh? Atau siapa? Dia mengingat lagi apakah nama itu pernah dia dengar.
Ponsel di tangannya masih bergetar. Indira mengerjap, terkejut, saat sebuah tangan merebut kasar ponsel dari tangannya. Persis seperti kejadian tempo hari. Ketika dia membuka dompet Arsad tanpa izin.
Getar itu berhenti. Arsad menolak panggilan. Tanpa bicara apa-apa, menyingkirkan ponselnya dari jangkauan istrinya.
Justru reaksi Arsad yang begini yang membuatnya tidak hanya penasaran, tapi juga bingung.
"Siapa Laras?"
"......"
"Ar? Siapa dia?"
"Temen."
"Aku nggak tahu kamu punya temen perempuan."
"Nggak semuanya mesti kamu tahu, 'kan?"
Ah, kalimat itu lagi. Indira marah mendengarnya tapi dia tidak bisa sekali saja melampiaskannya. Masih bisa dia tahan untuk saat ini. Untuk apa dia tahan? Dia tidak tahu. Dia jarang marah jadi dia tidak tahu sejauh mana dia bisa meledak. Dia tidak mau melukai orang-orang yang dia sayangi, karena dia juga punya luka.
"Dan barusan, kamu habis menemui dia?"
Arsad sempat diam. Lalu tanpa menatap mata istrinya, dia mengangguk. Mengiakan.
***
Bisa dibilang ini extended versionnya dari Chapter 1 yaa:
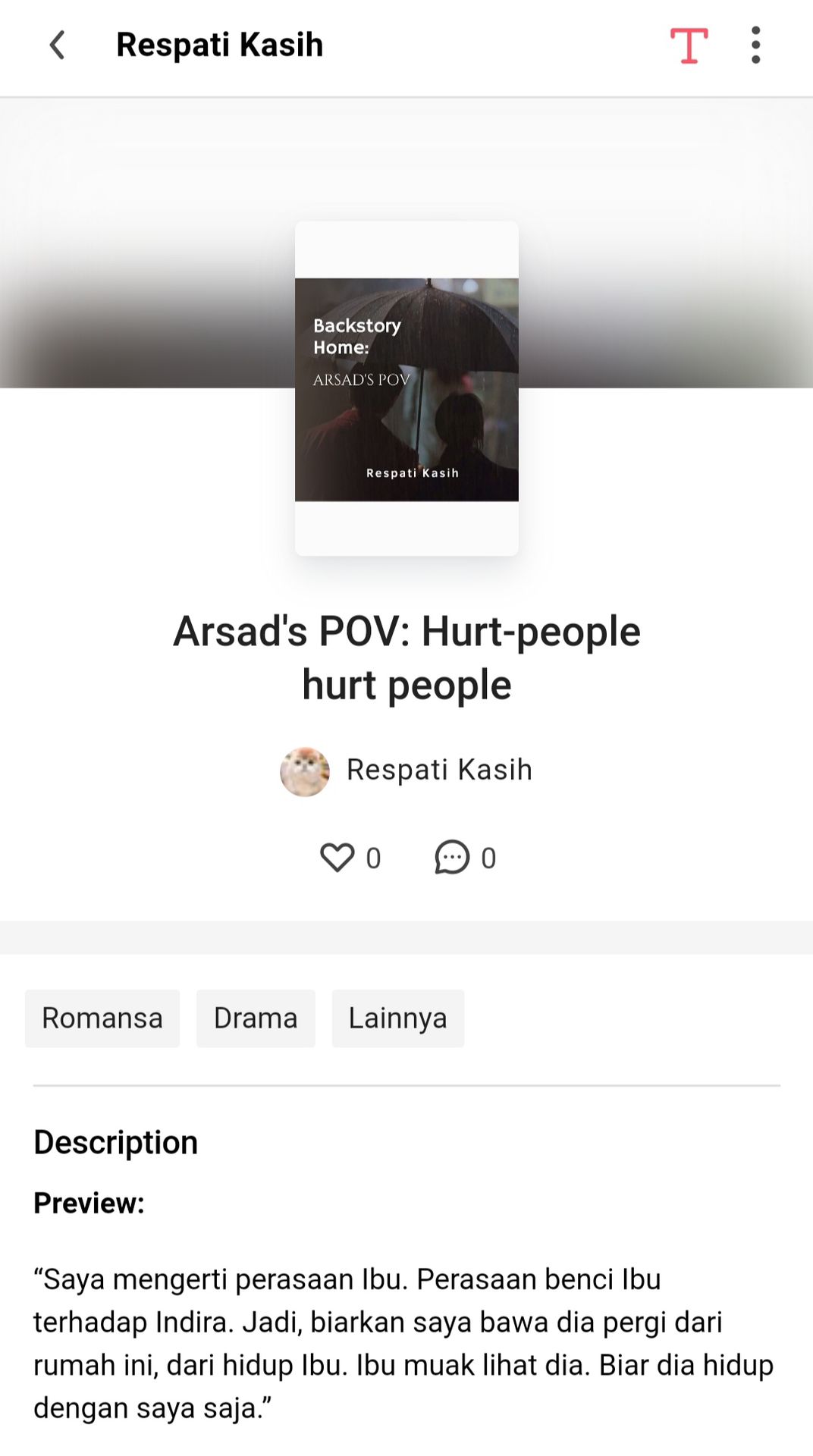
Hanya tersedia di Karyakarsa🙌
Makasih yaa. Ketemu lagi kapan enaknya? Minggu? Senin? 🐣
Kamis/17.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top