XIV - Gelap
Saat malam semakin dekat, perasaan ini semakin kosong.
Kegelapan mulai menyelimutiku.
Dan aku terus jatuh seperti ini.
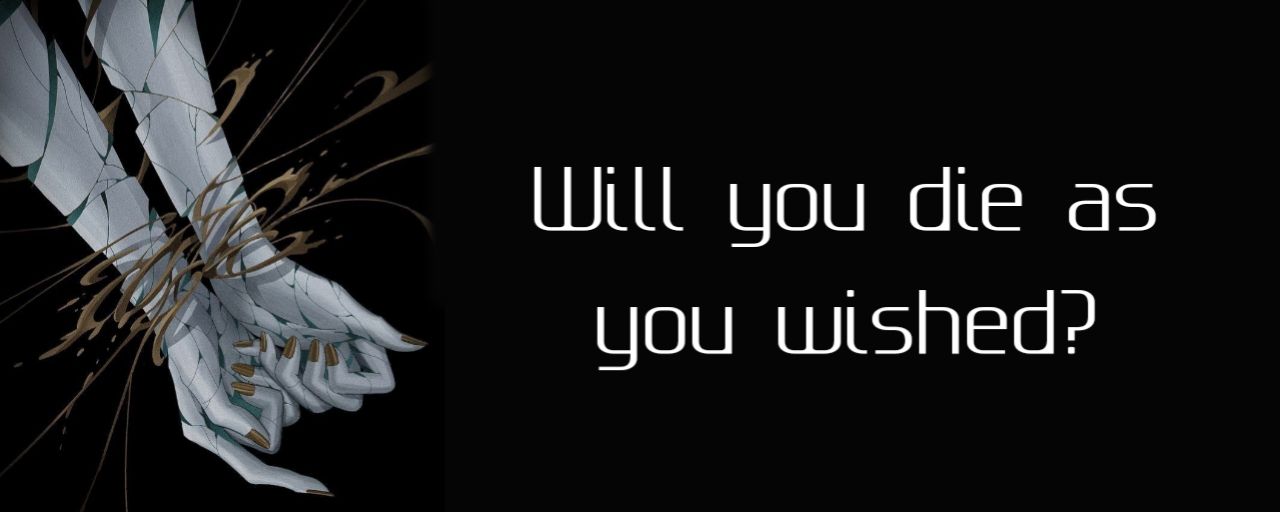
Sedari awal, datang ke sini adalah keputusan yang buruk.
Kampus di malam hari terasa sangat berbeda. Seakan kami sedang berada di dunia lain. Sunyi dan gelap. Banyak tempat persembunyian bagi para penghuni malam.
Tidak ada seorang pun yang terlihat di gedung fakultas Biologi pada malam hari. Hanya ada aku dan Eria, berdua di pinggir jalan, menunggu satpam yang berjanji menemani kami untuk mencari dompet Eria yang tertinggal. Jejak cahaya lampu kendaraan berlalu-lalalng di hadapan kami. Bayangan kuning, kela-kelip cahaya merah lampu rem, serta warna putih lampu depan yang menembus bayangan gedung-gedung. Pantulan lampu-lampu jalanan mengalir bagaikan air di atas kaca mobil yang sedang melaju.
Gedung Fakultas Biologi berada di deretan belakang kampus, memiliki empat lantai memanjang ke belakang. Di lantai satu ada lobi dengan barisan ruangan para petinggi, lantai dua ditempati para dosen, lantai tiga ruang kuliah, dan lantai lima dihuni berbagai jenis laboratorium.
Selain itu ada kafe di pekarangan fakultas yang sering direpotkan dengan banyaknya mahasiswa yang ingin menongkrong untuk sekadar mendapatkan jaringan internet gratis. Namun hiruk-pikuk itu tak bersisa di malam hari. Kursi-kursi yang kosong terasa mengerikan di bawah pohon beringin yang lebat.
Satpam yang dihubungi oleh Eria datang menghampiri kami dari seberang jalan. Baju dinasnya masih rapi tanpa kusutan dengan sepatu boots yang mengkilap. Namun wajahnya tidak selaras dengan penampilannya. Ada butiran keringat sebesar biji jagung di keningnya.
"Maaf, mungkin saya tidak bisa menemani Anda berdua di dalam. Sepertinya saya salah makan tadi sore. Jadi, saya akan menunggu di pos keamanan. Kalau ada apa-apa, silakan segera menelepon saya," jelasnya dengan nada suara bersalah.
"Beneran, Pak? Bapak percaya kami masuk begitu saja?" tanya Eria khawatir.
"Iya, saya percaya. Kalau pun ada barang yang hilang atau rusak, saya pasti akan mendatangi Anda berdua. Tapi semoga tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu, saya permisi dulu." Satpam itu meninggalkan kami tanpa menoleh sedikit pun.
Eria menunjukkan ekspresi sebal. "Bisa-bisanya dia malah lebih peduli dengan barang dibandingkan keselamatan kita berdua. Kalau kita yang kenapa-kenapa, dia mau tanggung jawab?"
"Sudah, sudah, Eria. Toh kita cuman masuk sebentar. Mengambil dompetmu yang tertinggal di ruangan Pak Alvi. Oh ya, kamu sudah menghubungi Bapak, kan?"
"Sudah, tapi ... cuman centang satu. Aku mencoba meneleponnya tapi tidak tersambung."
Aku mengerutkan kening sembari melipat kedua tangan di dada. "Eria ... kamu beneran mau masuk? Sekarang? Tanpa seizin yang punya ruangan?"
"Habis ... kalau tidak diambil sekarang, aku bakalan kepikiran sepanjang malam. Besok ada rapat, loh. Aku tidak mau terlihat menguap terus di depan para senior. Nanti aku bisa kena batunya."
"Oke, kita cuman ke sana saja. Selesai itu langsung pulang."
Eria memainkan helaian rambutnya yang lolos dari ikat rambutnya. Dia melirikku dengan tatapan memelas. "Sekalian ke ruangan juga. Aku lupa ambil berkas yang harus dibawa ke rektorat nanti pagi."
Aku menghela napas panjang. Apa boleh buat, jika tidak diselesaikan urusannya, bisa-bisa Eria akan merusak suasana hati para petinggi. Itu berarti masalah juga untuk diriku.
"Kita ke ruang dosen dulu. Habis itu ke ruang Pak Alvi. Setuju?" tawarku.
"Setuju!"
Alasan kenapa aku memilih naik ke lantai dua dulu sebelum menyusuri ruangan Pak Alvi bukan tanpa alasan. Elevator berada di tengah lobi dan ruangan dosen tidak jauh dari situ. Berbeda dengan kantor Pak Alvi yang berada di ujung sayap kiri gedung. Itu berarti kami akan berjalan di lorong panjang yang cukup jauh. Masuk akal kalau kita akan memilih jalan termudah dulu dan menyisakan yang sulit di bagian akhir.
Skenario terburuk, misal kami bertemu dengan sesuatu yang berbahaya, kami bisa segera keluar tanpa mengalami penyesalan karena ada urusan yang belum kelar.
Saat ini aku sedang berada di elevator, menuju lantai dua, tempat kerjaku dan Eria. Keluar dari elevator dan berjalan ke arah kanan beberapa langkah, aku berdiri di depan sebuah pintu kantor dengan plang di atasnya: Ruang Dosen, tertulis di sana dengan guratan sederhanan.
"Rin, aku boleh tanya, tidak?" Eria memulai pembicaraan setelah kami membisu di sepanjang jalan.
Aku yang sibuk mencari kunci untuk pintu menjawab tanpa menatap Eria, "Boleh, apa itu?"
"Kamu benar-benar tidak punya perasaan untuk Pak Alvi?"
"Nanti akan kujelaskan lebih lanjut. Kita selesaikan dulu urusan di sini." Secara kasual aku menolak membicarakan topk itu lebih lanjut.
Tentu saja ada alasannya kenapa aku menolak. Aku memang berencana membahas masalah ini dengan Eria. Oleh sebab itu, untuk menyampaikan segala curahan hati dan kegundahanku mengenai masalah tersebut kepadanya membutuhkan waktu yang tepat.
"Baiklah ...." Eria berjalan pelan mengikuti di belakangku yang berhasil membuka pintu dengan langkah sempoyongan.
Kami berdua melanjutkan penyusuran di tengah ruangan bercahaya remang-remang. Embusan angin membuat banguanan ini berderik. Suara air yang menetes terdengar dari kejauhan. Jangankan rumah penduduk, gedung fakultas lain berdiri berjauhan dari gedung ini. Yang ada hanyalah hamparan hutan dan lereng bukit, di mana pepohonan hitam meraung-raung diterpa angin kencang.
"Tunggu di sini, aku ambil barangnya secepat mungkin." Eria berlari kecil-kecil menuju meja kerjanya sedangkan aku mengawasi tidak jauh dari pintu keluar.
"Dapat! Selanjutnya, ke ruangan Pak Alvi!"
"Eria ternyata orang yang setimental, ya." Aku menyunggingkan seutas senyum kering sambil setengah mendesah.
"Aku tidak pernah menganggap diriku sentimental. Aku bahkan tidak paham apa itu yang disebut dengan sentimen," balas Eria tanpa beban.
Setelah turun dengan menggunakan elevator yang sama, kami melanjutkan perjalanan ke bagian sayap kiri gedung. Baru saja meninggalkan lobi, tiba-tiba seluruh lampu padam.
Jantungku melompat ketika Eria spontan berteriak tepat di depanku. Dia berbalik menghadapku, masih dengan mulut terbuka.
"Tidaaakkk! Kenapa harus mati lampu segala, sih!" omel Eria yang disertai tangisan kecil.
"Mungkin sekringnya lagi turun, lihat, tempat yang lain masih menyala." Aku menunjuk luar jendela di mana berkas cahaya dari bangunan yang lain terang benderang.
"Bisa jadi ... argh! Ayo, kita harus ambil dompet dan langsung pulang dari sini."
Sementara Eria menyalakan senter darurat dari ponselnya, aku mengecek jam tanganku.
Jam sembilan lewat lima belas.
Masih sepertiga malam awal, tapi terasa seperti sudah berjam-jam kami berada di sini.
Aku juga ingin cepat pulang.
Sejauh mata memandang, baik di depan maupun belakang, semuanya gelap total. Tidak ada yang terlihat. Hanya terdengar suara angin yang menyusup melalui celah-celah bangunan bagaikan tangisan seorang wanita.
Rasanya seperti sedag berenang dalam kegeglapan. Apabila senter menerangi jalan di depan, maka kegelapan itu akan menenggelamkan kaki. Apabila menerangi langkah kami, maka kegelapan itu akan menutupi jalan di hadapan kami. Dengan waswas kami terus berjalan.
Dalam kesunyian yang menyesakkan itu, aku sempat menoleh ke jendela di sisi kanan, melihat pekarangan di mana kafe fakultas berada. Dalam sekejap, aku menyadari ada sesuatu yang lewat di jendela. Ada sesuatu yang terjatuh dari atas. Bayangan yang besar, lebih besar dari hewan pengerat yang berkeliaran sepanjang malam.
Saat aku menyadari bahwa sosok tadi memiliki rambut panjang yang lebat, sontak aku berteriak keras dan membuat kaget Eria yang berada di sisiku.
"A-ada apa, Rinda?! Jangan bikin kaget!" ucap Eria jengkel. Dia menghampiri diriku yang terduduk dan menggigil hebat di atas lantai.
"Eri! Eri lihat tadi, kan?! Di-di-di luar ... ada orang di luar!" Jari-jariku bergetar sangat hebat, mencoba menunjuk lurus ke jendela meski sulit kulakukan.
"Luar?" Eria melangkah mendekati jendela. Ketika dia menjulurkan kepala keluar, wanita itu langsung berteriak keras. "Pa-panggil ambulans! Ada orang jatuh dari atas--"
Ucapan Eria terpotong sebab sosok yang berjatuhan itu ... kembali turun. Bukan satu, dua, atau tiga ... tapi ada lima. Mereka menjatuhkan diri dengan kepala terlebih dahulu. Sedetik kemudian suara teriakan histeris menggemparkan seiisi bangunan. Keadaan tidak bisa dikendalikan.
Aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan aku pun tidak mau mengingatnya sama sekali.
Wajah mengerikan itu.
Mulut yang menganga lebar.
Seperti mereka sudah mati sebelum membentur tanah. Mata kelam seperti mata ikan yang kehilangan cahaya kehidupannya. Jiwa mereka sudah lama menghilang, sebelum raganya hancur sepenuhnya.

Seremnya udah dapat?
Atau masih kurang horornya?
Masukkan dari kalian amat berarti untuk naskah ini untuk bisa lebih baik lagi. Ayooo, para silent reader, ayok gerakan jari kalian untuk komen di sini!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top