Epilog

Gangwon-do, Korea Selatan.
Hari Halloween, 2024.
Bunyi kereta yang melaju dan bisik-bisik penumpang lain merecoki remaja laki-laki itu.
Keningnya berkerut. Keretanya terlalu berisik. Orang-orangnya terlalu ramai. Seseorang kiranya perlu memberitahunya bahwa dia tak bisa menggunakan kereta pada jam pulang kantor dan berharap mendapat tidur yang tenang.
Bukan berarti dia benar-benar tidur.
Remaja itu menguap, mengganggu percakapan seru seorang Cleopatra dan Gumiho di sebelah kanannya—atau sesungguhnya, dua remaja perempuan yang berpakaian seperti Cleopatra dan Gumiho. Meski, kalau boleh jujur, dia sama terganggunya; salah satu ekor si Gumiho menusuk pinggangnya. "Maaf," kata remaja itu, mengantisipasi masalah.
Si Gumiho menatapnya dari atas ke bawah, menilainya dari skala satu sampai sepuluh apakah layak atau tidak si remaja ditanggapi. Lalu tersenyum. Dari standar gadis mana pun, remaja itu akan selalu mencetak skor bagus. "Oh, tak apa. Tidak merayakan Halloween ... Wonbin?"
Remaja itu melirik guitar case yang berada di antara kakinya. Di sudut kiri bagian atas, terdapat coretan dari spidol merah yang membentuk seni Doodle dan tulisan, 'CUMA PUNYA WONBIN!!!' yang berasal dari jari-jemari anak-anak. "Karya sepupuku," jelasnya. "Dan tidak. Aku lupa meninggalkan taring vampirku di rumah." Dia balas tersenyum, menunjukkan sederet gigi putih rapi dengan gigi taring yang biasa.
Kedua gadis itu cekikikan. Sedangkan seorang pemuda yang duduk di depan mereka mendengus. Pemuda yang juga tidak merayakan Halloween.
Wonbin menatapnya. Dua pasang mata kecokelatan mereka beradu pandang. Pemuda itu barangkali satu-dua tahun lebih tua darinya, dan kebetulan lebih berisi. Namun sementara Wonbin punya rambut bob sebahu yang menutupi telinganya, pemuda itu berambut pendek ala tentara. Kemejanya yang tipis tidak cocok dengan udara dingin—tak heran kulitnya memucat.
Pintu kereta terbuka. Suara kondektur mengumumkan sampai di stasiun mana mereka, dan tolong, bagi penumpang yang terhormat, agar memeriksa barang bawaan mereka. Semoga perjalanan Anda menyenangkan!
Pemuda itu bangkit sebelum kondektur selesai bicara, dan menerobos di tengah seorang wanita dan pria pekerja kantoran supaya menjadi yang pertama keluar. Kedua orang itu kompak mengumpatinya. Pemuda itu tidak menggubris.
Wonbin ikut bangkit, dan memanggul guitar case-nya. "Nona-nona"—dia menepuk topi imajiner di dahinya—"Semoga kalian tidak bertemu monster sungguhan. Selamat hari Halloween!"
Malam itu stasiun ramai. Acara yang diadakan di pusat kota bisa disalahkan. Wonbin meliuk-liuk di antara puluhan monster palsu—sendirian, menentang arus. Beberapa dari mereka mengenakan kostum dari mitos-mitos tradisional seperti Dokkaebi dan Imoogi. Tapi kebanyakan lebih memilih budaya barat atau karakter dari film-film terkenal.
Wonbin kesulitan menahan tawa. Mudah membayangkan ayahnya bersungut-sungut seandainya berada di sini bersamanya. Sang ayah selalu menganggap perayaan Halloween itu "meremehkan".
Sepuluh langkah dari Wonbin, tukang mendengus menuai lebih banyak protes akibat cara berjalannya yang serampangan. Wonbin mengamati bagaimana pemuda itu mengambil jalan pintas ke gang-gang sempit yang jauh dari keramaian. Kegelapan tidak menjadi musuhnya—pemuda itu justru berbaur di dalamnya.
Akhirnya, perjalanan itu berakhir. Tukang mendengus berhenti di sebuah rumah sederhana di daerah sepi dan masuk.
Wonbin mengeluarkan ponselnya. Dia memotret rumah itu dan mengirimkannya ke group chat beranggotakan dirinya, kontak bernama 'si tukang ngorok Yushin' dan kontak lain bernama 'si tukang makan Naevi' disertai alamat dan pesan lain yang lebih menyerupai ancaman.
Asal tahu saja, kalau aku mati, aku akan menghantui kalian.
Sempurna.
Kirim.
Sejenak, dia melirik ke belakang. Apa ada yang membuntutinya? Apa dia gagal mengendap-endap? Wonbin mengangkat bahu. Dari dekat, dia memperhatikan rumah yang seperti benteng itu. Seluruh jendelanya tertutup rapat, dilengkapi terali besi. Tidak ada balkon. Pintu depan kemungkinan satu-satunya akses masuk dan keluar. Tidak ada bel juga. Jadi Wonbin mengetuk—agak terlalu keras.
"Tuan Han Rim, saya dari layanan pesan antar restoran Seorae. Saya datang membawa ayam Anda."
Suara marah Han Rim berteriak dari dalam. "Aku tidak memesan ayam!"
Tentu saja, batin Wonbin, seolah-olah kau bisa memakannya. Wonbin lanjut mengetuk, semakin keras. Tangannya yang bebas menyusup ke guitar case-nya dan mengeluarkan sebuah tongkat perak berukuran sedang. "Benarkah? Mungkin Anda mau keluar dan memeriksanya dulu."
"Pergi dari sini, keparat!"
Wonbin memutar sedikit gagang tongkatnya. Alat itu seketika menjadi lebih hangat. "Tuan Han, saya tidak akan pergi sebelum Anda membayar. Anda tidak bisa terus-menerus menipu restoran kami begini." Ketukannya menjadi lebih mendesak. Wonbin menanti dengan sabar.
Pada hitungan kelima, pintu terbuka dengan kasar—tetapi cukup lebar—menampilkan wajah Rim yang terusik. "Dengar, sudah kubilang—"
Tongkat Wonbin menyumpal mulut Rim yang hendak berceloteh dan mengubahnya menjadi teriakan kesakitan. Di detik pertama tongkat itu menyentuhnya, listrik 1000 volt mengalir dan membuat Rim terjengkang. Wonbin menyeret guitar case-nya dan masuk tanpa diundang. Pintu tertutup mengurung mereka berdua. "Suka hidangannya?"
Tubuh Rim mengejang. Pemuda itu mengutuk-ngutuk di lantai. "Kau—kau yang di kereta—"
Ruangan di mana Wonbin berada sekarang adalah ruang tamu yang tidak dipersiapkan untuk menerima tamu. Perabotannya mewah tetapi terbatas. Alih-alih makanan atau vas bunga, hanya ada asbak yang penuh di meja. Dan wallpaper-nya? Warna kuning anggurnya memudar jadi lebih mirip warna urine. Astaga.
Dengan santai, Wonbin menyetrum Rim lagi. Tepat di kepala, yang pasti akan menyebabkan manusia pingsan atau lebih buruk lagi. "Jangan lupa beri rating 5, ya. Atau mampir langsung. Ada diskon 15% untuk pelajar."
Seandainya Rim manusia—padahal bukan.
"Kau kelihatannya seperti pelajar, tapi berapa lama kau sudah menjadi remaja? Jangan-jangan kau malah lebih tua dari kakekku."
Rim menggeram. "Siapa kau? Siapa yang mengirimmu, bangsat?"
Bukannya menjawab, Wonbin justru menggeleng prihatin. Ditariknya Rim sampai berdiri dan membenturkan kepalanya ke dinding. "Mereka bilang masa remaja itu masa yang paling canggung. Apa jadinya kalau kau harus jadi remaja selamanya? Sulit masuk ke kelab malam, terlalu muda untuk banyak hal. Tidak seindah di film-film kan?"
Mata Rim menggelap. Pemuda itu mencengkeram lengan Wonbin yang terlindungi jaketnya yang tebal. Perlahan, gigi taringnya yang semula normal mulai memanjang.
Wonbin berdecak. "Di mana Hong Gaeul? Ke mana temanmu menculiknya?"
"Ke neraka," sembur Rim. Taringnya membuat kata-katanya seperti diucapkan sambil berkumur-kumur.
Wonbin mengangguk. "Maka mimpikanlah neraka." Dia memutar gagang tongkatnya lebih ke kiri dengan jari, menaikkan dayanya hingga tongkat itu memanas. Saking panasnya, tongkat itu menyerupai obor. Percikan listrik melompat di udara. Namun Wonbin tetap memegangnya. Dia mengayunkannya ke leher Rim untuk ketiga kalinya, sekaligus sebagai serangan paling fatal.
Akan tetapi hal yang luar biasa terjadi—atau tidak terjadi—karena mendadak tongkat itu mati. Tidak ada reaksi.
Baik Wonbin atau Rim melongo. Wonbin, khususnya, memandang ngeri pada senjatanya, lalu pada Rim. "Oh, sial ...."
Rim rupanya cukup pintar membaca situasi. Dengan sigap, Rim menepis belitan Wonbin dan mendorongnya di perut—gerakan yang sekilas terlihat seperti tanpa usaha. Namun ternyata mampu menerbangkan Wonbin ke seberang ruangan, menabrak meja—dan nyaris mematahkannya. Asbak tumpah; isinya berhamburan. "Tak bisa apa-apa tanpa tongkat anehmu?"
Yang bisa dilakukan Wonbin saat itu adalah berguling. Abu rokok memicu dia terbatuk. Dia bahkan tak bisa melihat. Dia merutuk. "Bibi Lyn dan alatnya ...."
Tubuh Rim masih gemetar. Walaupun ia tidak gentar. Rim menghampiri Wonbin dengan pasti. "Siapa kau? Makhluk apa kau ini?"
Sesuatu bergeser ke sudut mata kanan Wonbin saat dia menggosok-gosoknya. Air matanya menitik. "Kau tahu, kita tak perlu melalui semua ini seandainya kau menurut saja. Maksudku, apa salahnya bicara?"
"Mungkin kau yang harus bicara. Aku tanya sekali lagi, siapa yang mengirimmu?"
"Sejujurnya? Pamanku."
"Pamanmu?" Rim membungkuk, berniat memaksa Wonbin bangun seperti yang Wonbin perbuat padanya. Sebelum sesuatu menghentikannya. Rim berganti terkekeh. "Aku mengerti. Kau salah satu keluarga Pemburu itu. Konon, beberapa dari mereka memiliki mata sewarna rumput. Oh, maksudku sebelah mata."
Wonbin berkedip polos. "Aku tak pernah tahu cara memasang lensa kontak dengan benar." Di salah satu jarinya, terdapat sepotong lensa kontak kecokelatan yang telah robek, menampakkan warna mata kanannya yang sejati dan berbeda dengan mata kirinya yang tak berubah; hijau. Sehijau rumput.
Rim meludah. "Keluarga Yoo. Aku pernah dengar tentang kalian. Sepertinya kalian menganggap diri kalian adalah polisi kaum supernatural. Berpura-pura menjadi pahlawan dan sebagainya. Menjijikkan."
"A-ah." Wonbin mengoreksi tidak terima. "Paman dan sepupu tertuaku memang polisi, jadi mereka tidak berpura-pura. Tahu detektif Yoo Jinman? Kalian bertemu di kantor polisi tadi pagi."
"Paman dan keponakan. Sama-sama makhluk campuran hina." Kembali, Rim membungkuk.
Waktu habis. Salahnya. Rim menunggu terlalu lama. Kali kedua dia datang, Wonbin siap. Sebelum Rim meraihnya, Wonbin menendang dadanya yang berisi jantung yang tak lagi berdetak. Rim sontak terpelanting. Dalam sedetik, posisi mereka terbalik. Dan, Wonbin masih memegang tongkatnya. "Ada yang aneh. Begitu kau dan temanmu pindah kemari, seorang gadis menghilang. Gadis werewolf. Pamanku hanya ingin bertanya, dasar lintah. Kau dan pengacaramu tak perlu membuat keributan. Kau tak bisa melakukan itu. Tidak di Gangwon-do."
"Menurutmu apa yang terjadi pada anjing yang nakal?"
Wonbin memutar gagang tongkatnya ke arah yang berlawanan, dan menarik ujung lainnya. Tongkat itu seketika bertambah panjang. "Tidak akan lebih buruk dari apa yang akan terjadi pada lintah sepertimu."
Dipenuhi amarah, Rim menerjang Wonbin membabi buta. Sayang, jangkauan tongkat Wonbin lebih luas, dan tongkat itu menghantam pipi Rim dengan telak. Darah merah gelap, cenderung hitam, mengalir dari mulutnya. Darah orang yang menghindari kematian dan mengira dirinya menang.
Rim mengusapnya. "Kau mati sekarang."
Mengenai bercanda, Wonbin sudah selesai. Wonbin tidak memberi Rim kesempatan berkembang. Dia memainkan tongkatnya dan memukul lutut Rim. Pemuda itu berpaling, siap mengeringkan darah Wonbin. Taringnya tampak lebih tajam dari pisau mana pun. Wonbin berkelit, dan dengan tangannya yang lain merogoh sakunya. Tangan itu muncul dengan sebuah jarum suntik.
"Tidur," perintah Wonbin, dengan paksaan, karena sembari menanamkan ujung jarum itu ke leher Rim.
Rim serta-merta terhuyung-huyung. Ia berubah kaku, lalu lemas, lalu ambruk laksana sekarung beras.
Wonbin menendangnya untuk sekadar memastikan. Rim tidak melawan. Tendang dua kali. Masih tidak ada perlawanan. Jadi Wonbin mengembuskan napas dan bersandar hati-hati ke dinding. "Aduh, punggungku ...." keluhnya, kemudian sikapnya berubah serius tiba-tiba. "Kau bisa keluar sekarang. Siapapun dirimu."
Tak ada respons.
Wonbin menggapai guitar case-nya dengan kaki. "Aku tahu kau di sana. Kau terhibur?"
Pintu terbuka dari luar. Seorang pria mempersilakan sendiri dirinya masuk. Di malam yang gelap ini, ia memakai pakaian serba hitam. Sepatutnya juga hitam. Hanya mata dan rambutnya yang berwarna cerah—dengan potongan pendek yang memamerkan telinga runcingnya. Yang ini, Wonbin tahu, bukanlah kostum. "Kau ...."
Doyoung menyelipkan tangan ke saku mantelnya. "Aku memang terhibur. Lama tidak bertemu, Yoo Wonbin."
.
.
.
Guitar case Wonbin tidak pernah berisi gitar sejak awal.
Daripada gitar, di satu sisi ada dua belati—masing-masing terbuat dari perak dan besi—dengan sabuk pengikat yang mencegah mereka berguncang saat dia berjalan. Berbagai tabung suntik dengan berbagai cairan ditata di bagian atas—sengaja, agar mudah dijangkau. Sedangkan sisi lain dikhususkan untuk tongkat. Begitu melihat Doyoung, Wonbin melepaskan tangan dari belati besi yang hendak diambilnya dan merosot di lantai. "Kaukah yang mengikuti tadi?"
"Aku tidak mengikutimu," sangkal Doyoung, melirik Rim yang tergeletak dalam posisi aneh—dan melengos. Bangsanya dan vampir tak punya sejarah yang baik. "Ini satu-satunya malam dalam setahun di mana aku bebas berkeliaran. Aku sedang berjalan-jalan saat melihatmu. Jadi aku ingin memastikan apa itu benar-benar kau."
"Dan memutuskan mengintip?"
Doyoung tersenyum—senyum seorang makhluk berusia ratusan tahun yang sangat tenang, yang yakin hanya ada sedikit hal yang mampu menyakitinya. "Hanya mencari hiburan. Walaupun kau hampir memergokiku."
"Di luar? Ya."
"Bagaimana?"
Alis Wonbin terangkat—yang percuma saja karena tertutup poni ikalnya. "Sulit dijelaskan. Aku tahu begitu saja. Pokoknya aku selalu tahu saat ada makhluk yang bukan manusia di sekitarku. Seperti dulu."
"Kau mendengarnya? Menciumnya?"
"Lebih ke ... Merasakan. Aku tidak bisa membedakannya. Ini seperti kau mendengar anjing menggonggong tapi tidak tahu apa jenisnya sebelum melihatnya. Meski kata 'mendengar' itu tidak terlalu tepat."
"Unik," puji Doyoung. Atau semacam itulah. "Belum pernah dengar bakat seperti itu. Terakhir kali kita bertemu, kau sibuk berebut es krim dengan kakakmu. Sekarang lihatlah dirimu; menghadapi vampir sendirian."
Wonbin memberengut. "Itu lima tahun lalu saat usiaku 11 tahun."
Terakhir kali mereka bertemu, terjadi di halaman belakang rumah pamannya di hari libur Chuseok, ketika seluruh keluarga berkumpul. Entah dari mana, Doyoung muncul dengan cara yang kurang-lebih sama seperti saat ini; tanpa peringatan dan tanpa salam. Wonbin-lah yang pertama kali menyadarinya, dan dia lari mengumumkannya pada orang-orang dewasa. Wonbin kecil kebingungan karena mereka tidak bereaksi seperti dugaannya. Para orang dewasa itu justru berdiskusi dengan Doyoung, tanpa melibatkan senjata.
Kakak laki-lakinya yang kini kuliah memberitahunya. "Tidak apa-apa, Bin. Itu Doyoung. Dia teman keluarga kita. Ayah bilang kalau datang, berarti dia mau berbagi informasi penting atau hanya ingin berkunjung."
"Doyoung yang di catatan?"
"Iya. Dia cuma datang beberapa tahun sekali. Aneh, ya?"
"Warna rambutnya juga aneh, seperti kulit jeruk."
Kala itu, seakan mendengar dirinya digosipkan oleh para bocah, Doyoung menoleh. Dan menghela napas. Wonbin menjulurkan lidahnya. Wle!
Lima tahun kemudian, Wonbin, dengan punggung nyeri, mendongak padanya dan membandingkan. "Kau ... Terlihat sama saja dengan dulu."
"Terima kasih."
Apakah dia baru saja menyanjungnya? Wonbin keheranan. Dia tak terbiasa berada sedekat ini dengan bangsa Doyoung yang seharusnya tinggal di hutan. Kebanyakan dari mereka begitu. Wonbin jadi penasaran apakah Doyoung juga tinggal di hutan atau telah diusir sepenuhnya ....
"Tidak," celetuk Doyoung tiba-tiba. "Aku punya rumah di sudut kota dan di tempat lain. Sang Ratu tidak berhak melarangku ke hutan, tapi aku lebih suka menjauh."
"Apa?"
"Itu yang kau tanyakan kan? Di pikiranmu."
Hampir saja Wonbin lupa! Dia menepuk kepalanya. "Aku baru ingat kau seorang pembaca pikiran. Bagaimana rasanya terusir dari kerajaanmu?"
Sekilas, kejengkelan melapisi wajah Doyoung. "Aku tidak diusir. Tidak tepat demikian. Ketika aku pura-pura mencari Karina dan gagal, Sang Ratu hampir membunuhku. Aeri menolong dengan mengoceh bahwa Karina memang cerdas, dan karenanya kegagalan itu bukan salahku. Aku menggunakan momen itu untuk meminta izinnya keluar dari kerajaan dengan alasan menebus dosa. Sang Ratu setuju setelah memberiku bekas luka yang takkan kulupakan. Harga sebuah kebebasan."
"Aeri? Dia lebih dikenal sebagai 'Nona Ramah' di catatan nenek buyut-buyut-buyutku."
Wonbin bisa saja salah. Namun agaknya Doyoung nyaris tertawa saat dia menyebut 'nenek buyut-buyut-buyut'. Sosoknya yang sekarang terlihat berbeda dengan yang dideskripsikan Jimin. Doyoung yang ini lebih ramah. Lebih rileks. "Begitulah Aeri dan Karina. Aku sudah beberapa dekade tidak bertemu dengannya."
"Nona Ramah masih hidup?"
"Segar bugar. Aeri bukan lagi Penjaga, tentu saja. Tapi dia tahu rencanaku meloloskan diri dari sangkar dan berbaik hati menyimpannya. Tidak seperti Sang Ratu yang mengira aku berteman dengan Karina sebagai sesama orang buangan. Pada saat itu, tak ada yang bisa dia lakukan karena aku bukan lagi miliknya."
Tak peduli berapa kali dibahas, konsep mengenai kerajaan bangsa Doyoung selalu aneh bagi Wonbin. Siapa, sih, yang mau dipimpin ratu bertangan besi itu? Bukan orang yang waras, Wonbin tebak. "Kau pernah ... Menyesalinya? Membantu nenek buyut-buyut-buyutku. Aku mendapat kesan dia masih tidak menyukaimu setelah semuanya."
"Memang tidak," ujar Doyoung blak-blakan. "Karina selalu waspada terhadapku. Tapi dia juga tidak menolak bantuanku bila itu menyangkut putranya, Jion* ... Yang sangat mirip dengan Jeno. Dan tidak, aku tidak menyesal. Karina bisa dibilang juga membantuku bebas dengan suatu cara."
"Pasti sulit rasanya," gumam Wonbin. Ponsel di saku celananya bergetar. Dua sepupunya melaporkan bahwa mereka akan segera sampai. "Dengan sebelah mata hijau dan telinga runcing, aku takkan kaget kalau ada yang menuduh Jion penyihir. Maksudku, itu abad ke-18."
Kali ini, Doyoung membiarkan tawanya tumpah. Sosoknya jadi menyerupai kelinci yang diberi sekarung wortel. "Tidak. Tidak juga. Jangan lupa siapa yang membesarkannya. Jion itu pembicara yang menawan. Dia selalu berhasil menemukan alasan. Aku merindukan mereka kadang-kadang."
"Mengapa mantan ratumu tidak berusaha membunuhnya?"
"Bosan. Merepotkan. Siapa tahu? Dari penjelasan Aeri, Sang Ratu bahkan tidak tahu keberadaan Jion sampai Jion sudah dewasa. Kurasa dia tidak menyangka keluarga kalian akan bertahan selama ini. Ketika dia tahu—"
"—terlambat baginya." Wonbin menyelesaikan kalimat Doyoung seraya meluruskan kaki. "Mewakili nenek buyut-buyut-buyutku, kurasa aku harus mengucapkan terima kasih."
Doyoung menunduk ke arahnya. "Sudah kubilang aku tidak menyesal. Kalian melakukan hal yang benar di sini. Karina, Jeno, dan Jion pasti bangga. Jaga dirimu, Nak. Kau mengingatkanku padanya."
"Pada siapa?" tanya Wonbin, menurunkan pandangannya sebentar saja. Namun pintu kembali terbuka dan Doyoung pergi dalam sekejap mata sebelum menjawab apakah Wonbin mengingatkannya pada Jimin, Jion, atau ... Jeno.
.
.
.
Satu jam setelah jam makan malam, Yoo Wonbin mendorong pintu sebuah restoran bernama Seorae dan disambut tatapan tajam seorang wanita yang berdiri di balik meja kasir nomor 1 dan dari gelagatnya siap melahapnya bulat-bulat. Wonbin nyengir. "Ibu, cemberut itu tidak baik untuk bisnis."
Wanita itu memukulnya dengan botol air mineral. "Menghadapi preman seperti itu sendirian, bersikap sok jagoan. Kemari kau!" Bagi ibunya, 'preman' adalah kata yang lebih cocok menggambarkan makhluk-makhluk yang bukan manusia.
"Ibu—aw! Aduh!" Selama semenit berikutnya, Wonbin berputar-putar berupaya menyelamatkan hidupnya. Bukan tanpa alasan; ibunya mengincar punggungnya. Jadi caranya mengaduh bukanlah pura-pura. "Ibu tidak tahu saja, si lintah itu sadar dirinya diikuti dan melompat ke kereta. Aku satu-satunya yang sempat mengejarnya. Yushin dan Naevi tertinggal. Aku bisa apa?"
"Kau bisa menunggu mereka."
"Terlalu lama."
Satu pukulan lagi mendarat di—untungnya—kepala Wonbin, meski tetap saja sakit. "Kalian keluarga Yoo memang pencandu bahaya yang sinting. Ibu tak tahu kenapa Ibu menikahi ayahmu."
Suara tawa seorang pria terdengar menggelegar dari dapur, disusul seraut wajah dan tangan yang memberinya tanda jempol. "Bagus sekali, Bin. Kalau begini, ayah bisa mengoper semua urusan keluarga padamu."
"Jangan coba-coba!" Ibunya memperingatkan dengan galak. Insting induk ayamnya diaktifkan. Ayahnya membuat gerakan menggorok leher dan cepat-cepat kembali ke dapur. "Sini." Wanita itu memeriksa wajah Wonbin dari segala sisi. "Biar ibu lihat. Kau pulang dengan selamat. Kau masih utuh—"
"—dan tampan."
Ibunya menjewernya. "Apa kau terluka?"
Wonbin berdiri lebih tegak. "Selain mata yang kelilipan? Tidak."
Wanita itu menyerah dan meminta guitar case Wonbin. "Nanti ibu belikan lensa kontak lagi. Tunggu di sini. Ibu akan membuatkanmu teh."
Masih menurut ibunya, teh merupakan ramuan ajaib yang ampuh menyembuhkan berbagai hal. Lelah? Minum teh. Stres? Minum teh. Putus cinta? Coba tebak, minumlah lebih banyak teh! Wonbin menyeringai pada kasir kedua, seorang gadis pekerja paruh waktu, yang duduk tak jauh darinya. "Dia selalu mengira usiaku enam tahun."
"Kau les gitar pada preman, Bin?"
Wonbin berlagak seperti agen rahasia. "Maaf, itu urusan keluarga." Gadis itu memberi tanda jempol juga—tapi terbalik.
Terlepas dari tutorial penyiksaan anak yang dipraktikkan ibunya, para pelanggan menyantap makanan mereka dengan tenang. Sekelompok remaja putri bahkan larut dalam kegiatan mereka berfoto-foto. Seorae adalah restoran yang besar—kasirnya saja ada tiga!—dengan dekorasi art deco yang menyejukkan mata. Bagian luarnya terbuat dari kaca, memberi akses pada pelanggan untuk menikmati pemandangan laut yang bisa dicapai dengan beberapa menit berjalan kaki. Dari sini, pasir putihnya tampak seberkilau kristal.
Wonbin sedang mengutak-atik komputer, demi memilih lagu yang diputar melalui speaker, saat gadis itu datang bersama seekor kucing calico yang lebih dulu menyapanya.
"Meow."
Gadis itu menggaruk kepala kucingnya. "Seol-ie, kau lapar lagi, ya?"
Rahang Wonbin terbuka lebar—sebelum dia ingat menutupnya. Tidak setiap hari Wonbin menjaga restoran dan kedatangan seorang dewi. Atau seseorang dengan visual yang memenuhi kriteria anggota grup idola. Atau gabungan keduanya. Pelanggan yang baru tiba itu adalah gadis tinggi langsing yang rambutnya di cat pirang—dan di cepol manis di puncak kepalanya. Wajah tirusnya mulus dan bersih. Dahinya, seperti Wonbin, ditutupi poni yang bermodel "tirai".
Matanya yang berbentuk almond menatap Wonbin dengan kelap-kelip seolah ia menyimpan seluruh galaksi di sana. Hidungnya yang kukuh berakhir pada sepasang bibir tipis sewarna cherry. Singkatnya, oooh, gadis itu membuat Wonbin lupa pada apa yang harus diucapkannya.
Wonbin berdeham. "Selamat datang di Seorae. Siap memesan? Saya bisa merekomendasikan menu kalau ini kali pertama Anda berkunjung."
"Ini memang kali pertamaku. Benarkah restoran ini menggunakan resep yang sama sejak abad ke-18?"
"Benar. Kecuali untuk menu baru, tentu saja. Restoran ini warisan keluarga."
"Dan kalian menyajikan ayam padahal berdiri di tepi pantai?"
"Kalau tidak menjadi unik," dendang Wonbin, setiap kali pertanyaan semacam itu diajukan. "Bagaimana kau akan dikenal?"
Penjelasan itu cukup bagi si gadis, yang mengangguk. "Benar juga. Lalu, apa kalian menerima hewan peliharaan di sini?"
Service dog berhak berada di mana saja menemani tuannya. Seorae tidak pernah menolak. Faktanya, Seorae tak punya aturan khusus mengenai hewan peliharaan. Namun Wonbin berakting meneliti kucing gadis itu. "Ini kucingmu?"
"Oh, bukan. Seol adalah kucing yang kutemukan dua hari lalu, dan aku berencana bertemu pemiliknya di sini—kalau boleh."
"Karena dia sangat imut, maka boleh."
Gadis itu menebar senyum. Tak kalah imut dari kucing yang bukan kucingnya. Ia memesan menu pertama yang Wonbin rekomendasikan, serta ayam tanpa bumbu porsi anak-anak untuk Seol si kucing.
Wonbin mengetikkan pesanannya. "Atas nama?"
"Jimin."
"Maaf?"
"Jimin," ulang gadis itu. "Bae Jimin. Seperti nama laki-laki, ya?"
Wonbin tergelak. "Tidak juga. Itu hanya mengingatkanku pada orang yang ... Kukenal. Tunai atau non-tunai?"
Transaksi selesai secara kilat. Wonbin meminta Nona Bae Jimin menunggu dan ia mengiakan. Tetapi tidak bergerak memilih meja. Nona itu malah menggigit bibir bawahnya ragu-ragu. "Anu—maaf—aku tidak bermaksud ikut campur ... Tapi kurasa satu lensa kontakmu hilang."
"Oh, ini?" Wonbin menunjuk mata hijaunya. Dia seperti akan menangis. "Saya baik-baik saja. Ini heterochromia. Kondisi genetik langka ketika dua iris mata memiliki kadar melanin yang berbeda." Dia telah menghafal kalimat itu sejak TK. Kalimat standar yang diajarkan pada anak keluarga Yoo yang terlahir dengan warna mata yang tidak selaras.
Pipi Jimin langsung bersemu merah. "Maaf. Maaf! Aku tidak tahu." Ia segera duduk di kursi kosong yang tersedia dan menyibukkan diri dengan Seol.
Wonbin melanjutkan aktivitasnya memilih-milih lagu. Pilihannya jatuh pada lagu "Once Again" dari penyanyi bernama Winter dan Ningning.
Tepat ketika intro lagu dimainkan, seseorang untuk kesekian kalinya mendorong pintu restoran dan membawa masuk angin dingin dari pantai. Seorang pemuda dengan tatanan rambut comma hair. Seumuran kakak Wonbin, dari penampilan luarnya. Dan ternyata juga tidak terlalu tinggi, walaupun berotot. Pemuda itu kelihatan seperti tipe pemuda yang suka nongkrong di gym ... Atau perpustakaan, berkat kacamatanya. Sebuah selendang biru melilit lehernya.
Pemuda itu menjelajahi restoran dengan matanya yang sangat normal, dan sudah akan mengangkat ponsel ketika Jimin melambai dari mejanya.
Untuk sesaat, pemuda itu membuat Wonbin mempertimbangkan memotong rambutnya (yang kemungkinan tidak akan terjadi, Wonbin terlalu cinta rambut panjangnya). Harus diakui, pemuda itu tampan dalam artian ketampanan klasik Korea. Namun ada sesuatu pada struktur tulang wajahnya yang membuat ia pantas-pantas saja mengaku sebagai keturunan Amerika atau Eropa dengan bantuan sedikit cat rambut dan lensa kontak. Sesuatu yang sulit digambarkan ... Memberi sentuhan misterius. Ia memakai pakaian kasual yang nyaman. Sebuah jam tangan adalah satu-satunya aksesorisnya.
Pemuda itu menarik kursi di depan Jimin. Mereka berdua selanjutnya sibuk membungkuk pada satu sama lain yang lazim dilakukan sepasang orang asing. Wonbin terkekeh geli. "Bae Jimin, kan?" Sapa si pemuda. "Aku, eh, kau—maksudku, kita bicara di ponsel kemarin—"
Seol mengeong lagi. Mereka bertiga—termasuk Wonbin yang menguping—tertawa. Mata pemuda itu menyipit saat melakukannya.
"Kurasa itu artinya kau ayah Seol," kata Jimin, mengulurkan kucing itu.
Si pemuda berniat mengambilnya, tapi sial sekali, lututnya menabrak meja dan membuatnya miring. Ponsel Jimin di atasnya meluncur jatuh. Mereka berlomba-lomba menangkapnya. Karena tangannya lebih panjang, pemuda itu menang. "Maaf. Maafkan aku. Ponselmu tidak apa-apa. Ini dia. Aku memang ceroboh. Maaf."
Wonbin meringis. Gadis seperti Jimin berpotensi menyebabkan pemuda mana pun gugup.
Jimin menggeleng-geleng. "Kemarin kau bilang kau kehilangan Seol di tempat penampungan hewan saat donor darah, dan sekarang kau hampir meremukkan ponselku. Bisakah untuk sehari saja kau tidak bersikap ceroboh?"
Pemuda itu nyaris terlalu malu untuk menatap Jimin. "Aku—"
"Hanya bercanda. Ya ampun. Tenang saja—siapa namamu? Aku pelupa."
Seol berpindah tangan. Kucing itu kini berada di pelukan pemiliknya yang asli, dan tanpa sungkan-sungkan mencakar bahu si pemuda, menjatuhkan salah satu ujung selendang birunya. "Jeno. Lee Jeno."
Di tempatnya, Wonbin ternganga tak percaya. Jimin dan Jeno? Apa-apaan—
Jeno menaikkan kembali selendangnya. "Apa kau sudah menunggu lama, Jimin?"


*Jion adalah nama panggung Karina yang batal dipakek.
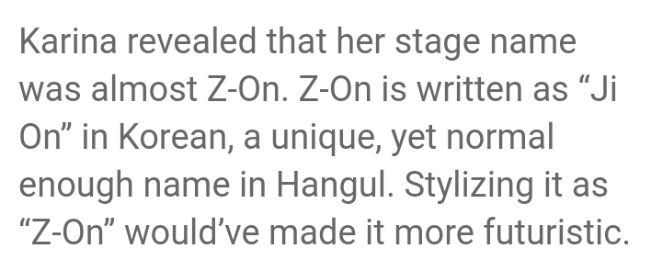
(Sc : Koreaboo)
Hei-ho, kawandzku sekalian yang budiman dan budiwati, dengan ini HSL resmi tamat, ya! Setelah setahun di mana minat nulis gua menurun drastis karena kerja dan sebagainya. Makanya walaupun pendek, HSL jadi salah satu anak gua dengan pengerjaan paling lama.
HSL ini dibilang happy ending bener, dibilang sad ending juga bener. Suka-suka kalian mau nangkepnya gimana 😂 Buat Wonbin, gua nggak punya alasan khusus pilih dia selain karena bingung mau pilih siapa lagi. Ditambah, foto Jeno yang pas ngobrol sama Wonbin itu menurut gua lucu (☞゚∀゚)☞

HSL bukan anak yang sempurna. Gua sadar tumbuh kembangnya/? lambat dan anak ini punya beberapa ketidakjelasan. Kayak, contohnya, nyadar nggak, sih, gua nggak pernah nulis karakter Jeno ini sebenernya makhluk apa? Antara elf atau peri, gua pusying pilih yang mana. Jadi lagi-lagi suka-suka kalian maunya apa *digapluke*.
Makasih mau baca cerita di mana Karina punya semacam kepribadian ganda, Jeno jadi makhluk fantasi kagak jelas, Giselle-nya jago panahan, Sungchan kena chinguzone *ketawa sendiri* dan Taeyong jadi abang durjana. Ekstra makasih yang banyak kalau kalian mau ninggalin komen buat penyemangat ak hehe 👊🙂
Bonus si Seol, kucing asli Aa' oneJ :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top