24. Awal: Pemburu

Ada banyak jenis bunga mawar di dunia—dan tiap jenisnya melambangkan sesuatu yang berbeda.
Misalnya saja mawar kuning, memberikannya pada pria yang tidak kau suka bisa jadi alternatif menolaknya, sebab mawar kuning berarti persahabatan. Di sisi lain, mawar merah mewakili cinta atau kekaguman. Yang paling malang adalah mawar hitam—hanya karena warnanya, banyak orang otomatis berprasangka bahwa mawar hitam adalah lambang kematian. Padahal bukan. Salah besar. Mawar hitam sejatinya berarti awal yang baru atau kebangkitan. Ada pula mawar putih yang merupakan bahasa bunga untuk 'kemurnian', 'sakral' atau 'cinta yang abadi'."
Yoo Jimin sedang membawa seikat mawar putih di tangannya.
Di desa yang kini sepi, dia berjalan dengan leher tegak. Enggan melirik rumah-rumah atau bangunan lain baik yang direnovasi atau ditelantarkan. Tidak ada yang menyapa atau melambai riang padanya seperti dulu. Suasananya terlalu muram. Orang-orangnya masih berduka. Akhir-akhir ini, di kesempatan langka ketika Jimin keluar dari rumahnya, semua orang yang dia temui entah sibuk memperbaiki sesuatu, melamun atau mendongak ke langit—tegang dan waspada—menanti tanda-tanda burung ganas yang nyaris meratakan desa mereka dengan tanah.
Kehidupan yang dulu, Jimin menyimpulkan, tidak akan pernah terulang.
Jimin mendekap bunga-bunganya lebih rapat, meski duri-duri mereka menusuk-nusuk kulitnya. Dia berjalan lebih cepat, mengabaikan sedikit rasa tidak nyaman yang masih tersisa di kakinya setelah tiga bulan. Tabib bilang lukanya memang parah—dan terus bertanya bagaimana Jimin mendapatkannya—tapi menyatakan bahwa selama Jimin menjaganya dari infeksi, dia pasti bisa kembali berlari di masa depan. Namun dia tidak berlari. Belum.
Di ujung lain desa yang berlawanan dengan hutan, Jimin berbelok ke sebuah tikungan dan masuk ke dunia orang mati. Puluhan nisan menyambut Jimin dalam keheningan. Sebagian kecil terbaring di sana karena kecelakaan. Sebagian besar dibungkam selamanya oleh penyakit. Hanya sedikit yang cukup beruntung (atau sial) hidup sampai rambutnya memutih dan meninggal karena usia tua. Dan hanya satu, yang makamnya paling tidak mencolok, yang pergi karena pedang kakaknya.
Makam Jeno terletak di dekat makam ibunya, dan di saat yang sama juga agak tersembunyi. Setumpuk kecil batu menandai lokasinya. Tanpa hiasan apapun selain dedaunan yang ditiup angin dan bunga layu yang diletakkan Jimin minggu sebelumnya dan sebelumnya lagi. Dia yakin ibunya akan menyukai Jeno dan tidak keberatan.
"Hai, ibu, Jeno," ujar Jimin, memberi mereka masing-masing tiga tangkai mawarnya yang dia atur dengan hati-hati. "Ini masih aku. Tapi kali ini aku punya kabar buruk." Jimin berpaling. "Aku akan pergi. Aku harus pergi."
Dua meter di sisi kanan Jimin, sebatang pohon ek menggoyangkan dahannya. Dengan pelan. Dengan anggun. Menghasilkan musik lembut yang menghibur orang-orang yang telah tiada. Jimin memejamkan mata sebentar, tetapi membuka telinganya lebar-lebar. Adakah yang menguping? Mengingat lengahnya dia minggu lalu, Jimin jadi sangsi.
Pundak Jimin merosot oleh kegundahan. "Aku tidak tahu kapan aku akan kembali, tapi aku pasti kembali. Pasti. Karena yang di sana"—tatapan Jimin tertuju pada tanah kosong di samping makam Jeno—"Itu milikku. Tempatku. Hanya bersama kalian aku ingin tidur dalam keabadian."
Dia ingin tertawa. Dia berusaha tertawa. Namun sudah lama sekali Jimin tidak melakukannya dan lupa bagaimana caranya. Lagipula, hidup ini pahit. Apa yang bisa ditertawakan? Jimin mengusap matanya. "Kuharap kalian tidak berpikir aku hendak lari dari semua ini. Bukan itu niatku. Sungguh." Lalu karena yakin dia sendirian, dia membiarkan setetes air matanya meluncur turun. Hanya satu.
Tidak ada yang menginterupsinya.
Hal itu berbeda dengan minggu lalu, ketika Jimin kira dia sendirian dan detik berikutnya, Doyoung muncul di belakangnya—bersandar kaku di pohon ek seolah mereka sudah membuat perjanjian.
"Apa manusia bisa merasa bersalah, Karina?"
.
.
.
"Apa manusia bisa merasa bersalah, Karina?"
Kala itu, dibanding kehadiran Doyoung yang mendadak, Jimin lebih terkejut pada panggilan yang pria itu gunakan. Selain Jeno dan Aeri, tak ada lagi yang mengenal Karina. Dan Jimin ingin sosok pembohong itu ikut terkubur untuk selamanya.
"Hanya penasaran. Jangan tersinggung." Imbuh Doyoung santai.
Jimin mengepalkan tangannya. Dia melirik Doyoung sekilas. "Apa yang kau inginkan, Doyoung?"
"Mengapa kau selalu berasumsi aku menginginkan sesuatu darimu?"
"Aku berasumsi kau tidak berkunjung untuk sekadar beramah tamah."
"Tepat sekali." Doyoung mengulangi perkataannya di hari pertama mereka berjumpa. "Aku ingin kau pergi, Karina. Dari desa ini. Sejauh-jauhnya."
Jimin tertawa tanpa rasa humor. "Mengapa aku harus mematuhimu?"
"Demi keselamatanmu sendiri. Sang Ratu tidak senang padamu."
"Betapa anehnya," sindir Jimin. "Ingatkan aku kapan dia pernah menyukaiku?"
Doyoung berdecak. Sekilas pandangan Jimin ke arahnya memberitahunya bahwa Doyoung masih mengenakan gaya berpakaian yang sama, dalam warna-warna netral yang cenderung gelap. "Simpan permainan katamu, Nak. Kau tidak mengerti. Sang Ratu mengincar kematianmu. Taeyong—dia salah satu yang dikasihinya. Sekarang setelah bosan berduka, Sang Ratu sibuk memperhitungkan cara terbaik membunuhmu."
"Kenapa kau peduli?"
"Aku tidak peduli," hardik Doyoung. "Tapi aku mengenal Jeno di seumur hidupnya yang singkat. Dia anak baik. Sangat baik. Dan Jeno jelas ingin kau hidup. Sayang sekali menyia-nyiakan pengorbanannya menurutku."
Siapapun yang dipanggil Sang Ratu itu, ancamannya tidak main-main. Jimin takkan menganggap orang yang memerintahkan manusia mana pun yang memasuki wilayahnya harus mati sebagai seorang penggertak. Tidak. Jimin merasa dia seharusnya takut. Dan dia akan takut—andai usianya masih sembilan tahun. Kini, di usia yang menuju 19, dia menangkap basah dirinya menyeringai. "Apa yang akan ratumu lakukan? Mengirim seseorang dan mengurusku saat aku tidur?"
"Kau tidak menyimak satu pun peringatanku, bukan?"
Punggung Jimin bergetar oleh tawa palsu yang kedua. "Repot-repot kemari untuk memperingatkanku. Baik sekali kau. Sungguh. Maaf membuang-buang waktumu. Pulanglah sekarang dan katakan pada ratu sialanmu bahwa aku sudah membunuh satu. Kalau dia mengusikku, aku akan membunuh lebih banyak."
Kegeraman Doyoung meningkat, seperti arsiran tinta yang menebal. "Kau tidak mengerti juga, ya? Ada pertarungan yang tidak bisa kau menangkan! Ini salah satunya. Sang Ratu bukanlah Taeyong, sebab dia akan memastikan tak ada lubang dalam rencananya."
"Semoga berhasil kalau begitu."
Doyoung menggeleng-geleng. "Aku bukan musuhmu, Karina. Jangan keras kepala. Pergilah dari desa ini. Ke Utara—"
"Keluargaku ada di sini. Bahkan meski aku tidak tahu di mana ayahku."
"Ya, dan mereka sudah meninggal," balas Doyoung telak. Tak sadar bahwa ucapannya laksana menekan sebuah memar. "Keluargamu dan Jeno sudah meninggal, tapi kau punya kesempatan untuk memulai keluarga baru. Menikah. Memiliki anak—"
"Cukup," potong Jimin sekali lagi. Satu kata itu ibarat pisau yang memotong apel menjadi dua dalam satu tekanan. Dia menelan ludah. Tangannya yang tadinya mengepal terbuka, dan dia mengadu kuku jari telunjuk dan kuku jempolnya—sebuah isyarat kegugupan. "Aku sudah menyuruhmu pulang. Apa yang kau tunggu?"
Roda berputar: giliran Doyoung yang tidak mendengarkan. "Anak? Kenapa dengan anak?" Doyoung mengernyit. Kepalanya dimiringkan secara refleks. Selama sekian detik, mereka tidak bercakap-cakap. Angin kencang menampar mereka. Si mantan penjaga tersentak—tak ada hubungannya dengan angin sama sekali. "Kau mengira dirimu tengah mengandung?!"
.
.
.
Suara ringkikan kuda menyeret Jimin keluar dari aktivitasnya mengurai simpul ikatan masa lalu.
Jung Sungchan menghampiri Jimin seraya menuntun seekor kuda betina putih dengan bercak-bercak hitam di tubuhnya. Namun berhenti persis di garis batas pemakaman sehingga tak mengusik siapapun yang terlelap di bawahnya. Kuda itu sudah dipasangi pelana, berikut beberapa perlengkapan bepergian yang seharusnya cukup untuk sepekan. Sungchan menepuk-nepuk lehernya. "Seorae siap berangkat, Nona."
Seorae, kuda yang sama yang mereka naiki saat mereka kecil.
Istal keluarga Sungchan adalah satu dari beberapa bangunan yang ajaibnya masih utuh ketika Taeyong memulai acara bakar-bakarnya. Kuda-kuda di dalamnya mengalami malam yang sulit, dan jelas panik akibat semua keributan di luar, tapi secara keseluruhan, mereka baik-baik saja. Karena itulah Seorae di sini; tampak tidak sabar berpetualang. Ayam-ayam tidak seberuntung itu.
Jimin mengelus surai Seorae yang dia kepang kemarin. Kuda itu beraroma jerami, sinar matahari, dan gairah yang menggebu-gebu. "Kau benar-benar siap, Seorae sayang?"
"Tentu saja. Tapi dia tidak harus ke mana-mana. Belum terlambat membatalkannya."
"Sungchan—"
Sungchan mengangkat bahu. "Apa salahnya mengingatkan? Kita masih bisa berputar balik, membongkar muatan ini, dan pulang ke rumah."
"Rumahku sudah hampir ambruk."
"Kau tahu maksudku rumahku."
"Tepat sekali." Jimin mengangguk. "Rumahmu. Bukan milikku."
Sungchan membasahi bibirnya dan menggeliat tidak nyaman. "Katakan padaku alasannya, Jimin. Mengapa kau ingin pergi? Mengapa sekarang?"
Dengan sengaja, Jimin menghindari tatapan menyelidik Sungchan. Mungkin dia pandai berbohong. Namun dia tak pernah bilang itu mudah dilakukan—terutama pada orang-orang yang dia pedulikan. "Apa maksudmu mengapa? Separuh penduduk desa kita pergi. Aku hanya terlambat menyadari bahwa aku seharusnya menyusul mereka lebih cepat."
"Lalu kenapa Utara? Ada apa di sana yang sangat ingin kau kejar?"
"Entahlah." Jimin menjawab dengan teka-teki. "Kurasa aku ingin memulai sesuatu di tempat tidak ada seorang pun yang mengenalku. Membuka restoran ayam di Utara kedengaran bagus kan?"
Sungchan tidak sependapat. "Terlalu jauh. Terlalu berbahaya. Rumornya ada banyak serigala di sana. Kau bisa ikut denganku ke barat, Jimin. Ke tujuan yang lebih pasti. Kau tidak harus sendirian."
"Aku bisa saja melakukannya," ujar Jimin dengan nada merenung. "Tapi bukan itu yang kuinginkan."
Habis sudah. Tak ada harapan. Ini seperti rempah-rempah yang terlanjur ditumbuk; tak ada cara mengembalikannya ke bentuk semula. Sama halnya dengan Jimin yang telah memutuskan sesuatu—tak ada yang bisa meyakinkannya untuk berubah pikiran. Dibanding siapa pun, Sungchan lebih tahu. "Jadi ... Kita takkan pernah bertemu lagi?"
Jimin sempat membisu. "Mari berharap sebaliknya. Barangkali 50 tahun dari sekarang, kita akan berpapasan di sebuah pasar saat kita sama-sama butuh bantuan tongkat untuk berjalan ...."
Mau tak mau Sungchan tergelak. "Punggung bungkuk, mata rabun, dan linglung?"
"Ya. Jangan malu-malu menyapaku jika itu terjadi."
Dua sahabat itu saling tersenyum. Jimin—setidaknya dia berupaya. Masing-masing dari mereka paham bahwa ini bagian lain dari menjadi dewasa, yakni dengan melepaskan meski hati menolak. Lalu entah siapa yang memulai, tiba-tiba Jimin ada di pelukan Sungchan; suatu tempat yang tak pernah terasa asing baginya. "Bagaimana pun rupamu nanti, bahkan walau kau dipanggil dengan nama yang berbeda, aku akan selalu mengenalimu, Jimin. Selalu."
"Terima kasih," ucapan Jimin agak teredam pakaian Sungchan. "Untuk segalanya. Aku tidak bisa menjanjikan apapun karena aku pelupa, tapi terima kasih banyak."
Menghentikan upaya membujuknya yang sia-sia, Sungchan memandu Jimin ke Seorae dan membantunya naik, dengan tangannya yang berbeda dari sembilan tahun lalu—lebih lebar, lebih besar, tidak lengkap pula. Namun juga lebih kuat. Tangan yang akan dia rindukan. "Aku memasukkan dua buah buku ke tasmu. Sama-sama."
Jimin memutar bola matanya. "Hobi baruku adalah tidur, bukan menulis." Terlepas dari rumahnya yang sebagian hangus, buku-buku Jimin anehnya selamat dari kebakaran. Api tidak menyentuh kamarnya, hanya ruang makan dan kamar orang tuanya. Jimin bingung harus bersyukur atau memandangnya sebagai sebuah pertanda.
Sungchan terkekeh. "Cobalah menulis lagi. Ceritakan kisah tentang kita semua. Itu bisa jadi buku yang laris."
Jimin bergidik. "Orang-orang akan menganggapnya kisah yang menggelikan."
"Atau," ralat Sungchan, "Dongeng sebelum tidur yang bagus untuk anak-anakmu kelak."
Sekali lagi, kata 'anak' disebut. Kali terakhir, Jimin menatap makam ibunya dan Jeno. Apa mereka mendengarkan? Apa pendapat mereka soal menjadi nenek dan ayah? Ekspresi Jimin melembut. Diam-diam dia mengelus perutnya. "Kau benar. Itu bisa menjadi warisanku."
Sesuatu balas menendang dari dalam.
.
.
.
"Kau mengira dirimu tengah mengandung?!"
Akhirnya Jimin berbalik. Kemarahan menyelimuti wajahnya. "Bahkan jika itu benar, itu bukan urusanmu."
Doyoung menunjukkan gelagat seperti akan meledak kapan saja. Segera. "Karina—kau! Demi bintang-bintang! Tak satu pun dari kau atau Jeno yang menyadari bahwa kalian sebenarnya hanya anak-anak! Bukan urusanku? Kau benar. Itu urusan Sang Ratu."
"Apa hubungannya dia dengan hal ini?"
"Tidak ada, tapi kujamin berita ini akan menghiburnya. Dia tak perlu memikirkan hukuman yang lebih sempurna untukmu."
"Apa yang kau ocehkan ini? Hukuman apa?"
Doyoung menyugar rambutnya ke belakang—gerakan yang sangat halus seperti percikan api yang melayang ke udara. "Karina, jika perkiraanmu benar, dia akan merebut bayimu."
Sekujur tubuh Jimin kontan mati rasa. Ada momen mengerikan ketika dia pikir jantungnya berhenti berdetak. Jari-jarinya berubah menjadi sedingin es. Dia layaknya orang yang berdiri di tepi danau yang membeku lalu tanpa peringatan orang lain mendorongnya. Kekagetannya teramat hebat—dia merasa jatuh tanpa batas waktu. "Tidak," sangkal Jimin lambat-lambat. "Dia tidak akan melakukannya."
"Ya, dia akan melakukannya." Doyoung bersikeras. "Dia sudah melakukannya selama berabad-abad; memisahkan anak dari ibu atau ayahnya, membesarkan mereka menjadi budak yang memujanya, dan membuat mereka percaya bahwa darah manusia adalah pencemaran yang tercela. Kau dan Jeno bukan yang pertama melanggar batas demi cinta. Ada orang-orang lain. Manusia yang lain. Setiap kali itu terjadi, Sang Ratu selalu membunuh si pengkhianat dan membiarkan si manusia hidup dengan duka karena kehilangan anak."
Luka gores kecil terbentuk di jari telunjuk Jimin saat dia menekankan kuku jempolnya terlalu dalam. "Dia tidak bisa melakukannya! Apa haknya melakukannya?"
"Seperti kataku, tidak ada. Tapi kami ini bangsa yang angkuh yang mengira kami lebih baik dari manusia—termasuk soal mengasuh anak."
"Kalian"—saking marahnya, Jimin tergagap—"Kalian semua gila! Aku sungguh-sungguh. Kalian gila kalau kalian pikir bisa merebut bayiku tanpa perlawanan."
"Jadi kau yakin kau mengandung?"
Jimin merapatkan giginya. Puncak tulang pipinya menjadi semerah warna rambut Doyoung. Tak ada jawaban.
Memberanikan diri, Doyoung mendekati gadis yang menyerupai singa betina itu. Awalnya tangannya terangkat, lalu turun secara bertahap. Di jarak yang aman, Doyoung mencopot semua cincin di tangan kirinya dan memaksa Jimin menggenggamnya. "Salah satu kesamaan antara bangsamu dan bangsaku adalah, kita sama-sama menyukai perhiasan. Itu emas murni. Gunakan untuk memulai hidup barumu."
"Jangan sentuh aku—"
"Tidak. Dengarkan aku. Dengarkan! Seumur hidupnya, Jeno merasa terkurung. Aku mendengarnya setiap saat dia bersamaku." Dia menuding dahinya. "Di sini. Aku tahu betapa dia tidak bahagia. Jangan buat bayinya mengalami hal serupa. Kau berutang itu pada Jeno."
Jimin mundur dan melempar cincin Doyoung ke dadanya. "Mungkin tidak ada bayi. Aku-aku tidak tahu apa yang kupikirkan tadi. Kita sangat berbeda. Bayi itu—memangnya dia akan jadi apa?"
Dengan tenang, Doyoung memungut cincin-cincinnya. "Seseorang berdarah campuran, tentu saja. Dia mungkin bisa menyentuh besi. Mungkin tidak. Dia mungkin menyerap ciri-ciri fisikmu, tapi menerima keistimewaan dan kekurangan Jeno. Mungkin sebaliknya. Atau mungkin dia akan hidup sampai usia 150 tahun dan tampak seperti berusia 60. Sejujurnya, tidak ada cara mengetahuinya dengan pasti."
Berbagai emosi tergambar di wajah Jimin yang biasanya terkendali, dengan kebingungan yang dominan terpampang. Luapan informasi Doyoung menyebabkan Jimin terpaku, tak tahu harus bereaksi bagaimana selain menutup mulutnya.
Ekspresi Doyoung berubah simpatik. "Dia hanya akan sedikit berbeda. Itu saja. Tapi—"
"Tapi apa?!" Sekarang Jimin membentak si pembawa pesan.
"Itu tidak akan hilang. Maafkan aku. Ada kemungkinan bayimu terlihat sangat manusiawi, tapi jika demikian, besar kemungkinan justru cucumu yang seperti kami. Begitu pula anak dari cucumu. Dan seterusnya. Keturunanmu, Karina, akan selalu berbeda. Kau akan selalu melihat kami di pohon keluargamu."
"Maksudmu bukan manusia, sekaligus juga manusia ...."
"Ya. Semacam itu. Dalam kasus ini, darah bukanlah noda yang bisa memudar. Kalau kau tidak menginginkannya ...."
Jimin langsung memelototi Doyoung. "Kenapa aku tidak menginginkan bayiku sendiri?! Aku hanya ... Takut."
"Maka pergilah dari sini." Belum menyerah, Doyoung mengulurkan ketiga cincinnya. Sebuah tawaran terbuka. "Jangan beri mereka kesempatan. Pergi. Ada surga kecil manusia di Utara. Tempat itu dikelilingi hutan pinus yang sepenuhnya milik bangsamu. Kudengar bahkan ada pantai yang pasirnya seputih kristal."
Bibir Jimin mencibir. "Mustahil ada pantai berpasir putih."
"Kenapa kau tidak membuktikannya sendiri? Tempat itu lebih besar dari desamu dan ada lebih banyak manusia. Kau akan aman. Dan jangan khawatirkan aku—aku punya rencana."
"Rencana?"
"Jeno bukan satu-satunya yang muak terkurung di hutan. Tapi itu urusanku. Ayo, ambil."
Harga diri Jimin berkata: tidak. Hatinya berkata: terima saja. Keduanya saling bertabrakan. Logika dan musuh bebuyutannya, perasaan. Logika Jimin berbisik padanya, tidak ada yang pasti! Kau bisa saja salah! Sementara perasaan membantah, kau tahu kebenarannya. Kau punya seseorang yang harus kau lindungi sekarang. Tunas yang merekah. Bunga mungil yang mekar. Seorang bayi yang mungkin mewarisi senyum atau mata ramah Jeno ....
Jimin mengambilnya.
Kelegaan Doyoung tidak ditutup-tutupi. "Tiga tahun lagi aku akan mengunjungimu. Jika saat itu kau berubah pikiran, aku akan membawa si bayi. Jeno masih punya orang tua—yang sangat patah hati. Tapi kuharap tidak. Mereka ... Yah, bukan pengasuh yang ideal. Selamat tinggal untuk saat ini, Karina."
Ketiga cincin pria itu sekarang berpindah ke genggaman Jimin. Berat, indah, dan berkilauan. Jenis cincin yang bisa dipakai laki-laki atau perempuan, tetapi yang sangat, sangat kaya. Jimin belum pernah melihat seorang pun di desanya mengenakan cincin sebesar ini. Salah satunya dihiasi permata biru berbentuk persegi yang permukaannya mengilap, sehingga Jimin bisa melihat wajahnya dengan jelas.
"Doyoung?"
Doyoung menunda kepergiannya dan menoleh.
Jimin memasukkan semua cincin itu ke sakunya. "Aku tidak akan pernah berubah pikiran. Aku akan mencintai bayiku. Dia akan hidup. Dia akan bahagia. Akan kuajari dia cara melindungi diri atau menyerang kalian."
Doyoung terdiam sejenak. "Seorang Pemburu?"
.
.
.
Sehelai atasan hanbok berwarna merah muda tergeletak di tanah.
Seorae mengendusnya. Barangkali penasaran kenapa manusia punya banyak warna bulu yang berbeda dan kenapa bulu itu bisa dilepas dan dipasang kapan saja. Kalau kuda bisa bicara, Jimin berani bertaruh, semua kuda akan setuju manusia itu makhluk yang aneh.
Tanpa bicara, Jimin meraih atasan lain dari bekalnya dan berganti pakaian di situ, di sebuah padang rumput yang sepi, ketika sejauh mata memandang tak ada makhluk hidup lain yang terlihat. Atasan barunya berwarna putih. Seputih roknya. Seputih pasir di pantai di Utara ... Bila itu memang ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Jimin memakai atribut berwarna putih. Dia bahkan mengganti pitanya dan menyanggul rambutnya dalam gaya sederhana.
Persis ibunya setelah ayahnya tidak pulang. Persis ibu Sungchan setelah Tuan Jung lenyap.
Persis para wanita yang kehilangan suaminya.
Penjahit di desanya begitu membutuhkan uang dan dengan bijak tidak bertanya mengapa Jimin minta dibuatkan beberapa pakaian putih dan mengapa harus selesai dalam seminggu. Mungkin si penjahit menduga Jimin memesannya untuk ibu Sungchan. Apapun itu, hasil karyanya terasa pas dan nyaman.
Terasa seperti perubahan.
"Bagaimana menurutmu, Seorae?"
Bukannya Seorae, yang merespons justru burung dengan suara yang akrab. Jimin berputar dan memergoki seekor burung hantu yang bangun terlalu sore. Burung hantu itu menggoyangkan badannya, dan menatap Jimin dengan mata kekuningannya yang bulat.
Dan untuk pertama kalinya setelah tiga bulan, Jimin tersenyum tulus. Benar-benar tersenyum.
Pada salah satu sesi mengobrol mereka di tepi sungai Edra, Jeno pernah mengakui bahwa suara burung hantu yang Jimin dengar pada kunjungan pertamanya ke hutan bukanlah burung hantu sungguhan, melainkan berasal darinya. Jeno bahkan pamer kemampuan uniknya dan menirukan suara hewan-hewan lain. Jimin ingat mereka terbahak saat Jeno tiba pada katak. Dia ingat semuanya—masa lalu yang indah itu.
Jeno memang tidak ada di masa depan. Namun Jimin sadar bahwa Jeno masih bisa berada di masa depannya selama Jimin mengingatnya. Terlebih dengan adanya seorang pengingat ... Bintang yang bersinar di tengah matahari dan bulan.
Jimin tersenyum lebih lebar. "Sampai jumpa di kemudian hari, Jeno."

Masuk plot twist kagak nih? Apa jan2 dah ada yang nebak sejak bagian ehem2 🌚🌚🌚
Bwodo amat, gua mah cuma seneng ini otw mau tamat soalnya udah setahun woy, eh busyet 😭😭😭
Ditunggu epilognya ya, kawandz~
Tambahan nih, gua sebenernya pengen bikin bagian ehem2 itu tapi maloe sendiri dan bentar lagi puasa HAHAHAHA tobat deh ampun 💀
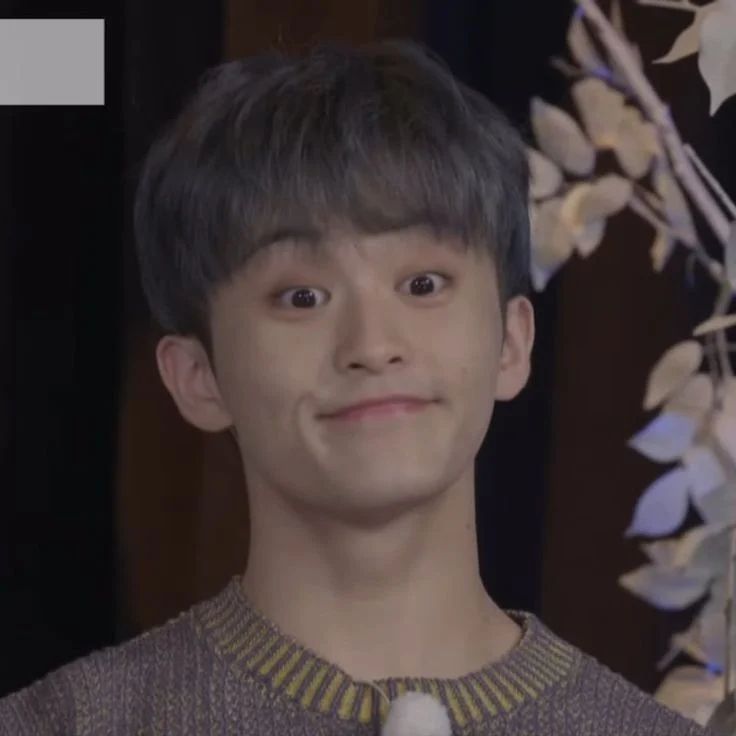
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top