17. Kegelapanku
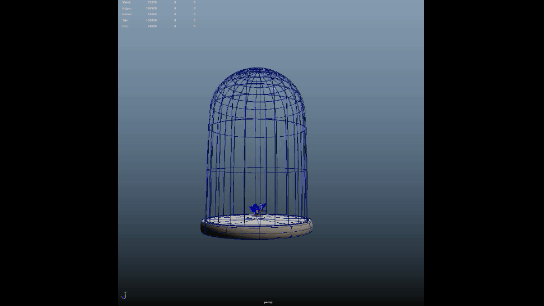
Pada satu titik, Yoo Jimin bisa saja berhenti.
Di rumahnya, Jimin berbaring dalam kegelapan di kamar orang tuanya. Kamar yang, bila diperhatikan, tidak mengalami banyak perubahan dengan atau tanpa kehadiran mereka. Bahkan selimutnya masih sama. Jimin menjaganya tetap demikian seolah ayah-ibunya hanya bepergian singkat dan akan pulang kapan saja. Tidak benar, kata sisi realistis dalam dirinya. Kini tak ada lagi ayah akan memanggilnya 'tuan putri' atau ibu yang batuk tanpa henti. Ketika Jimin berbalik menyamping, yang dia lihat adalah wajah sahabatnya sejak kecil.
Bocah pemalu itu, Sungchan, entah sejak kapan sudah tumbuh menjadi pemuda tegap yang membuat gadis-gadis sulit mengalihkan pandangan. Tingginya mengalahkan Jimin sekarang, dan tidak sekadar menarik dari segi fisik, Sungchan juga memiliki pegangan yang stabil pada masa depan. Kesimpulannya, sahabat Jimin itu telah berubah jadi bujangan paling diincar di desa. Jimin penasaran apakah fakta bahwa Sungchan mendengkur saat tidur akan mengurangi daya tariknya.
Pertanyaannya, adilkah dia menyeret Sungchan ke dalam bencana ini?
Jimin bisa saja berhenti. Ada kesempatan untuk berhenti yang terbentang selebar ngarai. Dia ingat di malam Jeno menunjukkan "ikan" di langit, Jimin berlari ke desa dalam kegelapan—nyaris tanpa menyadarinya—dan berpikir, cukup sudah. Aku sudah selesai. Menjadi diri sendiri bagi sebagian manusia sudah cukup berat; menjadi dirinya dan Karina bagi Jimin ternyata jauh lebih sulit. Itu ... Melelahkan. Sangat melelahkan.
Jadi mengapa dia tidak berhenti?
Malam semakin larut. Jika bersikap bijak, Jimin akan membangunkan Sungchan dan menendang pemuda itu pulang demi menghindari rumor yang tidak-tidak. Ibu Sungchan, yang tak pernah pulih dari peristiwa sembilan tahun lalu, juga pasti mengkhawatirkannya. Namun Sungchan terlihat sangat lelap, dan salah satu keuntungan dari memiliki rumah yang agak terasing adalah, kau bisa luput dari banyak mata yang terlalu suka ikut campur. Mungkin Sungchan bisa tinggal lebih lama?
Di sisi kamar yang lain, peti-peti kayu berisi anak panah, busur, pedang, dan beberapa belati yang semuanya terbuat dari besi teronggok menunggu karat. Hal lain yang pasti akan ditakuti oleh makhluk-makhluk hutan terkutuk itu selain ancaman terekspos yang nyata. Hal lain yang, Jimin tidak tahu apakah akan dia gunakan atau tidak, sama seperti dia tidak bisa memutuskan bagaimana nasib Jeno.
Jeno.
Jimin mengerjap. Mahkluk bodoh itu. Apa yang harus Jimin lakukan padanya? Jimin bukan orang baik—dan dia takkan pernah mengaku-ngaku begitu. Namun adakah orang yang benar-benar baik di dunia ini? Jimin bukan monster. Namun dia cukup tahu diri untuk tak melabeli dirinya sebagai orang suci.
Sejak awal, ini adalah ide buruk.
Jimin menutupi matanya seperti ketika pikirannya terlalu riuh dan berbalik ke arah yang berlawanan, menghadap dinding. Diiringi dengkuran halus Sungchan dan mata yang terpejam, dia bisa merasakan ingatannya kembali ke masa lalu, ke malam itu ....
.
.
.
Malam itu dihabiskan Jimin dengan cara yang sama seperti sekarang—itulah bagian lucunya, Jimin rasa.
Kala itu sepulang dari hutan, Jimin masuk ke satu-satunya tempat dia paling merasakan kehadiran orang tuanya—satu-satunya tempat yang, dia bisa menipu dirinya sendiri bahwa dia masih anak-anak yang wajar melakukan kesalahan; kamar orang tuanya. Sebelum masuk, Jimin bisa saja menyalakan penerangan. Menyantap makanan. Menyeduh teh kamomil. Atau sungguh, seratus hal lainnya yang lebih berguna daripada langsung berbaring dengan mata nyalang, berusaha mematikan suara-suara di kepalanya—dan gagal.
Yoo Jimin adalah seorang pemikir—kalau tidak, bagaimana dia bisa datang dengan rencana ini? Jimin kadang hanya lelah dengan kecepatan berpikirnya. Jadi dia sekadar berbaring, mengamati sinar keperakan bulan digantikan oleh sinar fajar. Satu per satu penduduk desa bangun dan mulai beraktivitas. Jimin tidak peduli. Lalu entah pukul berapa, Sungchan menyelinap masuk ke kamar.
Sungchan menunduk memandang Jimin yang tidak bergerak, matanya yang dihiasi lingkaran hitam, dan menggeleng. "Kau sadar kan aku bisa memecatmu kalau kau membolos seperti ini?"
Jimin berkedip pun tidak.
"Ayam-ayam kelaparan, Jimin, dan mereka tidak bisa mengambil makanan mereka sendiri. Aku cukup yakin tadi aku mendengar mereka memanggil namamu. Kau mau bangkit atau aku harus memaksa?"
Di masa depan, akan ada gestur yang menggambarkan reaksi Jimin dengan sempurna. Di zaman itu, isyarat jari tengah sayangnya belum diciptakan. "Pecat saja aku kalau berani."
"Pekerja kurang ajar," keluh Sungchan, yang lantas mempersilakan dirinya duduk sebab tak kunjung mendapat undangan. "Harus ada alasan bagus mengapa kau mengabaikan ayam-ayam. Beri aku satu."
"Aku sedang malas."
"Kau benar-benar minta dipecat, ya?"
"Tidak enak badan." Jimin mencoba lagi.
Menyandarkan kepalanya ke dinding, Sungchan tersenyum lebar. "Aku bisa melihat kau sebugar kuda yang hendak berlomba di pacuan. Ada apa, Jimin?"
Dari luar, penyataan itu mungkin benar. Namun di dalam, Jimin merasa kacau balau. Dia adalah kuda pacuan yang paling tidak berpeluang menang. Isi benaknya terlalu tak keruan. "Sungchan," bisik Jimin, amat pelan. "Aku—aku ingin berhenti."
"Dari pekerjaan?"
Tawa Jimin pecah berderai. "Sungchan, ayolah. Kau tahu maksudku."
Sungchan memang tahu, dan dia juga tahu bahwa itu bukan keputusan impulsif. Jika Jimin memutuskan sesuatu, bisa dipastikan itu sudah dipikirkan matang-matang. "Apakah itu menjadi terlalu berat, Jimin?"
"Barangkali. Entahlah. Menurutku ...."
"Ya?"
"Ini tidak akan berhasil." Jimin mengamati respons Sungchan dengan seksama, seolah dia tersesat dan Sungchan adalah peta yang akan membantunya kembali menemukan arah yang tepat. "Aku minta maaf, Sungchan. Semua kerja kerasmu—"
"Bukan hanya aku."
"—Menjadi sia-sia. Dan itu buruk sekali. Aku menyesal. Kau sudah berkorban banyak waktu dan tenaga. Kau berharap. Kau menunggu dengan sabar selama ini. Semusim penuh dan semuanya ... Sia-sia. Itu—itu—"
"Jimin." Sungchan menghentikan racauan sahabatnya dalam sekejap, memakai satu kata. "Kaulah yang lebih banyak berkorban. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Bukan aku yang pergi ke hutan tiap dua-tiga hari dalam sepekan."
Jimin hampir setiap hari ke hutan—Sungchan hanya tidak mengetahuinya.
"Bukan aku pula yang diam-diam sering mengambil ginseng dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk membayar senjata-senjata kita. Dan jelas bukan aku yang harus berurusan dengan makhluk-makhluk itu. Kau ingin berhenti? Baiklah. Tak perlu merasa bersalah."
"Itu saja? Kau bahkan tidak bertanya kenapa?"
Sungchan mengelus dagunya. "Ceritakan lagi tentang kenalanmu di hutan."
"Namanya Jeno. Dia bilang padaku itulah namanya."
"Jeno ...."
Jimin menyeret dirinya duduk di sisi yang berlawanan dengan Sungchan, supaya bisa berhadapan dengannya. "Dan, Sungchan, dia sangat bodoh. Jeno memercayaiku sejak awal. Dia tertarik pada manusia. Di pertemuan ketiga atau keempat, dia berhenti membawa belatinya karena dia kira itu membuatku takut. Aku punya ratusan kesempatan untuk membunuhnya."
"Yang tidak kau lakukan."
"Yang tidak kulakukan. Ya." Jimin mengangguk. "Karena dia terlalu bodoh, kau mengerti? Dia menelan semua kebohonganku seperti dia menelan makanan yang kubawakan, padahal aku bisa saja meracuninya. Dia bercerita padaku tentang kakaknya. Dia tidak curiga. Dia tidak pernah menyakitiku. Bodoh, kan?"
"Sungguh kebodohan yang sangat bodoh."
"Dia orang bodoh paling bodoh yang pernah kutemui."
Mereka saling lirik selama beberapa saat usai melontarkan lelucon yang tak disengaja itu, kemudian kompak menyeringai. Dua-duanya.
"Takkan ada yang mencarinya kalau dia hilang, Sungchan. Jeno melanggar peraturan sakral dengan tidak membunuhku. Kakaknya tidak menyukainya. Rekannya bersikap sinis pada kami. Aku khawatir bila meneruskan rencana, kita tidak akan memperoleh apa-apa."
"Itulah kenapa menurutmu ini tidak akan berhasil."
Kedua telapak tangan Jimin menyatu di pangkuannya. "Ini jalan buntu."
Setelah itu keduanya tenggelam dalam kebisuan. Tali topi Sungchan bergoyang-goyang. Waktu berlalu, ditandai dengan secercah sinar matahari yang menerobos lewat jendela—mengumumkan hadirnya satu lagi hari musim semi yang indah. Musim yang, tidak seharusnya dilewati dengan bermuram durja.
Tiba-tiba Sungchan berdiri. Tangan kirinya—karena Sungchan kidal—terjulur, terbuka. "Kau mau berkuda denganku?"
"Berkuda? Bagaimana dengan ayam-ayam?"
"Mereka akan terlambat sarapan, sepertinya."
Jimin menengadah, tak segera menerima atau menolak. Sungchan menjulang di depannya sementara dia duduk meringkuk, berpendapat dirinya tak pantas dimaafkan. Sungchan ibarat musim panas, dan Jimin merupakan si gadis musim dingin yang meleleh terkena kehangatannya. Siapa bilang mereka tidak bisa berdampingan?
Dengan cepat Jimin mengepang rambutnya dan menyematkan pita. Tanpa ragu disambutnya tangan Sungchan. "Marilah. Berkuda adalah ide bagus mumpung hari ini cerah."
.
.
.
Mengurus ayam-ayam mungkin pekerjaan yang kotor, sekaligus juga mudah.
Biasanya Jimin datang di jam ketika ayam-ayam itu menyelesaikan paduan suara mereka—demi kesehatan telinganya. Makanan ada di gudang di rumah Sungchan. Minuman bisa diambil di sumur yang bisa dicapai dengan berjalan kaki singkat. Telur selalu menjadi prioritas. Kumpulkan mereka dalam ember yang dasarnya diberi setumpuk jerami. Berikutnya fokus pada yang kecil-kecil sambil memeriksa apakah ada yang sakit—pisahkan yang sakit jika itu terjadi. Dilanjutkan bersih-bersih dan pengiriman.
Jimin telah melakukannya sejak usianya sembilan tahun dan dia menemukan bahwa pekerjaan bisa mengalihkan pikirannya dari hampir apa saja. Bekerja adalah pilihan utama saat dia butuh distraksi, dan selama beberapa hari, itu berfungsi dengan baik. Lagipula, sulit memikirkan apapun dengan lusinan ayam yang ber-petok-petok di sekelilingmu. Demi Tuhan, mereka berisik! Namun Jimin ingat dia merasa damai setelah berhenti ke hutan dan tak harus membohongi siapa-siapa.
Lalu sore itu tiba—sore yang berbeda.
Jimin tengah mengantongi upah dari bibi pemilik restoran ketika keributan menghampirinya. Seorang warga, yang kerap meramalkan hari kiamat, terhuyung-huyung duduk di bangku dan melapor bahwa dia melihat sesuatu yang aneh di tepi hutan. Tubuhnya yang bau alkohol membuat kredibilitasnya patut dipertanyakan. Akan tetapi tak lama kemudian beberapa warga lain tergesa-gesa berlari melintasi restoran, dan pemabuk itu mengakhiri ucapannya dengan, "Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri!"
Jimin yang skeptis memutuskan menuruti nasihat itu. Dia ikut berlari sembari membayangkan satu nama dan hal bodoh yang mungkin pemilik nama itu lakukan. Di pinggir desa yang berbatasan dengan hutan, Jimin berhenti. Di sana sudah ada beberapa tetangganya yang menunjuk-nunjuk sebuah pohon.
Para wanita memeluk diri mereka sendiri, merinding menyaksikan keanehan terbaru hutan terkutuk dan buru-buru menggiring anak mereka pergi—takut itu membawa sial. Para pria saling sikut, bicara pada saat bersamaan yang berkisar pada "Dulu pernah ...." atau "Aku dengar ...." dan ditutup dengan kalimat, "Hutan itu selalu jadi tempat yang mengerikan!" atau semacamnya.
Jimin satu-satunya orang yang lebih dominan menyerap kejadian itu dengan mata dibanding mulutnya. Dia menatap pohon yang menciptakan kehebohan itu, lidahnya kelu. Sebab di salah satu cabang tertingginya, diikat erat agar mampu melawan terpaan angin, terdapat selendang biru yang dia berikan pada Jeno. Tepat di depan mata. Sangat mencolok. Itu pesan yang gamblang bagi mereka yang memahaminya. Mereka yang tak lain adalah Jimin dan—
"Kutebak itu artinya dia ingin bertemu denganmu?"
Sungchan.
Jimin menoleh. Bayangan mereka jatuh saling menimpa. "Aku tidak tahu apa-apa soal ini."
"Jadi itu inisiatifnya? Rupanya dia kreatif."
"Sekarang bukan saat yang tepat untuk memujinya. Bukan itu yang penting."
Sungchan menggaruk ujung hidungnya. "Memang. Yang penting sekarang adalah, apa kau akan menyampaikan pujianku padanya atau tidak?"
Dari sisi kanan Jimin, seorang pria renta yang dia kenal dari masa kanak-kanaknya bergabung dengan kerumunan. Pria yang, sepanjang ingatan Jimin, selalu berbau rempah-rempah akibat pekerjaannya sebagai tabib. Ciri khas itu belum berubah, kini dia hanya bergantung pada tongkat untuk membantunya berjalan. "Sangat aneh bukan?" tanya pria itu. Tas kain kecil yang dibawanya ketika mencari bahan-bahan pengobatan sedikit terbuka. "Kalian berdua pasti punya ingatan buruk tentang hutan itu."
Sungchan menyentuh pinggiran topinya sekilas. "Selamat sore, Tabib Yoon."
Masa lalu bukanlah topik yang ingin dibahas Jimin, jadi dia mencari-cari pengalihan. Isi tas si tabib kebetulan menarik perhatiannya, dan matanya seketika memicing. "Apakah—apakah itu daun jinshil?"
"Benar, Nak. Setetes saja bisa membuat manusia atau seekor lembu tertidur. Tapi jika terlalu banyak akan menyebabkan kelumpuhan sementara. Aku berencana memakainya untuk—"
Jimin tidak lagi mendengarkan. Dia maju demi menatap selendangnya lebih dekat. Selendang Jeno. Selendang yang berayun-ayun pelan bermeter-meter darinya dan tak pernah dia duga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan.
Sungchan menyusul, menyelipkan jari telunjuknya di jari telunjuk Jimin. Ada ceruk kecil di jari pemuda itu karena kegemarannya berlatih memanah. "Terserah padamu," ujar Sungchan netral, tanpa harapan atau larangan. "Keputusannya selalu ada di tanganmu."
Jimin tidak menjawab. Tangannya kosong. Pikiran, atau bagian yang belum selesai dari masa lalunya memangsanya seperti anjing yang lapar—dan mungkin berikut hati nuraninya.
Pesan Jeno sangat jelas.
Aku cukup putus asa untuk melakukan ini, kata Jeno melalui selendang itu, kumohon kembalilah.

Akhir2 ini inspirasi lagi kek layangan; sering nyangkut di genteng orang dan susah diambilnya, makanya update lama.gg 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top