09. Sembilan Tahun Lalu I
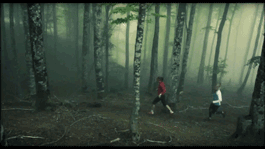
"Ayah?"
Bilah tajam kapak berkilau tertimpa cahaya matahari, lalu terayun mantap membelah gelondongan kayu jadi dua, tepat di tengah.
"Ayah!"
Yoo Minjoon meletakkan kapaknya di tanah, lantas meregangkan punggung dan mengusap keringat di dahinya. Di kakinya, terdapat potongan-potongan kayu yang dia persiapkan untuk musim dingin yang akan datang. "Ya, Tuan Putri?"
Putrinya tersenyum. Selalu begitu saat dipanggil dengan nama tertentu. Jimin di usia sembilan tahun, duduk di bangku di halaman rumahnya dengan selendang biru ibunya yang melilit lehernya. "Ada apa dengan ibu?"
"Ada apa dengan ibu?"
Jimin memberengut. "Ayah, jangan bercanda. Ayah tahu maksudku. Akhir-akhir ini ibu terus batuk dan tidur lamaaa sekali. Apa ibu sakit parah?"
"Dia ...." Kapak yang Minjoon gunakan memantulkan ekspresinya yang resah. Matahari kala itu bersinar terik, tetapi Minjoon tidak tahu yang manakah yang membuatnya berkeringat antara matahari itu atau pertanyaan putrinya. "Ibu akan baik-baik saja." Dia meringkas. "Ibu hanya sedikit kurang sehat." Cari aman一siasat yang akrab bagi Jimin setelah dewasa.
"Sudah coba memberi ibu jahe? Aku bisa membelikannya. Jika dicampur dengan serai, khasiatnya akan bertambah."
Sang ayah tertawa. "Dari mana kau mengetahuinya?"
"Buku Sungchan. Dia yang membaca," imbuh Jimin cepat-cepat. "Sungchan menjadi lebih pandai sekarang. Dia bisa membaca sangat fasih. Koleksi bukunya juga banyak. Sekarang ini Sungchan sedang belajar tentang pengobatan. Apa ayah tahu ekstrak daun jinshil¹ bisa membuat manusia dan hewan apapun tertidur meski hanya beberapa tetes?" Jimin berbaring di bangku, pura-pura mendengkur, lalu menatap tajam ayahnya. "Buku itu menakjubkan. Tolong belikan aku satu, Tuan Minjoon yang tampan."
"Rayuan, rayuan." Minjoon berdecak. Dia menghampiri Jimin dan mengepalkan tangan di atas perutnya. "Siapa nona cantik ini dan kenapa dia sangat mahir merayu pria? Apa ini Jimin kecilku? Coba lihat apa yang Ayah punya. Mungkin ini buku."
Pelan-pelan Jimin menepuk kepalan tangan ayahnya, mundur seraya menggigit bibir, dan menjerit kegirangan kala Minjoon menggelitiknya hingga hampir jatuh dari bangku. Pipi Jimin berubah semerah apel yang matang. Dia menggeliat. Namun selalu, ketika sedikit lagi jatuh, Minjoon menangkapnya di saat yang tepat dan memeluk Jimin, mengurungnya dalam jenis rasa nyaman yang tak bisa dia temukan pada siapa-siapa bertahun-tahun kemudian. Jimin merasakan kecupan di puncak kepalanya.
"Maafkan Ayah, Nak. Maafkan pula dunia ini yang tidak ramah pada perempuan. Bahkan walau Ayah punya uang, Ayah tak yakin ada cara agar kau bisa belajar seperti laki-laki."
"Karena perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan itu bodoh."
"Siapa yang mengatakannya?"
"Guru Sungchan saat mendengar Sungchan mengajariku." Jimin mendongak dalam dekapan Minjoon. "Setelah itu Sungchan marah dan tidak mau menemuinya."
Minjoon memeluk Jimin lebih erat. "Tidak, tidak. Baj一dia salah. Laki-laki dan perempuan sama saja. Kecerdasan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Kau tidak bodoh, anakku, kau hanya tidak mendapat kesempatan. Suatu hari kesempatan itu akan tiba. Mungkin bukan besok atau lusa, atau bahkan 100 tahun lagi, tapi Ayah yakin hari ketika orang seperti mantan guru Sungchan menyadari kesalahannya pasti akan datang."
"Juga bukan hari ini?"
Dengan kelembutan yang hanya bisa dilakukan seorang ayah, Minjoon membelai pipi Jimin dan mencubit batang hidungnya. "Hari ini Ayah terlalu sibuk untuk mengajak orang itu berkelahi. Ayah harus pergi ke hutan, mencari ginseng."
"Bukannya kemarin sudah?"
"Kemarin Ayah hanya memperoleh ginseng muda yang harganya murah. Itu akan memberi kita makan, tapi tidak cukup untuk membeli obat yang bagus. Bekerja mengurus kuda Tuan Jung rupanya masih kurang, dan kami berniat mencarinya di hutan."
Mulut Jimin terbuka lebar tanpa sengaja. "Apa yang Ayah bicarakan adalah hutan terkutuk? Tidak! Jangan, Ayah!"
"Kami harus mencoba, Jimin. Karena jarang dimasuki, Ayah yakin banyak ginseng liar yang bisa dipanen. Tuan Jung sudah berbaik hati menemaniku一dan omong-omong, itu dia, bersama Sungchan."
Sepasang pria dewasa dan pria muda yang lebih kecil berjalan beriringan dari jalan masuk. Salah satunya melambai, membawa buku yang dijepit di lengannya. Jimin mengabaikan mereka, malah menarik lengan pakaian ayahnya. "Itu berbahaya. Bagaimana kalau Ayah tidak pulang?"
Menyadari putrinya khawatir, Minjoon menyejajarkan matanya dengan mata Jimin dan tersenyum. Dua wajah yang mirip bertemu. Alis tipis yang sama. Bibir mungil yang sama. Mata Jimin hanya sedikit lebih lebar, dan di momen ini, digenangi kekhawatiran. "Itu tidak akan terjadi. Rencana Ayah adalah mengambil beberapa ginseng, menjualnya di Hanyang, membeli obat dari tabib terkenal untuk ibumu, dan sebuah buku." Dia berkedip penuh arti. "Mungkin juga hanbok sutra, siapa tahu? Tak perlu khawatir. Ayah janji akan pulang, Nak."
Pembohong. Itu kebohongan terbesar yang Jimin dengar dari ayahnya.
.
.
.
"Mau belajar membaca sekarang, Jimin?"
Yoo Jimin mengerucutkan bibirnya, dan menggeleng一yang mengejutkan Sungchan. Biasanya Jimin selalu senang belajar, alih-alih uring-uringan. Padahal bukannya tidak mau, Jimin hanya tengah memikirkan pesan ayahnya yang meninggalkan sekeping koin untuknya dan menyuruh Jimin membeli "apapun yang tidak membuat sakir gigi". Mereka berangkat setengah jam yang lalu. Anak kecil tidak boleh ikut. Menyebalkan!
"Apa menurutmu mereka sudah sampai di hutan, Sungchan?"
Sungchan yang di usia delapan tahun tumbuh lebih tinggi dari Jimin turut menggeleng. Keduanya duduk di bangku tempat sebelumnya ayah Jimin berada. "Aku tidak tahu."
"Kau tidak cemas?"
"Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku cemas ayah kita dimakan harimau."
"Bukan roh hutan?"
"Roh hutan juga. Konon, siapapun yang masuk ke sana takkan bisa pulang. Mereka yang pulang takkan pernah jadi orang yang sama."
Jimin berpikir keras. "Kalau roh hutan dan harimau bertengkar, siapa yang akan menang?"
"Aku tidak tahu," ulang Sungchan. "Aku belum pernah bertemu keduanya. Kuharap tidak selamanya."
Wajah Jimin mendadak berubah cerah, dan dia mengemukakan ide cemerlangnya. "Kalau begitu ayo kita susul mereka! Ke dalam hutan!"
Atau mungkin tidak terlalu cemerlang, sebab Sungchan terperangah. "Jangan, Jimin. Ayah menyuruh kita tinggal. Mengapa kita tidak beli sirup saja atau makanan lain?"
Alis Jimin naik, dua-duanya. "Kau takut, ya?"
"Tentu saja tidak!" seru Sungchan buru-buru.
Jimin sengaja tersenyum mengejek. "Tentu saja iya. Aku tidak mengira kau ternyata penakut, Tuan Muda."
"Mana ada! Jangan aneh-aneh一"
"PE-NA-KUT! Sungchan penakut!" Lidah Jimin dijulurkan. Dia bertepuk tangan. "Huu, dasar penakut. Sungchan sama saja dengan bayi."
"Aku一" Sungchan hendak membantah, lalu berakhir menghela napas. Dia berpaling ke arah yang ditempuh ayahnya dan menatap pohon tertinggi hutan terkutuk yang bisa diintip dari tempatnya duduk. Rumah Jimin yang dekat dengan hutan memungkinkannya berbuat begitu. Menghentikan Jimin一itu yang tidak mungkin. Lagipula, Sungchan juga penasaran. "Baiklah, baik. Kita susul mereka. Tapi kalau ada apa-apa, aku akan bilang ini idemu. Jangan一"
Bila Sungchan ingin menyelesaikan ucapannya, dia terlambat; Jimin terlanjur melompat turun dari bangku. Gadis cilik itu melesat riang ke rumahnya bak angin puting beliung, dengan rok dan selendang yang berkibar-kibar. Di dalam, Jimin mengambil segenggam garam dan memasukkannya ke kantong kain kecil, dilanjutkan mengisi segelas air dan membawanya ke kamar orang tuanya. Ibunya berbaring di kamar itu sendirian, nyaris terkubur di bawah selimut yang menutupi tubuhnya. Setelah sekitar sepekan sakit, Jimin tidak percaya seberapa drastis kini bobot ibunya berkurang.
"Ibu?"
Ibunya mengerjap, kesusahan untuk sekadar mengangkat kepala. "Ya, Nak?"
Dengan hati-hati, Jimin meletakkan gelas di samping bantal sang ibu. "Boleh aku bermain dengan Sungchan?"
Batuk. Ibunya menekankan sapu tangan ke mulutnya, dan selama semenit, Jimin berdiri kaku di situ tanpa tahu harus berbuat apa. "Tentu saja, pulanglah sebelum gelap."
Sapu tangan itu menarik perhatian Jimin. Ada noda merah di sana yang bisa jadi berasal dari motif bunganya atau ... Sesuatu yang lain. Jimin jadi ragu-ragu. "Aku mengerti, Ibu. Apa Ibu butuh hal lain?"
"Hanya istirahat. Terima kasih untuk airnya, anak manis."
Bibir Jimin melengkung membentuk senyuman. "Jangan lupa minum supaya tenggorokan Ibu tidak sakit." Lantas dia menutup pintu.
Sungchan telah menunggunya begitu Jimin keluar, memeriksa kantong yang dia bawa, dan mengerutkan kening. "Bukankah garam hanya ampuh untuk mengusir hantu?"
"Memangnya kau tahu perbedaan hantu dan roh hutan?" balas Jimin tak mau kalah.
Satu serangan itu membuat Sungchan menyerah. Mereka langsung saja berangkat daripada berdebat sia-sia一waspada, gugup, dan bersemangat sebagaimana yang dirasakan anak-anak kala melanggar peraturan. Belum pernah ada yang senekat ini sebelumnya! Para orang tua selalu melarang anak mereka ke hutan, meski sebenarnya itu tidak diperlukan. Tampilan luar hutan itu sudah cukup membuat anak-anak gentar. Jimin menelan ludah. Paling tidak, ini akan menjadikan mereka anak-anak paling berani di desa.
Sungchan bergerak-gerak gelisah. "Jimin, cuma mau mengingatkan, kita masih bisa berputar balik."
Jimin menyikutnya. "Jangan bersikap seperti anak-anak begitu," kata Jimin membingungkan. Dia menggenggam tangan rekan seperjalanannya. "Dan tidak perlu takut, aku bersamamu."
"Kau tidak takut?"
"Tidak."
Mereka kemudian melangkah memasuki hutan. Langkah pertama yang menakutkan. Mereka bahkan kompak menutup mata, membayangkan akan disergap ular raksasa, beruang (kalau ada) atau harimau yang ganas. Namun tidak ada apapun. Tidak ada pula yang menghentikan mereka. Desa tertinggal jauh di belakang. Maka Jimin membuka matanya, mendongak, dan terpana. "Wow. Aku tidak sadar betapa tinggi pohon-pohon di hutan ini."
Hutan tanpa nama itu membentang di hadapan mereka, luas dan seolah terkurung dalam kegelapan abadi meski malam belum lagi tiba. Setiap batang pohon berkali-kali lipat lebih tinggi dari mereka, dari para ayah juga! Tanah di bawah kaki mereka dihiasi kerikil dan ranting. Jalan setapak yang ada di desa, di sini lenyap. Akan mudah sekali kehilangan arah di hutan itu, tetapi karena malam sebelumnya hujan turun, keduanya bisa melihat jejak kaki ayah mereka seperti tanda untuk terus maju.
Sungchan merapat pada Jimin. "Kau ingat kakak Hanrim yang baru pulang dari Tamra?"
Jimin berbisik. "Kenapa dengannya?"
"Dia pernah bercerita kalau saat kecil dia pernah bertemu roh hutan, dan dia bilang mereka punya cakar yang tajam. Dan taring. Dan tubuh yang bungkuk. Rambut mereka awut-awutan. Sedangkan mata mereka melotot一"
"Sungchan?"
"Ya?"
"Hentikan." Jimin mendelik galak. "Kau membuatku takut."
Sungchan meliriknya. "Kukira kau tidak takut."
"Sedikit saja. Tidak sebanyak kau. Ayo."
Mereka berjalan lagi. Seharusnya tidak. Dua anak kecil itu, dengan bahu yang tegang berdempetan, mengendap-endap di hutan yang hanya dimasuki segelintir manusia dalam beberapa dekade. Wajah mereka tersembunyi di balik topeng keberanian palsu一milik Jimin, entah bagaimana, lebih meyakinkan. Sungchan ingin menjadi sepertinya; lebih berani, lebih tangguh. Namun Sungchan tidak tahu bagaimana cara untuk tidak bersikap seperti anak-anak. Dia belum berpengalaman jadi orang dewasa. "Ke mana mereka pergi?"
"Ssssttt!"
"Kenapa aku tidak boleh bicara?"
"Nanti harimau dengar. Ikuti saja jejak kakinya, Sungchan."
Itu masuk akal bagi Sungchan, akan tetapi penyebab Sungchan bungkam bukanlah harimau, melainkan pemandangan yang sangat berbeda. Insting Sungchan seketika bereaksi, dan dia memeluk Jimin agar menunduk ke semak-semak. Ke tempat yang akan menyembunyikan tubuh mereka dengan baik asal mereka duduk sambil menekuk lutut, dan menjadi amat, sangat, diam. Jimin cukup pintar untuk tidak memberontak一sebagian karena kaget, sebagian karena tidak sempat bereaksi. Kantong garamnya yang terbuka tumpah, isinya berhamburan. Selendang birunya terkulai di tanah.
"Ada apa?"
"Diam, Jimin, diam. Lihat." Sungchan menunjuk ke depan.
Di depan, adalah pemandangan yang kelak akan menghantui mimpi buruk Jimin dalam waktu yang lama. Di depan, tampak Yoo Minjoon dan Jung Sanghyeon yang bersimpuh, tangan kedua pria itu terangkat sejajar dengan kepala. Sementara seorang pria asing berpostur tanggung berdiri dengan angkuh, mengawasi. Baik Jimin atau Sungchan tidak melihat wajahnya karena pria itu membelakangi mereka. Rambut gelapnya yang panjang terurai di punggungnya yang tegap.
Pria asing kedua berdiri lebih dekat dengan anak-anak, dan karena itu dia terlihat jelas. Bahasa tubuhnya menunjukkan keengganan. Dia lebih tinggi, dan rambutnya, walaupun sama-sama panjang, sewarna dengan api. Telinganya runcing tidak biasa. Dan saat dia tiba-tiba menoleh, Jimin mengamati bahwa matanya berwarna biru. Membara. Hidup. Dalam. Warna biru api yang paling panas. Pria api melangkahkan kakinya. Dia celingukan. Kepalanya miring ke satu sisi.
"Doyoung?" tanya si rambut gelap.
Si "Doyoung" ini memandang persis ke tempat persembunyian Jimin dan Sungchan. "Sepertinya aku mendengar sesuatu."

¹Cuma rekaan.
Rambut "api" Doyoung di bayangan gua, dan ya, ini emang gif prasejarah :
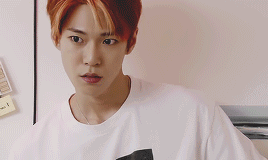
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top