03. Namamu
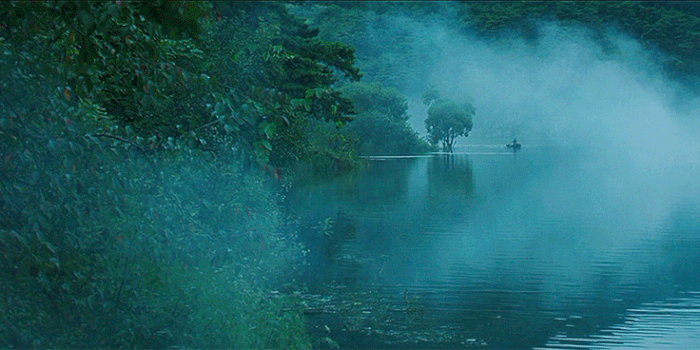
Langit berubah cerah.
Tanah hutan kembali mengeras.
Satu lagi hari yang panjang di mulai.
Mungkin akan jadi lebih panjang kalau satu-satunya temanmu justru tidak mau bicara denganmu. Baiklah, pikir Jeno, terima saja. Tak ada yang bisa dilakukan soal itu. Dia cukup mengenal Aeri untuk tahu bahwa Aeri tidak bisa dibujuk. Cara terbaik menangani kemarahan Aeri adalah menjadi sediam batu, tidak membuat masalah baru, sampai hati Aeri tergerak memaafkannya. Lagipula memang dia yang salah. Pokoknya terima saja.
Jeno menghirup napas dalam-dalam, membiarkan aroma hutan yang khas mengisi dadanya. Sesuatu yang tidak berubah dari hutan ini adalah kabutnya. Kabut tebal memenuhi hutan dari segala penjuru, begitu padat hingga nyaris terkesan bisa disentuh. Layaknya tirai, menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Satu rahasia bahkan dianggap sangat berharga, dan karena itulah Jeno di sini sekarang. Makan apel, kunyah, telan. Dia berharap bisa menghancurkan kebosanan seperti dia menghancurkan daging apelnya, yang dalam cahaya fajar berwarna seputih salju yang akan datang. Apel dari rumah. Yum yum. Tak ada duanya.
Selain karena reputasinya yang telah melegenda, Jeno percaya alasan lain manusia enggan mengunjungi hutan adalah kabut ini. Tak akan ada yang secara sukarela memasuki sebuah tempat dimana jarak pandangmu tak lebih dari dua meter一tiga paling banyak. Berkali-kali Jeno menyaksikan manusia-manusia berdiri di pinggir hutan, mengumpulkan keberanian, maju selangkah, kemudian balik kanan dan bubar. Seringnya sambil tertawa atau saling mencemooh一tergantung siapa yang kau ajak. Kebanyakan adalah remaja-remaja yang menganggap itu permainan atau cara untuk membuktikan siapa yang paling bernyali di antara mereka.
Aneh. Jeno tak mengerti apa asyiknya permainan itu. Tidak ada anak dari bangsanya yang akan memandang pemukiman manusia sebagai arena bermain yang menyenangkan. Terlalu berbahaya. Dia sendiri tak pernah keluar dari hutan一seumur hidupnya. Pengetahuannya tentang manusia sebagian besar diperoleh dari cerita mulut ke mulut atau pengamatan dari jauh.
Sampai gadis itu muncul.
Jeno menggigit apelnya lagi. Sari apel itu membasahi bibirnya kala dia menyunggingkan senyuman. Dia tak terlalu memikirkan kejadian itu semalam, tapi setelah dipikir-pikir, gadis itu lucu juga. Caranya berlari tergopoh-gopoh dengan hanbok kuningnya ... Jeno terkekeh. Gadis itu terlihat menyerupai anak bebek yang panik! Terlalu buruk itu menjadi pertemuan pertama dan terakhir mereka.
Atau begitulah yang Jeno duga.
Semenit belum berlalu ketika hal itu terjadi. Jeno baru akan menandaskan apelnya ketika suara itu, kecil dan gemetar, menyapa pendengarannya, disusul langkah kaki yang dimotivasi keragu-raguan.
"Halo? Emm, halo? Apa kau, eh, di sini?" Suara gadis itu bergema di hutan yang sepi, dipantulkan pepohonan, dan menyebar hingga bukan tidak mungkin didengar rakun yang tuli. Gadis itu buru-buru menutup mulutnya, terkejut sendiri.
Jeno meringis. Makhluk itu masih seribut sebelumnya. Hanya kali ini dia memakai pakaian berwarna merah muda. Pertanyaannya, mau apa dia kemari?
Gadis itu berdeham. "Mata hijau! Tuan Mata Hijau, kalau kau mendengarku dan kebetulan ada di sekitar sini, bisa tidak kau menjawabku?"
Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Yang pasti gadis itu tidak bisa lebih spesifik. Jeno bisa merasakan tatapan bingung Aeri yang pasti juga melihat gadis itu. Untuk sejenak, mereka sama-sama tak tahu harus berbuat apa pada makhluk cantik yang agaknya tidak berniat segera pergi ini.
"Aiiish!" Gadis itu bersungut-sungut. "Padahal telinganya lebar tapi kenapa kemampuan mendengarnya payah? Atau jangan-jangan kemampuan mendengarnya payah karena telinganya lebar?"
Terlepas dari situasinya, Jeno hampir tertawa.
Gadis itu mencengkeram tepian roknya erat-erat, siap diangkat untuk kabur pada waktunya. "Tuan, aku datang dengan damai. Aku tidak bermaksud mengganggumu atau apa, aku hanya ingin bicara!" Lalu, lebih pelan, "Tolong jangan biarkan aku jadi orang bodoh yang bicara dengan pohon."
Permintaan dikabulkan. Jeno menghabiskan apelnya, mengantongi tangkai apel itu untuk dibuang nanti, dan sebelum Aeri bisa memberitahunya untuk bertindak bagaimana, dia meluncur turun dari tempatnya一sepuluh langkah di belakang gadis itu. "Kau mencariku?"
Gadis itu berbalik dengan wajah ngeri. Dalam keterkejutan, dia mundur menjadikan jarak di antara mereka sebelas langkah. "Demi bintang-bintang! Astaga. Astaga! Kau mau aku kena serangan jantung, ya?"
Serangan jantung apa? Jeno tak yakin dia paham maksudnya. Dia tersenyum, berupaya tampak tidak mengancam. "Maaf."
"Kurasa kau punya bakat mengagetkan orang lain, Tuan. Kau ahli mengendap-endap. Tapi sudahlah, lupakan saja. Bagaimana pun, aku senang kau一"
Sekelebat gerakan tak jauh dari sini. Di selatan. Itu dia一pohon beech di sana, yang dahannya tumbuh berkelok-kelok tak terkendali. Salah satu rantingnya bergeser, menggugurkan beberapa helai dedaunan, yang akan dikira manusia sebagai pengaruh angin belaka. Bukan. Aeri mengintip dari sana. Jeno bisa membaca ekspresinya sama halnya bila mereka duduk bersebelahan. Apa yang kau lakukan, Jeno?
Jeno memandang Aeri dan gadis itu bergantian. Temannya dan manusia asing ini一yang kikuk, berisik, dan masih terus mengoceh. Keduanya bukan perbandingan yang adil. Mendekati pun tidak. Aeri mampu melumat gadis ini dalam sekejap, tanpa menyentuhnya. Punggung gadis ini akan jadi sasaran yang mudah; bagai undangan yang terbuka. Jika Aeri ingin一jika Aeri memang menginginkannya ....
Jeno berkedip. Mendadak dia sadar betul posisi mereka. Detik itu pula dia mengambil keputusan. Jeno meraih tangan gadis itu, menariknya menjauh dari Aeri dan panahnya. "Ikutlah denganku!"
"Tunggu, kita mau ke mana? Hei一"
Jangan halangi aku, Aeri berpesan kemarin.
Maka Jeno berlari, lebih lambat一jauh lebih lambat一dari yang bisa dia lakukan, agar si gadis kikuk tidak tertinggal. Dia memandu gadis itu melewati jalur yang becek, memperingatkannya terhadap bebatuan yang bisa jadi sandungan, dan cabang-cabang pohon yang terlalu rendah.
Apa yang kau lakukan, Jeno?
Dan dalam hati Jeno menjawab, aku tidak tahu, Aeri. Aku benar-benar tidak tahu.
.
.
.
Tepi sungai adalah tempat terbaik yang terpikirkan oleh Jeno dalam waktu singkat.
Secara resmi, bangsanya menyebut itu sungai Edra, tapi barangkali manusia punya sebutan lain. Edra bukan sungai yang luas. Lebarnya sekitar tiga meter, tetapi memanjang hingga nyaris mencakup seluruh wilayah hutan, dengan formasi melengkung tak beraturan seperti sabuk. Airnya yang jernih juga tidak dalam, kira-kira setinggi pinggang orang dewasa. Kalau melongok dari tepiannya, kau bisa melihat bagian dasar sungai itu yang berhias kerikil dan terkadang ikan yang melintas, menjadikan Edra tempat yang ideal untuk memancing, lokasi bermain anak-anak, atau memandikan kuda.
Ketiganya belum pernah dilakukan.
Satu-satunya tujuan Aeri mendekati sungai Edra hanyalah mengisi kantong minumnya. Jeno, sebaliknya, sering duduk di sana menikmati musik yang dihasilkan percikan air. Melamun, istilah lainnya, yang oleh Aeri dianggap kegiatan tak berguna. Namun Jeno tak bisa disalahkan; Edra diapit pohon-pohon berbatang tebal dari kedua sisi. Formasi pepohonan itu, bila dimanfaatkan dengan baik, bisa menyembunyikan nyaris apa saja. Dengan kata lain, itu tempat yang cocok untuk melakukan dosa besar, misalnya berbincang dengan manusia. Jeno menelan ludah. Dosa yang tak termaafkan.
Dia mencoba mengabaikan bayangan kemarahan kakaknya seandainya tahu perbuatannya. Kakaknya tidak akan sekadar marah一dia pasti murka. Sejak dulu kakaknya itu terkenal dengan temperamen keras yang tidak bisa dilunakkan oleh siapapun, dan sudah lebih dari sekali Jeno menjadi sumber kemarahannya. Kendati demikian, Jeno memastikan gadis itu berdiri membelakangi pohon dan hanya pohon saja, memperkecil risiko dia tertembak panah sebelum mereka sempat bicara. Bicara. Apa bahayanya?
"Nah, kita bisa bicara di sini sekarang."
"Kenapa di sini?" Gadis itu bertanya-tanya.
Jeno menelengkan kepala, berusaha mendengar suara-suara yang tidak biasa. Apakah Aeri mengikuti mereka? Sepertinya tidak. "Kau tidak suka tepi sungai?"
"Bagiku hutan ini sama saja dari segala sisi. Semua serba hijau. Atau dalam kasus ini, kecokelatan."
"Seperti mataku?"
Gadis itu tersipu-sipu. "Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Aku hanya ingat warna matamu sebagai ciri fisikmu yang menonjol."
"Jeno."
"Apa?"
"Aku tidak keberatan dengan Tuan Mata Hijau, tapi kau boleh memanggilku Jeno."
"Oh." Bibir gadis itu mengerucut. "Belum pernah dengar seseorang dengan nama seperti itu."
"Inikah yang ingin kau bicarakan denganku? Namaku?"
Pipi gadis itu bersemu merah. "Bukan. Tentu saja bukan. Maafkan aku. Kebiasaan melanturku sulit diobati. Aku ke sini untuk berterima kasih atas pertolonganmu kemarin."
Ketegangan Jeno menguap. Dia menghadap gadis itu dengan bahu turun, lebih santai. "Itu bukan apa-apa. Kau sudah mengatakannya."
"Benar, setelah itu berlari seperti orang tolol." Dia memutar bola mata. "Tingkahku sungguh tidak sopan. Harap jangan anggap itu mewakili seluruh manusia. Aku akan menendang diriku sendiri jika bisa. Padahal kalau tidak ada kau, aku mungkin menderita patah tulang atau cedera yang lebih parah. Salahku."
"Bukan apa-apa," ulang Jeno.
"Kau terlalu baik untuk tertawa. Aku tahu kau sebenarnya ingin tertawa kan?" Di luar kendalinya, Jeno memang ingin tertawa, yang dia samarkan dengan senyum tipis. Gadis itu mendesah. "Ayo, tertawa saja. Aku tidak akan tersinggung. Manusia pasti akan tertawa, dan tidak aneh roh hutan memiliki selera humor yang sama."
Pernyataannya membangkitkan keingintahuan Jeno. "Mengapa tidak?"
Gadis itu bimbang. "Yah, kau tampak cukup mirip dengan kami, selain gaya berpakaianmu, gaya rambutmu, dan .... " Dia memberi isyarat ke telinganya. "Itu. Telingamu一apakah itu asli?"
"Mungkin ini aksesoris yang kutempelkan di samping kepalaku," jawab Jeno iseng.
"Bolehkah aku ....?" Gadis itu mengepalkan dan melonggarkan jemarinya berulang-ulang. Dia menyeret kakinya maju selangkah, kemudian dua, sampai dia dan Jeno berhadapan, dan Jeno bisa menghirup aroma rambutnya. "Hanya sebentar," janjinya. Jeno diam saja. Jari gadis itu menyentuh telinga Jeno, di mulai dari bagian belakang一rasanya geli dan tidak sehalus yang dia kira一lantas naik menuju ujungnya yang runcing. Gadis itu berlama-lama di sana, menyusuri telinga Jeno seakan itu peta, seakan ingin menentukan apakah ujung itu tajam atau tidak. Jeno bergerak sedikit, dan dia langsung terlompat mundur.
"Astaga, kau benar-benar roh hutan!" Dia mondar-mandir. "Selama ini aku sudah sering mendengar tentangmu一sejak aku kecil一tapi aku selalu menyangka itu dongeng atau rumor yang dilebih-lebihkan. Kau tahu kan bagaimana penduduk desa bergosip?" Jeno tidak tahu.
"Apakah kau menceritakan pertemuan kita pada orang lain?"
Gadis itu berhenti berjalan一yang merupakan ide bagus karena Jeno dibuat pusing一dan sebagai gantinya menggigiti kuku jempolnya. "Tidak. Apa kau ingin aku merahasiakannya?"
Jeno mengangguk. "Ya, tolong."
Pada saat itulah gadis itu melihat belati Jeno di pinggangnya. Alisnya berkerut, dan wajahnya yang semula takjub kembali diselimuti rasa takut yang kemarin membuatnya lari tunggang langgang. Dia menjadi gelisah, seolah baru menyadari bahwa dirinya tidak hanya berduaan di tempat sepi bersama laki-laki asing, tapi juga laki-laki asing yang bukan manusia. "Jangan khawatir, aku pandai menyimpan rahasia." Keberaniannya surut. "Aku harus pergi."
Tak ada yang bisa Jeno katakan saat itu. Dia berniat memindahkan belatinya. Namun mengapa dia perlu melakukan itu? Pendapat manusia ini seharusnya tidak penting. Dan bagaimana jika dia mengira Jeno hendak menyerangnya? Jadi Jeno mempertahankan sikap diamnya. Dia menonton gadis itu pelan-pelan menyingkir, berubah dari gadis yang ceria menjadi gadis yang ingin pulang. Sampai Jeno teringat sesuatu. "Tunggu." Gadis itu berhenti. Tatapannya adalah tatapan seorang mangsa yang tak yakin akan nasibnya. "Apa kau punya nama?"
Gadis itu tertegun. Ekspresi takutnya terhapus dan dia mematung. Reaksi yang, menilik pertanyaan sesepele nama, terbilang tidak wajar. "Aku一aku ...."
"Apakah nama adalah rahasia bagi manusia?"
"Tidak, aku一"
"Tidak apa-apa." Jeno menenangkannya. "Itu bukan urusanku. Aku terlalu penasaran一"
"Karina!" cetus gadis itu tiba-tiba. Dia mengerjap. "N-namaku Karina. Panggil aku Karina."
Jeno tersenyum. "Belum pernah dengar seseorang dengan nama seperti itu."
Karina mengeluarkan suara tawa yang melengking tidak alami. Dia melambai canggung, lalu berlari dengan cara yang terlihat lebih lucu hari ini. Senyum tak kunjung lenyap dari wajah Jeno. Dia berbalik, berniat melanjutkan tugas yang telah dia kacaukan sedemikian rupa, sebelum sebuah panggilan memaku kakinya ke tanah. "Jeno, Jeno!" Karina kembali. Dia tersengal-sengal. Tangan berada di lututnya. "Jangan ... Pergi dulu."
"Ya?"
"Begini." Gadis itu menegakkan badan. "Dalam tradisi manusia, ketika kami berutang dalam bentuk apapun pada orang lain, kami harus membayarnya. Aku tak punya cukup uang untuk mengganti jasamu, tapi aku bisa memasak. Kalau aku datang besok, maukah kau menemuiku lagi?"
"Besok?"
"Ya. Kau mau?"
Insting pertama Jeno adalah menolak. Bagian dirinya yang waras menyarankan hal yang sama. Hentikan kegilaan ini secepatnya. Usir dia. Pakai akal sehatmu, Penjaga. Namun sisi lain yang tertarik pada manusia一atau gadis itu?一mendorongnya menganggukkan kepala. Ini ibarat berenang; apa gunanya mencelupkan satu kaki saja? "Besok ...."
Karina mengangguk bersemangat. "Aku sangat pintar memasak, kau akan lihat besok. Sampai jumpa di jam yang sama seperti saat kita pertama kali berjumpa!" Dengan itu Karina pamit. Sosoknya yang ramping meliuk-liuk di antara pepohonan. Langkahnya, kali ini, seperti lebih ringan.
Jeno menelusuri arah yang berlawanan, lupa pada segalanya selain janji yang tadi dibuat secara sepihak一kecuali entah bagaimana dia tak sengaja menyetujuinya. Dia bahkan lupa pada Aeri yang menunggunya di pohon beech tempat Jeno memergokinya一hanya turun, tidak berpindah. Dia lupa merangkai alasan. "Aeri ...."
"Tolong katakan padaku bahwa tak peduli dengan cara apa, kau berhasil menakuti gadis itu."
"Aeri."
"Katakan padaku bahwa kau sudah mengancamnya dan bahwa aku keliru menangkap basah kau tersenyum padanya."
Jeno tak kuasa membela diri.
Aeri terguncang. "Jeno, sialan, apa yang salah denganmu?"
Jeno masih tidak tahu. Dia tidak sanggup membalas baik tatapan atau ucapan Aeri. Dia menunduk, menunggu mekarnya rasa bersalah atau rasa malu atau apa saja. Namun dalam benaknya dia malah melihat gadis itu lagi; ketakjubannya saat memastikan telinganya asli, caranya menertawakan diri sendiri, senyumnya. Dan tentu saja, namanya.
Karina.
Itulah kebohongan pertamanya.

Update dalam rangka ultah Aa' Jeno hehehe 😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top