🎼 ; 𝕵𝖊 𝖙𝖊 𝖑𝖆𝖎𝖘𝖘𝖊𝖗𝖆𝖎 𝖉𝖊𝖘 𝖒𝖔𝖙𝖘 - 𝕻𝖆𝖙𝖗𝖎𝖈𝖐 𝖂𝖆𝖙𝖘𝖔𝖓
· · · ・ • 𓆩♡𓆪 • ・ · · ·

💭 ; Levi Ackerman x Reader
R-EVERIE
┄──┄──
DISCLAIMER —
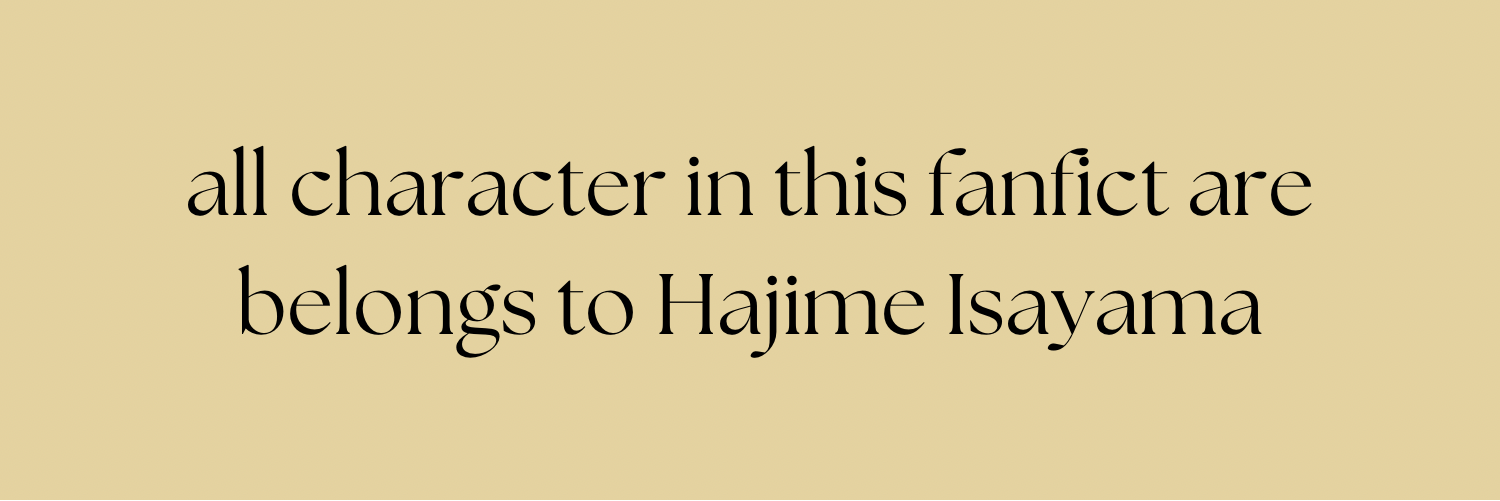
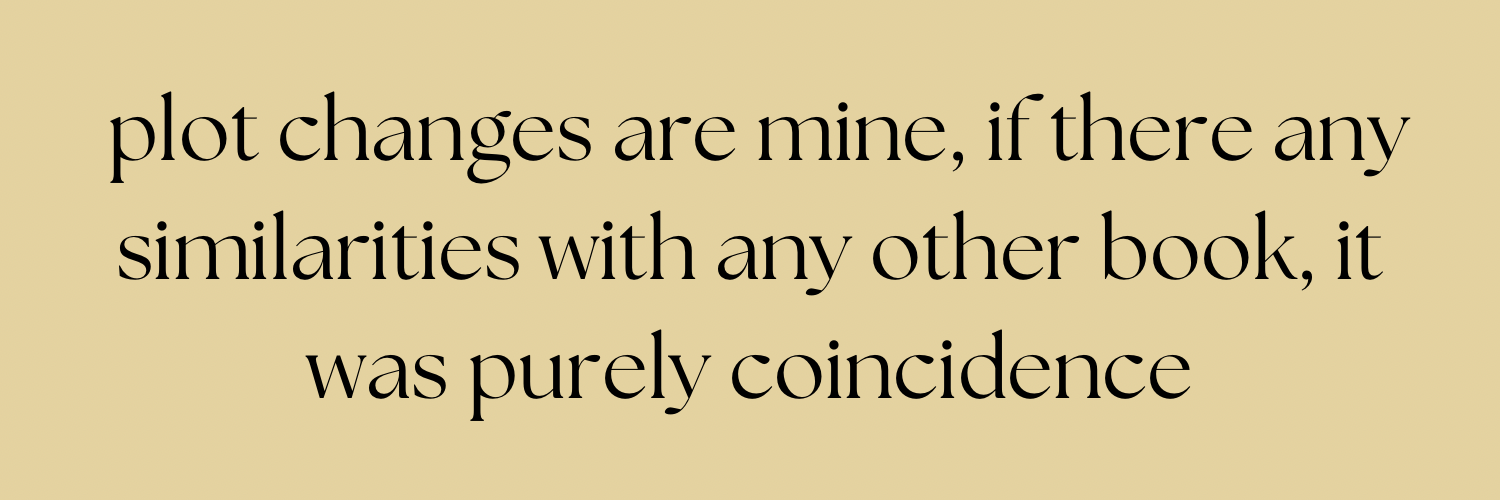

┄──┄──
"Kakak, sarapanmu sudah siap."
Dua bilah kusen jendela pinus tua terbuka lebar, menghantarkan embusan tipis udara hangat yang semula melanglang buana dan berakhir singgah pada ruangan bernuansa kayu coklat. Mendengar lontaran pernyataan dari wanita muda yang tegak berdiri di depan jendela, sosok wanita berbalut selimut itu tak segera membalas. Terseok lemas sebab baru terbangun dari rehat sekian waktu.
"Pagi, [Name]."
Tapak kaki halus mengetuk marmer perlahan, wanita itu beranjak kemudian menghampiri [Name]; melihat hiruk pikuk manusia menghantui metropolitan.
"Aku akan pergi ke hutan."
"Perlu kutemani?"
[Name] menggeleng, "kau harus bekerja, kak."
Pita putih yang mengikat surai [Name] bergoyang terembus angin bersama manik yang sudah mengarah pada cermin dalam ruangan kayu bernuansa lawas. Kakinya mengendap mendekati objek, bersolek sedemikian rupa.
"Cepat bersiap-siap, kak. Aku akan mengunci rumah saat kamu sudah keluar."
Seulas senyum terpatri pada paras rupawan sang kakak yang kini sudah berdiri tepat di ambang pintu kayu kecokelatan, "siaga sekali, ya. Sudah pasti 'itu' tandanya."
Wanita muda yang asyik bersolek mengernyit heran memandangi sang kakak dari jarak yang cukup jauh. "Maksudmu?"
"Bukankah ini tandanya kalau kamu sudah siap menikah?" goda kakak kemudian sembari melangkah pergi dari ruangan.
Ruangan lawas itu kini berisi seorang wanita belia yang terdiam, tak mengucapkan sepatah kata. Dilanda kebingungan.
──┄──┄ ⋆ ּ ۫ ִ 💭 ִ ۫ ּ ⋆ ┄──┄──
Semilir udara mengalunkan desirnya, menerpa sekian objek alam. Tangan menggenggam sebuah kuas bangsai, menari elok meninggalkan beberapa bekas tumpahan adiwarna dalam kanvas yang semula polos bersih. Terus menari dan menari hingga tatanan warna dalam kanvas itu memuaskan ekspetasi dalam benaknya.
Peluh membasahi dahinya, kemudian bergulir turun memeluk sekujur tubuh. Wanita muda yang bernaung di bawah pohon itu memutuskan menghentikan sejenak kegiatannya, diri menggaruk frustasi ujung kepala.
Sekeliling hutan selanjutnya menjadi hening. [Name] yang tengah frustasi itu meletakkan kuas lukisnya pada penyangga kanvas. Raganya beranjak dari singgasana simpel berbobot kayu lawas, mendarat kemudian merebahkan diri pada tanah rerumputan nan luas.
Sanubarinya tak tenang, serasa digerogoti sejuta serangga. "Dia akan menepati janji ini, kan?" Jemari [Name] meraba halus benda yang mengikat sebagian helainya, benar, pita putihnya.
Monolog pendek itu membawanya ke dalam lubang kekhawatiran lebih dalam. Jantungnya berdetak cepat, sergap tangannya meraba asal rerumputan hingga tangannya mengacak-acak tas bawaannya sendiri sampai menggenggam sebuah miniatur kucing bermodel feminim dengan gaun putih indah, menggunakan tudung yang menutupi wajahnya seraya menggenggam sebuket bunga mawar. Layaknya sesosok pengantin.
"Tuan baron tak mungkin melupakan istrinya, bukan, Lucy?"
──┄──┄ ⋆ ּ ۫ ִ 💭 ִ ۫ ּ ⋆ ┄──┄──
"Tolonglah tuan, saya hanya ingin menjadikan miniatur ini sebagai model lukisan saya."
"Tidak bisa, kalau kau mau kau harus membelinya."
"Kalau begitu saya hanya butuh miniatur pengantin wanita ini saja."
"Tanpa membayar? Tidak bisa, pergilah! Tawaranmu tidak akan membuatku untung, dasar orang Perancis."
Desahan pasrah keluar begitu saja dari mulut sang wanita. Ujung pandang kini beralih, memandang rentetan manusia kota yang bercengkrama satu sama lain. Semakin ramai destinasi, semakin memuncak pula amarah yang membelenggu ruhnya.
Tapak tilas membekas bersama di atas tanah cokelat, pada akhirnya dia memutuskan pergi dari toko kelontong yang menjual miniatur tersebut seraya mencaci maki atas kejadian yang telah terjadi. Bagaimana tidak? Wanita itu sendiri kelelahan mengais ide untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan seninya, bahkan saat dia menemukan objek tepat untuk menyempurnakan ide, pemikiran simpel dan klimaksnya telah menghancurkannya.
Ujung sepatu mengetuk alas bumi berkali-kali hingga dia menghentikan langkahnya pada sebuah tempat makan sederhana yang tak jauh dari toko kelontong tadi. Setidaknya meminum secangkir kopi hangat akan membuat pikirannya dingin kembali, itu yang dia harapkan.
Kini raganya berehat di atas kursi khas tempat makan, tangannya mengobrak-abrik tas besar yang ditenteng berjam-jam hingga dia mendapatkan sebuah buku sketsa beserta pensil dalam genggamannya.
Di depan mata telah terpampang lembaran polos dan kosong. Masih dilanda rasa frustasi, dia mengalunkan tangannya abstrak.
"Hei, berhenti mencoret-coret bukumu, suara pensilmu benar-benar mengganggu."
Pasang bahunya tersentak, suara berat tiba-tiba saja menyahutnya. Merinding, berakhir menjejal tanya. Siapa gerangan yang baru saja mengasarinya?
Tak disangka, wanita ini semakin meledak begitu menengok rupa visual tersebut? Nampak seorang bocah laki-laki dari bangku seberang yang sepertinya kelas menengah pertama, dengan mimik wajah penuh rajuk terpampang jelas membuatnya merasa kalau diri sedang ditantang.
"Saya tidak mengerti kamu datang ke sini dengan ibumu atau bagaimana, tapi bukankah anak kecil sekelas sekolah menengah sepertimu seharusnya sudah diajarkan sopan santun dalam mengingatkan orang asing?" Dia membalas, nadanya jelas terdengar tidak tenang.
Sudah melampaui batas kesabarannya sendiri.
"Anak kecil? Sekolah menengah? Ulangi kembali kalimatmu, orang asing." Rupanya tak ingin mengalah, laki-laki di seberang semakin membuatnya merinding dengan balas ancamannya.
Menjaga harga dirinya sebagai sosok mahasiswa berpendidikan tinggi, wanita muda itu membalas penuh amarah. "Jaga sopan santunmu pada yang lebih tua, anak kecil. Terutama pada seorang perempuan."
Situasi tempat makan yang semulanya hangat dan tenang, berubah dalam sejenak menjadi dingin dan suram. Atensi mengarah jelas pada dua insani yang setelahnya melempar tatapan sinis satu sama lain.
"Sopan santun?"
Bulu kuduknya berdiri, firasatnya mengatakan jikalau diri harus bersiap siaga bila mendapat ancaman fisik. Tangan wanita yang sejak mulanya menggenggam pensil kayu klasik telah berbalik arah, menghadap pada laki-laki di seberang yang sekarang beranjak dari tempat duduknya dan berjalan lurus ke arahnya.
"Ucapanmu terdengar seperti kamu mengenalku, jangan berlaga akrab layaknya paman dan keponakan yang baru bertemu."
Alis wanita bertaut, jiwanya telah ditelan oleh amarah. Sudah persetan dengan kalimat mengandung sopan santun, ia mengeluarkan segala emosi yang membendung relung hatinya selama sekian jam yang lalu.
"Baiklah, kalau begitu aku yang minta maaf! Dengan begini kau puas, kan? Enyahlah dari hadapanku, bocah sekolah tak tahu malu."
Sejenak ia membangun ekspetasi kalau laki-laki di hadapannya ini akan segera berjalan meninggalkannya, entah bagaimana pun caranya saat ini yang diri harapkan ialah ketenangan sembari menyeruput segelas kopi hangat. Namun sia-sia saja patrian angan tersebut, seketika hancur lebur begitu setelahnya dia terbelalak.
"Bocah, jaga mulutmu. Aku sudah berkepala dua, jangan asal bicara."
Hilang sudah harga diri wanita sebagai pemilik titel wanita berpendidikan, rasanya baru saja akal sehatnya ditelan ego, lupa bahwa dia juga tak menjaga sopan santun pada orang asing.
Rupanya tertunduk penuh menghadap alas cokelat beruas, jemari mungilnya meremas kain gaun berpoles corak bunga kuning yang menutupi lutut. Arah pandang diri memburam, setetes demi tetes rintik air mata berjatuhan kemudian berjalan hingga pangkal dagu.
"Maaf."
Tapak kaki menghantam alas klasik keras, pacu larinya semakin cepat selepas beranjak dari singgasana kemudian keluar dari tempat makan tanpa peduli seberapa banyak orang yang menengok kilas dramanya.
Muak terasa, rasa negatif mendominasi relung hatinya. Hempasan larinya menerobos jejeran daun musim gugur, raga diterpa dingin. Menjejal tanya, apa kesalahan yang dia lakukan hingga semesta membuat pupus harinya?
Cukup merasa kelelahan berlari, napasnya tersengal dan kakinya berhenti melangkah. Air mata yang semula dia tahan karena terjebak kerumunan insani metropolitan telah meledak. Rindang pohon oranye menjadi saksi sekeras apa dia berteriak mengataskan kendalanya hari ini.
Bunyi tapak kaki diterima gendang telinga, secepat mungkin wanita belia menghapus bekas rintisan air mata di parasnya dan menoleh pada sumber suara.
"Cepat juga kau berlari, ya." Suara itu tak asing lagi, mata membelalak begitu menapaki visual yang dia temui di belakangnya.
Laki-laki dari seberang bangku tempat makan tadi.
Tak tahan untuk kedua kalinya, amarahnya kembali merundung dan kembali menangis sekeras mungkin.
──┄──┄ ⋆ ּ ۫ ִ 💭 ִ ۫ ּ ⋆ ┄──┄──
"Sudah lega, [Name]?"
Pemilik nama menggeleng, "bagaimana aku merasa lega begitu aku sadar bahwa sebelumnya ada sosok seram yang mengejarku saat menangis? Kemudian sosok itu bukannya menenangkanku, malah mengingatkanku kalau aku belum membayar pesanan kopiku. Kamu membuat rasa bersalahku semakin menjadi-jadi, tuan!" Seguk tangisan menyelangi kalimatnya, laki-laki yang terduduk di sampingnya hanya menatapnya datar.
Layaknya tak memiliki iba atau pun rasa manusiawi pada seorang wanita yang menangis.
"Salahmu sendiri." Celutuknya singkat.
"Setidaknya ucapkan permintaan maaf atas cara bicaramu."
"Aku tidak akan bicara seperti ini kalau kamu tidak berulah."
Rimbun daun berdesir, begitu sayup tiupan angin berembus beraroma rumput. Menyapu surai [Hair Color] dengan halus, membelai lapisan kulit dengan lembut. Pula meringsek nuansa hati yang semula belum membaik semakin tak membaik.
Telapak tangan mengusak-usah paras, tepatnya mengusak mata. Sejenak ia kembali menyegukkan tangisan, setelahnya berucap, "jahat, tapi tuan penjaga toko kelontong itu lebih jahat dari tuan." dalam bisik.
"Toko kelontong?"
Lama menanti balasan, akhirnya sebuah anggukan ditunjukkan.
"Ya sudah, bukan urusanku sebenarnya." lanjutnya santai.
Atensi yang semula mengarah pada alas aspal yang menjadi bekas tapak kaki kini dialihkan paksa menghadap manusia tak tahu cara bertutur kata. Alisnya bertaut kembali, "setidaknya kalau tidak merasa iba pada wanita yang menangis, kondisikanlah caramu bertutur kata, tuan!"
"Lalu apa maumu?"
Manik menatap sumber suara, di antara sayup-sayup daun sang wanita memerhatikan rupa visual sang lelaki. Surai hitam yang berantakan karena dibelai angin, pasang mata yang tajam membawa kesan bahwa dia lelaki dingin, pakaian simpel dengan sebalut blazer menutup balut atasan dengan kerah hitam yang mencakup hingga lehernya.
Kulitnya terang pucat berpadu dengan gaya pakaian yang cocok, sejenak dia dibuat kagum.
Iya, sedikit.
Asumsinya, setidaknya walau wajahnya sedikit menyeramkan, gaya berpakaiannya masih sedap dipandang.
"Tuan pikir aku akan mengatakan permintaanku pada orang asing?"
"Ya sudah. Selamat tinggal." dia berdiri, hendak meninggalkan zona oranye tersebut.
Sang wanita buka mulut, untuk sejenak saja ia butuh seseorang untuk wadah curah kesahnya. Mulutnya mulai melafalkan kata demi kata, membentuk sebuah cerita lampau yang berselang beberapa waktu. Walau tak menghadap ke arahnya, diri tahu kalau ada sosok pendengar yang senantiasa mendengar deru kesahnya.
Hingga sampai pada ujung kalimat, diri menyegukkan tangisan kembali. Lega.
"Kalau begitu kenapa kamu tidak membelinya saja?"
[Name] menggeleng tak setuju, "aku yakin kelak jika
miniatur itu sudah menjadi milikku, itu tak akan berguna, aku hanya membutuhkannya untuk sementara."
"Toko kelontong mana?"
Desir angin mengisi kosong suasana, menyapu kian sudut pula pelosok sekitar. Pula meringkas habis konversasi, menyisakan hening.
"Apa?" tanya diri.
"Toko kelontong mana?"
"Tak jauh dari tempat makan tadi."
"Berdiri, tunjukkan toko yang mana."
──┄──┄ ⋆ ּ ۫ ִ 💭 ִ ۫ ּ ⋆ ┄──┄──
Lembayung senja menghantui metropolitan, manusia kota tak berhenti menjalari rentetan toko kelontong. Di sana diri dengan lelaki pendek berbaur dengan insani yang dilanda kesibukan, menawar sana-sini.
Langkah kaki mereka seiras, turut meramaikan pelosok toko kelontong. Hanya langkah kaki, tak ada konversasi. Agaknya angin telah menyapu topik supaya terjadi suasana hening seperti ini.
"Sudah aku bilang ini, barang ini tak akan berguna setelah aku menyelesaikan tugasku."
"Lebih baik daripada kamu harus menangis seperti bocah nakal tak diberi mainan."
Alis diri kembali tertaut, "sebentar saja bisakah kamu tidak membuatku naik darah? Kita baru saja bertemu."
Lawan bicara tak memberi tanggapan, bergeming menyisakan hening.
"Miniatur pengantin itu simpan saja."
[Name] bergeming, menjejal tanya, "hanya pengantin wanita?"
Lelaki bersurai hitam di sampingnya mengangguk, kembali terpatri tanda tanya pada benaknya. "Bagaimana dengan pengantin pria?" jejal diri memandang miniatur pengantin wanita dalam genggaman.
Bentuknya indah, ukirannya sangat detail. [Name] terkagum, eloknya sang pengantin wanita membuatnya berapriori dan bertanya dalam benak. Jikalau saja miniatur ini hidup dan benar-benar menikah, bagaimana reaksi sang pengantin pria begitu melihat eloknya rupa kekasih?
"Kamu tidak butuh pengantin pria?" [Name] menggeleng.
"Konsep lukisanku tidak menggambarkan euforia dari asmaraloka, melainkan lakuna dan distopia dari asmaraloka."
"Aku akan simpan pengantin prianya kalau begitu."
Diri mengernyitkan alis, keheranan untuk sekian kalinya.
Nuansa senja menghangat dalam sejenak, lembayung oranye terasa menyelimuti. Dalam lembayung, insani ini tak berhenti berjalan tanpa tujuan pasti. [Name] sendiri keheranan, mengapa tiba-tiba alur perjalanan harinya terasa seperti lesat kereta modern?
"Tuan—"
"Levi, namaku Levi."
"Baiklah, Levi. Terima kasih untuk hari ini, untuk balas budi. Mau minum teh sejenak? Aku yang akan membayar."
──┄──┄ ⋆ ּ ۫ ִ 💭 ִ ۫ ּ ⋆ ┄──┄──
Senja ditelan malam, dua manusia ini menepi dari lalu lintas metropolitan. Memasuki tempat makan sederhana untuk menepati balas budi sang wanita. Menghadap satu sama lain, namun tak mengarahkan atensi pada satu sama lain. Wanita itu menghadap pada jendela yang memeparkan pemandangan malam di Kota Tokyo. Di saat yang sama pula, sang lelaki sibuk menyeruput teh hangat dalam cangkir putih bercorak tulip.
Diam, menopang dagu. Tenggelam dalam lamunan tanpa subjek, itu yang dirasakan sang wanita. Hingga akhirnya sang lelaki buka mulut, "[Name]." panggilnya tegas.
Pemilik nama tak menaruh atensi, matanya masih berbaur pada manusia kota di luar sana.
"Jika lukisanmu sudah selesai, aku ingin melihatnya." Lanjut Levi.
[Name] mengangguk, menyetujui, "boleh, tapi bagaimana dengan miniatur ini?" [Name] menunjukkan miniaturnya kemudian meletakkannya pada alas meja.
"Ya, simpan saja."
"Tak mungkin kita memisahkan pasangan ini, bukan?"
"Mereka hanya miniatur."
"Hargailah konsep yang diberikan oleh pengrajinnya, Levi."
Levi menghembuskan napas kasar, setelahnya menyeruput kembali teh hangat dalam cangkirnya. "Ya sudah, kalau begitu aku akan menemuimu untuk melihat lukisanmu dan mempertemukan baron dengan istrinya. Di Perancis. Ingatlah, ini janjiku."
──┄──┄ ⋆ ּ ۫ ִ 💭 ִ ۫ ּ ⋆ ┄──┄──
Rerumputan menjadi jalan setapak sang wanita yang kini berkepala dua itu untuk kembali pada bongkahan kayu rapih atau tempat tinggalnya. Kilas balik yang senantiasa berada dalam pikirannya terjeda untuk sebentar, saatnya [Name] pulang dan mengerjakan pekerjaan yang lain.
Memang pertemuan insani ini hanya sekilas, namun entah mengapa sangat membekas di hati [Name]. Tanpa sadar dia selalu memutar balik momen-momen kala bertemu dengan laki-laki bernama Levi itu, layaknya video lama. Tanpa sadar pula ia selalu bertanya dalam benak, apa kabar dia saat ini? Apa dia melupakanku? Apa dia masih ingin melihat hasil lukisan pengantin baron ini?
Bentuk rupanya tak dilupakan, lantang suaranya ingin dia dengarkan selalu.
Namun [Name] sendiri sudah sadar, dia telah jatuh cinta pada Levi.
Namun pula, tak mungkin ada harapan bagi mereka untuk bersama. Lagipula itu hanya janji klise, sang wanita merasa pertemuan mereka sama saja dengan menyapa orang lain, hanya sebentar dan tak bertahan lama.
Wajah [Name] tertunduk lesu mengingat kenyataannya, mungkin dia memang harus melupakan perasaan yang telah bernaung dalam hatinya selama dua tahun lampau dan mencari pujaan hati yang lain.
Yang tak berjarak jauh.
"Lama."
Suaranya membuat wanita bergidik ngeri, merinding. Tiba-tiba seutas suara familier diterima gendang telinganya, tepat berarah dari teras rumahnya. [Name] mendongakkan kepala, tak percaya dengan yang baru dia dengar.
Itu suaranya, suara Levi.
Levi berada tepat di hadapannya, bersandar pada tembok kayu, menatap dirinya tajam. Seperti kala dulu. Namun dalam keadaan fisiknya telah terbaut untai kain putih yang menutupi sebagian wajahnya, layaknya telah terluka parah.
Manik telah membulat sempurna, [Name] tak dapat mengeluarkan sepatah kata ataupun kosa kata dari mulutnya. Suaranya tak dapat keluar dari titik tenggorokan.
"Lama tak berjumpa, [Name]." sapa lelaki di hadapannya.
Kanvas dan berbagai peralatan yang semula digenggam terlepas begitu saja. [Name] melesatkan kakinya, meraih jas lengan yang dikenakan lelaki. "Levi?" tanyanya terbata-bata.
"Aku membawanya, si baron." Tangan Levi menggenggam miniatur kucing dengan jas putih, memegang topi klasik. Itulah si baron, pengantin miniatur pengantin wanita.
"Apa yang terjadi padamu, Levi?" Namun [Name] tak menghiraukan, ia lebih memprioritaskan kondisi fisik Levi.
"Jepang diserang oleh sekutu, aku sebagai tentara militer negara harus turun tangan menghadapi mereka."
Lemas.
Dalam sejenak urat dan sendi jemari [Name] melemas mendengar pernyataan langsung dari Levi. Tangannya melepas jas hitam yang dikenakan sang lelaki.
"Tak perlu panik, aku tetap hidup walau sudah tak berpenampilan seperti dulu. Yang lebih penting lagi, aku menepati janjiku untuk menemuimu, [Name]."
Pandangan memburam penuh, isakan tangis keluar begitu saja dari mulutnya. Raganya tak kuat lagi menampa diri, akhirnya terduduk lemas di atas kayu klasik.
"Terima kasih sudah kembali dengan selamat, Levi."
"Aku pulang, [Name]. Terima kasih juga sudah menungguku."
──┄──┄ ⋆ ּ ۫ ִ 💭 ִ ۫ ּ ⋆ ┄──┄──
Halo! Ini debut saya dalam event Pungut Project, saya Camelia.
Saya merasa sudah lumayan lama tidak menjamah dunia menulis, rasanya skill saya sedikit berkurang? Mohon maaf bila sekiranya pemilihan kata saya tak dapat menyampaikan firasat dari pemeran, saya juga mohon maaf apabila salah dari pembaca merasa kurang adanya korelasi dari cerita dengan lagu yang saya pilih untuk songfict ini.
Dari pada itu, saya berterima kasih pula untuk pembaca yang sudah menyempatkan diri untuk membaca karya saya yang satu ini.
Saya pamit dulu, semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Sampai jumpa!
—Camelia, on Thursday.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top