08 Masih Tetap Berdiri
⭐
Hangover #2
The Unintended Aftermath
08 Masih Tetap Berdiri
⭐
Aku mulai bertanya apakah aku masih hidup atau sudah mati karena hitam menyesaki rongga mata. Ke mana saja bola mataku bergulir tak secercah pun tertangkap lensa. Hati kecilku terbahak.
Jika memang harus pergi maka matilah saja. Daripada tetap hidup terbunuh perlahan sebab menghirup takdir beracun setiap waktu. Kapasitas otakku terlalu rapuh untuk menampung semua rentetan pahit ini.
Sialnya, mungkin 'derita' memang nama tengahku. Meski tak terlihat namun aku masih bisa merasakan lengan dan kakiku. Aku belum mati. Tubuhku masih bisa digerakkan. Tenagaku masih utuh. Hanya penglihatanku yang dirampas.
Ini mimpi lagi.
Tapi kenapa hitam?
Kukira mimpi di alam putih kosong itu sudah cukup menyiksa. Rupanya aku lebih benci hitam. Aku tak melihat tanganku. Atau kakiku. Atau badanku. Dan aku harus berjalan tanpa arah dengan tangan terulur, meraba udara hitam, si buta yang putus asa.
"Eh! Uh--uhh!"
Telingaku meruncing. Bumi?
Lekas aku berlari, mempercepat kedua kaki. Ke manapun yang terdengar seperti asal tangis Bumi. Jantungku berlompatan bersama setiap derap. Semakin bergemuruh ketika kakiku sampai di pusat jerit parau itu, namun tak dapat kutemukan anakku. Karena… buta.
Aku berlutut. Merangkak dengan ketiga tungkai seperti bayi pincang. Satu tangan mempertajam indra peraba, terus berusaha menggapai apapun yang begitu kumohon sebagai Bumi.
Sampai, tanganku menyentuh sesuatu. Aku meraba cepat. Lengan gempal ini. Pipi luber ini. Rambut sarang ini. Tangis melengking ini. Ini anakku.
Kuangkat tubuh bundarnya dalam pangkuan. Tanpa melihat, namun aku masih bisa menepuki pantat empuknya. Menciumi lembut pipinya. Bibirku tergelincir karena wajahnya licin, kurasa karena air mata.
Geleng kepala Bumi membingungkanku. Tangannya meronta, kakinya menjejak gesit. Mungkin dia mau susu? Aku meraba dada, menemukan tiga kancing teratas dan membukanya. Dada kiri yang kukeluarkan, dan tanpa perlu kucari dalam gelap, mulut Bumi sudah tahu kemana harus menguncup.
Sesuatu merambat keluar dari payudaraku yang disesap Bumi. Aku memejam, tak ada bedanya dengan membuka mata. Namun kelegaan merebak, menggelitik setiap arteri.
ASIku keluar lagi.
Tak apa. Tak apa aku buta, asal bisa mengASIhi Bumi.
Daya hisap pipi Bumi mengendur, berangsur hilang. Mulutnya terlepas dari dadaku. Ronta dan jejaknya tak lagi memukulku. Ada yang aneh. Kenapa sebentar sekali?
Jemariku menyusuri halus wajahnya. Dingin. Matanya tertutup. Sekujur kulitnya terasa kelat, seperti air matanya mulai kering.
Cahaya datang menyorot kami. Mataku berfungsi.
Bukan air mata, melainkan darah pekat yang menyimbah sekujur tubuh anakku.
***
"Mel!"
Aku memelotot napasku terjegal. Rongga dadaku menyempit.
Yang langsung terlihat olehku adalah rona lelah dokter McFord dengan matanya terpejam. Seperti aku, dia berbaring menyamping. Kami berhadapan.
Napasku terembus. Bumi ada di sini, diapit tubuhku dan Dokter. Dia damai dalam tidurnya. Hampir tersenyum. Tak ada sebercak darahpun.
"Kamu mimpi apa, Mel?"
Aku bertumpu siku di ranjang, ingin bangun, tapi tak semudah itu. Tenagaku nol. Tulangku membelot dan Elia memintaku tetap berbaring. Dia duduk di sisi ranjang menggenggam jemariku yang mati rasa.
"Mel."
Mulutku membuka. Mengatup. Kubenahi napas yang semrawut sebelum merespon dengan, "memangnya aku kenapa?" yang lebih terdengar seperti cicitan.
"Kamu ngigau, nangis manggil-manggil Bumi." Elia mengusap tulang pipiku, yang baru kusadari, kuyup. Dia meraba kening lalu leherku dengan punggung tangan. "Kenapa? Mimpi apa? Kamu pucet banget… tapi udah nggak panas."
Aku tersenyum, membalas genggam tangannya, sekadar untuk meluruskan kerutan cemas di wajah ayunya. Kuceritakan mimpi-mimpi jahatku sambil menahan sesak ketika mengingatnya. Elia menyimak dalam diam. Tak sepatahpun keluar dari bibirnya, kecuali sorot sendu berkaca dari matanya.
Dan tak mau dia sedih gara-gara aku, aku melirik jam dinding, lantas mengalihkan topik.
"Kamu kenapa di sini? Udah subuhan?"
"Udah barusan." Dia mengangguk, mengucek mata sekilas. "Semaleman selama kamu tidur Bumi cuma mau sama Mas. Padahal dia juga minta ASI. Tapi dia nggak mau ASIP dari kulkas karena ada kamu, jadi… aku…"
Elia mengusap ekor matanya lagi, tersenyum rikuh. Kemudian, menunjuk bagian dadaku yang… terbuka polos. Belingsatan kurapatkan dan mengancingkan atasan piyama.
Tunggu.
Aku mendelik. "Jadi semaleman aku tidur buka-bukaan gini di depan Dokter?!"
"Iyaa… gimana nggak ngerti lagi aku, Mel." Dia gelagapan. "Jadi ya gitu, kamu 'kan nggak bisa bangun, merem-rem-rem habis minum obat semalem. Sementara Bumi rewel mau susu, trus, ya… maaf banget… aku buka kancing bajumu, Mel."
Volumenya mengecil di ujung kalimat. Agak lega, kukira Dokter yang melakukannya. Tapi kelegaan itu tak bertahan lama karena Elia menambahkan.
"Tadinya aku yang mau nempelin Bumi ke kamu. Tapi kamu tau sendiri Bumi kalo nangisnya udah kejer gitu pilih-pilih orang, maunya cuma sama kamu atau Mas. Makanya… tadi malem Mas Luke yang nempelin Bumi ke kamu."
Jantungku memelorot.
Ya Gusti...
Aku tidur di bawah pengaruh obat dengan dada terbuka bersama Dokter. Serasa disetubuhi untuk kedua kalinya.
"Tapi sumpah, ada aku juga!" Dia mengacungkan jari berbentuk V. "Makanya aku di sini. Mas Luke takut dia khilaf macem-macemin kamu pas tidur jadi aku ngawasin di sini. Dan demi Allah, demi almarhum Ayah aku, Mas Luke nggak macem-macem sama sekali."
Bibir dan lidahku masih kelu. Bahkan kelopakku tak bisa berkedip. Otakku macet tak berjalan baik.
Elia menggamit jemariku lagi. Kabut sesal merundung parasnya.
"Bumi mau ASI. Maaf, Mel, maaf. Aku sama Mas nggak punya banyak pilihan. Tolong jangan marah sama Mas, karena awalnya aku yang ngusulin ini. Kasian dia belum tidur, baru bisa merem habis subuhan tadi…"
Aku menggeleng, tersenyum, memaklumi semuanya. Kalau aku di posisi darurat seperti Elia, aku pasti melakukan hal yang sama. Apa saja, asal hak ASI Bumi dapat terpenuhi.
"Nggak papa, Li. Harusnya aku yang makasih, kamu sama Dokter mau direpotin Bumi sama aku."
"Kamu ngomongnya kek baru kenal kemaren aja." Tawa Elia kembali. Dia menoyor pipiku. "Anyway, aku boleh nanya sesuatu?"
Aku mencubit lengannya. "Kamu ngomongnya kek baru kenal kemaren aja."
"Emm, oke. Sori, soalnya aku kepikiran terus. Mas Luke apalagi, dia sampe nggak bisa makan nggak bisa tidur…" Seketika sorotnya menjadi serius. Elia menahan napas dan perasaanku makin gamang. "Kenapa dadamu luka-luka, Mel?"
Ah.
Jadi mereka melihatnya. Luka frustrasi karena habisnya persediaan ASI.
Meski sudah tidur semalaman, otakku masih terasa lemah. Tak mampu memikirkan alasan, aku mengungkapkan lagi, semuanya. Seusainya, ketika kupikir Elia akan jijik, memarahiku semacam, 'Gitu doang stress?!', menjustifikasi aku sakit jiwa--ya aku tahu, aku memang sakit jiwa--tetapi tidak.
Mata bulatnya berkaca, lagi. Cepat dia menghapus air itu dengan lengan atasnya sebelum menitik. Aku mengumpulkan kekuatan untuk duduk lantas merangkulnya. Mengusap punggungnya. Elia terisak di bahuku. Hangat menjalar dari dadaku, beredar ke seluruh tubuh.
"Kamu keren, Mel…" Bahunya gemetar. Begitu pula lirihnya. "Kamu keren. Banget. Kamu hebat."
Aku tertawa serak. Tersendat di tenggorokan.
"Kamu diuji dengan hal-hal yang… yang kalo aku di posisi kamu, aku..." Napasnya menyapu kulit tengkukku. "Aku nggak mungkin kuat."
Darah berkumpul di wajahku. Sesak. Aku memejam keras. Menunduk dan menggeleng tertahan. Tanggul air mata yang mati-matian kubendung, akhirnya harus runtuh.
"Aku nggak sekuat itu, Li. Kamu--ehm." Bibirku mengatup. Hidungku menarik napas basah. "Kamu tau sendiri gimana aku hampir…"
"Nggak. Nggak seperti itu, Mel."
Elia melepasku, berganti menangkup wajahku. Jemarinya mengusapi pipiku yang lembap, padahal wajahnya sendiri kacau. Merah. Mengilap karena air mata. Untuk beberapa detik, kami hanya mengikat pandang.
Sampai akhirnya, dia tertawa sengau.
"Maaf, aku malah bikin kamu nangis lagi. Kamu tau, Mel? Kamu memang selalu gini…" Kali ini, Elia menyeka matanya sendiri. "Dari awal kita ketemu. Dari pertama kalinya kamu bukain pintu kamar kos buat aku. Aku nggak bisa ngelupain ini. Muka kamu sembap, bengkak, Bu kos bilang kamu lagi sakit, tapi yang aku lihat, kamu lebih dari sekedar sakit. Mata kamu redup, terlalu gelap... dan aku nggak lihat ada semangat hidup...
"Kamu selalu gini… berkali-kali kamu ada di titik di mana menyerah jadi pilihan instan untuk ngilangin semua sakitnya... dan kamu hampir memilih itu. Menurut aku kamu itu lemah, lemah banget. Tapi pada akhirnya kamu selalu memilih melawan. Kamu masih terus berdiri gimanapun lemah dan hancurnya kamu, Mel."
Dalam beberapa hal, Elia mengingatkanku pada Mama. Aku meraihnya. Keningku jatuh di bahunya. Air mataku merembesi kausnya. Elia mengusap punggungku dalam hening.
Hari ini, pertahananku runtuh.
Elia benar. Aku lelah. Aku lebih dari sekadar lelah. Aku ingin mati. Tapi sebenarnya, aku hanyalah pengecut. Secuil bagian hatiku tetap takut mati. Secuil bagian itu tetap mengemis pada kesadaranku agar tetap nyala.
"Kamu nggak harus kuat, Mel," lirih Elia, menelusup sela rambutku. "Lemah pun nggak papa, tapi tetaplah berdiri. Tetap jadi Melati yang sensitif. Tetap jadi Melati yang cengeng, dan terus ngerepotin Mas Luke, aku, Sandra, dan cowok-cowok itu… Oke, Mel?"
Rahangku kaku. Dadaku naik turun, tak mampu berkata. Hanya terisak, sesengukan, "Maka… sih."
"Kamu lemah, tapi kamu keren. Oke?"
Aku mengangguk. Menggigit bibir dalam, menahan lengkung senyumku. Elia membingkai wajahku lagi, mencubit pipi licinku, dan menertawakan rupaku.
"Baru diginiin thok baper? Cengeng!"
"Yang penting keren," dan, masih tetap berdiri.
***
"Kalau ada apa-apa, tolong segera hubungi saya."
"Beres, Dok!" Sanda dan Joko kompak memperagakan hormat bersamaan.
Aku menunduk malu--sangat malu--ketika dokter McFord menepuk puncak kepalaku sebelum punggungnya bergerak menjauh ke rektorat. Masih di parkiran, Sandra memiting leherku dan aku megap-megap.
"Enaknyaaa punya pacar!"
Dia menggiringku masuk gedung. Aku menapuki mulutnya. Terima kasih pada suara toanya, kepala orang-orang berputar menuju kami bertiga.
"Jadi kemaren dokter McFord uthuk-uthuk nyelonong ke rumah itu jemput kamu gitu?"
Sandra membulatkan mata. Aku mengangguk. Kurasa Elia sudah cerita masalah itu ke Sandra, setelah aku mengizinkannya. Sepertinya Sandra takut bertanya langsung demi menjaga perasaanku.
"Iya, San." Aku tersenyum tipis. "Katanya dia tau dari Fathir sama Joko. Aku halu, sih. Sakit kepalaku udah akut. Antara yakin nggak yakin kalo yang datang itu Dokter. Tiba-tiba semua gelap. Waktu bangun aku sudah di mobil, Dokter langsung minumin aku karena dehidrasi."
"Mouth to mouth gak?"
Kucubit pinggang Sandra sampai dia lompat dan mengaduh. Usil bener dah nanyanya.
"Trus darimana dokter McFord tau rumah itu? Udah pernah kesana sebelumnya?"
Aku menggeleng. "Belum. Dia minta orang rumah sakit nelusurin database pasien buat nyari alamatnya."
"Ish ish ish… demi kamu banget." Sandra mendecak lidah. "Apa nggak ada lagi stok perjaka tong-tong kayak Doktermu itu? Yang kearifan lokal juga boleh kok."
"Nggak tahu." Senyumku melebar. "Aku sama Dokter aja cukup, nggak mau tahu yang lain."
"Ck. Susah emang ngomong sama orang kasmaran. Telek kambing rasa coklat."
"Kamu teleknya, aku coklatnya."
Pitingan di leherku makin mencekik. Joko yang daritadi diam, menepuk dahiku pelan.
"Kamu masih anget. Masih pucet. Yakin mau kuliah?"
"Nggak papa, Jok," Kuturunkan tangannya. Kucoba mengusir cemas di rautnya dengan senyumku. "Aku kena kartu kuning. Nggak boleh izin. Semalem udah tidur lama habis minum obat. Habis sarapan juga minum obat. Lumayan enakan lah."
"Noh, nggak papa, Jok." Sandra mengibas di depan hidung Joko. "Kan ada kita. Inget Jok, 'Kalau ada apa-apa, tolong segera hubungi saya,'"
Impersonasi dibuat-buat Sandra terhadap gestur dokter McFord meningkatkan produksi asam lambungku. Huek!
***
Udara Malang sedang panas--panas menurut standar Malang. Artinya, tidak dingin seperti biasa. Atmosfer yang sempurna untuk beraktivitas, misalnya main ke alun-alun kota Batu, tetapi tidak ketika kamu sedang demam.
Suhu tubuhku masih naik-turun tak tentu. Setelah otakku diperah tutorial, praktikum, dan remedi, langkah kakiku kembali mengawang. Ibarat menapak di permukaan air. Otot dan tulangku nyeri, pandangku berkunang.
Padahal, ini masih jam 1 siang. Kuliah tatap muka diganti belajar mandiri dan tugas take home karena sebagian besar dokter kami disibukkan oleh perkara akreditasi. Belajar mandiri dalam kamus kami adalah tanda tangan daftar presensi, lalu bebas meninggalkan kampus.
Anak-anak berniat membawa Bumi main ke alun-alun kota Batu, tapi melihat rupa pucatku, rencana itu ditunda dan aku dipulangkan. Masih banyak waktu untuk jalan-jalan dengan Bumi, asal aku baikan secepatnya. Itu kata mereka.
Terima kasih pada mereka, siang ini aku selesai makan nasi padang bersama Mbak Sari di rumah. Setelahnya, aku minum obat lalu bergulingan di kasur dengan Bumi.
"Haaa! Hoahh-haaa! Ah ah!"
Bumi membenamkan pipinya di dadaku. Kesurupan menggesekkan wajahnya. Sudah naluri dan mengerti, jemariku otomatis membuka tiga kancing teratas. Sudut bibirku terangkat tinggi lantas mengembus takjub.
Baru selesai makan siang, dia langsung minta dessert berupa ASI. Anakku benar-benar jagoan.
Aku mencolek-colek gelambir pipinya yang naik-turun. Dia balas melirikku dari balik dada tanpa jeda kedip. Iris pekat polosnya melemahkan rasaku.
Iris pekat ini.
Sekarang aku tahu iris siapa ini.
Tapi, benarkah?
Sesuatu di dalam diriku bergerak semaunya, menyelam ke dasar lautan hati. Mengobrak-abrik pasir di sekitarnya, menemukan, dan membawa sebuah kotak hitam kembali ke permukaan. Sebuah kotak pandora.
"Bisa dansa?"
Tidak. Dan tidak seharusnya aku mabuk dan menerima ajakan dansa berbisa itu.
"Well, yours are… yummiest lips I've ever kissed,"
Oh. Begitu. Jadi sebelumnya dia sudah pernah, bahkan sering dan berkali-kali, berciuman. Bagus sekali. Itu justru ciuman pertama yang tak kuharapkan.
"You're bleeding. Ini pertama kalimu?"
Ya. Pertama kali seseorang memasuki aku. Dan aku berdarah itu karena… sakit. Terlalu.
"Kamu nggak akan hamil. Relax, just enjoy it."
Nggak akan hamil karena vonis azoospermia dari dokter, begitu? Maka dengan dalih itu, dia merasa tidaklah penting bersarung pengaman? Bersembunyi di balik itu, dia yakin menyetubuhi dan menyembur benih berulang kali di rahimku tidak akan berbuah apapun?
Keliru. Dia salah besar.
Bumi masih menatapku lekat ketika aku mencium dalam ubun-ubunnya.
Jika ada satu hal yang benar tentangnya, maka itu adalah dia tidak akan bisa punya anak seumur hidupnya. Aku bersumpah dan mengutuknya untuk itu. Bumi bukan anaknya. Bumi hakku, seutuhnya.
Kami tidak butuh dia.
***
Mataku terbelalak siaga satu karena guncangan. Kupikir gempa kecil, karena memang sering terjadi di Malang. Rupanya itu Mbak Sari yang menepuk bahuku. Aku dan Bumi ketiduran, dengan Bumi masih menempel padaku. Mulutnya kulepaskan lalu segera mengancing piyama.
"A-ada apa, Mbak?" lirihku terbata. Dunia di mataku masih berkabut.
"Anu, Mbak, ada yang nyari. Tadi saya suruh pulang karena Mbak masih tidur, tapi katanya dia mau nunggu soalnya penting."
Dahi dan alisku berkerut. "Siapa?"
"Mas Garda, Mbak."
◇ BERSAMBUNG ◇
Hilih kinthil memang Garda tu gak ada kapoknya.
(Lah kalo dia kapok kelar dong ceritanya. 😂)
Semoga feelnya dapet dan masih bisa dinikmati aja hehehe
Luv u to the moon and back, MeLuk 💕
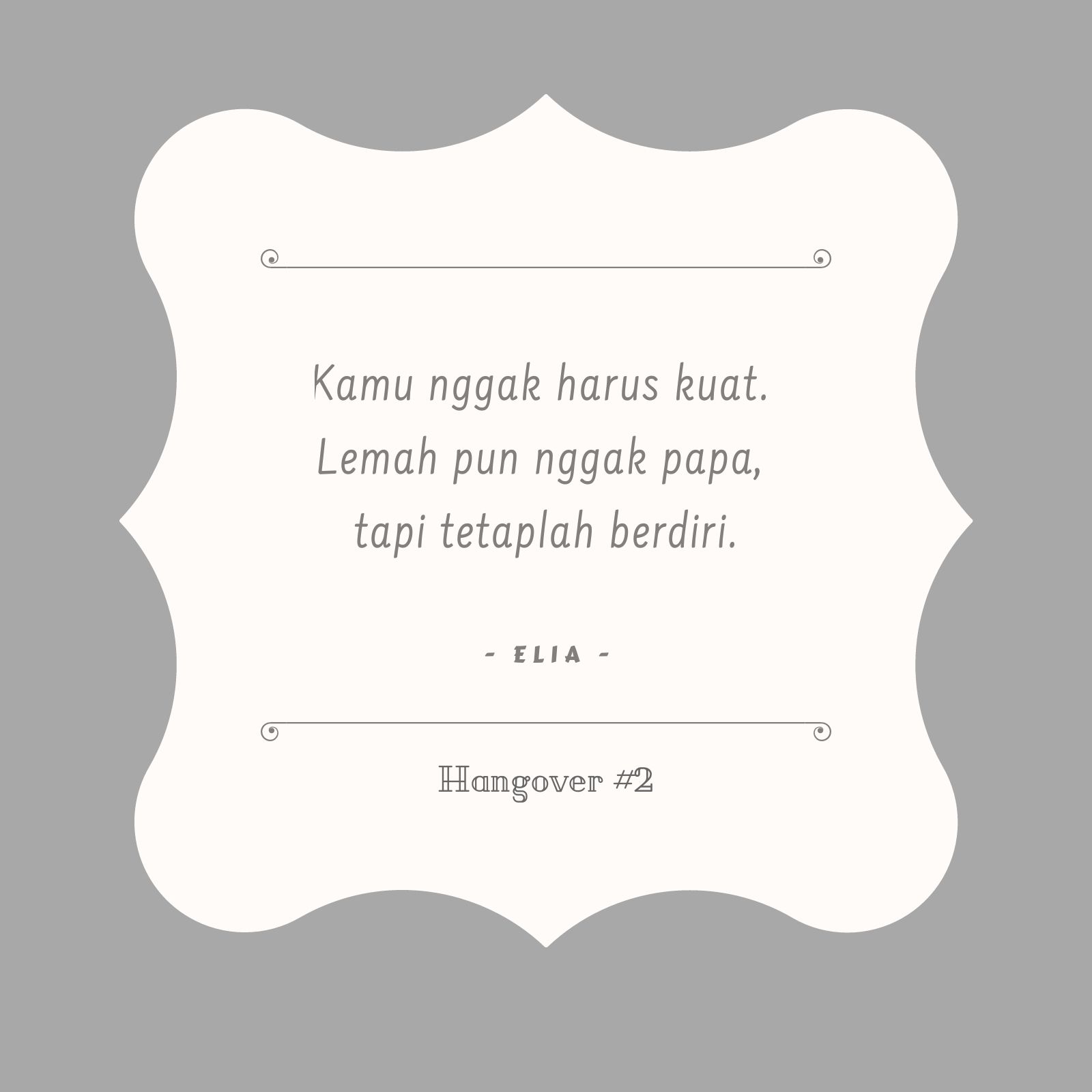
Malang, 20 Juli 2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top