@IniSandri One Shot Story
Wattpad Malaysia open-heartedly presents IniSandri, a Wattpad Ambassador, a multi-talented writer and she's best known for her story 'The Secret Temptation'. She's coming all the way from Indonesia to share an amazing story written for your awesome folks.
...
HELLO!
Congratulation and welcome to AmbassadorsMY!
I'm Yu. You all probably know me as Uni (it means sister in Minang Melayu). I'm so excited to be part of the opening ceremony for Wattpad Malaysia! I've been on Wattpad since 2014 and started writing stories a year later. I want to give you all my one shot story.
Selamat membaca!
***
KIDUNG MALA
(Nyanyian Kesengsaraan)
Suara petir bersahutan dengan suara tangis bayi yang baru saja lahir. Deru napas tersenggal-senggal terdengar dari seorang wanita muda yang baru saja menghempaskan badannya ke belakang—tepat setelah bayi itu disambut di tangan sang Dukun Beranak. Butir keringat sebesar biji jagung mengalir dari keningnya.
"Bayi laki-laki." Suara Dukun Beranak terdengar setelah bayi tadi dimandikan. "Silakan disusui."
Wanita muda yang baru saja beranak itu menggeleng. Napasnya masih sedikit tersenggal. "Berkenankah untuk membantuku, Mak?" suaranya begitu lirih terdengar di telingga Dukun Beranak.
"Bantuan apa, Marni?"
Marni mengerling ke arah bayi yang sudah dibalut kain panjang di tubuhnya. Dengan tangan sedikit bergetar, disentuhnya kepala bayi itu. "Aku tidak menginginkan anak ini, Mak!" Marni menarik napasnya dalam-dalam, lalu menghelanya dengan perlahan, "Tolong rawat anak ini, Mak! Atau jika perlu titipkan saja di panti asuhan."
Kontan saja Dukun Beranak itu terdiam mendengar permintaan Marni. Gurat bahagia karena berhasil menolong Marni melahirkan pun berganti dengan raut terkejut—raut marah lebih tepatnya. "Marni, anak ini adalah darah dagingmu! Sampai kapan pun akan menjadi anakmu. Saat ini mungkin kau malu akan kehadirannya. Tapi, Marni, suatu hari nanti anak inilah yang akan membantumu berjalan, menyuapkan nasi ke mulutmu, atau bahkan menjadi pengantar mayatmu ke peristirahatan terakhir."
"Tidak, Mak! Aku tidak butuh anak ini menjadi penolongku. Aku sudah cukup malu dan menderita karena mengandungnya."
"Tapi, Marni, anak ini—"
"Tidak, Mak! Sekali aku berkata tidak, maka sampai kapan pun akan tetap sama. Aku tidak menginginkan apalagi membutuhkan anak ini!"
Dukun Beranak yang sudah tampak berumur itu menghela napas. Bayi laki-laki tadi berbaring dengan tenang di samping Marni. "Kau tidak mau menyusuinya?"
Marni membuang muka ke arah lain. Dukun Beranak mengangguk, lalu beranjak ke dapur kecil di belakang pondok. "Untung air nasinya belum kering." Ia bergumam pada dirinya sendiri. Menyalin air nasi ke dalam cawan kecil, menambahkan sedikit garam lalu mengambil sendok dari dalam kotak penyimpanan.
"Marni?" Dukun Beranak lantas menaruh cawan tadi di atas meja kayu kecil di samping dipan yang sudah menyisakan bayi laki-laki tadi seorang. Hanya ada seuntai kalung dari benang berwarna merah dengan mainan terbuat dari batu akik yang dibentuk sedemikian rupa yang terletak di samping bayi laki-laki tersebut. Dukun Beranak terdiam beberapa detik lamanya.
"Malang betul nasibmu, Nak."
***
Begitulah dongeng yang selalu dibacakan Mak Sati padaku sebelum tidur. Dongeng pilu yang pada akhirnya kuketahui adalah kisah asli antara aku dan Ibuku. Entah karena alasan apa Ibu meninggalkanku, aku tidak tahu, begitupula dengan Mak Sati. Beruntung beliau berkenan merawatku, meski usianya sudah tidak muda lagi kala itu.
Usiaku sendiri kini sudah memasuki sepuluh tahun. Berada di kelas lima sekolah dasar negeri yang terletak sekitar satu kilometer dari pondok tempat kami tinggal. Setiap pagi Mak Sati selalu mengisikan bekal ke dalam tas yang terbuat dari jerami milikku. Entah kepandaian siapa yang mewarisiku, hingga bisa membuat karya seni sedemikian rupa. Maklum saja, Mak Sati kini sudah berusia enam puluh enam, sudah tidak bisa lagi menolong para ibu yang ingin beranak. Penghasilan beliau kini didapat dengan mengolah sawah kecil di belakang pondok. Sekali-kali aku membantu jikalau Mak Sati tidak melarang.
"Kidung?"
Aku mengangkat tangan kanan lalu bersuara, "Hadir, Bu."
Namaku Kidung. Mungkin terdengar aneh. Tetapi, begitulah Mak Sati memberiku nama. Tidak sedikit dari teman-teman sekolah mengejek namaku yang begitu sukar untuk disebut—atau lebih mudahnya untuk diolok-olok. Buatku pribadi bukan masalah besar. Mak Sati sudah berbaik hati mau merawatku, memberiku nama, dan tidak lupa pula memberiku kasih sayang layaknya seorang ibu yang selalu kurindukan.
Ah, tidak. Ibu dengan tega mencampakkanku tanpa belas kasih. Beliau mengatakan aku hanya akan menambah malu di hidupnya. Jadi, buat apa pula aku merindukan sosoknya?
Mak Sati seringkali berujar sedih di saat aku berkata betapa aku membenci Ibu. Beliau selalu berkata bahwa Ibuku pasti punya alasan di balik keputusannya. Alasan? Bukankah alasan terlalu pelik untuk dijelaskan kepada seorang anak yang ditinggal pergi orangtuanya?
Oh, baiklah. Aku hanya tahu mengenai Ibu dari Mak Sati. Sedangkan mengenai Ayah, aku maupun Mak Sati tidak tahu sama sekali. Hanya Ibulah yang menyimpan bagaimana rupa dan kepribadian Ayah di dalam ingatannya. Sebab, Mak Sati juga pernah berkata bahwa Ibu sangat membenci Ayahku.
Urusan orang dewasa; terlalu pelik, memuakkan, dan memberi rasa sakit. Aku tidak lagi memikirkan masalah Ibu ataupun Ayah. Saat ini, yang menjadi fokus utamaku adalah sekolah, dengan begitu aku bisa membuat Mak Sati bangga karena telah merawatku.
Mungkin terdengar kejam untuk anak seusiaku berkata bahwa 'aku pasti akan mengabaikan Ibuku saat bertemu nanti'. Ya, mau bagaimana lagi?
Tuhan maha pemaaf. Oke. Itu hanyalah Tuhan. Sayangnya aku hanyalah seorang umat yang tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Jadi, aku tidak perlu memaafkan semua orang, bukan?
Aku tidak percaya dengan perkataan bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Itu mustahil. Mana mungkin surga terletak di sana, sementara Ibuku sendiri pergi meninggalkanku tanpa tahu apa salahku. Lantas aku tidak tinggal di neraka setelah Ibu pergi membawa surga itu. Pun aku masih di bumi, bersama Mak Sati yang telah membasuh kotoranku sewaktu kecil. Bahkan terdengar konyol jika aku dengan lantangnya berteriak bahwa 'surgaku bukan lagi di telapak kaki Ibu, melainkan di telapak kaki Mak Sati yang sudah menjadi ibu pengganti bagiku'.
Jangan tanyakan paham atau agama, karena pada hakikatnya setiap orang yang berpaham dan beragama pun masih punya hasrat terpendam mengenai lika-liku dunia. Oh, ayolah! Aku hanya bocah sepuluh tahun yang dipaksa untuk tumbuh dewasa dengan cepat, agar aku bisa melawan tantangan dunia yang begitu kejam, agar aku bisa membuktikan bahwa surgaku bukan di telapak kaki Ibu yang telah meninggalkanku.
Surga terletak di telapak kaki ibu. Tidak. Itu hanyalah mitos untuk anak pembangkang. Bukan untuk anak yang ditinggal pergi seperti diriku.
***
"Bagaimana sekolah tadi, Dung?"
"Lancar, Mak. Aku belajar dengan baik, sesuai petuahmu."
Mak Sati mengangguk. Tangannya menyalinkan nasi ke dalam piring karah berwarna merah di depanku. "Makan yang banyak. Supaya kau cepat tinggi."
"Aku sudah tinggi sekali di kelasku, Mak. Bahkan temanku iri dengan tubuh yang kumiliki," ucapku dengan bangga. "Seharusnya Mak doakan aku agar cepat dewasa. Dengan begitu aku tidak perlu menuntut ilmu seukuran anak SD lagi."
"Dung ... Dung...." Mak Sati menggeleng mendengar penuturanku. "Sudahlah. Selesaikan saja makanmu."
Aku tahu apa yang dipikirkan Mak Sati saat ini. Tatapan sayu berlinang air mata itu begitu mudah untuk dibaca. Seringkali aku terbangun tengah malam, lalu mendengar Mak Sati berbicara sendiri dengan balutan kain lusuh yang menutupi semua tubuhnya. Setiap perkataannya adalah sederetan doa yang selalu terselip atas namaku.
Sementara aku....
Yang bisa kulakukan hanyalah berbaring membelakangi Mak Sati yang terus berdoa. Menahan suaraku yang hendak berteriak protes terhadap takdir Tuhan.
Apakah Ibu mendoakanku di luar sana?
Ah, mustashil!
Mana mungkin orang yang telah dibuang akan muncul dalam sebait doa. Semua mitos sialan dan pengharapan kosong itu tidak berpengaruh padaku. Sebab, hanya ada dua perintah dalam otakku: belajar, lalu bahagiakan orang yang mencintaiku.
"Aku tadi melihat seorang wanita disenggol mobil, Mak." Aku mulai bercerita begitu makanan habis. "Tidak sampai berdarah."
"Kau tidak menolongnya, Dung?"
Aku menggeleng, "Tidak, Mak. Sudah terlalu banyak orang di sana. Jadi, untuk apa pula aku turut membantu?"
"Dung ... Dung...."
Aku paham dengan irama lirih Mak Sati. Terlebih dengan gelengan kepalanya yang tampak sangat kecewa dengan sikapku. "Mak, kau tahu sendiri 'kan, aku punya prinsip dalam hidupku."
"Tentu aku ingat, Dung," Mak Sati mengangguk. "Tapi, Dung, untuk anak seusiamu tidak baik memegang prinsip begitu."
"Tidak, Mak. Usiaku boleh saja masih kecil. Tapi, tidak dengan cara pikirku." Aku mengemasi perlengkapan makan, lalu membawanya ke belakang pondok untuk dicuci.
Tidak ada yang salah dengan cara pikirku. Aku bukan Tuhan yang akan selalu menolong orang, yang akan selalu memaafkan setiap kesalahan orang, atau pun yang akan memberikan kasih sayang pada orang. Tidak. Lantas karena aku bukan Tuhan, maka aku berhak atas hidupku sendiri. Tuhan mungkin berhak mengatur jalan hidupku. Tetapi, aku lebih berhak untuk mengubahnya. Bagaimanapun caranya, aku tidak akan pernah melanggar prinsipku. Prinsip seorang bocah yang ditinggal pergi orangtuanya. Persetan dengan orang dewasa.
Hari-hariku berjalan tanpa ada hambatan berarti. Masih dengan kaki yang sedikit pegal ketika pergi atau pun pulang sekolah. Dan ekspresi konyol ketika mencoba untuk membuat Mak Sati kembali tersenyum seperti saat masih mengguyuku dulu. Hingga tiba suatu ketika, aku benar-benar kehilangan sosok Mak Sati.
"Mak!" Aku terkejut melihat Mak Sati yang tengah mengusap dadanya menahan sakit. "Mak! Apa yang terjadi, Mak? Apa yang sakit?"
"Dung...," Mak Sati mengarahkan tangannya ke arah bambu yang menyangga bagian atap pondok, "Di sana ada dua gulungan kertas. Ambillah!"
"Kertas apa ini, Mak?" tanyaku setelah mengambil dua gulungan kertas yang dimaksud. Yang satu agak besar gulungnya. Sementara yang satunya lagi hanya gulungan tipis—selembar.
"Buka gulungan besar itu, Dung!" sesuai perintah, aku pun membukanya, "Itu adalah uang yang Mak kumpulkan untukmu ke depan. Waktu Mak tidak akan lama lagi, Dung. Mak sudah dapat merasakannya dari beberapa waktu yang lalu." Mak Sati terbatuk, bercak darah tampak di telapak tangan kirinya. "Mak menyayangimu, Dung. Kau tahu itu, 'kan?"
"Aku pun sama, Mak. Tidak ada yang kusayangi di dunia ini kecuali kau. Hanya kau sandaranku, Mak," air mataku mulai berjatuhan, membasahi pipi kusam dekilku. "Jangan berkata seolah kau akan turut meninggalkanku, Mak. Jangan! Sekalipun itu hanya dalam mimpi."
"Dung, kau cukup pintar untuk melihat bagaimana keadaanku sekarang." Mak Sati kembali batuk berdarah, "Jangan ... jangan sampai sekolahmu putus, Dung. Sekarang bukalah gulungan kedua."
"Mak?" suaraku semakin bergetar, "Aku tidak akan meninggalkan pondok ini, Mak! Lebih baik aku tetap tinggal di sini, daripada aku harus bergabung dengan anak panti!" Aku menggeleng dengan keras, "Tidak, Mak. Aku tidak mau bergabung dengan siapa pun itu. Aku hanya ingin bersamamu di sini, Mak. Jangan tinggalkan aku, Mak!"
Mak Sati tersenyum tipis. Napasnya semakin tersenggal, beriringan dengan batuk yang semakin keras. "Jangan ... nakal, Dung. Maafkan ... Ibumu."
Tepat setelah mengatakan itu, Mak Sati pun tidak sadarkan diri. Aku hanya bisa meratap, meraung dengan keras atas kehilangan yang begitu menyayat nadiku. Kini aku benar-benar seorang diri. Terima kasih kepada Ibu yang telah mencampakkanku. Terima kasih atas penderitaan bertubi-tubi yang diwariskannya padaku. Terima kasih, Ibu.
"Jangan tinggalkan aku, Mak! Aku tidak bisa hidup sendirian, Mak! Aku membutuhkanmu. Aku butuh nasihat-nasihatmu, Mak. Aku berjanji akan melupakan prinsipku, aku akan menolong orang lain, dan aku—" Aku terdiam sejenak, "—aku akan memaafkan Ibuku, Mak. Tapi, kumohon bangunlah! Aku akan menepati janjiku, asalkan kau kembali membuka matamu, Mak!"
Hening. Tidak ada sahutan apa pun. Mak Sati meninggalkanku. Sendirian. Tanpa tahu harus bertupang pada siapa lagi setelah ini. Suara yang menghantam atap pondok semakin menguatkan fakta, Mak Sati benar-benar telah pergi, di saat hujan merintik dengan derasnya di tengah kesunyian yang begitu jauh dari keramaian.
***
Aku pernah membaca sebaris puisi yang berbunyi 'di antara datang dan suatu kali pergi', karya Sapardi Djoko Damono. Sekarang aku paham maksud dari sajak itu. Ya, jelas sekali dengan kehidupanku sekarang. Aku datang tanpa pernah diharapkan ke dalam rahim Ibu, lalu aku ditinggal pergi begitu saja. Kemudian aku datang ke dalam kehidupan Mak Sati dengan begitu tiba-tiba, lalu beliau turut meninggalkanku—pergi untuk selamanya.
Atau mungkin saja ini balasan dari Tuhan, karena aku pernah berkata dengan lancang pada-Nya. Dan, oh, sial! Aku hanyalah bocah sepuluh tahun dengan kedewasaan yang datang terlalu cepat kala itu. Akan tetapi aku tidak menyesal. Kedewasaan yang cepat kala itu membawaku ke jalan yang memang sudah sepatutnya terbuka untukku.
Mataku menatap gundukan tanah cokelat yang sudah hampir sama rata dengan tanah. Tidak terasa delapan tahun sudah berlalu semenjak kepergian Mak Sati. Itu artinya aku bukan seorang bocah sepuluh tahun lagi. Tidak. Aku bukan bocah kusam dekil yang akan selalu meratap sepulang dari sekolah, yang akan menonton dengan iri bagaimana orang seusiaku tertawa dengan lepas saat dijemput kedua orangtua mereka di sekolah.
Semuanya sudah berubah sekarang. Aku seorang laki-laki delapan belas tahun. Laki-laki yang berhasil menamatkan sekolah dasar tanpa pernah berniat untuk meneruskan pendidikan. Tidak. Pendidikan tidak selalu harus di lingkungan yang penuh dengan peraturan—penuh dengan biaya ini-itu. Tidak. Aku masih bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus berada di lingkungan terkutuk itu.
Aku melanjutkan hidup dengan menggarap sawah kecil kami—milik Mak Sati di belakang pondok. Seperti janjiku sebelum Mak Sati menghembuskan napas terakhir. Delapan tahun hidup seorang diri di tengah kesunyian. Hidup dengan hasil sawah seadanya, tanpa perlu meminta bantuan orang lain. Tidak. Bukannya sombong, tapi aku masih ingat jelas dengan prinsipku. Mungkin aku pernah berjanji akan mengingkari prinsip sialan itu. Tetapi, tidak setelah Mak Sati ternyata benar-benar pergi meninggalkanku selamanya. Jadi, aku tidak perlu mengingkarinya, bukan?
"Melamun lagi, Dung?"
Ini sura Imam, temanku yang sedikit bernasib sama; Ayahnya pergi saat tahu Ibunya tengah mengandung dirinya. Sudah pernah kubilang, urusan orang dewasa begitu pelik. Apa salahnya dengan memiliki anak?
"Aku tidak akan mendengar suaramu jikalau aku melamun, Mam."
"Oh, ayolah! Aku tahu arti tatapan kosongmu." Imam memberikan tabu manis yang baru ditebang di sawah. "Sering-seringlah makan tabu. Siapa tahu hidupmu bisa semanis rasanya."
"Setelah kau berhasil membuktikannya, maka aku akan turut mencoba," senyum tipis kuberikan pada Imam.
Imam menggigit ujung tabu yang sudah dikupas kulitnya, mengisap habis serat manisnya lalu meludahkan ampasnya ke tanah. "Sudah, Dung. Sudah sering kubuktikan. Lihat ke sana, sayur pahitku semakin subur karena aku sering makan tabu. Dengan suburnya sayur itu, berarti aku tidak perlu hidup dalam kepahitan—seperti namanya sendiri." Imam menghela napas melihat keningku yang mungkin saja bergelombang, "Aku tahu kau pasti paham," kembali digigit tabunya, "Karena kau begitu berpaham."
***
Kuhempaskan tubuh tinggi besarku di atas kayu beralas kasur tipis di pondok—mungkin aku harus menggantinya dengan sebutan rumah—yang sudah kutempati semenjak hadir ke dunia ini. Ya, rumahku. Suara jangkrik dari balik batu berair di belakang rumah ini turut menemani sunyi malamku. Tidak ada hiburan apa pun kecuali tumpukan kertas berisi syair protes atas kehidupan yang diberikan Tuhan. Nyanyian kesengsaraan akan hidup yang kujalani.
Bolehkah protes?
Bukankah protes diperkenankan kepada siapa saja yang merasa tidak menerima keadilan?
Dan bukankah ini sebuah bentuk ketidakadilan dalam hidupku?
Atau bolehkah aku protes kepada Ayah, yang telah dengan kurang ajarnya membentukku bersama Ibu yang telah dengan keterlaluannya tidak menginginkanku?
Terlalu banyak sasaran protesku semenjak lahir ke dunia ini; Tuhan, kedua orangtua yang tidak pernah kuketahui, lalu malaikat maut suruhan Tuhan. Semuanya ingin kuprotes. Namun, kapan aku bisa bertemu dengan mereka semua? Apakah begitu mustahil bagiku untuk bertemu dengan mereka?
Tidak ada yang tidak mungkin.
Persetan dengan kata-kata tersebut. Mengapa rasanya tidak mungkin untuk bisa bertemu dengan Tuhan?
Apakah orang-orang yang memiliki musibah dengan sebutan indigo bisa melihat Tuhan?
Oh, astaga. Aku terlalu lancang untuk berpikir demikian. Namun, aku tetaplah aku. Seorang anak yang berharap bisa bertemu dengan Tuhan; bertanya mengapa aku dititipkan ke dunia ini jika hanya untuk ditelantarkan. Aku hanyalah seorang anak yang ingin untuk diakui oleh orangtuanya. Tidak. Pilihan kedua tidak lagi kuinginkan. Aku tidak perlu lagi untuk mengetahui siapa mereka, karena semua itu hanyalah angan-angan belaka yang akan hilang bersama sapuan angin.
Laksana mawar berduri kecil. Begitulah kehidupan ini kujalani sekarang. Aku ini ibarat mawar, sedangkan Tuhan, kedua orangtuaku, dan malaikat maut, mereka adalah duri-duri kecil yang begitu menyakitkan. Hidupku dikelilingi oleh kesengsaraan.
Pernah sekali aku mencoba untuk mencari tanda-tanda apakah mungkin bisa bertemu dengan Ibuku. Sebab, Mak Sati pernah berkata bahwa kalung yang sudah kupakai semenjak masih bayi ini adalah pemberian Ibuku. Namun, bukankah sekarang sudah begitu banyak orang yang memiliki kalung dengan mainan batu akik ini? Semuanya menjadi begitu mustahil bagiku. Kehidupan begitu tak tersentuh.
Berharap akan kehadiran orang yang tidak pernah ditemui ibaratkan mencium bangkai yang tak akan pernah kautemui.
Hidupku dipenuhi protes. Berkelanjutan dengan pencarian jati diri. Namun, tidak dengan memberikan maaf kepada mereka yang telah membuatku menderita.
Karena aku bukan Tuhan. Aku hanyalah Kidung; laki-laki yang hidup penuh dengan kesengsaraan dan sakit hati. Dan kesendirian.
***
Well, if you want to read my other stories, you can visit my profile IniSandri. But, all is in Indonesian. And if you like poems, you can visit my instagram inisandri.
See you!

Thank you so much for sharing such an amazing one shot story, Yu. Terima kasih!
@IniSandri will gift an Ebook, read and comment on ONE lucky winner's story . Enter her giveaway now. Click here.
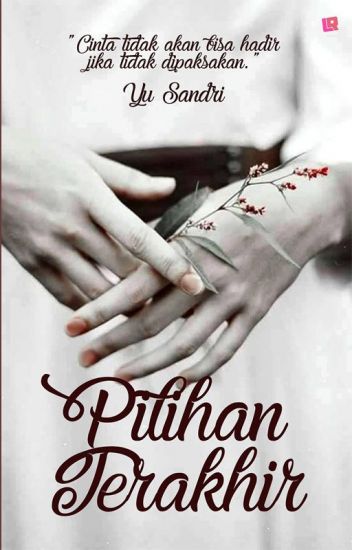

If you have any questions to ask her, feel free to comment below.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top