12 | Dari Kamera Tembus ke Hati
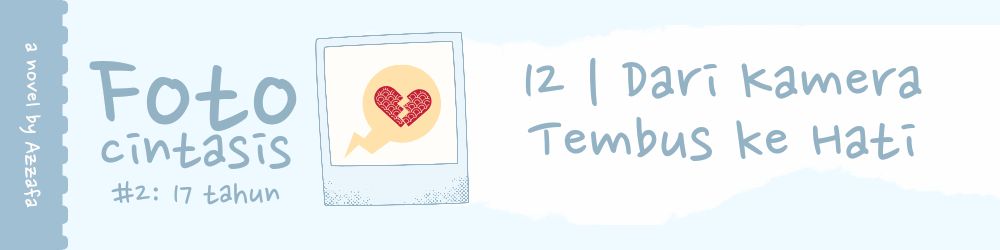
Aku mengawali hari ketiga FLN dengan menunggu Kelvin di luar rumah, bersandar malas-malasan pada pagar. Agak melamun sementara tangan asyik memainkan tali pinggang seragam pramuka. Efek kehabisan baju kasual.
Biasanya aku tidak hobi menunggu seperti ini. Mama berulang kali mengomel karena aku sering menyelinap ke rumah seberang seolah-olah itu rumah sendiri. Padahal niatku hanya memastikan bahwa Kelvin juga berangkat, lalu menghabiskan waktu dengan berbincang dengan Tante Indri. Sesekali juga aku melihat Om Bima pamit pergi bekerja.
Namun, aku mulai menahan diri sejak Kelvin mulai berubah dan sejak aku tahu bahwa Tante Indri hamil lagi. Meskipun katanya dulu beliau menikah muda dan umurnya tidak jauh dari Mama, aku tetap khawatir karena Mbak Lila saja sudah bisa dipinang anak orang kapan saja. Jadi, untuk mengurangi rasa penat Tante Indri, aku mengurangi frekuensi kunjungan.
Yah, kalau Kelvin bolos hari ini, aku bisa berangkat sendiri. Aku juga paham. Mungkin dia agak sakit hati karena tim debatnya kalah dari tim kelasku kemarin. Karena meskipun performa Kelvin dan timnya bagus, performa tim Wahyu-Jenny-Hansamu sedikit lebih berkilau di atas panggung.
Siapa juga yang berselera menonton babak final lomba debat tim lawan? Lebih baik malas-malasan, datang terlambat, atau bahkan sama sekali tidak datang ke sekolah.
Harus kuakui, walaupun kelihatan keren, Kelvin ternyata memang kurang cocok berdebat.
"Lho, Ra? Kok, pakai seragam?"
Nah, ini dia. Panjang umur tetangga gantengku.
Sambil sibuk menyelot kembali pagar rumahnya, Kelvin memindaiku dari kepala sampai kaki. Lalu tiba-tiba dia menarik seringai tengil yang rasanya ingin kucubit sampai hilang.
"Kehabisan baju, ya?"
"Ngaca." Aku misuh-misuh dari seberang jalan, barangkali suaranya agak terlalu besar. Di saat yang sama kutunjuk setelan seragam pramukanya yang juga minus kacu, peluit, dan atribut lain. "Kamu juga pakai seragam."
"Eh, dari kemarin, kan, aku pakai seragam. Buat lomba."
"Cih."
Melihatnya cengar-cengir minta dipukul begitu, sepertinya semuanya tidak seburuk yang kukira. Air wajahnya juga tidak sekeruh yang kubayangkan. Mungkin dia memang tidak ambil hati soal yang kemarin.
"Udah lama nunggunya? Kenapa enggak mampir aja sekalian? Kamu aneh, deh, belakangan ini. Kayak lagi sama orang asing aja." Dituntunnya Jelly menyeberang jalan, berhenti di depanku, barulah dia duduk di sadel depan. "Sip. Yuk, berangkat."
Sambil membuang segala pikiran negatif, aku berdiri di pijakan kaki sepeda Kelvin. "Kenapa enggak bawa motor lagi?"
"Enggak."
"Ya, iya. Kenapa?"
"Hm ..., lagi mau bawa sepeda aja," katanya, menyerah dengan jawaban yang tidak-tidak. "Kenapa? Kamu lebih suka dibonceng pakai motor?"
"Dibonceng kamu pakai gerobak pun aku rela, yang penting gratis." Aku berceloteh di tengah sepinya jalanan. Berpegangan erat pada bahu Kelvin agar aku tidak oleng saat berusaha melihat wajahnya dari samping. "Tapi aku enggak sangka ternyata kamu berangkat ke sekolah hari ini. Kirain bakal bolos karena kemarin kalah debat."
Kelvin misuh-misuh. Jelly berhenti dikayuh. "Buruan turun. Sana. Hus."
"Eh, enggak mau."
"Satu. Dua—"
"Enggak!"
Di pinggir jalan, sudah separuh perjalanan ke sekolah, Kelvin menyikutku main-main dan aku mati-matian bertahan di pijakan tanpa bisa menahan tawa heboh. Jelly mendadak oleng, tapi kali ini aku berusaha untuk tidak terjengkang seperti yang sudah-sudah.
Setelah keributan pagi berakhir, pedal Jelly kembali dikayuh dan perjalanan ke sekolah pun berlanjut.
"Teman-temanmu keren," kata Kelvin tiba-tiba. "Cara ngomongnya Wahyu bagus, Jenny hampir bikin Tere kebawa emosi, dan yang satu lagi ... Hansamu? Mukanya agak mengintimidasi, tapi mulutnya lumayan bisa ditahan."
Sejujurnya, aku bahkan tidak menyangka akan disuguhi pemandangan Jenny dan Hansamu bekerja sama. Dan sepertinya bukan hanya aku; seisi XI Bahasa 2 bahkan mungkin beberapa guru pengajar juga berhasil dibuat melongo.
"Wahyu rajin cekcok sama Dine. Jenny dan Hansa sering sindir-sindiran. Mungkin gara-gara itu aura mereka agak ngajak ribut," kataku. "Tapi kemarin timmu juga keren, lho. Tere semangatnya menggebu-gebu, argumenmu bagus, dan temanmu yang satu lagi itu stok kosakatanya banyak. Aku enggak tahu banyak soal debat, jadi yang kelihatan di mataku kemarin itu mirip orang berantem. Bedanya, yang kemarin itu berantem pakai ilmu. Aku, sih, enggak bakal tahan berdiri di sana."
"Tapi ternyata kamu bisa nonton sampai habis." Kelvin menoleh ke belakang sekilas dengan senyuman. "Kamu juga keren, Ra."
"Aw, makasih." Aku menumpu kedua lengan di bahu Kelvin, agak condong ke depan, lalu kutepuk kedua pipinya pelan-pelan. Tepat ketika dia melirik, senyumku melebar. "Kamu juga keren. Semangat, ya."
Kelvin terdiam, melirik tanganku yang masih di pipinya, lalu entah kesambet jin dari mana tiba-tiba dia berusaha menggigit salah satunya.
Di tepi jalan yang mulai ramai, aku mengomel keras-keras sementara dia terbahak-bahak sampai Jelly oleng lagi.
Mungkin ada baiknya aku mengajak Kelvin santai-santai hari ini.
•∆•
Kutarik ucapanku tadi.
"Tolong, ya, Er."
Andai yang minta tolong barusan bukan Akbar mode OSIS, aku pasti langsung buru-buru pergi sebelum kalimat itu keluar. Nahas kesempatan menolak sudah lewat karena Akbar keburu menyodorkan sebuah kalung panitia dan kamera DSLR yang sepertinya milik sekolah. Soalnya mustahil ada orang yang rela meminjamkan barang mahalnya sendiri. Selain itu, Akbar juga mengalungkan sebuah kamera lain, lebih besar pula.
Ini pasti tugas panitia FLN yang seharusnya turun ke lapangan bersama Akbar, tapi rekannya hari ini hilang entah ke mana.
"Emangnya anak OSIS pada ke mana?" Kelvin mewakiliku bertanya setelah bolak-balik menatap aku dan kamera. Barangkali sejak tadi dia memperhatikan perubahan ekspresi tetangganya. "Bukannya panitia dokumentasi wajib hadir setiap hari selama ada event?"
"Ah, soalnya itu—"
"Enggak apa-apa. Hari ini aku enggak ada kesibukan juga," buru-buru kusela Akbar sebelum suasana makin mencekik. "Dokumentasi santai aja, 'kan? Enggak harus yang bagus-bagus banget?"
Akbar melirik Kelvin yang hanya sedikit lebih tinggi darinya sebelum menatapku lagi.
Lirikannya itu, lho. Astaga. Hampir saja kuraup wajahnya agar dia fokus kepadaku seorang.
"Iya, yang penting foto kegiatan," dia mengangguk. "Tapi kalau bisa hasilnya yang bagus, ya. Anak ekskul fotografi, 'kan? Pasti bisa, dong, Er."
Disindir Akbar di depan Kelvin adalah hal yang tidak pernah kubayangkan seumur hidup. Aku mengenal Akbar selama satu tahun di SMA dan setahuku dia ini kalem serta memiliki aura anak baik. Siapa sangka kalau mulutnya lumayan pedas?
Sudah kuduga. Ini pasti akibat terlalu banyak bergaul dengan Wahyu.
Dan, hei, meskipun aku ini anggota ekskul fotografi, nyatanya aku tidak aktif-aktif amat soal praktik dengan kamera mahal.
Bagaimana bilangnya, ya? Aku ini bisa, tapi hanya sekadar bisa. Kemampuan fotografiku terbilang ecek-ecek karena aku mengandalkan intuisi seperti, Kayaknya kalau difoto begini cantik, deh. Aku tidak begitu profesional, walaupun lumayan paham teorinya sedikit-sedikit.
Cowok futsal yang berdiri di sebelahku ini justru lebih paham soal kamera. Maklum. Dulu di SMP dia ini tukang dokumentasi OSIS. Persis seperti pekerjaan Akbar saat ini.
Setelah Akbar melenggang pergi, Kelvin menghela napas keras-keras.
"Kenapa kamu mau disuruh-suruh begitu?"
Aku menoleh. Mengernyit. Sungguh pertanyaan yang unik dari anak yang sering disuruh ini-itu oleh guru dan dia mau-mau saja.
"Tahu, enggak? Minimal ngaca. Udah dua kali kamu kelupaan ngaca pagi ini," kataku, dengan senang hati mengingatkan.
Namun, Kelvin tampaknya tidak puas dengan friendly reminder dariku. Sekarang dia cemberut hebat. Dongkol bukan main. "Minimal bilang dulu sehari sebelumnya."
Ih, orang aneh. Padahal bisa saja Akbar tidak dapat kabar dari rekannya hari ini. Kenapa malah dia yang marah-marah? Yang disuruh bertugas juga aku. Malah sudah seharusnya Kelvin meninggalkanku sendirian sejak Akbar menghampiriku untuk meminta bantuan. Ipang atau Abang pasti sedang menunggunya di kelas, atau di kantin, atau di mana pun mereka biasa berkumpul.
"Pin, kamu aneh hari ini," kataku tanpa mengalihkan pandangan dari kamera. "Kalau emang mau ikutan keliling-keliling, tinggal bilang aja."
Gerutuan Kelvin mendadak berhenti. Aku menoleh, memastikan bahwa dia sudah benar-benar diam.
Nah, 'kan? Sekarang mulutnya seolah-olah tersumpal sesuatu hingga tidak ada lagi gerutuan yang keluar.
Aku nyengir kuda. "Oalah. Gengsi."
"Enggak, ya." Tanpa bilang permisi, tangan besarnya menyasar kepalaku, menggosok puncak kepalaku hingga longgarlah kepang tunggal mahakaryaku tadi pagi. "Oke, deh. Kira-kira boleh enggak, ya, kalau aku ikut keliling dan bantu-bantu, wahai Mbak Dokumenter?"
"Oh, boleh banget!" Siapa pula yang mampu menolak tawaran asisten gratis? "Yuk, Mas Asisten. Kita mulai dari gerbang."
Bak anak bebek mengekori induknya (atau mungkin induk bebek mengawasi anaknya), aku memimpin langkah dengan Kelvin tepat di belakang. Dengan kekuatan kalung panitia, aku berani mengangkat kamera terang-terangan.
Kelvin lalu bilang bahwa ada baiknya menghemat penyimpanan sampai acaranya dimulai, atau paling tidak sampai terjadi sesuatu yang meriah. Aku yang amatir ini memutuskan untuk menurut. Ucapan seorang asisten itu juga penting.
Menjelang penampilan drama musikal dari klub teater, aku dan Kelvin pindah ke pinggir lapangan, tak jauh-jauh dari panggung. Di sana pula kami bertemu Dine, Ipang, dan Galang.
Berbagai macam keluhan meluncur dari mulut Dine, menyalahi aku yang tidak memberi kabar lebih dulu, juga mengomeli Kelvin yang—katanya—malah kegirangan mengekoriku ke mana-mana.
Di balik bahunya, Ipang mengangguk-angguk di setiap ucapan Dine. Rambut brokolinya yang makin gondrong ikut bergoyang-goyang. Entah apa tujuannya. Kalau dia bermaksud untuk membuatku sebal, dia berhasil.
"Ini lagi. Bukannya berusaha cari kawanan sebangsanya, malah ngayap ke kelas tetangga gara-gara kesepian, berisik, nempel terus lagi." Dine menunjuk Ipang dengan ibu jari, bersungut-sungut jengkel, sementara yang ditunjuk malah tersenyum sambil menelengkan kepala berulang kali. "Jauhan sana, ah!"
Ipang cemberut. "Dine jahat."
Dine menyikutnya agar menjauh. "Gerah!"
"Pang," kuperingatkan dia. "Dine PMS. Dua hari lagi dia mens."
Ipang segera bergeser dan merapat ke Kelvin.
Di sisi lain, Galang secara ajaib tidak terlalu tengil pagi ini. Dia malah sibuk menoleh ke sana kemari selama Dine marah-marah.
Kutanya dia, "Kenapa, Lang? Cari siapa?"
"Bebebku," jawabnya, dan aku harus menahan diri untuk tidak bergidik geli. "Kalian lihat, enggak? Tadi udah kucari di ruang ganti anak teater, tapi dianya enggak—"
"Eh! Galang!"
Hanya dengan satu suara, mata Galang mendadak berbinar-binar. Bergegas dia mencari sumber suara, celingukan, dan senyumnya langsung mereka ketika berhasil menemukan Putri yang hampir tenggelam di keramaian. Untung saja kostumnya agak mencolok.
Galang bergegas menghampiri Putri, menganggap aku dan yang lain sebagai angin lalu. Dia berhenti tepat di depannya, agak menunduk sementara Putri mendongak untuk pamer jajanan. Senyum lebarnya berubah menjadi cengiran.
Tanganku refleks menekan tombol shutter untuk mengabadikan pemandangan yang lucu dan membuat Dine iri ini.
"Ah, bete. Di mana-mana orang pacaran."
Nah, 'kan? Sudah kubilang, pemandangan ini membuatnya iri.
"Daripada bete, mending kita jajan juga," usul Ipang, dengan antusias menunjuk sebuah stan yang letaknya di seberang lapangan, tepat di sebelah gerbang. "Stan yang itu jajanannya enak-enak, lho. Baru buka kemarin, tapi langsung ludes sebelum jam sepuluh. Mau coba, enggak? Mumpung belum ramai banget."
Dine bersedekap, bergumam-gumam, dan ditutup dengan anggukan setuju.
"Oke," katanya, lalu dia beralih padaku, "Kalian mau ikut? Apa mau pacaran aja sampai perut keroncongan?"
"Sembarangan." Kutendang ujung sepatu Dine. Tak peduli bibirnya manyun berapa senti. "Ayo, ah. Bareng aja."
Ipang memimpin jalan. Dine melangkah di sebelahnya. Di bawah potongan bendera kertas warna-warni yang digantung sepanjang lapangan, mereka mengobrol dengan suara yang tidak dapat kudengar serta dengan gerakan tangan yang antusias. Orang-orang yang berlalu lalang di sekitar sama sekali tidak memedulikan mereka.
Sekali lagi aku mengangkat kamera, berhenti sejenak untuk mengabadikan momen itu.
"Dari tadi jepretnya orang pacaran terus, ya."
Aku terkekeh-kekeh bangga. Membiarkan Kelvin agak membungkuk dari balik bahuku, berusaha mengintip layar kamera.
"Dari segi mana pun enggak kelihatan kayak sengaja minta foto, kok. Tuh. Bagus, 'kan? Yang Galang sama Putri tadi emang kayak romantis, sih, tapi yang Ipang sama Dine ini vibes-nya kayak betul-betul menikmati festival. Ngobrol santai, stan jajanan, dikelilingi manusia-manusia pengunjung FLN juga." Meskipun agak ngawur, kujelaskan semuanya dengan sudut pandang yang profesional agar foto ini dapat bertahan. "Tuh, lihat. Langitnya cantik, lighting-nya alami, proporsi benderanya seimbang, bokeh pula. Akbar enggak boleh hapus yang ini, sih, pokoknya. Wajib masuk ke medsos OSIS."
Kudengar Kelvin mendengkus geli sambil kembali berdiri tegak. "Lumayan juga hasilnya. Katanya amatiran?"
"Secara teknik pengambilan gambar, iya. Secara feeling, mungkin enggak," jawabku. Bangga bukan main. "Berapa kira-kira nilaiku?"
"Sepuluh."
"WAH—"
"Dari seratus."
"Cih. Jahat, ya, kamu. Aku kecewa sama kamu."
Tawa rendah Kelvin entah kenapa membuatku dongkol. Kutatap sinis dirinya, tapi anaknya malah makin girang.
"Kalau kamu bisa foto aku sekali jepret dan hasilnya estetik, kutambah nilaimu jadi sebelas."
"Idih?"
"Jangan idih, dong. Sakit hati, nih."
"Kalau aku bisa ambil gambar kamu dalam sekali jepret dan hasilnya estetik ...," aku mengangkat dagu agar terlihat sedikit lebih mengintimidasi, "traktir aku satu jajanan di stan yang Ipang tunjuk."
Kelvin manggut-manggut. Barangkali sudah merasa terbiasa. Malah aneh kalau dia minta selain itu, barangkali adalah isi pikirannya.
"Kalau malah dapat komuk jelek," katanya, "kamu yang bawa sepeda pas pulang."
Wah ....
WAH.
OKE.
Begitu cara mainnya, saudara-saudara! Licik! Manusia licik! Picik! Udang di balik bakwan!
"Oke. Deal."
"Deal." Kelvin mengangguk, mendahuluiku beberapa langkah, lalu berbalik menghadapku tanpa berhenti bergerak bak cacing kepanasan. "Mulai. Satu jepretan. Harus bagus."
Mendengkus, kuangkat kamera dengan serius. Setelah kutunggu beberapa detik, sialnya Kelvin tak kunjung berhenti. Dia terus berayun ke kanan dan kiri bahkan ketika disapa oleh temannya yang lewat. Setelah mereka selesai mengobrol singkat pun dia masih tidak berhenti juga.
Dan yang lebih menyebalkan, dia tidak melihat ke arah kamera sekali pun.
"Pin."
"Hm?"
Aku mencebik. Lelah mengangkat kamera ke depan wajah, akhirnya kuturunkan benda itu setinggi dada dalam posisi siaga. "Kalau misalnya tiba-tiba kakiku keseleo dan enggak bisa bonceng kamu pulang, gimana?"
"Hei, mulutnya." Kelvin tampak mati-matian untuk tidak melihatku. Mulutnya cemberut.
"Kan, misalnya," kataku, kembali bersiaga dengan kamera. Wajah Kelvin—masih melihat-lihat ke arah lain—kini masuk ke frame. "Kalau nanti aku bikin sostel aja, gimana? Dari kemarin aku mau bikin, tapi kelupaan terus."
Dari frame kamera, aku bisa melihat Kelvin mengulum senyum, sok-sokan berpikir keras. Dia menatap langit, menatap orang yang lewat di depannya dengan segelas es teh di tangan. Lalu ketika senyumnya melembut, dia menatap kamera dan jantungku mencelos seketika.
"Boleh—"
Bunyi CEKREK yang renyah menyadarkanku dalam sekejap. Diam-diam aku merasa bingung, tidak sadar kalau telunjukku sendiri yang menekan tombol shutter. Kemudian aku tergelak kegirangan begitu sadar hasil fotonya bagus.
"EH, DAPAT! AHAHAHA! MANTAP!"
Kelvin mendekat. Tangannya menahan kepalaku untuk tidak melompat-lompat dan berputar-putar. "Pusing. Awas itu ada orang yang mau lewat."
Dengan super bangga, aku merapat pada Kelvin, dan kuangkat kamera serta kupamerkan hasil foto yang tadi. Memang tidak simetris-simetris amat, tapi di situlah poinnya. Efek bokehnya menambah kesan dramatis. Ditambah lagi dengan tatapan Kelvin yang ... wah.
Aku pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Misalnya saat Ayah disambut Mama setelah pulang kerja, mata dan senyumnya akan terlihat seperti itu. Kukira hanya Ayah yang begitu, tapi rupanya aku juga melihat tatapan yang sama di mata Mama saat Ayah menemaninya selama memasak di dapur. Terkadang, kalau mampir ke rumah Kelvin pagi-pagi, Om Bima memasang tatapan yang sama sebelum dan sesudah mencium kening Tante Indri. Bahkan pernah satu kali sebelum Mbak Lila kembali ke kosan, pacarnya mampir untuk mengajak jalan sore dan tatapannya pun begitu juga. Tidak kusangka Kelvin punya tatapan yang serupa.
Kenapa, ya? Apa semua orang memang begitu? Apa mungkin mataku begitu juga?
"Mana fotonya? Enggak kelihatan."
"Eh." Aku berkedip. Terbangun dari lamunan. "Sebentar."
Pelan-pelan aku menjauhkan diri, tapi Kelvin malah membungkuk di sebelahku, berusaha melihat hasil foto sekali jepret kebanggaanku. Dari jarak sedekat ini, aku bisa merasakan rambutku menggesek pipinya dan hidungnya bisa kusundul hanya dengan satu telengan kepala.
Dari jarak sedekat ini pula, aku mencium wangi parfum. Wanginya agak berbeda dari biasanya, tapi enak. Apa ini? Dia pakai parfum baru?
"Kamu ganti parfum?"
"Kamu ganti sampo?"
Aku menatap Kelvin. Kelvin menatapku.
Kami terdiam berdua, melongo, lalu cekikikan berjamaah.
"Iya, aku ganti parfum." Kelvin menjelaskan lebih dulu, bahkan sampai menggosokkan pergelangan tangan ke baju dan mengulurkannya padaku. "Wanginya gimana?"
Aku refleks mendekat dan mengendus pergelangan tangannya. Mungkin mataku menipuku, tapi aku melihat tangannya agak tersentak.
"Wah, enak," aku bergumam. Agak kagum dengan tipe aromanya. "Yang ini lebih lembut, bukan wangi yang cowok banget kayak parfummu yang kemarin, tapi enak. Kayak ... apa, ya? Wangi hutan? Suasananya itu, lho."
Kalau Kelvin cekikikan karena aku menyebut wangi hutan, akan kubawa Jelly pulang sendiri. "Suka?"
Ya?
Siapa?
Aku?
Ke parfumnya?
"Mm-hm." Aku mengangguk walaupun agak bingung. "Aku suka."
Kelvin manggut-manggut lalu menunjuk rambutku. "Sampomu gimana? Kenapa ikut-ikutan ganti?"
Sambil bergumam, aku mengambil ujung kepangan untuk kuendus. "Tadi pagi stok sampo di rumahku habis. Mendadaknya kebangetan kayak tahu bulat, jadi aku langsung ke luar cari warung. Untung aja ada yang buka. Barusan kecium banget, ya? Gimana wanginya? Enak, 'kan? Enggak nyengat?"
Lain dariku, Kelvin tidak mengendus ujung kepangan yang sudah kusodorkan. Dia malah mengusak rambutku lagi sampai wangi samponya menguar lembut. "Enak, kok. Wangi buah."
"Kamu suka?" Aku balas bertanya dengan maksud membalikkan pertanyaannya yang tadi, tapi Kelvin malah terkekeh-kekeh.
"Iya. Suka."
"BUSET. DARI TADI DITUNGGUIN TERNYATA MASIH DI SITU-SITU AJA?!"
Masih berdiri di stan jajan yang sama, Dine lagi-lagi meledak. Memang agak gila dia ini. Bahaya betul emosinya di hari-hari menjelang menstruasi.
Tuh, lihat. Walaupun kantong plastik yang dia genggam sudah penuh dengan aneka ragam jajanan, mulutnya masih saja mengomel.
Ipang pun hanya bisa berdiri pasrah di sebelahnya. Membungkuk-bungkuk minta maaf kepada murid yang lewat dengan tatapan terganggu.
Aku cengar-cengir. Merasa bersalah, tapi asyik juga melihat sohibku marah-marah.
"Khodamnya keluar." Kelvin mengedikkan bahu, tertular cengiranku. "Yuk?"
Yah, bolehlah. Sekarang aku juga mendadak lapar. Beli jajanan sebelum menonton drama sepertinya seru juga.
Sementara Kelvin berjalan memimpin, aku melangkah pelan-pelan di belakangnya. Sibuk memeriksa hasil foto-foto yang sebelumnya, menimbang-nimbang apakah sebaiknya kuhapus atau tidak. Soalnya, kan, ini kamera sekolah. Gawat kalau ada berita mading bertajuk "Kesempatan Dalam Kesempitan: Anggota Tim Dokumenter FLN Diduga Hanya Mengincar Siswa Tampan".
Meski begitu, aku masih merasa kagum. Tidak kusangka foto sekali jepretku bisa terlihat sebagus itu untuk ukuran amatir.
Namun, ada sesuatu yang janggal di dalam foto. Makin dilihat baik-baik, makin terasa pula apa yang janggal. Di bagian pinggir foto, tak jauh dari gerbang, ada sosok pria familier yang pernah kulihat sebelum-sebelumnya. Sama seperti yang kulihat di karyawisata kelas 10, di tengah perjalanan bersama Kelvin, juga di depan pagar rumahku sendiri.
Tahu-tahu saja aku sudah berlari ke arah gerbang.
Kalau memang sejak tadi orang itu berkeliaran di sana, itu artinya dia belum pergi jauh. Lucu kalau berspekulasi dengan gagasan dia hanya asyik berkeliling atau iseng mampir ke sekolahan yang sedang mengadakan festival. Dia pasti punya tujuan.
Ini kesempatan. Aku harus bertemu dengannya. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Ada banyak hal yang harus dia katakan.
Kami harus bertemu.

Catatan Jempol:
Tarik napas, semuanya. Pegangan. Mulai dari sini perjalanannya bakal agak berguncang dan banyak kelokan. ୧( ಠ Д ಠ )୨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top