Chapter 62. Move On (BACA EXTRA PART EPS 7. Menyerah di Karyakarsa)
Extra Part 7 dari 10 extra part Factory Romance udah aku update di karyakarsa, ya.
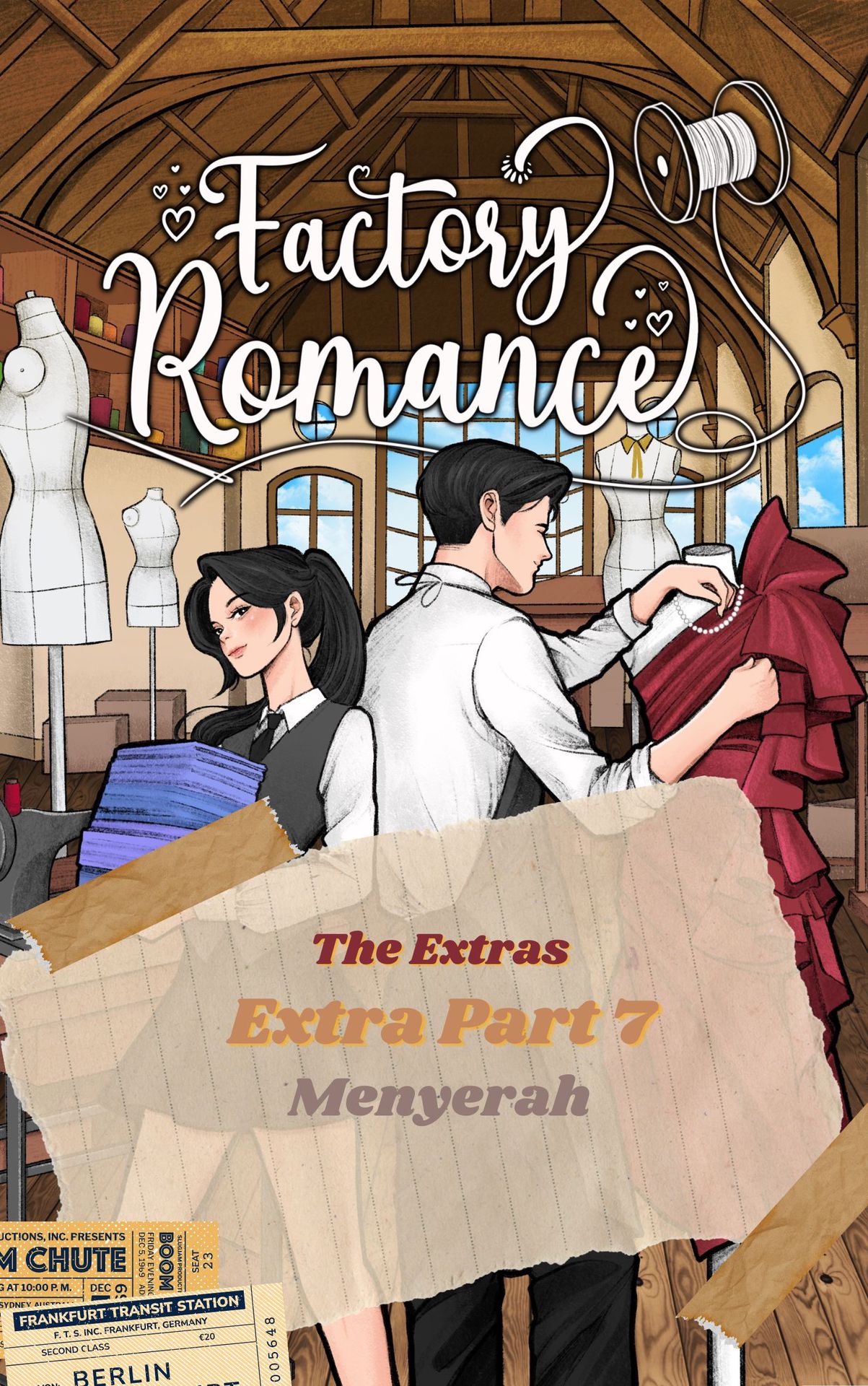
Selamat membaca.

Untuk pembaca wattpad yang tetap ingin membaca cerita ini sampai tamat, silakan nabung dulu karena nanti chapter 71-100 versi wattpad akan aku share di karyakarsa dengan harga lebih hemat.
FR akan berhenti diupdate di Wattpad pada chapter 70, ya ^^

Chapter 62
Move On
Pram menggenggam kembali jari jemarinya. Dia menoleh padaku seolah meminta penjelasan. Apa salahnya?
Kalau dia hanya salah satu teman seangkatanku di SMA, aku bisa menjelaskannya dengan mudah. Ayah dan ibu membenci semua teman seangkatanku di SMA. Semua. Sampai beberapa tahun pasca kejadian, ibu bahkan membatasi diri dari acara-acara kompleks. Hampir semua teman sebayaku yang tinggal di kompleks bersekolah di SMA yang sama denganku, itu berarti orang tua mereka satu rukun tetangga dengan kami. Meski Ayah dan ibu tahu nggak semua siswa paham apa yang terjadi, mereka tetap sakit hati karena nggak seorang pun membelaku. Mereka berpikir, apa yang terjadi padaku pasti pernah juga dialami siswi lain, padahal mungkin memang tidak. Hanya aku yang nggak beruntung sore itu. Mereka baru membuka diri setelah Grace kembali ke rumah dan tercatat sebagai warga. Like always, Grace membuka mata semua orang dengan ketajaman mulutnya.
Namun, nama belakang yang disebutkan Pramana memberi Ayah seribu alasan untuk membencinya secara instan.
"Gimana dia bisa ada di sini?" tanya Ayah dingin.
Aku maju. "Yah... Pramana... juga rekan kerjaku di kantor...," terangku, terbata. Berharap itu sedikit melunakkan hati Ayah.
Ayah menatapku. Sejuta tanda tanya menambah kerut merut di keningnya.
Sudah lama sekali sejak kali terakhir kami membahas tentang insiden sore itu. Kurasa Ayah juga nggak mau membicarakannya lagi. Beliau mengendurkan rahangnya yang mengetat. "Kebetulan yang aneh sekali," katanya pelan. "Lalu... buat apa jam segini dia masih di sini? Bukannya jam kerjamu sudah berakhir beberapa jam yang lalu, Nggrid?"
"I—iya... Pram... ada sedikit urusan sama Inggrid—"
"Urusan apa yang bikin kamu sampai basah kuyub begitu? Hm?" tanyanya. Ayah lantas mendekat padaku dan menyeretku ke bawah naungan payungnya. Hujan saat itu sudah tinggal gerimis saja. Beliau membelakangi Pramana. "Bachtiar... berarti dia anaknya Sri Astuti?"
Aku mengangguk.
Suara Ayah semakin pelan, "Apa urusannya di sini?"
"Dia buyer QA-ku di kantor, Ayah," jawabku gugup. Kubiarkan Ayah menanggalkan jaket dan menaruhnya di pundakku. "Kami tadi... sama-sama lembur."
Alis Ayah yang sebagian sudah memutih mengerut curiga. "Satpam kompleks tadi nelepon rumah... katanya kamu pulang bawa sepeda hujan-hujanan. Kamu habis lembur dari mana?" selidiknya. Tangannya yang masih ada di bahuku lantas mencengkeram. "Apa dia gangguin kamu?"
"Enggak."
"Apa dia ngebahas-bahas soal yang lalu?"
"Enggak," sahutku cepat. Khawatir Pramana bisa mendengar. "Kami nggak pernah ngomongin itu."
Raut Ayah justru semakin nggak enak dilihat. "Sombong sekali," geramnya tertahan. Beliau menoleh sekilas ke balik pundaknya, menilik Pramana yang masih berdiri di bawah hujan dan Benny yang menunggui kami di teras. "Masuk aja," perintah Ayah. "Biarin Benny nemenin kamu sampai kamu tidur. Suruh dia pulang."
Belum juga aku ngomong sesuatu, Ayah sudah berbalik dan menghadapi Pramana dengan dagu terangkat dan dada membusung lebar. "Kamu bisa pulang sekarang?"
Pramana tergeragap.
"Tolong pulang sekarang juga dan jangan temui Inggrid selain di kantornya," sambung Ayah tegas. "Gimana kalian bisa kerja di kantor yang sama? Apa kamu sengaja?"
Pram semakin bingung.
Aku berusaha mencegah segalanya menjadi semakin rumit. Kutarik lengan Ayah supaya dia berbalik padaku. "Pramana nggak ingat apa-apa," bisikku. "Dia kecelakaan dan nggak ingat apa-apa. Inggrid mau tetap seperti itu."
Reaksi Ayah sama sekali nggak kuduga. Beliau bertanya, "Dia masih nggak ingat apa-apa sampai sekarang?"
Masih nggak ingat sampai sekarang? Gantian mukaku yang mengerut bingung. Kok ayah nggak kaget, heran, atau ragu mendengar bisikanku tentang kecelakaan yang dialami Pram? Terlebih soal Pram yang nggak ingat apa-apa. Aku nggak sempat nanya, Ayah sudah telanjur kelihatan jauh lebih lega.
"Nyaman sekali hidupnya kalau begitu," celetuknya. "Kamu merasa lebih nyaman nggak membicarakannya?"
Aku mengangguk.
Ayah juga mengangguk. "Mungkin kamu benar. Udah saatnya mempertimbangkan pekerjaan lain kalau di pabrik harus berurusan sama orang-orang jahat ini. Kesehatan mentalmu yang utama, Nggrid."
Habis bicara begitu, suara Ayah menggelegar menyuruh Benny tinggal sampai aku tidur dan terang-terangan mengusir Pram dari rumahku. Setelah interogasi singkat Ayah tentang hubungan Pramana dan pekerjaanku berakhir, beliau pulang duluan.
"It's not going to work, Mbak," kata Benny begitu kami berdua masuk rumah. "Ayah belum bisa move on."
Aku cuma bisa mendesah.
"Kamu sendiri udah bisa move on?" tanyanya.
"Move on dari apa?" balasku malas.
"Jangan pura-pura. Dia orang yang kemarin aku lihat di sini, kan? Kalau kalian pacaran... berarti mau nggak mau kamu bakal berurusan sama orang yang paling dibenci Ayah sedunia. Kamu mungkin udah jatuh cinta, tapi aku nggak yakin ayah bisa terima. Kamu tahu nggak? Sampai sekarang Ayah masih nggak mau tegur sapa sama Pak Dayat dan Pak Jati cuma karena anak-anak mereka dulu sekelas sama kamu. Ayah nyalahin semua orang, termasuk orang-orang yang nggak salah. Apalagi anaknya dokter gila itu!"
Apalagi kalau ayah tahu Pramana yang mengundangku ke gudang belakang sekolah sore itu.
"Aku nggak tahu, Ben. Kamu mending pulang aja kalau mau pulang. Aku capek, mau langsung tidur."
"Aku mau live stream pake HP di sini aja," kata Benny. "Di rumah pasti lagi ribut-ribut."
Keesokan harinya, Benny udah nggak ada di kamar sebelah waktu aku bangun. Badanku nggak keruan gara-gara semalam keujanan. Tidurku juga nggak nyenyak. HP kumatiin buat jaga-jaga kalau Pram memberondongku dengan berjuta pertanyaan. Namun, saat kuhidupkan kembali, nggak ada satu pesan pun kuterima darinya. Mungkin Pramana udah capek nanya. Dia tahu aku nggak akan jawab apa-apa.
Pagi ini hujan lagi... hujan lagi....
Inginnya aku membolos, tapi nggak mau dianggap pengecut sama Pram. Aku mesti jawab apa kalau dia nanyain tentang sikap buruk ayah semalam? Kebohonganku semakin sulit kupertahankan. Apa aku benar-benar nggak punya pilihan selain menceritakan kembali kejadian di gudang belakang sekolah ke Pramana?
Apa itu akan bikin Pram teringat semuanya? Termasuk terlibat, atau enggaknya dia dengan insiden itu? Dia menulis namaku di jurnalnya. Dia menulis surat cinta dan tersenyum padaku sebelum kelas sore itu dibubarkan. Dia juga muncul pertama kali di gudang bersama Diana dan beberapa anak perempuan yang tertawa-tawa riang.
Apa artinya kalau bukan mereka yang merencanakan semuanya?
Kamu sudah ingat lagi, kan, Nggrid? Kenapa kamu seharusnya benci Pramana? Ayo benci dia. Benci dia. Benci dia!
Aku nggak bisa.
Honda Jazz tuaku berdecit di aspal yang basah saat membelok tajam di depan pagar. Mesin-mesin dan rangkanya pasti sudah mulai habis dimakan karat karena keseringan tersiram air pasang dan hujan di Kawasan Berikat. Kalau diibaratkan usia mobil, mungkin kondisi psikologisku sama dengan Honda Jazz ini. Belum terlalu tua, tapi sudah uzur. Keujanan campur pikiran dikit aja, bangun-bangun punggung menjerit dan perut kembung.
Aku berdiam di belakang kemudi. Mesin mobil sudah mati. Sabuk pengaman sudah terlepas. Kalau bisa, aku ingin menghidupkannya lagi, lalu berbalik meninggalkan area pabrik. Orang lain mungkin berpikir, percuma sudah jauh-jauh menyetir, bergelut dengan kemacetan dan rintik hujan yang nggak kunjung berhenti cuma buat putar balik, kembali menggeluti jalanan yang muram hanya biar bisa tidur dengan pakaian lengkap dan riasan wajah.
Kenapa nggak dari awal mutusin bolos aja?
Orang-orang yang punya pikiran kayak gitu pasti nggak pernah ngerasain derita depresi. Aku rela kehilangan pekerjaan buat kembali bergelung di balik selimut dan menikmati hujan sambil minum teh panas. Entah kenapa aku nggak pernah benar-benar mengundurkan diri dari pekerjaan tanpa alasan.
Ini bukan soal tagihan yang hanya akan terbayar kalau aku terus bekerja, bukan soal eksistensi diri, dan semacamnya. Aku sudah menipu diriku terlalu lama, aku nggak pernah menginginkan semua ini. Masalahnya, aku juga nggak tahu apa yang sebenarnya kuinginkan. Oh aku tahu. Yang kuinginkan adalah kebebasan. Sesederhana itu. Bisa kembali tidur karena pagi itu nggak kepingin bangun... itu yang kumau.
Aku lelah.
Semalam, mengaku jujur pada Pramana bahwa kami nggak pernah pacaran rasanya seperti sebuah ide yang brilian. Aku sudah menuruti hati nuraniku. Aku berkata jujur. Que serra-serra. Whatever will be, will be.
Pagi ini, aku ingin menghapus semuanya, pura-pura malas bertemu dengannya seolah dia mantan kekasih yang nggak pernah ingin kutemui lagi, mendengarkan rayuannya, dan menolak pelukannya. Aku sudah membuktikan, aku nggak perlu memaafkannya atau melupakan kejadian belasan tahun lalu yang begitu dalam menoreh luka di hati remajaku untuk kembali menyukainya lagi seperti dulu. Mungkin aku nggak pernah membencinya. Mungkin yang kubenci adalah kenyataan bahwa aku nggak akan pernah bisa memilikinya.
Dulu... maupun sekarang.
Aku nggak bisa nyalahin Ayah yang memusuhi semua teman SMA-ku, apalagi Pramana. Dari sekian banyak siswa yang menertawakanku, nggak seorangpun membelaku. Saat ditanyai, nggak seorang pun tahu bagaimana kejadiannya sampai bisa begitu. Aku sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya disampaikan oleh kawan-kawanku, tapi kepala sekolah dan ketua yayasan yang menangani langsung kasusku—menurut ayah—terdengar setengah menuduh bahwa aku memang datang ke sana untuk berciuman dengan Pandu, lalu tertangkap basah.
Itu menjijikkan. Pandu. Memikirkannya saja aku ingin muntah.
Pandu memang dihukum, dia diskors beberapa minggu. Akan tetapi, memang dasarnya anak nakal, setelah diskors Pandu nggak pernah lagi datang ke sekolah. Dia juga nggak muncul pada hari ujian akhir dan hampir nggak lulus kalau saja pihak sekolah nggak mencari dan menemukannya. Mereka menyeretnya ke sekolah buat ujian susulan. Sekilas, itu nggak ada hubungannya denganku, tapi enggak dengan pikiran semua orang.
Yang bikin ayah semakin marah, orang-orang berbalik menuduhku sebagai penyebab hancurnya masa depan Pandu. Suatu hari saat beliau datang ke sekolah untuk mengurus administrasi, Ibu Pandu menghampiri dan nyaris memukulnya. Aku nggak bisa melupakan raut ayah saat beliau pulang siang itu. Di dapur, dengan rahang mengatup dan suara bergetar, dia bilang pada ibu betapa dia merasa semua orang menatapnya dan seolah bertanya, apa putrimu sudah puas menghancurkan hidup seseorang?
Saat itu, aku merasa yakin keputusanku menyembunyikan surat Pramana dari siapapun sudah tepat. Kalau aku menunjukkan surat itu dan Pramana menjadi tersangka utama perundungan, lalu dia melakukan hal bodoh yang sama seperti Pandu, entah bagaimana orang-orang akan memandangku.
Pramana; siswa unggulan, mantan kapten team basket, idola murid-murid perempuan, putra pasangan kepala sekolah sebuah SMP Negeri di kota yang sama dan ketua yayasan di SMA kami, sekaligus dokter baik hati yang taman bunga di depan rumahnya paling indah di kompleks perumahan, pemuda tampan, dan sempurna.
Sedangkan aku? Rahasiaku menguntit Pramana bertahun-tahun sudah bukan rahasia lagi sejak aku membocorkannya pada Diana. Aku hanya akan dianggap remaja obsesif patah hati yang marah karena dikerjai sedikit oleh Pramana. Itu cuma permainan anak-anak. Hanya ciuman biasa. Tidak perlu dilebih-lebihkan.
Pokoknya, posisiku sebagai korban semakin hari terasa semakin nggak valid. Nggak ada yang peduli pada perasaanku, kecuali ayah dan keluargaku.
Dan itu bukan hanya ciuman.
Demi Tuhan.
Hatiku menjengit pedih setiap kali mengingatnya.

Boleh lanjut baca chapter ini di karyakarsa.
Terima kasih udah vote dan komen
Jangan lupa follow instagram baruku, kincirmainan_19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top