Chapter 52. She Closed Her Eyes (CHAPTER ENDING SUDAH TERSEDIA)
Chapter penghabisan alias ending alias tamat udah dipost di karyakarsa, spesial pula. Part 70-100 nantinya nggak akan ada di wattpad, ya...
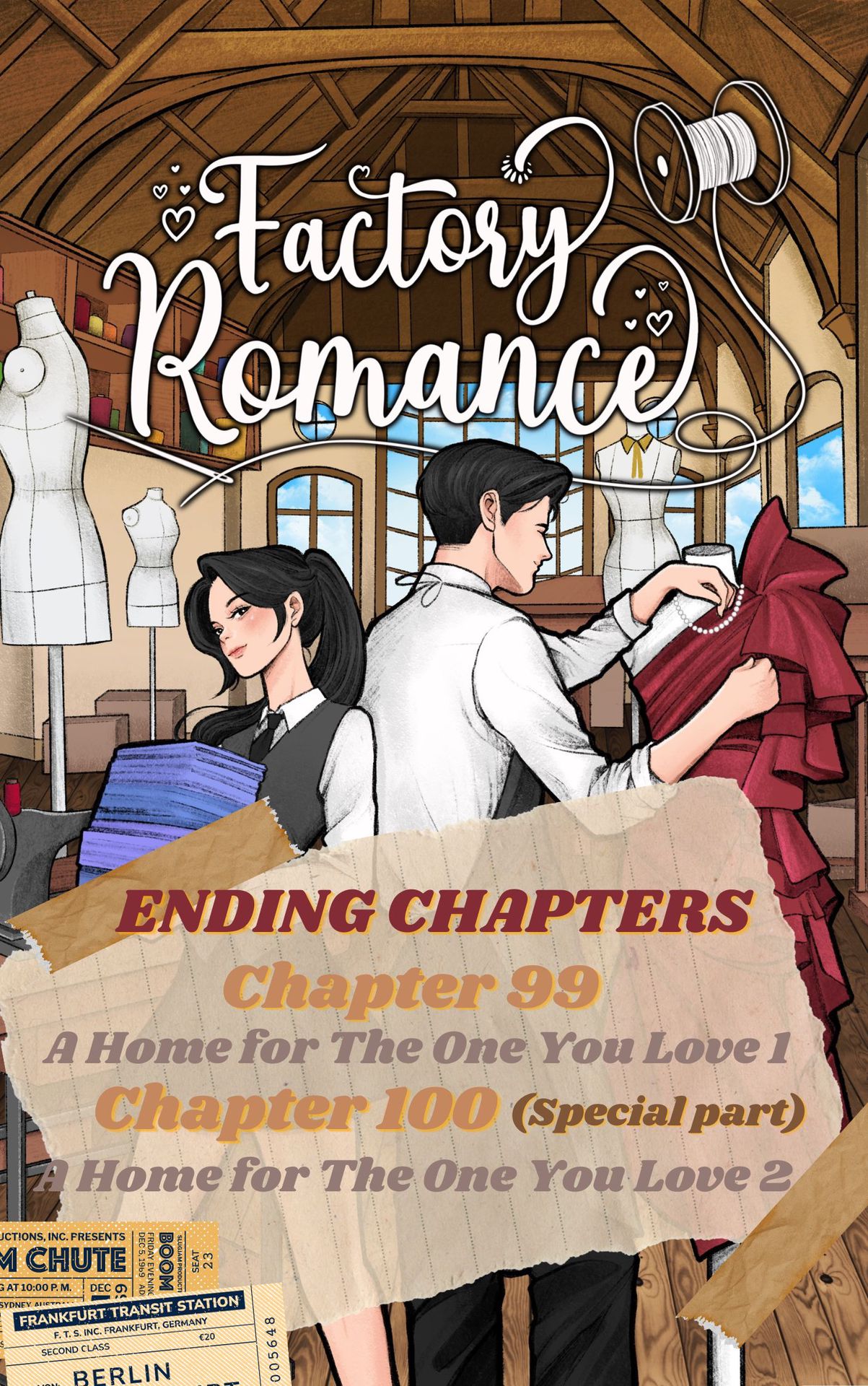
Chapter 52

POV PRAMANA
She Closed Her Eyes
"Pramana...?"
Aku sedang mengetik, How to talk to someone you love without making her angry. Ternyata, Elliot sedang bicara padaku. Tentu saja dia bicara padaku. We are having a video conversation. Maksudku, tadi dia melantur soal project ini dan itu. I don't even bother listening. Sekarang dia baru sadar aku sama sekali nggak memperhatikan.
"What do you think?" tanya El.
You wanna know what I think? I think Inggrid is crazy. "I think it's great," kataku.
Elliot melipat bibir dan tersenyum. "Did you listen to what I am saying?"
"I—eum...." I didn't. Aku nggak bisa berhenti mikirin kegilaan Inggrid, El. Dia kayak petasan. Dia mirip bubuk mesiu. Kamu gesek dikit aja, meledak. Aku pengin teriak di mukanya, I want to caress you. Let me try! Dia terus mendorongku menjauh. Bikin aku frustrasi. Apa yang terjadi? Apa yang bikin emosinya terus menerus tersulut? Is it me? Atau dia selalu kayak gitu sama lawan jenis? This has to stop. Aku harus nyari tahu apa yang terjadi sama masa lalu kami dan kayaknya aku nggak mungkin nanyain hal itu ke Inggrid. I need to be more sensitive. Clearly, we have issues.
"What's the matter? You seemed troubled. Something happened in the factory?"
Tadi dia nanyain back strap dress yang fotonya baru aja kukirim. Inggrid kelihatan cantik di foto-foto itu dan yang kupikirkan cuma satu, apa yang sedang dilakukannya dengan Samudra Gandhi di Spiegel selain bicara? She kept coming back to him. Dia udah dibohongin, dia harus menendang selangkangannya to make her point, tapi dia tetap menemuinya. Aku paham dia khawatir soal temuan itu, tapi aku ngerasa dia merespons Gandhi terlalu cepat. Gandhi mau ketemu di pabrik, dia mau. Gandhi mau ketemu di Spiegel, dia mau. Aku harus antre kopi jam enam pagi di KFC supaya nggak ngantuk demi nyamperin dia pagi-pagi buta so we can talk again like normal persons. Itu aja nggak cukup. Apa yang harus kusimpulkan? Did she want him? Apa dia masih bimbang mau sama aku, atau sama Gandhi?
"Sorry, El. I am... not foccused. I have to share my thoughts with other things here. I guess I am not in a best condition to discuss about the dress yet—too many on hand works here," bualku.
Akhirnya, Elliot setuju kami menunda pembicaraan setidaknya sampai akhir hari.
Aku mengemasi barang-barang dengan cepat. Hujan deras di luar semakin meresahkan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Menelepon Diana dan membuat janji temu, atau berbuat sesuatu sekarang juga, sebelum terlambat?
Sudah kucoba menekan keinginan menyusul Inggrid ke Spiegel. Relaks, itu cuma makan malam. Memangnya Gandhi mau ngapain di sana? Merayunya? Tentu dia akan merayu. Hanya itu yang bisa dilakukannya di tempat umum. Berkata-kata manis. Lalu aku ingat, aku selalu lebih bisa membujuk Inggrid dengan kata-kata manis. Dia suka mendengarnya. Dia luluh lebih mudah dengan kata-kata. Part of her is a writer. Words move her. Dan dia sedang rapuh gara-gara emosi.
Aku percaya Inggrid nggak akan ngelakuin hal bodoh kayak jatuh ke pelukan Gandhi, atau semacamnya. Kalau Gandhi mengambil kesimpulan yang sama kayak aku, dia nggak akan cepat-cepat memindahkan pertemuan itu ke tempatnya menginap. Inggrid akan langsung menolak. She's super aware when it comes to physical touch. Setiap kali kami naik ke tahap selanjutnya dalam sentuhan fisik, selalu ada sesuatu yang memicunya untuk tiba-tiba berubah pikiran. Maybe... something actually happened in her past.
Apa aku terlibat dalam masa lalu yang mempengaruhinya?
Nama Diana ada di ujung jariku. Aku tinggal memencet kontaknya, tapi tetap saja kami nggak akan bisa ketemuan malam ini. Dia mungkin sudah berkeluarga. Jadi kupikir, aku akan menangani hal lain yang lebih mendesak.
Bagaimana kalau perempuan rapuh yang jelas sekali nggak punya kemampuan menentukan apa yang diinginkannya itu terbujuk oleh rayuan laki-laki lain malam ini? If words matter more to Inggrid, aku harus lebih khawatir terhadap Spiegel daripada hotel tempat Gandhi menginap. Shit. Kenapa aku nggak langsung terus terang aja ngasih tahu dia apa yang kudengar tentang Gandhi? Kenapa aku nggak mau menurunkan egoku? Aku masih ingin Inggrid mendengar kebohongan Gandhi lebih banyak sebelum dia tahu kebenarannya. I wanna hear her say, Pram... you're right.
Aku begitu yakin aku bakal unggul dengan kebenaran yang sudah ada di tanganku sampai-sampai aku berani bilang sebaiknya mulai sekarang kita hanya bertemu di tempat kerja. Omong kosong. Aku mau melihatnya terus, setiap detik, setiap waktu. It's like finding what you're actually looking for after you lost it because you were young and stupid. Aku mau dia kembali sejak pertama kali kami ketemu lagi.
Dia sudah menyita seluruh perhatianku sebelum aku tahu kami punya masa lalu. Walaupun mukanya jauh lebih sering kuingat daripada yang lain tanpa sebab yang jelas, tapi Inggrid yang menyita perhatianku sekarang bukan gadis remaja yang ada dalam benakku. Aku nggak lagi peduli kenapa ingatanku tentang kebersamaan kami masih tersembunyi sampai detik ini, aku mau dia yang sekarang. Yang ada di depanku.
Tapi, masih ada sesuatu yang mengganggu Inggrid. Sesuatu yang menahannya. Kalau dibandingkan dengan mudahnya dia memaafkan Gandhi, Inggrid terlalu waspada terhadapku. Kenapa? Itu yang harus kucari tahu.
Niatku menghubungi Diana kuurungkan.
Hanya bertemu di tempat kerja katamu? Kalau mau jujur, setiap sudut pabrik ini bikin aku mual. Ngebayangin jejak-jejak perbuatannya sama Gandhi di ruangan ini bikin aku lebih gampang emosi. Aku melepas kacamata dengan kasar dan nyaris meremukkannya. Hanya bertemu di tempat di mana dia menolak untuk disentuh? Kenapa? Karena ini working environment-nya? Working environment my ass. Dia menolak sentuhanku di sini seolah lantai produksi adalah tempat yang sakral. Sialan. Kalau memang begitu, ngapain aja dia sama buyer QA Lanoste sialan itu di ruangan ini?
Hujan belum kunjung reda. Aku nyoba pesan taksol lewat aplikasi, tapi terus ditolak. Banjir di bawah udah setinggi mata kaki. Driver mana yang mau jemput orang di tempat kayak begini? Gimana caranya aku keluar dari sini?
Saat aku kebingungan, seseorang mengetuk pintu ruanganku. HRD Supervisor yang nggak kuingat namanya meski sudah pernah dikenalkan pada hari pertamaku bergabung muncul dari balik pintu. "Selamat petang, Pak Malik. Saya mau konfirmasi sekali lagi. Bapak beneran minta disewain motor aja selama residensi alih-alih mobil?"
"Oh... ya...," jawabku. "Menurut saya itu bakal lebih praktis."
"Bapak yakin? Udah lihat di luar? Di kawasan ini... hujan dikit pasti banjir. Nggak ujan aja suka tiba-tiba banjir. Kalau bapak mau... bapak bisa coba nengok ke luar—"
"Saya udah tahu. Justru itu. Kalau bawa mobil bakal makin repot, makin macet, makin bikin stress," kataku, ketus.
"Bapak tahu, kan... kalau disewain mobil... bakal sekalian sama supirnya?" tanyanya.
Aku menatapnya. "Saya tahu," kataku dengan imbuhan senyum. "Itu berarti... bakal ada dua orang stres di dalam mobil."
HRD Supervisor itu menarik dagunya ke belakang. Jelas sekali dia menganggap reaksiku berlebihan. "Kalau memang bapak sudah mempertimbangkannya baik-baik, saya mau tanya satu hal lagi. Apa bapak bisa mengendarai Honda CB150R?"
"Bisa," jawabku singkat.
"Soalnya rekanan kami cuma bisa menyediakan motor jenis itu sisa bulan ini. Kita baru bisa ganti dengan jenis lain pada awal pergantian bulan—"
"Doesn't matter," potongku.
"Kalau begitu, saya deal-kan dengan rekanan malam ini supaya motornya bisa diantar ke apartemen besok pagi."
"Besok pagi?" sahutku kecewa. Berarti nggak ada alasan lagi buatku maksain Inggrid menjemput. "Nggak bisa agak siang aja?"
"Pagi bisa, kok, Pak. Jadi Pak Pramana sudah bisa mulai ngantor bawa motor besok pagi. Orang dari rekanannya bakal nyampe apartemen sebelum pukul enam. Kalau bapak belum bangun, kunci dan armadanya mereka titipkan ke pos satpam."
"Oh... ya sudahlah...."
Kening supervisor itu mengerut lagi mendengar nada kecewa di suaraku, tapi mengabaikannya. "Untuk malam ini, karena Inggrid sudah pulang duluan, Bapak bisa nunggu Ms. Fok beberapa jam lagi, atau jika mendesak.... saya bisa pesankan taksi. Hubungi saya saja di ekstensi 339. Selamat sore, Pak—"
"Nggak ada taksi yang mau," sambarku. "Aku udah nyoba. Kamu punya solusi lain?"
"Nungguin Ms. Fok beberapa jam lagi?"
"Aku nggak mungkin bisa nunggu selama itu," gumamku.
"Kalau gitu... nggak ada pilihan lain selain nungguin ujannya agak reda."
"Kalau kamu?" tanyaku. "Jam berapa kamu pulang?"
"Mungkin segera setelah saya menelepon perusahaan rekanan mengenai motor yang bapak mau sewa—"
"Kamu bawa mobil? Atau motor?"
"Mobil...?"
"Kira-kira... mana yang lebih dulu bisa saya tumpangi, taksi, atau mobil kamu?"
"Eng... anu...," dia meringis. "Sebenarnya saya nggak bawa mobil, sih, Pak... saya bawa motor...."
"Terus kenapa barusan kamu bilang bawa mobil?" aku nyaris membentak. Tapi setelah ngelihat ringisannya makin lebar, aku baru nyadar. "Kamu pikir aku nggak akan mau naik mobil banjir-banjir begini karena memicu stres?"
"Suami saya cemburuan, Pak...," cengirnya.
"Suami kamu cemburuan... atau kamu nggak suka saya tumpangin?" tuduhku tersinggung. "Pakai motor kamu aja. Aku yang depan. Lagian kelamaan kalau nunggu taksol, apalagi nungguin Ms. Fok. Kamu nggak usah khawatir sama suamimu. Dia juga nggak akan tahu. Aku cuma perlu diantar ke Spiegel. Nggak sampai apartemenku."
"Motor saya cuma Honda Beat lho, Pak... bukan Aerox...."
"Ya terus kenapa?"
"Kan kecil...."
"Kamu pikir saya segede apa sampai Honda Beat aja kekecilan?"
"Bukan Bapak yang gede... saya yang gede," katanya sambil menampakkan seluruh badannya yang sejak tadi disembunyikan di balik pintu geser.
"Udah tahu kamu gede, kenapa kamu pakai Honda Beat?"
"Yang cicilannya murah, Pak...."
"Ya udah. Kamu mau ditumpangin, enggak? Kalau enggak ada, cariin siapa gitu yang bisa nganter saya ke Spiegel sekarang juga. Saya nggak mau tahu. Ini saya turun, depan lobi harus udah ada motor. Atau mobil."
"Kalau Tossa, Pak?"
"Kamu emang sengaja mau bikin saya marah?"
"Soalnya... ibu kantin yang udah siap pulang jam segini bawa Tossa, Pak. Ada kerudungnya juga, jadi Bapak nggak akan kebasahan."
Untungnya, aku nggak perlu merendahkan derajatku sampai harus numpang di bak belakang motor Tossa meski aku udah sempat menyanggupinya. Satpam shif pagi kebetulan juga udah mau pulang, jadinya HRD supervisor itu ngebatalin permintaan tolongnya ke si ibu-ibu kantin. Aku cuma bisa berdoa semoga Inggrid nggak memilih tempat yang terlihat di Spiegel. Kalau satpam yang kutumpangi motornya tahu aku sempat rela numpang Tossa buat nyusul Inggrid ke Spiegel dan dia ngelihat Gandhi juga di sana, suatu hari semua orang akan curiga Inggrid lah yang ngebawain salinan logbook ke pihak ketiga. Itu nggak akan bagus buat surat rekomendasinya nanti.
Sebagai tindakan pencegahan, berdasarkan google map, aku minta dengan sopan buat diturunin di depan Sai Ramen. Beberapa meter letaknya sebelum Spiegel.
"Ini sih bukan Spiegel, Pak," katanya. Ujan udah tinggal rintik-rintik aja. Aku turun dan ngelepas helm lalu melompat mundur ke bawah payungan kanopi. "Spiegel yang di depan."
"Nggak apa-apa. Di sini aja."
"Cuma tinggal bentar doang, Pak. Tinggal cus gitu. Biar tuntas kerjaan saja. Paling nggak suka, Pak, kalau kerja setengah-setengah."
Astaga. Orang-orang ini pada kenapa, sih? "Nggak apa-apa. Ya udah... anggap aja kamu nggak jadi nganter saya ke Spiegel, tapi ke...." Aku mencari-cari papan nama restoran yang atapnya menaungiku. "Sai Ramen. Okay?"
Satpam bertubuh kekar itu kelihatan lega. "Oh... gitu, dong. Kalau begini kan saya tenang. Jadi kalau ditanya... saya nganter Bapak ke Sai Ramen, ya? Bukan ke Spiegel?"
"Iya. Begitu aja."
"Kalau begitu baik. Hati-hati di jalan, ya? Bapak tahu jalan ke apartemen kalau dari sini?"
"Eng... tahu...," jawabku.
"Takutnya bapak nyasar."
"Oh... nggak apa-apa, Pak. Saya nggak bakal nyasar."
"Soalnya saya nggak bisa nungguin, nih...."
Ya malah bagus. Buruan pergi sana sebelum Inggrid atau Gandhi kelihatan, atau udah keluar dari Spiegel gara-gara kelamaan.
"Bapak pakai Grab aja nanti, ya, Pak," sarannya. "Sopirnya pasti tahu alamat apartemen Bapak. Mohon maaf, nih, ya, tapi saya capek. Nggak bisa nganter lebih jauh.... Ini aja saya mesti putar balik...."
"Okay... Pak...?"
"Sartono, Pak."
"Pak Sartono... makasih udah nganter jauh-jauh dan harus putar balik"—kubuka dompetku dan kuserahkan padanya selembar uang seratusan ribu—"Buat beli bensin."
"Wah... jangan gitu, Pak... saya nggak enak," katanya, tapi jarinya dengan cepat mencubit ujung lembaran duit di tanganku. "Saya ikhlas bantuin Bapak. Kalau Bapak mau ditungguin, saya juga ikhlas. Cuma kalau sampai atas...."
"Kurang?"
"Kurang, Pak."
"Saya nggak perlu ditungguin dan dianterin sampe atas. Bapak pulang aja. Nanti kalau kelamaan kena ujan, masuk angin, duit segitu nggak cukup buat ke dokter...."
"Pabrik sekarang udah ada asuransi, Pak. Kalau ke dokter yang ditunjuk, gratis, nggak bayar."
"Just... go," aku menggeram nggak sabar. "Just go. Please."
"Gimana, Pak?"
"Selamat malam, Pak Sartono. Terima kasih atas bantuannya."
"Saya lihatin bapak masuk dulu aja. Biar yakin selamat. Saya mesti laporan ke Bu Rina. HRD. Pasti habis ini saya ditelpon. Ditanyain tadi bapak selamat sampai tujuan, atau ada apa-apa di jalan."
Tanpa basa-basi lagi, aku pura-pura masuk ke Sai Ramen, pura-pura antre di mesin pemesanan, dan baru keluar setelah motor satpam itu menghilang.
Spiegel dalam jarak tempuh jalan kaki, tapi gara-gara kebanyakan ngoceh, hujan yang tadinya udah mau reda menderas lagi. Terpaksa, aku menerabas hujan, berlarian sambil melindungi kepalaku dengan tas kerja. Baru aja sampai di sisi kiri gedung tua di tengah kota lama, aku melihatnya. Inggrid. Duduk manis di tepi jendela dengan tangan tergamit erat dan senyum terkulum manis.
Samudra Gandhi.

Ada kejadian gemes, sih, di part ini waktu Pram ngasih tahu kebusukan Gandhi ke Inggrid.
Lanjutin aja chapter 52 di karyakarsa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top