Chapter 48. Maju Kena, Mundur Kena (Baca Chapter 93-95)
Factory Romance chapter 93-94 udah aku update di karyakarsa.

Intinya menguak luka lama sang pemeran utama pria. Hohoho....
Ati2 mewek baca part ini saking bangganya sama development Pram sama Inggrid ^^ aku berasa kayak a proud mom ngelihat anak-anaknya tumbuh dewasa dengan baik. Kalian boleh jadi kakak, adek, atau tantenya wkwk

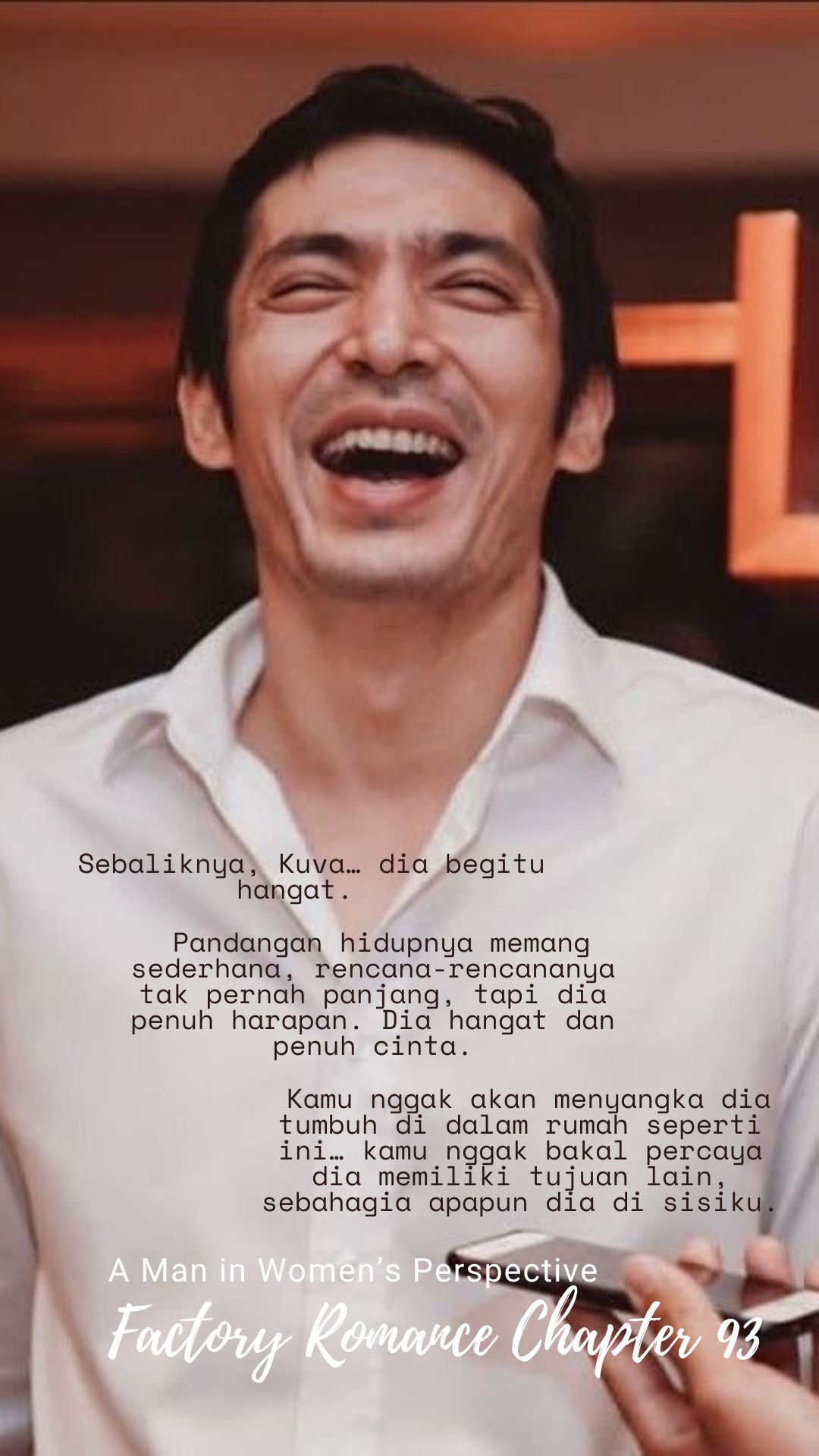
Okay...
Karena chapter 48 ini mini special part sepanjang 4500 kata, aku kasih bagian enggak specialnya aja, ya? Panjang, kok. 2000an kata. Adegan sebelum yang kupost di sini,silakan baca di karyakarsa.

Chapter 48
Maju Kena Mundur Kena
"Kalau kamu nggak mau bilang terus terang maumu apa, okay... biar aku aja. Let's hook up," katanya.
"Apa?"
"Let's be friend... with benefit...?"
Aku menatapnya nanap. Semakin kesal. Semakin marah.
"Supaya usahaku mendampingi kesiapanmu yang bertahap itu nggak sia-sia. Supaya nantinya kesiapanmu bisa kupetik hasilnya."
Rahangku jatuh. Mulutku ternganga-nganga.
"You can't handle honesty...," cemoohnya. "Aku bilang begitu karena aku nggak tau apa maumu. I said I like you... kamu nggak mau bilang kamu juga suka sama aku. Tapi kamu mau kucium, mau ngelakuin hal sejauh itu sama aku... so what do you want? Kamu nggak mau balikan sama aku, but you don't say no. You know I want you. So what do you want? You want us to be friends... with benefit? You want us to be fuck buddy? What do you want?"
"I want you to go to hell," kataku. Meradang.
***
Habis itu, kami nggak saling bicara lagi.
Sepanjang perjalanan ke pabrik, aku dan Pramana memendam emosi masing-masing. Aku tahu dia bakal segera minta maaf lagi, tinggal nunggu waktu aja. Masalahnya, pertanyaannya sebelum kukatai supaya dia ke neraka bikin tenggorokanku tercekat. Diam-diam aku menangis di kamarku yang lain sementara Pramana nungguin di ruang tamu. Aku muncul lagi beberapa saat kemudian, langsung ke garasi. Dia menyusul, membiarkanku tetap di belakang kemudi dan menyetir.
Di pabrik, aku nggak masuk ke ruangannya. Langsung belok ke ruang meeting buat ngikutin briefing yang tersisa beberapa menit saja. Kami lost contact selama jam kerja, aku bahkan nggak mau nanyain dia mau makan siang apa. Mungkin dia order sendiri, atau minta tolong HRD, aku nggak mau tahu. Ms. Fok juga terlalu sibuk buat notice bahwa aku dan Pramana seharian nggak berada di ruang yang sama.
Di sela-sela jam kerja, Gandhi meneleponku.
"Ya... logbook-nya udah ada sama aku, tapi kemarin Ms. Fok tahu kamu ke kantor," terangku malas. "Kubilang itu cuma alasanmu aja buat ngajak aku keluar makan siang."
Gandhi tertawa di seberang sana sementara aku berdiri di pojokan ruang departemen sewing, berusaha berbicara sepelan mungkin supaya nggak mengganggu konsentrasi para buruh, atau lebih buruk, memicu kecemburuan mereka. Ada peraturan tertulis tentang larangan membawa ponsel di ruang produksi, sesuai compliance buyer manapun, tapi karena nggak tercantum siapa saja yang mendapat kelonggaran atas peraturan tersebut, staf kantor dan supervisor produksi biasanya dianggap punya privilige melanggar peraturan. Beberapa hal memang kadang nggak bisa ditunda bagi pihak-pihak yang berwewenang. Tentu saja hal-hal nggak bisa ditunda itu nggak termasuk persoalan pribadi seperti menerima panggilan dari buyer QA yang bulk production-nya bahkan nggak lagi running seperti Gandhi ini.
Ngomong-ngomong, aku juga sembunyi dari Pramana yang bolak-balik kelihatan batang hidungnya di balik jendela kaca.
"Dia bilang dia mau melapor ke atasanmu," imbuhku.
Sisa tawa Gandhi belum habis saat dia mengecoh, "Nggak mungkin production manager mau ngambil risiko itu. Kami masih punya banyak antrean desain di tempatmu."
Sesuai dugaanku.
"Jadi... kapan kita bisa ketemu supaya aku bisa segera baca laporan Budi?" desak Gandhi tanpa basa-basi. "Meet me in Spiegel tonight?"
"Sebenarnya... di-Gosend juga bisa, kan, Gan?" tanyaku.
"Bisa, sih, bisa... tapi kalau aku butuh cross check-cross check?"
"Yang lebih tau soal logbook itu kan Budhi, Gan. Kamu suruh aja Budhi ke hotelmu. Dia pasti senang, apalagi kalau kamu izinin berenang—"
"Nggrid... jangan bikin aku mual," Gandhi mengerang.
Aku menjilat bibir. Melamunkan hal lain. Departemen sewing berada di ruang produksi lantai dua, sejajar dengan ruang inspeksi yang ditempati Pramana. Tapi, kecuali orang itu berdiri di dekat jendela, aku nggak bisa lihat apa-apa dari sini. Sebaliknya, kalau Pramana sedang mengawasi, dia bisa melihat semua hal yang terjadi di departemen ini.
Apa dia sedang mengintai? Apa dia tahu aku lagi nerima telepon sembunyi-sembunyi? Otakku bekerja keras memikirkan alasan apa yang harus kuberikan pada Pramana kalau nanti dia minta maaf sebelum jam pulang dan mengajakku makan malam. Aku yakin dia bakal minta maaf sebelum akhir hari, dia mau bareng sama siapa lagi selain menumpang mobilku pulang?
Gandhi menambahi dengan suara pelan, "I need to see the report soon and discuss it with you. That's all."
Aku masih menimbang-nimbang.
"Beside it's in Spiegel, memangnya aku mau ngapain selain nerima kopian logbook Budi? Takut amat, sih, Nggrid?"
"Bukan begitu," sahutku nggak enak. Aku nggak lagi mikirin kamu. "Okay let's see what I can do."
"Pukul delapan kamu udah selesai kerja, kan? Dari situ ke Spiegel paling lima belas menit. We meet, talk, you took me to the hotel, and that's it. I promise. Aku nggak akan minta kamu mampir. Besok, atau lusa aku udah harus ke Jakarta naik kereta. Nggak ada waktu lagi selain malam ini. Gimana?"
"Berapa lama kamu di Jakarta?" tanyaku. Maksudku, kalau nggak malam ini banget, aku mungkin masih bisa mikirin alasan lain supaya Pram nggak curiga.
"Kalau nunggu aku balik dari Jakarta, kelamaan, Nggrid. Memangnya kenapa sih kalau malam ini?"
Iya. Kenapa, sih, kalau malam ini, Nggrid?
Biar aja Pramana curiga. Lagian, emang ada aturan harus selalu maafin dia setiap kali dia minta maaf? Kan enggak.
"Okay, nanti kukasih kabar jam berapa aku pulang."
That's it. Pembicaraan berakhir singkat, lalu aku buru-buru menyimpan ponsel dan menjemput dua fit sample susulanku yang baru selesai dijahit. Aku mengeceknya kilat bersama supervisor departemen sewing berdasarkan measurement sheet, kemudian mengangkutnya ke ruang Embroidery and Accessories untuk memasang rhinestone logo.
"Mbak Inggrid mau masang logo di fit sampel?" tanya Anti, team leader sewing departemen yang ditempatkan di divisi aksesoris.
"Iya, buat dijajal aja."
"Yakin, Mbak? Nanti kalau malah salah... mbak bisa kena marah sama Pak Malik, lho...," bisiknya.
Justru itu tujuanku, aku membatin. Kalau dia marah, dia nggak bakal jadi minta maaf. Aku bisa pergi nemuin Gandhi tanpa gangguan siapapun.
"Nggak apa-apa," kataku yakin. "Kan fit sampel nggak perlu ada logo, jadi kalaupun salah, harusnya bisa diabaikan."
Muka Anti mengerut. Dia jelas nggak sepaham denganku. "Mbak Inggrid... jangan cari penyakit, Mbak... emang enak ya dimarahin terus sama Pak Malik?"
"Yah... aku pengin lihat gimana reaksinya...," gumamku.
"Maksud Mbak?"
Aku tersenyum. "Maksudku... aku mau lihat gimana jadinya kalau udah ditempel, An. Ayok, kerjain sekarang."
Sebelum jam makan siang, sampelku udah selesai resting dan kubawa ke atas untuk diserahkan pada Pramana.
Saat aku membuka pintu, dia sedang berbicara di telepon. Tangannya terangkat ke arahku, menahanku bicara. Kututup pintu di belakangku tanpa suara dan kuletakkan sampel-sampelku di atas meja inspeksi. Sambil menunggu, kucek sekali lagi letak logo Baronness di bagian saku depan kemeja dan mulai mengukur letaknya. Aku begitu sibuk dengan measurement tape sambil membandingkan angka-angka toleransi antara fisik sampelku dengan yang tertera di spec sampai nggak menyadari Pramana tiba-tiba sudah berdiri di belakangku.
Dia membungkuk, mengurungku dengan lengan-lengannya yang diletakkan di tepi meja. Sontak, tubuhku mengaku saat dia mengintip apa yang kukerjakan di balik pundakku. Hawa panas serta merta menjalari tengkukku sangking dekatnya posisi Pramana di balik punggungku. Aku seakan bisa mendengar detak jantung, serta hangat napas yang membelai lekuk leherku.
"Tolong, ya, kamu jangan asal dekat-dekat," imbauku, berkelit dingin menjauh.
Pram ikut-ikutan menjauh. "Aku nggak bermaksud dekat-dekat," gerutunya. "Aku lagi ngelihatin apa yang kamu liatin."
"Nanti juga kan kamu bakal ditunjukkin... orang ini juga dibikin buat kamu...," kataku sinis. "Nggak usah ngintip-ngintip."
"Kamu ngobrol sama siapa tadi di telepon?"
Nah... kan...?
"Dibilang jangan ngintip-ngintip...."
"Kalau aku nggak ngintip... memang kamu bakal ngasih tahu?"
"Ya enggak lah," kataku. "Ngapain? Kan yang ditelepon aku... bukan urusanmu."
"Nerima telepon di ruang produksi masal itu melanggar buyer complience, Nggrid...."
Mulutku langsung kicep.
Pram geleng-geleng kepala seraya mendekat kembali ke meja. Tanpa menyentuh apa-apa, dia langsung berkomentar, "You know you don't have to put that logo in fit sample."
"Don't have... doesn't mean we can't, kan?" aku menantang.
"You CAN'T have any logo in any sample before production samples, Inggrid," tegasnya.
Aku tahu itu. Dadaku membusung, daguku terangkat. Tapi paling enggak, aku yakin ukuran dan segalanya sudah sangat pas. Kalaupun nggak diterima di fit sample, nantinya bisa kupakai di production samples. Aku kan emang cuma mau nyari-nyari—
Sebelum kalimat yang kuucapkan dalam hati berakhir, Pram keburu nanya, "Are you trying to impress me... atau memang sengaja nyari-nyari penyakit?"
Wow... aku jadi bertanya-tanya, apa ada mesin penyadap di departemen sewing, atau malah di dalam hatiku juga ada?
"Kuharap kamu punya cadangan material buat fit sampel kalau sampai logo ini nggak terpasang sempurna," decihnya. Dia membalik sampel berlogo yang kuletakkan di tumpukan paling atas dan terlihat kecewa melihat sampel-sampel berikutnya polos tanpa hiasan apa-apa.
"Ya udah, sih," kataku acuh tak acuh. "Kalau fit sampel nggak perlu logo, kamu bisa mengabaikannya. Nanti kupakai aja buat production sample."
"Yakin amat kamu nggak akan ada perubahan requirements sampai ke proses production sample," katanya.
Shit. Aku nggak kepikiran sampai sana.
"Kamu mungkin bisa kayak gitu sama brand lain, tapi enggak sama Baronnes," tegasnya sambil membungkuk meraih pouch berisi peralatan kerjanya. Pramana membentangkan measurement tape dan mulai mengukur. "When you decide to put unnecessary things on the sample that doesn't require anything yet, you have to put it perfectly. Kalau enggak, aku akan menganggapnya sebagai sikap arogansimu saja. You better pray."
Okay... kamu mungkin sudah membuang-buang material, Inggrid. Kamu harusnya tahu, banyak kasus perubahan requirements antara fit sample sampai bulk production samples. Sial. Sial. Sial. Akhirnya, terpaksa aku mengakui kebodohanku, "Aku cuma penasaran—"
"Kalau penasaran, kamu kan bisa nyobain aksesorisnya di tempat lain, di jidatmu barangkali?! Bukan di sampel yang mau kamu submit! Ini bukan mainan, Inggrid."
"I am sorry."
Lah... malah aku yang minta maaf jadinya.
Pramana mengabaikan permintaan maafku dan membalasnya dengan gelengan kepala jenuh seakan dia nggak tahu lagi bagaimana menghadapiku. Keringat dingin meluncur pelan tapi pasti di pelipisku saat menanti Pramana selesai mengecek ukuran letaknya. Paling enggak, ukurannya benar. Paling enggak, sampelnya sempurna sesuai requirement terakhir. Paling enggak....
Jantungku melorot ke dengkul saat dia menempelkan satu defect sticker, lalu dengan kesal membanting sampel itu ke atas meja. Dia bahkan nggak mau repot-repot mengecek sampel lain yang polos tanpa logo. Tanpa mengatakan apa-apa, Pramana kembali ke mejanya, lalu duduk menyembunyikan muka di balik layar laptop. Aku mencoba nggak membuat suara, apalagi berkomentar.
"A quality assurance and officer have to work based on procedure, a strict procedure," katanya, memecah keheningan. "Ada kalanya kamu harus pakai nyali dan insting, tapi bukan ego, apalagi arogansi. Satu proses yang kamu lalui dengan baik, bahkan sempurna, nggak lantas bikin kamu naik kelas kalau kamu mengulang kesalahan, atau membuat kesalahan baru. Patuhi prosedurnya, jangan lakukan hal yang nggak perlu kamu lakukan."
Aku mengangguk.
"Apa rencanamu habis ini?"
"Bikin sampel baru."
"Bikin sampel baru, bikin sampel baru, enak aja," cemoohnya. "Jangan lupa. Kamu kerja buat perusahaan ini, bukan buat aku. Kalau kamu kerja buat aku, terserah kamu mau buang-buang material produksi perusahaan rekanan selama kita nggak diminta membayar lebih. Kamu kerja di sini, kamu harus mikirin berapa banyak perusahaan dirugikan gara-gara ulahmu."
Mulutku sepenuhnya terkunci.
"Just take off that logo gently," tambahnya. "Bawa ke washing dan minta mereka bersihin tanpa mencuci ulang. Pastikan nggak ada bekas lem di sana, lalu steam ulang area itu aja. Kalau beres, bawa lagi ke sini. Kalau enggak, baru bikin ulang. Aku mau semuanya selesai sebelum pukul lima."
"Okay. Eum... kalau enggak, tetap harus kubawa ke sini dulu, atau langsung kubikin ulang?"
"Menurutmu gimana?"
"Langsung bikin ulang?"
"Bawa ke sini dulu lah. Remember, you don't use your working and quality standard, you're using mine. Do you understand?"
"I understand."
"Satu lagi."
Langkahku tertahan.
"Kenapa kamu tadi nggak pesenin aku makan siang?"
"Maaf,"—dua kali—"Aku sibuk di production floor."
"Sibuk di production floor, apa sibuk bikin kesalahan konyol?" cemoohnya. "Udahlah. Aku mau spicy tuna dan rainbow roll dari Ichiban buat makan malam. Kamu juga boleh pesan kalau mau. Makan malam di sini aja sama aku."
"Aku makan di kantin aja."
"Nggrid...."
"Aku makan di kantin aja," ulangku, mulai jengkel. Enak aja, habis marah-marah nyuruh nemenin makan malam. Dia boleh saja marah-marah selama ada kaitannya sama pekerjaan, tapi aku punya hak menolak diajak makan bareng oleh siapapun.
"Are you upset?"
"No."
"Yes you are. Kamu kesel karena dimarahin, terus kamu bersikap nggak profesional dengan menolak makan malam bareng—"
"Yang nggak profesional itu ngajak rekan kerja makan malam dan ngatain nggak profesional karena ajakannya ditolak!" bantahku kesal. "Aku punya hak menentukan mau makan siang, makan malam, atau makan pagi di mana aja."
"Oh... okay...."
"Okay."
"Atau... kamu masih marah soal tadi pagi?" sambungnya. "Aku yang salah, atau gimana, ya? Bukannya kamu yang ngatain aku supaya pergi ke neraka? Atau lagi-lagi aku yang harus minta maaf?"
Sebenarnya aku mau bilang, nggak akan ada orang yang nyuruh dia pergi ke neraka kalau dia nggak ngapa-ngapain. Tapi buat apa? Paling-paling kami cuma akan debat nggak jelas, ujungnya aku menyerah karena nggak mau ribut, dan akhirnya aku malah nggak bisa nemuin Gandhi di Spieghel. Kalau Gandhi nggak ditemui, dia bakal menganggapku nggak bisa diajak kerja sama. Sudahlah. Maju kena, mundur pun kena.
"Aku nggak mau bahas itu, Pram... aku nggak bisa nemenin kamu makan malam. Itu aja."
Titik.
"Tapi kamu tetap bakal ngantar aku pulang, kan?"
"Nanti aku cek lagi. Siapa tahu HRD udah dapat sopir dan mobil sewaan buat kamu—"
Dia menyambar, "Aku nggak mau dicariin mobil dan supir sewaan lagi—"
"It's not up to you," aku gantian menyahut, habis sudah kesabaranku. "Antar jemput kamu nggak masuk dalam job desc-ku."
Rahang Pramana terlihat mengetat, aku nggak menyangka dia menelan harga dirinya bulat-bulat dengan terus berusaha, "Jadi kamu nggak mau ngantar aku pulang, dan nggak ngurusin makan malamku juga?"
"Jangan nyari-nyari kesalahanku terus, Pram. Kamu mau spicy tuna dan rainbow roll dari Ichiban, kan? Udah kucatat di otakku."
"I want to have dinner with you," tegasnya. "Kenapa kamu nggak bisanya?"
"Aku ada urusan lain."
"Urusan apa?"
"Urusan yang bukan urusanmu."
Setelah itu, meski dia masih memanggil dengan nada yang jauh lebih mendesak, aku sama sekali nggak menoleh, dan melanjutkan menutup pintu ruangan tanpa membanting, atau menimbulkan suara. At least, aku nggak perlu menjelaskan apapun untuk menolak ajakan makan malamnya supaya bisa bertemu Gandhi malam ini.

Oh iya... buat yang masih komen-komen dengan nada, jaga tubuhmu biar lelaki menghormatimu, atau punya pendapat kehormatan perempuan tuh HANYA kalau dia masih virgin, kayaknya kalian salah masuk lapakku. Nilai2 dalam ceritaku berbeda. Buat aku, berharganya perempuan nggak dilihat dari sana, dan buatku cinta sejati serta ketulusan hati adalah harapan paling besar yang akan menyelamatkan kita. Selain itu, nilai-nilai personalmu silakan simpan untuk dirimu sendiri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top