7. Cinta Bersemi
Nikah?
Atau tanggung jawab betulan?
https://youtu.be/WhVyGGenmQw
Aku nggak tahu dia udah nyebut nggak mungkin seberapa banyak, yang jelas banyak. Kayak tiap dia mau ngomong sesuatu dia bilang nggak mungkin dulu. Misalnya gini, "Nggak mungkin ... kamu mau langsung pulang apa di sini dulu?", "Nggak mungkin ... kayaknya nggak mungkin ... mendingan kita pulang aja kamu kelihatan pucat," "Nggak mungkin ... seingetku, langsung kutarik sebelum netes, aku yakin, ini lewat mana? Tol atau jalan biasa?"
Sampai di parkiran kos, waktu terakhir kalinya dia bilang, "Kok nggak mungkin ya kayaknya ... aku nggak mungkin seceroboh itu ... aku boleh masuk supaya kita bisa lanjutin bicara?" aku nggak bisa menahan tawa.
Dan dia kebingungan melihatku tertawa.
"Ini lelucon, ya?" kernyitnya. "Kalau ini lelucon, aku berani sumpah, kamu bakal kubikin hamil beneran. Aku udah mikir macam-macam ini!"
Aku mengangsurkan test pack yang sudah kusiapkan.
Dia nggak langsung menerima uluranku, "Apa ini?"
"Test pack."
"Mu?"
Aku ngangguk, baru dia menyentuh ujungnya.
"Kalau garisnya dua begini artinya hamil?" dia nanya. Lalu menatapku, "Kok kamu nggak kelihatan hamil?"
"Mungkin karena baru dua bulan?"
Dia menyipitkan mata, "Aaah ... tapi waktu tabrakan di dance floor tadi memang aku sempat kaget, sih."
"Kenapa?"
Yudha menyentuh dadanya sendiri lalu menggembungkannya dengan gerakan ke depan, "Kayak gedean."
Sialan.
"Kamu serius ini anakku?" terus terangnya.
"Aku nggak ngapa-ngapain habis sama kamu," tuturku lirih. Kusimpan kembali test pack yang hanya diliriknya sekilas.
"Sebelumnya?"
Ragu, karena sebelumnya aku bilang udah lama enggak, aku pun jujur, "Aku masih perawan. Aku minta maaf, waktu itu aku bohong karena males ngejelasin hubunganku sama mantan."
Yudha jatuh duduk di sisiku. Tubuhnya memantul sedikit sebelum bergeming. Sepertinya dia lebih syok sekarang daripada waktu nyadar apa yang terjadi padaku di Go-Go. Begitu ngelihat aku muntah, pertanyaan 'kenapa baru sekarang menghubungi'-nya terjawab oleh kesimpulanya sendiri. Aku sendiri nggak banyak menjelaskan, hanya membenarkan.
"Kamu nggak berdarah," tegunnya. "Kukira kalau pertama kali selalu akan—yah ... kata orang-orang ... eng ... berdarah, kan?"
Sebenarnya sih, sedikit, tapi aku nggak mau bilang. Malu. Kalaupun kubilang, mungkin akan terdengar lucu dan dibuat-buat hanya untuk meyakinkannya. Celana dalam sebagai buktinya juga udah kucuci dan kupakai ulang berkali-kali, aku bisa apa?
"Oh sorry ... aku benar-benar nggak bermaksud," katanya.
"Aku tahu," kataku. "Kalau kamu bermaksud, kamu nggak mungkin mau menemuiku lagi."
"Maksudku soal nanyain berdarahnya tadi—"
Melihat mukaku yang mungkin langsung memerah karena malu, Yudha gelagapan, "Eh ... maksudku yang itu juga aku nggak bermaksud! Sungguh!"
Dengan kepala menunduk, kuulangi kalimatku sebelumnya.
"Ya Tuhan ...," sebutnya sambil memijit kening, kemudian mengacak rambutnya frustrasi. "Kenapaaa waktu itu kita nggak pakai kondooom?"
"Hsssttt!!!" aku menyuruhnya memelankan suara. Besar kemungkinan ketiga mbak kosku sekarang ini lagi di depan pintu dan menguping. Waktu aku mengajaknya masuk, mereka bertiga lagi asyik masker-maskeran di common room.
"Kenapa waktu itu kita nggak pake kondom?" ulangnya, mukanya panik kayak orang hilang akal. Dengan ekspresi gemas dia mengguncang bahuku, tapi aku hanya bisa menukikkan alis dan menggeleng lemah.
"Udah berapa lama kamu tahu?"
"Semalem," aku menjawab jujur.
"Kok kamu tenang banget?" protesnya.
"Semalem aku udah kayak kamu gitu," kataku enteng. Bukannya ngentengin, sama sekali bukan. Aku sendiri juga mumet, tapi kalau kami sama-sama histeris, kepalaku bisa pecah nahan pusing. Sekarang aja dekat-dekat dia gini aku udah mual mau muntah.
"Terus ... terus aku harus gimana?"
"Aku nggak tahu."
"Yang bener aja ... kamu nyari aku buat apa kalau nggak tahu juga? Kamu mau aku gimana?"
"Kamu mendingan tenang dulu. Kamu nggak akan bisa mikir kalau panik gitu."
"Kamu udah ke dokter?"
"Belum."
"Berarti baru kamu tes pake gituan tadi itu?"
"Iya."
"Akurat?"
"Nggak tahu."
"Kalau ke dokter dan beneran hamil ... eng ... bisa nggak sih dokter tahu aku bapaknya atau bukan?"
Aku diam, menatap tajam. Orang ini cuman panik, apa memang bego, atau kebanyakan nonton film, sih? Mana bisa dokter tahu bakal janin berusia delapan minggu di dalam rahim itu perbuatan siapa? Dia pikir anak ini ada labelnya apa?
"Bukannya gitu ..., bu—bukannya aku nggak percaya," gugupnya, tahu aku tersinggung. "Yah ... biar jelas aja."
"Aku udah bilang, sebelum dan habis sama kamu, aku nggak ngapa-ngapain!" kataku mulai sebal. "Terserah kamu mau percaya atau enggak,"
"Lho kok gitu ...? Terus kalau aku nggak mau tanggung jawab gimana?"
"Ya udah ... berarti kamu ... kamu ...."
"Kamu apaaa? Brengsek? Bajingan? Apa?"
"Kamu ... dosa!" tandasku. Hanya itu yang terlintas di benakku.
"Dosa?"
"Iya. Tuhan tahu aku jujur! Aku cuma gituan sama kamu!"
Dia langsung mengatupkan kembali rahangnya yang jatuh.
***
Habis mandi, dia mendekatiku sambil mengeringkan rambut dengan handuk.
"Gimana?"
Aku mengendus, "Oke."
"Memang sebau apa, sih?" tanyanya risau.
"Ini bukan salahmu," aku menenangkannya. "Dari beberapa artikel yang kubaca, wanita hamil memang sangat sensitif pada bau-bauan. Di beberapa kasus ... ada yang sebal pada aroma tubuh pasangannya."
Kemudian, kami sama-sama kikuk.
Begitu aku bilang Tuhan tahu aku jujur, segala daya upayanya mengelak lantak. Dia lantas bertanya baik-baik apa yang sebaiknya kami lakukan. Mungkin emosiku yang nggak stabil karena hamil muda, ditanyai baik-baik gitu, aku malah nangis lagi. Namun, saat dia berusaha memeluk buat nenangin tangisku—sama seperti kejadian di lantai dansa—aroma tengkuknya menyentak indra penciumanku. Aku malah memuntahi dadanya. Untung jaketnya udah dilepas duluan.
Lalu dia mandi di bawah pancuranku dan sekarang telanjang dada.
"Bapakmu ..." pendeknya, tanpa diteruskan.
"Galak," lanjutku.
"Aku paling nggak bisa ngadepin orang tua."
Sama. Aku juga nggak bisa ngadepin orang tua. Sampai tiga tahun pacaran, Bima belum pernah mau ngajak aku sowan calon mertua, "Bapakmu gimana?"
"Papaku sih santai," katanya. "Tahu mau punya cucu, mungkin dia malah senang bukan kepalang."
Aku mengembuskan napas lega.
"Masalahnya ... mungkin kamu nggak akan suka sama dia."
"Kenapa?"
Sebaliknya, Yudha menghela napas berat.
"Kenapa?" aku mengulang.
Dia menoleh, "Kamu yakin mau aku bertanggung jawab?"
Aku menelan ludah. Tentu saja. Aku nggak punya pilihan.
"Aku bisa aja nikahin kamu sampai kamu lahiran, setelah itu terserah kamu."
Kepalaku lagi-lagi cuma menunduk, aku nggak punya pikiran serendah itu. Tapi, kalau memang itu maunya, mau gimana lagi? Itu murni kecelakaan. Kalau orang nabrak di jalan aja, tanggung jawabnya juga sampai korbannya sembuh, kan? Mana ada tanggung jawab kecelakaan sampai seumur hidup. Tapi tabrakan di jalan kan nggak ada buntut bayinya, ya?
"Tapi itu namanya bukan tanggung jawab," tuturnya, bikin kepalaku terangkat lagi. "Aku nggak keberatan tanggung jawab sungguhan," sambungnya tanpa kuminta.
"Maksudnya?"
"Masalahnya mungkin kamu nggak akan suka kalau aku tanggung jawab sungguhan," dia ngomong sendiri.
"Aku nggak paham."
"Aku nggak punya apa-apa."
"Yah ... aku nggak punya banyak pilihan."
Dia mengangguk pasrah, "Pilihannya kamu mau aku nikahin kamu, atau tanggung jawab sungguhan."
"Kamu jangan bikin aku pusing, kepalaku udah mau pecah karena hormon bunting. Kalau kamu punya syarat dan ketentuan, mending kita omongin dari sekarang. Aku jelas mau kamu nikahin aku, kalau kamu nggak keberatan, apa bedanya sama tanggung jawab sungguhan?"
"Yah ...."
"Yah apa?"
"Aku bisa nikah sungguhan ... kalau kamu mau."
"Memangnya ada nikah main-main?"
"Aku ini produk nikah main-main."
Aku tercenung.
"Ayah dan ibuku nggak bersama setelah aku lahir," jelasnya.
"Oh ... mereka sama kayak kita?"
"Ya begitulah ... tapi aku nggak mau anakku kayak aku."
"Lha maumu gimana?"
"Memangnya kamu mau nikah sungguhan? Kita nggak kenal satu sama lain, aku nggak punya rumah, kerjaanku cuma ngurusin usaha keluarga. Kami masih berjuang, utang di sana-sini, dan ada hal-hal lain yang pokoknya besar kemungkinan kamu nggak akan mau nikah sungguhan."
Aku meremas jariku yang saling kait. Awalnya kupikir permasalahan terbesarnya meyakinkan Yudha untuk bertanggung jawab. Bagaimana enggak? Kami hanya tidur sekali dua bulan lalu, ketemu juga nggak sengaja. Habis itu nggak saling kontak sama sekali, dia nggak lari aja udah bagus. Aku nggak berpikir sejauh ini.
Yudha mengubah posisi duduknya menghadapku, menyentuh bahuku dengan ujung jarinya, "Hey ...."
Kepalaku bergerak ke arahnya seperti robot.
"Kalau kamu nggak hamil ... apa kamu bakal ngehubungin aku?"
Jujur, aku menggeleng.
"Karena aku nggak ngehubungin duluan?"
Jujur lagi, aku mengangguk.
"Bukan karena kamu nggak pengin ketemu aku lagi?"
"Bukan."
"Seandainya ponselku nggak hilang, mungkin sekarang kita udah pacaran, kan?"
"Mungkin."
"Kamu nggak ketemu seseorang dua bulan ini?"
"Enggak."
"Kayaknya kesan pertamaku ke kamu nggak begitu bagus, kan? Kamu nggak suka cowok yang pake rias wajah, kamu juga nggak berharap kejadian itu beneran terjadi. Aku lihat kok mukamu yang nggak yakin waktu kita gituan."
"Bukan gitu," sangkalku. "Aku cuma nggak mikir sejauh itu."
Kenyataannya, setelah tidur bersama, percakapan sehabis itu bikin sebagian hatiku tersentuh. Kalau aku nggak ketemu dia, mungkin sekarang aku udah balikan lagi sama Bima. Nangis-nangis mikirin selama kami berjauhan, dia selingkuh apa enggak. Secara nggak disadarinya, malam itu aku diselamatkan.
Mungkin aku jenis orang yang nggak bisa melupakan sentuhan. Aku percaya perasaan lain bisa timbul karena apa aja. Nggak melulu yang manis-manis, bahkan dari badan bisa banget turun ke hati.
"Aku sempat kepikiran bakal nidurin kamu lagi waktu kamu telepon kemarin," tukasnya sekonyong-konyong.
Aku mendecapkan lidah, nggak romantis amat.
"Maksudku ... aku memang berharap ada kelanjutan setelah malam itu. Cuma aku terlalu nggak yakin apa kamu menikmatinya atau enggak. Maksudku gini ... kalau dari sisiku, aku memang ingin kenal lebih jauh sama kamu. Kamu ... gimana?"
Aku bisa saja bilang aku merasakan hal yang sama, tapi kupikir-pikir ... dia orangnya cukup sensitif, aku nggak tega ngebohonginnya. Bukannya aku nggak mau kami berhubungan lebih jauh sejak malam itu, aku cuman nggak mau ngehubungin duluan. Dua bulan lalu, aku menganggapnya salah satu cara buat get over shit aja. Ples, aku sibuk ngurusin kehebohan tingkah Bima, pekerjaan, melupakan luka hati, dan lain-lain. Lebih kayak ya aku mau, tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa.
"Mendingan aku pulang dulu," katanya.
"Kamu bakal ke sini lagi, kan?" tanggapku cepat.
"Aku nggak akan lari," janjinya. "Besok kuantar ke dokter, kita pastiin kamu hamil atau enggak dulu. Baru kamu putuskan nikah, atau tanggung jawab betulan."
"Kok jadi aku yang mutusin?"
"Karena kamu nggak ngasih kepastian sama pertanyaanku," dia tersenyum, mengecup cepat keningku dan beranjak kembali ke kamar mandi.
"Eng ... Ran," panggilnya saat aku mengantarnya ke pintu.
"Hm?"
"Bibirmu ...," katanya. "Boleh kucium?"
"Hah?"
"Nggak boleh, ya?"
"Bukan gitu, aku cuman kaget aja."
"Sama kalau kaget, aku juga."
"Maksudku ... semua ini terasa terlalu buru-buru. Jujur, aku beneran nggak tahu apa yang harus kita lakukan setelah ini. Yang kutahu ... aku pengin kamu tahu, paling enggak aku nggak sendirian. Bukan nggak boleh ... atau apa ...."
Kepala Yudha mengangguk, tangannya masih memegang handle pintu tanpa memutarnya, "Oke ... kalau gitu mending kita sama-sama tidur nyenyak dulu malam ini supaya besok bisa ngobrol lebih tenang."
"Ya ... kalau bisa nyenyak ....," keluhku.
"Harus," ucap Yudha. "Kamu harus banyak istirahat."
"Aku takut ...."
"Mau kupeluk sebelum pulang? Biar kamu ... tenang. Sebab ... mungkin selain bapakmu ... nggak ada yang perlu kamu takutkan."
"Nggak apa-apa?"
Pegangan Yudha di handle pintu sepenuhnya terlepas, tas plastik berisi kemeja kotornya diletakkan di lantai tanpa menimbulkan suara. Aku melangkah saat kami berhadapan, membiarkan tangan Yudha menyentuh bahuku, kemudian menarik tubuhku menempel di dadanya.
Aku masih ingat dadanya yang tak bidang tapi wangi dan hangat. Aroma sabun tak membuatku mual karena parfumnya tak tercium. Ketika kepalaku mendarat di bahunya, kuhirup permukaan kulitnya yang menyapu hidungku. Kami bertahan dalam posisi itu tanpa bergerak sampai beberapa lama. Entah siapa yang memulai, lalu kami saling melepaskan diri.
Napas Yudha mendengus lembut di ujung hidungku, "Aku pulang, ya?"
"Yud ...."
Detik berikutnya, seolah panggilanku barusan menarik kembali keberatanku sebelumnya, Yudha mencium pipiku tanpa izin. Karena rasanya khidmat banget kecupan itu, aku nggak buru-buru membuka mata. Malah, kunikmati bagaimana Yudha membasahi permukaan bibirku dengan bibirnya.
Setelah itu, baru ia pulang.
Paginya, dia SMS, aku antar kerja, mau?
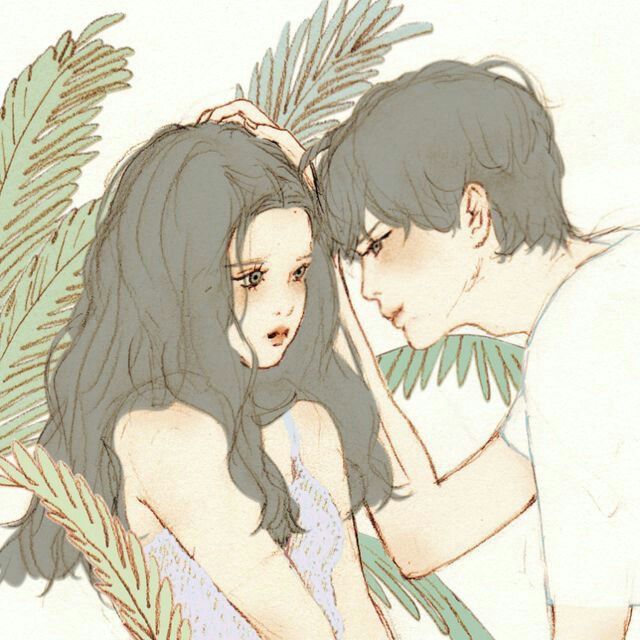
Yudha
"Nanti, kalau cucunya lucu, dia pasti luluh juga."

Maharani
"Tapi anak kita pasti lucu, kan, Yud?"
Bakal luluh mudah nggak ya bapaknya Rani?
Hihi... jangan lupa vote dan komen ^^
Kin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top