4. Cinta 'kan Membawamu
Cowok yang bobok sama aku dulu itu?
Nggak ada kabarnya, tuh.
***
Delapan minggu kemudian
"Pagi, Rani ...."
Meski badanku enggak enak, senyumku tetap manis terkulum.
Langkahku terayun mantap menyisir lorong demi lorong antar kubikel untuk mengambil formulir rencana lembur di tiap meja. Aturannya, sih, harus sudah siap pukul sembilan tepat di meja masing-masing, kenyataannya ada aja yang belum siap.
Jam segini Mas Justin pasti masih ngobrol heboh sama Mas Rian dan yang lain di pantry, magabut sampai petinggi pada dateng.
Khusus hari ini, mereka cuma melambai ke arahku, "Habis gajian, nggak dulu," katanya.
Cis. Sombong. Paling dua tiga hari kalau tagihan kartu kredit udah jatuh tempo juga ngais-ngais lemburan.
"Mbak Tiwi lembur enggak?" tanyaku sesampainya di kubik copy writer itu.
"Lembur!" Keke yang menjawab sambil melambaikan dua lembar form padaku dengan tangan kirinya, tangannya yang lain sibuk memegang sekeping pai apel. Aku menyambar form-nya dengan suka cita.
"Dari mana itu pagi-pagi?" aku nanya.
"Dari klien yang beres kemarin," jawab Keke renyah. "Aku suka banget pai ini. Mbak Rani mau?"
Biasanya aku nggak pernah menolak snack yang manis-manis, apalagi pai apel cap Mama termasuk pai paling enak yang pernah kujajal, tapi entah kenapa, aku nggak kepengin. "Nanti aja, deh, nggak pengin."
"Eh ... Rani!"-Mbak Tiwi mencegahku berlalu-"Tumben nggak mau pai, kamu sakit?"
Aku mengernyit. Memang aku agak pusing udah beberapa hari, tapi dengan pekerjaan menumpuk, paling-paling cuma kecapaian, "Enggak, tuh, Mbak."
"Masa, sih?" tanyanya nggak yakin sambil beranjak keluar kubikel. Dengan lembut dia menyentuh keningku, "Kamu pucat lho, Sayang ... istirahat, dong. Tipes kamu udah sembuh, kan? Jangan sampai sakit lagi, nanti siapa yang nemenin kalau kita-kita lembur?"
Huh. Gombal.
Masih inget aja dia sama kebohonganku dua bulan lalu waktu izin sakit tiga hari gara-gara Bima. Kubilang aku kena gejala tipes, tapi Mbak Tiwi jelas tahu aku cuti patah hati. Orang aku yang cerita.
Kucubit pinggangnya, "Mbak Tiwi ngeledek, ya?"
Cewek maskulin itu mengekeh.
"Lagian tumben banget kamu nolak pai apel Mama. Serius pai ini beneran nggak ada duanya! Mungkin karena yang bikinnya campuran lekong sama pere kali, ya, lebih enak dari yang dibikin perempuan tulen!"
"Ih Mbak Tiwi ngawur! Sendirinya aja cewek, tapi rasa cowok!" balas Keke renyah, tetap ketawa meski kepalanya kena getok.
Karena dipaksa, akhirnya aku mencubit sedikit kue yang ditawarkan Keke dan mencicipnya. Memang, kue ini lezat luar biasa. Lagi happening banget pula di kalangan perusahaan ibu kota karena sering dipakai buat bingkisan terima kasih dan ucapan selamat ulang tahun. Tapi, selera makanku sedang jelek banget nggak tahu kenapa. Kegemaranku menyantap makanan manis dan kesukaanku pada pai itu nggak bikin aku pengin menghabiskan meski hanya sepotong.
"Emang beneran ya mbak yang punya Pai Mama itu waria?" tanyaku iseng.
"Iya."
"Aku pernah ke sana, tapi nggak lihat ada waria, tuh."
"Emang kayak perempuan tulen, Mbak Rani!" sahut Keke. "Tapi cowok sih kabarnya, dadanya aja masih pake fake breast bra gitu, nggak dioperasi. Menurut gosip, dia nikahnya juga sama perempuan, kok. Anaknya cowok, sering nganter ke sini, emang Mbak Rani nggak tahu?"
"Yang nganter ke sini kan orang gede semua, Ke. Mana ada anak-anak?" sergahku yakin.
"Ih ... iya ... emang aku ada bilang yang nganter balita? Anaknya si Mama Joana itu ... udah sekita-kita, kok!"
"Masa, sih? Seriusan dia nikah sama perempuan, tapi dianya juga pakai baju perempuan?"
Mbak Tiwi dan Keke mengangguk bersamaan.
"Terus yang nyusuin anaknya siapa kalau gitu?" gumamku.
Nggak tahu kenapa mereka malah menepuk jidat masing-masing denger pertanyaanku.
"Ya maksudku siapa tahu anaknya bingung mau nyusu siapa kalau dua-duanya pakai baju perempuan, kan?"
"Terserah lo aja deh, Ran."
Tadinya aku masih mau mampir agak lamaan di kubik Mbak Tiwi, lumayan buat ngilangin penat.
Oh ... penatku bukan lagi soal patah hati, kok, aku udah lumayan lupa sama putus hubunganku dengan Bima.
Memang terjadi beberapa insiden yang nggak mengenakkan, kayak tahu-tahu Bima ke rumah dan mengemis-ngemisku kembali lewat bunda seolah dia objek penderita, atau menghubungi teman-temanku yang dikenalnya dan minta supaya mereka membantunya meluruskan pikiranku, macam-macam lah tingkahnya. Tapi bapak, bunda, dan teman-teman Jogjaku sudah tahu benar itu cuma sandiwara. Mereka malah ngadu sambil ketawa-ketawa. Singkatnya, aku udah sepenuhnya move on dari dia.
Kedengarannya memang mudah, tapi caranya tak mengacuhkanku sejak aku minta putus benar-benar menjadi titik balikku. Seolah itu belum cukup, justru bagaimana dia menghubungi kembali saat aku mulai bisa bangun pagi dan langsung melompat dari tempat tidur buat siap-siap masuk kerja tanpa air mata, tanpa beban di dada, malah bikin aku ilang feeling sama sekali.
Saat itu aku berpikir, memangnya dia pikir aku cewek apaan? Memangnya dia pikir dia siapa? Dia kira aku nggak tahu kenapa dia nggak langsung ngajak aku bicara begitu kuminta putus? Dia ngambil kesempatan pasca putus ngelanjutin perselingkuhannya dengan pura-pura ngasih aku waktu berpikir, lalu kembali seenaknya setelah puas main gila.
Aku yakin hubungannya sama cewek itu nggak berjalan mulus, makanya dia ingat aku lagi. Kami udah pacaran selama tiga tahun dan dia masih saja pakai alasan ngasih jarak supaya bisa saling merenungkan kesalahan masing-masing ke aku? Kalau nggak ada perempuan lain, nggak pake lama juga dia udah nyium kakiku, minta maaf sudah memperlakukanku seenaknya.
Aku nggak sebodoh itu. Selama dia nyuekin aku, aku mengumpulkan bukti kebusukannya selama ini di belakangku. Dan yah ... setelah tahu kami beneran putus, nggak sulit membuka mulut semua orang yang pernah jadi saksi pengkhianatannya. Bulat sudah tekadku. Setelah bisa mandiri dan menghemat gajiku sebulan, aku nggak mau lagi dijadiin ATM berjalan seorang pengangguran.
Jadi kalaupun sesekali aku butuh guyonan dengan Mbak Tiwi, atau trio mbak kos-ku, bukan karena aku belum move on, atau apa.
Aku nggak bisa lama-lama di kubikel Mbak Tiwi karena keburu ngelihat Pak Andreas dan Pak Gito jalan ke sini sambil ngobrol serius.
Aku sih nggak ada masalah sama mereka, tapi yang namanya staf biasa, kayak alergi aja kalau harus papasan sama atasan. Mana Pak Gito yang asli Tegal kalau sama aku suka iseng ngomong bahasa Jawa, aku males diketawain sama yang lain.
Tapi terlambat, saat aku berjingkat meninggalkan kubikel staf, Pak Gito keburu buka pintu kaca sambil teriak, "Lho ... Nok?!" gitu.
'Nok' itu buat manggil gadis dalam bahasa Jawa, biasanya digunakan oleh pria yang lebih tua. Kesannya sayang kalau yang manggil bapakmu, tapi kalau bos yang manggil, jadi berasa intim dan kurang senonoh.
"Kok wajahmu pucet ngono?" tanyanya campur-campur.
Huh?
Aku meraba pipiku sendiri. Emang sepucat apa sih aku?
Secara otomatis, namanya juga bawahan, aku menjawab dengan logat Jawa ngikutin beliau, "Ndak, kok, Bapak. Rani endak sakit."
"Iya, lho, Rani. Pucat. Kamu yakin nggak sakit?" imbuh Pak Andreas dengan suara serak basahnya yang berwibawa.
Aku sudah kenal bapak yang satu ini, nada dan cara bicaranya bisa berubah-ubah sesuai waktu, kebutuhan, dan kondisi. Kalau lagi di depan staf, kadang berwibawa, kadang celelekan. Tapi kalau berduaan aja, suaranya lembut, penuh bujuk rayu. Dan kalau berduaannya udah malam, bisa bahaya.
Lagi-lagi, aku menolak dikatain sakit, "Enggak ... cuma capek aja kali."
"Nggak demam, kan?" tanyanya perhatian.
"Masuk angin kali, Ran," Mbak Tiwi ikut-ikutan.
Dengar pendapat Mbak Tiwi, Pak Gito jelas nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ngeledek, "Waduh ... kalau masuk angin, ada yang ngerokin ndak tuh? Pacarnya Rani kan jauuuh!"
Sialan. Terang aja seisi kantor gempar. Yang cowok-cowok langsung sahut-sahutan kayak nggak pernah ngerokin perempuan.
"Kalau ndak ada, Si Andreas pasti mau, nih!"
"Enak aja bapak, nih," Pak Andreas pura-pura jual mahal. "Saya nggak suka ngerokin perempuan yang jauh lebih muda."
Sama denganku, semua perempuan di kantor memutar bola mata sampai nyaris nggak bisa balik lagi ke tempatnya semula.
"Terus, maunya ngerokin yang lebih tua? Tuh Mbok Darmi Indomie juga pake koyo tadi, mungkin lagi masuk angin!"
Pak Andreas menjeb, nggak bisa ngelawan kalau yang ngatain si bos.
Aku juga ikutan ketawa, sih, tapi serius, deh, risih banget kalau cowok-cowok ini bercanda konten seksual bawa-bawa kerokan, pijetan, hiyyy ... geli aja gitu. Tapi sebagai bawahan perempuan kami bisa apa selain kulum senyum pahit. Palingan yang berani protes Mbak Tiwi doang, teriak-teriak setengah bercanda (padahal aku yakin serius setengah mati) bahwa bercandaan kayak gitu tuh termasuk pelecehan seksual.
Setelah ledek-ledekan nggak penting antara Pak Gito dan Pak Andre, aku mengendap-endap, ngelanjutin nyisir kubik ngumpulin form.
Sampai jam makan siang kalau nggak ada tugas lain, aku akan berada di ruang personalia menyelesaikan laporan harian, nyicil mingguan, rekap ini, itu, di depan PC dengan tenang tanpa gangguan. Di luar, meski semua divisi hiruk pikuk, ruanganku selalu tenang, satu-satunya suara yang akan terdengar hanya kuap dan dengung pendingin ruangan.
Ah dasar Pak Gito. Bikin aku baper ajah.
Sebenarnya yang bikin kondisiku nggak jauh berbeda single maupun taken adalah karena hubunganku dengan Bima hubungan jarak jauh. Dulu atau sekarang sama aja, nggak ada yang mijitin, atau ngerawat kalau lagi sakit. Yang lebih mengenaskan paling-paling aku suka kesepian karena ponselku jadi jarang bunyi, kecuali dari bapak.
Kalau kebanyakan anak perempuan ditelepon orang tuanya tiga hari sekali, bapak kadang bisa menelepon tiga kali dalam satu jam. Itu bukan itungan yang berlebihan, lho. Kalau yang lain silent HP supaya fokus ke kerjaan, aku harus silent HP supaya bapak yakin aku memang punya pekerjaan.
Hidupku serasa nggak ada yang ngisi, kecuali ya itu, urusan pekerjaan.
Cowok yang dulu bobo di kosku? Nggak pernah ketemu lagi, tuh. Pertama karena aku nggak mau ngehubungin duluan, kedua karena dia juga nggak inisiatif ngehubungin duluan. Malam itu kami tidur sampai pagi dan saat aku bangun, dia udah rapi siap pergi. Masih sambil ngantuk-ngantuk, aku menerima tawarannya tukeran nomor hape. Kalimat terakhirnya yang kuingat sampai kemudian aku jatuh tertidur di ketiaknya adalah "Yah ... siapa tahu aja ... ini bukan hubungan satu malam, kan?"
Entah apa maksudnya, sebab habis itu dia nggak pernah muncul lagi. Nelepon enggak, chat enggak, SMS juga enggak. Aku lumayan nungguin, sih, bukannya ngarep, tapi gimana, dong, namanya juga udah bobok bareng. Untungnya nggak lama aku buru-buru sadar sama niat awalku untuk get over shit. Kulupain dia, seperti kulupain Bima. Manjur juga, kok, habis itu rasanya ringan dan Bima seolah bukan lagi seseorang yang istimewa bagiku.
"Ran ... habis rekap FRL, lo ke bawah, ya? Cek mesin absen, tintanya kurang jelas tadi pagi," Mbak Nin mengangkat wajahnya dari monitor.
"Siap, Mbak Nin," jawabku ceria.
"Nanti malam ... kalau lo nggak enak badan, biar gue aja yang lembur."
Mau nggak mau, aku terkejut.
"Memangnya mukaku kelihatan pucat banget ya, Mbak?" aku nanya sambil ngaca.
Dahi Mbak Nin mengerut, "Lo ganti bedak?"
"Enggak."
"Kalau gitu, iya. Lo kelihatan pucat. Sakit?"
Pasti karena kantong mataku, nih. Aku memang punya kantong mata yang menyebalkan. Kalau kurang tidur dikit, nyembung dan warnanya akan berubah abu-abu seperti mata panda.
"Aku agak pusing udah beberapa hari," aku menggumam.
"Lo pernah gejala tipes, kan?" Mbak Nin mendengar. "Kalau pernah gejala tipes kudu ati-ati, Non. Jangan kecapaian. Kalau memang lagi nggak bisa lembur, bilang aja."
"Iya, Mbak. Makasih. Kalau gitu, nanti aku nggak lembur dulu."
Puas dengan jawabanku, Mbak Nin kembali berkutat dengan susunan SOP baru yang akan naik cetak setelah ada perubahan kebijakan dari manajemen bulan lalu. Kerjaan kayak gitu kerjaan senior, kerjaanku masih yang sifatnya nyebarin, ngumpulin, ngerekap, dan ngangguk-angguk. Udah setahun lebih kerja, tapi masih gini aja. Mungkin perusahaan belum bisa percaya sama aku, kerjaan kayak gitu kan butuh ketelitian tinggi. Aku aja masih suka salah masukin absen, yang ujungnya kena marah staf cewek divisi lain. Mereka galak-galak, nggak kayak karyawan cowok. Yang cowok lebih ramah, kalaupun salah, mereka langsung maklum kalau aku memelas minta maaf.
Bukannya aku nggak mampu ngerjain kerjaan input-input doang, aku cuma kurang teliti aja. Semua orang juga kadang kurang teliti, toh? Mbak-mbak itu aja yang suka kelewatan. Aku bahkan pernah nangis sesenggukan karena Mbak Kikan dan Mbak Tari pernah ngusulin supaya aku dipindah aja jadi petugas foto kopi karena salah-salah terus. Untung Mbak Tiwi selalu belain aku.
Kutumpuk berkas FRL hari ini bersama berkas selama seminggu di mejaku. Merapikannya sedikit sambil tersenyum puas karena nggak banyak yang ngajuin lembur hari ini. Hari kedua setelah gajian, sih. Mereka lebih senang lembur di mal. Setelah mastiin tumpukannya rapi, baru aku duduk manis sambil memencet layar monitor. Nggak lupa kubuka laci dan kuganti tempat tisu motif Doraemon dengan Keropi. Sambil nunggu PC loading, aku mengelap satu demi satu stationery mulai dari staples sampai stabilo.
Aku nggak suka kalau kerja, meja dan alat tulis nggak rapi.
Kayak udah jadi rutinitas, hal pertama yang kulakukan setelah PC selesai loading adalah memutar playlist yang diawali dengan Januari-nya Glen Fredly. Mataku memejam. Dadaku mengembang oleh udara yang kutarik dalam-dalam dan mengempis kembali begitu kuembuskan lewat mulut. Sungguh menenangkan.
Pintu ruangan terbuka.
"Pagi!" seru Bu Cynthia sambil memasuki ruangan. "Taruh situ aja, Mbok Darmi!" katanya.
Satu mataku membuka untuk mengintip.
"Ran, lo sakit? Muka lo kok kuyu gitu?"
Astaghfirullah ... orang keempat hari ini yang bilang gitu.
"Bu Cynthia bawa apaan, sih?" Mbak Nin nyerobot sambil memencet hidungnya.
Mh! Bau apa, nih? Bau amis telor dan pedas merica!
"Sorry ... gue belum sarapan," jawab Bu Cynthia sambil mengeluarkan uang dari dompet yang kemudian diserahkan pada ibu kantin yang ngehits dengan sebutan Mbok Darmi Indomie.
Kenapa, nih? Kok perasaanku jadi nggak enak gini?
"Baunya amiiis!" Mbak Nin protes.
Iya, amis. Tapi biasanya perutku nggak segitunya kalau nyium aroma ginian. Apalagi kepalaku. Kok muter gini, sih?
"Ya udah, deh, gue makan di pantry. Bentar gue ngidupin PC dulu, sori, sori. Eh Ran ... lo sakit?" dia nunjuk mukaku lagi.
"Enggak ...," kataku lemah, kali ini aku nggak yakin apa benar aku enggak sakit.
Bau indomie rebus yang telornya diacak kegemaran Bu Cynthia memang mengganggu, apalagi dibawa ke ruangan ber-AC. Merica yang selalu minta dibanyakin juga menyengat tajam di hidung, tapi biasanya aku fine-fine aja. Nggak bisa bilang nggak terganggu sama sekali, sih, tapi bisa kutahan. Nggak lantas protes kayak Mbak Nin barusan.
Masalahnya ... perut ini mendadak mual tak tertahankan. Keringat dingin bahkan sampai menitik sebutir di keningku.
"Muka lo pucat lho, Ran!" Suara Bu Cynthia yang tengah sibuk mengangkat kembali mangkuk mie dan teh panasnya menggema di telingaku.
Pandanganku kabur.
Aku muntah di tong sampah.

Maharani
"Bapakku nggak akan paham sama tipe-tipe cowok yang terlalu memperhatikan penampilan, apalagi pakai warna yang menurutnya biasa dipakai perempuan."
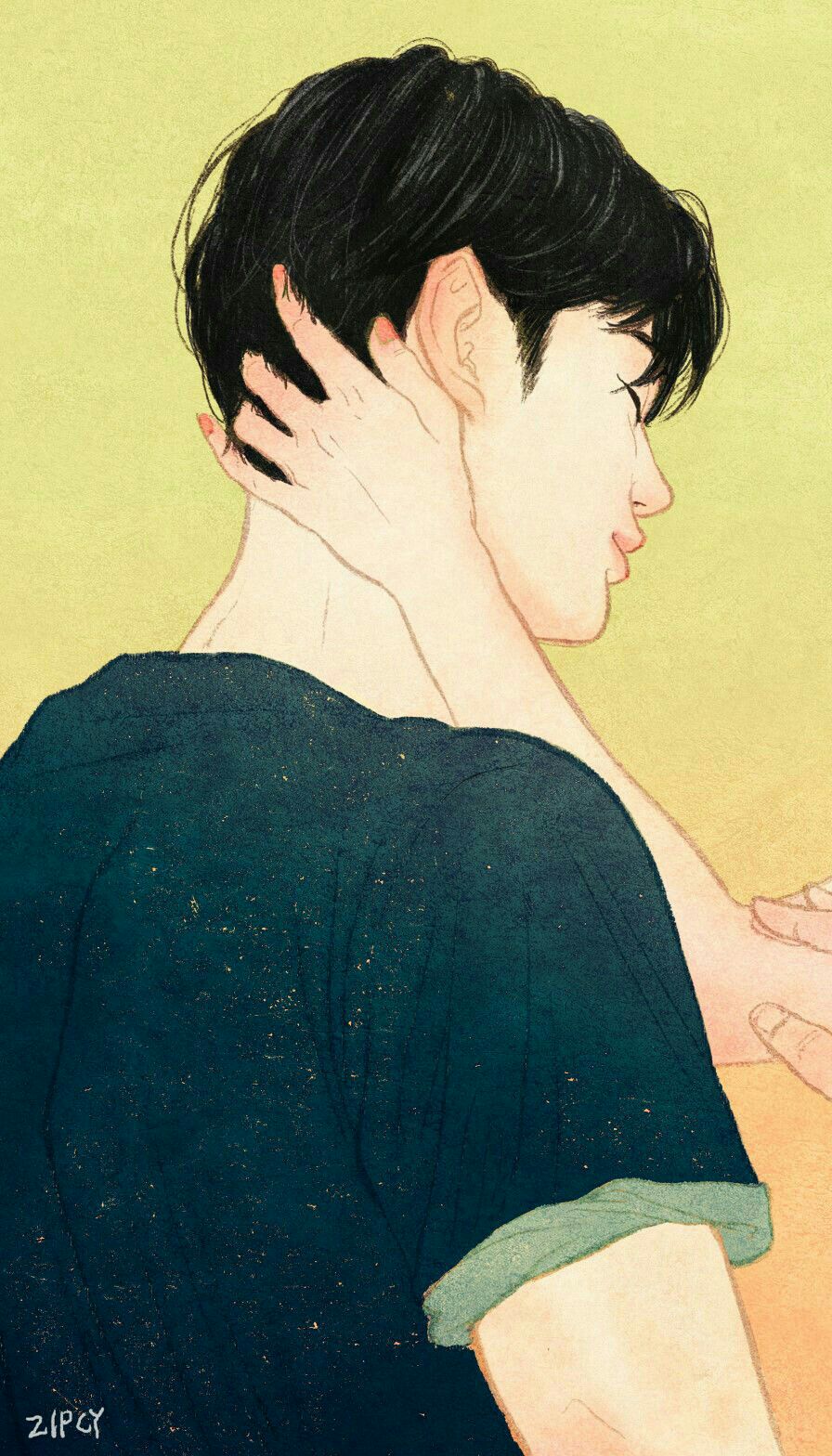
Yudha
"Maksudku lucu yang manis, Ran, bukan lucu yang bikin ketawa kayak donal bebek gitu."
If you love it, vote. If you got anything to say, comment. I love youuu!
Kin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top