15. Cobaan Cinta
Your parents know you
Sometimes more than you've ever known
https://youtu.be/EcZJh_axDa0
Aku dipanggil ke kamar beberapa menit setelah makan malam. Terpaksa, keinginan Yudha buat ke Angkringan Tugu benar-benar harus batal malam ini. Dia ngasih aku kecupan di kening buat meyakinkan kalau semua akan baik-baik aja, dia bilang ini saatnya jujur. Toh, dia udah beli oleh-oleh. Kalau diusir, paling enggak kami pulang dengan buah tangan.
Bapak sudah pake kaus singlet dan sarung rumahnya yang bulukan, duduk di kursi goyang sambil mainan jenggot. Bunda ganti daster kebangsaan yang tenunannya rantas nyaris berlubang, agak nguap-nguap karena nggak biasa tidur kemaleman. Jam sepuluh paling mentok bunda udah berbaring, jam dua dini hari bangun, salat malam, masak, dan ngurusin urusan rumah tangga lain-lain. Waktu aku gabung, volume televisi ruang keluarga dikecilkan.
Topik bahasan utama ya soal pekerjaan.
"Bapak nggak bilang yooo kalau laki-laki nggak bisa punya toko kue!" sangkal bapak pertama kali saat bunda membuka pembicaraan. Keberatan sama komentar bapak yang mungkin menyinggung Yudha di meja makan tadi.
"Tapi bapak kayak yang aneh banget gitu ekspresinya," protesku.
"Lho ... di mana-mana itu, toko kue dan masakan biasanya pakai nama ibu-ibu. Gudeg Yu Djum, Gudeg Bu Pudjo, Tahu Baso Bu Pudji, Ayam Goreng Soeharti, Mbok Berek—"
"Bebek Pak Slamet? Sop Ayam Pecok Pak Djek?" sambungku, penuh sanggahan.
"Raminten malah waria," celetuk bunda.
Aku langsung nelen ludah, mukaku kayak ditampar pake kain pel.
Untung, bapak kelihatan mereda sinisme-nya gara-gara ucapan bunda, "Iya, udah, bapak nyerah," katanya. "Soalnya kamu nggak ngelurusin sih waktu bapak nanya toko bangunan."
"Ya biar nanya sendiri."
"Emangnya bapak staf personalia disuruh nanyak sendiri, apa gunanya ada kamu sama bundamu kalau nggak bisa ngasih info? Gengsi, dong."
"Padahal mukanya alus banget ya, Pak, cocoknya jadi pegawai kantoran."
"Pegawai kantoran gajinya kecil," bapak mencemeeh.
"Lho kantor apa dulu, kalau kantornya besar, atau di perusahaan pemerintah, ya gajinya gede."
Melihatku memijat kening, bapak dan bunda serempak berhenti membawa-bawa soal perusahaan pemerintah, sebab pasti ujungnya dibandingin sama suaminya Mbak Halimun. Aku nggak pernah suka, nggak sama Bima yang mahasiswa tua, atau Yudha, nggak pernah sebanding di mata orang tua.
Bak tikungan curam, topik pembicaraanpun dibelokkan.
"Lha kamu kok bisa kenal dia, katamu temannya teman, apa kalian dijodoh-jodohin?" bunda nanya.
Padahal, tadi siang udah nanya, tapi nggak cukup kalau enggak detail. Malah kalau bisa ada tanggal, jam, dan menitnya sekalian kayak berita acara pemeriksaan.
Jadi aku mengarang indah, "Rani kan staf personalia dan general affair, sering dimintain tolong kalau divisi mau ngirim paket ucapan terima kasih ke klien. Misalnya kayak ulang tahun klien, gitu, nah sekarang di Jakarta lagi ngehits pai apel bikinan toko papanya Yudha. Ya udah Rani sering ketemu."
"Lha temen kamu yang temennya Yudha itu kerja di kantormu, atau kerja di tempat Yudha?"
"Kerja di kantor Rani, Bun," karangku.
"Si Tiwi itu?" bapak inget aja. Mbak Tiwi memang pernah mampir waktu ke Yogya, dibanding ketiga Mbak kosku yang berisik, bapak lebih suka sama Mbak Tiwi yang tomboi dan gampang akrab sama siapa aja.
"Iya," gampangin ajalah, pikirku.
Pertanyaan selanjutnya, "Lha kamu ... udah berapa lama kenal dia, Ran?"
"Udah lama," jawabku ngasal.
Bapak dan bunda lihat-lihatan, "Bukannya apa-apa, bapak cuman pengin tahu aja," kata bapak.
"Udah lama kok kenalnya aja," aku menegaskan, biar nggak kerasa aneh kalau udah saatnya aku jujur nanti. Kan aku dan Yudha udah sepakat untuk ngerahasiain bayi ini kami bikin dari hubungan satu malam.
Bunda menyelidik, suaranya mendesis, "Sebelum putus sama Bima?"
Nah ini pun udah ada dalam perkiraanku sebelumnya. Kalau kubilang kenalnya udah lama, lalu nggak ada tiga bulan sejak saat itu aku udah bawa cowok baru, pasti dikira aku selingkuh. Sama aja kayak Bima.
"Iya, tapi deketnya yang baru-baru ini."
"Lak habis putus sama Bima toh yang kamu maksud baru-baru ini?" terka bunda lagi.
"Iyaaa."
"Udah lulus dia ini kuliahnya?" imbuh bapak.
"Udah."
Jeda sebentar.
"Bapak bukannya apa-apa, kok mendadak," bapak kayak kumur-kumur. "Mau diajak ke Angkringan Tugu segala, kamu tuh udah udah dewasa lho, Nduk, yang udah ya udah ...."
"Lho, Yudha kok yang ngajak ke Tugu, lagian nggak jadi!" aku merengut. "Rani ya ngapain sih ngajak ke Tugu kalau bukan karena Yudha belum pernah ke sana."
"Di sana kan pasti ada Bima," bapak nggak mau dengerin aku. "Nanti kalau berantem, apa nggak malah malu-maluin?"
"Rani ngajak Yudha ke sini ini bukan buat dipamerin ke Bima," gerutuku, bisa baca pikiran mereka.
"Lho bapak nggak bilang gitu, lho," ngelesnya.
"Soalnya ... kok cepet banget aja ... gitu ...," sahut bunda ragu-ragu.
Tanganku udah mulai dingin dan mati rasa. Kalau nggak bunting juga aku nggak akan bawa-bawa cowok kurang dari tiga bulan habis putus hubungan. Bawa cowok ke rumah buat anak gadis itu bukan hanya demi menaikkan gengsi, tapi juga memberi harapan pada kedua orang tua. Apalagi habis putus, nggak boleh sembarangan bawa pacar baru ke rumah. Aku ngerti semua itu, makanya bapak nuduh aku mau pamer ke Bima.
"Kalau bukan buat dipamerin ya sudah ...," suara bapak melunak. "Bapak tuh nggak nuduh, cuman was-was aja. Kalau bapak sih penginnya kamu pikir masak-masak, nggak usah grusa-grusu. Kamu masih muda, santai aja, nggak usah didengerin mulut orang yang suka nyengit sama jomlo. Bapak mana pernah sih ngoyak-ngoyak kalian?"
Aku menunduk.
Bapak nambahin, "Kalau bundamu ya mungkin ...."
Bunda mendecapkan lidah, "Yah ... gimana, semua orang udah tahu kamu pacaran sama cecurut itu. Setelah huru-hara dia ke sini diusir bapak, sekampung juga denger kalian nggak gathuk lagi. Meskipun bunda bersyukur kamu lepas dari madesu, tapi perasaan khawatir itu pasti ada. Namanya juga punya anak perempuan."
"Ya kalau anaknya baik ya wes, dicoba jalanin dulu aja. Bapak sama bunda cuma nggak nyangka aja ... ya itu tadi, kok ... cepet," bapak nyender di kursi.
"Maksud bapak?"
"Ya nggak apa-apa, wong ya Bima di sini ternyata juga kurang ajar sama kamu."
"Kalau bapak mau nanya Rani selingkuh atau enggak, Rani nggak selingkuh, Pak. Rani ini setia," ucapku berapi-api.
"Bapak percaya. Bapak kan cuma bilang kalau bapak paham yang namanya orang pacaran, wajar kalau nyari yang lebih baik. Semoga aja yang ini lebih baik. Bapak nggak masalah soal kerjaannya, yang penting tanggung jawab."
Kalau tanggung jawab, Yudha sih jelas tanggung jawab. Tinggal yang bapak maksud tanggung jawab dalam artian kayak gimana. Jelas beliau nggak nyangka kalau tanggung jawab yang kupikirkan dengan tanggung jawab yang beliau maksud beda. Bapak dan bunda masih berputar-putar di persoalan mata pencaharian, aku ya soal perutku ini.
"Ngantor, atau punya kantor sendiri itu nggak masalah. Yang penting bukan penghasilan tetapnya, tapi tetap berpenghasilan. Artinya nggak nganggur-nganggur, santai-santai, tahu macarin anak orang dibesarin butuh biaya," cerocos bapak.
Bunda menjeb aja. Kenyataannya, bapak dulu dikasih lampu hijau juga karena udah jadi PNS. Pernah mau pensiun dini dan buka toko taneman, bunda pulang ke rumah kakek. Nangis. Nggak siap kalau hidup bergantung laku atau enggaknya pupuk tahi sapi dan Gelombang Cinta, waktu lagi booming-boomingnya di majalah Trubus.
Interogasi terus bergulir.
Bunda, "Kalau bapaknya gimana?"
Aku, "Baik."
Bapak, mengernyit.
Aku nggak siap sama pembahasan yang satu ini. Ini lebih jadi momok buatku daripada ngabarin soal kehamilan. Orang tuaku mungkin akan murka, tapi aku cukup mengenal mereka. Bagaimanapun marahnya, mereka nggak akan membiarkanku mengandung tanpa suami. Begitu cucunya lahir, semua ini akan jadi cerita masa lalu yang nggak akan dibicarakan di kemudian hari. Persis seperti ketidaklolosanku masuk perguruan tinggi negeri, atau kisah kelam Pakdhe yang ketahuan mau poligami lalu disembunyiin sementara oleh bapak dari amukan Budhe. Tapi soal Jonah, bukan hal yang bisa dilupakan, atau pura-pura dilupakan dan dianggap sebagai aib.
Besan itu harus pantas dan cukup bisa diajeni, makanya orang tua Jawa selalu nanyain bibit. Kenapa? Karena penting buat mereka duduk sejajar, kalau perlu punya besan yang lebih tinggi derajatnya, jangan lebih rendah.
Kalaupun lebih rendah, ya paling enggak jelas lah jenis kelaminnya!
Aku pengin nangis.
Setiap kali aku minta bantuan ke Yudha gimana meyakinkan bapak soal papanya, dia cuma bilang, bilang aja sejujurnya, hilangin dulu soal atributnya. Tapi otakku terlalu mampet kalau disuruh menggambarkan sosok camer ideal.
"Baiknya gimana?" tanya bapak, penasaran. "Kalau cuma baik, Pak Jokowi juga baik, tapi Selvi nggak mungkin ngenalin ke orang tuanya cuma pake kata 'baik' tok, pasti ada embel-embelnya. Bapaknya Gibran walikota Solo, gitu misalnya."
"Presiden!"
"Waktu pacaran masih walikota!"
Subhanallah.
"Yah ... kata Yudha ... papanya ulet. Dari dulu suka usaha sendiri"—aku nggak bilang dia usaha sendiri karena nggak ada kantor yang mau nerima cowok ngondek berlebihan, atau dulu kerjanya model terus berhenti karena ngasuh bayi—"punya toko pai yang lagi happening itu, sama ... kafe ..."—nggak kujelasin juga kafe apa, bapak nggak akan mikir sejauh itu—"punya rumah, ruko, mobilnya dua—yang bagus dia pakai, yang biasa dipake Yudha—ramah, lucu, tinggi, ramping—"
Begitu nyampe ke ramah, lucu, apalagi tinggi, ramping, wajah bapak mengeruh. Memotong, "Masih muda emangnya?"
"Lumayan," jawabku.
"Sama bapak?"
"Sepuhan bapak."
"Hmmm..." lenguhan bapak terdengar puas.
Bapak senang kalau besannya lebih muda, jadi nggak perlu sowan-sowan kalau pas lebaran atau kebetulan lagi sekota. Orang yang lebih tua jatahnya didatangi dan bapak kurang suka bertamu demi unggah-ungguh.
"Kamu udah diajak ke sana, Nduk?" Selalu bunda yang mengawali topik pembicaraan baru, tingkat kekepoannya bikin gengsi bapak selalu terselamatkan. Jadi bapak nggak perlu banyak nanya, padahal sebenernya sama aja keponya.
"Udah."
"Ya pasti udah," tukas bapak. "Enak aja perempuan dirantau sudah bawa laki-laki ke rumah jauh-jauh, kok perempuannya belum dikenalin sama keluarga. Lancang itu namanya."
Ini nyindir Bima. Tiga tahun pacaran dan tinggal di kota yang sama dengan orang tuanya, aku hanya pernah lihat pagar rumahnya doang. Belum diajak masuk, alasannya karena dia belum lulus. Aku nggak protes karena posisinya di keluargaku sama, nggak akan dia dibiarin ngawinin aku kalau gelar sarjana aja nggak bisa dia dapet. Sama kuliahnya aja nggak tanggung jawab, gimana mau tanggung jawab sama istri.
Aku memutuskan untuk nggak tersinggung, aku harus bersikap senurut mungkin, supaya mood bapak dan bunda nggak jumpalitan saat aku akhirnya mengaku.
"Bapaknya senang sama kamu, Ran?"
"Ya senang," serobot bapak lagi. "Anak cantik, kerjaannya bagus, mandiri, anak orang baik-baik, nggak ada alesan buat nggak senang."
Kerjaanku sih nggak bagus-bagus amat seperti gambaran bapak, tapi lumayan lah. Sekali lagi, kuingatkan, bapak itu agak seksis. Buatnya, wanita kerja aja udah bagus, nggak usah ngarep jabatan tinggi atau gaji luar biasa besar. Bunda yang seorang guru SD aja nggak pernah dikasih izin sama bapak buat naik jabatan jadi kepala sekolah, katanya nggak usah ngoyo, yang penting dapur ngebul, anak-anak nggak terlantar.
"Papanya baik kok, Bun," kataku meyakinkan. "Maksudnya baik dan ramah sama aku, ya senang-senang aja aku sama Yudha."
"Bapaknya tahu Yudha kamu ajak ke sini?"
Aku mengangguk.
"Tahunya kamu ajak jalan-jalan aja, atau sowan bapak sama bunda?"
Bismillah, pembicaraan sudah mulai mengerucut, "Sowan."
Benar, kan, bunda dan bapak saling lempar tatapan curiga.
Kali ini, otoritasnya bapak, "Tapi ... ini kan belum serius-serius banget to hubungannya?"
Begini—kupikir di semua keluarga juga mungkin sama—kalau anak cowok ke rumah anak cewek, itu udah biasa. Ngapel malam minggu juga sopannya mereka ke rumah. Hubungan naik selevel saat anak perempuan mulai dikenalkan pada orang tua pria. Hubungan jadi serius saat orang tua pria tahu bahwa—dalam hal ini karena orang tuaku tinggal lain kota, sedangkan aku merantau di kota yang sama dengan tempat tinggal calon suamiku dan keluarganya—anaknya diajak ke rumah orang tua perempuan dalam rangka sowan, bukan hanya jalan-jalan. Aku tinggal terpisah dari bapak dan bundaku, jadi Yudha datang ke rumah nggak bisa disamain dengan mantan-mantanku yang ngapel malam minggu zaman masih sekolah dulu.
Kuharap, situasi yang ada di benak orang tuaku cukup tergambarkan.
Berdasarkan uraian di atas, aku menjawab, "Masa dibawa pulang nggak serius, Pak?"
"Ya ... bapak ngerti, bagus itu. Kamu udah cukup umur, pacaran ya harus serius. Bapaknya juga pasti paham kenapa Yudha diajak kenalan sama bapak."
Bibirku kubasahi sebelum mengangguk, tenggorokanku mulai kering. Kusahut jeruk hangat bapak yang udah dingin dan kuteguk banyak-banyak.
Bapak makin kelihatan punya banyaaak sekali pertanyaan, urat-urat di dahinya sampai bertonjolan. Tandanya beliau mikir keras mau nanya sesuatu yang akan menghasilkan jawaban sarat informasi tanpa dianggap pengin tahu aja.
Semacam begini contohnya, "Yudha bilang apa waktu pamit sama bapaknya kemari?"
"Mau ketemu sama bapaknya Rani di Jogja," jawabku, sederhana.
"Terus bapaknya gimana?"
"Ngizinin."
Bapak mengembuskan napas. Mulai jengkel. "Ya pasti diizinin, wong wes gede tuo, bukan anak SD," geramnya. "Maksud bapak ... apa bapaknya Yudha nanya dia ke sini dalam rangka ramah tamah aja, atau punya pikiran ke ...."
"Mantenaaan," lanjut bunda karena bapak berhenti dan malah berdeham.
Hening sebentar.
Bapak menyambung, "Bapaknya Yudha ... atau Yudha kan nggak pengin cepet-cepet, toh, Nduk? Kamu juga nggak pengin cepet-cepet, toh, Nduk?"
Aku menggigit bibir bawah, jantungku jedag-jedug nggak keruan. Napasku udah lewat mulut saking gugupnya.
"Nduk ...," panggil bapak.
Karena aku nggak mau menjawab, bapak lagi-lagi bicara seperti meyakinkan dirinya sendiri, bukan aku. "Wong kamu habis putus, pasti masih terpukul. Bapak tahu kamu mungkin panik, putus dari hubungan yang udah terjalin bertahun-tahun di usia begini. Tapi ... jodoh itu ada yang ngatur, Nduk, asal kamu nggak putus usaha. Dipikirin baik-baik dulu, diselami dulu, dikenali dulu. Kamu tahu bapak percaya sama kamu. Sama semua anak bapak, bapak percaya kalian nggak akan ngecewain orang tua. Makanya bapak berani memberi izin pacaran ke kalian. Menikah itu harus dipikirin baik-baik, bukan lantaran kecewa, atau balas dendam, apalagi pengin membuktikan kepada sesama manusia. Nggak penting itu."
Tatapan bunda kurasakan makin menusuk sepanjang bapak berkhotbah.
"Rani ...," bunda memanggil. Beliau pasti sudah bisa mencium gelagat anehku. Wanita itu duduk menyebelahiku, mengelus pundakku lembut. "Kamu udah yakin memangnya sama Yudha ini?"
Kepalaku mengangguk.
Bapak kembali terintimidasi. "Seyakin apa? Seberapa yakin? 25%, 50%? Berapa? Kan barusan aja pacarannya. Kalian udah punya rencana nikah memangnya?"
Lagi, aku hanya mengangguk.
Punggung bapak bersandar di kursi goyang, baru kemudian beliau bertanya lagi, "Kapan?"
"Maunya Rani sih secepatnya," aku menunduk, nekat.
"Secepatnya itu kan masih itungan setahun, dua tahun toh, Maharani?" bunda berbisik sambil terus mengelus bahuku.
"Secepatnya itu maksud Rani sebulan, dua bulan," aku makin nekat lagi.
Nggak ada tanggapan. Bukan karena mereka setuju, tapi karena kaget dengan jawabanku.
"Sebulan dua bulan piye, toh?" akhirnya bapak meledak setelah aku nggak berniat meralat ucapan. Nada bicaranya meninggi.
"Yang bener lho, Rani, bapak sama bunda nanya nggak bercanda," bunda ikutan serius.
"Sebulan dua bulan," dengus bapak. "La opo mbentuk panitia tirakatan tujuh belasan, pesen tumpeng, lalu pengajian!"
"Ya pengajian kayak tirakatan juga enggak apa-apa," lemahku, tak berdaya. Udah lemes aku sebadan-badan. Kalau berdiri, aku pasti kliyengan.
"Nikah itu nggak sembrono lho, Ran. Jangan ambisius cuma karena hubunganmu sama Bima nggak berhasil, kamu nggak harus ngotot, Nduk ...," bunda masih mengelus pundakku, kali ini bukan dengan lembut, melainkan penuh tekanan.
"Lagian ya nggak bisa, noh, sebulan dua bulan. Paling cepet tahun depan. Bapak kan udah bilang, bapak udah siapin tanah buat dijual setahun dua tahun lagi buat kawinanmu. Kok malah minta pengajian. Nanti bapak ditanyain sama malaikat, kok punya anak tiga yang satu dibikinin pesta nanggep wayang, yang satunya cuma pengajian, bapak mau ngomong apa?"
Malaikat tuh bukannya cuman nanya siapa pangeranmu, apa kitabmu, ya? Emang nanyain kawinan anaknya nanggep wayang apa enggak?
"Kesambet apa sih kamu ini kok tahu-tahu minta kawin sebulan dua bulan," bapak mengentakkan kaki, beranjak dari kursi goyang. "Meteng opo piye? Sembarangan ae."
Lalu aku mulai nangis.

Yudha
"Kamuakan manggil aku kalau emosimu udah turun, kan?"

Maharani
"Enggak. Aku nggak akan manggil kamu."
Halooo ... update hehe ... sori kemarin kan update Saya-Kiki dulu, karena sebelumnya Rani yang diduluin. Sebagai mama, saya dituntut berlaku adil /halah/ kalau lupa ceritanya, baca lagi part sebelumnya ya ... siapa tahu ada part2 yang belum di-vote kan sekalian LOL
Yang punya akun IG ini, hubungi saya via IG yaaa... biar nggak usah verifikasi lagi. Pemenang ini dipilih secara acak oleh saya sendiri, wkwkwk... Makasih yaa semua yang udah ikutan dan maaf banget telat pengumumannya. Nanti kita bikin GA lala lili lagi. Terus kemarin kan ada yang bilang, bikin GA yang bukan via IG, biasanya gimana sih GA-nya kalau di wattpad-wattpad aja? Jangan susah-susah ntar nggak ada yang ikut kalau hadiahnya paling receh-recehan. LOL
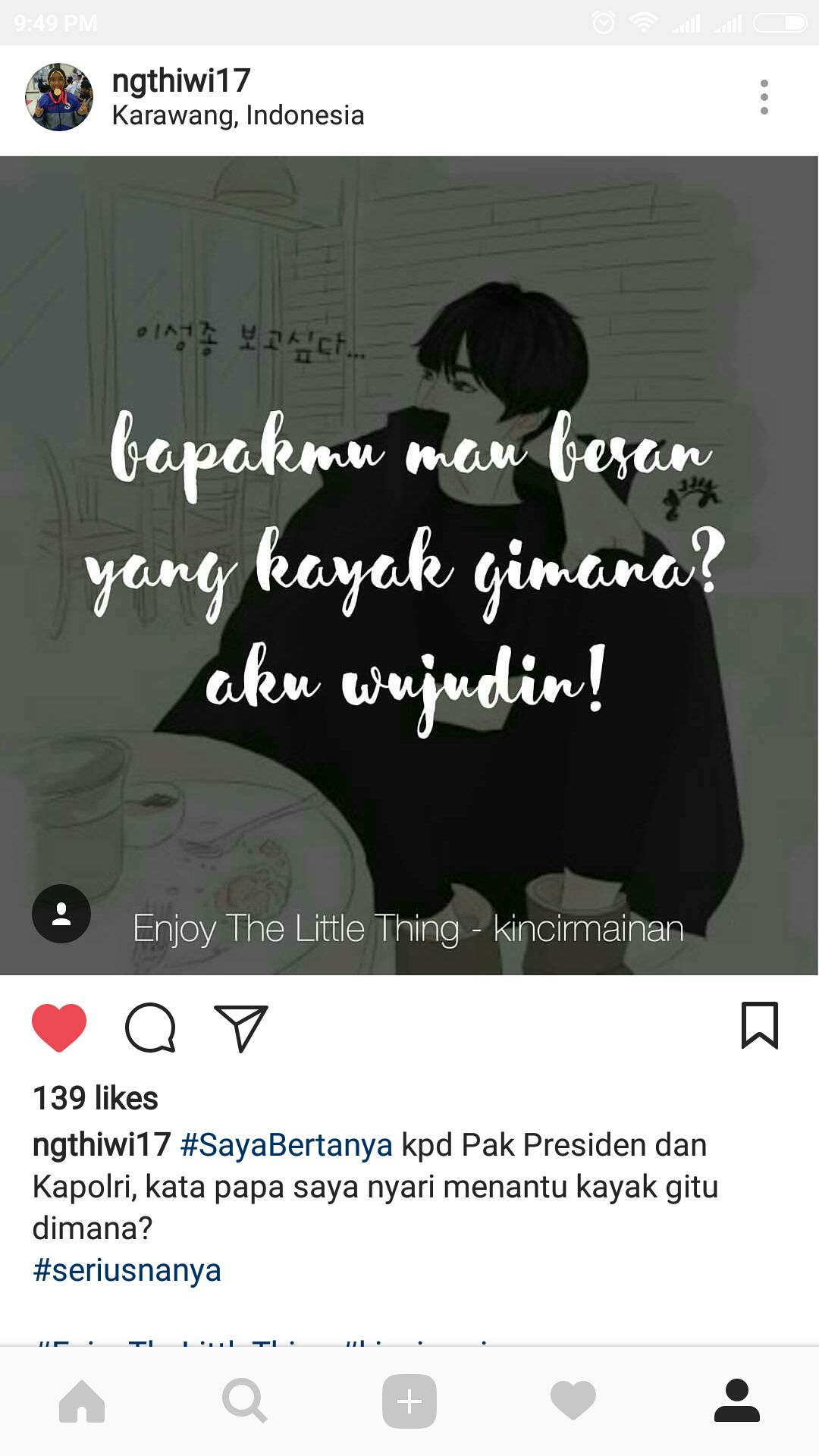
Nah lho bapaknya Rani udah bisa tahu nih kayaknya part depan. Semaput apa enggak ya si bapak, belum kalau tahu soal Jonah. Apakah ceritanya akan makin berliku atau malah manis-manisan aja langsung disetujui, menikah dan punya anak?
Tunggu lima hari lagi, yaaa!
Oh iya, kemarin Maharani sama Yudha ketemuan lho di Inkigayo, lihat aja kalau nggak percaya.
https://youtu.be/mc5kDtLKy-M
Wkwkwk bisa pas tuh sebelahan Sungjong sama Jisoo (paling kanan). Momen langka ini soalnya nggak ada ceritanya Sungjong dipasangin sama Jisoo, sedunia nggak ada kayaknya yang nge-couple-in, yang bikin ini ngasal soalnya. Ngahahaha
Jangan lupa vote dan komennya ya, kalau vote cuma bisa sekali, komennya aja siiih yang banyak sekali.
I love you.
Muach
Kin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top