12. Kekuatan Cinta
Bapakmu juga pasti suka sama Yudha
Dia supel gitu
https://youtu.be/SfrtnM_9BBE
Malam ini aku pulang dengan perasaan setengah lega, setengah tertekan. Permohonan cutiku dikabulkan.
Seperti yang bisa diduga, Yudha malah senang bukan buatan. Kayak anak kecil yang nggak paham apa yang akan dihadapinya. Kadang aku suka heran sama dia, nggak ada takut-takutnya jadi orang. Orak ndolor kalau orang Jawa bilang.
"Kamu pulang aja, deh, Yud ...," saranku, yang sebenarnya nyuruh, sebelum dia ikutan turun dari mobil.
Mukanya langsung berubah. "Lho kenapa?" dia nanya dengan nada kecewa. "Tadi katanya capek? Nggak mau dibikinin air panas dulu sekalian ngomongin apa yang mau kita bilang ke bapak."
Itu alasannya aja. Jujur, Yudha lebih sering mendengarkanku mengoceh daripada ngasih ide atau urun rembug. Kecuali kalau topik obrolan nggak ada hubungannya sama hal-hal yang memicu emosiku, baru ceriwisnya keluar. Kalau aku lagi ngebahas yang penting, dia diem. Takut salah ngomong, dia bilang. Paling dia mijitin (untung pijitannya enak), nawarin nyabunin punggung (karena memang udah susah karena badanku pegal semua), atau ngajak sayang-sayangan kayak anak kecil. Pantesan Jonah protektif banget sama dia, anaknya aja manja begini. Aku memang baru sekali lihat mereka barengan, tapi udah langsung kelihatan.
"Nggak ah, mau langsung bobo aja," jawabku malas.
"Aku pijit dulu betisnya," dia masih maksa.
Kalau nggak bete mikirin bapak, aku pasti tergoda. "Kamu kan harus siap-siap, lusa pagi-pagi kita berangkat. Jangan mepet nyiapin bajunya, kan kamu harus milih yang mana yang layak dipakai di depan bapak."
Kepalanya tertunduk. Muram.
Aku cari-cari alasan. "Jaket bomber yang kamu pesan kemarin udah datang?"
Menggeleng.
"Tuh, kaaan ... kamu nggak akan pakai jaket yang ada bordiran pumanya, kan, Yud? Ya aku tahu bordirannya emang puma, tapi warna benangnya tetep aja ungu, mana ada swarozsky-nya lagi. Kamu jangan percaya kalau Jonah yang pilihin, Yud, nggak macho itu mau bahannya dari kulit juga!"
"Iyaaa ... aku nggak akan pakai itu. Jaketnya juga pasti datang besok, orang ditracking juga udah keliatan sampai mana."
"Kok nggak beli di toko aja, sih," aku menggerutu, padahal aku ya tahu jawabannya. Paginya 'kan dia kerja ngurusin kedai sama Jonah. Malemnya ngurusin aku. "Lagian ... kamu ini cowok kok jaketnya bermotif semua, sih. Sekalinya ada yang doreng, warnanya pink sama item. Kamu pakai gituan emang, Yud?"
Diem.
Aku jadi nggak enak. "Maaf ..., aku kan cuman nanya...."
Lidahnya mendecap. "Udah dibilang itu hadiah fans di pub, aku aja nggak pernah make."
"Nggak pernah make kok sampe belel," dengusku.
"Dipakai Jonah, terakhir dipinjem temen."
"Cewek?"
"Cowok!"
Astaga ... temen cowoknya pakai begituan juga? Makin puyeng aja akutuh. Tapi, kalau yang minjem cewek, aku juga bakal cemburu, sih.
Aku lagi pusing soalnya. Tegang gitu mau ketemu bapak. Nggak pengin mesra-mesraan dulu sama Yudha karena bikin perasaanku makin kacau. Akhirnya, dengan susah payah, aku berhasil melarangnya masuk kamar. Meski alasan nyiapin perlengkapan buat lusa ke Jogja sebenarnya berlebihan, besok juga masih bisa, Yudha menyerah. Mukanya kelihatan mau nangis karena masih pengin berduaan, dengan lunglai dia putar badan dan berlalu dengan mobilnya.
Begitu sendirian aja aku mandi air dingin dan menyicil menata koper. Aku hanya nyiapin sedikit pakaian toh di sana bisa pinjam baju Kintamani. Begitu selesai, tergoda buat ngerumpi di kamar sebelah.
"Yudha mana?" Mbak Ambar menyambutku masuk kamarnya. Sekarang kalau ada aku, tapi nggak ada Yudha, pada nanyain semua. Dia memang gampang populer di antara wanita, tapi bukan untuk dikagumi, melainkan dijadikan teman ngerumpi.
"Pulang," jawabku, duduk di tengah Mbak Arum dan Teh Winna.
"Tumben?"
Aku mendesah, "Siap-siap."
"Udah dapet cuti?"
Kepalaku menunduk, mengangguk, badanku lungkrah ke bahu Mbak Arum.
"Yang sabar," nasehatnya. "Mau gimana lagi? Yang penting Yudha mau tanggung jawab."
"Yudha tuh manis banget, ya?" Teh Winna senyum-senyum, nyenderin bahuku. Kami jadi kayak kue lapis surabaya.
"Iya," timpal Mbak Ambar. "Gue udah agak ngeri kalau si Alex itu kayak Harry. Udah nyaris ngasah golok gue kalau-kalau dia mangkir dari tanggung jawab."
"Alex?" Kening Mbak Arum mengernyit. "Oh ... dulu dia kenalannya nggak pake nama Yudha kan, ya?"
"Di antara mereka berempat, cuman si Alex ini dong yang akhirnya kita tahu nama aslinya," Teh Winna mengikik.
"Emang Teteh nggak lanjut komunikasi sama yang dulu?" tanyaku penasaran.
"Najis," Teh Winna pura-pura ngeludah.
"Dulu ..."—aku ragu nanya enggak—"gitu enggak?"
"Enggak-lah!" semburnya. "Duh amit-amit, deh. Omongannya aja gede banget, semalaman ngomongin jabatannya di kantor, tiap tahun ke sinilah, ke situlah. Dia pikir gue anak kampung diiming-imingin gituan supaya mau diajak tidur? Kalau dia nggak banyak ngomong mah ganteng, cowok tuh kalau banyak cing-cong bikin males."
"Yudha juga ceriwis," kataku.
"Lagian lo kan emang anak kampung, Win," kelakar Mbak Arum bikin kata-kataku nggak ada yang ngerespons.
"Yudha nggak ah," Mbak Ambar ternyata dengar.
"Iya, kok. Dia tadinya bawel banget," aku manyun. "Kita aja tadinya udah nggak mau gitu, gara-gara ngobrol serius ... jadi kebawa suasana."
"Dia asyik ah orangnya," Mbak Ambar masih berusaha membantah pendapatku. "Emang sih kadang agak suka ngomong."
"Serius?" Mbak Arum terheran-heran. "Bukannya di Go-Go dulu dia diem aja, sampe gue becandain habis lepas behel?"
Teh Winna tertawa. "Lo nggak pernah lihat Yudha kalau habis diamuk sama Rani, sih. Kalau udah melipir ke sini, memang seru ngobrol sama dia. Surprisingly, dia nggak kayak cowok kebanyakan. Dia suka cerita, kadang ngeluh, kayak anak bungsu."
"Kayak cewek," dengusku.
"Itu namanya sentimentil," sergah Teh Winna lagi. "Cowok sentimentil itu bagus diajak membina rumah tangga, kayak abah gue."
Aku tertarik.
"Abah tuh nggak kayak ayah-ayah lain, dia nggak keberatan berbagi pekerjaan rumah tangga sama ambu. Kalau diajak curhat juga nyambung, nggak formal kayak orang tua pada umumnya. Orangnya sentimentil, agak sensitif. Kata ambu Kalau berantem, diem, ngalah, hanya marah kalau udah keterlaluan."
"Itu bagus ya, Mbak?" aku beneran nanya, soalnya bapakku nggak kayak gitu.
"Lah ... kamu kan udah beberapa minggu jalan sama dia, gimana kayaknya?" Mbak Arum menyela pertanyaanku.
"Yah ... emang kayaknya gitu, sih. Dia memang asyik dan seru. Aku juga ngebayangin ... dia bakal sayaaang banget sama anaknya."
Aku nggak bilang bapak nggak asyik. Bapak juga bapak yang baik, penuh tanggung jawab, prinsipil, meskipun galak dan kadang sengit. Namun, harus kuakui, nggak sedikitpun bapak mau nyentuh pekerjaan rumah bunda. Padahal, kalau soal nafkah, bunda juga kerja meski penghasilannya nggak sebesar bapak. Kadang anak-anak perempuannya suka kasihan sama bunda. Aku aja kadang ngeri kalau-kalau entar dapat suami kayak bapak, udah kerjaku sampai malam, masa masih harus ngurusin semua-semua sendiri? Bapak tuh ya ... kaus kaki, celana dalam, semua disiapin sama bunda.
Kulihat-lihat, Yudha nggak gitu.
"Tenang aja ...," Mbak Ambar menepuk bahuku dari belakang. "Yudha itu kebetulan yang baik. Dalam hidup manusia, kadang ada faktor X yang nggak diharapkan, tapi membawa berkah. Bapakmu juga pasti suka sama Yudha. Dia supel gitu."
"Nggak tahu deh, Mbak ... bapak tuh kurang suka cowok yang modelnya kayak Yudha gitu. Terlalu pesolek. Terlalu ...."
Lanjut Mbak Arum, "Feminin?"
"Iya."
"Tapi tingkahnya enggak, kok," sanggahnya sendiri. "Biasa aja dia, itu namanya flamboyan. Cowok zaman sekarang banyak yang gitu. Bersolek, bicaranya manis, perhatian ...."
"Aku suka-suka aja sih sama Yudha," timpal Teh Winna.
Aku mendengus. "Ya bagus kalau Teh Winna bapakku."
"Udah ... yakin aja, semuanya pasti lancar."
"Kalau lancar ... kira-kira kapan kalian nikahnya, ya?"
"Harusnya sih secepatnya."
"Kita harus nyiapin baju, dong."
"Nggak usah, Mbak. Ngapain?" aku menggerutu. "Kalaupun bapak setuju, nikahnya juga nggak akan gimana-gimana, paling pengajian. Mungkin malah aku nggak akan dikasih ngundang mbak-mbak."
"Ah masa? Nikahannya Halimun dulu gede-gedean."
Teh Winna kena sikut Mbak Arum.
Iyalah ... Mbak Halimun nikahnya mewah, dapat orang PLN. Termasuk nikahan paling mewah buat ukuran orang yang tinggal di gang belakang Malioboro. Bapak nanggap wayang kulit segala. Prosesi pernikahan Jawa lengkap dua hari dua malam. Bahkan, bapak secara spesifik bilang ke aku, tunggu dua tiga tahun lagi, ya, Nduk. Jangan buru-buru. Biar bapak napas dulu, ngumpulin duit lagi. Nggak ada setahun, aku malah kayak gini.
Manalah Yudha nggak jelas kerjaannya.
Ya iya dia usaha sama papanya, tapi aku tahu betapa konvensionalnya bunda. Buat bunda, nyari nafkah tuh ya jadi PNS, kerja di BUMN, atau yah pokoknya ngantor lah meskipun di perusahaan swasta. Gaji urusan belakangan. Bapak mungkin lebih terbuka pikirannya kalau soal beginian, dia malah suka kalau ada pemuda yang mau wiraswasta. Masalahnya ... bapak mana yang bakal terima kalau punya besan waria?
***
Bapak
"Pulang kenapa?" tanya bapak di telepon.
Kuputuskan begitu, telepon dulu. Paling enggak, supaya kagetnya nggak dobel-dobel. Bapak nggak suka kejutan, apalagi kalau kejutannya nggak menyenangkan. Beliau lebih suka dikasih tahu dulu kalau anaknya mau pulang, nggak ujug-ujug. Soalnya, biasanya dia suka meluangkan waktu di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana supaya bisa nanggap cerita anak-anaknya. Nah kalau kami datang pas dia sibuk, dia kesal.
"Ya Rani dapet cuti," kataku.
Di sampingku ada Yudha, meremas jemariku, menguatkanku. Kalau udah begini, rasanya itu nggak berarti banyak. Telapak tanganku basah, sekujur tubuhku panas dingin. Padahal ya nggak berencana ngomong apa-apa dulu.
"Kamu bawain oleh-oleh apa buat bapak?" tanya bapak, khas. Orang tuaku yang satu ini memang suka minta dibawa-bawain. Seneng dia. Kalau kebanyakan bapak lain akan bilang yang penting kamu pulang, selamat, bapak udah senang. Bapakku sih cemberut kalau nggak dibawain apa-apa. Katanya, kayak nggak perhatian.
"Bapak maunya apa?"
"Yang manis-manis."
"Yang spesifik, dong. Manis-manis kan banyak."
Terdengar bunda menyahut, "Mau dimasakin apa, Nduk?"
"Apa aja, Bun," jawabku, bapak meneruskannya ke bunda. "Rani bawa temen, Pak."
"Nggak usah," decap bapak.
"Lho kok nggak usah? Orang Rani nggak nawarin, ngasih tahu."
"Temenmu yang mana? Yang tiga orang itu? Berisik, suruh tidur losmen aja. Kalau pulang malem bikin was-was. Kamu lak di sana nggak kelayapan sampe malem, toh?"
"Mboten dong, Pak."
"Jangan lupa salatnya, begitu bedug tuh langsung ambil wudlu."
"Iya."
"Nanti pulang jangan lupa bawa mukena."
"Kan di sana ada."
"Cek dulu sama bundamu, dicuciin nggak mukenamu yang di sini."
"Ya udah ... Rani bawa mukena!"
"Naik apa?"
"Pesawat."
Bapak nggak menyahut, nggak biasanya aku naik-naik pesawat segala macem. "Naik kereta aja," dia bilang.
"Kan biar cepet nyampe, Pak."
"Emang buru-buru?"
"Ya enggak ...."
"Kenapa mesti cepet nyampe?"
"Biar nggak capek."
"Naik kereta juga bisa tidur."
"Ya udah sih orang Rani pengin naik pesawat."
"Alaaah ... nggaya ...."
Aku tersenyum simpul. Obrolan dengan bapak selalu gini, random.
"Kamu balikan sama mantanmu, Nduk? Lak enggak, to?"
Tuh, kan, pasti curiga. Soalnya dulu aku memang sering pulang karena punya pacar di sana. Dikiranya aku balikan. Aku melirik Yudha yang mukanya langsung berubah begitu topik pembicaraan bapak menikung curam.
"Enggak. Kenapa? Dia ke rumah lagi?"
"Enggak," pendek bapak. "Nggak usah buru-buru punya pacar, nyantai aja."
Serempak, aku dan Yudha saling pandang. Mukanya pucat, aku yakin mukaku juga.
"Bapak habis beli tanah," beritahunya, aku bisa membayangkan dadanya membusung. "Ya belum deal, sih. Baru ngomong-ngomong aja. Dua tahun lagi kalau dijual, harganya bisa beberapa kali lipat. Pas buat kamu kawinan."
Napasku memberat.
"Nyari calon suami yang setiti, Nduk. Jangan gegabah. Nggak harus kerja di PLN, yang penting tanggung jawab, setia, jangan grusa-grusu. Inget nih rumus bapak, laki-laki kalau kebanyakan alesan kayak mantanmu itu, kebanyakan asu semua. Kalau dia berani datang ke rumah lagi, bapak tempeleng mukanya."
Yudha menahan mulut supaya tawanya nggak pecah. Aslinya, bapak nggak beneran segarang itu. Lebih tepatnya, bapak nggak mau ikut campur karena dia belum jadi siapa-siapaku. Kayak nggak selevel gitu lho kesannya. Kecuali dia suamiku, terus selingkuh, wah ... bisa digoreng garing kayak ayam pejantan kesukaannya.
"Kalaupun Rani punya calon, kawinannya nggak usah kayak Mbak Halimun nggak apa-apa, kok, Pak," kataku hati-hati, mencoba memberi petunjuk. "Rani kan bukan anak sulung."
"Oh nggak bisa, bapak harus adil. Mbakmu nanggap wayang, kamu juga. Kintamani baru masuk kuliah, paling masih lima sampai enam tahun lagi kawinnya, bapak masih punya waktu buat leha-leha. Umurmu berapa sekarang?"
"Dua empat."
"Belum usia kawin."
"Bapak nikah usia dua empat."
"Itu dulu."
"Apa bedanya dulu sama sekarang?"
Jeda. Lalu, "Hayooo ... kamu udah punya pacar?"
Siapa bilang laki-laki nggak peka?
"Udah ada pandangan," kataku.
"Yang besok mau diajak?"
Aku diam.
"Siapa namanya?"
"Yudha."
"Kerja di mana?"
Mataku memejam, Yudha meremas tanganku erat, tapi juga lembut menenangkan. Bismillah, "Punya toko."
Bapak diam lumayan lama. "Toko apa? Bangunan?" tebaknya.
Aku tahu kenapa bapak nebak toko bangunan, sebab manly, dan cocok dengan image pria di kepalanya. Belum kujawab, bapak udah nyerocos lagi, "Cina?" Terus buru-buru ditambahkanya, "Bukannya bapak rasis, lho, ini. Biasanya yang punya toko bangunan kan orang Cina. Kayak Koh Ahong itu seberang jalan. Cina juga nggak apa-apa. Tapi muslim, kan?"
"Muslim, tapi bukan Cina juga."
"Lha kok punya toko bangunan?"
Ya Allah ... siapa coba yang ngomong toko bangunan. Aku hanya bisa mendesah, panjaaang, kehabisan energi meladeni imajinasi bapak.
Denger desahanku, bapak malah ketawa, "Punya toko bangunan juga enggak apa-apa, yang penting jelas."
"Jelas gimana?"
"Jelas berpenghasilan."
Aku ingin menjelaskan lebih lanjut, tapi Yudha menahanku bicara, maksudnya supaya membiarkan bapak berpikir sesukanya dulu.
"Nduk ...."
"Njih, bapak?"
"Lak belum mau kawin, to?"
"Kalau itu terserah bapak nanti."
"Lho kok terserah bapak, bapak kan cuma nyiapin uang sama restu. Kamu yang nggenah, lho. Kalau udah mantep, ya nanti bapak usahain gimana caranya."
Duh ... bapak .... Aku pengin nangis.
"Ya sudah, bapak tunggu besok."
Lalu hening, aku nggak tahu gimana memutus pembicaraan.
"Nduk ...," panggilnya. "Ya udah. Naik pesawat aja. Biar cepet nyampe."

Yudha
"Kayaknya aku bakal suka bapakmu, dia lucu."
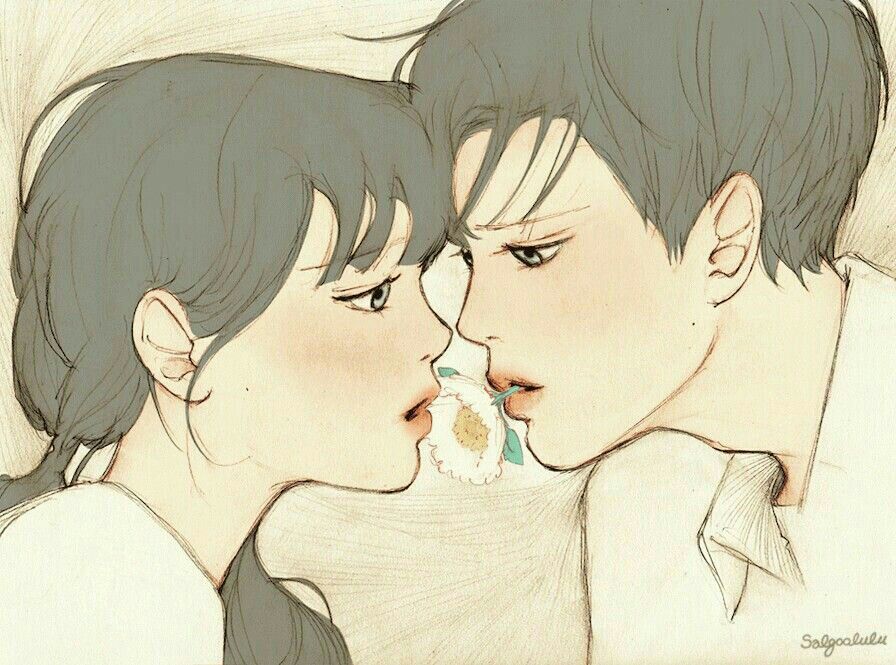
Maharani
"Oh nggak selucu bapakmu!"
Lima hari lagi Yudha bakal jalan-jalan ke Jogja, nih, ketemu bapak dan bunda.
Kalau yang ada di benak kalian bapaknya Rani ini kayak siapa? Ada nggak yang bapaknya agak nyentrik kayak bapaknya Rani gitu? Mungkin banyak, ya? Bapak tuh kalau udah tua biasanya jadi suka lucu nggak, sih? Papah saya mudanya dulu serem, sekarang masih suka serem sih, tapi udah mulai manja dan aneh-aneh. When I was younger, I've never thought I'd laugh with my father. Treasure your parents, spend your time with them.
Send my regards to your great parents at home!
Kin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top