27. Gerimis dan Optimis
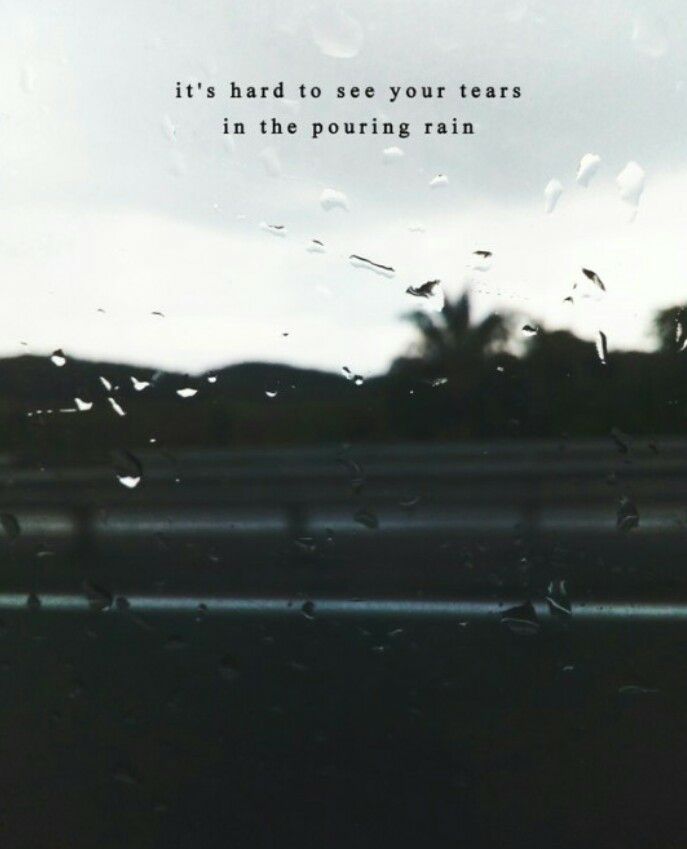
Gelap. Caca terus berlari menyusuri lorong yang seakan tak berujung. Peluh membanjiri wajah dan seluruh tubuh. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya seakan memantul ke telinganya sendiri. Tidak ada siapa pun dan apa pun. Hanya ada gelap. Caca berlari lagi, tak peduli meski akan kehabisan napas. Namun, baru beberapa langkah, ia tersandung.
Tangannya meraba-raba, entah mencari apa. Sementara hati mendadak terasa pilu. Caca ingin keluar dari sini. Ia ingin melihat langit, awan, pelangi, dan matahari. Ia benci kesendirian, juga gelap. Ketika hampir terisak meremas permukaan tanah, secercah cahaya muncul. Setelah melihat tangan mulusnya yang kotor, ia mendongak cepat. Cahaya itu semakin melebar, memenuhi pupil matanya.
"Kak Fella?"
Perempuan berambut sebahu yang berdiri tepat di depannya memamerkan deretan gigi. "Hai, cantik."
Caca menyambut uluran tangan kakaknya tanpa ragu. "Kakak kok di sini?"
"Kamu yang ngapain di sini, Ca?" Setelah itu Fella tertawa kecil sambil menggeleng-geleng pelan.
"Enggak tahu juga, Kak," jawabnya lirih. Pandangannya jatuh pada rerumputan hijau di bawah kaki mereka. "Tadi tuh gelap banget. Aku takut."
"Ya udah enggak usah dipikirin dulu." Fella menyipitkan mata, memandangi sekeliling. "Eh, kita duduk di sana, yuk?" Perempuan itu menunjuk sepasang ayunan besi.
Caca mengangguk dan mengikuti Fella yang menggandeng tangannya. Semua pemandangan di sini terasa asing. Gaun putih yang ia kenakan pun terasa aneh, seperti bukan miliknya. Mawar putih di belakang ayunan sangat cantik untuk dipetik, tapi ia memilih menduduki salah satu ayunan. Hening, tanpa detik. Tak ada siapa pun kecuali mereka berdua. Entah kicauan burung, gemericik air, atau dedaunan yang bergesek. Tidak ada embusan angin, hanya ada awan yang berarak.
"Kak, aku kangen sama Kakak." Entah kenapa rongga dadanya terasa sangat lega. Kalimat barusan telah lama tertahan di bibirnya.
Fella tertawa kecil. "Aku selalu ada di samping kamu, Ca." Mereka saling berpandangan sesaat, kemudian Fella menarik senyum lebar. "Kehilangan apa yang berat menurut kamu, Ca?"
"Kehilangan Kakak." Caca menjawab begitu saja tanpa pikir panjang.
Fella memandang hamparan langit biru. Ia mulai mengayun pelan, rambutnya bergerak lembut. "Don't leave him. Jangan jadikan kakak sebagai alasan kamu enggak bisa bahagia, ya? Kita punya cerita masing-masing, Ca."
Kening Caca berkerut samar. "Aku enggak ngerti, Kak."
"Nanti kamu ngerti, Dek." Fella mengusap bahunya sekilas, kemudian berdiri. "Kakak mau pulang, ya?"
Caca menahan tangan Fella dengan raut cemas. "Ayo pulang bareng, Kak."
Fella menggeleng. "Enggak bisa, Dek. Arah kita berbeda."
Cekalan Caca terlepas tiba-tiba. Jeda satu tarikan napas, punggung Fella menjauh sekian belas meter. Jauh, semakin jauh. Gadis itu tak menoleh sesudah Caca meneriakkan namanya berkali-kali. Fella lenyap secepat hujan turun membasahi bumi, digantikan oleh cahaya yang menyilaukan netranya. Mimpi panjangnya berakhir.
"Bun ...," panggilnya lirih. Perih karena sayatan di perutnya mulai terasa. Sementara dingin mulai menjalar ke seluruh tubuh.
"Bunda lagi keluar sebentar, kamu butuh apa?"
Pertanyaan itu diakhiri usapan lembut di kepalanya. Caca menoleh ke asal suara yang familier. Ya, suara yang belakangan ini sangat ingin ia dengar.
"Kamu di sini?" tanya Caca dengan terbata.
Laki-laki itu hanya diam menatapnya tanpa jeda. Caca belum bercerita tentang hubungan mereka yang mandek pada Bunda. Ia masih berharap mereka akan tetap berlanjut. Mungkin Ayah atau Bunda yang mengabari laki-laki itu.
"Dingin, aku mau selimut." Caca mengalihkan titik pandangan. Ia paling tidak menyukai tatapan belas kasihan, seperti yang terlihat dari mata Dio detik ini.
"Tunggu sebentar, ya."
Caca mengangguk kecil, selang yang terpasang di hidung sebelah kiri sampai ke lambung itu membuatnya sulit bicara. Jangan tanya seberapa sakitnya saat dokter memasangkan alat sialan itu. Selang tersebut berguna untuk mengecek perkembangan warna cairan lambung. Tak lama, Dio membentangkan bedcover hingga sebatas leher. Gerakan laki-laki itu selembut kepakan sayap kupu-kupu. Seolah Caca adalah hal paling rapuh.
"Gimana?" tanya laki-laki setelah duduk di samping brankarnya.
"Lumayan. Makasih ya, Kak."
Dio tersenyum tipis dan hening kembali merenggut mereka. Ada banyak hal yang ingin ia sampaikan, tapi mulutnya terkunci rapat. Tidak masalah, berada di samping Caca tanpa sebuah penolakan saja sudah cukup. Aneh melihat gadis itu di sini. Sesuatu menghantam telak jantungnya ketika melihat suster menggeret brankar gadis itu menuju ruang pemulihan. Dio sulit memercayai bahwa yang terbaring dalam keadaan tidak berdaya dan terpasang banyak selang adalah Oxafia Djenara Nindyar. Ia ingin bertukar posisi dengan Caca, kalau bisa.
"Ca ... aku boleh pegang tangan kamu?"
Pandangan mereka bersirobok. Degup jantung Caca tak pernah berubah untuk laki-laki itu. Rindunya pun masih milik laki-laki itu.
Dio Anggara, kamu ngapain nanya sih? bisik Caca dalam hati.
"Sebentar aja, Ca."
"Harus aku jawab ya, Kak? Aku susah ngomong."
"Maaf." Laki-laki itu malah menunduk, tatapannya kosong. "Aku minta maaf."
Kenapa Dio harus seperti itu? Kenapa juga matanya sekarang memanas? Caca menelan ludah.
"Kak Dio, hold my hand. Please ...."
Caca berkata lirih dengan suara sedikit serak. Namun, pandangannya tertambat pada langit-langit kamar. Tanpa sadar sudut matanya basah. Genggaman Dio masih sehangat kemarin dan ia rindu. Detik ini, biarkan ia menganggap hubungan dan percakapan mereka tidak pernah mandek sebelumnya.
***
Dio memasangkan sepasang sandal hotel di kaki Caca. Gadis itu duduk di pinggir brankar memegang tiang infus. Hari ini Caca ingin belajar berjalan di sekitar kamar supaya lekas pulih. Selang yang terpasang sudah berkurang, tersisa infus dan drain saja. Zenar dan Nadia biasa meninggalkan mereka berdua ketika ia berkunjung.
"Kamu baru operasi dua hari yang lalu. Kamu yakin?" tanya Dio sekali lagi.
Gadis itu mengangguk bersama senyum hangat, lalu Dio memegangi kedua bahunya saat hendak turun dari brankar.
"Lihat, aku bisa kan?" Caca merentangkan kedua tangan.
"Kamu hebat."
Mereka berjalan sebanyak satu putaran. Selama itu Dio yang memegangi kedua bahunya dan sesekali meringis melihat darah naik ke selang infus. Ia malah tak mengkhawatirkan hal itu. Selangnya hanya perlu dijepit sebentar lalu disentil hingga cairan infus kembali mengalir. Hujan yang turun di luar sana tidak begitu deras, tanpa petir juga. Setiap titik-titik hujan yang membekas pada jendela membuat caca memilih berhenti. Mereka berdiri di depan jendela besar yang menampilkan pemandangan jalanan serta gedung-gedung pencakar langit.
"Lucu, aku pernah nanya tentang selamanya sama Kak Dio. Sebenarnya justru aku yang paling enggak percaya sama kata itu. Ini operasi keduaku. Aku mengulang fase yang sama di lain masa. Aku tahu, aku bukan mengalami sakit yang separah pengidap kanker, tapi—" Pandangannya lurus, seolah sedang menyelami diri sendiri lewat pantulan kaca. "Aku tetap selalu merasa sedekat itu dengan kematian. Dokter bilang prosentasenya tujuh puluh lima dan dua puluh lima persen."
"Tujuh puluh ...." Dio hendak memberi motivasi pada gadis itu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tetapi gadis itu menjedanya.
"Iya, aku tahu tujuh puluh lima persen jelas lebih besar dan aku harus percaya itu." Kali ini gadis itu menatapnya secara langsung. "Aku benci rumah sakit, brankar, meja operasi. Semuanya."
Dio lebih memilih mendengarkan ocehan Caca tanpa menjeda lagi. Ia tidak pernah merasakan apa yang Caca rasakan, tidak bisa berpendapat lebih selain meyakinkan gadis yang tengah demotivasi itu. Dio ingin memeluk gadis itu, tapi ia tidak mungkin melakukannya. Pertama, karena kata break sialan kemarin. Kedua, selang yang masih menempel membuatnya lebih takut membuat gadis itu kesakitan.
"Aku enggak tahu apa aku bisa lanjut kuliah sampai lulus. Bekerja, menikah, dan punya anak. Terkadang aku sering bertanya, God why must me. Habis itu aku cuma bisa diam sampai dapat jawaban, why not dari hati kecilku sendiri." Bulir bening di pelupuk mata membuat pandangannya kabur saat ini.
"Bukan, maksud yang benar itu, Tuhan tahu kamu sanggup. Tuhan tahu kamu kuat." Dio memegang bahu yang sangat rapuh itu. "Kamu akan sembuh total. Lulus kuliah, bekerja, menikah dan punya anak."
"Gimana kalau ternyata aku ada di dua puluh lima persen?"
Detik ini Dio tidak menyukai apa yang terpancar dari mata Caca. Padahal binar di mata gadis itu adalah salah satu favoritnya. Saat gadis itu berbalik, ia tidak tahan untuk tidak mengecup dahinya cukup lama.
"Tuhan menyayangi kamu, lebih dari kamu menyayangidiri kamu sendiri," ujar Dio yang membenamkan hidungnya di helaian rambut Caca.Ia tidak peduli dengan harum shampoo yangberganti bau antiseptik. "Kamu harus percaya itu, Ca."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top