Babak 2. Bruma (5. Lentera)
.
.
.
.
BABAK 2: BRUMA
Bruma―nama sebuah desa (milik Kaum Putih)
Diambil dari Arumdalu, kitab peradaban manusia sebelum manusia terbagi menjadi dua kubu bertentangan. Bruma berarti 'batu giok'.
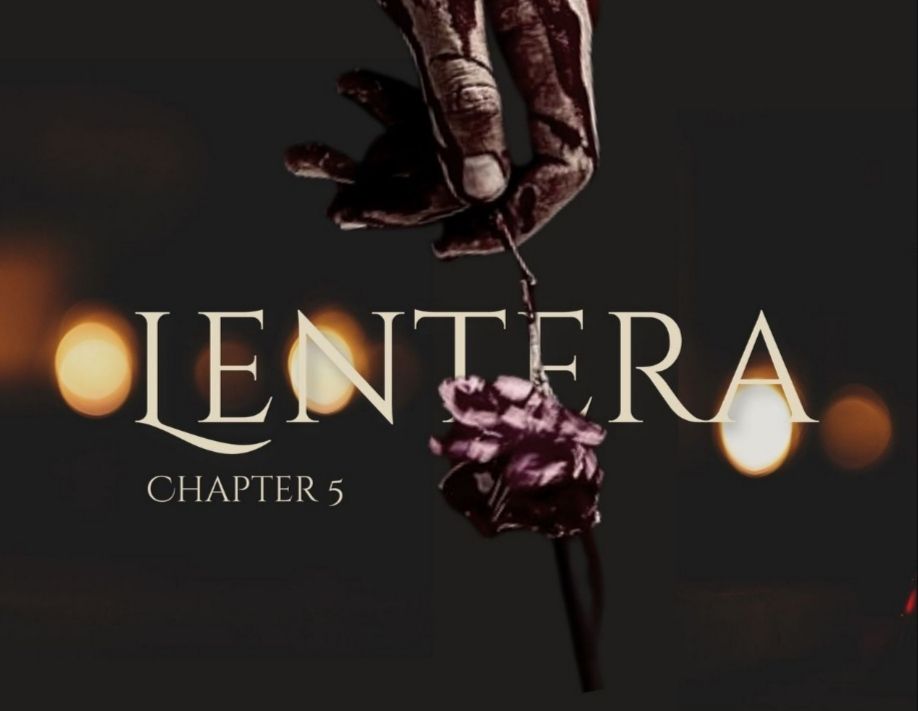
-oOo-
5. Lentera
SELURUH dunia sejenak terasa berhenti, dan kakiku seakan dipaku di tanah ketika peluru itu melesak di punggung Heera.
Adikku mengeluarkan suara seperti tercekik, dan kengerian tidak berhenti sampai situ. Setidaknya, setelah aku merasakan peluru mengoyak menembus punggungnya dan pecahannya menusuk dadaku, takdir kami memantul-mantul dalam kepalaku, membisukanku, membunuhku.
Aku limbung ke belakang, tepat ketika salah seorang sraden menaikkan moncong senjatanya, membidik kepalaku.
Keparat, adalah umpatan terakhir yang kuludahkan padanya saat aku memutuskan untuk roboh ke belakang. Tumitku kumundurkan hingga melewati tepian tebing, dan akhirnya tubuhku jatuh menghantam air.
Semuanya telah usai, begitulah pikirku ketika kami ditelan oleh kedalaman pekat. Dunia ini berubah menjadi kekosongan, tanpa gravitasi, tanpa kebisingan. Cahaya menembus masuk melalui permukaan air. Seiring tubuh kami turun ke pusat bumi, kehangatan itu hilang dan tergantikan dengan rasa dingin yang membekukan. Heera, Heera adikku. Dia melayang di atasku, dan matanya yang penuh kesakitan mengedip samar. Sekonyong-konyong, aku dibangunkan oleh kenyataan.
Napasku menyembur berupa gelembung-gelembung air, dan aku menendang-nendang agar bisa keluar ke permukaan. Kusambar tubuh mungil Heera, sementara aku menukik naik, setengah menyelam, setengah membiarkan tubuhku ditarik arus air. Heera masih hidup, pekikku dalam hati―setengah ragu, setengah lega. Dalam kegelapan yang terimbas cahaya lemah aku hanya bisa melihat air di sekitar kami berubah keruh―ternoda darah.
Bisakah dia bertahan?
-oOo-
Kami muncul di permukaan yang cukup jauh dari kejaran para sraden. Aku menggendong Heera melewati batu-batuan ke tepi sungai dan merebahkannya di rerumputan yang bercampur lumpur. Ekspresinya, ekspresinya saat itu adalah hal paling mengkhawatirkan yang pernah kulihat pada wajah adikku. Matanya setengah terbuka, dan kosong. Kurebahkan kepalaku di dadanya. Tidak terdengar denyut jantung.
"Heera, tidak, jangan meninggalkanku―"
Kulakukan segala cara untuk menolongnya. Aku pernah membaca dalam sebuah buku, metode untuk menolong orang yang tenggelam adalah dengan menekan dadanya sampai dia memuntahkan air, tetapi Heera tidak menunjukkan tanda-tanda sadar. Aku memakai cara kedua, yaitu memberinya napas buatan, tetapi dia masih tergolek lemas. Lubang akibat tembakan yang menembus dari punggung ke dadanya jauh lebih memprihatinkan, dan aku tahu luka itu di luar kuasaku untuk menyembuhkannya. Aku berjongkok di hadapannya, memandang pakaiannya yang berlumuran darah tanpa bisa berbuat apa-apa. Tanganku terulur mengangkat tubuhnya dan kupeluk dia di dadaku.
Selama beberapa saat, aku duduk di sana sambil merengkuh Heera. Tubuhku berayun depan dan belakang, sementara air mata melelehi wajahku entah sejak kapan. Hanya dia yang kupunya, dan bila kepergiannya adalah sesuatu yang harus kupasrahkan, aku tidak tahu apakah aku masih sanggup bertahan untuk hidup tanpa tali harapan yang memegangku. Aku tidak mau jatuh pada lubang yang dalam, sunyi, tanpa kehadirannya.
"Heera, kumohon." Tubuhnya terkulai di pelukanku bagai boneka. Darahnya masih terus mengalir dan kini ikut membasahi pakaianku. Beberapa menit lalu Heera masih ada di sini, bersamaku. Sekarang, kepergiannya melemparku telak.
Angin berembus, daun-daun berkeresak, dan nyawanya tersapu pergi bersama debu-debu yang hilang. Heera-ku, adik kecilku.
Kutundukkan kepalaku untuk mencium keningnya.
-oOo-
Lusa adikku berusia delapan tahun, tetapi hari ini dia meninggalkan dunia.
Heera kukuburkan jauh dari tepi sungai di tanah yang tersembunyi di balik semak-semak, yang semata-mata kulakukan demi menghindari penyelidikan sraden yang masih memburu kami.
Aku tidak bisa berhenti memandanginya. Dia seperti tupai kecil yang tak berdaya. Ketika tubuhnya kubaringkan di kedalaman tanah, tangisanku meledak. Aku membiarkannya tumpah bersama rasa sakit hati karena ditinggal mati keluargaku. Aku membiarkan hatiku hancur bersama memori masa lalu yang mewarnai jenazah seluruh anggota keluargaku. Tubuhku berguncang dan aku tidak bisa menahan gemetar ketika serpihan tanah kujatuhkan, menutupi wajah Heera, menutup tubuhnya seutuhnya. Dengan ini, kami benar-benar berpisah.
Kupetik bunga-bunga liar yang tumbuh di akar pohon, dan kuwarnai makamnya dengan aneka rupa bunga. Walau kepergian Heera adalah selamanya, aku berusaha membuat momen terakhir kami lebih bermakna dengan cara paling sederhana yang bisa kulakukan. Kubayangkan Heera seperti berbaring di sana, tertidur dan terbuai dalam mimpi kanak-kanaknya yang terputus. Aku menancapkan batu berukuran genggaman tangan di puncak makam sebagai nisannya.
Kematian Ibu dan Heera menajamkan rasa benciku pada Kaum Putih, ketidakadilan yang kami alami, kecurangan, pembodohan masal. Segala hal yang berkaitan dengan kebijakan keji mereka mengelupas jati diriku yang lemah dan tidak berguna. Tiba-tiba, hanya dengan memikirkan arti keberadaan Heera, aku kembali kuat.
Aku mungkin bisa membalas dendam pada mereka.
Semenjak hari itu, gelora ketakutan dan kepanikan yang kupelihara di balik kulitku hilang, sekeping demi sekeping, dan aku hampir tidak memedulikan kakiku yang melepuh karena berjalan melintasi hutan tanpa alas kaki. Sepatu dan sisa makanan yang kubawa sebelumnya hilang terseret sungai ketika aku menceburkan diri. Dan, setiap kali kakiku melangkah, beban di pikiranku menguat, pemikiran-pemikiran balas dendam yang paling payah sampai yang paling berani mulai kurancang, tetapi aku masih tumpul oleh rencanaku selanjutnya. Apakah aku bisa membalas dendam kepada Kaum Putih? Dengan cara seperti apa?
Karena kelelahan, kurang makan, dan digaungi oleh bayang-bayang kematian keluargaku, kepalaku kembali sakit. Pada suatu malam, ketika aku berbaring menempel di dinding gua sempit dan memaksakan diri untuk tidur, aku bermimpi buruk.
Mimpi-mimpi mendatangiku bagai hantu. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, tetapi bayangan hitam datang memenuhi pikiranku, seperti monster dalam dongeng yang siap mencakar fisik dan hatiku. Digilas oleh kilasan aneh yang tak kukenal, rasa sakit hati dan duka membara dalam kepalaku bagai dijilat oleh api. Dalam mimpi itu, aku melihat Ibu memunggungiku, sedang duduk di meja makan reyot rumah kami sambil mengupas umbi sayur hasil jatah. Aku mendekatinya, memegang bahunya.
"Kita gagal," katanya tanpa mau repot-repot berpaling padaku. "Kita sudah gagal."
"Ibu."
"Heera pergi." Dia melanjutkan, lalu umbi-umbian di tangannya tahu-tahu berganti menjadi sosok bayi kecil yang diselimuti kain putih. Ibu menggendong bayi itu dengan rapuh di dadanya, "Heera-ku pergi," ulangnya, sementara suaranya mulai berubah menjadi nada-nada melengking yang mengerikan. Ini tidak nyata, aku mengingatkan diriku sendiri. Tidak nyata.
"Gara-gara kau!" bentaknya padaku. "Kau tidak menolongnya!"
"Tidak."
"Kau bohong, River."
Ibu berdiri, berbalik padaku. Seluruh tubuhnya basah seperti habis tercebur ke kolam, dan kini matanya melotot padaku, sepekat nafsu ingin membunuh. "Kau membuatku kecewa."
Kutatap ke dalam matanya yang cekung dan kesakitan.
"Tidak, Bu." Aku merapatkan rahang. "Aku tidak sengaja."
-oOo-
Keesokannya, aku terbangun dengan telapak tangan basah serta serangan rasa bersalah di dada.
Di luar, langit sudah kembali pagi, dan cahaya kabut samar-samar terpapar pada kulitku yang berkeringat dingin. Tubuhku meriang dan kepalaku pusing. Aku membuka kemeja bagian atas yang melapisi dadaku, mengelupas secarik kain dari potongan pakaian Heera yang kutempelkan di sana. Di baliknya, ada borok luka basah akibat pecahan peluru yang bersarang di dekat ketiak kananku―tertanam cukup dalam, dan aku tidak tahu mengapa aku masih bisa hidup. Barangkali rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan duka yang kurasakan, sehingga aku tidak begitu memikirkannya. Walau begitu tetap saja, karena tidak ada sekaliber obat-obatan yang kubawa kemari, aku tidak berani mencongkel peluru itu sendiri. Risikonya lebih besar. Aku mungkin bisa mati kehabisan darah.
Aku merangkak keluar dari gua dengan pelan, karena setiap gerakan membuat ngilu otot-otot tubuhku. Lalu, seperti biasa―sambil melakukan perjalanan―mencari-cari buah-buahan liar atau jamur yang bisa kumakan. Harus hati-hati dalam memilih karena bisa saja makanan yang kucari beracun. Keluargaku pernah merasakannya. Terjadi beberapa tahun lalu, saat aku mengais makanan di dekat perbatasan hutan, kutemukan jamur payung kecil yang tumbuh menempel di dasar batu. Ibu memasaknya untuk kami, dan pada sore harinya kami semua muntah-muntah.
Sepanjang perjalanan, aku membayangkan kembali kehidupanku di masa lalu. Kevra yang kumuh dan bau kini terasa bagai tempat yang kurindukan. Aku mengingat atap-atap bolong rumahku, keran pancuran yang mengalirkan air bersih dan disesaki oleh antrean tiap pagi, ruang tidur kami di rumah yang dilapisi karpet tipis dan berkutu. Segalanya kini meredup samar dalam dekapanku, meninggalkanku sendirian dalam kubangan hampa ini.
Pada hari kedua, Ibu kembali mengambil peran dalam mimpiku, dia memandangiku dengan tampang seperti wanita lemah yang mengalami histeria. Aku masih ingat pesannya padaku sebelum meninggal, yang bahkan juga terselip dalam lapisan mimpiku malam itu; Kembali dan Miron.
Kembali ke Miron.
Satu pesan itu membangunkan diriku seperti sengatan lebah. Kenyataan yang sejak dulu terkelupas dari benakku. Benar. Ibu menyuruhku pergi ke Miron. Di mana tempat itu? Apakah itu adalah nama suatu wilayah di Rawata? Apakah itu adalah nama sebuah desa atau pemukiman? Keluargaku tidak punya peta, tetapi entah bagaimana penyelidikanku mengucur pada kesimpulan bahwa Ibu menyuruhku pergi ke Rawata untuk mencari tahu tentang lokasi bernama Miron. Fakta ini entah bagaimana memunculkan kembali semangatku, walau aku tidak tahu bagaimana caranya bisa berada di sana tanpa tertangkap. Kurasa kini tujuanku adalah pergi ke balik gunung terlebih dulu.
Setelah lama mengitari hutan―yang bisa kupastikan perjalanan sepanjang dua hari meninggalkan Kevra, rute yang kulewati menjadi menyempit, pohon-pohon mulai jarang, dan malam harinya, aku menemukan pemukiman di dekat kaki gunung.
Aku perlu menyipitkan mata untuk memastikan tentang apa yang kulihat: Perkampungan.
Tempat itu berada di ujung perbatasan hutan, dalam barisan pondok-pondok kecil dan sumur serta area luas seperti ladang yang letaknya lebih jauh lagi. Lentera-lentera yang benderang digantung di pasak kayu sehingga aku bisa melihat dengan begitu jelas. Asap pembakaran yang tercium membuat cuping hidungku mengerut. Perutku keroncongan, kakiku gemetar menahan sakit akibat kulit yang melepuh, sementara luka di dadaku berkembang menjadi radang menyakitkan sebagai sumber demam yang kualami. Aku berdiri di dekat bantaran parit sempit, merosot pelan-pelan ke bawah untuk mengistirahatkan tubuh yang menolak berjalan selangkah lagi. Dari sini, mereka tidak bisa melihatku, sebab aku meringkuk dan bersandar di pohon yang tertutupi ilalang tinggi. Walau begitu, aku bersyukur tersembunyi seperti ini, sebab pemukiman yang kutemukan masuk dalam daftar tempat yang berbahaya bila dikunjungi tanpa persiapan.
Pemukiman penduduk Kaum Putih.
Perutku dililit dengan perasaan cemas, kelaparan, dan rasa takut terancam, sehingga aku perlu menekannya dengan tangan untuk mengurangi rasa sakit. Aku tidak bisa minta bantuan ke perkampungan itu. Mereka bisa membunuhku atau mungkin melaporkanku pada sraden karena melihat rambut dan mataku yang berwarna hitam. Berputar jalan juga bukan keputusan bijak, karena sesuatu dalam diriku berkata bahwa aku harus bertanya tentang letak Miron ke mereka. Tapi, dengan cara apa aku harus ke sana?
Sementara itu, pemandangan di hadapanku berubah menjadi sesuatu yang kutakutkan. Aku melihat dua orang―perempuan dan seorang gadis yang lebih muda, berjalan menghampiri tempat persembunyianku. Rambut mereka tampak bersinar dinaungi kegelapan malam, dan aku sudah menggenggam batu besar sebagai senjata yang bakal kupakai. Namun, rupanya kedua orang itu menuju gubuk yang terletak tidak begitu jauh dari tempatku beristirahat. Gubuk itu terbuka dan cukup terang, dan aku bisa melihat tumpukan jerami di dalamnya. Aku mengamati mereka, selama beberapa menit, sebelum keduanya keluar dari gubuk sambil membawa sebuah kotak kayu berukuran kecil. Aku tidak tahu apa yang mereka bawa, tetapi gubuk itu mengingatkanku pada lumbung makanan di Kevra. Apakah di sana ada sesuatu untuk dimakan?
Aku duduk, berpikir-pikir, nyaris terkantuk-kantuk. Konsentrasiku pecah karena demam dan aku mulai kehilangan kendali untuk tetap sadar.
Sementara perkampungan mulai larut dalam bayang-bayang kegelapan yang sunyi, aku meringkuk di bawah pohon seorang diri. Kedinginan, kelaparan, dan hampir pingsan. Lalu, suara gesekan sayap serangga mulai melarutkan dunia di sekelilingku. Aku tidak punya tenaga untuk sekadar menghalau barisan semut dan jangkrik yang mengitari kaki dan lengan, tapi aku punya keinginan lain yang ingin kutuju.
Kutatap lentera yang digantung di dekat pintu dan sinarnya memancar kuat, seolah memanggilku untuk datang.
Di dalam gubuk itu pasti jauh lebih hangat.
Lantas, aku memaksakan diri untuk bangkit, sedikit demi sedikit mendorong tubuhku ke atas. Terseok-seok menuju gubuk, aku hanya berharap tidak ada anjing atau hewan penjaga yang mengawasi di dalamnya. Dari jarak hanya beberapa meter, dinding kayu gubuk sempit itu retak-retak dan berlubang, tetapi di dalamnya sinarnya begitu hangat dan benderang. Aku melihat ruangan di dalamnya diisi oleh tumpukan kotak kayu, bersama timbunan jerami yang dibiarkan teronggok. Wajah kurusku tidak bisa menolak kemewahan itu.
Saat berada di dalamnya, aku sadar telah masuk ke sarang yang salah. Namun ketika menginjakkan kaki di ruangan sempit itu, tenagaku telah terkuras sampai habis sehingga tubuhku langsung roboh ke tumpukan jerami. Gerakan jatuh itu membuat dadaku nyeri, amat nyeri sehingga aku berpikir mungkin lukaku telah berubah menjadi racun yang membunuhku.
Sebagian diriku bertanya-tanya apakah aku akan mati di tempat ini. Dan jawabannya segera kutemukan ketika aku melihat titik-titik hitam mulai menyebar dari sudut mataku, mengambil alih seluruh penglihatanku.
Aku mungkin sungguhan mati, tapi kalaupun aku tidak mati di atas jerami, nasibku tetap akan berakhir di tangan para penduduk kampung ini.[]
-oOo-
.
.
.
Tebak apa yang terjadi selanjutnya:
A. River diselamatkan seseorang
B. River ditangkap seseorang
C. River sadar dan langsung kabur
Jangan lupa untuk vote dan/atau meninggalkan komentar. Tolong hargai penulis yaa gais 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top