9. Buronan
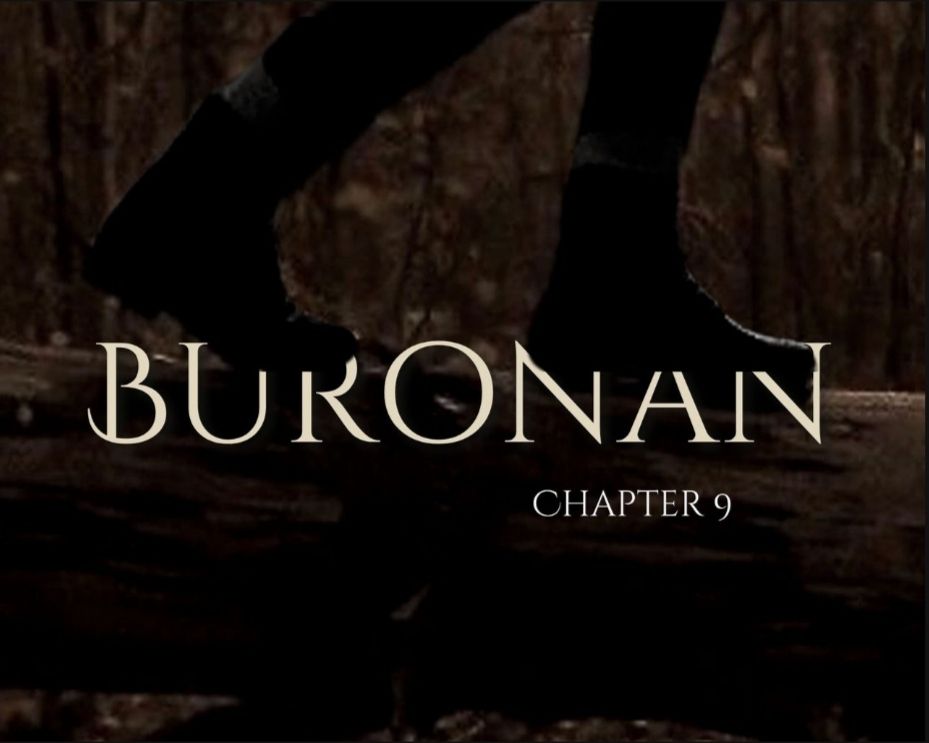
-oOo-
SETELAH mengetahui betapa banyak simpanan buku Ursa, hasratku untuk membaca buku semakin bertambah.
Di salah satu buku sejarah yang kupinjam, Kaum Liar dianggap sebagai minoritas budak, yang artinya mereka terlahir untuk melayani Kaum Putih. Mantan penguasa Rawata yang pertama memberlakukan upeti anak-anak delapan tahun sebagai caranya agar dikenal sebagai Raja murah hati yang membebaskan eksekusi Kaum Liar atas kesalahan kami yang dulu terlibat peperangan. Sungguh biadab dan tidak masuk akal. Apabila kami terbebas dari eksekusi mati dan malah diperintahkan untuk menjadi budak, bukankah itu tak ada bedanya dengan menghancurkan harapan kami sejak lahir?
Hal yang lebih ironis lagi, doktrin sejarah menyeramkan ini rupanya ditulis di buku-buku sekolah, sebagai cara yang kunilai sangat efektif untuk menanam pola pikir pada masyarakat bahwa Kaum Putih merupakan penguasa di muka bumi. Tidak heran, semua anak-anak dari golongan mereka terbiasa menindas kaum lain yang tidak setara, seperti keluargaku.
Malam sudah larut sementara emosiku yang belum stabil menggedor jantungku bagai jam yang berdetak mundur, menghitung seberapa banyak pelajaran yang bisa kutangkap sebelum keadaan ini menjungkirbalikkan diriku dalam kekacauan yang baru. Kututup buku dengan cepat, kemudian merangkak naik ke tempat tidur. Jendela pada sisi ranjang tidak ditutup tirai, sehingga langit gelap terlihat jelas menggantung di langit.
Pada keheningan itu, benakku bertarung dengan segala hal yang berkaitan dengan keanehanku. Tentang rambutku yang berubah warna, apakah aku dan Heera sebetulnya merupakan keturunan Kaum Putih? Apakah Ibu dan Ayah dulunya adalah Kaum Putih? Bila benar, mengapa keluarga kami dibuang di Kevra, dan mengapa rambutku dan Heera berwarna hitam sejak kecil?
Dan mengapa Ibu menyebut nama penguasa Rawata di saat terakhirnya?
Aku memikirkan semua itu sampai perlahan-lahan kesadaranku tergelincir.
Malam itu aku bermimpi banyak hal. Aku bermimpi bertemu dengan Aris dan adiknya, kemudian melihat Heera yang tersenyum sambil menggenggam tanganku. Suaranya lembut dan manis ketika mengajakku pergi ke perbatasan hutan untuk mencari telur burung.
Dulunya aku berpikir bahwa Kevra adalah tempat paling kumuh dan menjijikan yang tak ingin kutinggali lagi bila mendapat kesempatan keluar dari sana. Dan, semenjak aku kehilangan keluarga dan temanku, aku menjadi berpikir, bahwa yang kurindukan sebetulnya lebih dari tempat itu sendiri, melainkan orang-orang yang ada di dalamnya. Teman-teman dan keluargaku, yang seluruh kenangannya berharga lebih besar dari arti hidupku sendiri.
-oOo-
Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku terbangun. Benakku terlalu sibuk sehingga aku tidak bisa beristirahat pulas. Aku turun dari ranjang dan melihat pantulanku di cermin kamar mandi. Rambutku masih berwarna putih, bahkan kelihatannya lebih mengilat dan lebih sehat daripada kemarin.
Kucengkeram erat pinggiran tempat cuci muka sampai kuku-kuku jariku sakit, meredam kehampaan yang perlahan tumbuh menjadi rasa gelisah dan amarah. Tidak ada jawaban melegakan yang bisa membuatku sabar dengan situasi. Aku menarik napas dan membuangnya perlahan, berusaha tenang. Akhirnya, kuputuskan untuk mengubur semua rahasia ini sembari mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi, sepotong demi sepotong. Jalani saja. Aku tidak akan bisa memecahkan suatu masalah jika menyerah pada rasa takut, bukan?
Segera kucuci muka dan pergi ke dapur. Di sana, aku disambut oleh Tobi yang melonjak-lonjak sambil menggoyangkan buntutnya. Ursa yang sedang mengaduk isi panci mengatakan bahwa sepertinya Tobi menyukaiku. Dia hanya tidak tahu saja kalau di Kevra terkadang aku memakan daging anjing liar.
Alya datang sambil membawa sepiring berisi salad dan ikan tuna. Hidungku langsung kembang kempis ketika mencium aromanya yang enak. Aku duduk di meja makan sambil memegangi perut, takut kalau-kalau ususku jatuh karena memelototinya terus-menerus.
"Mau ikut ke sekolah?" tanya Alya tiba-tiba.
Aku menaikkan alis, terkejut dengan pertanyaannya. "Apa?"
"Aku mau mengajak Abang River ke sekolah."
Abang River....
Mendadak saja aku mengingat bagaimana Heera menyebutku. Aku menatap ke dalam mata Alya dan menemukan secercah kepolosan anak-anak di sana. Alya memiliki wajah mirip Ursa, kecuali rambutnya yang dipangkas hanya sebahu. Dia hanya sekitar dua tahun di atas Heera, tapi caranya memandangku terkesan dewasa dan berani. Apakah semua anak Kaum Putih memang tumbuh lebih cepat dari usianya, ataukah Heera yang masih terlalu kekanakan?
"Alya benar," Ursa menghampiri kami sambil membawa panci berisi sup. "Jalan-jalan ke luar bagus untuk pemulihan tubuhmu. Kita bisa ikut Alya. Sekalian temani aku ke pasar beli bahan makanan."
Keluar rumah bukanlah ide bagus selama diriku masih menjadi buronan sraden Kevra. Namun, sekarang rambutku berwarna putih. Tidak akan ada yang menyangka bahwa aku keturunan Kaum Liar.
Kutatap jendela yang mengirimkan berkas sinar kepucatan, dan membayangkan terpapar matahari mungkin bisa membuat badanku lebih pulih.
Tanpa pikir panjang, aku menyetujui ajakan kakak beradik ini.
-oOo-
Mataku menyipit tatkala bersentuhan langsung dengan paparan sinar yang menyengat. Alya, dengan langkah meloncat-loncat, menuruni undakan rumah. Pekarangan mereka diisi tanaman liar merambat, bersama bunga-bunga ungu dan merah yang menyembul di antara semak dan pot-pot. Ursa memastikanku berada di sampingnya. Katanya aku bisa tersesat kalau jelalatan terus.
Jalanan di perkampungan Bruma berliku dan dipenuhi batu-batuan. Jarak antar rumah begitu dekat. Beberapa hanya dipisahkan sumur dan semak-semak. Banyak orang melakukan aktivitasnya di luar rumah pada waktu pagi; Seorang gadis sebaya Ursa menjemur di pekarangan, Ursa juga menyapa seorang kakek yang menarik tali sumur, lalu ada segelintir anak kecil seusia Alya berlari di jalan yang diapit pepohonan sambil menopang tas-tas gemuk di punggung.
Tercium bau manis tajam buah-buahan yang matang dari atas pohon. Aku mendongak, mendapati buah berwarna kemerahan menggantung di atas sana. Di Kevra kami juga memiliki pohon jambu dan kesemek, tapi buahnya tidak sematang dan seranum ini. Buah kami kisut dan kebanyakan berasa hambar. Sembilan dari sepuluh pohon yang ditanam di rumah-rumah warga biasanya kena parasit dan penyakit. Kami tidak punya cukup uang untuk membeli pupuk dan alat perawatan tanaman. Kalaupun ada uang, kami pilih membeli beras atau minyak untuk masak.
Sekolah Alya merupakan bangunan dua lantai yang terbuat dari bata dan baja, tampak bersih dan kokoh bila dibandingkan gedung-gedung bangunan yang ada di Kevra, yang sebagian besarnya bahkan tidak pernah rampung dibangun karena para Dewan menilap dananya (begitulah kata para orang tua di Kevra yang senang bergosip). Ada banyak anak sebaya Alya―beberapa terlihat dua atau tiga tahun lebih tua―berlarian menuju gang setelah pintu masuk utama.
Alya yang semula ada di dekatku, segera memisahkan diri.
"Sampai jumpa!" katanya sambil melambai pada kami berdua. Dia berlari menjauh, masuk ke ruangannya.
Aku tak sempat melambaikan tangan untuknya, sebab seorang murid laki-laki tahu-tahu berlari dari belakangku. Lengannya tak sengaja menabrak bahuku. Aku berpaling ketika melihat seorang anak perempuan di dekatnya juga tersenggol, lalu jatuh ke lantai semen dengan keras.
"Jalan pakai mata!" si anak laki-laki membentak.
Si anak perempuan bangkit sambil menepuk-nepuk pakaiannya. Buku pelajarannya jatuh tercecer dari tasnya yang terbuka. Tak ada yang berniat menolongnya, sebagian besar murid yang melewati lorong itu hanya melihatnya dengan tatapan sinis. Namun, tubuhku bergerak tanpa disuruh―aku berjongkok untuk memunguti bukunya. Tatapan kami tak sengaja bertemu, dan saat itu kulihat warna matanya yang sehitam malam, sepertiku.
Untuk sekejap saja, dia tampak resah, lalu merebut buku-bukunya dari tanganku dan berlari pergi. Bocah laki-laki yang menyenggolnya hanya mengawasi anak perempuan itu dengan pandangan risi. Dia juga berpaling melihatku.
"Oh," katanya padaku, "satu lagi keturunan terkutuk yang tidak berguna. Lihat, dia tinggi sekali. Aku bertaruh dia tidak naik kelas enam kali!" Lalu anak itu merangkul bahu temannya yang juga tertawa mengejek. Mereka lantas berputar dan masuk ke pintu kelas yang terbuka.
Jantungku berdegup kencang, rasa panik mencakar bekas tembakan di dadaku sehingga untuk beberapa detik aku lupa caranya bernapas. Apa yang anak itu bilang? Keturunan terkutuk? Apakah dia tahu kalau aku dari Kaum Liar?
"Ayo kita kembali," Ursa tiba-tiba menepuk pundakku. Lekas kubuntuti Ursa menuruni undakan keluar ke muka halaman sekolah. Kami sudah setengah jalan ketika aku berhasil bertanya, "Mengapa dia memanggilku seperti itu?"
"Seperti apa?"
"Kau tadi dengar sendiri. Anak laki-laki itu memanggilku keturunan terkutuk."
Apakah aku, untuk suatu sebab, mirip Kaum Liar? Secara spontan aku menyentuh rambutku sendiri, menarik-narik helainya ke depan hingga aku bisa melihat poniku yang menjulur. Rambutku masih berwarna putih. Syukurlah.
"Itulah julukan yang mereka berikan pada Kaum Putih yang memiliki mata hitam," kata Ursa, ketika kami berbelok ke arah tikungan yang lebih sepi. "Kau lihat anak perempuan yang jatuh tadi, kan? Dia punya warna mata sepertimu, sudah nasibnya menjadi bulan-bulanan di sekolah."
"Bulan-bulanan?" ulangku. "Maksudmu, anak perempuan itu diganggu oleh teman-temannya karena warna matanya berbeda?"
"Karena mata hitam melambangkan ketiadaan kesaktian, dia diremehkan dan dikucilkan."
"Kalian menindas kaum kalian sendiri!"
"Bukan aku, tapi mereka." Lalu Ursa berhenti dan mendongak padaku. "Dan mengapa kau mengatakan hal itu seolah-olah kau sendiri bukanlah bagian dari Kaum Putih?"
"Oh, iya. Kan aku hilang ingatan. Hilang ingatan," kataku menyembunyikan panik.
Ursa menggulir bola matanya dan lanjut melangkah, "Dasar kau aneh."
Dalam beberapa menit, kami telah sampai di pasar. Kawasan ini serupa tenda-tenda kecil yang digelar saling mengapit di sepanjang jalan. Dibandingkan jumlah penjual sayur dan bahan makanan lain, ada lebih banyak pengrajin besi yang berdiam di sana. Meja-meja di hadapan mereka penuh dengan senjata tajam seperti pisau, pedang, busur dan anak panah. Selagi membiarkan Ursa membeli beberapa bahan kebutuhan, aku menghabiskan waktu melihat bagaimana para pengrajin mengasah senjata mereka di permukaan lempeng baja, memukul-mukul pedang pendek dengan batu, juga mengelap bilah pisau dengan kain katun tebal. Sinar matahari yang terpapar di mata pisaunya membuat logam itu tampak mengilat berbahaya.
Salah seorang di antara para pengrajin itu mendadak berceletuk, "Kau mau yang seperti apa?"
Aku tersentak karena tiba-tiba ditanyai. Tatapannya memicing padaku.
"Aku tidak tahu," jawabku, selagi memandangi berbagai jenis pisau yang dipamerkan di atas meja. Di antara berbagai macam senjata dengan mata pisau yang normal―tajam dan tipis, ada pula model unik yang bergeligi seperti gigi hiu, bermata bengkok seperti sabit, dan memiliki bilah bercabang seperti pengait. "Apa bedanya antara pisau ini dan ini?"
Si penjual menatap tajam padaku seolah dia baru saja melihat fenomena aneh di matanya. Aku menjadi panik karena barusan pasti sudah terdengar salah bicara. Rasa ingin tahuku adalah kesalahan. Sebagian besar penduduk Bruma adalah ahli senjata, sudah pasti pertanyaan bodoh itu hanya membuatku semakin dicurigai.
"Tentu saja ada bedanya," katanya, hampir mengejek, lalu menunjuk sebuah pisau yang memiliki bilah yang melengkung dan tebal seperti cakar harimau. "Kau bisa mengoyak isi kepala babi dengan benda ini―" tangannya lalu berpindah ke pisau yang lebih tipis dan memiliki pegangan dari kayu yang ringan, "tapi tidak dengan yang ini."
"Ya, ya," jawabku, jelas kelihatan tolol. Percakapan tentang isi kepala entah bagaimana membuatku resah.
"Aku belum pernah bertemu orang sepertimu sebelumnya," katanya sambil mengusap gagang salah satu pisau sampai mengilat, "Kau bukan asli sini?"
"Bukan," jawabku cepat. "Aku dari Amarabu."
"Ah, pantas, kota para pedagang relik."
Dia terkekeh kecil, dan dari caranya menarik bibir, aku bisa tahu dia sedang meledek. Suaranya bergumam rendah ketika melanjutkan, "Apa bahkan kau memiliki saudara yang mengakuimu di sini? Atau jangan-jangan kau datang kemari karena dibuang oleh keluargamu?"
Sudah jelas kata-katanya adalah penghinaan atas warna mataku. Namun, dibandingkan dengan perlakuan keji yang kudapatkan selama hidup di Kevra, kesinisan ini tak ada apa-apanya. Setidaknya dia menerima keberadaanku di sini karena rambutku berwarna putih―kami dari Kaum Putih yang sama, yah, setidaknya, saat ini.
Saat aku memikirkan jawaban yang cerdas untuk membalasnya, Ursa datang menjemputku. Dia menggamit lenganku untuk pergi ke pedagang berikutnya. Kami menyusuri ujung gang yang terbuka, ke sebuah jalanan berbatu kerikil yang cukup lebar untuk dilewati pasukan berkuda. Aku berkata begini karena memang benar saat itu ada derap kuda yang mendekat, dan saat kutengadahkan kepala untuk melihat siapa penunggangnya, jantungku seketika jatuh ke perut.
"Tidak biasanya sraden Kevra datang kemari," Ursa berkata pelan, lalu mengajakku menyingkir ke pinggir agar mereka bisa lewat.
Udara di sekelilingku terasa berat dan panas. Aku menundukkan kepala agar mereka tidak bisa melihatku. Derap sepatu kuda yang menginjak bumi di bawahku terasa bergetar, sementara pikiranku kental oleh ketakutan dan kecemasan. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka berniat mengejarku? Mengapa waktunya bertepatan sekali dengan kedatanganku kemari?
Mereka membawa pasukan lebih banyak―empat ekor kuda cokelat besar berjajar di belakang kuda hitam yang memimpin, dan semua penduduk Bruma yang terlibat perdagangan otomatis menyingkir untuk memberi jalan.
Terdengar dengung masyarakat sekitar yang mengeluh di dekatku. Aku bisa menduga semua orang merasakan kecemasan yang sama, walau tingkatan kecemasan kami berbeda. Ursa juga memandangi mereka dengan tatapan sinis―jenis kemarahan yang membara dalam jantungnya, seolah dia menginginkan untuk menarik salah satunya ke tanah dan menendangi kerongkongannya, tetapi gadis ini memiliki kontrol diri yang begitu besar. Aku tidak tahu mengapa dia bersikap seperti itu, tetapi kuharap ini berhubungan dengan kebenciannya terhadap sraden Kevra yang gemar menyiksa Kaum Liar.
Dia menarikku ke salah satu ruko penjual ikan. Aku berdiri mematung di sana, perlahan menjadi lebih tenang, menyaksikan dari kejauhan bagaimana para sraden itu menaiki kudanya dan berhenti di sebuah titik, entah apa yang mereka lakukan.
"Untuk apa mereka kemari?" gerutu penjual ikan di dekatku. Dia membuka tutup tangki lalu mengeluarkan beberapa ekor ikan mentah dari sana. Ursa memutuskan tak mencuri pandang pada sekawanan sraden dan sibuk memilih ikan.
"Sepertinya membawa kabar penting," jawab Ursa.
"Mereka tak punya malu untuk menginjakkan kaki ke sini, iya, kan?" komentarnya sambil mengambil lembaran uang Ursa dan menjejalkan beberapa ekor ikan ke dalam kantong plastik. Penjual wanita itu merapatkan bibir seolah dia merasa tak tahan lagi berkata kotor. "Kalau bukan karena membawa berita darurat, berani bertaruh, mereka tak akan mau datang kemari karena merasa malu pada kita. Mereka kan hanya keturunan terkutuk. Aib keluarga."
Ursa tersenyum tipis. "Terima kasih," katanya, lalu mengambil sekantong penuh berisi ikan mentah. Dia mengajakku pulang.
Saat kami melewati para sraden yang masih terdiam di pinggir, salah seorang di antara mereka menunduk dari atas kuda dan tatapannya langsung bersiborok denganku. Aku berlagak tenang dan langsung menepis pandangan ke depan, tetapi rasa takut dibantai membuatku tanpa sengaja membungkus jemari Ursa erat-erat.
"River, ada apa?"
"Tidak," kataku, tetapi aku merasakan tanganku bersimbah keringat. Aku ingin berlari dari sini dan kabur sejauh mungkin, secepat mungkin.
Dari belakangku, terdengar gedebuk suara seseorang yang turun dari kuda. Ketakutanku meningkat hingga aku bisa merasakannya seperti harimau yang mengaum di telinga. Aku menggamit tangan Ursa, berkata dengan suara patah-patah yang tak bisa kusembunyikan, "Se-sepertinya aku tidak enak badan. Ayo ... jalan lebih cepat."
Gadis itu menurut saja saat aku menariknya, tetapi suara sraden yang berdiri di dekatku menghentikan kami.
"Tunggu, dua orang di sana," katanya dengan dingin.
Ursa berhenti, lalu berputar. Aku merasakan keringat meleleh di pelipis.
"Ambil," dia berkata sambil menyodorkan selembar kertas kepada Ursa. "Siapa tahu kalian belum mendengarkan berita yang tersiar di radio kota."
"Apa itu?"
"Pengumuman lengkapnya bisa kalian baca sendiri di papan berita di sana. Aku ingin kalian membacanya dengan cermat dan tidak meremehkan berita ini."
Kutatap sraden itu. Ternyata dia bukan kelompok yang mengejarku sampai ke hilir sungai. Dia tidak mengenalku, tetapi raut wajahnya yang angkuh dan kerut tegang di tengah alisnya mengirimkan gejolak minta ditonjok. Atau, barangkali ekspresinya menyiratkan hal lain―seperti kata penjual ikan tadi, dia bisa saja enggan datang kemari karena takut warna matanya yang gelap malah membuatnya diserang oleh penduduk asli Bruma yang bermata hijau.
"Hei, kenapa diam saja? Ambil kertas ini!"
Ursa merebut kertas dengan sedikit marah. Dia membacanya, dan aku ikut mengintip dari bahunya.
Sesuai dugaan, firasat burukku mengatakan kebenaran. Isi kertas itu adalah sketsa wajah dan fisik dua buronan―bisa dipastikan itu adalah aku dan Heera―yang dinyatakan kabur dari Kevra. Aku digambarkan sebagai laki-laki tinggi dan kurus, berwajah masam, dengan rambut hitam menutupi mata. Lalu gambar seorang bocah perempuan berdiri di sampingnya―deskripsi usianya dituliskan, "sudah cukup untuk dikirimkan ke Rawata sebagai upeti", gambar tubuhnya kurus ceking dengan mata bulat berukuran lebih besar dari yang seharusnya.
Mereka betul-betul datang untuk mencariku.
Mendadak, kenangan saat aku dikejar di hutan kembali menyusup. Aku merasa ingin muntah. Kubungkukkan badan dan menutup mulut, berusaha menahan sarapan di perut.
"Kenapa dia?" tanya sraden itu, dan aku merasakan tubuhnya mendekatiku.
"Dia sedang sakit," Ursa tiba-tiba menghalaunya. "Biarkan kami pergi. Aku sudah dapat informasinya."
Sraden itu berdecak jengkel. "Pastikan kalian menghubungi pihak yang tepat bila melihat dua buronan tengik itu." Aku tak bisa melihat bagaimana respons Ursa, tetapi dari pandanganku yang berputar karena pening, pria itu akhirnya berjalan menjauh.
Ursa berkata, "Ikut aku."
Kemudian dia menarik pergelangan tanganku, kali ini cengkeramannya lebih kasar. Ursa membawaku melintasi gang berikutnya yang berupa jalan setapak penuh pepohonan dan lebih sepi dari pasar. Sementara itu, benakku bertarung dengan berbagai lapisan emosi negatif; rasa takut ketahuan, perasaan gelisah, terancam, dan keinginan untuk menghilang dari dunia. Gelombang itu memuncak saat Ursa mendadak melepaskan cengkeramannya, lalu beralih memegangi kedua bahuku dengan amat erat.
"Aku sudah tahu ada yang salah," katanya, sedikit terengah. Tatapannya yang sinis dan mengintimidasi membuat kakiku goyah tanpa sebab yang jelas. "River, aku tahu ada yang salah denganmu."
"Apanya yang salah?"
"Orang itu kau."
Aku kebingungan, merasa sudah di ujung tanduk. Ursa memegang rahangku dengan jemarinya dan mengamati wajahku lebih dekat. Suaranya yang berbisik dan penuh keheranan mendobrak relung jantungku;
"Tidak bisa disangkal lagi, kaulah buronan yang dimaksud sraden itu."[]
-oOo-
.
.
.
.
Baru awal ketemu Ursa udah ketahuan awkwkwk. Menurut kalian gimana nasib River selanjutnya?
A. Kabur dari ursaaaa!
B. Pura-pura pingsan
C. Cari alesan supaya nggak dicurigai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top