35. Pengorbanan
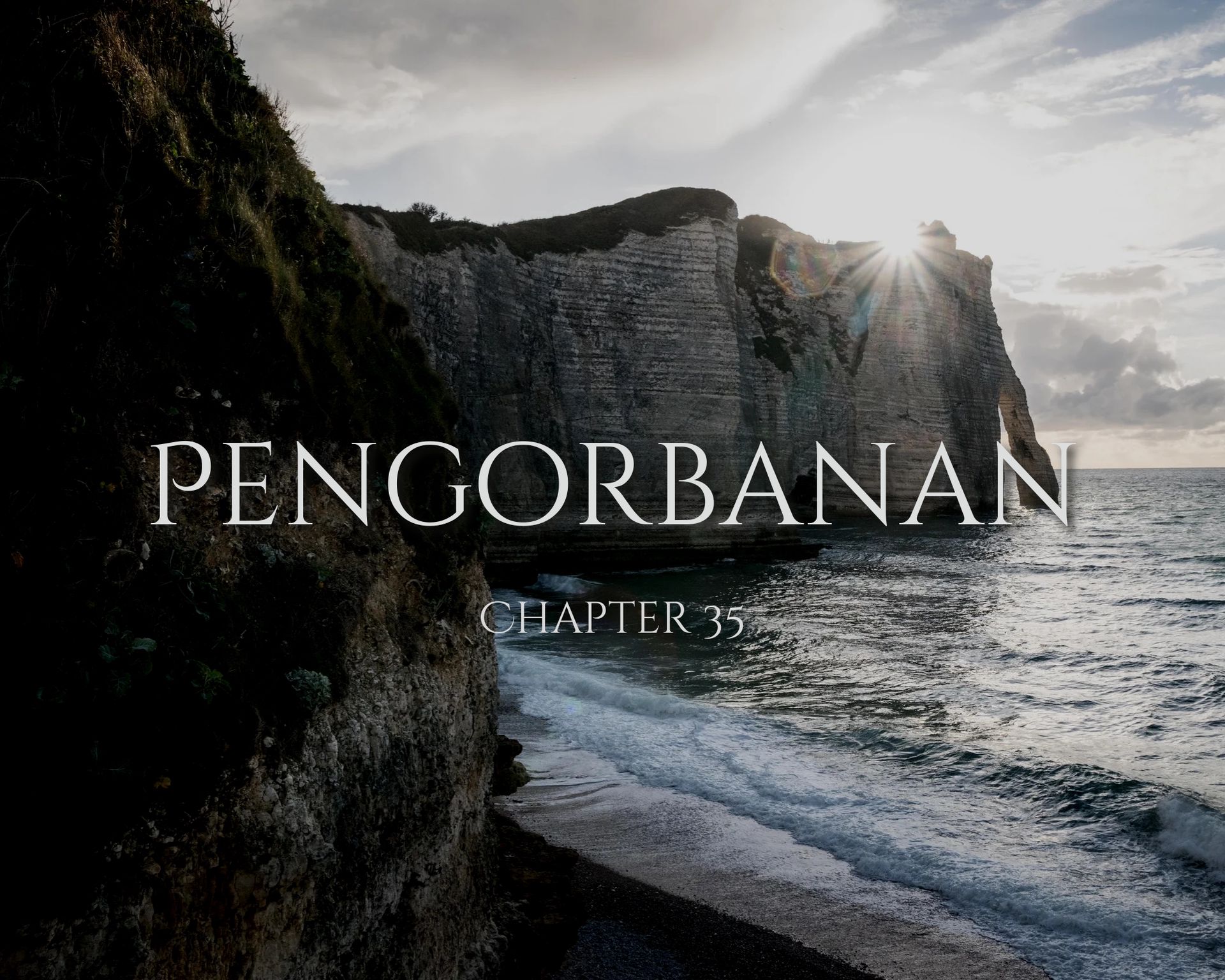
PAGI itu aku terbangun dengan secercah perasaan sedih yang tak asing. Ursa berbaring memelukku dengan kepala bersandar di dadaku. Saat aku menunduk untuk menatap wajahnya, aku mengingat bahwa semalam aku tertidur dengan segumpal perasaan lega setelah menumpahkan semua rasa sakitku padanya. Namun, seperti halnya kabut yang pudar ditelan pagi, perasaan lega itu kini tersapu lenyap, tergantikan dengan kecemasan masa depan yang merayap di ujung perjalanan.
Ketakutan ini sungguh tak terbendung; rasa sakit. Kecemasan. Perang. Kematian yang menunggu di depan mata. Aku tak peduli lagi dengan nyawa Raja, tapi aku peduli dengan nyawa pasukan di belakangku. Bagaimana bila Philene dan kawan-kawan tak bisa menghadapinya? Bagaimana bila di antara kami banyak yang tewas? Bagaimana bila Ursa juga pergi meninggalkanku? Aku tak sanggup membayangkan hidup tanpa siapa-siapa di sisiku. Aku tak mau kehilangan lagi orang-orang yang terlanjur kusayang.
"Kau sudah bangun?" Ursa tiba-tiba berkata lirih. Kepalanya mendongak dan dia menatapku dengan dua mata hijaunya yang sempurna. Berkilau seperti lumut hutan, cantik seperti wajahnya. Aku menariknya dalam pelukan erat.
"Ursa," kataku dengan dagu di puncak kepalanya, "Saat aku hilang kemarin, bagaimana perasaanmu?"
"Aku mengira kau sudah mati. Dan perasaan itu seperti daging yang membusuk dalam diriku. Aku tak bisa melakukan pekerjaan dengan baik karena aku terlalu marah pada diriku sendiri yang tak bisa menjagamu dengan benar." Gadis itu menyentuh dadaku dan menekan telapaknya di sana. Dia bernapas pelan hingga aku bisa merasakan embusan hangatnya di kulitku. "Saat itu kupikir aku tidak akan memaafkan diriku sendiri selamanya."
"Kau tidak salah apa pun."
"Tidak," kata Ursa. "Akulah yang membawamu ke sini. Aku memenuhi dirimu dengan kebencian sehingga kau membuang segalanya dan memulai semuanya dari awal. Bersamaku. Bersama ibu dan kawan-kawan perampok yang kita temukan di jalan. Seandainya sejak awal kita tidak bertemu, barangkali kau akan dianggap hilang dari muka bumi ini, dan...."
"Dan peperangan tidak terjadi?"
Ursa terdiam lama, "Tidak juga. Kalau soal itu ... mungkin Aved punya cara lain untuk memberontak tanpa dirimu."
"Kita berdua tahu bahwa pada akhirnya perang akan pecah. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menahannya."
Ursa tak menjawab apa-apa lagi. Dia hanya mengetuk-ngetukkan jemarinya di dadaku dan membuat pola-pola lingkaran kecil di sana. Suaranya terdengar melamun kali berikutnya, "River, saat pertama kali melihatmu, aku merasa kau sangat lemah dan tidak berdaya. Bagiku kau hanyalah pemuda malang yang diliputi kesedihan atas kematian ibu dan adikmu. Badanmu kurus, wajahmu terlalu tirus, matamu cekung seperti orang yang digerogoti penyakit, gerak-gerikmu kaku juga lambat. Aku nyaris meluapkan kemarahan pada ibuku karena dia menginginkan aku untuk membawa pemuda selemah kau ke Rawata, padahal aku tahu betul kau tidak akan bertahan. Saat itu, River, ... di tengah perjalanan kita ke Rawata, sebetulnya aku berdoa supaya kau bukanlah orang yang dimaksud ibuku. Namun semuanya jungkir balik ketika kau melawan gerombolan Philene dan matamu berubah menjadi biru. Pada saat itu hatiku bimbang. Harusnya aku senang bahwa aku berhasil menemukan orang yang selama ini kita cari-cari. Tapi di sisi lain aku selalu diderai rasa takut karena melibatkan pemuda malang sepertimu ke dalam peperangan ini. Sejak kita bertemu aku selalu merasa khawatir, tapi aku tak bisa mengatakannya di hadapanmu."
Kata-kata Ursa mengirimkan semacam sengatan terkejut dalam benakku. Rupanya selama ini―semua sikap ketusnya, caranya menatapku yang menyiratkan cibiran dan sebelah mata, keangkuhannya yang sekeras batu karang di lautan, hanyalah cangkang tebal yang membungkus rasa khawatirnya padaku? Aku menatapnya dengan pandangan tak percaya, "Tahu tidak? Aku membencimu pada beberapa minggu pertama kau menolongku."
"Aku tahu. Aku melihatnya dari matamu," kata Ursa, terkekeh tipis. Dia mendongak dan menatapku, "Saat itu aku berpikir, kau membenciku karena kita berasal dari dua kaum yang berbeda."
Kemudian aku berguling menyamping dan membuat wajah kami menghadap satu sama lain. Jarak Ursa begitu dekat denganku sehingga aku bisa memperhatikan bulu mata lentik berbaris indah di tepi kelopaknya.
"Ursa, sejak dulu, kebencianku terhadap kaum berambut putih sama besarnya seperti kebencianku ketika melihat ibuku dibunuh. Aku merasa malu dan tertindas karena saat itu tidak pernah bisa berbuat apa-apa selain mengutuk serta memaki mereka di dalam hati. Dan walaupun dulu aku membencimu, sekarang aku...."
Ursa hanya menatapku, lalu aku melanjutkan lirih seraya meremas tangannya, "Aku tidak percaya kalau sekarang aku telah jatuh hati pada seorang gadis berambut putih."
Dia tersenyum lemah di bawah sinar lampu minyak. Jemariku terjulur mengusap pipinya, lalu dia berkata dengan nada berat dan menyesal, "River, aku menanamkan rasa benci di dalam dirimu dan mempersiapkanmu terjun ke dalam peperangan ini."
"Tidak," kataku, mendorong diri lebih dekat padanya. Bibirku di telinganya, berbisik lirih, "Kau memadamkan jiwaku yang rapuh dan menggantinya dengan kobaran api yang menyala-nyala. Aku hidup kembali berkat dirimu, Ursa."
Kemudian kutekankan bibirku pada bibirnya. Kubawa tangannya ke dadaku, dan jemari pada tangan satunya kutautkan dengan jemariku. Aku bisa mendengar deru napasnya yang hangat di pipiku, merasakan kulitnya yang lembut dan basah oleh air mata di bawah sentuhanku.
"Kenapa kau menangis?"
"Aku ingin bersamamu selamanya, River."
"Aku juga," kataku, kemudian kukecup matanya yang basah, pipinya yang dialiri air mata, dan bibirnya yang gemetar karena rasa sedih. Di mana ada jejak air matanya, aku mengecupnya. Jantung Ursa berdegup kencang di bawah sentuhanku, dan saat itu aku tahu, satu-satunya hal yang paling kutakutkan di dunia ini adalah tak mendengar detak jantungnya lagi selama-lamanya.
Kukecup kelopak matanya yang terpejam dan mengatakan kalimat itu dengan sepenuh hati;
"Aku mencintaimu, Ursa. Sekarang dan selamanya."
-oOo-
Markas besar Aved berupa sebuah bangunan beton mirip benteng kecil yang dibangun di sebuah dataran tinggi wilayah Rawata Utara, dikelilingi hutan lebat dan tebing curam di atas laut yang ombaknya mengganas. Pada suatu hari sebelum jam makan siang, semua orang berlatih di beberapa lokasi yang mereka suka. Aku bergabung bersama Dumbo, Hathen, dan Ursa untuk berlatih di luar, di sebuah perbukitan luas di dekat tebing yang deru anginnya sangat kencang.
Anak panah terakhir melesat di udara dan menembus papan sasaran yang diletakkan tersembunyi di puncak pepohonan. Aku menurunkan busurku dan menghadap Dumbo, yang berdiri paling dekat denganku. "Aku melepas dua puluh anak panah. Berapa skorku kali ini?"
"18 dari 20."
"Sial," rutukku jengkel. Sedikit lagi.
Aku menendang kaki ke udara bebas dan menatap Ursa yang berdiri sambil berteduh di sebuah pohon besar bersama Hathen. "Kau menang kali ini," kataku pada gadis itu.
"Aku selalu menang darimu," Ursa mendengkus tawa.
"Tidak, tidak. Biasanya aku menang kalau pertarungan jarak dekat."
"Pertarungan dinilai lebih efektif bila kita bisa merobohkan banyak musuh dari jarak jauh."
"Akan lebih efektif lagi bila kita mengubur semua musuh hidup-hidup dalam bangunan yang runtuh."
"Oh, ayolah," Hathen mengerang. "Kau serius mau meledakkan Rawata dengan kesaktianmu?"
"Percayalah, aku akan memakai cara itu bila rencana Kegan gagal. Dengan begitu, semua orang termasuk Raja akan langsung tewas tergencet beton," kataku.
Lalu kami kembali latihan. Ursa dan Hathen sama-sama berdiri di tempat semula dan Dumbo mulai menghitung skor mereka, sementara aku memilih istirahat sebentar di bawah pohon. Aku sudah hendak merosot duduk dan bersandar di batang pohon ketika kulihat punggung seorang yang sedang kukenal sedang duduk sendirian di tepi tebing laut yang terbuka di kejauhan.
Itu Philene.
Aku menghampirinya yang sedang merenung sendiri, lalu duduk di sampingnya.
"Jadi, di mana letak Martes?"
"Di sana," katanya seraya menunjuk arah barat lautan lepas.
Kemudian Philene menunduk lagi dan baru kusadari dia tengah menggenggam sesuatu di tangan kanannya. Ada sebuah liontin yang menyembul di antara jemarinya, dan rantai peraknya memanjang lalu terburai di pangkuan. Aku pernah melihat kalung itu satu kali, saat aku tidur bersamanya di dalam geladak kapal yang berayun. Kupikir itu adalah perhiasan milik kekasihnya, tapi ternyata―
"Ini punya adik perempuanku," kata Philene yang menangkap basah aku sedang memandangi kalung itu.
"Oh, ya," kataku. "Siapa namanya?"
"Samara."
Sejenak aku teringat tentang cerita Philene ketika dia memberitahu tentang kedua adiknya yang masih berusia sekolah dasar. "Adikmu yang paling bungsu atau...."
"Adikku yang paling tua. Usianya sudah dua belas tahun," kata Philene, kemudian dia terkekeh kecil. "Dia memaksaku membawa kalung ini supaya aku bisa menjualnya begitu sampai Rawata. Untuk biaya hidup, katanya."
Philene menatapku lurus-lurus. Matanya yang hijau tampak bersinar cemerlang di bawah sinar matahari lautan. "Aku pergi ke Rawata demi mereka berdua. Kami sudah tak punya orangtua, jadi akulah satu-satunya harapan."
"Mengapa mereka tak diajak kemari juga?"
Saat aku masih memandangi kalungnya, Philene berkata lagi, "Aku tak mau mengajak adikku ke sini karena takut mereka hidup susah. Kau tahu maksudku, orang-orang di sini sangat rasis."
Aku mencerna kalimat terakhir Philene baik-baik, "Apa? Jadi maksudmu...."
"Kedua adikku tidak punya kehebatan seperti kakaknya."
"Jadi mereka seperti Dumbo dan Hathen?"
"Persis begitu."
Aku mengangguk pelan, merasa lebih memahami bagaimana perasaan Philene. Barangkali inilah alasan yang membuat Philene berbeda dari penduduk lainnya yang bersikap semena-mena terhadap kaum tanggung seperti Dumbo dan Hathen. Walaupun dia tidak sopan dan bermulut kasar, tetapi orang-orang seperti Philene, yang memiliki pengalaman dan nasib mirip antara satu dan yang lainnya, akan lebih terhubung dalam sebuah ikatan.
"Dengarkan aku," katanya, "sejak aku tahu bahwa kau adalah Sang Terpilih, aku memercayakan semuanya padamu, River. Aku yakin, keadilan bagi masyarakat kita dapat tercipta bila kejayaan Raja yang sekarang runtuh. Aku kemari demi keadilan adik-adikku juga. Sebab itulah aku mendukungmu."
Suara tawa Hathen dan Dumbo, samar terdengar menembus di antara deru angin dan ombak yang menabrak karang. Philene mengangkat kepalan tangannya dan mengarahkannya padaku, berkata sambil tersenyum, "River, jangan mati di pertarungan nanti."
Aku mendengkus, lalu menyambut kepalan tangannya dengan semacam tos persahabatan.
"Tidak akan. Aku akan berjuang demi adik-adikmu."
"Demi kita semua, yang masih hidup dan yang telah tiada," koreksi Philene. "Berjanjilah."
Aku janji.[]
-oOo-
.
.
.
Kalau ending cerita ini nggak sesuai sama harapan, jangan marah sama aku yaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top