Home of Memories
Aku mengendarai mobil dengan gamang, bingung mau ke mana karena sudah menolak apartemen Andra sebagai pilihan. Tidak punya rumah, sendirian, juga terluka.
Air mata masih saja mengalir, sesekali kuseka dengan punggung dan telapak tangan agar tidak menghalangi pandangan. Tuhan, cobaan apa lagi ini?
Akhirnya kuarahkan mobil ke arah sebuah kedai kopi, berhenti di pelataran parkirnya kemudian merenung. Iya, merenung. Karena sesungguhnya aku sama sekali tidak berselera dengan kopi saat ini.
Ponsel yang berkali-kali berdering, kuabaikan. Itu Andra, aku tahu. Kami berdua selalu tidak tahan untuk berpisah atau bertengkar terlalu lama. Namun, untuk sekarang, mendengar suaranya saja aku enggan.
Akhirnya kuraih ponsel, mematikan daya, dan melempar kembali benda pipih itu ke kursi penumpang. Ini menyiksa. Sungguh!
Kuatur kursi pengemudi hingga berbaring, menatap langit-langit mobil dengan perasaan yang seakan melayang. Tubuhku di sini, tapi pikiranku entah ke mana. Banyangan tentang Andra yang menjadi bagian dari kematian Ibu terasa menyesakkan. Apa pun perannya di sana, sama saja. Ujung-ujungnya Ibu meregang nyawa.
Kenyataan bahwa aku mencintainya dengan sangat, itu lebih mengerikan lagi. Bagaimana bisa seorang anak jatuh cinta pada seseorang yang membuat ibunya kehilangan nyawa? Di mana nurani dan kehilangan yang selama ini kugadang-gadang, kalau kenyataannya aku masih memaksa untuk bertahan bersama Andra?
"Sialan!" makiku sendirian. Memaki diri sendiri tepatnya.
Ah, mungkin secangkir kopi yang pahit bisa sedikit menenangkan.
Segera aku keluar mobil, melangkah ke arah kedai yang terlihat sepi. Aku tidak perlu mengantre untuk mendapatkan kopi hitam tanpa gula. Benar-benar tanpa gula. Pahit.
Kupilih duduk di sudut ruang, melempar pandangan ke luar jendela.
Tiba-tiba rintik hujan turun, bersamaan dengan sepasang muda-mudi yang berlarian ke arah kedai. Mereka berteduh di pelatarannya sambil bergandengan tangan. Sesekali tangan si lelaki mengusap kepala kekasihnya, menyentuh pipinya, yang dibalas dengan senyuman lebar sang kekasih.
Ini benar-benar menyebalkan. Keromantisan selalu mengingatkanku pada Andra. Bagaimana dia menyentuh, membelai, dan menciumiku dengan sayang.
Tanpa sadar, air mata yang sempat berhenti menetes lagi. Cepat kuusap dengan telapak tangan agar tidak ada yang melihat. Setelahnya aku bangkit, meninggalkan kopi yang bahkan tidak tersentuh oleh bibir. Melangkah tergesa keluar kedai, aku berlarian kembali ke mobil.
Hari sudah gelap, sementara hujan yang turun semakin deras. Sepasang muda-mudi tadi sudah tidak ada lagi di pelataran kedai. Entah ke mana tidak kuperhatikan. Sekarang saatnya memutuskan, ke mana harus pergi.
Kulirik ponsel yang masih tergeletak di kursi penumpang dalam keadaan mati. Kuraih dan menyalakan kembali daya. Beberapa pesan masuk dengan segera. Sekilas kulihat ada pesan dari Andra, Bian, bahkan dari Clara. Namun, kuabaikan.
Ketika ponsel mendadak berdering, otomatis mataku kembali pada benda itu. Nama Clara berkedip-kedip di sana. Tidak kujawab, hanya kuperhatikan sampai mati dengan sendirinya.
Aku berdecak, mengingat bagaimana aku berteriak tadi ke arah gadis kecil itu. "I love you, Clara ...." Dan bagaimana aku membalas perkataan ayahnya dengan sebaliknya, "I hate you, Ndra ...." Napas ini segera terhela. Aku benar-benar belum memutuskan apa yang harus kulakukan sekarang.
Kulirik jam pada dashboard, angka-angka yang benderang di sana menunjukkan pukul 8 malam. Sepertinya aku harus segera memutuskan di mana aku harus tinggal malam ini.
Perlahan kakiku menginjak pedal gas, membawa mobil keluar dari parkiran kedai kopi, berjibaku dengan kemacetan yang segera menyambut.
Pikiranku kembali berkelana, menimang-nimang beberapa pilihan. Hotel atau ... kembali ke tempat itu.
***
Mobilku memasuki pekarangan sebuah bangunan bercat putih yang luas. Jendela-jendelanya sebagian besar sudah menutup. Yang kuingat, tidak ada kaca di jendela-jendela yang tertutup. Hanya sekat-sekat besi yang diamankan dengan kayu penutup. Unik,
Sudah sepi di sini, ketika kulirik jam di tangan sudah hampir jam sepuluh malam. Pantas saja. Pada jam ini dulu, aku sudah dipaksa untuk tidur. Meski belum mengantuk sekali pun, aku akan berada dalam selimut, mencengkeram ujung-ujungnya agar tidak ketakutan di dalam kamar yang gelap karena lampu dimatikan.
Langkahku bergerak menuju teras utama. Tadinya mau langsung memencet bel, tapi urung ketika aku mendengar tawa-tawa tertahan dari sisi dinding sebelah kanan. Seingatku, di sana ad ataman dengan beberapa kursi yang bersandar pada dinding. Sepertinya, ada beberapa orang yang masih bercengkerama dengan asyik di sana.
Maka, ke sana kaki ini melangkah. Sedikit mengendap sambil bertanya-tanya siapa yang berada di sana. Ibu kepala pantikah? Atau kakak-kakak pengasuh yang menjagaku dan teman-teman dulu?
Aku nyaris berbelok, ketika menangkap suara laki-laki di antara ramainya suara perempuan.
"Dan cokelatnya dibuang. Aku sedih ...." Suara lelaki itu terdengar memelas. Disambut tawa para perempuan.
"Dia enggak kenal kamu?"
Astaga! Aku masih ingat suara ini. Suara yang sering kali menenangkanku di saat aku menangis karena merindukan Ibu dulu. Suara ibu panti. Aku rindu.
"Kayaknya enggak. Aku udah berubah jadi ganteng berkali-kali lipat. Iya, kan, Bu?"
Dan sepertinya, suara ini juga tidak asing.
"Jangan ngerayu gadis enam puluh delapan tahun, Bagas ...." Ibu panti tertawa, semua turut tertawa.
Bagas?
Sepertinya ada seorang lelaki bernama Bagas yang datang. Sama sepertiku, sepertinya mengunjungi rumah lamanya.
Kuhela napas, kusungging senyum. Kemudian dengan pasti melanjutkan langkah, berbelok ke arah suara kemudian berseru, "Ada yang kangen sama aku enggak?!"
Semua tawa sontak terhenti, ada empat pasang mata yang saat ini menatapku dengan terkejut. Di antara keempatnya, satu orang membuatku terkejut setengah mati.
Si laki-laki yang kudengar tadi disebut sebagai Bagas, menatap dengan senyum merekah.
"Panjang umur amat, Vin. Baru aja diomongin ...," katanya sambil memamerkan deretan giginya yang rapi.
Sesaat aku tidak bisa berkata apa pun. Ketika akhirnya bisa menggerakkan bibir sekali pun, yang terlontar hanya satu kata penuh kebingungan.
"Keevan?" tanyaku seraya menganga.
"Bagas kalau si Ibu mah taunya." Lelaki itu menatapku dengan binar di mata. "Keevan itu nama setelah Mama Papa bawa aku dari sini. Kalau kamu, dulu manggil aku cuma pakai kata, 'Kakak'." Dia nyengir.
Aku masih terdiam di tempatku berdiri, menatap Keevan dengan takjub. Kakak? Kakak yang sering kali memberikanku cokelat saat aku menangis dulu?
"Sini. Peluk Ibu, kenapa bengong di sana?" Suara Ibu panti menyentakku yang masih kebingungan. Tangannya bergerak memanggil. Mau tidak mau aku mendekat, memeluk dan mengecup kedua pipinya, mengambil duduk di sebelah wanita yang sudah menua itu, sambil lagi-lagi menatap ke arah Keevan, bos-ku.
Ini gila!
Tidak lama, setelah berbincang panjang dan lebar bersama ibu panti dan dua pengasuh yang baru kukenal, hanya tinggal aku dan Keevan yang tersisa. Aku duduk di bangku kayu yang menempel pada dinding, sementara Keevan bersandar pada pilar kayu di hadapanku.
Sejak tadi, dia tersenyum tiada henti. Menatapku dengan tidak malu-malu. Membuatku merasa tidak yakin kalau dia benar adalah anak lelaki yang usianya lebih tua dariku dulu. Yang sering kali memberiku cokelat dan mengusap kepalaku saat menangis dulu.
"Dunia sempit, 'kan?" katanya yang masih memandangku dengan tangan yang terlipat di dada. "Kamu tau enggak sih, aku selalu mikirin kamu selepas dibawa dari sini. Apa kamu masih cengeng, siapa yang bakal diemin kamu pas lagi mewek. Kamu bikin aku tegang di awal-awal kepindahan."
Aku menghela napas, kemudian mengangkat kedua bahu. "Aku sering bertanya-tanya kenapa kamu enggak pernah muncul lagi. Dan agak terkejut dengan cara kamu muncul sekarang ini. Enggak disangka-sangka."
Keevan tertawa geli. Sepertinya dia senang dengan keterkejutanku.
"Kenapa kamu enggak langsung bilang siapa kamu sebenarnya waktu pertama kali kita ketemu?" tanyaku seraya mengerutkan kening.
"Kenapa harus bilang? Dari kecil pun, kamu enggak pernah tau siapa aku, siapa namaku. Kusebut Bagas pun, kamu enggak akan kenal," sahutnya.
Aku mendengkus, karena dia ada benarnya juga. Aku tidak akan mengenalnya meski dia memperkenalkan diri dengan nama kecilnya sekali pun.
"Hidup ini emang luar biasa, ya ...."
"Maksud kamu?" Keningku mengerut.
Keevan tidak langsung menjawab. Diraihnya tas yang tergeletak di ujung kakinya, dan mengeluarkan bungkusan panjang dari dalam sana. Cokelat.
"Mata kamu bengkak. Abis nangis?" Disodorkannya makanan manis itu ke arahku. "Kali ini, jangan dibuang. Ya?" Dia tersenyum.
Kubalas senyumnya, sementara tanganku segera terulur hendak menyambut cokelat dari tangannya. Namun, ponsel yang berdering dari dalam tas yang sejak tadi kubawa, membuatku menarik lagi tangan yang terulur.
Kuberi kode ke arah Keevan agar dia maklum kalau aku harus melihat siapa yang menelepon. Kuraih ponsel dari dalam tas, dan menatap nama yang terpampang pada layar.
Andra is calling ....
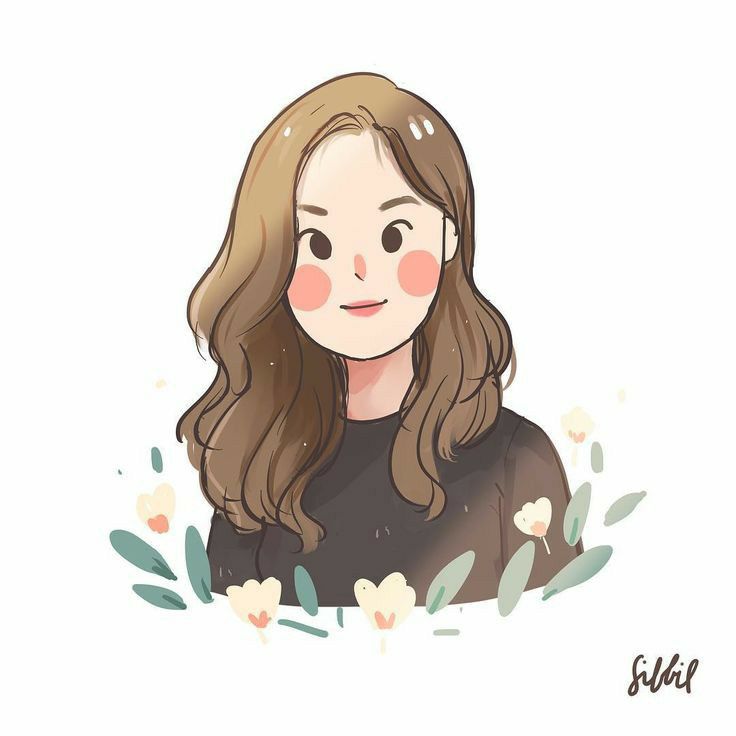
Pic: pinterest.
Vini versi cartoon.
Oiya, Gaes, aku cuma mau bilang kalau aku juga punya akun Joylada. Di sana, aku update satu cerita baru. Siapa tau kalian mau mampir ke sana dan ngasih aku semangat!
Cari aja: Verlitaisme.

Thanks, ya! 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top