1. Adit
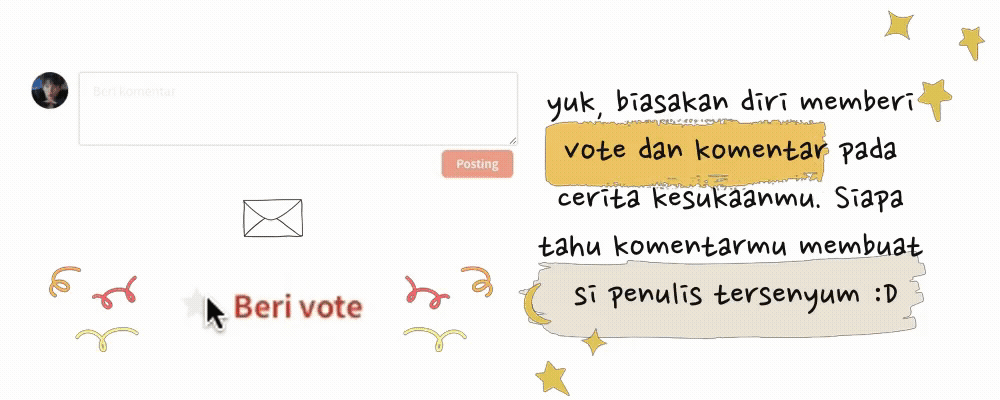
"Saya nggak gila."
Itu yang Adit katakan saat duduk di hadapan Dokter Devan. Kalau bukan karena paksaan Mama, Adit tidak akan ada di sini sekarang.
"Siapa yang bilang Adit gila?" tanya Dokter Devan prihatin, kedua tangannya saling tertaut dengan sorot mata kebapakan.
"Kalau ke sini, ya berarti saya gila. Saya nggak gila," ulang Adit, menjelaskan lebih detail. Berharap orangtua di hadapannya mengerti.
Dokter Devan menatap Adit beberapa detik tanpa mengatakan apa pun. Maka, Adit mengalihkan tatapan pada poster di dinding. Judul poster tersebut tentang depresi. Sekian dari 10 orang dapat mengalami depresi, katanya.
"Adit tau sekarang tanggal berapa?"
Pertanyaan Dokter Devan membawa Adit kembali menatapnya.
"12 Juli."
"Sekarang 8 Agustus."
Adit mengerutkan dahi. Adit yakin banget sekarang tanggal 12 Juli. Kenapa sekarang berubah jadi 8 Agustus?
"Apa hal terakhir yang Adit ingat tadi pagi?" tanya Dokter Devan.
Pertanyaan tersebut sungguh mudah, pertanyaan sehari-hari, tetapi Adit kesulitan untuk menjawabnya. Apa yang ia lakukan tadi pagi? Kenapa ia bisa berada di tempat ini? Adit nggak ingat. Yang ia ingat adalah papan nama Dokter Devan yang bertuliskan Spesialis Kesehatan Jiwa saat ia duduk di kursi panjang ruang tunggu bersama mamanya. Di momen itu, Adit tau mamanya menganggap Adit gila. Itu sebuah kekeliruan.
"Adit?"
Panggilan Dokter Devan menyentak Adit dari lamunan. Adit mengerjap pelan, berusaha fokus menatap mata Dokter Devan, tetapi sulit. Rasanya, Adit ingin pergi sekarang juga, entah ke mana, dia sendiri nggak tahu.
"Selama tanggal 12 Juli sampai hari ini, Adit nggak ingat apa yang Adit lakukan?"
Seperti tersihir, Adit menggeleng pelan.
"Adit ingat papanya Adit ada di mana?"
Kenapa tiba-tiba jadi Papa? Adit mengerutkan alis. "Ya, ada di kantornya. Memang ada di mana lagi, Dok?"
Raut wajah Dokter Devan seperti enggan memberitahu sesuatu pada Adit. Sorot prihatin itu juga lagi-lagi muncul. Membuat Adit tak nyaman, seolah ada yang salah dengan jalan pikirannya.
"Adit ...," Dokter Devan mengembuskan napas berat. "Papa kamu sudah tiada sebulan yang lalu."
Dokter Devan pasti bercanda.
***
Di sinilah Adit berada sekarang. Ruang tunggu farmasi menunggu obatnya selesai diracik.
Setelah Dokter Devan mengatakan hal tak masuk akal itu, Adit ke luar dari ruangan, mengatakan pada Mama bahwa mereka harus pulang sekarang dan mencari Papa.
Mama histeris. Orang-orang di sekitar menahan Adit untuk tetap di tempat, tidak ke mana-mana. Dokter Devan ke luar ruangan dan meminta Mama untuk mengobrol. Adit tidak tahu apa yang mereka obrolkan. Adit ingin sekali menarik Mama dari Dokter Devan. Bisa-bisa Mama ikut terpengaruh ucapan dokter jadi-jadian itu. Namun, orang di sekitarnya makin memegangnya erat-erat, seolah Adit tak ada bedanya dengan banteng lepas.
Setelah bermenit-menit penuh teror, Mama kembali dengan mata merah yang sembab dan secarik kertas berisi resep obat untuk Adit.
Adit yakin dirinya sama sekali nggak butuh obat.
"Atas nama Aditya Hilmi Putra."
Mama bangkit dari sebelah Adit, mengambil obat racikan tersebut. Pihak apoteker memberitahu Mama kapan dan berapa kali obat tersebut harus diminum. Adit hanya memperhatikan dari jauh.
"Ayo pulang," ucap Mama ketika sampai di hadapan Adit.
"Cari Papa, yuk, Ma."
Mama menangis lagi.
***
"Bu ... Adit nggak baik-baik aja."
Suara Mama samar-samar terdengar oleh Adit yang tengah menyapu di ruang keluarga. Aneh sekali. Sepulang dari rumah sakit, Adit disuguhkan pemandangan rumah yang berantakannya melebihi kapal pecah belah. Padahal, Mama dan Adit sama-sama orang yang rapi. Nggak mungkin sekali ada tumpukan baju kotor di ruang keluarga, buku-buku berserakan, dan barang elektronik berhamburan dari laci. Tetapi, itu yang terjadi sekarang.
"Iya, Bu ... sepertinya Adit butuh suasana yang baru juga ...."
Suara Mama kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih lirih. Mama sedang menelepon ibunya, nenek Adit. Nenek Adit tinggal di Sukabumi. Sekitar empat atau lima jam perjalanan dari Jakarta. Tiap kali lebaran dan tahun baru, Adit ke sana bersama Mama. Papa jarang ikut. Sibuk.
"Ratih pulang ke Sukabumi ya, Bu .... Surya juga udah nggak ada ... nggak ada alasan lagi Ratih dan Adit tinggal di Jakarta ...."
Adit menggenggam gagang sapu erat. Surya adalah nama Papa. Lagi-lagi, Mama mengkhayal Papa udah nggak ada. Pengaruh Dokter Devan tampaknya kental.
"Ma," panggil Adit, berdiri di ambang pintu kamar orangtuanya.
Mama tengah menempelkan ponsel di telinga. Mata Mama masih saja memerah. Entah sudah berapa lama Mama menangis. Di sekeliling Mama, barang-barang berserakan di mana-mana, bahkan lebih berantakan dari ruang keluarga. Seperti ada seseorang yang mengobrak-abrik rumah ini untuk mencari sesuatu ... atau seseorang.
"Aku nggak mungkin pindah ke Sukabumi. Sazkia gimana? Tahun depan aku sama Sazkia nikah."
Lagi, pandangan prihatin itu muncul. Tadi dari Dokter Devan, sekarang dari Mama. Seolah apa yang barusan Adit katakan jauh dari nalar.
Mama menyudahi obrolannya di telepon, kemudian turun dari tempat tidur dengan langkah pelan. Mama membuka laci meja riasnya dan mengambil sesuatu di sana. Sebuah cincin. Cincin yang ... familiar di ingatan Adit.
"Cincin tunangan Sazkia kok ada di Mama?" tanya Adit.
"Adit ...." Mama memeluk Adit, bahunya bergetar hebat, tetapi Mama masih menepuk-nepuk punggung Adit seolah Adit yang butuh dikuatkan. "Sazkia yang mengembalikan cincin ini ke kamu ... dia sekarang sudah bersama Vino ...."
Kerutan di kening Adit berlipat-lipat.
"Mana mungkin, sih, Ma? Vino kan sahabat aku."
***
Adit bingung. Ponselnya entah ada di mana. Dia tidak bisa menghubungi Papa, Sazkia, atau Vino. Bahkan dua jam setelah Adit merapikan rumah pun, Adit tidak menemukan ponselnya.
"Mama liat hape aku, nggak?" tanya Adit untuk kesekian kali, namun dijawab gelengan lemah oleh Mama.
Mama seperti kehilangan tenaga. Dari tadi duduk di ruang keluarga memandangi Adit yang sibuk mondar-mandir. Di rumah ini, yang tersisa memang hanya Mama, Papa, dan Adit. Itu pun akan tersisa Mama-Papa saat Adit menikah dengan Sazkia, karena Adit sudah membeli rumah pinggiran Jakarta untuk keluarga kecilnya.
Adit menyerah mencari ponselnya. "Aku boleh pinjem hape Mama, nggak?" Hanya itu opsi terakhir yang Adit pikirkan.
Mama menatap kosong Adit. Seolah, semakin Adit bersikeras, semakin membuat Mama terluka.
"Ma?"
Mama memberikan ponselnya pada Adit. Orang pertama yang Adit hubungi adalah Papa. Nggak diangkat. Adit menghubungi Sazkia. Nggak diangkat juga. Sekarang Vino. Sama seperti dua telepon barusan, Vino sama sekali nggak mengangkat teleponnya.
"Aneh," gumam Adit.
"Adit ...," panggil Mama lemah. "Ikhlas-in, Adit ... ikhlas-in ...."
Maksud Mama, Adit harus rela bahwa Papa benar-benar meninggal dan Sazkia berkhianat dengan sahabat Adit sendiri?
Padahal, Adit akhirnya bisa membuktikan pada Papa bahwa tanpa menyandang gelar sarjana, ia bisa hidup dari hasil tulisannya. Bahkan tahun depan ia akan menikah dengan Sazkia, memulai hidup baru. Tanpa Papa dan kritikan tajam menusuknya. Padahal, Papa harus tetap hidup agar Adit dapat menunjukkan kehidupannya yang bahagia.
Tujuan Adit hilang. Tiba-tiba, kapalnya yang tenang kehilangan kemudi, lalu karam tertabrak batu karang. Tenggelam dengan semua impian-impian ilusinya.
Sekarang, apa yang harus Adit lakukan?
***
Gimana bab 1-nya? Ikut bingung kayak Adit, nggak? Menurut kamu, apa yang terjadi pada Adit?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top