03. Si Tetangga Dan Kebohongannya
Tepat pukul 3, kala siang tergelincir dan sinar matahari memudar, kisah Baek Seung Hwan berakhir bahagia.
Dia bebas.
Tangis keluarga dan pacarnya tumpah ketika hakim mengetukkan palu, membacakan keputusannya dengan suara kuat nan tegas yang berwibawa. Mereka tak henti-hentinya berterima kasih, menyalami Irene dan berkata bahwa mereka berhutang budi selamanya.
Irene mengangguk, menikmati setiap pujian atas kemampuannya, juga bonus tatapan marah Han yang pergi diiringi umpatan. Sungguh musik yang merdu. Ia sengaja terbahak keras, mengolok-olok pria yang pernah meremehkannnya. Sampah harus dibuang ke tong sampah. Mereka yang tidak handal harus siap dipermalukan. Itu hukum alam, aturan kehidupan. Bukan salahnya kan?
Irene sekedar menjalankan tugas, dan hasilnya membuat ia puas.
Lampu sorot kini tertuju ke arahnya. Reporter berlomba-lomba memperoleh pernyataannya. Apakah sejak awal ia yakin Baek Seung Hwan tidak bersalah? Ya, tentu. Apakah menurutnya pengacara lawan akan mengajukan banding? Tidak tahu. Dalam hati menambahkan, nggak peduli juga.
Han Sung boleh mengajukan banding sesukanya, kalau mau dipermalukan 2 kali.
Setelah menjawab lusinan pertanyaan dan tersenyum manis untuk foto-foto yang kemungkinan dimuat besok, Irene berlalu pergi一memaksa kerumunan memberi jalan. Kadang, ia menyukai reporter, kadang tidak. Kehadiran mereka di saat tertentu, bisa sangat mengganggu.
Tapi Irene selalu bersikap ramah pada para pencari berita tersebut. Karena cukup dengan beberapa kalimat yang disiarkan televisi, mereka mampu mempengaruhi publik. Mereka berbahaya.
Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang anonim, "Hanya dengan kekuatan media, kami bisa menggiring massa."
Mengerikan. Irene bergidik, merapatkan mantelnya. Cuaca di luar jauh lebih dingin karena turunnya salju. Ia ingin cepat-cepat pergi, tapi kehadiran 1 polisi berpakaian preman menghalangi niat itu.
Kim Suho, polisi yang tadi menjadi saksi bersandar di depan pintu kemudi, tampak setara model Gucci.
Ia mengangkat sebelah alisnya melihat kemunculan Irene, menggeleng pelan. "Lama amat, aku hampir jadi patung nungguinnya."
Irene bersedekap, menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Semua pelayan publik一contohnya polisi, tentara, dan dokter一mendapat kekaguman tersendiri darinya. Ia menganggap orang-orang sejenis Suho hebat, tapi bukan itu saja yang membuatnya menghentikan langkah kaki. Ada faktor lain, yang berhubungan dengan betapa enaknya Suho dinikmati mata, dan cara bicaranya yang sopan. "Kapan kita janjian?"
"Belum sih." Suho mengakui, mengacak rambutnya main-main; gerakan khas kaum pria bila sedang gugup. "Tapi aku mau ngasih hadiah buat kamu."
"Apaan?" Tanya Irene penuh selidik, mencoba mengenyahkan bayangan Suho yang memakai seragam polisi. Itu pasti sangat menggoda. Dan pasti, mengganggu konsentrasinya.
"Nih." Berlagak bagai Houdini yang pamer sulap, Suho menyodorkan bungkusan kecil, berhias lambang sebuah minimarket. "Seneng nggak?"
Gelak tawa Irene seketika pecah, namun langsung ia samarkan dengan tangannya. Ini tidak biasa一sangat tidak biasa. Isi bungkusan itu sama sekali tidak ia sangka-sangka. 28 tahun hidup, baru kali ini ada yang memberinya permen, bukan tiket kapal pesiar, buket bunga, atau perhiasan berkilau. Tapi permen一makanan manis beragam rasa. Tidak sampai 50 won harganya. "Ini seriusan? Permen?"
Anggukan. Alih-alih malu, Suho justru menegakkan tubuhnya, narsis sekaligus bangga. "Kamu tadi pengen itu tapi kehabisan, jadi aku beliin. Bener kan?"
Benar. Itu jelas tindakan yang benar, tapi tetap saja Irene menganggapnya lucu. Tertawa sampai membungkuk, memegang kedua lutut. Tas tangannya merosot, nyaris jatuh. Ia membetulkan posisi tas itu, lalu menampung hadiah unik Suho di sana. "Iya, iya, bener. Aku suka permen kok. Makasih."
"Makasih doang?" Ekspresi Suho berubah kecewa. Bahu bidangnya yang tertutup jaket kulit terkulai, memberi kesan panas ganjil di musim dingin ini. "Nggak ada yang lain?"
Si pengacara memutar bola mata, pura-pura jengah. Ia benci pria-pria norak yang menggodanya dengan kalimat basi, mengajak berkenalan menggunakan cara-cara kuno yang ketinggalan zaman. Tapi Suho, dia berbeda. Menawan dan tampan. Suho ibarat boneka beruang lucu, tapi memiliki otot-otot menakjubkan yang tak sepenuhnya berhasil disembunyikan.
Jadi jangan salahkan Irene saat ia merapat, mengeluarkan pulpennya dari tas. Jempolnya menekan bagian atas pulpen itu, sementara tangan lain meraih tangan Suho, dan bergerak. Tarian jarinya menulis 1 demi 1 angka yang ia hafal di luar kepala, menyalin nomor yang jarang ia beritahu pada siapa-siapa. Nomor khusus keluarga, teman dekat dan ... teman kencan potensial.
"Telepon aku nanti, oke?" Bisik Irene di telinga Suho, menepuk-nepuk dadanya yang terdapat kartu identitasnya. "Aku traktir makan, asal kamu nggak nilang aku pas kita jalan."
Kekehan sang polisi adalah jawabannya. Suho menunduk membaca tulisan Irene yang seukuran semut, lagi dan lagi, lantas mengepalkan tangan sebelum deretan angka itu dirusak salju. "Malem ini bisa?"
"Sori." Tak semulus jalan tol, kencan pertama mereka rupanya gagal terjadi secepat itu. Penolakan Irene terucap dari bibir merahnya, disertai senyum yang memperhalus kalimatnya. "Aku mau ketemu adekku. Lain kali aja, ya?"

Bagi murid-murid di seluruh Korea selatan, hari ini adalah hari pertama mereka libur musim dingin. Taeyong sama一atau setidaknya, tidak jauh berbeda. Ini juga hari pertamanya libur sebagai staf, tapi tak seperti mereka, ia tidak bisa bersantai.
Barang-barangnya menunggu dirapikan. Perabotan minta ditata ulang. Peralatan makan pun berserakan. Menertawakan Taeyong dan seolah berkata, "Cie, libur tapi masih kerja!"
Aduh.
Di hotel, bersih-bersih memang pekerjaannya, tapi membersihkan rumah sendiri terasa lain. Punggung, pundak, dan kakinya digelayuti malas yang enggan pergi, setia menemani.
Kehadiran kakaknya yang mondar-mandir juga menyulitkan. Sebab jangankan membantu, Irene fokus berkeliling menggendong Ruby, bak polisi menyisir TKP dengan anjing pelacaknya, kemudian berujar tanpa dosa, "Lumayan buat ukuran rumah rakyat jelata."
Taeyong kontan merengut, wajahnya kusut, mengalahkan pakaian yang tidak disetrika berminggu-minggu. "Mending bersihin kulkas, daripada nganggur."
Sudut-sudut bibir Irene tertarik ke atas, geli mengamati pria 24 tahun yang tidak cuma berbagi gen dengannya, tapi juga latar belakang. Secara fisik, mereka tidak mirip. Namun semua orang selalu terkagum-kagum ketika tahu mereka bersaudara, dilanjut memuji dan bertanya apa yang ibu mereka makan waktu mengandung keduanya. "Sensi banget najis. Inget, kamu nggak bakal dapet diskon kalo bukan karena aku. Mestinya bersyukur."
Urat-urat lengan Taeyong bertonjolan saat ia mengangkat sofa, menyedot debu di bawahnya. Vakum pun bekerja, sedikit menenggelamkan suaranya. "Tapi tetangga di sini aneh-aneh, kemaren aja ada yang cosplay jadi mayat."
Mengernyit membuat 2 garis samar terbentuk di dahi Irene. Gerakannya yang mengelus puncak kepala Ruby terhenti. "Mayat gimana? Jangan sampe kamu ngapa-ngapain orang lho."
"Dikira aku punya tampang kriminal?"
"Nggak, tapi tampang kamu mirip rakyat jelata."
2 bersaudara itu bertatapan; 1 menyeringai nakal, yang lain luar biasa kesal. Ini tradisi, kebiasaan lama yang tidak hilang walaupun Taeyong dan Irene tak lagi tinggal bersama. Jauh dari istilah brother/sister goals, mereka terbiasa perang ejekan sejak kecil. Bersaing, mengaku benci satu sama lain, padahal sebenarnya saling menyayangi. "Kampret. Mau di usir, ya?"
Irene tertawa, menyerupai tokoh antagonis di drama. Kalau ia beralih profesi, tak diragukan lagi, peran itulah yang paling tepat untuknya. Apalagi ia kerap jadi korban salah paham; dinilai menyeramkan hanya karena jarang tersenyum. "Udahan dulu lah, kita makan. Kamu nggak laper?"
Taeyong mengangkat bahu, menekan tombol merah untuk mematikan vakum, kemudian menggulung kabelnya. "Laper kalau di traktir."
"Dih, dasar miskin." Pedas dan menusuk, Irene meledek. Akhirnya menurunkan Ruby dan membersihkan pakaiannya dari bulu-bulu anjing itu. Dia meraih tasnya, memakai kembali benda berisi dompet, ponsel, dokumen penting, serta permen-permen yang sebagian ia makan di perjalanan. "Yaudah ayo, ada warung tenda di depan kan? Kali aja nyediain kalguksu."
"Mungkin," jawab Taeyong tidak yakin, menutup pintu apartemennya dengan kaki. 3 hari sudah berlalu, tapi ia tak sempat berkeliling, atau memperluas lingkup pergaulannya setelah berkenalan dengan Shin dan Jisung. Taeyong bukan introvert一hm, mungkin sedikit一tapi mencari teman bukanlah keahliannya. "Belum ke sana."
"Kamu jarang keluar sih," cerocos Irene, mengaktifkan mode keibuannya dan dijamin, akan segera menceramahi Taeyong panjang lebar. "Akibatnya gini, temenmu dikit banget. Cowok itu Taeyong一"
Ting!
Lift berbunyi, membuka sepasang pintu bajanya dan menghentikan ucapan Irene一meski sementara. Seorang pria yang Taeyong taksir lebih muda darinya menatapnya, mengepit ponsel di antara bahu dan telinganya, ikut marah-marah pada lawan bicara yang ia telepon. "Halo? Ini Winwin, mana Danbi? Aku nggak mau ngomongin buku ini kecuali sama Danbi, panggil dia sekarang!"
Ransel si pria berkemeja hitam putih menyenggol lengan Taeyong dan ia menggumamkan maaf pelan, lalu beringsut keluar dengan lebih hati-hati.
Hal terakhir yang Taeyong lihat sebelum lift resmi menelan tubuhnya dan Irene, adalah pemandangan pria itu yang berbelok ke kiri, menuju unitnya.
Satu lagi tetangga aneh, pikir Taeyong, sambil menekan tombol lift dan bersiap mendengar ceramah Irene lagi.
"Cowok itu Taeyong, nggak boleh sering ngurung diri. Sesekali keluar terus一"
"Beli narkoba?"
"Iya一eh nggak! Maksudnya nggak! Apasih bego!"

Menjelang akhir tahun 2019, teknologi telah semakin maju. Asal punya uang, kita bisa mengubah warna rambut, gaya berpakaian, bahkan wajah kita. Tapi selera makan tidak termasuk di dalamnya.
Baik Taeyong dan Irene, beruntung dikaruniai wajah yang tak memerlukan banyak skincare, tapi Tuhan itu maha adil; mereka tidak terlahir dari keluarga kaya. Mereka pernah sekolah mengendarai sepeda bekas, memakai sepatu kekecilan, dan menghangatkan diri dengan jaket berlubang.
Hal inilah yang membuat Irene tidak sungkan menyusup ke warung tenda. Gaji tingginya tidak serta merta meninggikan gengsi. Ia sederhana. Ia tidak tahu caranya bersikap sombong dan benci orang-orang yang begitu.
Kini, 14 menit usai pergi dari kediaman Taeyong, Irene sibuk meneliti buku menu, mengabaikan tatapan pengunjung lain yang tertuju ke wajah dan mantel bermerknya. "Kalguksu nggak ada, Taeyong. Diganti apa?"
Yang ditanya mengambil alih buku menu, membaca kilat dengan menyusurkan tangan di permukaan halus buku tersebut. "Tteokbokki sama eomuk, kayaknya enak."
Irene mengangguk, lekas menjentikkan jari guna memanggil pelayan. Soal makan, mereka kompak tidak pilih-pilih, kecuali ayam, karena Irene alergi. Ia juga enggan mencicipi alkohol jenis apapun, yang menurun pula pada Taeyong. Toleransi keduanya sangat rendah terhadap minuman itu. "Halo? Permisi, kita mau pesan. Haiii!"
Tak ada respon.
Hiruk pikuk tempat itu menyamarkan kata-katanya. Terlalu banyak orang, dan terlalu sedikit pelayan. Semua sibuk, sedangkan pelayan yang terdekat malah bergosip dengan pengunjung yang tampaknya temannya. Dia cekikikan, tidak mendengar panggilan Irene.
"Biar aku aja." Usul Taeyong, berdiri dari kursinya. Berniat menghampiri pelayan itu, sebelum bosnya memergoki dan ia dimarahi.
Tapi tak sengaja, sepasang iris gelapnya menangkap sosok tinggi yang familiar. Itu, beberapa meter di depan, membawa belanjaan yang terlalu jauh untuk Taeyong kenali. Kepalanya menunduk, tertutup tudung hoodie. Namun ya, ia yakin, itu pasti Jisung.
Taeyong mengamatinya, maju tanpa sadar. Ia tak punya alasan melakukan ini selain penasaran, tidak berarti ia suka memata-matai orang. Kalaupun iya, Taeyong akan memilih target lain, bukan remaja pendiam seperti Jisung.
Jisung berjalan pelan一amat pelan. Ada yang salah dengan kaki kirinya sehingga ia menumpukan berat badannya ke kaki kanan. Sama seperti kemarin. Apa ia bilang? Kram? Cuma kram? Mana ada kram yang bertahan 2 hari?
Jisung benar-benar bohong ternyata.
"Taeyong?" Irene tiba-tiba bersuara, diam-diam menyusul dan menyikut perutnya. "Lihat apa? Kamu kenal sama anak itu?"
"Dia yang cosplay jadi mayat, Park Jisung," Taeyong memberitahu, menggugah ingatan Irene tentang cerita yang belum ia selesaikan. "Kemaren dia tidur di koridor, kata Ayahnya gara-gara telat pulang. Keluyuran gitu."
"Abis itu?"
Mulut Taeyong terbuka, hendak menjelaskan lebih banyak, perihal kalimat kasar yang dilontarkan Asa, dan keanehan Shin yang tidak memperkenalkan diri sebagai ayah Jisung, ketika mendadak, seorang pria menubruk bocah itu hingga terjatuh.
Pria mabuk. Taeyong tahu hanya lewat gerak-geriknya. Para pecandu alkohol selalu melangkah sempoyongan, tak memiliki keseimbangan yang baik, terlebih kemampuan berpikir jernih.
Dia bangkit, oleng sejenak, kemudian mulai menunjuk-nunjuk Jisung dan mengeluarkan rentetan kalimat penuh amarah yang tidak masuk akal. Seakan semuanya salah Jisung sedangkan dia korban. Pria itu menyumpah, membawa-bawa nama binatang dan beberapa kata paling kasar yang Taeyong sendiri, jarang mengucapkannya.
Ia mengamuk di depan anak laki-laki bodoh yang tidak melawan, justru memilih minta maaf dan membungkuk berulang-ulang. Sementara barang belanjaannya tercecer di trotoar.
Namun detik berikutnya, pemabuk itu berhenti mengoceh. Terkejut oleh sebuah kaleng cola kosong yang menghantam kepalanya.
"Woi, siapa yang ngelempar一"
Kali kedua, giliran batu berukuran sedang mengenai bahunya.
Dia menoleh, bertatapan dengan Taeyong yang memegang kemasan susu kotak dari tong sampah warung tenda.
"Heh, kutu." Tantang Taeyong, mendekat, lebih dekat, lalu menarik Jisung agar minggir. "Balik ke habitatmu sana, otakmu ketinggalan."

Semoga tydak bosan dengan alurnya yang lambat 😂 Btw yang susah bayangin winwin marah coba liat ini :
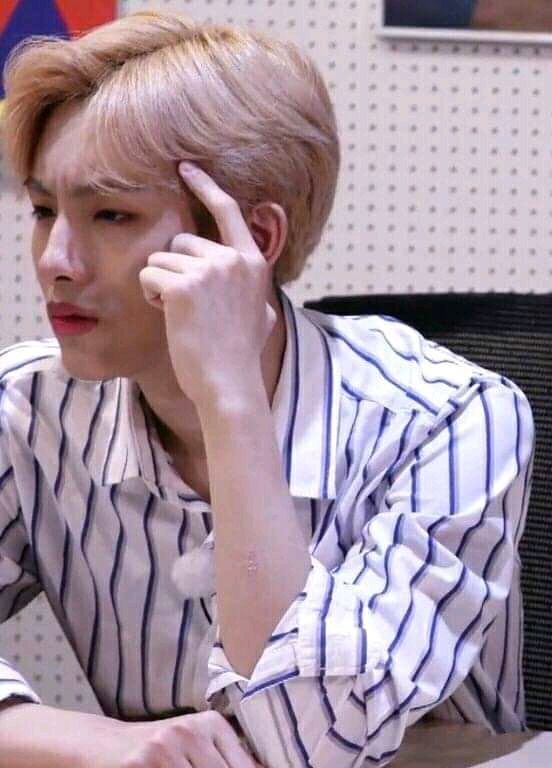

Sekali uwu tetaplah uwu :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top