15. Melukis
"Lidah itu lebih tajam dari sebilah pedang, karena dia bisa membunuh tanpa menyentuh."

💙Happy Reading 💙
.
.
.
Baru saja mereka menginjakkan kaki ke dalam rumah, Thomas dan Reina sudah duduk di ruang tengah seakan menanti kedatangan keduanya.
"Aku yang akan jelasin semua, Ma, Pa," tukas Mattew bahkan sebelum kedua orang tua itu berucap apa pun.
"Mattew, masuk ke kamarmu dan belajar. Minggu depan kamu ada olimpiade terakhir yang harus kamu ikuti sebelum fokus ke universitas, Papa harap kamu bisa memenangkan olimpiade itu dan dapat nilai kelulusan yang memuaskan," titah Thomas pada si sulung, yang membuat Mattew bungkam seketika.
"Iya, Sayang. Lebih baik kamu mandi terus belajar, nanti biar Bi Atun yang bawa makan malam kamu ke atas," imbuh wanita cantik yang tak lain adalah ibu dari kedua bocah tersebut.
"Tapi, Pa—"
"Udahlah, Kak. Lo belajar aja, gue bisa, kok, jalan ke kamar sendiri," balas Daniel sebelum Mattew selesai mengucapkan kalimatnya. Anak itu tak mau jika Mattew ikut terkena dampak dari kesalahan yang ia perbuat.
Pada akhirnya Mattew menuruti perintah sang ayah. Dengan berat hati anak itu melenggang pergi meninggalkan ruangan tersebut dan berjalan menuju kamarnya. Menatap nanar sang adik yang mungkin akan dimarahi lagi oleh sang ayah.
"Duduk," titah Thomas pada putra bungsunya yang langsung dibalas dengan anggukan oleh si lawan bicara.
Daniel mendudukkan dirinya secara perlahan ke atas sofa yang letaknya berhadapan dengan kedua orang tuanya. Anak itu lantas meletakkan tongkat yang sedari tadi membantunya untuk berjalan.
"Daniel," panggil Thomas, membuat si empunya nama malah menundukkan kepala.
"I–iya," cicit Daniel.
"Kamu tahu apa kesalahan yang sudah kamu lakukan?" tanya Thomas dengan tatapan tajam mengarah pada Daniel.
Jangankan menjawab, Daniel bahkan tak berani untuk mengangkat kepalanya. Anak itu lebih memilih untuk bungkam tanpa tahu harus memberikan pembelaan apa.
"Daniel, jawab pertanyaan Papa. Jangan diam saja, kamu dengar 'kan yang Papa bilang barusan?" Lagi sang ayah kembali bertanya.
"Ma–maaf, Pa. Aku nggak berantem, beneran aku nggak berantem." Dengan terbata anak itu mencoba memberikan jawaban, dengan keberanian yang mulai terkumpul ia mulai mengangkat kepalanya.
"Dengan wajah babak belur dan kaki pincang seperti itu, kamu bilang nggak berantem? Jangan macam-macam kamu." Reina yang semula diam kini angkat bicara. Wanita itu agaknya tak sabar melihat tingkah Daniel yang lambat dalam menjawab pertanyaan yang suaminya berikan.
Perasaan Daniel makin tak karuan kala sang ibu ikut bicara. Ia merasa seperti sedang diinterogasi karena telah melakukan kejahatan fatal, padahal dirinya adalah korban. Mengapa ia selalu berada diposisi yang disalahkan?
"Ma, Pa. A–aku emang nggak berantem, kakak-kakak itu yang mukul aku," balasnya memberi penjelasan, meski ia tahu jika itu mungkin tidak akan diterima.
"Apa, sih, yang ada di pikiran kamu sampai-sampai bisa berantem sama berandalan seperti itu? Apa kamu pikir dengan berkelahi seperti itu akan membuat kamu terlihat hebat? Apakah Papa akan bangga setelah melihat kamu babak belur seperti ini? Jangan gila kamu."
Bukannya memikirkan penjelasan yang baru saja Daniel utarakan, Thomas justru melontarkan kalimat tersebut. Tidakkah ia menyadari jika itu melukai perasaan buah hatinya?
Usai mendengar kalimat pedas dari sang ayah, Daniel kembali menundukkan kepalanya. Hatinya yang sudah sakit menjadi makin sakit ketika seseorang menorehkan luka ke hatinya, padahal luka yang lama bahkan belum sembuh sepenuhnya. Oh, jangankan sembuh, luka itu bahkan sama sekali tidak pernah bisa hilang dari hatinya.
"Kamu bisa nggak, sih, jadi sedikit lebih berguna? Apa pun yang kamu lakukan nggak pernah bisa sempurna. Anak yang Mama lahirkan nggak akan gagal dalam apa pun. Huh, Mama nyesel sudah ngelahirin kamu. Kamu hidup itu nggak ada gunanya." Lagi, kalimat menyakitkan terlontar dari bibir wanita yang sudah mengandungnya selama sembilan bulan lebih itu.
"Maaf ...." Tak ada lagi kata yang bisa Daniel ucapkan selain maaf, tenggorokannya seperti tercekat dan kering.
Efek dari kalimat kekecewaan mereka sangat melukai hati bocah yang sebenarnya rapuh itu. Anak itu tak mampu untuk mengutarakan pembelaan lagi, ia menunduk dalam dengan tangan meremas kuat ujung seragam yang dikenakannya hingga kusut.
"Kalau kamu pikir Papa sedang memarahi kamu, maka kamu salah. Papa dan Mama seperti ini karena kami ingin kamu berkembang dan menjadi lebih maju lagi. Lihat kakak kamu, dia bisa menjadi sepintar ini karena dia selalu menuruti apa yang Papa dan Mama katakan. Dia mengikuti semua yang kami katakan, karena itu memang terbaik untuknya."
"Orang tua melakukan semua ini untuk kebaikan anaknya, kalau kamu ingin menjadi yang terbaik maka turuti saja apa yang sudah Papa atur," imbuh Reina atas apa yang suaminya katakan.
Cukup! Daniel tidak tahan lagi! Ia lelah, ia bosan dan muak dengan setiap kalimat yang orang tuanya ucapkan kala ia berbuat kesalahan. Ia tak mau seperti ini lagi. Dengan sekuat tenaga anak itu memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya dan menatap tepat ke netra dua orang dewasa di hadapannya itu.
Dengan mata yang mulai berair dan suara bergetar Daniel berucap, "Nggak semua yang terbaik bagi kalian adalah terbaik juga buat aku. Otakku nggak sebaik otak Kak Mattew, aku nggak mampu untuk mengikuti langkah dia, Pa, Ma. Semakin aku berusaha buat ngejar, rasanya semakin jauh. Aku nggak akan pernah bisa sepadan dengan Kak Mattew. Kenapa kalian nggak bisa paham, sih? Aku capek gini terus!"
Air mata tak lagi mampu dibendung, untuk pertama kalinya Daniel menangis di hadapan kedua orang tuanya setelah sekian tahun berlalu. Rasa sesak di dada membuat ia tak bisa berucap lebih panjang lagi, hatinya sakit dengan ujaran kekecewaan yang ditujukan padanya tadi.
Sementara itu Thomas dan Reina dibuat ternganga dengan kata-kata yang baru saja meluncur dari bibir putra bungsunya. Keduanya juga nampak terdiam, tak tahu harus memberi respon apa. Jujur, kalimat itu menimbulkan gejolak aneh dalam diri mereka. Alhasil keduanya hanya mematung ketika Daniel mulai beranjak dari tempat duduknya. Anak itu memutuskan untuk pergi ke dalam kamarnya, ia rasa percuma jika banyak bicara karena mereka tetap tak akan paham.
"Daniel, kamu mau ke mana? Papa belum selesai bicara!" seru Thomas ketika Daniel melenggang begitu saja tanpa berpamitan, akan tetapi panggilan itu tak dihiraukan oleh sang putra.
Daniel terus memacu langkahnya, meski kakinya berdenyut ngilu ia pangkal berhenti. Tujuan utamanya adalah kamar, hingga di depan tangga ia berpapasan dengan bi Atun yang hendak menghantarkan makan malam untuk Mattew. Wanita paruh baya itu lantas mendekati Daniel dengan raut khawatir yang kentara.
"Den Daniel! Astaga, Aden kenapa? Ini, kok, kakinya diperban gini, sakit kena apa ini?" tanya bi Atun khawatir, wanita itu nyaris menjatuhkan nampan yang dibawanya namun beruntung dengan sigap ia mampu mempertahankan keseimbangan dirinya agar tidak jatuh.
Daniel mengusap bekas air matanya dengan punggung tangan kemudian tersenyum.
"Nggak apa-apa, kok, Bi. Tadi Daniel jatuh di sekolah, jadi deh gini, sakit sedikit hehe," sahutnya diiringi cengiran.
"Ya, ampun, Den. Makanya kalau jalan hati-hati, jangan sampai jatuh terus luka seperti ini, jadi sakit, 'kan?" tukas wanita itu pada putra majikannya.
"Iya, Bi. Besok-besok Daniel lebih hati-hati kok. Eum, bisa bantu naik nggak? Kaki Daniel nggak kuat buat naik tangga," pinta bocah itu dengan raut memohon, karena memang jika untuk menaiki tangga kakinya tak mampu, ia butuh bantuan.
Bi Atun tersenyum lantas mengulurkan tangannya yang kosong untuk membantu Daniel menaiki tangga. Perlahan tapi pasti, Daniel bisa sampai ke depan kamarnya dengan selamat atas bantuan bi Atun. Ia berterima kasih pada wanita yang selama ini merawatnya tersebut sebelum akhirnya memasuki ruangan yang menjadi salah satu tempat ternyaman baginya.
"Hah ...." desah bocah itu setelah melemparkan tasnya ke sembarang arah dan menyalakan lampu guna menerangi ruangan yang semula gelap.
Tubuhnya luruh ke sisi kiri ranjang, satu kaki sehatnya tak mampu untuk menahan beban tubuh dan pikirannya lagi. Ia sakit, fisik maupun mental. Di saat seperti ini, Daniel bahkan tak memiliki seorang pun untuk berkeluh. Maka jangan salahkan dia jika sebilah benda tajam nan mengkilap itu menjadi temannya. Mengiris lapisan kulit putihnya secara perlahan hingga menghasilkan sebuah luka di atas luka lama.
Rasanya perih, tapi juga nikmat dalam waktu bersamaan. Entahlah, Daniel sendiri tak bisa mendeskripsikan perasaannya tiap kali ia mengiris lapisan kulit lengannya itu. Perih dan aliran darah yang tak seberapa banyak, bau anyir yang cukup familiar di hidung seakan menjadi obat tanpa resep yang dapat melegakan baginya. Beban yang mengendap seakan terangkat ketika ia melakukan ritual tersebut. Maka apakah bisa ia menghentikan kebiasaan ini? Sepertinya tidak, ini terlalu nikmat untuk disudahi.
Sesuatu yang berbulu tiba-tiba menyeruak naik ke pangkuan anak itu kala tangannya mulai bergerak untuk menorehkan goresan keempat. Daniel refleks menghentikan aksinya lantas menoleh ke makhluk mungil di pangkuannya itu.
"Astaga, Kevin," lirihnya saat tahu jika benda berbulu itu adalah Kevin, kucing mungil yang satu bulan lalu ia temukan. Dibandingkan dengan keadaan dahulu, kini Kevin menjadi lebih gemuk dan semakin menggemaskan.
Kucing berbulu putih itu bergelung nyaman di pangkuan Daniel sembari mengusapkan pucuk kepalanya ke seragam yang dikenakan oleh sang tuan. Tak seperti biasanya, Kevin yang sering mengeong itu menjadi pendiam, seakan paham dengan perasaan Daniel saat ini.
Daniel tersenyum miris, bahkan hewan lebih mengerti perasaannya dibandingkan manusia yang diberi kelebihan akal dan pikiran. Andaikan kucing bisa berbicara dan memiliki akal dan pikiran, mungkin Daniel akan bersahabat dengan kucing. Oh, atau ia akan memilih menjadi kucing saja dan menjadi teman Kevin? Sepertinya bukan ide yang buruk.
Menanggapi apa yang terlintas di kepalanya membuat Daniel tertawa ringan.
"Kayaknya gue udah gila," tukasnya kemudian membersihkan luka yang tadi ia ciptakan tanpa ragu.
Malam ini berakhir dengan kisah seorang anak yang nyaris kehabisan darah, tapi diselamatkan oleh seekor kucing yang setia pada tuannya. Daniel rasa itu cukup untuk menjadi penutup kisahnya hari ini. Dia tidak tahu, apakah hari esok akan lebih baik atau buruk. Namun, keinginan untuk menyerah selalu muncul di saat-saat lelah seperti ini.
Daniel memejamkan matanya dan mendongak. "Satu tahun rata-rata ada 365 hari, dan gue udah berhasil lewatin enam belas kali. Kira-kira tahun ini bisa nggak, ya?"
🍁🍁🍁
See you next part, dan silakan mampir ke KaryaKarsa kalo nggak sabar nunggu update seminggu sekali
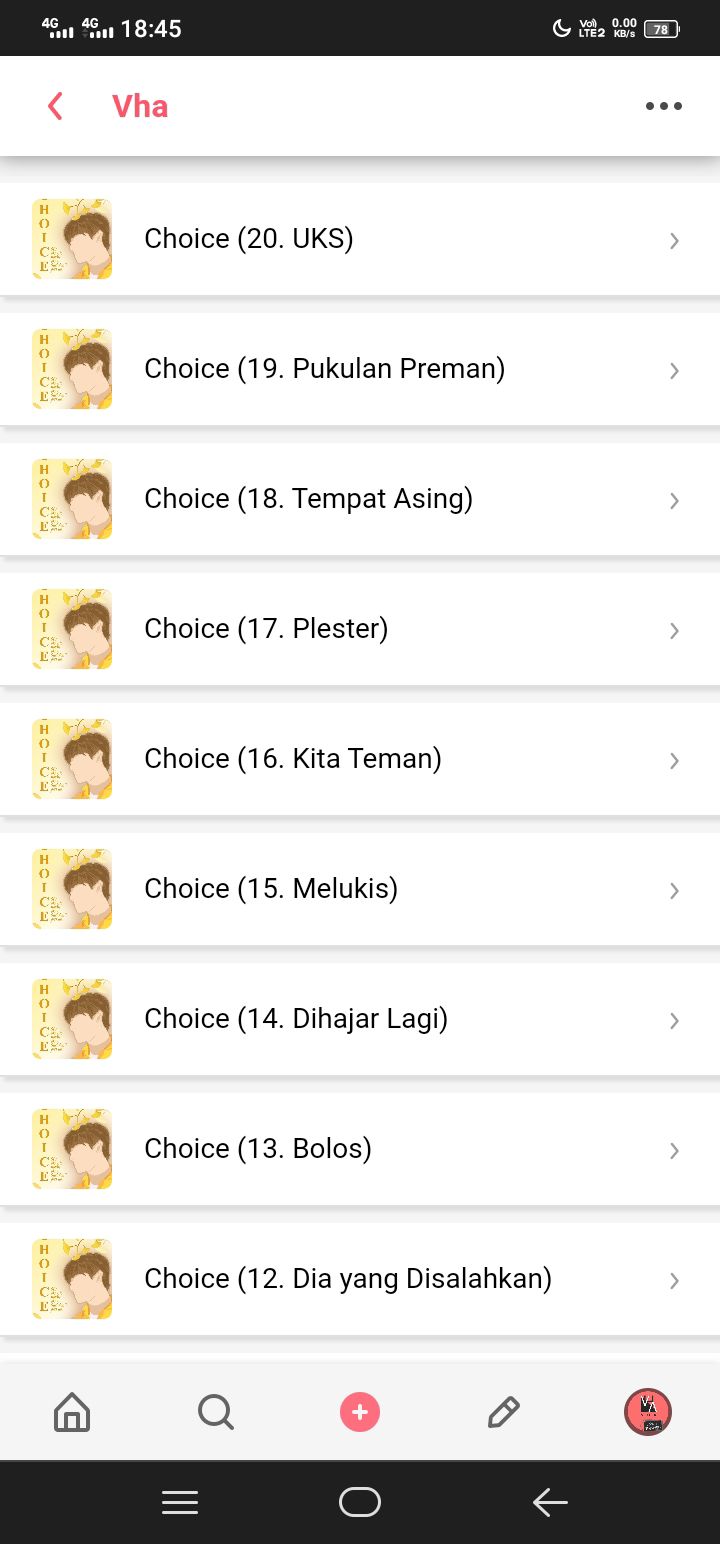
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top