Unfair
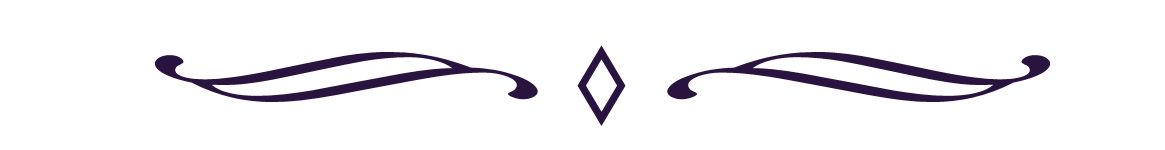
Konon Dewa Pencipta, membuat segala sesuatunya dengan adil. Memang ada berbagai pertimbangan dan perhitungan, tetapi tak ada sebutir pasir pun yang dibuat dengan sia-sia. Menurutku itu omong kosong.
Aku tahu dengan berpendapat seperti ini, bukan hanya ibu yang bekerja sebagai abdi kuil yang akan memberiku ceramah panjang, tapi seluruh anggota keluarga besar akan menganggapku anak sesat yang perlu diluruskan. Kakek yang pendeta tinggi, akan memberiku ritual penyucian. Lalu nenek yang guru telaah kitab suci, akan menyuruhku menyalin semua ayat yang beliau anggap bisa membersihkan pikiranku yang ternoda.
Ah ... Sudah terbayang wajah kecewa keponakan-keponakan yang manis ketika orang tua mereka, para sepupuku, melarang untuk menerima permen dan cokelat yang kutawarkan. Hanya karena aku melontarkan pendapat yang berseberangan dengan mereka.
Sedangkan ayahku ... Yah, beliau cukup santai. Walau itu juga berarti beliau tidak akan mendukung pendapatku. Sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua, ayah nyaris tak punya suara. Karena itu aku juga hanya diam dan menunduk patuh setiap kali kakekku memulai pagi kami dengan doa penuh, dilanjutkan dengan nasehat dari nenek untuk jatah sehari—masih ada petuah jatah seminggu setiap usai doa bersama di hari libur.
Jangan salah, aku bukan jadi begini sejak lahir. Tidak ada anak yang begitu keluar dari rahim langsung menjerit, "Aku pendukung setaaan!"
Pendapatku ini juga bukan murni buah pikiranku sendiri. Kuakui pikiran ini tercipta dari percakapan dengan sesama rekan seperirian—mohon maklumi istilah tak baku yang tercipta asal-asalan dari rasa frustrasi kami ini. Kami berkumpul dan bergunjing pada objek yang menimbulkan rasa iri dan dengki, lalu dari obrolan tak berfaedah itu kami seenaknya menyimpulkan bahwa Dewa Pencipta tak pernah betul-betul adil.
Dengan kata lain, aku adalah satu dari banyak pecundang yang selalu memandang dengki pada dua bocah baru di akademi.
"Sebentar ... Kok, kamu bilang bocah?" protes sobat karibku, Rene. "Bukannya kita semua seangkatan?" koreksinya.
"Ck!" Aku tidak suka ada yang menginterupsi saat sedang bermonolog. "Kau tak lihat postur mereka? Kaki dan tangan yang pendek ... Jambul merah bocah bangsawan itu saja hanya mencapai pundakku!" semburku berapi-api.
Rena terlihat akan menyampaikan rasa keberatan atas pernyataan itu. Namun aku bersikukuh pada pendapat bahwa mereka berdua adalah bocah sok jago, yang lahir dengan bergelimang berkat dari Dewa Pencipta. Akhirnya karibku itu memutuskan untuk kembali pada aktivitas menggosok bilah pedangnya.
Bocah lelaki berambut merah itu cucu pendekar ternama, bergelar ksatria, Masa kecilnya pasti diisi dengan latihan berpedang eksklusif dari sang Pendekar, sendiri. Mungkin dia sudah mahir memainkan rapier sejak baru bisa berjalan.
"Uhh ... bukannya itu menyedihkan?" Rene kembali menyela. "Keluarga ksatria pasti tahu kalau latihan berpedang terlalu dini hanya akan merusak struktur otot anak."
"Shhht!" Aku mendesis dengan telunjuk teracung tajam ke arah hidungnya. "Latihan eksklusif dari sang Pendekar, sejak dini, adalah satu-satunya alasan bocah pendek itu bisa menang dariku di kelas praktek!"
"Kalau begitu, bagaimana dengan Kadet Shuei, dia bukan dari keluarga ksatria ternama, kan?"
Ah, ya ... nama bocah menyebalkan satu lagi. Perempuan yang seperti boneka pajangan—itu bukan pujian. Wajah angkuhnya selalu membuat orang merinding dengan mata yang seperti gelas. Kulit gelap, rambut hitam, kalau ada yang bilang dia titisan iblis, aku pasti percaya.
"Kudengar, warna kulit dan mata Kadet Shuei seperti itu karena memiliki darah Merian," Rene kembali berkomentar.
Aku ternganga. Informasi yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Merian ... kaum penyihir air itu?" tanyaku.
Rene mengangguk.
"Kenapa ada keturunan kaum penyihir di akademi militer?"
Rene mengangkat bahu.
Huh! Dia juga tak tahu, beraninya memotong monologku lagi.
"Tapi aku penasaran, apakah Kadet Shuei masih memiliki kemampuan menggunakan sihir air, seperti moyangnya."
Berbeda dengan Rene yang terlihat antusias untuk mencari tahu, aku menggertakkan gigi. "Sihir?" gumam parau itu terlontar melintasi geligi yang masih beradu karena emosi. "Pantas saja aku kalah melawan bocah perempuan itu. Kadet biasa mana bisa menang melawan kekuatan sihir?"
"Hei, Sophia ... Praktek latih tanding kelas bawah itu melarang penggunaan buff dan mantra. Jadi-"
"Jadi dia pasti telah melakukan kecurangan! Lihat saja, akan kubuktikan bahwa bocah Merian itu menggunakan cara ilegal untuk menang!"
Saat itu aku terlalu asyik dengan berbagai skenario 'pembuktian' dalam kepalaku sendiri, sampai tidak menyadari Rene, karibku sedari kecil, yang sedari tadi kuajak bicara, bukanlah bagian dari kumpulan pendengki di akademi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top