Sembilan ☁️ Hubungan Darah
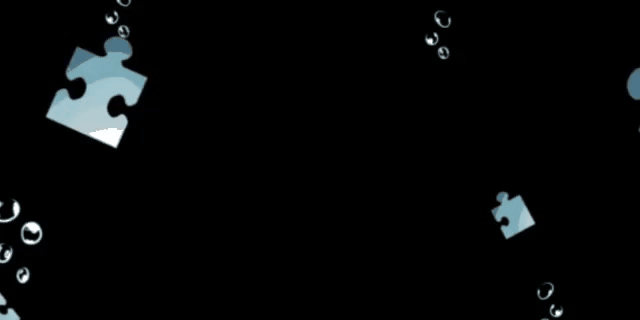
Kami meninggalkan Yoga dengan tenang, Dala kembali menarik tanganku setelah anak yang membogemnya tadi kembali ke barisan dan membubarkan diri. Dala masih diam saja, bahkan setelah kami menyeberang dan tiba di main hall mall.
"Kok tiba-tiba?" tanyaku.
Dala mengangkat alis, kemudian membuang muka dan mengusap tengkuknya. "Nggak papa sih ...."
Tidak, tidak bisa seperti itu. Pasti dia memprovokasi Yoga agar berhenti dan menurut padanya. "Apa yang kau lakukan? Tidak, apa yang kau bisikkan?" Aku tidak percaya orang pendiam sepertinya mampu memprovokasi lawan dengan sekali bisikan.
Wajahnya culun dengan poni nyaris menyentuh alis, tubuhnya juga tak lebih besar dari Yoga bahkan Abidine yang ceking. Suaranya lebih lembut dari laki-laki lain, matanya besar seakan tak mampu membuat wajah sinis. Yah, penampilan memang tidak bisa dijadikan tolak ukur kekuatan seseorang.
"Ada yang melapor. Meski kau belum mengirim rekamanmu ke mana-mana, ada orang lain yang lebih cepat melapor tanpa tahu sikon." Matanya kembali menatap lurus.
Kami menaiki eskalator, berbelok sana-sini untuk mencapai toko buku. Dala masih menggandeng tanganku. Alih-alih mesra, genggamannya lebih seperti anak kecil mencekik leher kucing.
"Sebelum polisi atau apalah itu datang, kita harus cepet-cepet pergi," sambungnya. "Makanya kubilang, mending kita pura-pura baikan aja, baku hantamnya disambung lain waktu."
Aku menepuk jidat keras-keras. Bodo amat dilihat orang banyak. Apa yang terjadi pada anak laki-laki zaman sekarang?! Mana ada begituan, 'kan? Zaman edan!
Peduli amat, asalkan hari ini aku puas menyikut hidung anak orang sampai berdarah dan dapat modul, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Dala juga tampak tak keberatan menemaniku sampai ba'da magrib. Dia menikmati jalan-jalan di mall kota orang. Hitung-hitung aku jadi guide tour bagi turis ibu kota—ingat, Dala dari Jakarta.
Ada hal baru yang kutahu dari Candala. Dia atlet taekwondo sebab pemimpin Rumah Anak-nya adalah Sabeum¹. Dia bercerita padaku tentang itu secara sukarela. Namun, ketimbang bela diri, Dala lebih senang seni rupa dan musik.
Aku pulang sebelum isya. Dala tak bisa mengantarku sampai rumah karena rumahnya dan rumah ayah bertolak arah. Aku harus mengambil beberapa barang di sana sebelum pulang ke rumah lama ibu.
Esoknya aku bangun pagi-pagi sekali untuk ngacir ke sekolah sebelum ibu bangun. Meski lebih tepatnya aku lupa belajar materi matematika wajib untuk ulangan harian jam ketiga nanti. Jam belajarku di rumah jadi berantakan semenjak Dala mengajakku main sore-sore.
Tak butuh waktu lama untukku mencapai sekolah. Rumah lama ibu lebih dekat dari sekolah ketimbang rumah ayah. Seperti dugaanku, kelas masih sepi, bahkan gerbang sekolah barusan dibuka—rajin memang diriku ini.
Langsung kuhambur barang-barang dari tas ke meja, mengeluarkan buku paket dan catatan. Bisa berbahaya kalau nilaiku kali ini tidak tuntas. Minggu depan kami akan kelas sebelas, berati minggu-minggu ini akan lebih banyak praktek dan ulangan harian.
Aku tak sadar kelas mulai ramai, otakku terlalu dalam menyelam dalam angka untuk mencari X atau Y yang suka ghosting siswa. Dua huruf itu memang yang paling menyusahkan dari dua puluh enam huruf alfabet.
"Nad," panggil seseorang menepuk pundakku.
Awalnya aku tak mampu merespons suara siapa yang memanggilku sangking fokusnya pada buku. Namun, kemudian aku menoleh dan mendapati Abidine dengan raut serius menatapku dalam.
Mataku berpendar ke seisi kelas, semuanya sudah ada di kelas. "Apa?" jawabku setelah memastikan tak ada yang benar-benar memerhatikan.
"Ikut aku ke luar sebentar," pintanya pelan, mengambil lengan kananku. Netranya mengikuti ke mana arahku melirik, jam dinding kelas. "Masih setengah jam lagi. Ayo ikut dulu, aku mau ngomong."
Apa lagi sekarang? Aku terpaksa berdiri dan mengikuti geretan tangannya. Kami menjadi sorotan saat melewati koridor, semoga mereka tidak mengira kami melakukan KDRT di sekolah.
Abidine membawaku ke tepian lapangan. Ada tempat duduk keramik di sana, di bawah pohon jambu. Air wajahnya sejak tadi tidak tenang. Apa yang hendak dia katakan? Pengakuan cinta? Tidak mungkin. Masalah kedua orang tuaku lebih masuk akal.
"Tante—" Dia tidak melanjutkan kalimatnya.
Sudah kuduga, pasti masalah keluarga. Mungkin orang tuanya sudah tahu, dan Abi ikut mendengar. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal itu. Abidine juga perlu tahu.
Kurangkul dia dari samping. "Iya. Tante sama Om-mu pisah." Bisa kulihat dia menggigit bagian dalam bibir keras-keras. "Awas berdarah."
"Tapi nanti kita—" ucapnya lagi separuh-separuh.
Kali ini kedua tanganku merangkul bahunya dengan erat. Jangan berharap romantis, ingatlah kami sepupu. Aku sering memeluknya di rumah, atau saat kami menginap dan tidur sekamar tujuh tahun lalu.
Tiba-tiba aku merindukan masa kecil kami. Waktu itu aku tak tahu malu, mengenakan rok tetapi bermain gundu bersama anak laki-laki. Jajan es teh yang ada pemanis buatannya sembunyi-sembunyi dari ibu. Berlagak sombong karena aku satu-satunya perempuan di antara teman Abidine.
"Dalam darahku masih ada gen kakek, bung. Kau tak perlu khawatir aku bakal menghilang atau jadi anak broken home yang mabuk-mabukan. Jengkol buatan mamamu sudah lebih dari cukup membuatku semaput." Kuusap punggungnya saat merasakan tangannya balas memelukku.
Dia mengembuskan napas panjang, bau khas anak laki-laki menyapaku. "Kupikir kau bakal kenapa-kenapa. Atau makin jarang ngomong denganku."
Aku menggeleng. Itu tidak mungkin, hanya dia satu-satunya laki-laki yang dipercaya ibu dan ayah untuk tidur bersamaku kalau dalam keadaan terdesak. Di samping itu, dia paham setiap maksudku dengan lebih baik dari orang lain di dunia.
Terlalu banyak kenanganku dengannya untuk dibuang percuma, hanya karena hak asuhku jatuh kepada ibu yang tidak ada hubungan darah dengan Abidine.
"Tolol, kau pikir aku siapa?" kekehku mempererat dekapan. "Dah. Matwa." Kulepas pelukannya dengan sekali gerakan cepat, lantas berdiri dan membersihkan bagian belakang rok dari debu.
"Bentar," cegahnya. "Kau masih sayang sama aku, 'kan?"
Kalau kami sedang berada di rumahnya, aku sudah muntah di lantai. "Jijik."
Namun, dia tersenyum kala mendapat jawabanku demikian, kemudian menyusulku berdiri juga. Dia paham, bahwa itu tandanya aku tidak benar-benar membencinya atau punya dendam dan sebagainya.
Ngomong-ngomong tentang hubungan darah, aku baru ingat jadwal praktikum kimia hari ini di jam kelima. Bicara singkat dengan Abi selalu membuatku lebih tenang. Aku juga tak bisa menyimpan rahasia terlalu lama darinya. Kami tidak serenggang yang terlihat di kelas, dia sering main ke rumahku kalau orang tua kami belum pulang hingga larut, lalu menghabiskan malam di kamar untuk membedah materi.
Aku dan Abidine kembali ke kelas seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Kadang, anak-anak kelas menggosipkan tentang hubunganku dengan Abi. Mereka tidak tahu kami sepupu dekat. Sengaja dirahasiakan agar tak ada perlakuan khusus dan sebagainya.
"Dari mana?" tanya Dala berbisik.
Tak kujawab pertanyaannya. Lagipula bukan urusan dia apa yang kulakukan barusan. Dia menatapku dengan wajah klasik, meminta penjelasan lebih.
Tunggu, wajah itu ... apa dia cemburu?
Alisnya bertaut kemudian, mendekatkan wajahnya padaku. "Kau—"
Aku diam saja tak bergeming di tempat, tanpa berusaha menjauh atau lainnya. "Apa," kataku dingin.
"Pacaran sama Abi?"
Tidak, bodoh. Aku tak mungkin pacaran dengannya. Sudah kuduga dia cemburu, perilaku sosial yang umum terjadi.
Dala melihat ekspresiku, kemudian kembali duduk dengan tenang setelah memahami. "Mukamu emang nggak bisa dibohongi, ya."
Setelahnya dia diam saja. Sama seperti kemarin, kami memilih belajar dengan khidmat. Aku menyelesaikan ulangan harian matematika wajib lima menit lebih cepat dari yang lainnya, dan mendapat nilai sempurna. Dala beserta Jamal menyusulku dengan nilai sempurna meski lima menit lebih lambat saat mengumpulkan kertas jawaban.
Bu Rahma keluar kelas setelah membahas sepuluh soal di papan tulis. Sebab nilai terendah hanya 80, kami mendapat jam kosong sebelum istirahat dan menyambung kimia.
Sungguh, hari ini lebih tenang dari biasanya. Keenan mendadak kalem, juga Abi dan Giam. Mereka berbondong-bondong ke kantin, saling berangkulan dengan langkah serenpak, tanpa teriak-teriak, tanpa tatapan mengintimidasi Jamal, tanpa grusak-grusuk Keenan, ataupun gombalan manis Abi.
Jangan heran, mereka biasanya seperti itu karena melepas stress. Kalau sedang kumat, Giam bisa kesurupan secara harfiah dan memulai drama kucing oren yang kena siram air—ribut luar biasa. Satu-satunya yang bisa menyadarkan Giam hanya Gosal. Dia tinggal menyembur muka kembarannya dengan air campur liur. Sudah, nanti dia sadar sendiri.
Begitu bel masuk menjerit, kami segera menyambar jas lab dan pergi ke lab kimia tempat Bu Heni seharusnya sudah menunggu kami. Bila dan Rina mengajakku berangkat duluan dan memilih meja percobaan sebelum anak-anak cowok merebutnya.
Namun, begitu kami tiba di sana, Bu Heni tak tampak batang hidungnya. Lima menit kami celingukan seperti anak ayam hilang, kelas dua belas datang bersama guru kimia lain dan mengisi lab.
Taufan mengangkat alisnya heran. Sebagai ketua kelas, dia bertanya pada guru mata pelajaran kelas dua belas. Rupanya mereka sepakat untuk memakai lab agar kelas kakak kelas lebih cepat mendapat nilai. Bu Heni datang setelah mereka berbincang sebentar, kemudian menyuruh kami mengikutinya.
Aku tidak begitu memperhatikan mereka. Pikiranku melayang-layang memikirkan sekolah di masa depan. Kira-kira aku harus apa setelah lulus SMA? Kuliah, tentu saja. Namun, apa aku mampu hidup di luar sana sendirian? Ngekost?
Setelah dipikir-pikir lagi, kata-kata orang tentang memiliki teman itu memang benar. Aku butuh relasi untuk mencari pekerjaan dan penasihat saat aku melakukan kesalahan. Memang kesannya seperti datang saat butuh, maka untuk menghilangkan kesan itu, aku juga harus ada di samping orang itu saat dia membutuhkan.
Kalau ibu tidak ada, berarti aku memang harus mencari orang lain yang bisa kuandalkan. Aku tak bisa menunggunya sadar bahwa anak perempuannya ini juga butuh perhatian.
Saat tersadar, kami semua sudah ada di lab kimia lama. Raut teman-teman langsung berbeda. Tak ada lagi senyum atau aura bahagia. Aku sendiri juga kurang menyukai tempat ini, seakan ada sesuatu yang menakutiku untuk jatuh bersama semua barang di sini.
"Nad, sini," panggil Dala.
Aku mengikutinya ke salah satu meja lab berdebu. Beberapa keramiknya mulai menguning dimakan waktu dan bekas reaksi. Mataku berpendar ke sekitar. Bu Heni mulai menjelaskan materi, semua mata termasuk milikku tertuju serius padanya.
Mungkin saja, setelah keluar dari lab kimia lama hari ini tak lagi tenang.
。 ☆ 。
Sabeum¹ Instruktur dalam olahraga taekwondo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top